|
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Terminal Peti Kemas (TPK) Koja merupakan salah satu pelabuhan yang memberikan
jasa pelayanan bongkar dan muat peti kemas yang terletak di wilayah Pelabuhan
Tanjung Priok, Jakarta. Terminal ini merupakan badan usaha terminal operator yang
dibentuk melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT Pelabuhan Indonesia II
(Pelindo II) dengan PT Ocean Terminal Petikemas (OTP).
TPK Koja beroperasi sejak tahun 1997 sebagai antisipasi terhadap
meningkatnya
permintaan
pelayanan
peti kemas
pada
awal
tahun
1990-an
seiring
dengan pesatnya peningkatan aktivitas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok.
Berdasarkan statistik, sebesar 90% aktivitas komoditi perdagangan internasional
dilakukan melalui pelabuhan laut (Winklemans, 2002) dan sebesar 65% melalui jalur
Asia Pasifik (PSA, 2003).
Metoda
pengiriman
barang
dalam
bentuk
peti
kemas
juga
menjadi
pilihan
yang paling dominan saat ini. Kondisi ini menyebabkan terminal peti kemas di
wilayah Pelabuhan Tanjung Priok memiliki peran yang penting dan strategis karena
aktivitas ekspor dan
impor nasional secara dominan, yakni sebesar 60%, digerakkan
dari Jakarta. Akibatnya tingkat persaingan antar operator terminal yang ada menjadi
meningkat.
|
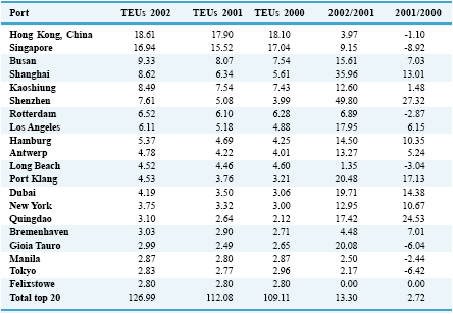 2
Tabel 1.1. Daftar 20 Besar Terminal Peti Kemas Dunia dan Throughput-nya (dalam
Juta TEU).
Sumber : Containerization International, Maret 2003
Selain TPK Koja, di wilayah pelabuhan Tanjung Priok terdapat tiga terminal
peti kemas
lainnya,
yaitu
PT
Jakarta
International
Container
Terminal
(JICT),
PT
MTI, dan PT Segoro Fajar Satryo. Di luar wilayah pelabuhan Tanjung Priok antara
lain terdapat
Terminal
Peti
Kemas
di Lampung, Cirebon,
Semarang
dan
Surabaya.
Tingkat persaingan ini akan lebih ketat apabila rencana pembangunan pelabuhan
Bojanegara,
di
Banten, direalisasikan
dan
dijadikan
sebagai international hub port
(Atas News, Februari 2003).
|
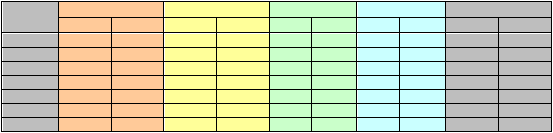 3
Tingkat throughput
TPK Koja
di
wilayah
pelabuhan Tanjung Priok saat ini
berada pada urutan kedua setelah PT JICT dengan kecenderungan pangsa pasar yang
semakin berkurang.
Tabel 1.2. Throughput Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
Tahun
TPK KOJA
PT JICT
PT MTI
PT SEGORO
TOTAL
Box
TEUs
Box
TEUs
Box
TEUs
Box
TEUs
Box
TEUs
1997
97,598
137,821
1,047,984
1,533,090
0
0
0
0
1,145,582
1,670,911
1998
197,034
287,681
968,043
1,425,347
0
0
0
0
1,165,077
1,713,028
1999
268,033
393,872
993,685
1,472,707
0
0
0
0
1,261,718
1,866,579
2000
330,884
494,795
1,029,537
1,530,497
0
0
0
0
1,360,421
2,025,292
2001
326,592
490,120
1,010,251
1,500,221
0
0
0
0
1,336,843
1,990,341
2002
365,535
551,179
1,031,720
1,537,091
0
0
0
0
1,397,255
2,088,270
2003*
337,593
507,216
919,837
1,376,996
95,920
133,898
75,417
99,692
1,428,767
2,117,802
Sumber : Departemen Marketing TPK Koja
*
terhitung hingga November 2003
Kondisi
tersebut
menyebabkan
pihak TPK Koja merasa perlu untuk
meningkatkan kinerjanya. Salah satunya yang telah dilaksanakannya adalah
menambah quay crane sehingga
jumlahnya
menjadi enam buah dan
memperpanjang
dermaga menjadi 650 meter. Selain itu pihak terminal juga perlu meningkatkan
kecepatan proses bongkar muatnya untuk meningkatkan throughput.
Peningkatan kecepatan proses bongkar muat juga akan meningkatkan
kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan waktu singgah kapal menjadi lebih singkat.
|
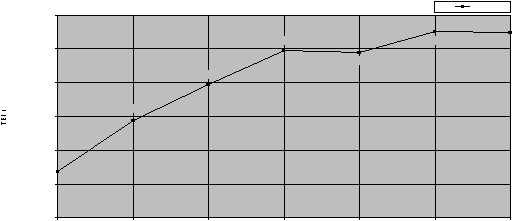 4
1.2. Rumusan Permasalahan
Permasalahan
yang
dihadapi
oleh
pihak TPK
Koja
adalah
adanya
kecenderungan
throughput
yang
relatif
tetap
dan
stagnan
seperti yang ditunjukkan data statistik
terminal.
600,000
TEUs
500,000
400,000
393,872
494,795
490,120
551,181
547,280
300,000
287,681
200,000
100,000
137,821
-
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TAHUN
Gambar 1.1. Pertumbuhan Throughput TPK Koja Tahun 1997 – 2003 (Departemen
Marketing TPK Koja, 2004).
Kecenderungan stagnasi throughput mulai tampak tahun 2000
hingga tahun
2003, walaupun kapasitas terminal masih di atasnya. Throughput tertinggi yang
pernah dicapai adalah sebesar 551.181
TEU, sedangkan kapasitas terbangun adalah
sebesar 630.000 TEU. Sehingga
tingkat utilitasnya baru
mencapai 87,48%. Apabila
5% dari kapasitas digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas terminal,
maka masih tersisa kapasitas sebesar 7,52% atau sebesar 47.376 TEU yang masih
dapat dicapai.
|
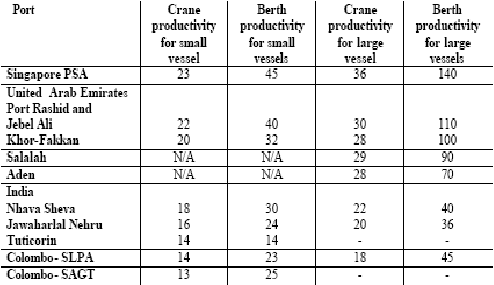 5
Dilihat dari sisi indikator kinerja proses bongkar muat, yaitu BCH (Box Crane
per
Hour)
dan
BSH (Box Ship
per
Hour), TPK Koja masih di urutan bawah bila
dibandingkan
dengan
terminal
peti
kemas regional
(lihat
Tabel
1.3).
Nilai
BCH
menunjukkan
jumlah
boks
peti
kemas
yang
dapat
dilayani
oleh crane
per
jam,
sedangkan
nilai
BSH
menunjukkan
jumlah boks peti kemas yang dapat dibongkar
muat dari sebuah kapal selama 1 jam.
Tabel 1.3. Produktivitas Crane dan Dermaga Terminal Peti Kemas Regional.
Sumber : UNCTAD Monographs on Port Management , 2003
Besarnya BCH rata-rata per kedatangan kapal dibandingkan dengan rata-rata
nilai BCH selama setahun, dan kecendrungan peningkatan nilai BCH yang ada di
TPK Koja berdasarkan data historis operasional tahun 2003 dapat dilihat pada
Gambar 1.2.
|
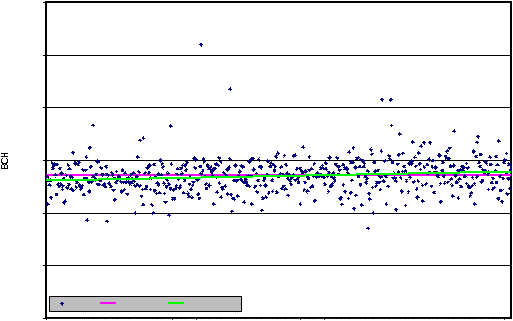 6
BCH TPK Koja 2003
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
BCH
Rata-Rata
Linear (BCH)
-
1 15 29 43
57
71 85 99 113 127 141 155
169
183 197 211 225 239
253 267 281 295 309 323
337
351 365 379 393 407
421
435 449 463 477 491
505
519 533 547 561
No Urut Kedatangan Kapal
Gambar 1.2. Nilai Variasi BCH Rata-rata per Kapal di TPK Koja.
Sedangkan nilai BSH yang secara teoritis merupakan jumlah total BCH
masing-masing crane (apabila penanganan bongkar muat peti kemas dilayani lebih
dari satu crane) pada kenyataannya hanya menghasilkan rata-rata sebesar 1,20 kali
dari nilai BCH seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3.
|
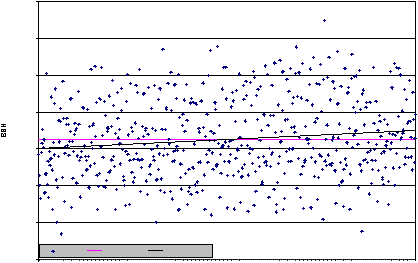 7
BSH TPK Koja 203
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
BSH
Rata-Rata
Linear (BSH)
-
1 23
45 67 89
111 133 155 177 199 221 243 265 287 309 331 353 375 397 419 441 463 485 507 529 551
No Urut Kedatangan
Kapal
Gambar 1.3. Nilai Variasi BSH Rata-Rata per Kapal TPK Koja.
Dari
hasil
pengumpulan
data
awal dan
informasi
dari
pihak
manajemen,
penurunan throughput disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun
eksternal, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:
a)
Peralatan yang dimiliki oleh TPK Koja sudah mulai usang dan mengalami
berbagai
kerusakan. Sementara penambahan atau perbaikan peralatan
memerlukan prosedur yang rumit.
b) Beberapa
jenis
kapal
yang
harus
dilayani
memiliki
karakteristik
yang
menghambat proses bongkar muat.
c)
Kecenderungan
meningkatnya waktu tunggu kapal baik disebabkan oleh
hal-
hal yang dapat dikontrol maupun yang tidak.
|
|
8
d)
Penetapan BCH dan BSH yang perlu disesuaikan dengan kapasitas dan
tingkat produktivitas yang dicapai dalam operasionalnya.
e) Terminal
lain
menerapkan
kebijakan discount, sementara TPK Koja harus
mengikuti kebijakan PT Pelindo II. Akibatnya banyak perusahaan pelayaran
dan cargo owner yang berpindah ke terminal lain.
Dari
faktor-faktor
tersebut
di
atas
dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang
dihadapi oleh TPK Koja adalah bagaimana meningkatkan kinerja (performance)
operasional terminal. Selain itu juga bagaimana meningkatkan jasa pelayanan
operasional
sehingga
masih
tetap
dapat mempertahankan keunggulan bersaingnya.
Pihak
manajemen
juga
perlu
mengidentifikasi bagian operasional mana saja yang
secara dominan mempengaruhi kinerja operasional secara keseluruhan.
Berdasarkan
hal
tersebut
di
atas,
maka permasalahan
yang
akan
diselesaikan
adalah:
a)
Melakukan analisis terhadap indikator bongkar muat yang ditetapkan dalam
bentuk BCH dan BSH untuk mendapatkan faktor-faktor yang secara
signifikan mempengaruhinya.
b)
Bagaimana
memperbaiki
dan
meningkatkan BCH dan BSH sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkan throughput?
c)
Faktor-faktor
apa
saja
yang
secara
dominan
dan
signifikan
mempengaruhi
nilai BCH dan BSH?
d) Yang juga
sangat
penting
adalah
menurunkan tingkat
variabilitas
BCH dan
BSH agar terdapat konsistensi operasional. Konsistensi sangat penting karena
dapat mengoptimalkan pengalokasian pada berthing window.
|
|
9
e)
Metodologi apa
yang secara tepat dapat diterapkan
untuk
melakukan analisis
dan evaluasi dibandingkan dengan metoda-metoda lainnya?
f)
Bagaimana memanfaatkan dan meningkatkan peran sistem Teknologi
Informasi sebagai alat (tools) dalam rangka
memperbaiki dan
meningkatkan
BCH dan BSH?
1.3.
Tujuan dan Manfaat
Tujuan
penelitian
yang dilaksanakan
dalam rangka
GFP
(Group Field
Project) di
TPK Koja adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui hubungan antara BCH dan BSH dengan faktor-faktor yang
merupakan faktor pembentuknya serta hubungan keduanya.
2. Mengetahui faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi nilai indikator BCH dan
BSH di terminal peti kemas serta mendapatkan solusi perbaikan dan peningkatan
nilainya.
Dengan
kata
lain
mengurangi
tingkat
variabilitas
indikator
BCH
dan
BSH pada proses bongkar muat peti kemas (transfer cycle).
3.
Membuka dan sekaligus
memperlebar berthing window sehingga dimungkinkan
untuk mendapatkan berthing contract yang baru.
4.
Mendapatkan
perangkat
(tool) yang dapat digunakan untuk memonitor dan
mengendalikan variabilitas yang terintegrasi dalam sistem operasional terminal.
5. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap jasa layanan bongkar muat peti
kemas.
|
|
10
6. Mengetahui
peran
dan
manfaat
sistem
Teknologi
Informasi
yang
dibangun
di
TPK Koja dalam
memberikan dukungan
bagi
perbaikan
dan
peningkatan
BCH
dan BSH.
7. Memberikan masukan dan bahan rekomendasi
solusi
untuk
TPK
Koja
dalam
rangka
peningkatan produktivitas bongkar muat,
khususnya
untuk peningkatan
throughput.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
a)
Memberikan kepastian waktu operasional bongkar muat bagi pelanggan.
b)
Meningkatkan pendapatan jasa bongkar muat sebagai akibat adanya efisiensi
dan produktivitas terminal.
c)
Munculnya
kesadaran
staf
operasional untuk bersinergi dengan staf
perencanaan dan pengendalian guna mencapai sasaran mutu yang sesuai
dengan ditetapkan pada ISO 9001:2000.
d)
Meningkatkan daya
saing antarterminal peti kemas di lingkungan pelabuhan
Tanjung Priok.
e) Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pihak lain yang
tertarik
untuk
melakukan
riset
yang
lebih
mendalam tahapan
demi
tahapan
operasional terminal. Yakni, riset lanjutan yang ditujukan untuk menjadikan
suatu
terminal
peti
kemas
yang
mampu
beroperasi
menjadi lean
port
management.
|
|
11
1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah mencakup analisis salah satu tahapan operasional
terminal,
yaitu
sistem bongkar muat
dari kapal ke
dermaga
(berth)
atau sebaliknya
serta
analisa
untuk
perbaikan
dan
peningkatanya dengan mengoptimalkan sistem
Teknologi Informasi yang telah ada di TPK Koja. Pada analisis kinerja operasional
tidak memilah kategorisasi untuk jenis pelayanan kapal maupun jenis kapalnya.
Di luar tahapan bongkar muat seperti tahapan untuk sandar, proses penumpukkan,
proses di gate (delivery) tidak dicakup dalam penelitian ini.
Batasan penelitian ini ditetapkan dengan berbagai pertimbangan dan alasan, yaitu:
1.
Masing-masing
tahapan
dalam operasional
terminal
peti
kemas
melibatkan
banyak faktor yang saling terkait sehingga memunculkan kompleksitas yang
sulit untuk dipahami. Selain itu waktu penyelesaian penelitian juga terbatas
sehingga tidak memungkinkan semua tahapan operasional dapat dianalisa.
Oleh karena itu pembatasan diperlukan untuk mendapatkan simplifikasi
masing-masing tahapan.
2. Analisis dibatasi hanya pada operasional bongkar muat pada tahapan transfer
cycle.
3. Peningkatan
lebih
ditekankan
pada optimalisasi
sistem dan
prosedur
bukan
dengan cara peningkatan kapasitas fisik terminal.
4. Analisa
lebih
ditekankan
pada
langkah-langkah
efisiensi, perbaikan
sistem,
dan prosedur operasi.
|
|
12
5. Perbaikan operasional bongkar muat tidak menyentuh masalah investasi yang
melibatkan dana yang besar.
1.5.
Definisi dan Terminologi
Definisi dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1.
Terminal Operator, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk
melakukan proses bongkar muat peti kemas ekspor dan impor yang dilakukan
melalui pelabuhan laut.
2. Peti kemas, yaitu kotak yang terbuat dari metal dengan konstruksi kaku yang
digunakan untuk
mengangkut kargo
yang
dapat dipindahkan ke kapal, truk,
kereta
api, pesawat terbang atau ditumpuk
(stack) di lapangan penumpukan.
Peti kemas
dapat dilengkapi
dengan
ventilasi,
pendingin, flat rack, terbuka
(open top), berisi cairan (bulk liquid), atau bahkan memiliki peralatan khusus.
Terdapat beberapa ukuran peti kemas, yaitu dengan panjang 20 kaki, 40 kaki,
45 kaki, 48 atau 53 kaki. Lebarnya dapat berukuran 8 kaki atau 8 kaki 6 inci.
Sementara tingginya dapat memiliki ukuran 8 kaki 6 inci atau 9 kaki 6 inci.
3. TEU (Twenty foot Equivalent Unit), yaitu satuan ukuran peti kemas dengan
panjang 20 kaki.
4. Throughput, yaitu banyaknya peti kemas dalam ukuran TEU yang masuk dan
keluar dari
terminal peti kemas dalam satu periode
waktu tertentu (biasanya
dalam 1 tahun).
5. Hub Port, yaitu pelabuhan yang memiliki berthing window yang tetap
sehingga dapat berperan sebagai pelabuhan collecting bagi pelabuhan feeder.
|
|
13
6. BCH,
yaitu satuan indikator
yang
menunjukkan rata-rata jumlah peti kemas
yang
ada pada sebuah kapal
yang dapat dilayani oleh
satu buah quay crane
dalam waktu satu jam.
7.
BSH, yaitu satuan indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata peti kemas
yang dapat dilayani dari sebuah kapal oleh sebuah dermaga dalam waktu satu
jam.
8. Crane
atau
juga
disebut
sebagai
quay
crane
(container
crane,
disingkat
CC), yaitu peralatan berupa sebuah tower yang berada di sepanjang dermaga
dan digunakan sebagai alat transpor antara truk dengan kapal peti kemas.
9. Dermaga
(berth),
yaitu satu
tempat
dimana
kapal dapat
bersandar di
pelabuhan untuk melakukan proses bongkar muat.
10. Perusahaan Pelayaran (shipping liner), yaitu perusahaan yang menyediakan
kapal
untuk
pengangkutan
laut baik cargo bulk atau peti kemas, dan untuk
keperluan ekspor maupun impor.
11. Cargo
Owner,
yaitu perusahaan
yang
memiliki barang
yang akan diekspor
atau diimpor.
12. Lean
Port,
yaitu pelabuhan
laut
yang
telah
terintegrasi dengan
moda
lain
(darat, udara, kereta api) dalam sistem pengelolaan operasionalnya.
|
|
14
|