|
32
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Masalah Kecelakaan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan dan kesehatan kerja didalam perusahaan
berhubungan erat dengan
salah satu sumber daya manusia yang memegang peranan yang sangat penting
didalam proses
produksi,
yaitu
tenaga
kerja.
Dibandingkan
dengan
faktor-faktor
produksi lainnya, tenaga kerja merupakan
faktor produksi yang paling
menentukan,
karena
tenaga
kerja
dapat
mempengaruhi kualitas
dan
kuantitas
dari
produk
yang
dihasilkan.
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat,
alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan
lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran
segala temapt kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air,
maupun diudara. Tempat-tempat demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi,
seperti pertanian, perindustrian, pertambangan,
perhubungan, pekerjaan
umum,
jasa
dan lain-lain. Keselamatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja.
Kecelakaan bisa
terjadi karena kondisi
yang
tidak membawa
keselamatan kerja,
atau perbuatan yang tidak selamat. Jadi definisi kecelakaan kerja adalah :
“Setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan”.
|
|
33
•
Berdasarkan definisi kecelakaan kerja
maka lahirlah dokrin keselamatan dan
kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja
adalah meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan mengadakan pengawasan ketat.
Untuk memberikan batasan definisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja,
dibawah ini akan disajikan beberapa definisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
yang dikemukaan oleh para ahli, antara lain:
• Dr. Suma’mur PK, Msc (Suma’mur,1976) memberikan definisi keselamatan kerja
sebagai: “Sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai
akibat kecelakaan kerja”.
• Drs. A.S Moenir (Suma’mur, 1981) memberikan definisi keselamatan kerja
sebagai: “Suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang dapat menjamin
secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada didaerah atau ditempat
tersebut, baik orang tersebut pegawai ataupun bukan pegawai dari organisasi
tersebut”.
• DR. Santoso, MS (Suma’mur,1981) pada forum
seminar Keselamatn dan
Kesehatan
Kerja
di Surakarta
tanggal
28 Februari
1986
memberikan
definisi
mengenai keselamatan kerja sebagai: “Pengetahuan tentang upaya untuk pencegahan
kecelakaan kerja yang berhubungan dengan penggunaan mesin, pesawat, alat,
bahan, dan proses pengolahannya, lingkungan tempat kerja serta melakukan
pekerjaan”.
|
|
34
Dari definisi-definisi mengenai keselamatan kerja yang diberikan oleh beberapa
ahli
diatas
sangat
jelas bahwa
keselamatan
kerja
memegang
peranan
yang
sangat
penting didalam lingkungan kerja, karena tenaga kerja yang menginginkan
lingkungan kerjanya yang aman, sehat dan nyaman. Selain itu keselamatan dan
kesehatan kerja bagi karyawan dapat menambah semangat dabn ketenangan para
karyawan, sehingga hasil kerjanya dapat lebih baik.
Disamping keselamatan kerja yang memberikan perlindungan dari resiko bahaya
yang dapat terjadi akibat kerja, kesehatan kerja juga membutuhkan perhatian khusus
untuk memebrikan jaminan akan kondisi fisik para karyawannya.
Untuk
memberikan batasan
definisi
kesehatan kerja, dibawah ini akan disajikan
beberapa definisi tentang kesehatan kerja, antara lain :
Drs.
Suma’mur
PK,
Msc.
(Suma’mur,1976) memebrikan
definisi
kesehatan
kerja
sebagai
:
“Spesialisasi
dalam
ilmu
Kesehatan/Kedokteran
beserta
prakteknya yang
bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-
tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial dengan kesehatan yang diakibatkan
faktor-faktor
pekerjaan dan
lingkungan
kerja
serta
terhadap
penyakit-penyakit
umum”.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat
dilihat
bahwa
kemampuan seorang tenaga kerja tergantung dari keadaan kesehatannya, sebab
derajat kesehatan seorang tenaga kerja bukan suatu hal yang bersifat statis melainkan
berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan kemauan masyarakat.
|
|
35
Program higine
perusahaan
dan
kesehatan
kerja
didalam sebuah
perusahaan
mempunyai dua tujuan
utama,
yaitu
sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan
kerja dari tenaga kerja yang setinggi-setingginya dan sebagai alat untuk
meningkatkan
efisiensi
dan
daya
produktivitas
faktor
manusia
dalam produksi
(suma’mur, 1976).
2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan kerja
Faktor-faktor penyebab kecelakaan
tidaklah selalu
sama antara satu dengan
yang
lain.
Akan
tetapi
walaupun
berbeda
semua
memilki
kesamaan
umum,
yaitu
kecelakaan disebabkan oleh dua faktor yaitu
1. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (Unsafe Condition)
2. Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (Unsafe Human
Acts)
Banyak
para
ahli
(Expert)
menyimpulkan
faktor
manusia
dalam timbulnya
kecelakaan sangat
penting,
karena
dari hasil-hasil
penelitian,
bahwa
80-85%
kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Dari hasil persentase
tersebut dapat disimpulkan bahwa akhirnya langsung atau tidak langsung semua
kecelakaan
adalah dikarenakan
faktor
manusia. Faktor
manusia
dapat juga
meliputi
kesalahan
yang
mungkin
saja
dibuat
oleh perencana pabrik, oleh kontraktor yang
membangunnya, pembuat
mesin-mesin, pengusaha, insinyur, ahli kimia, ahli
listrik,
pimpinan
kelompok,
pelaksana,
atau
petugas
yang
melakukan
pemeliharaan
mesin
dan peralatan.
|
|
36
Upaya untuk mencari sebab kecelakaan disebut analisa sebab kecelakaan. Analisa
ini dilakukan dengan mengadakan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap peristiwa
kecelakaan. Analisa
kecelakaan
tidak
mudah,
oleh
karena penentuan
sebab-sebab
kecelakaan secara
tepat adalah pekerjaan sulit.
Kecelakaan kerja
harus secara tepat
dan jelas
diketahui, bagaimana dan mengapa terjadi. Hanya pernyataan bahwa
kecelakaan dikarenakan
oleh
misalnya alat kerja atau
tertimpa benda jatuh tidaklah
cukup, melainkan perlu adanya kejelasan tentang
serentetan peristiwa atau faktor-
faktor
ini
adalah penting artinya
bagi
terjadinya kecelakaan,
tetapi
serentetan
peristiwa
seluruhnyalah
yang
menyebabkan
terjadinyas
kecelakaan.
Apabila
sebab
satu bagian dari rentetan peristiwa tersebut dihilangkan, kecelakaan tidak akan
terjadi.
2.1.2 Hal-Hal Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Kecelakaan Kerja
Dalam
menghindari
terjadinya
kecelakaan
kerja,
harus
adanya
tanggung
jawab
dari
segala
pihak
yang
bersangkutan.
Secara
operasiaonal
pencegahan kecelakaan
kerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab para manajer lini, penyelia, mandor
kepala dan juga kepala urusan. Funsioanris lini wajib memelihara kondisi kerja yang
selamat sesuai dengan ketentuan pabrik pnduan praktek pembikinan yang baik (Good
Manufacturing Practice). Dilain pihak, para kepala urusan wajib senantiasa
mencegah
jangan
sampai
terjadi
kecelakaan.
Kedua
macam funsionaris
ini
kelihatannya mempunyai tanggung jawab berbeda, sebebarnya tidak, pemeliharaan
keadaan tidak selamat dan pencegahan kecelakaan adalah satu funsi yang sama.
|
|
37
Hal-hal yang dapat dilakukan guna mencegah kecelakaan dari aapek manusia
harus bermula pada hari pertama ketika semua karyawan bekerja. Setaip karyawan
harus diberitahu secara tertulis uraian mengenai
jabatannya
yang
mencakup
funsi,
hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab, serta tugas dan syarat-syarat
kerjanya.
Setelah itu harus dipegang prinsip bahwa kesalahan utama sebagian besar
kecelakaan, kerugian atau kerusakan terletak pada karyawan
yang kurang bergairah,
kurang terampil, kurang tepat, terganggu emosinya, yang pada umumnya
meneyebabkan kecelakaan dan kerugian.
Manajemen
(dari
manajer
bagian
hingga ketua
kelompok)
bertanggung
jawab
dalam seleksi, penempatan, pembinaan untuk para karyawan. Manusia adalah mahluk
yang
serba
mudah
berubah
sehingga
pembinaan
yang
serba
baik
tidak selamanya
membawa hasil yang baik. Kelengahan dan kelalaian manajemen dalam pengelolaan
sumber
daya
manusia
perusahaan
akan mengakibatkan
kecelakaan
atau
kerugian.
Setiap anggota manajemen harus tanggap dan serba berhati-hati dalam memimpin
bawahan mereka.
Sikap-sikap karyawan yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut:
1. Tidak mau memakai alat pelindung yang disediakan
2. Melanggar peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diwajibkan
dengan sengaja.
3. Tergesa-gesa dan kurang berhati-hati dalam pekerjaan.
4. Bersikap kasar, bergurau, atau berkelakar sambil kerja (kurang konsentarsi).
|
|
38
5. Tidak memahami arti kerugian bagi perusahaan maupun dirinya.
Tiga sebab mengapa seorang karyawan melakukan kegiatan tidak selamat adalah:
1. yang bersangkutan tidak mengetahui tatacara yang aman atau perbuatan-
perbuatan berbahaya.
2. yang bersangkutan
tidak
mampu
memenuhi
persyaratan
kerja
sehingga
terjadilah tindakan yang dibawah standar.
3. Yang bersangkutan mengetahui seluruh peraturan dan persyaratan kerja, tetapi
dia sungkan memenuhinya.
Dari aspek manusia, gejala penyebab kecelakaan bermula pada kegiatan/perbuatan
tidak
selamat
manusia
itu
sendiri. Beberapa perbuatan yang mengusahakan
keselamatan antara lain:
1. Setiap karyawan bertugas sesuai dengan pedoman dan penuntutan yang
diberikan.
2. Setiap kecelakaan atau kejadian yang merugikan harus segera dilaporkan
kepada atasan
3. Setiap
peraturan dan
ketentuan
keselamatan
dan kesehatan
kerja
harus
dipatuhi secermat mungkin.
4. Semua karyawan harus bersedia saling mengisi atau mengingatkan akan
perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya.
|
|
39
5. Peralatan
dan
perlengkapan keselamatan
dan
kesehatan
kerja
harus dipakai
atau dipergunakan bila perlu.
Selain
itu,
bermacam-macam usaha
yang
dapat
dilakukan
untuk
meningkatkan
keselamatan kerja
diperusahaan-perusahaan atau
tempat-tempat
kerja,
yaitu dengan
membuat dan mengadakan:
1.
Peraturan-peraturan, yaitu peraturan perundangan yang berhubungan dengan
syarat-syarat kerja umum, perencanaan, konstruksi, perawatan, pengawasan,
pengujian
dan
pemakaian peralatan
industri,
kewajiban
pengusaha dan
pekerja,
latihan,
pengawasan
keehatan kerja,
pertolongan
pertama
pada
kecelakaan (P3K) dan pengujian kecelakaan.
2.
standarisasi
:
menyusun
standar-standar
yang bersifat
resmi, setengah
resmi
atau tidak resmi yang berhubungan dengan konstruksi yang aman dari
peralatan industri, keselamatan dan kesehatan kerja, atau alat-alat pelindung
diri.
3. Pengawasan
:
pengawasan
terhadap pelaksanaan dan peraturan perundangan
yang berlaku
4. Technical
research
:
meliputi
hal-hal
seperti
penyelidikan
kandungan
dan
karakteristik dari bahan-bahan berbahaya,
mempelajari
pengamanan
mesin,
pengujian respirator, penyelidikan tentang cara pencegahan gas dan debu yang
mudah meledak, menyelidiki bahan dan desain yang cocok untuk bahan baku
yang digunakan.
|
|
40
5.
Medical
Research : meliputi
hal-hal
yang
khusus mengenai
penyelidikan
pengaruh psikologis dan fisiologis dari faktor-faktor lingkungan dan teknologi
serta keadaan fisik yang menjurus kepada kecelakaan.
6.
Psychological Research
:
misalnya penyelidikan mengenai pola-pola
psikologis yang menjurus kepada kecelakaan.
7. Statistic Research :
untuk menentukan berbagai macam dari kecelakaan yang
terjadi, jumlah, jenis orang-orangnya, operasinya dan sebab-sebabnya.
8. Pendidikan :
meliputi pengajaran dan pendidikan keselamatan kerja sebagai
mata pelajaran disekolah-sekolah teknik dan pusat-pusat latihan.
9.
Training
: misalnya
memberikan
instruksi
atau
petunjuk-petunjuk
praktek
kepada para pekerja dan pekerja-pekerja yang baru masuk, mengenai hal
keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Penerangan :
misalnya menanamkan pengertian dan kesadaran keselamatan
dan kesehatan kerja kepada para pekerja dengan cara pembinaan dan
penertiban dan lain-lain.
11. Asuransi
:
misalnya memberikan insentif keuangan untuk meningkatkan
usaha pencegahan kecelakaan, umpamanya dalam bentuk pemberian reduksi
terhadap premi yang dibayar oleh pihak pengusaha, apabila ternyata tingkat
kecelakaan dalam pabriknya menurun.
12. tindakan usaha keselamatan kerja ditempat kerja.
|
|
41
2.2 Beberapa Prinsip Pencegahan Kebakaran
2.2.1 Pencegahan Kebakaran
Banyak
sekali kebakaran
pabrik terjadi diluar
jam kerja.
Tentunya
hal
ini
tidak
menimbulkan korban manusia tetapi dapat menyebabkan kehilangan lapangan
pekerjaan yang berarti kerugian dibidang sosial dan ekonomi. Kebakaran-kebakaran
yang
terjadi
dalam jam-jam kerja
sangat
berbahaya
bagi
pekerja.
Sesungguhnya
banyak yang dapat dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap tempat
kerja
untuk mencegah bahaya kebakaran, dan pekerja pun bertanggung
jawab
terhadap pemakaian alat-alat pencegahan kebakaran secara efektif.
2.2.2 Bahaya Kebakaran Umum
Timbulnya suatu kebakaran disebabkan tiga unsur yaitu oksigen, bahan bakar dan
panas.
Tanpa oksigen tidak
ada
yang dapat terbakar, tanpa panas tidak akan
terjadi
kebakaran.
Penyebab
terjadinya
kebakaran
umum adalah
api
rokok,
cairan
yang
mudah terbakar, nayal apai terbuka, penataan ruang yang tidak sempurna, mesin-
mesin yang terlalu panas karena kurang perawatan, instalasi listrik, listrik statis,
peralatan las dan solder. Beberap industri antara
lain
industri kimia,
minyak dan cat
mempunyai potensi bahaya kebakaran khusus.
2.2.3 Konstruksi Dan Pintu Keluar Bangunan
Konstruksi bangunan erat sekali hubungannya
dengan
usaha
penaggulangan
kebakaran.
Bangunan-bangunan
industri harus dari bahan
tahan
api.
Hal
ini adalah
|
|
42
masalah arsitek dan perencana. Konstruksi tahan api dapat meyakinkan bahwa
bagian-bagian dari bangunan tidak dapat terbakar dengan mudah dan api tidak dapat
menyebar
melalui
bangunan
baik secara
vertikal
melalui
dinding-dinding,
lantai-
lantai, pintu-pintu, lift, tangga atau saluran-saluran ventilasi. Pintu-pintu keluar
penting sekali dan harus sesuai dengan syarat-syarat berikut:
1. Bagian dari bangunan tidak boleh jauh dari pintu-pintu menuju keluar,
jaraknya tergantung dari tingkat bahaya didalamnya.
2. Setiap lantai harus mempunyai paling sedikit 2 pintu keluar, dengan luas yang
cukup,
bebas dari
nyala
api
dan
asap dan keduanya
garus
terpisah dengan
jarak yang cukup jauh.
3. Tangga kayu, tangga spiral dan lift tidak dihitung sebagai pintu keluar.
4.
Pintu-pintu keluar
harus
diberi tanda petunjuk dan dengan penerangan yang
cukup.
5. Pintu-pintu keluar harus selalu bebas atau tidak terdapat rintangan-rinatngan.
6.
Tangga luar dan jalan-jalan pelarian kebakaran (Fire Escape) tidak boleh
merupakan jalan buntu dan harus menuju keluar bangunan.
2.2.4 Peralatan Pemadam kebakaran
Penyediaan
peralatan
pemadam
api
dapat terdiri
dari
peralatan
yang
sederhana
sampai kepada peralatan yang modern misalnya Sprinkler systems. Macam dan
jumlah
peralatan
yang
dibutuhkan
tergabtung
pada
luas
dan
konstruksi
bangunan
|
|
43
yang akan dilindungi atau diamankan dan proses produksi yang dilakukan
didalamnya.
Kadang-kadang cukup dengan tabung pemadam api atau persediaaan pasir kering
atau beberapa ember
yang diisi air. Didaerah yang
mempunyai jaringan
ledeng air,
kebayakan pabrik-pabrik dilengkapi dengan Hydrant dan selang pemadam kebakaran.
2.2.5 Tabung-Tabung Pemadam Api
Dalam pemakaian tabung-tabung pemadam api, harus dijaga betul supaya tabung-
tabung tersebut tidak menimbulkan bahaya. Sering terjadi bahwa konstruksi tabung
pemadam api tidak sesuai dengan pengisian zat kimia, sehingga menyebabkan mulur
semprotnya menjadi buntu. Sewaktu tabung ini harus dipergunakan zat kimia
didalamnya tercampur dengan membalikkan tabung pemadam api. Tekanan dalam
silinder
meningkat
sehingga
memaksa
bahan pemadam
api
yang
didalamnya
menyemprot keluar,
tetapi jika mulut semprot kebetulan buntu, tekanan tinggi yang
ada didalam dapat mengakibatkan tabung silinder menjadi pecah atau meledak. Oleh
sebab
itu konstruksi yang sesuai dengan isinya dan pemeliharaan
serta pengawasan
secara teratur dapat mencegah terjadinya kecelakaan semacam ini.
2.2.6 Alarm Kebakaran
Alarm kebakaran harus tersedia untuk
memperingatkan kepada setiap orang jika
terjadi kebakaran. Hal ini dapat dilakukan apabila tersedia alarm yang bekerja secara
otomatis dengan pemasangan alarm bells, sirine ditempat-tempat kerja didalam
|
|
44
pabrik dan tersedia pula tombol tekan atau handles untuk membunyikan alarm apabila
dianggap
perlu.
Alarm harus
dapat
didenganr
dimana
saja
didalam
area
pabrik
termasuk diruangan kerja didalam gudang,
gang-gang, dikamar pakaian kerja dan di
kamar kecil.
2.3 Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
2.3.1 Pengertian Manajemen
Manajemen sebagai satu ilmu prilaku yang mencakup aspek sosial dan eksak tidak
tidak terlepas
dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari segi
perencanaan, maupun pengambilan keputusan dan organisasi. Baik kecelakaan kerja,
gangguan kesehatan, maupun pencemaran lingkungan harus merupakan bagian dari
biaya
produksi.
Sekalipun
sifatnya
sosial, setiap
kecelakaan
atau
tingkat
keparahannya
tidak
dapat
dilepaskan
dari faktor
ekonomi
suatu
lingkungan
kerja.
Pencegahan kecelakaan dana
pemeliharaan hygene
dan
kesehatan
kerja
tidak
saja
dinilai dari segi biaya pencegahannya, tetapi juga dari segi manusianya.
|
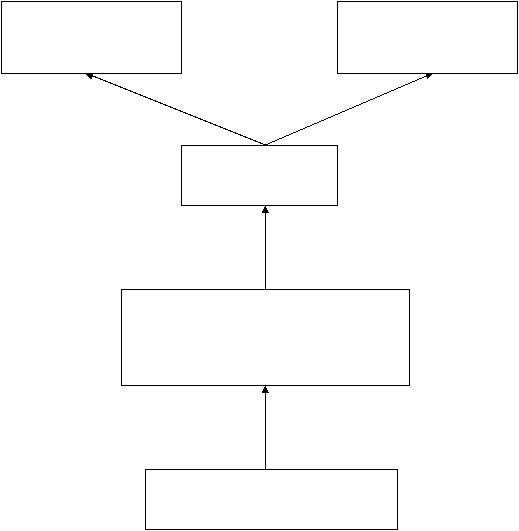 45
2.3.1 Akar Kecelakaan Kerja
KERUGIAN MATERI
KERUGIAN TENAGA
KERJA
KECELAKAAN
•
PERBUATAN TIDAK SELAMAT
•
KEADAAN TIDAK SELAMAT
KEBIJAKAN MANAJEMEN
Diagram 2.1. Manajemen : Akar Kecelakaan Kerja
|
|
46
Adapun yang termasuk didalam perbuatan tidak selamat dan keadaan tidak
selamat, masing-masing unsurnya adalah sebagai berikut :
A. Perbuatan tidak selamat / berbahaya ditekankan kepada unsur manusia :
1. Kegiatan tidak sah
2. Kegiatan dengan kecepatan yang berbahaya
3. Tidak memanfaatkan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja
4. Salah penggunaan perlengkapan atau penggunaan alat perlengkapan yang
tidak tepat
5. Pemuatan, penempatan, pencampuran, penyatuan yang tidak selamat
6. Mengambil kedudukan atau sikap yang tidak selamat
7. Bekerja pada peralatan yang bergerak atau yang perlengkapannya berbahaya
8. Mengganggu, mengejek, menyalahgunakan, dan mengejutkan
9. Tidak memakai pakaian keamanan atau pelindung badan
B. Keadaan tidak selamat / berbahaya ditekankan pada unsur lingkungan
1. Perlindungan yang kurang memadai
2. Tanpa pelindung
3. Keadaan yang rusak
misalnya kasar, tajam, licin, ambruk, berkarat, longgar,
bengkok
4. Rancangan
atau
konstruksi
yang
tidak
selamat
(Unsafe
design
or
constraction)
|
|
47
5. Penyusunan, penimbunan, penyimpanan,
gang, pintu, keluar, tata
ruang,
rancangan, muatan yang berlebihan, penjajaran yang berbahaya
6. Penerangan yang kurang selamat
7. Peredaran udara yang tidak selamat
8. Pakaian atau perlengkapan yang kurang selamat
2.4 Pengukuran Kinerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
American National Standard Instirute (ANSI) menerbitkan metode standar untuk
mengukur kinerja dengan menggunakan ratio kekerapan cidera (injury frequency
rate) dan ratio keparahan cidera (injury severity rate).
Kedua angka ini membandingkan jumlah kejadian kecelakaan dan jumlah hari
hilang
karena
kecelakaan
dengan
jumlah
jam orang
bekerja.
Kedua
ratio
ini
distandarisasi sehingga tidak dipengaruhi jumlah tenaga kerja yang bekerja
diperusahaan. Dengan demikian kinerja yang diukur dengan ratio ini dapat
diperbandingkan. Dengan menggunakan ratio ini kinerja perusahaan untuk kurun
waktu yang berbeda bisa pula dibandingkan.
2.4.1 Ratio Kekerapan Cidera
Menurut standar ANSI, ratio kekerapan cidera adalah jumlah cidera yang
menyebabkan
tidak
bisa
bekerja
per
sejuta orang
pekerja,
dengan
rumus
sebagai
berikut :
|
 48
Ratio kekerapan cidera = Jumlah kecelakaan x 1.000.000
Jumlah man-hours kerja
2.4.2 Ratio Keparahan Cidera
Sedangkan ratio keparan cidera adalah jumlah hari kerja yang hilang per sejuta
jam pekerja dengan rumus sebagai berikut :
Ratio keparahan cidera = Hari kerja yang hilang x 1.000.000
Jumlah Man-Hours kerja
Yang dimaksud dengan
hari kerja yang hilang terdiri dari hari kerja yang aktual
yaitu jumlah hari kerja pekerja tidak dapat masuk bekerja karena cidera dan hari kerja
sebagai
nilai dari
beratnya cacat
tetap
yang
dibebankan
sebagai
hari
kerja
hilang.
Misalnya
standar ANSI
Tahun 1992 (tabel 2.1). Mati dinilai
dan dibebankan 6000
hari kerja. Demikian pula cacat tetap total. Cacat tetap sebagian dinilai sesuai dengan
berat
cacatnya
misalnya
kehilangan
tangan
dinilai
600 hari
kerja. Nilai
yang
dibebankan lebih besar dari kehilangan hari kerja yang sesungguhnya sebagai
kompensasi
turunnya
kemampuan
kerja karena
cacat tetapnya. Untuk menghitung
jumlah man-hours kerja yang digunakan dalam perhitungan ratio cidera adalah
jumlah total jam kerja karyawan dalam setahun
/
sebulan dikurangi jumlah absensi
pekerja dalam setahun / sebulan.
Memperhitungkan
hari
kerja
yang
hilang karena cidera akibat kerja, yang
sebenarnya
adalah
hari
seorang
pekerja
tidak
bisa
masuk
bekerja,
yang
|
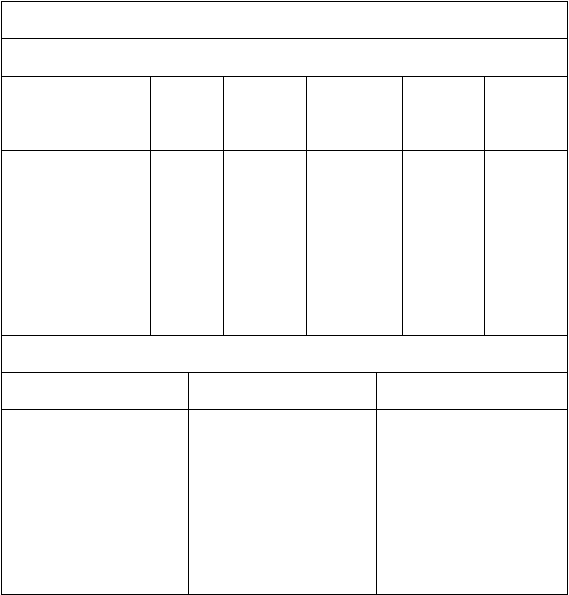 49
diperhitungkan mulai shift hari berikutnya. Pada cacat anatomis atau cacat fungsi
digunakan
konversi
nilai
cacat
kedalam hari
kerja
yang
hilang
sesuai
tabel
2.1.
dibawah ini:
Tabel 2.1. Konversi Cacat Badan dan Hilang Hari Kerja
A. Kerugian Anggota badan Karena Cidera Atau Pembedahan
1. Tangan Dan Jari
Amputasi seluruh
atau sebagian tulang
Ibu Jari
Telunjuk
Jari Tengah
Jari manis
kelingking
Ruas Tulang
Ruas Tengah
Ruas Bawah
Bagian Telapak
Pergelangan = 3000
300
-
600
900
100
200
400
600
75
150
300
500
60
120
240
450
50
100
200
400
2. Jari Kaki
Jari Kaki
Ibu Jari
Jari Lain
Ujung
Ruas Tengah
Bagian Bawah
Bagian Telapak
Pergelangan : 2000
150
-
300
600
35
75
150
350
|
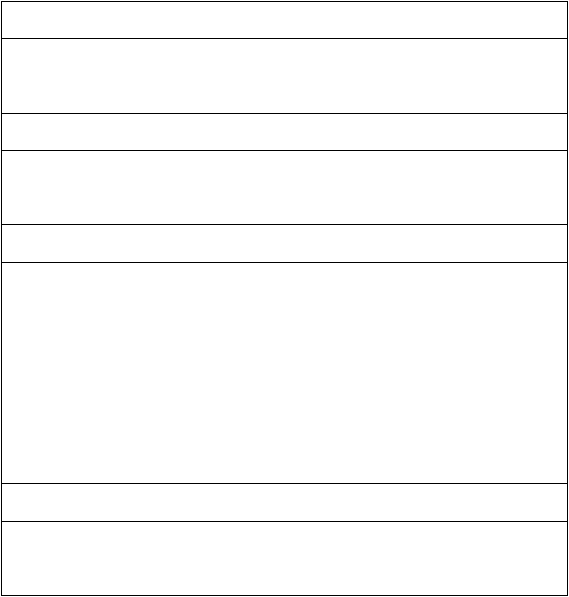 50
3. Lengan
Tiap bagian dari pergelangan sampai siku
: 3600
Tiap bagian siku sampai sendi bahu
: 4500
4. Tungkai
Tiap bagian dari atas mata kaki sampai lutut
: 3000
Tiap bagian dari atas lutut sampai pangkal paha
: 4500
B. Kehilangan Fungsi
Satu mata
: 1800
Dua mata
: 6000
Satu telinga tidak berfungsi
: 600
Dua telinga tidak berfungsi
: 3000
Lumpuh total
: 6000
Meninggal dunia
: 6000
C. Lumpuh Total Atau Meninggal
Lumpuh total menetap
: 6000
Meninggal
: 6000
|
|
51
2.5 Kalisifikasi Kecelakaan Kerja
Klasifikasi
kecelakaan kerja
menurut Organisasi
Perburuhan
Internasional
tahun
1962 adalah sebagai berikut :
1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan :
a. Terjatuh
b. Tertimpa benda jatuh
c. Tertumbuk benda-benda, terkecuali benda jatuh
d. Terjepit oleh benda
e. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
f.
Pengaruh suhu tinggi
g. Tekanan arus pendek
h. Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi
i.
Jenis-jenis
lain, termasuk kecelakaan-kecelakaan yang data-datanya tidak
cukup atau kecelakaan-kecelakaan lain yang belum masuk kalsifikasi tersebut.
2.
Klasifikasi menurut penyebab:
a. Mesin
i.
Pembangkit tenaga, terkecuali motor-motor listrik
ii. Mesin Penyalur (transmisi)
iii.
Mesin-mesin pengolah kayu
iv.
Mesin-mesin pertanian
v. Mesin-mesin pertambangan
vi.
Mesin-mesin lain yang tidak termasuk klasifikasi tersebut
|
|
52
b. Alat-alat dan alat angkat
i.
Mesin angkat dan peralatannya
ii.
Alat angkutan diatas rel
iii.
Alat angkutan lain yang beroda, terkecuali kereta api
iv.
Alat angkutan udara
v. Mesin-mesin pertanian
vi.
Mesin-mesin pertambangan
c. Peralatan lain
i.
Bejana bertekanan
ii. Dapur pembakar dan pemanas
iii.
Instalasi pendingin
iv.
Instalasi listrik, termasuk motor listrik
v. Alat-lata listrik (tangan)
vi.
Alat-alat kerja dan perlengkapannya
vii. Tangga
d. Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi
i.
Bahan peledak
ii.
Debu, gas, cairan dan zat-zat kimia, terkecuali bahan peledak
iii.
Benda-benda melayang
iv.
Radiasi
v. Bahan-bahan dan zat-zat lain yang belum termasuk golongan tersebut
|
|
53
e. Lingkungan kerja
i.
Diluar ruangan
ii.
Didalam bangunan
iii.
Dibawah tanah
f.
Penyebab-penyebab lain yang belum termasuk golongan-golongan diatas:
i.
Hewan
ii. Penyebab lain.
3.
Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan
a. Patah tulang
b. Dislokasi/ keseleo
c. Regang otot/ urat
d. Memar dan luka dalam
e. Amputasi
f.
Luka-luka lain
g. Luka dipermukaan
h. Gegar dan remuk
i.
Luka bakar
j.
Keracunan-keracunan mendadak (akut)
k. Akibat cuaca
l.
Mati lemas
m.
Pengaruh arus listrik
n. Pengaruh radiasi
|
|
54
o. Luka-luka yang banyak dan berlainan sifatnya
p. Lain-lain
4.
Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka ditubuh
a. Kepala
b. Leher
c. Badan
d. Anggota atas
e. Anggota bawah
f.
Banyak tempat
g. Kelainan umum
h.
2.6 Beberapa Prinsip Pencegahan kecelakaan
2.6.1 Perencanaan
Perencanaan yang baik penting sekali artinya
untuk keselamatan
kerja
produksi.
Apabila suatu pabrik baru akan dibangun atau pabrik yang sudah ada ingin diperbaiki,
maka dalam tingkat perencanaan harus diperhatikan mengenai keselamatan kerja dan
produksi, misalnya ruangannya, fasilitas untuk penimbunan dan pengambilan barang-
barang dan alat-alat,
lantai-lantai, penerangan, pemanasan,
ventilasi, lift, ketel uap,
listrik, mesin-mesin, fasilitas perawatan, perbaikan dan usaha pencegahan kebakaran.
Penting
sekali
bahwa
masalah
keselamatan
kerja
timbul
dalam pemikiran
pada
waktu perencanaan dan bukan pada waktu pabrik sudah selesai dibangun. Jadi harus
|
|
55
selalu
diikutsertakan ahli keselamatan
kerja
mulai dari perencanaan
sampai selesai
pekerjaan.
Sebaiknya rencana pembuatan dan perbaikan pabrik disampaikan terlebih dahulu
kepada pengawas keselamatan kerja setempat untuk mendapatkan tanggapan dan
saran-saran. Hal
ini penting untuk
usaha pencegahan kecelakaan. Perencanaan
yang
baik sangat menguntungkan baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi
keselamatan kerja.
Ada beberapa
prinsip
manajemen pabrik yang
dapat diikuti dalam perencanaan
keselamatan kerja dan efisiensi produksi, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Usahakan seminimal mungkin pengaturan barang yang dilakukan dengan
pekerjaan tangan.
2. Penyediaan tangga-tangga, paltform, gang-gang dan
lantai-lantai yang aman
untuk dilalui pekerja.
3. Penyediaan ruangan yang cukup untuk penempatan mesin-mesin dan alat-alat.
4. Penyediaan jalan masuk yang aman ketempat-tempat kerja.
5. Penyediaan tenaga
untuk perawatan dan pemeliharaan
yang mengetahui
tentang keselamatan kerja.
6. Penyediaan fasilitas angkutan-angkutan yang aman.
7. Penyediaan sarana
yang cukup baik untuk jalan-jalan atau pintu-pintu keluar
bila terjadi kebakaran.
8. Memungkinkan untuk perluasan
9. Penyekatan terhadap proses yang berbahaya.
|
|
56
10. Sedapat mungkin harus diusahakan pembelian mesin-mesin dengan peralatan
pengaman yang sudah langsung terpasang.
2.6.2 Penataan Ruangan Yang Baik Dan Penjagaan Kebersihan
Penataan
seluruh
ruangan
pabrik
dan penjagaan
kebersihan
merupakan
faktor
penting dalam
usaha peningkatan keselamatan kerja. Apabila tersedia tempat khusus
untuk keperluan masing-masing barang dan peralatan dan masing-masing berada
pada tempatnya yang tertentu, kecelakaan-kecelakaan mungkin dapat dihindari.
Penataan
secara
teratur akan dapat mencegah benturan-benturan
dan
tersandung
serta memperlancar usaha untuk berlari keluar ruangan apabila timbul bahaya. Jalur-
jalur jalan harus diberi tanda dengan jelas dan tidak boleh dipergunakan untuk tempat
penyimpanan barang-barang. Penataan yang teratur berarti pula bahan dan barang-
barang harus disimpan dalam ruangan khusus sesuai keperluannya.
Suatu aspek kebersihan dan penataan yang baik adalah pemeriksaan secara teratur
dan
membuang
alat-alat
yang
sudah
rusak.
Penataan
ruangan
yang baik dan
penjagaan kebersihan, tidak hanya bertujuan untuk mencegah kecelakaan, tetapi juga
penting untuk pengaruh psikologis. Hal ini dapat menyebabkan pekerja akan bekerja
dengan
tenang
dan
hati-hati,
sebaliknya
jika ruangna kotor dan tidak teratur dapat
menyebabkan kecelakaan kerja.
|
|
57
2.6.3 Kacamata Pengaman
Yang paling sulit dalam usaha pencegahan kecelakaan adalah masalah pencegahan
kecelakaan mata. Orang biasa memakai kacamata dengan resep dokter, biasanya
menolak memakai kacamata pengaman karena dianggap mengganggu dan
menyebabkan tidak enak. Kini penyediaan kacamata pengaman yang memuaskan
sudah semakin meningkat. Namun demikian tidak cukup dengan hanya menyediakan
kacamata pengaman yang baik saja, tetapi penting pula dalam hal mengusahakan agar
pekerja bersedia memakainya. Hal ini dapat dilakukan dengan disiplin dan
pendidikan. Pekerja
yang
berfikir bahwa kecelakaan
mata
merupakan
suatu
resiko
besar,
akan bersedia
memakai
kacamata
pengaman
dengan
kesadaran
sendiri,
sedangkan mereka yang menganggap ringan terhadap bahaya tersebut akan
melalaikan pemakainya.
2.6.4 Sepatu Keselamatan Kerja
Sepatu keselamatan kerja harus dapat melindungi kaki dari bahaya kejatuhan
benda
pada
kaki,
palu,
benda
cair
yang
panas,
cairan
asam dan
lain-lain.
Sepatu
keselamatan kerja
yang baik dan
memenuhi syarat
yang dapat
melindungi terhadap
bahaya tekanan, harus memakai pelindung baja pada ujung sepatu dan sol baja.
Sepatu
macam
ini penting untuk
mencegah
bahaya
keselamatan
bagi
pekerja
bangunan dimana banyak terdapat paku-paku dan benda-benda lainnya yang dapat
terinjak dan tersentuh kaki. Sepatu keselamatan juga berguna
untuk mencegah
|
|
58
kecelakaan terpleset akibat banda cair karena memiliki lapisan karet yang tebal atau
biasa disebut sepatu Boots.
2.6.5 Sarung Tangan Pengaman
Sarung tangan pengaman harus diberikan kepada pekerja-pekerja dengan
pertimbangan
untuk
mencagah
bahaya. Macamnya
sarung
tangan
yang
dipakai
tergantung pada bahaya yang harus dicegah misalnya bagi pekerja yang pekerjaannya
memebuat
lubang,
memotong,
mengerjakan
zat kimia yang berbahaya, pekerjaan
listrik, dan lain-lain.
2.6.6 Perlindungan Paru-paru
Perlindungan paru-paru diperlukan ditempat-tempat kerja yang terdapat zat-zat
berbahaya
atau
kelainan
oksigen dalam udara.
Zat-zat
yang
berbahaya
itu
memungkinkan dalam bentuk gas, uap, kabut atau debu dan kelainan oksigen dalam
udara yang berada dalam tempat kerja yang ventilasinya tidak baik misalnya tangki-
tangki atau peti besar.
Zat-zat
yang berbahaya dapat pula berupa racun, korosi atau
zat yang merangsang yang dapat menyebabkan kelainan-kelainan pada kondisi paru-
paru
yang dikenal sebagai Pneumoconiosis. Pada
umumnya Pneumoconiosis adalah
Siliconsis yang disebabkan debu silica. Pemakaian respirator dan masker termasuk
dalam bidang
keselamatan
kerja.
Beberapa
negara
menganggap
masalah
gas
merupakan sumber bahaya kecelakaan.
|
|
59
2.6.7 Peringatan Dan Tanda-tanda (Display)
Peringatan
atau
tanda-tanda
dapat
disediakan untuk
bermacam-macam tujuan
misalnya pemberian instruksi, peringatan-peringatan bahaya, atau informasi secara
umum.
Peringatan
dan
tanda-tanda
tidak boleh
dianggap
sebagai
pengganti
untuk
usaha pengamanan, tetapi hanya untuk membantu usaha tersebut.
Larangan
merokok adalah
salah satu
contoh
yang
umum dipakai
sebagai
tanda
peringatan,
untuk
mengingatkan
nahaya
kebakaran. Peringatan lainnya yang umum
dipakai adalah larangan membuka klep yang
terkunci atau larangan
melayani saklar
sewaktu dilakukan pekerjaan perbaikan atau perawatan. Dan sejumlah tanda
peringatan
lainnya
dipakai
untuk
lalu
lintas
dipabrik. Tanda-tanda penjelasan
disediakan untuk menyatakan dimana letak pintu-pintu bahaya, pos-pos pertolongan
pertama waktu terjadi kecelakaan dan lain-lain.
Display adalah suatu ungkapan yang digunakan pada semua metode penyampaian
informasi
secara tidak langsung. Misalnya pemberitahuan bahaya panas pada mesin
dengan
menggunakan
gambar
yang
bertuliskan
“bahaya
panas,
jangan
dipegang”,
akan
membantu
pekerja
untuk
menghindari mesin tersebut. Display juga dapat
menggunakan media visual, seperti lampu denga warna-warna tertentu yang dapat
mewakili
tanda
peringatan
tertentu. Contohnya
warna
merah
dapat
mewakili
tanda
bahaya, artinya tempat atau mesin dengan lampu merah merupakan tempat yang
berbahaya jadi harus hati-hati apabila berada
atau
menyentuh
tempat tersebut. Dan
juga warna lainnya yang dapat digunakan.
|
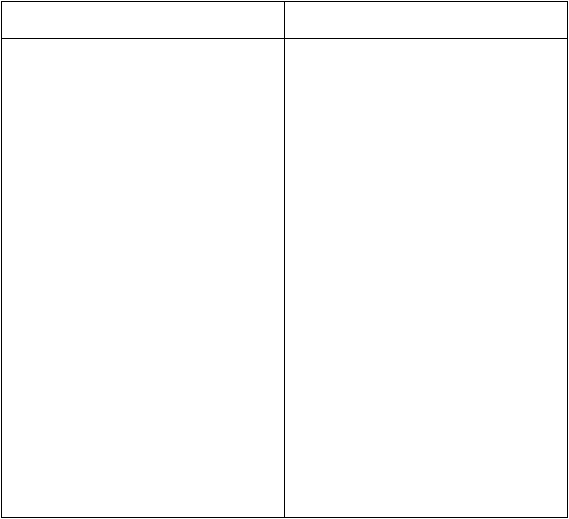 60
Dengan display ini diharapakan para pekerja dapat mengetahui tanda-tanda
peringatan yang diberikan sehingga dapat lebih berhati-hati, dan dapat mecegah
terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan.
Tabel 2.2 Pemilihan Jenis Display
Gunakan Penyajian Suara Jika :
Gunakan Penayjian Visula Jika:
1.
Pesan sederhana
2.
Pesan pendek
3.
Pesan
tidak akan
dikaitkan
lagi
pada
masa yang akan datang
4.
Pesan berhubungan dengan kejadian
dalam waktu tertentu
5.
Pesan memberikan tindakan segera
6.
Sistem
visual
dari
orang
tersebut
sudah terlalu sibuk
7.
Lokasi penerimaan terlalu terang atau
gelap sehingga diperlukan adapatasi
8.
Pekerjaan dari orang tersebut selalu
berpindah-pindah
1.
Pesan rumit
2. Pesan panjang
3. Pesan akan diperlukan lagi pada masa
yang akan datang
4. Pesan
berhubungan
dengan
lokasi
pada suatu daerah
5. Pesan tidak
membutuhkan
tindakan
segera
6. Sistem audio (pendengaran) dari orang
tersebut sudah terlalu sibuk
7. Lokasi penerimaan terlalu sibuk
8. Pekerjaan
orang
tersebut
selalu
tetap
pada satu tempat.
|
|
61
2.7 Kondisi Lingkungan Kerja Fisik
Manusia sebagai seoarnag pekerja pekerja tidak luput dari kekurangan, dalam
arti kata segala kemampuannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-
faktor tersebut bisa datang dari dirinya sendiri (intern) atau
mungkin dari pengaruh
luar (extern). Salah satu faktor yang berasal dari laur adalah kondisi lingkunag kerja
yaitu semua keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja, seperti: temperatur,
kebisingan, pencahayaan, sirkulasi udara, bau-bauan, dan
lain-lain –
yang dalam hal
ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil kerja manusia tersebut.
2.7.1 Penerangan (Lighting)
Penerangan penting sekali sebagai suatu faktor keselamatan kerja dalam
lingkungan kerja. Beberapa hasil penyelidikan menunjukan bahwa penerangan yang
baik dapat mengurangi kecelakan dan meningkatkan
produksi
dan
efisiensi
kerja.
Kecelakaan dapat
pula
disebabkan oleh
faktor
kelelahan, penerangan
yang
baik
merupakan suatu usaha pencegahan kecelakaan.
Apabila dalam suatu ruangan kerjaterdapat banayk pekerja, penting sekali untuk
memebri penerangan pada tempat-tempat
yang gelap seperti gang-gang, tangga-
tangga dan jalur-jalur keluar. Dalam prakteknya hal ini memang merupakan masalah
yang sulit. Biasanya digunakan penerangan
dengan
lampu-lampu
darurat
yang
mendapat aliran khusus dari generator kecil terpisah dari aliran listrik umum, tetapi
tidak semua perusahaan dapat melaksanakan sistem ini.
|
|
62
Pencahayaan sangat mempengaruhi manusia untuk melihat suatu objek secara
jelas, cepat, tanpa menimbulkan kesalahan.
Kemampuan mata untuk dapat melihat objek dengan jelas ditentukan oleh ukuran
objek, derajat kontras, lumenensi dan lamanya melihat. Derajat kontras adalah
perbedaan derajat terang relatif antara objek dengan lingkungan sekitarnya.
Lumenensi artinya banyaknya berkas cahaya perunit area yang dipantulkan atau
dipancarkan dari permukaan suatu objek.
Efektifitas mata dalam melihat suatu objek ditentukan oleh
letak
sumber cahaya.
Sebaiknya mata tidak langsung menerima cahaya dari sumbernya (akan menyebakan
silau), tetapi cahaya tersebut harus terpantul dari objek yang ingin dilihat.
Cahaya
adalah
energi
yang
dipancarkan
dan
mampu
merangsang retina
dan
menghasilakn sebuah visual. Cahay datang dari dua sumber yaitu:
1. Dari sumber panas misalnya : matahari dan api
2. Dari sumber dingin yaitu objek yang memantulkan cahaya.
cahaya yang dipantulakn dari objek mempunyai 3 karakteristik :
1. Panjang gelombang dominan yang memungkinkan kita mengenali warna dari
cahaya misalnya : kuning, biru, dan lain-lain.
2. Luminance (Terangnya cahaya)
3. Saturation
(Jenuhnya
cahaya)
adalah
derajat
perbedaan
cahaya
dari
warna
abu-abu.
Lampu dengan watt yang sama tidak memebrikan derajat terangan yang sama.
Lampu bohlam
dengan daya
100
W
bisa
memberikan
lumen
(derajat terang)
yang
|
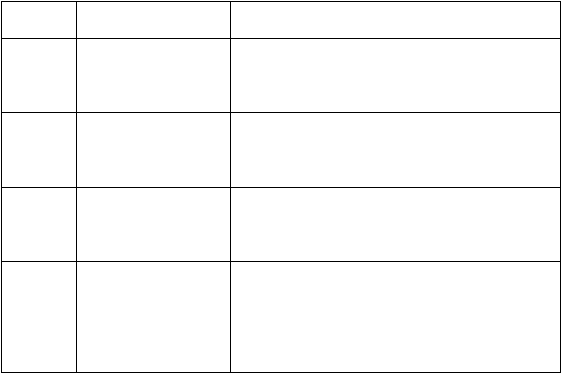 63
lebih rendah dibanding dengan lampu neon. Karena itu, yang harus dipertimbangkan
juga nilai lumen dan daya listrik yang diperlukan.
Bennet, Chitangia, dan Pangrekar (1977)
menemukan
bahwa
terang sumber
cahaya
tidak berhubungan secara
linear dengan
kecepatan penyelesaian
tugas. Ada
batas tertentu dimana penambahan terang sumber cahaya tidak lagi membantu
penyelesaian tugas.
Ross (1978)
menambahkan,
meningkatkan
iluminasi
lebih
dari
500
lx
(50
fc)
hanya
meningkatkan
sedikit performans kerja.
Hal
lain
yang
perlu
diperhatikan adalah bekerja ditempat yang terlalu terang justru menyilaukan mata dan
berakibat buruk pada jangka panjang.
Tabel 2.3 Tingkat Pencahayaan Yang Disarankan Oleh IESNA
Kategori
Terang lux (fc)
Jenis Aktivitas
A
20-30-50
(2-3-5)
Tempat publik dengan lingkungan yang gelap
B
50-75-100
(5-7,5-10)
Daerah untuk kunjungan singkat
C
100-150-200
(10-15-20)
Area kerja dimana pandangan mata tidak penting
D
200-300-500
(20-30-50)
Pekerjaan
visual dengan keadaan kontras
tinggi
dan
ukuran
besar
:
membaca,
mengetik,
pemeriksaan, dan perakitan kasar
|
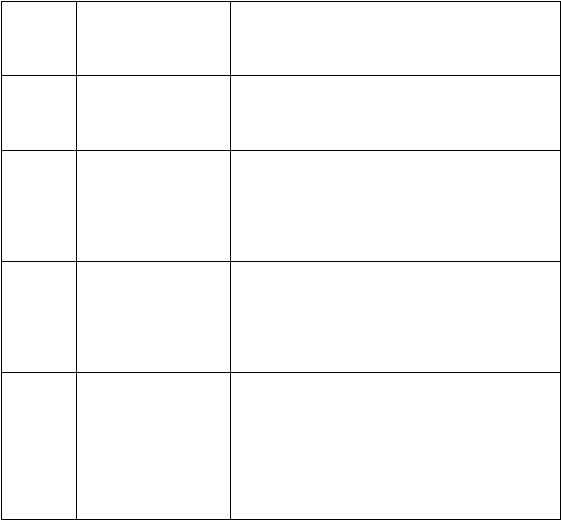 64
E
500-750-1000
(50-75-100)
Pekerjaan visual dengan kontras medium dan
ukuran kecil
F
1000-1500-2000
(100-150-200)
Pekerjaan
visual
dengan
kontras
rendah
dan
ukuran sangat kecil
G
2000-3000-5000
(20-30-50)
Pekerjaan
visual
dengan
kontras
rendah
dan
ukuran yang sangat kecil dan dalam waktu lama
: inspeksi yang sulit, perakitan yang rumit
H
5000-7500-10000
(500-750-1000)
Pekerjaan
yang
sangat
lama dan
membutuhkan
pandangan
yang eksak
:
perakitan dan inspeksi
yang super sulit
I
10000-15000-20000
(1000-1500-2000)
Pekerjaan
yang
membutuhkan
pandangan
mata
khusus pada kontras yang sangat rendah dan
ukuran yang sangat kecil : ruang operasi gawat
darurat
2.7.2 Temperatur
Dalam keadaan
normal,
tiap
anggota
tubuh
manusia
mempunyai
temperatur
yang berbeda-beda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk memepertahankan keadaan
normal ini dengan
sesuatu sistem tubuh yang sangat sempurna sehingga dapat
menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi diluar tubuhnya. Tetapi
|
|
65
kemampuan manusia untuk meneysuaikan diri inipun ada batasnya, yaitu bahwa
tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika
perubahan temperatur luar tubuh ini tidak melebihi dari 20% untuk kondisi panas dan
35% untuk kondisi dingin, semuanya dari keadaan normal tubuh (Sutalaksana, 1979,
h.81)
Penyesuaian diri dilakukan dengan konveksi, radiasi, dan penguapan. Dalam
keadaan dingin, tubuh manusia akan kehilangan
panas tubuh
melalui konveksi
dan
radiasi serta sebagian kecil melalui penguapan. Dalam keadaan panas, tubuh manusia
akan menerima konveksi dan radiasi yang jauh lebih besar dari penguapan yang
dilakukan tubuh. Ini menyebabkan temperatur tubuh ikut naik sebanding dengan
makin tingginya temperatur uadar. Temperatur yang terlampau dingin akan
mengakibatkan gairah kerja menurun, sedangkan temperatur udara yang panas akan
mempercepat kelellahan tubuh dan pekerja akan cenderaung lebih banyak melakukan
kesalahan. Kondisi optimum untuk manusia sekitar 24-27°C.
Kebanyakan orang tidak menyadari tentang kondisi suasana nyaman didalam
ruangan. Hanya bila kondisi itu menyimpang dari batas kenyamanan, kita akan
mengalami
ketidaknyamanan.
Perasaan tidak
nyaman
dapat
bervariasi
dari
menggangu
sampai
pada
kesakitan,
bergantung
pada
derajat
usikan
dari
pengatur
suhu. Rasa tak nyaman penting secara biologis, karena ia menyebabkan orang
mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan keseimbangan suhu. Manusia
dapat menghindari rasa tak nyaman dengan jalan mengenakan pakaian yang sesuai
atau dengan menciptakan lingkungan nyaman dengan menerapkan teknologinya,
|
|
66
Penyimpangan dari batas kenyamanan suhu menyebabkan perubahan fungsional
yang meluas. Terlalu panas dapat menyebabkan perasaan cepat capai dan lelah yang
mengurangi kesediaan untuk berprestasi dan meningkatkan frekuensi kesalahan.
Hambatan
atas
kejadian
ini
mengurangi
laju
produksi
panas
didalam badan.
Sebaliknya jika terlalu dingin membuahkan rasa ngantuk dan mengurangi daya atensi,
yang berpengaruh negatif terutama pada kerja mental.
Menurut
penyelidikan
untuk
berbagai tingkat
temperatur
akan
memberikan
pengaruh yang berbeda-beda seperti berikut:
•
±
49°
C
:
Temperatur
yang dapat
ditahan
sekitar
1
jam,
tetapi jauh
diatas
tingkat kemampuan fisik dan mental.
•
±
30° C : Aktivitas mental dan daya tanggap mulai menurun dan cenderung
untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan, timbul kelelahan fisik.
•
± 24° C : Kondisi optimum.
•
± 10° C : Kecelakaan fisik yang ekstrim mulai muncul.
Kombinasi dari kerja dan temperatur lingkungan kerja dapat menyebabkan sebuah
peningkatan
dalam penyimpangan
panas
dalam tubuh,
yang
akhirnya
dapat
menghasilkan kondisi resiko yang serius pada kesehatan pekerja, dan penurunan
produktivitas pekerja.
Pekerja
pada lingkungan kerja
yang
dingin
dapat
melindungi
diri dengan beberapa
lapis pakaian tetapi kombinasi antara temperatur
yang
rendah
dengan pakaian dapat menyebabkan akibat negatif
pada
sistem motorik tubuh
manusia.
Lingkungan
dengan
temperatur
yang
dingin
sekali
dapat
mempengaruhi
|
|
67
kesehatan pekerja,
bagian
tangan,
lengan,
jari tangan serta
kaki
merupakan bagian
tubuh yang paling banyak terkena dampak temperatur yang dingin.
2.7.3 Sirkulasi Udara
Untuk menjaga agar udara disekitar tempat kerja tetap sehat dalam arti kata cukup
mengandung oksigen dan bebas dari zat-zat yang bisa mengganggu kesehatan, harus
dipikirkan tentang sirkulasi udara yang baik, sehingga udara kotor bisa diganti
dengan udara segar dan bersih, dimana melalui jendela atau ventilasi inilah udara
bersih dan segar didalam ruangan bisa dijamin kesehatannya, karena akan terjadi
sirkulasi udara dengan sendirinya.
Sebagaimana kita ketahui, udara sekitar kita mengandung 21% oksigen, 78%
nitrogen, 0,03% karbondioksida dan 0,97% gas lainnya (campuran). Oksigen (O²)
merupakan
gas
yang sangat dibutuhkan oleh
mahlik
hidup terutama untuk
menjaga
kelangsungan
hidup
kita,
yaitu
proses
untuk metabolisme.
Udara
disekitar
kita
dikatakan kotor apabila kadar oksigen didalam
uadara tersebut telah berkurang dan
telah bercampur dengan gas-gas atau bau-bauan yang berbahay bagi kesehatan tubuh.
Kotornya
udara disekitar kita dapat dirasakan dengan sesaknya pernafasan kita, dan
ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama, karena akan mempengaruhi
kesehatan tubuh dan akan mempercepat proses kelelahan.
Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman disekitar tempat kerja.
Pada siang hari, dimana biasanya manusia melakukan sebagian besar dari
kegiatannya, pohon-pohon
merupakan penghasil oksigen
yang dibutuhkan oleh
|
|
68
pernafasan manusia. Dengan cukupnya oksigen disekitar kita, ditambah dengan
pengaruh
secara
psikologis
akibat
adanya tanaman-tanaman disekitar tempat kerja,
keduanya
akan
memberikan
kesejukan
dan kesegaran
pada
jasmani
manusia.
Rasa
sejuk dan segar selama bekerja akan sangat membantu untuk memeprcepat pemulihan
tubuh akibat lelah setelah bekerja (Sutaklaksana, 1979, h.84).
2.7.4 Kebisingan
Mengenai kebisingan
hingga
saat
ini belum ada perumusan yang tepat
mengenai
kebisingan
yang
melampaui batas, tetapi satu
ukuran
yang
telah disepakati bersama
menyatakan
bahwa
kekuatan
suara
berada
diatas 90 Decibels dianggap menggangu
pekerja. Kekuatan suara diatas 90 Decibels ini biasanya dapat disebabkan oleh suara-
suara mesin yang besar atau mesin yang tidak terawat dengan baik sehingga
menimbulakan suara diatas batas. Kebisingan yang melampaui batas menyebabkan:
1. Sulit berkomunikasi
2. Tidak dapat mendengar sinyal-sinyal peringatan
3. Salah pengertian
4. Kemungkinan hilangnya pendengaran secara permanen
5. Kelelahan, dan lain-lain.
Kebisingan dapat
didefinisikan
sebagai
bunyi
yang
tidak disukai, suara yang
menggangu. Ada tiga aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi yang bisa
menentukan tingkat gangguan terhadap
manusia, yaitu : lama, Intensitas, dan
frekuensi.
|
|
69
Bising yang keras dan berulang-ulang dapat menimbulkan hilang pendengaran
(hearing loss) sementara. Tetapi kalau rangsangan itu berjalan terus, bisa
mengakibatkan rusak pendengaran secara permanen, suatu kondisi yang disebut tuna
rungu.
Itulah akibat dari proses degenerasi
yang
lambat tapi berlanjut pada sel peka
suara dari telainga dalam.
Sumber
bising
yang bernada tinggi
lebih berbahaya
dari
pada yang dengan frekuensi rendah dan bising yang kadangkala lebih berbahaya dari
pada suara yang kontinu.
Bunyi terputus-putus (Non-continous) meliputi bunyi yang stabil (contoh : mesin
yang beroperasi untuk waktu yang singkat, bunyi kejatuhan barang dan bunyi
ledakan). Dlam kasus yang berat, bunyi ini juga memungkinkan terjadinya
kehilangan pendengaran. Hal yang perlu dipertibangkan juga intensitas bunyi,
spektrum kebisingan, frekuensi, dan lama paparan.
Telinga
manusia
kurang
sensitif
untuk frekuensi
dibawah
1000
Hz
dan
lebih
sensitif untuk frekuensi diatasnya. Karena itu, untuk suara dengan frekuensi rendah,
intensitasnya harus lebih besar dibanding dengan suara dengan frekuensi tinggi.
Kesimpulam umum mengenai kebisingan:
1.
Untuk dapat mempengaruhi kinerja memori
jangka
pendek (kegiatan
logika
sederhana), diperlukan
kebisingan yang lebih dari 95 dBA. Sedangkan
Weinstein menemukan bahwa pada tingkat kebisingan
68-70
dBA,
operator
mengalami
kesulitan
memahami
arti
dari
bacaan
(kegiatan ini
memerlukan
proses tata bahasa dan memori jangka pendek).
|
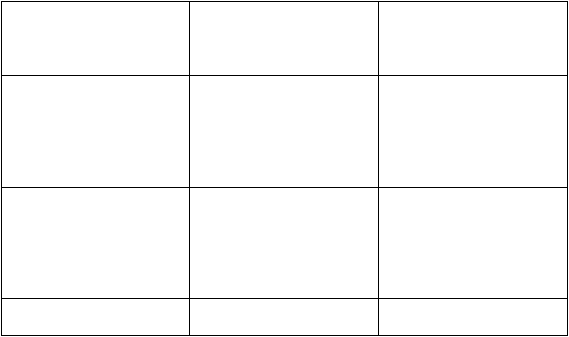 70
2. Kinerja dari tugas rutin
mungkin tidak akan
menampakkan pengaruh buruk
dari kebisingan, terkadang justru meningkat.
3.
Jika seorang operator harus bereaksi pada waktu
tertentu,
menerima sinyal
peringatan dan memerlukan pandangan yang baik untuk bekerja, maka bising
yang terus-menerus (>95 dBA) sedikit pengaruhnya.
4. Fungsi
penglihatan
seperti
:
perbedaan kontras,
kecepatan
gerak
mata,
dan
lain-lain, tidak berpengaruh.
5. Pengaruh buruk dari kebisingan umumnya berkaitan dengan tugas yang harus
dikerjakan terus-menerus tanpa henti dan tugas yang sulit yang memerlukan
pemikiran yang mendalam.
Tabel 2.4. Skala Intensitas Kebisingan (Sutalaksana, 1979, h.86)
Kriteria Pendengaran
Tingkat kebisingan
[dB(A)]
Ilustrasi
Memilukan
120
110
100
Halilintar, Meriam
Sanagt hiruk
90
80
Jalan hiruk pikuk
Perusahaan sangat gaduh
Peluit polosi
70
Jalan pada umumnya
|
 71
Kuat
60
Radio
Kantor gaduh
Sedang
50
40
Kantor pada umumnya
Percakapan kuat
Rumah gaduh
Tenang]
30
20
Rumah tenang
Kantor perorangan
Auditorium
Percakapan
Sangat Tenang
10
0
Suara daun-daun
Berbisik
Batas dengar terendah
Tabel 2.5. Keterangan Waktu Yang Diijinkan Berdasarkan Intensitas suara
Intensitas Suara (dBA)
Waktu Yang Diijinkan (Jam)
80
32
85
16
90
8
95
4
100
2
105
1
|
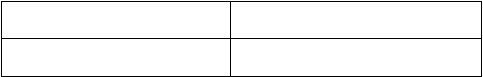 72
110
0,5
115
0,25
2.7.5 Bau-Bauan
Adanya bau-bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran
apalagi kalau bau-bauan tersebut sedemikan rupa sehingga dapat mengganggu
konsentrasi bekerja dan secara lebih bau-bauan
yang
terjadi
terus-menerus
bisa
mempengaruhi kepekaan penciuman.
Temperatur dan kelembaban merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi
kepekaan penciuman. Dan juga mempengaruhi tingkat ketajaman penciuman
seseorang.
Oleh
karena
itu
pemakaian
air
conditioning
merupakan
salah
satu cara
yang
bisa
digunakan
untuk
menghilangkan
bau-bauan
yang
dapat mengganggu
disekitar tempat kerja (Sutalaksana, 1979, h.87).
Pengendalian bau-bauan dilakukan dengan :
1. Penambahan bau-bauan baru kepada udara
yang berbau
untuk
merubah
zat
berbau menjadi zat lain yang kurang
merangsang. Percobaan harus diadakan
lebih
dahulu,
agar
penambahan
suatu zat baru tidak
berakibat lebih
memburukkan keadaan.
2. Proses menutupi (Masking
process) yang didasarkan atas kerja antagonistis
diantara dua
zat berbau. Kedua
zat
tersebut saling
menetralkan bau
masing-
|
|
73
masing. Misalnya bau karet dapat ditiadakan oleh paraffin atau minyak sedar,
sedangkan bau amoniak oleh ionone, dan lain-lain.
3.
Adsorpsi, absorpsi, kondensasi, dan proses-proses lainnya. Penggunaan
pancaran air, air pencuci dan
filter, kering atau basah,
tidak saja baik
untuk
menghilangkan
gas
dan
aerosol,
tetapi
juga bau-bauan. Jika air yang
digunakan, maka
yang dibersihkan hanya
gas-gas yang larut atau dapat
berkondensasi
dalam air.
Penyaringan kering
dengan
karbon
aktif
silika
mungkin
efektif
untuk
gas-gas
lainnya.
Untuk
efisiensi
tinggi,
volume
saringan mungkin dan kecepatan udara harus sebaik-baiknya.
4.
Pengubahan
kimiawi
dari
bau-bauan
meliputi penggunaan bahan oksidasi
sepertochlor dan persenyawaannya serta ozon. Zat-zat
yang dihasilkan
harus
tidak berbau. Oleh karena itu proses reaksi kimia memakan waktu, kecepatan
pengaliran udara keluar tidak boleh terlalu cepat.
5.
Air
conditioning adalah cara deodorasi
yang
baik
ditempat
kerja,
asalkan
dilaksanakan secara tepat.
2.8
Diagram Sebab Akibat
Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang
menunjukkan
hubungan antara
sebab
dan
akibat.
Berkaitan
dengan
pengendalian proses
statistical, diagram sebab
akibat
dipergunakan
untuk
menunjukkan faktor-faktor
penyebab
(sebab)
dan
karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor0faktor penyebab itu.
|
|
74
Diagram sebab akibat ini menunjukkan 5 faktor yang disebut sebagai sebabm dari
suatu akibat. Kelima faktor itu adalah man (manusia, tenaga kerja), method (metode),
material
(bahan),
machine
(mesin),
dan
environtment
(lingkungan).
Diagram ini
biasanya
disusun
berdasarkan
informasi
yang
didapatkan
dari
hasil
sumbang
saran
atau “Brainstorming”. Diagram sebab akibat ini sering juga disebut sebagai diagram
Tulang
Ikan
(Fishbone Diagram) karena bentuknya seperti
kerangka
ikan,
atau
diagram Ishikawa (Ishikawa’s diagram) karena pertama kali diperkenalkan oleh Prof.
Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953.
Pada dasarnya diagram sebab akibat
dapat dipergunakan untuk kebutuhan-
kebutuhan berikut :
1. Membantu mengidentifikasikan akar penyebab suatu maslah
2. Membantu Membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah
3. Membantu dalam penyelidikkan atau pencarian fakta lebih lanjut.
Langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat:
1. Definisi masalah utama yang akan dicari penyebanya, tuliskan pada bagian
kepala ikan dari diagram
2. Pilih metode analisa untuk mencari kemungkinan penyebab masalah misalnya
metode brainstorming, inspeksi, wawancara, dan lain sebagainya.
3. Tuliskan faktor-faktor uatama yang mungkin menjadi penyebab dari masalah
pada bagian ujung tulang uatama. Faktor
utama
misalnya
: 4M (Man,
Machine, Material, Method), 4P (People, Prosedure, Policy, Place), 4S (Skill,
Surrounding, Supplier, System), atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
|
 75
4. Tuliskan penyebab-penyebab masalah, yang mungkin, lebih terperinci pada
batang cabang tulang diagram.
5.
Kaji
kembali
setiap
penyebab
yang
telah tercantum, sepakati mana yang
terpenting
dan
benar-benar
penyebab yang
perlu
mendapatkan
penanganan
segera.
Manusia
Lingkungan
Material
Pengalaman
Pencahayaan
Penyimpanan
Pelatihan
Suhu
Pengangkutan
Kecelakaan
Kerja
Pembagian Kerja
Perawatan
Alat Potong
Metode
Mesin
Gambar 2.1 Sebab Akibat Kecelakaan Kerja
|