|
BAB 2
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1
Dasar Teori
Beton adalah campuran antara semen, agregat
halus, agregat kasar dan air yang
membentuk
masa
padat.
Jenis
beton
yang
dihasilkan
dalam
perencanaan ini
adalah
campuran beton normal
yaitu beton
yang mempunyai berat isi 2200 -
2500 kg/m³ dan
menggunakan
agregat alam
yang
dipecah
atau
tanpa dipecah
dan
tidak
menggunakan
bahan tambahan (SK. SNI T-15-1990-03, p1).
Salah
satu
bahan
utama penyusun
beton
adalah semen.
Semen
yang
biasa
digunakan adalah
semen
portland
yaitu
semen
hidrolik
yang
dihasilkan
dengan
menggiling klinker
yang
terdiri
dari
kalsium
silikat
hidrolik
dan
bahan
tambahan
berbentuk kalsium sulfat. Fungsi semen adalah untuk mempersatukan agregat kasar dan
agregat
halus
menjadi
satu
kesatuan yang
kuat
setelah
semen
berekasi dengan
air.
Berdasarkan fungsinya semen portland dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:
a. Semen portland
tipe
I
adalah
semen portland
yang
umum digunakan tanpa
persyaratan khusus.
b. Semen
portland
tipe II
adalah
semen
portland
yang
dalam penggunaannya
memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang.
c. Semen
portland
tipe
III
adalah
semen portland
yang
dalam penggunaannya
memerlukan kekuatan awal yang tinggi.
d. Semen
portland
tipe
IV
adalah semen portland
yang dalam penggunaannya
memerlukan panas hidrasi yang rendah.
|
|
6
e. Semen
portland
tipe V
adalah
semen
portland
yang
dalam penggunaannya
memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat.
Bahan
penyusun
beton
lainnya adalah agregat.
Agregat
yang
digunakan
terdiri
dari
agregat halus
dan
agregat kasar.
Agregat
halus
adalah
pasir
alam
sebagai hasil
desintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang mempunyai ukuran butir terbesar 4.75
mm sedangkan
agregat kasar adalah
kerikil
sebagai
hasil desintegrasi
alami
dari
batu
atau berupa batu pecah yang mempunyai ukuran butir terbesar antara 4.75 - 38 mm.
Di
Indonesia,
perancangan campuran
beton
didasarkan
pada
perancangan
campuran beton cara
Inggris (The
British
Mix
Design
Method) yang
tercantum dalam
Design of Normal Mixes, dikenal dengan DOE (Departement of Environment, Building
Research
Establishment
Britania).
Perancangan
dengan
cara
DOE
ini
dipakai
sebagai
standar perancangan beton normal Indonesia yang dimuat dalam buku Standar No. SK.
SNI. T-15-1990-03 dengan judul
Tata Cara
Pembuatan Rencana Campuran Beton
Normal.
|
 7
2
2.2
Perhitungan Proporsi Beton
2.2.1
Kuat Tekan Rata-Rata Yang Ditargetkan
Kuat tekan beton
yang disyaratkan (f’
c
)
adalah kuat
tekan yang ditetapkan oleh
perencana struktur sedangkan kuat tekan beton yang ditargetkan (f’
cr
)
adalah kuat tekan
rata-rata yang diharapkan dapat tercapai dan nilainya lebih besar dari f’c
.
Langkah untuk menentukan kuat tekan rata-rata yang ditargetkan adalah sebagai
berikut:
a. Menentukan deviasi standar
Nilai standar deviasi diperoleh dari hasil uji tekan beton dengan menggunakan rumus
berikut:
N
?
(
f
c
-
f
cr
)
s
=
1
N
-
1
........................................................................(2.1)
Dimana:
s
=
deviasi standar
fc
=
kuat tekan masing-masing hasil uji (MPa)
f
cr
=
kuat tekan beton rata-rata (MPa)
N = jumlah hasil uji kuat tekan (minimum 30 benda uji)
Data hasil uji yang akan digunakan untuk menghitung standar deviasi harus:
•
Mewakili bahan-bahan, prosedur pengawasan mutu, dan kondisi produksi
yang
serupa dengan pekerjaan yang diusulkan.
•
Mewakili kuat tekan beton yang disyaratkan f’c yang
nilainya dalam batas ± 7
MPa dari nilai f’c
yang ditentukan.
•
Paling sedikit terdiri dari 30 hasil uji yang berurutan atau dua kelompok hasil uji
selama jangka waktu tidak kurang dari 45 hari.
|
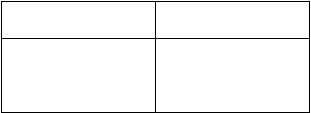 8
•
Bila suatu produksi
beton
tidak
mempunyai 30
data
hasil
uji,
tetapi
hanya
ada
sebanyak
15
sampai 29
hasil
uji
berurutan, maka
nilai
standar deviasi
adalah
perkalian nilai deviasi standar
yang dihitung dari data
hasil uji tersebut dengan
faktor pengali dari Tabel 2.1.
•
Bila data
uji
lapangan
untuk
menghitung
nilai
deviasi
standar
kurang
dari
15,
maka kuat
tekan
rata-rata
yang ditargetkan f’
cr
harus
diambil tidak kurang dari
(f’c
+
12) Mpa.
Tabel 2.1 Faktor Pengali Standar Deviasi
Jumlah Pengujian
Faktor Pengali
Deviasi Standar
15
20
25
30 atau lebih
1,16
1,08
1,03
1,00
Sumber: Tabel 1, SK.SNI.T-15-1990-03
b.
Menentukan Nilai Tambah (Margin)
Nilai tambah ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:
M
=
k x s
....................................................................................(2.2)
Dimana:
M = nilai tambah (margin)
k
=tetapan statistik yang nilainya tergantung pada persentase hasil uji
yang lebih
rendah dari f’c
,
dalam hal ini diambil 5 % sehingga nilai k = 1,64
s =
deviasi standar
c. Menentukan Kuat Tekan Rata-Rata Yang Ditargetkan
Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan ditentukan dengan rumus berikut:
f’
cr
=
f’c
+
M
........................................................................(2.3)
f’
cr
=
f’c
+1,64 . s
........................................................................(2.4)
|
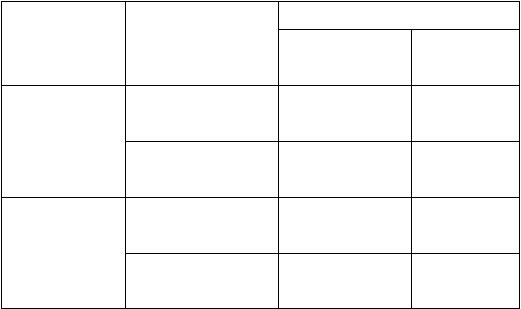 9
2.2.2
Nilai Faktor Air Semen
Faktor
air semen
adalah
angka
perbandingan
antara
berat
kadar
air bebas
dan
berat kadar semen dalam beton. Faktor air semen yang diperlukan untuk mencapai kuat
tekan rata-rata yang ditargetkan didasarkan pada:
a. Hubungan kuat tekan dan
faktor air semen yang diperoleh dari penelitian lapangan
sesuai dengan bahan dan kondisi pekerjaan yang diusulkan.
Bila tidak tersedia data hasil penelitian sebagai pedoman dapat dipergunakan Tabel
2.2 dan Gambar 2.1, Gambar 2.2, Gambar 2.3 atau Gambar 2.4.
b. Untuk
lingkungan khusus,
faktor air
semen
maksimum harus memenuhi ketentuan
SK.SNI Spesifikasi Beton Tahan Sulfat dan Beton Kedap Air
(Tabel 2.4 dan
Tabel 2. 5)
Tabel 2.2 Perkiraan Kuat Tekan (MPa) Beton Dengan Faktor Air Semen 0.5
Jenis Semen
Jenis Agregat Kasar
Kekuatan Tekan (MPa)
Umur (hari)
3
7
28
91
Bentuk benda
Uji
Semen Portland
tipe I atau
Semen tahan
sulfat tipe II,V
Batu tak dipecahkan
Batu pecah
17
23
33
40
19
27
37
45
Silinder
Batu tak dipecahkan
Batu pecah
20
28
40
48
23
32
45
54
Kubus
Semen Portland
tipe III
Batu tak dipecahkan
Batu pecah
21
28
38
44
25
33
44
48
Silinder
Batu tak dipecahkan
Batu pecah
21
31
46
53
30
40
53
60
Kubus
Sumber: Tabel 2, SK.SNI.T-15-1990-03
|
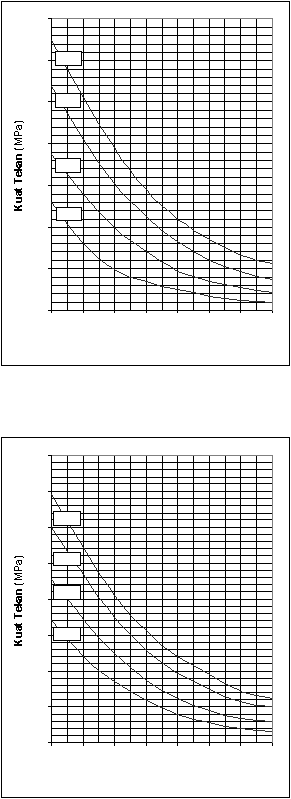 10
70
60
91 hr
50
28 hr
40
7
hr
30
3
hr
20
10
0
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Faktor Air
Semen
Gambar 2.1 Grafik Nilai Faktor Air Semen Untuk Benda Uji Berbentuk Silinder
Dan Jenis Semen Tipe I / II / V (Sumber: Grafik 1, SK.SNI.T-15-1990-03)
80
70
91 hr
60
50
28 hr
7
hr
40
30
3
hr
20
10
0
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Faktor Air
Semen
Gambar 2.2 Grafik Nilai Faktor Air Semen Untuk Benda Uji Berbentuk Silinder
Dan Jenis Semen Tipe III (Sumber: Grafik 1, SK.SNI.T-15-1990-03)
|
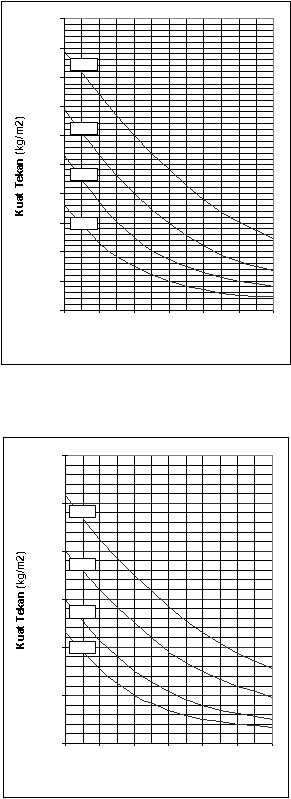 11
1000
900
800
91 hr
700
600
28 hr
500
400
7
hr
300
3
hr
200
100
0
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Faktor Air Semen
Gambar 2.3 Grafik Nilai Faktor Air Semen Untuk Benda Uji Berbentuk Kubus
Dan Jenis Semen Tipe I / II / V (Sumber: Grafik 2, SK.SNI.T-15-1990-03)
1200
1000
91 hr
800
28 hr
600
7
hr
400
3
hr
200
0
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Faktor Air Semen
Gambar 2.4 Grafik Nilai Faktor Air Semen Untuk Benda Uji Berbentuk Kubus
Dan Jenis Semen Tipe III (Sumber: Grafik 2, SK.SNI.T-15-1990-03)
|
|
12
Beton akan awet/tahan lama bila
mempunyai ketahanan terhadap pengaruh
cuaca,
zat-zat
kimia
dalam
air,
pengaruh reaksi
kimia
yang
terjadi
dalam
betonnya
sendiri, keausan (abrasi) dan berkemampuan menahan beban. Selain itu beton akan jauh
lebih
awet
bila
kedap air
atau permeabilitasnya
rendah, air
di
permukaan
beton
tidak
tembus
ke
dalam sehingga
tidak terjadi
reaksi
kimia
di
dalam
beton
karena
zat kimia
lebih reaktif bila
terjadi
larutan. Oleh karena
itu, perlu adanya perencanaan yang
lebih
teliti untuk kondisi beton pada lingkungan yang mengandung sulfat dan lingkungan yang
berhubungan dengan air.
|
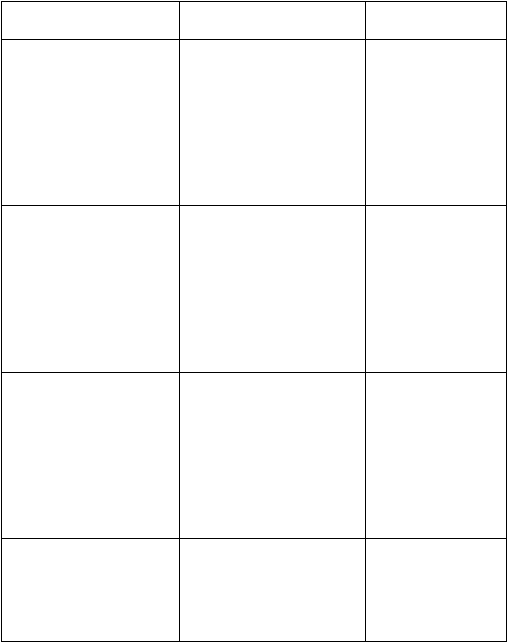 13
Tabel 2.3 Jumlah Semen Minimum Dan
Faktor Air Semen Maksimum
Pada
Lingkungan Umum
Jumlah Semen Minimum
per m³
Beton (kg)
Nilai Faktor Air
Semen maksimum
Beton di dalam ruang
Bangunan :
a.
keadaaan keliling
non-korosif
b.
keadaan keliling
korosif disebabkan
oleh kondensasi atau
uap air
275
325
0,60
0,52
Beton di luar ruangan
bangunan :
a.
tidak terlindung dari
hujan dan terik
matahari langsung
b. terlindung dari hujan
dan terik matahari
langsung
325
275
0,60
0,60
Beton yang masuk
ke dalam tanah :
a.
mengalami keadaan
basah dan kering
berganti-ganti
b. mendapat pengaruh
sulfat dan alkali dari
tanah
325
0,55
lihat Tabel 2.4
Beton yang kontinue
berhubungan :
a.
air tawar
b. air laut
lihat Tabel 2.5
Sumber: Tabel 3, SK.SNI.T-15-1990-03
|
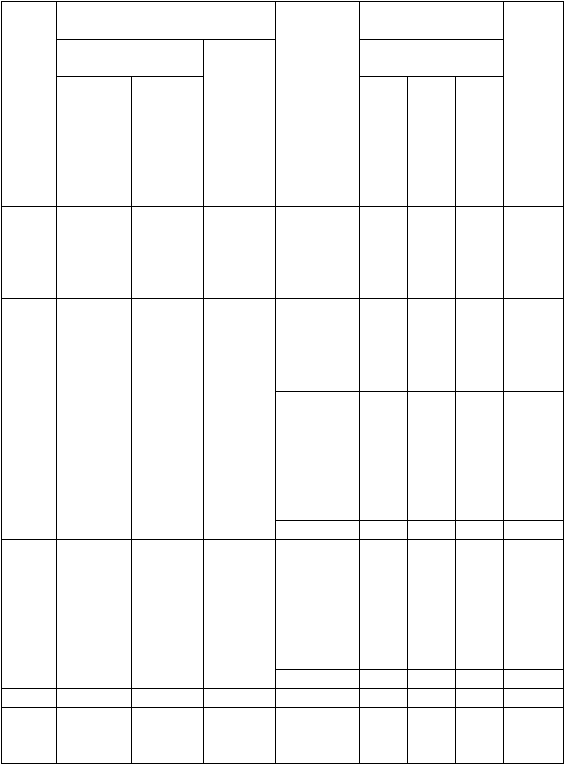 14
Tabel 2.4 Jumlah Semen Minimum Dan Faktor Air Semen Maksimum Pada
Lingkungan Yang Mengandung Sulfat Dan Alkali
Kadar
Gang
guan
Sulfat
Konsentrasi
Sulfat
dalam
bentuk SO³
Tipe
Semen
Kandungan
Semen
Min (kg/m³)
Faktor
Air
Semen
Dalam Tanah
Sulfat
(SO³)
Dalam
Air
Tanah
(g/l)
Ukuran
Agregat
Maks (mm)
Total
SO³ (%)
SO³
dalam
Campur
an Air :
Tanah =
2
:
1
(g/l)
40
20
10
1
<
0.2
<
1.0
<
0.3
Tipe
1
dengan
atau
tanpa
Pozolan
(15-40 %)
80
300
350
0.50
2
0.2 - 0.5
1.0 - 1.9
0.3 - 1.2
Tipe
1
dengan
atau
tanpa
Pozolan
(15-40 %)
290
330
380
0.50
Tipe I +
Pozolan
(15-40 %)
atau
Semen
Portland
Pozolan
270
310
360
0.55
Tipe II / V
250
290
340
0.55
3
0.5 - 1
1.9 - 3.1
1.2 - 2.5
Tipe I +
Pozolan
(15-40 %)
atau
Semen
Portland
Pozolan
340
380
430
0.45
Tipe II / V
290
330
380
0.50
4
1.0 - 2.0
3.1 - 5.6
2.5 - 5.0
Tipe II / V
330
370
420
0.45
5
>
2.0
>
5.6
>
5.0
Tipe II / V
+ Lapisan
Pelindung
330
370
420
0.45
Sumber: SK.SNI.T-15-1990-03
|
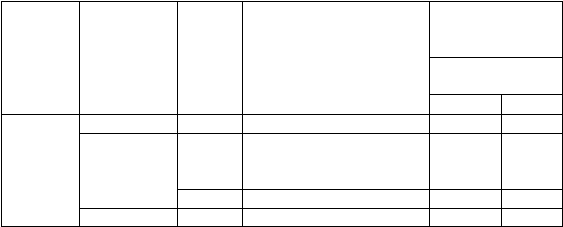 15
Tabel 2.5 Jumlah Semen Minimum Dan Faktor Air Semen Maksimum Pada
Lingkungan Yang Berhubungan Dengan Air
Jenis
Beton
Kondisi
Lingkungan
Berhubunga
n dengan
Faktor
Air
Semen
Maks
Tipe Semen
Kandungan
Semen
Min (kg/m³)
Ukuran Agregat
Maks (mm)
40
20
Bertulang
atau
Pratekan
Air Tawar
0.50
Tipe I - V
280
300
Air Payau
0.45
Tipe I + pozolan (15-40
%) atau
semen portland
pozolan
340
380
0.50
Tipe II atau Tipe V
290
330
Air Laut
0.45
Tipe II atau Tipe V
330
370
Sumber: Tabel 5, SK.SNI.T-15-1990-03
2.2.3
Nilai Slump
Penggunaan beton dewasa ini sangat populer digunakan untuk bermacam-macam
konstruksi
seperti pembuatan plat
lantai, kolom, pondasi, bendungan dan
lain-lain. Di
dalam
pelaksanaan,
bagian-bagian
tersebut
mempunyai
tingkat
workability
yang
tidak
sama,
oleh
sebab
itu
adukan
beton
yang
lebih
encer
sering
digunakan
untuk berbagai
konstruksi yang mempunyai jarak tulangan atau jarak antara acuan cetakan yang sempit,
dengan
maksud agar adukan beton
mengisi seluruh cetakan dengan padat atas bantuan
alat
penggetar. Pada
kondisi
sebaliknya dapat
digunakan adukan
yang
lebih
kental.
Secara
umum
workability
beton
normal
dipengaruhi faktor
air
semen. Jika
faktor air
semen tinggi maka workability juga tinggi tetapi mutu beton berkurang, sedangkan bila
faktor
air semen
rendah
maka
workability
menjadi
rendah dengan
mutu
beton
bertambah.
Slump
adalah
ukuran kekentalan adukan beton
yang dinyatakan dalam
mm dan
ditentukan dengan menggunakan kerucut Abram. Slump ditetapkan sesuai dengan
|
|
16
kondisi pelaksanaan pekerjaan agar diperoleh beton yang mudah dituangkan, dipadatkan
dan diratakan
(Mulyono
2004,
p88).
Selain
itu
slump
juga
sering
digunakan sebagai
acuan dalam menentukan tingkat workability.
Besar nilai slump dalam perancangan dikelompokkan menjadi 4, yaitu:
a. 0 – 10 mm (workability sangat rendah)
b. 10 – 30 mm (workability rendah)
c. 30 – 60 mm (workability sedang)
d. 60 – 180 mm (workability tinggi)
Dalam perancangan campuran beton, besar nilai slump perlu direncanakan
dengan
hati-hati karena
mempengaruhi mutu beton
juga kemudahan dalam pengerjaan
(workability).
Penentuan
nilai
slump
didasarkan
pada
pertimbangan pelaksanaan
pembuatan, cara pengangkutan, penuangan dan pemadatan beton.
2.2.4 Ukuran Agregat Maksimum
Ukuran agregat maksimum tidak boleh melebihi:
a. Seperlima jarak terkecil antara bidang-bidang samping dari cetakan.
b. Sepertiga dari tebal pelat.
c. Tiga per empat dari jarak bersih minimum diantara batang-batang atau berkas-berkas
tulangan.
Ukuran agregat maksimum dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
a. Ukuran agregat maksimum 10 mm.
b. Ukuran agregat maksimum 20 mm.
c. Ukuran agregat maksimum 40 mm.
|
 17
2.2.5
Daerah Gradasi Agregat Halus
SK.SNI.T-15-1990-03 memberikan syarat-syarat gradasi untuk agregat halus
yang
diadopsi dari
British
Standard
(BS
812).
Gradasi agregat halus
dikelompokkan
menjadi 4 daerah gradasi yaitu daerah 1, daerah 2, daerah 3 dan daerah 4.
120
100
80
60
95
100
100
90
70
60
40
34
30
20
20
10
15
0
0
5
0,15
0,3
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6
Ukuran Saringan (mm)
Gambar 2.5 Kurva Gradasi Agregat Halus Daerah 1 (Sumber: Grafik 3,
SK.SNI.T-15-1990-03)
120
100
80
100
100
100
90
90
75
60
59
55
40
30
35
20
10
8
0
0
0,15
0,3
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6
Ukuran Saringan (mm)
Gambar 2.6 Kurva Gradasi Agregat Halus Daerah 2 (Sumber: Grafik 4,
SK.SNI.T-15-1990-03)
|
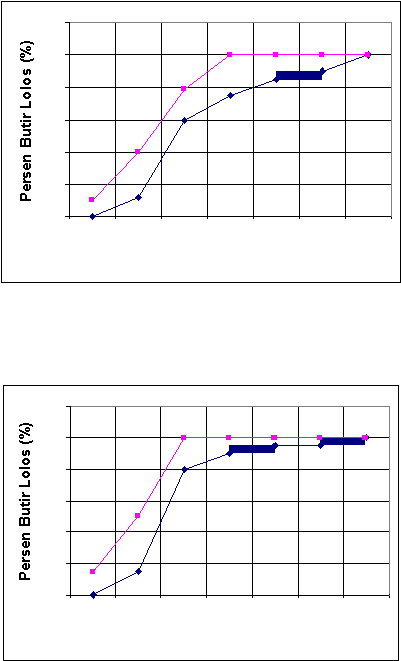 18
120
100
100
100
100
100
90
85
80
79
75
60
60
40
40
20
10
12
0
0
0,15
0,3
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6
Ukuran Saringan (mm)
Gambar 2.7 Kurva Gradasi Agregat Halus Daerah 3 (Sumber: Grafik 5,
SK.SNI.T-15-1990-03)
120
100
100
100
90
100
100
100
95
95
80
80
60
50
40
20
15
15
0
0
0,15
0,3
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6
Ukuran Saringan (mm)
Gambar 2.8 Kurva Gradasi Agregat Halus Daerah 4 (Sumber: Grafik 6,
SK.SNI.T-15-1990-03)
|
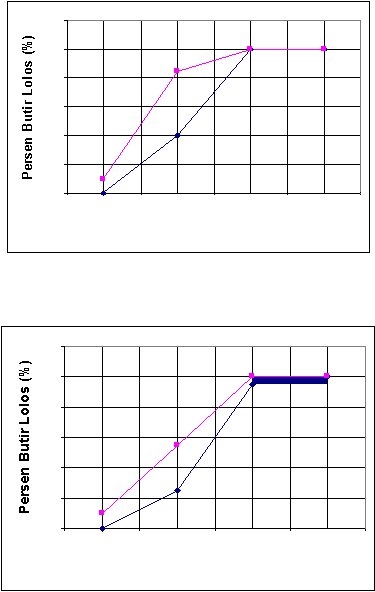 19
2.2.6
Daerah Gradasi Agregat Kasar
British Standard (BS 812) memberikan syarat-syarat daerah gradasi untuk
agregat kasar yang dikelompokkan menjadi 3 daerah gradasi yaitu gradasi agregat kasar
untuk
ukuran
agregat
maksimum
10
mm,
20
mm dan 40
mm.
Syarat
gradasi agregat
kasar ini digunakan sebagai panduan dalam pengujian kelayakan gradasi agregat kasar.
120
100
80
100
100
85
60
40
40
20
10
0
0
4,8
9,6
19,0
38,0
Ukuran Saringan
(mm)
Gambar 2.9 Kurva Gradasi Agregat Kasar Untuk Ukuran Agregat
Maksimum 10 mm (Sumber: BS 812)
120
100
100
100
95
80
60
55
40
25
20
10
0
0
4,8
9,6
19,0
38,0
Ukuran Saringan
(mm)
Gambar 2.10 Kurva Gradasi Agregat Kasar Untuk Ukuran Agregat
Maksimum 20 mm (Sumber: BS 812)
|
 20
120
100
100
95
80
70
60
40
35
30
20
5
10
0
0
4,8
9,6
19,0
38,0
Ukuran Saringan
(mm)
Gambar 2.11 Kurva Gradasi Agregat Kasar Untuk Ukuran Agregat
Maksimum 40 mm (Sumber: BS 812)
2.2.7 Daerah Gradasi Agregat Campuran
Daerah gradasi agregat campuran adalah daerah gradasi gabungan agregat halus
dan agregat kasar sesuai dengan ukuran agregat maksimumnya. Standar SK.SNI.T-15-
1990-03
memberikan syarat-syarat daerah
gradasi
untuk agregat
campuran
yang
diadopsi dari
British
Standard
(BS
812).
Daerah
gradasi agregat campuran
dikelompokkan menjadi 3 daerah
gradasi
yaitu
gradasi agregat campuran untuk
ukuran
agregat maksimum 10 mm, 20 mm dan 40 mm.
|
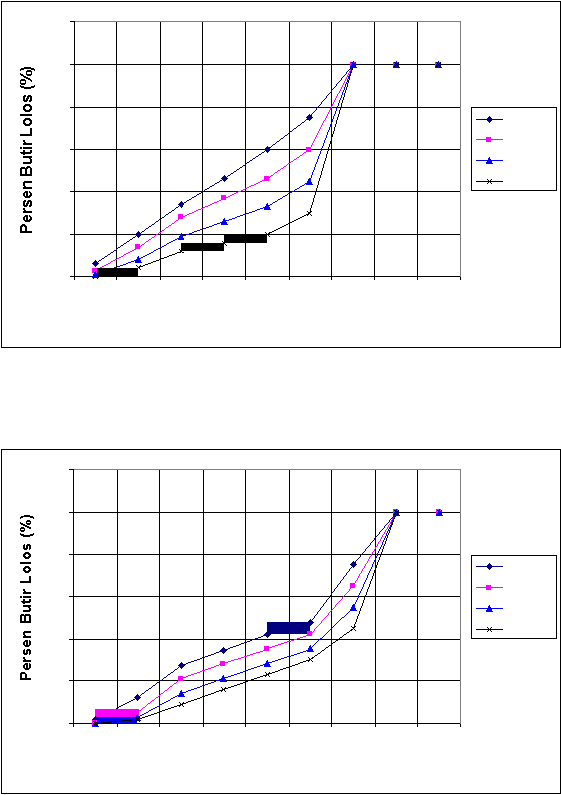 21
3
8
16
120
100
100
100
100
80
60
40
34
28
20
20
19
75
60
60
46
46
45
37
33
30
26
20
Kurva
4
Kurva
3
Kurva
2
Kurva
1
14
12
6
4
0
0
0,15
0,3
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6
19,0
38,0
Ukuran Saringan (mm)
Gambar 2.12 Kurva Gradasi Agregat Campuran Untuk Ukuran Agregat
Maksimum 10 mm (Sumber: Grafik 7, SK.SNI.T-15-1990-03)
120
100
100
100
80
60
40
20
0
2
0
34
27
28
21
21
12
14
16
9
5
2
75
65
55
48
42
42
45
35
35
28
30
23
Kurva
4
Kurva
3
Kurva
2
Kurva
1
0,15
0,3
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6
19,0
38,0
Ukuran Saringan (mm)
Gambar 2.13 Kurva Gradasi Agregat Campuran Untuk Ukuran Agregat
Maksimum 20 mm (Sumber: Grafik 8, SK.SNI.T-15-1990-03)
|
 22
?
?
120
100
100
80
60
60
75
Kurva
4
67
Kurva
3
59
40
20
5
0
0
²
23
15
17
11
12
7
7
3
52
50
47
44
38
40
36
30
31
32
24
25
24
17
18
12
Kurva
2
Kurva
1
0,15
0,3
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6
19,0
38,0
Ukuran Saringan (mm)
Gambar 2.14 Kurva Gradasi Agregat Campuran Untuk Ukuran Agregat
Maksimum 40 mm (Sumber: Grafik 9, SK.SNI.T-15-1990-03)
2.2.8
Kadar Air Bebas
Kadar
air
bebas
adalah
jumlah
air
yang
dicampurkan ke
dalam
beton
untuk
mencapai konsistensi tertentu, tidak termasuk air yang diserap agregat. Kadar air bebas
ditentukan sebagai berikut:
a. Agregat tak dipecah dan agregat dipecah dipergunakan nilai-nilai pada Tabel 2.6.
b. Agregat campuran (tak dipecah dan dipecah), dihitung menurut rumus berikut:
2
1
?
=
h
+
k
3
3
........................................................................(2.5)
Dimana:
?
=
kadar air yang dibutuhkan agregat
dalam 1 m³ beton.
?
h
=
kadar air yang dibutuhkan agregat halus dalam 1 m³ beton.
?
k
=
kadar air yang dibutuhkan agregat kasar dalam 1 m³ beton.
|
 23
Tabel 2.6 Perkiraan Kadar Air Bebas (kg/m3
)
Slump (mm)
0 - 10
10 - 30
30 - 60
60 - 100
Ukuran besar butir
agregat Maksimum
Jenis
Agregat
10 mm
Batu tak dipecahkan
Batu pecah
150
180
180
205
205
230
225
250
20 mm
Batu tak dipecahkan
Batu pecah
135
170
160
190
180
210
195
225
40 mm
Batu tak dipecahkan
Batu pecah
115
155
140
175
160
190
175
205
Sumber: Tabel 6, SK.SNI.T-15-1990-03
2.2.9
Berat Jenis Relatif Agregat
Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk menentukan berat jenis relatif
agregat, yaitu sebagai berikut:
a. Diperoleh dari data hasil uji atau bila tidak tersedia dapat dipakai nilai di bawah ini:
•
Agregat tak dipecah = 2,6 gr/cm³
•
Agregat dipecah = 2,7 gr/cm³
b. Berat jenis relatif agregat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
B
B
j
.A
g
= %A
h
x B
j
.
A
h
+
%
A
k
x B
j
.
A
k
....................................(2.6)
Dimana :
B
B
j
.A
g
=
berat jenis relatif agregat
% A
h
=
persentase agregat halus
% A
k
=
persentase agregat kasar
B
B
j
.A
h
=
berat jenis agregat
halus
B
B
j
.A
k
=
berat jenis agregat kasar
|
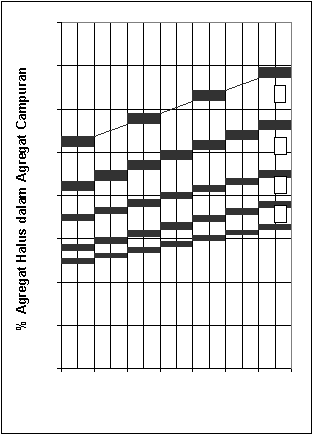 24
2.2.10 Proporsi Agregat Halus Dalam Agregat Campuran
Proporsi agregat halus ditentukan berdasarkan besar ukuran agregat maksimum,
besar slump, nilai faktor air semen dan daerah gradasi agregat halus. Nilai-nilai tersebut
kemudian
digunakan
untuk
menentukan
persentase
agregat
halus dalam agregat
campuran dengan
mengunakan grafik
proporsi
agregat
halus
dalam
agregat
campuran
(Gambar 2.15).
Pada gambar
ini
dicantumkan
nilai
1
sampai 4,
angka-angka tersebut
menunjukkan daerah
gradasi
agregat
halusnya.
Bila
daerah
gradasi
agregat
halus
termasuk daerah 1 maka untuk menentukan proporsinya ditunjukkan pada bidang
gambar angka 1 (menunjukkan daerah gradasi agregat halus adalah daerah gradasi 1).
80
70
1
60
50
2
3
40
4
30
20
10
0
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Faktor
Air Semen
Gambar 2.15 Grafik Tipikal Proporsi Agregat Halus Dalam Agregat Campuran
(Sumber: Grafik 10 - 12, SK.SNI.T-15-1990-03)
|
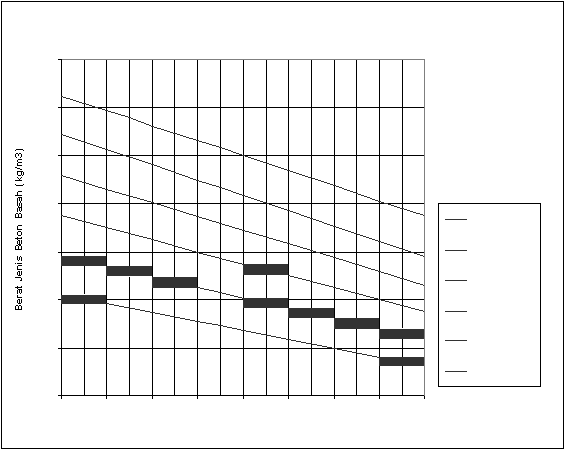 25
2.2.11 Berat Jenis Beton
Berat
jenis
beton
ditentukan
berdasarkan
nilai
berta
jenis relatif agregat
campuran dan kadar air bebas dengan
menggunakan grafik
nilai berat jenis beton
yang
terdapat
pada
Gambar 2.16.
Berat
jenis
beton
adalah
berat
beton
untuk 1
m³ volume
beton.
2800
2700
2600
2500
2400
BJ Relatif
2.9
BJ Relatif
2.8
2300
BJ Relatif
2.7
BJ Relatif
2.6
2200
BJ Relatif
2.5
BJ Relatif
2.4
2100
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Kadar
Air Bebas
(kg/m3)
Gambar 2.16 Grafik Berat Jenis Beton (Sumber: Grafik 13, SK.SNI.T-15-1990-03)
|
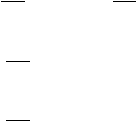 26
2.2.12 Koreksi Proporsi Campuran Beton
Apabila
agregat
tidak dalam
keadaan
jenuh kering
permukaan, maka
proporsi
campuran beton harus dikoreksi terhadap kandungan air dalam agregat. Koreksi proporsi
campuran
harus
dilakukan
terhadap
kadar
air
dalam
agregat
paling
sedikit
satu
kali
dalam sehari.
Dalam
perencanaan di
atas,
agregat
halus
dan
agregat
kasar
dianggap
dalam
keadaan jenuh kering permukaan (saturated surface
dry), sehingga apabila agregatnya
tidak
dalam keadaan
jenuh kering permukaan, maka
harus
dalakukan koreksi terhadap
kebutuhan bahan.
Hitungan koreksi campuran dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:
a. Air
=
B
-
(C
k
-
C
a
)
x
C
100
-
(D
k
-D
a
)
x
D
100
........................(2.7)
b. Agregat Halus
=
C + (C
k
-
C
a
)
x
C
100
................................................(2.8)
c. Agregat Kasar
=
D + (D
k
-
D
a
)
x
D
100
................................................(2.9)
Dimana:
B
=
jumlah air (kg/m³)
C
=
jumlah agregat halus (kg/m³
)
D = jumlah kerikil (kg/m3
)
C
a
=
absorpsi air pada agregat halus (%)
D
a
=
absorpsi agregat kasar (%)
C
k
=
kandungan air dalam agregat halus (%)
D
k
=
kandungan air dalam agregat kasar (%)
|
|
27
2.3
Tata Cara Perancangan Proporsi Beton
Langkah-langkah pembuatan rencana campuran beton normal dilakukan sbb:
a. Ambil kuat tekan beton yang disyaratkan f’
c
pada umur 28 hari.
b. Hitung standar deviasi menurut persamaan (2.1).
c. Hitung nilai tambah menurut persamaan (2.2).
d. Hitung kuat tekan beton rata-rata yang ditargetkan f’
cr
menurut persamaan (2.3) atau
persamaan (2.4).
e. Tetapkan jenis semen yang digunakan.
f.
Tentukan
jenis
agregat kasar dan
agregat
halus.
Agregat
ini
dapat
dalam
bentuk
alami (pasir atau koral) atau batu pecah.
g. Tentukan
nilai
faktor
air
semen.
Bila
dipergunakan Gambar
2.1, Gambar
2.2,
Gambar 2.3, atau Gambar 2.4, maka ikuti langkah-langkah berikut:
•
Tentukan nilai kuat tekan pada
umur 28 hari dengan
menggunakan Tabel 2.2,
sesuai dengan semen dan agregat yang akan dipakai.
•
Lihat Gambar 2.1 atau 2.2 untuk benda uji berbentuk silinder atau Gambar 2.3
atau 2.4 untuk benda uji berbentuk kubus.
•
Tarik garis
tegak
lurus ke atas
melalui
faktor air semen 0.5 sampai memotong
kurva kuat tekan yang ditentukan pada sub butir 2 di atas.
•
Tarik garis mendatar melalui nilai kuat tekan yang ditargetkan sampai memotong
kurva yang ditentukan.
•
Tarik garis tegak lurus ke bawah melalui titik potong tersebut untuk
mendapatkan faktor air semen yang diperlukan.
|
|
28
h. Tetapkan nilai faktor air semen maksimum menurut Tabel 2.3, Tabel 2.4 atau Tabel
2.5
(dapat
ditetapkan
sebelumnya atau
tidak).
Jika
nilai
faktor
air
semen
yang
diperoleh dari
lebih
besar
dari
faktor air
semen
maksimum,
maka
nilai
faktor air
semen yang digunakan adalah nilai faktor air semen maksimum.
i.
Tetapkan nilai slump.
j.
Tetapkan ukuran agregat maksimum.
k. Tentukan nilai kadar air bebas menurut Tabel 2.6 dan persamaan (2.5).
l.
Hitung jumlah semen yang besarnya adalah kadar air bebas dibagi faktor air semen.
m.
Jumlah semen maksimum jika tidak ditetapkan, dapat diabaikan.
n. Tentukan jumlah semen
minimum
menurut
Tabel 2.3,
Tabel 2.4
atau Tabel 2.5.
Kadar semen yang diperoleh dari perhitungan jika perlu disesuaikan.
o. Tentukan faktor air semen yang disesuaikan, jika jumlah semen berubah karena lebih
kecil
dari
jumlah
semen
minimum
yang
ditetapkan (atau
lebih
besar dari
jumlah
semen
maksimum
yang
disyaratkan),
maka
faktor
air
semen
harus diperhitungkan
kembali.
p.
Tentukan
susunan
besar
butir agregat
halus
berdasarkan kurva-kurva yang
tertera
dalam Gambar 2.5, Gambar 2.6, Gambar 2.7 atau Gambar 2.8.
q.
Tentukan
persentase
pasir
dengan
menggunakan Gambar
2.15.
Dengan
diketahuinya
ukuran
butir agregat
maksimum,
slump,
faktor air
semen
dan
daerah
gradasi agregat halus,
maka
jumlah persentase pasir yang diperlukan dapat dibaca
pada grafik. Jumlah ini adalah jumlah seluruhnya dari pasir atau fraksi agregat yang
lebih halus dari 5 mm. Dalam agregat kasar yang biasa dipakai di Indonesia
seringkali dijumpai bagian yang lebih halus dari 5 mm dalam jumlah lebih dari 5 %.
Dalam hal ini maka jumlah agregat halus yang diperlukan harus dikurangi.
|
|
29
r.
Hitung berat jenis relatif agregat campuran menurut persamaan (2.6).
s.
Tentukan berat jenis beton
menurut
grafik
yang terdapat pada Gambar 2.16 sesuai
dengan
kadar air
bebas
yang
sudah
ditentukan
dan
berat
jenis
relatif
dari agregat
campuran.
t.
Hitung
kadar
agregat campuran
yang besarnya
adalah
berat
jenis beton
dikurangi
jumlah kadar semen dan kadar air bebas.
u. Hitung kadar agregat halus yang besarnya adalah hasil kali persentase agregat halus
dengan agregat campuran.
v. Hitung kadar agregat kasar yang besarnya adalah kadar agregat campuran dikurangi
kadar
agregat
halus.
Dari
langkah
-
langkah
di
atas
telah
dapat
diketahui
susunan
campuran bahan-bahan untuk 1 m³ beton.
w. Koreksi proporsi campuran
menurut persamaan
(2.7), persamaan
(2.8) dan
persamaan (2.9).
x. Buatlah campuran uji, ukur dan catatlah besarnya slump serta kekuatan tekan yang
sesungguhnya, perhatikan hal berikut:
•
Jika
nilai
yang
di
dapat
sesuai
dengan
nilai
yang
diharapkan,
maka
susunan
campuran beton
tersebut
dikatakan baik.
Jika
tidak,
maka
campuran perlu
dibetulkan.
•
Kalau slumpnya ternyata
terlalu
tinggi/rendah, maka
kadar
air
perlu
dikurangi/ditambah (dengan
demikian
juga
kadar
semennya,
karena
faktor
air
semen harus dijaga agar tetap tidak berubah).
•
Jika kekuatan beton dari campuran uji
ini terlalu tinggi atau rendah, maka faktor
air semen dapat disesuaikan.
|