|
4
BAB II
DATA DAN ANALISA
2.1
Metode Penelitian
Data diperoleh melalui wawancara, survey, media cetak dan elektronik.
Wawancara:
Bpk. Sumari, SENAWANGI.
Survei dilakukan ke Gedung Perwayangan Kautaman.
Media cetak :
Nilai-nilai Kearifan Budaya Wayang, Drs. Soeparno, MSi
Tafsiran Ajaran Suluk Bharatayudha, Basri Priyo Handoko
Dhalang, Wayang, dan Gamelan, Wawan Susetya
Tuntunan Pedalangan Wayang Surakarta, Bambang Soewarno
2.2
Data dan literatur
2.2.1
Asal usul kesenian wayang
Kesenian
wayang
dalam bentuknya
yang
asli
timbul
sebelum
kebudayaan Hindu masuk di Indonesia dan mulai berkembang pada jaman
Hindu Jawa. Pertunjukan kesenian
wayang adalah merupakan sisa-sisa upacara
keagamaan orang Jawa yaitu sisa-sisa dari kepercayaan animisme dan
dynamisme. Tentang asal-usul kesenian wayang hingga dewasa ini masih
merupakan
suatu
masalah
yang
belum terpecahkan
secara
tuntas.
Namun
demikian banyak para ahli mulai mencoba menelusuri sejarah perkembangan
wayang dan
masalah
ini
ternyata sangat
menarik
sebagai
sumber
atau obyek
|
|
5
penelitian. Sekitar abad 10, raja Kediri berusaha menciptakan gambaran dari roh
leluhurnya dan digoreskan di atas daun lontar. Bentuk gambaran wayang
tersebut ditiru dari
gambaran
relief cerita
Ramayana pada
Candi
Penataran
di
Blitar. Setelah berganti generasi pada kerajaannya, gambar-gambar wayang dari
daun
lontar
hasil
ciptaan
leluhurnya
dipindahkan pada kertas dengan tetap
mempertahankan bentuk yang ada pada daun lontar. Pada masa itu sementara
pengikut agama Islam ada yang beranggapan bahwa gamelan dan wayang
adalah
kesenian
yang
haram karena
berbau
Hindu.
Timbulnya
perbedaan
pandangan antara sikap menyenangi dan mengharamkan tersebut mempunyai
pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan kesenian wayang itu
sendiri. Untuk menghilangkan kesan yang serba berbau Hindu dan kesan
pemujaan kepada arca, maka timbul gagasan baru untuk menciptakan wayang
dalam wujud
baru
dengan
menghilangkan
wujud
gambaran
manusia.
Berkat
keuletan dan ketrampilan para pengikut Islam yang menggemari kesenian
wayang, terutama para Wali, berhasil menciptakan bentuk baru dari Wayang
Purwa dengan bahan kulit kerbau
yang agak ditipiskan dengan wajah
digambarkan
miring,
ukuran
tangan
di-buat lebih panjang dari ukuran tangan
manusia, sehingga sampai dikaki. Wayang dari kulit kerbau ini diberi warna
dasar putih yang dibuat dari campuran bahan perekat dan tepung tulang,
sedangkan pakaiannya di cat dengan tinta.
Menurut
Wawan
Susetya
dalam bukunya
yang
bertajuk
“Dhalang,
Wayang
dan
Gamelan”,
2007.
Wayang
kulit
adalah pedalangan dan drama
tradisional
Indonesia, yang sudah digemari oleh rakyat Indonesia sejak zaman
|
|
6
prasejarah sampai sekarang, berkembang di Jawa dan di sebelah timur
semenanjung Malaysia seperti di Kelantan dan Terengganu. Wayang kulit
dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh
wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok
nayaga
dan
tembang
yang
dinyanyikan oleh
para pesinden.
Wayang berasal
dari kata ‘bayang’, mulai pada zaman purbakala sebagai upacara memanggil
arwah dengan memasang lampu minyak kelapa (blencong) sebagai sarana
penerangan dan menayangkan bayangan pada
dinding atau kain putih (kelir)
yang dibentangkan, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar
dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami
cerita wayang(lakon), penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh
wayang yang bayangannya tampil di layar.
Wayang kemudian berkembang sejak abad ke-9 dan ke-IO sebagai
media untuk pementasan lakon-lakon (cerita) yang diciptakan bertemakan sastra
epos Ramayana dan Mahabharata, dan kemudian sejak abad-abad pertengahan
diciptakan pula lakon-lakon yang dimasukkan kaedah-kaedah agama Islam.
Jenis-jenis wayang berkembang pesat dari zaman ke zaman, sehingga pada saat
ini, terdapat
lebih dari 60 jenis wayang, tersebar di seluruh Indonesia. Betapa
banyaknya corak ragam jenis wayang yang berkembang di
tanah
air. Wayang
Kulit atau Wayang Purwa termasuk kategori yang paling berkembang hingga
diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO sebagai ‘Masterpiece of Oral and
Intangible Heritage of Humanity’ pada tanggal 7 November 2003.
|
|
7
Wayang
istiwewa
sebagai
bentuk
kesenian karena
memiliki
sifat-sifat
yang dalam bahasa Jawa disebut adiluhung dan edipeni, yaitu sangat agung dan
luhur, dan juga sangat indah (etika dan estetika). Menurut para pujangga Jawa,
wayang
berfungsi
sebagai
tontonan
dan
tuntunan,
dan
merupakan
gabungan
lima jenis seni, yakni :
1. Seni Widya (filsafat dan pendidikan)
2. Seni Drama (pentas dan musik karawitan)
3. Seni Gatra (pahat dan seni lukis)
4. Seni Ripta (sangit dan sastra)
5. Seni Cipta (konsepsi dan ciptaan-ciptaan baru)
Setiap karakter dalam perwayangan
Jawa juga memiliki lambang
simbolis dan filosofi. Seperti yang dikutip dalam buku “Dari Ilmu Hastha Brata
Sampai
Sastra
Jendra Hayuningrat
(Wawan Susetya, 2006)” dijelaskan
bahwa
jumlah ‘Pandhawa 5’ identik dengan angka sakral 5 (lima), cermin jumlah
Rukun Islam, identik dengan jumlah shalat lima
waktu, dan melambangkan
buah-buah sila Pancasila. Dan melalui pendekatan visual diharapkan
masyarakat
dapat
lebih
memahami
sisi
karakter-karakter
dalam pembahasan
tentang simbolis dan filosofi perwayangan Indonesia.
Wayang bukan sekedar tontonan bayang-bayang atau "shadow play",
melainkan
sebagai 'wewayangane ngaurip'
yaitu
bayangan hidup
manusia. Dalam suatu pertunjukan wayang dapat dinalar dan dirasakan
|
|
8
bagaimana kehidupan manusia itu dari lahir hingga mati. Perjalanan hidup
manusia
untuk
berjuang
menegakkan yang benar dengan mengalahkan yang
salah. Dari pertunjukan wayang dapat diperoleh pesan untuk hidup penuh amal
saleh
guna
mendapatkan keridhoan
Illahi. Wayang
juga secara
nyata
menggambarkan
konsepsi
hidup
'sangkan
paraning
dumadi',
manusia
berasal
dari
Tuhan
dan akan
kembali
kepada-Nya. Berbicara kesenian wayang dalam
hubungannya
dengan
Pendidikan
Kepribadian
Bangsa
tidak
dapat
lepas
dari
pada
tinjauan
kesenian
wayang
itu sendiri
dengan
falsafah
hidup
bangsa
Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan
hidup bangsa Indonesia, merupakan ciri khusus yang dapat membedakan bangsa
Indonesia dengan bangsa lain.
2.2.2 Teknik Pembuatan Wayang
•
Bahan
Bahan pokok wayang kulit purwa adalah kulit kerbau atau kulit
lembu.
Kulit
kerbau
mempunyai
sifat
lebih
tebal,
kuat
tetapi
mudah
patah
dan
tahan
segala cuaca. Kulit kerbau biasanya
digunakan
untuk
tokoh utama atau wayang simpingan, misalnya danawa raton, boma,
sasran, katongan, satria, bambangan, putren dan bayen, serta wayang
jenis gamanan (panah, gada, tombak, dan sebagainya). Sedangkan kulit
lembu lebih tipis, ulet, tidak mudah patah, tapi tidak tahan cuaca dingin
sehingga mudah lembek. Jenis kulit ini biasa digunakan untuk membuat
|
|
9
wayang-wayang
dhudhahan
terutama
hewan
dan
rempahan
(prampongan dan kereta).
Kulit yang bagus untuk membuat wayang adalah kulit kerbau dan lembu
yang tidak terlalu tua (Jawa:kebo/sapi gemaron). Hal ini disamping serat
kulitnya padat dan ulet, juga warna kulitnya jernih (Jawa:ngaca).
Peralatan untuk menatah wayang kulit meliputi: penyorek, wali,
penggaris,
jangka, tatah, pandhukan,
rindhih,
gandhen, malam,
ungkal,
cowek, dan pethel. Penyorek digunakan menggambar wayang. Wali
digunakan
untuk
mengahaluskan bagian tepi
wayang. Penggaris
untuk
menggaris
bidang
datar
seperti
pundak,
serta
untuk
membagi
bidang.
Jangka
untuk
membentuk
mata
serta
untuk
persendian
tangan.
Tatah
untuk memahat wayang. Tatah berjumlah sekitar 20 biji; pahat bengkok,
pahat
lurus. Pandhukan
untuk alas
memahat, biasanya digunakan kayu
yang keras. Tindhih untuk menindih kulit yang ditatah. Gendhen utnuk
memukul tatah. Malam digunakan untuk
melicinkan
tatah.
Ungkal
digunakan
untuk
mengasah tatah.
Coek
untuk
tempat air
pada
waktu
mengasah. Pethel digunakan untuk mengatur tebal tipis kulit.
•
Gapitan
Gapitan wayang kulit pada dasarnya berfungsi memberikan
kekuatan pada wayang yang bersangkutan serta sebagai tangkai
pegangan.
Tangkai
penggapit wayang disebut
cempurit.
Gampitan
sangat erat kaitannya dengan bentuk dan gerak wayang. Lekukan-
|
|
10
lekukan cempurit pada pinggang,
leher, telinga dan bagian atas wayang
sangat besar pengaruhnya terhadap corekan wayang yang digapit. Dalam
hal penggapitan wayang kulit, dikenal istilahmecut, membat, dan
nggebug. Mecut yaitu suatu bentuk gerakan lentur seperti mencambuk,
mambat adalah suatu gerakan yang kenyal,sedangkan nggebug adalah
suatu gerakan yang kaku. Berkaitan dengan itu, Darman Gandadarsana
berpendapat untuk wayang-wayang bermahkota seperti Kresna,
Baladewa, dan figur Kayon, gapitannya mecut, sehingga kalau
digetarkan
ujungnya
dapat
bergerak ringan.
Untuk
tokoh-tokoh
satria
bergelung seperti Werkudara, Gatotkaca, dan Arjuna, gapitannya
membat, sehingga jika digerakkan akan
memunculkan
kesan
mantap.
Untuk tokoh yang cekatan dan lincah seperti Cakil dan prajurit kera,
gapitannya nggebug, sehingga tidak lentur jika digerakkan dengan ritme
cepat. Untuk wayang-wayang berbentuk besar seperti kereta, ampyak,
atau wayang-wayang
binatang,
gapitannya dibuat
seimbang
antara
bagian depan dan belakang, sehingga lebih mudah menghidupkan gerak
sesuai
dengan
sifatnya.
Disamping
itu,semua
bentuk
gapitan
harus
nyangga. Artinya, cempurit yang dipakai harus sesuai dengan ukuran
wayang.
|
|
11
•
Sunggingan
Sunggingan
adalah
pewarnaan
pada
wayang
kulit.
Setelah
pahatan selesai, makan proses pengamplasan biasanya dilakukan oleh
penyungging, agar kedua sisi wayang lebih halus.
Pewarna untuk
nyungging
terdiri
atas
lima macam warna dasar,
yaitu: putih, merah, kuning, biru, dan hitam. Untuk warna emas
digunakan prada atau brons, sedangkan untuk arsir (cawen) dan
drenjeman hitam digunakan tinta cina (mbag). Sebagai perekat
tradisional adalah ancur,
namun dalam perkembangannya sekarang
dapat
menggunakan
lem rakol dan
lainnya.
Untuk
memperkaya
warna
sunggingan perlu mencampur warna-warna dasar, meliputi:
1.
Campuran putih dan merah, menjadi merah jambu;
2.
Campuran kuning dan merah, menjadi orange ato sawo matang;
3.
Campuran kuning dan biru, menjadi hijau;
4.
Campuran putih dan hitam,
menjadi abu-abu (wesen atau
lemah
teles);
5.
Campuran putih, merah, dan biru, menjadi ungu;
6.
Campuran merah, hitam, dan biru, menjadi coklat (puru).
Adapun tahap-tahap penyunggingan sebagai berikut:
1.
nDhasari, yakni memberi warna dasar putih tipis pada tubuh dan
busana wayang kecuali rambut, muka dan tubuh yang akan
diwarnai hitam.
|
|
12
2.
Nyecegi, yakni menghitam pada seritan rambut, agar warna
hitamnya merata dalam pahatan seritan.
3.
Jika
menggunakan
prada,
maka
langkah
berikutnya
adalah
mendasari pada bidang yang akan diprada terutama pada bidang
busana, dengan warna kuning. Selanjutnya melekatkan prada
pada bidang busana.
4.
Mlepesi, adalah
memberi warna putih pada bidang busana,
sekaligus sebagai daasran warna jadi.
5.
Memberi
warna-warna, diawali warna
muda, yaitu merah jambu
muda, kuning dan biru muda, untuk menentukan komposisi
warnanya.
6.
Memberi
sorotan
warna
berikutnya
dengan
warna-warna
yang
lebih tua, yaitu; merah jambu tua (diatas merah jambu muda),
hijau muda (diatas kuning), dan biru agak tua (di atas biru
muda).
7.
Memberi
sorotan
warna
tua,
yaitu
merah
(diatas
merah
jambu
tua), hijau agak tua (diatas hijau muda), dan biru tua (diatas biru
agak tua).
8.
Memberi sorotan coklat dan hijau tua.
9.
Nyawi, yakni mengarsir pada sorotan warna dengan tinta
hitam;aadkalanya untuk sorotan merah digunakan tinta merah.
|
|
13
10.
Drenjemen,
yakni
titik-titik
pada
sorotan;
untuk
sorotan
warna
hijau
dan
biru
menggunakan
tinta
hitam, sedangkan
untuk
sorotan warna merah dan orange menggunakan tinta merah.
11.
Mrada, yaitu memberi warpada muka wayang atau muka.
12.
Ngraupi,
yakni
memberi
warna
pada
muka
wayang
sesuai
dengan warna yang dikehendaki; putih, merah jambu, biru muda,
hijau muda, dan sebagainya.
13.
Ulat-ulatan, yakni merias wajah, meliputi; membuat alis,
ganggeng kanyut (di muka godeg), kumis, simbar jaja, bulu-bulu
tangan, dan sebagainya.
14.
Toya
mangsi,
yakni
memberi
tekanan
pada
alis,
kumis,
bulu-
bulu, dan sebagainya, dengan menggunakan sorotan toya mangsi.
15.
Ngedus,
adalah
proses pelapisan pada
seluruh
bidang
agar
cemerlang dan mantap.
2.2.3
Pengelompokan Wayang
Wayang kulit purwa gaya Surakarta berdasarkan fungsinya dalam
pakeliran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni wayang baku dan
wayang srambahan. Wayang baku adalah peran
tokoh
utama
yang mempunyai
nama,
tipe
figur,
seperti;
Dasamuka,
Gatotkaca, Kresna, Setyaki, Puntadewa,
Werkodara,
Arjuna,
Dropadi,
Banowati,
dan sebagainya. Wayang srambahan
adalah
jenis
tipe
figur
wayang
yang
fleksibel
digunakan
untuk
peran
tokoh
|
|
14
sesuai dengan jenis tipologi dan karakternya, misal; danawa raton, boma,
sasran, katongan banyakan, patihan, dan beberapa putren.
Berdasar golongan, wayang satu kotak dapat dibedakan menjadi 15
kelompok, yakni :
1.
Katongan,
yaitu
para
raja
(Duryudana,
Baladewa,
Kresna,
Salya
dan
sebagainya).
2.
Putran, yaitu para satria (Bima, Arjuna, Abimanyu).
3.
Putren, yaitu tokoh wayang peran putri (Kunti, Banowati, Drupadi, dan
sebagainya).
4.
Boyen, yaitu wayang kecil untuk peran bayi,seperti Dewa Ruci.
5.
Dewa,
yaitu
tokoh
para
dewa
(Batara
Guru,
Narada,
Brahma,
Bayu,
Wisnu, dan sebagainya).
6.
Raseksa, yaitu tokoh wayang para raksasa (danawa raton, danawa nem,
punggawa raseksa, raksasa-raksesi wanan).
7.
Rewanda,
yaitu tokoh
wayang bala tentara kera (Anila, Anggada,
Anggeni, Jembawan, Saraba, dan sebagainya).
8.
Pungawa, yaitu wayang punggawa kerajaan (Udawa, Pragota, Prabawa,
Potropolo, dan sebagainya).
9.
Pandhita atau brahmana,
yaitu wayang tokoh pendeta, brahmana, biku,
dan cantrik (Abiyasa, Bisma, Krepa, dan sebagainya).
10.
Dhagelan, yaitu wayang-wayang humoris (punakawan dan setanan).
11.
Pawongan,
yaitu
wayang-wayang peran pembantu atau dayang-dayang
(Cangik dan Limbuk).
|
|
15
12.
Kewanan,
yaitu
wayang-wayang
rempahan
berupa
binatang
hutan
(harimau, banteng, ular, babi hutan, dan sebagainya).
13.
Titihan, yaitu wayang jenis kendaraan (kereta, perahu, kuda, gajah, dan
prampongan/ampyak).
14.
Gemanan,
yaitu
wayang-wayang jenis senjata (panah, cakra, keris,
tombak, gada, pedang).
15.
Kayon, yaitu wayang figur gunungan (gapuran dan blumbangan).
Berdasar
penataan
pada
pertunjukan,
jenis wayang dikelompokkan
menjadi tiga bagian:
1.
Wayang panggungan atau simpingan, yaitu wayang-wayang yang ditata
di atas batang pisang pada sisi kanan dan kiri panggungan.
2.
Wayang dhudhahan, yaitu wayang-wayang yang ditata di dalam kotak.
3.
Wayang ricikan, yaitu wayang-wayang yang ditata ditutup kotak.
2.2.4
Bentuk Organ Tubuh Wayang
Wayang kulit purwa gaya Surakarta dapat dikelompokkan berdasarkan
polatan, pasemon,
dan
adegnya.
Berdasarkan polatan atau raut muka, wayang
kulit Surakarta dibedakan menjadi tiga kelompok:
1.
Wayang
luruh/oyi, yakni
figur wayang
yang
raut
mukanya
menunduk
(Puntadesa, Werkudara, Arjuna, Abimanyu, Drupadi).
2.
Wayang
semuruh,
yakni
figur
wayang
yang
raut
mukanya
tegap
(Nakula, Sadewa, Irawan).
|
|
16
3.
Wayang
lanyap/endhel,yakni
figur
wayang
yang
raut
mukanya
mendongak (Narayana, Suman, Rukmarata, Banowati, Srikandi).
Berdasarkan
adeg
atu
postur
tubuhnya,
wayang
kulit
Surakarta
dibedakan menjadi empat kelompok:
1.
Adeg jejeg, figur wayang yang postur tubuhnya tegap (Abimanyu,
Arjuna, Bratasena).
2.
Adeg
ndhetheng,
yakni
figur wayang
yang
postur
tubuhnya rebah
ke
belakang (Narayana, Karna).
3.
Adeg sangkuk, yakni figur wayang yang postur tubuhnya membungkuk
(Anoman dan para kera, Rama).
4.
Adeg
wungkuk,
yakni
figur
wayang
yang
garis
punggungnya
membungkuk ke depan (Semar, pendeta tua).
2.3
Produk
Buku referensi visual mengenai karakter perwayangan Purwa versi Pandawa.
2.4
Karakteristik Produk
Produk publikasi Tugas Akhir ini memiliki beberapa ciri-ciri, yakni:
•
Membahas silsilah dan karakter-karakter dalam dunia perwayangan
yang ada dalam perwayangan purwa.
•
Pembahasan
yang
dilakukan
masih
berada
dalam
lingkup
pengenalan
karakter, dengan penceritaan yang bersifat mendasar, namun kaya akan
|
|
17
visual.
•
Memiliki visual
yang penuh ilustrasi dan
warna
yang disesuaikan
dengan selera target konsumen.
2.5
Struktur Buku
Spesifikasi buku secara terperinci, adalah sebagai berikut:
Cover
BAB I.
Pendahuluan
Legenda
Peta Negara
BAB II.
Pandawa
Puntadewa
Bima
Arjuna
Nakula
Sadewa
BAB IV.
Sesepuh
Bisma
Kresna
BAB V.
Punakawan
Semar
Bagong
Petruk
|
|
18
Gareng
Penutup
Ukuran buku
:
25cm x 30cm (hard cover)
Full Colour
Tebal buku
:
42 halaman.
2.5.1 Karakter-karakter
•
PUNTADEWA
Puntadewa adalah putra sulung Prabu Pandudewanata, raja negara
Astina
dengan
permaisuri
Dewi Kunti dari negara Mandura. Ia
mempunyai dua orang adik kandung bernama Bima dan Arjuna, dan dua
adik kembar lain ibu, bernama Nakula dan Sadewa, putra Prabu Pandu
dengan Dewi Madrim dari negara Mandaraka.
Puntadewa adalah titisan Batara Darma. Ia mempunyai watak
sabar, sabar, ikhlas, percaya atas kuasa
Tuhan,
tekun dalam agamanya,
tahu
membalas guna dan selalu bertindak adil dan jujur. Ia senang
bermain catur. Setelah Pandawa berhasil mebangun negara Amarta di
hutan
Mertani,
Puntadewa
dinobatkan menjadi
raja
Amarta
bergelar
Prabu Darmakusuma. Ia juga bergelar Prabu Yudhistira karena dalam
tubuhnya memanggil arwah Prabu Yudhistira, raja jin negara Mertani.
Prabu Puntadewa
menikah dengan Dewi Drupadi dari
negara
Pancala, dan berputrakan Pancawala. Prabu Puntadewa
mempunyai
|
|
19
pusaka kerajaan berwujud payung bernama Kyai Tunggulnaga dan
sebuah tombak bernama Kyai Karawelang.
Dalam perang
Bharatayudha,
Prabu
Puntadewa
tampil
sebagai
senopati
para
Pandawa,
dan
berhasil menewaskan
Prabu
Salya,
raja
negara Mandaraka. Sesudah berakhirnya
perang,
Prabu
Puntadewa
menjadi raja negara Astina bergelar Prabu Karimataya. Setelah
menobatkan Parikesit, putra Abimanyu dengan Dewi Utari sebagai raja
Astina,
Prabu
Puntadewa
memimpin perjalanan
moksa
para
Pandawa
yang diikuti Dewi Drupadi menuju Nirwana.
•
BIMA
Bima atau Werkudara adalah
putra
kedua
Prabu
Pandu,
raja
negara Astina dengan Dewi Kunti dari negara Mandura. Bima
mempunyai
dua
orang
saudara
kandung
bernama
Puntadewa dan
Arjuna, serta dua saudara lain ibu, yaitu : Nakula dan Sadewa.
Bima
memiliki
sifat dan perwatakan gagah berani, teguh, kuat,
tabah, patuh dan jujur. Ia memiliki keistimewaan ahli bermain gada dan
memiliki berbagai senjata antara lain; Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala,
Alagara, Bargawa (kapak besar) dan Bargawasta, sedangkan ajian yang
dimiliki
:
Aji
Bandungbandawasa,
Aji
Ketuklindu dan
Aji
Blatukpangantol-antol.
Bima
juga
memiliki
pakaian
yang melambangkan
kebesaran,
yaitu:
Gelung
Pudaksategal,
Pupuk
Jarot
Asem, Sumping
Surengpati,
|
|
20
Kelatbahu
Candrakirana,
ikat
pinggang Nagabanda
dan celama Cinde
Udaraga. Sedangkan beberapa
anugerah
Dewata
yang
diterimanya
antara
lain: Kampuh/kain
Poleng
Bintuluaji,
Gelang Candrakirana,
Kalung Nagasasra, Sumping Surengpati dan pupuk Pudak Jarot Asem.
Bima tinggal di kadipaten Jodipati, wilayah negara Amarta. Ia
mempunyai tiga orang isteri dan tiga orang anak, yaitu: Dewi Nagagini,
berputra Arya Anantareja, Dewi Arimbi, berputra Raden Gatotkaca dan
Dewi Urangayu, berputra Arya Anantasena.
Akhir
riwayat
Bima
diceritakan,
mati sempurna
(moksa)
bersama
keempat saudaranya setelah akhir perang Bharatayudha.
•
ARJUNA
Arjuna seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa dan
berguru menuntut ilmu. Arjuna pernah menjadi brahmana di Goa
Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan kesatria unggulan
para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari
negara Manimantaka.
Atas
jasanya
itu,
Arjuna
dinobatkan
sebagai raja
di Kahyangan Dewa
Indra, bergelar Prabu Karitin. dan
mendapat
anugrah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain: Gendewa (dari
Bhatara
Indra),
Panah Ardadadali
(dari
Bhatara
Kuwera),
Panah
Cundamanik (dari Bhatara Narada).
Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, teliti, sopan-
santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin
|
|
21
Kadipaten Madukara, dalam wilayah
negara
Amarta.
Setelah
perang
Bharatayuddha, Arjuna menjadi raja di Negara Banakeling, bekas
kerajaan
Jayadrata.
Akhir riwayat Arjuna
diceritakan,
ia
moksa
(mati
sempurna) bersama keempat saudaranya yang lain di gunung Himalaya.
•
NAKULA
Nakula dalam pedalangan Jawa disebut pula dengan nama Pinten
(nama tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dipergunakan sebagai
obat) adalah putra
keempat Prabu
Pandudewanata,
raja
negara
Astina
dengan permaisuri Dewi Madrim, putri Prabu Mandrapati dengan Dewi
Tejawati, dari negara Mandaraka. Ia lahir kembar bersama adiknya,
Sahadewa atau Sadewa (pedalangan Jawa). Nakula juga mempunyai tiga
saudara satu ayah, putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti, dari
negara
Mandura bernama; Puntadewa/Yudhistira, Bima/Wekodara dan Arjuna.
Nakula adalah titisan Batara Aswi, Dewa Tabib. Ia mahir
menunggang
kuda dan pandai menggunakan senjata panah dan lembing. Nakula tidak
akan dapat lupa tentang segala yang ia ketahui karean ia mempunyai Aji
Pranawajati
pemberian
Ditya
Sapujagad,
Senapati
negara
Mretani.
Ia
juga
mempunyai
cupu
berisi,
"Banyu
Panguripan/Air
Kehidupan"
pemberian Batara Indra.
Nakula mempunyai watak jujur, setia, taat, belas kasih, tahu
membalas
guna dan dapat
menyimpan rahasia.
Ia
tinggal
di
kasatrian
Sawojajar,
wilayah
negara Amarta. Nakula mempunyai dua orang
istri
|
|
22
yaitu, 1. Dewi Sayati, putri Prabu Kridakirata, raja negara
Awuawulangit, dan memperoleh dua orang anak bernama Bambang
Pramusinta
dan
Dewi
Pramuwati. 2.
Dewi
Srengganawati,
putri
Resi
Badawanganala,
kura-kura
raksasa
yang
tinggal di
sungai/narmada
Wailu
(menurut
Purwacarita,
Badawanangala dikenal
sebagai
raja
negara
Gisiksamodra/Ekapratala) dan
memperoleh
seorang
putri
bernama
Dewi
Sritanjung. Dari perkawinan
itu
Nakula
mendapat
anugrah cupu pusaka berisi air kehidupan bernama Tirtamanik.
Setelah selesai perang Bharatayuda, Nakula diangkat menjadi
raja negara Mandaraka sesuai amanat Prabu Salya, kaka ibunya, Dewi
Madrim. Akhir riwayatnya diceritakan, Nakula mati moksa bersama
keempat saudaranya.
•
SADEWA
Sadewa
atau
Sahadewa
dalam pedalangan
Jawa
disebut
pula
dengan nama Tangsen (buah dari tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat
dipakai
untuk obat) adalah putra kelima/bungsu Prabu Pandudewanata,
raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Madrim, putri Prabu
Mandrapati dengan Dewi Tejawati dari negara Mandraka. Ia lahir
kembar bersama
kakaknya,
Nakula.
Sadewa
juga
mempunyai
tiga
saudara satu ayah, putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti, dari keluarga
Mandura, bernama; Puntadewa, Bima/Werkudara dan Arjuna.
|
|
23
Sadewa adalah titisan Batara Aswin, Dewa Tabib. Ia sangat
mahir dalam ilmu kasidan (mistikus). Mahir menunggang kuda dan
mahir
mengguankan
senjata
panah
dan
lembing.
Selain sanagt sakti,
Sadewa
juga
memiliki
Aji
Purnamajati
pemberian Ditya
Sapulebu,
Senapati negara Mretani yang berkhasiat;dapat mengerti dan mengingat
dengan jelas pada semua peristiwa.
Sadewa mempunyai watak jujur, setia, taat, belas
kasih,
tahu
membalas
guna dan dapat
menyimpan rahasia.
Ia
tinggal
di
kesatrian
Bawetalun, wilayah negara Amarta. Sahadewa menikah dengan Dewi
Srengginiwati, adik Dewi Srengganawati
(istri
Nakula).
Dari
perkawinan tersebut
ia
memperoleh seorang putra bernama Bambang
Widapaksa.
Setelah
selesai
perang Bharatayudha,
Sadewa
menjadi
patih
negara Astina mendampingi Prabu Yudhistira. Akhir riwayatnya
diceritakan, Sadewa mati moksa bersama keempat saudaranya.
•
BISMA
Bisma terlahir sebagai Dewabrata. Ia merupakan putera dari
pasangan Prabu Santanu dan Satyawati. Ia juga merupakan kakek dari
Pandawa maupun Korawa. Semasa muda ia bernama Dewabrata, namun
berganti menjadi Bisma semenjak ia bersumpah bahwa tidak akan
menikah seumur hidup. Bisma ahli dalam segala modus peperangan dan
sangat disegani oleh Pandawa dan Korawa. Ia gugur dalam sebuah
|
|
24
pertempuran besar di Kurukshetra oleh panah dahsyat yang dilepaskan
oleh Srikandi dengan bantuan Arjuna. namun ia tidak meninggal pada
saat itu juga. Ia sempat
hidup selama beberapa hari dan menyaksikan
kehancuran para Korawa. Ia menghembuskan nafas terkahirnya saat
garis balik matahari berada di utara (Uttarayana).
Nama Bhishma dalam bahasa Sansekerta berarti “Dia yang
sumpahnya
dahsyat (hebat)”, karena ia bersumpah akan hidup
membujang selamanya dan tidak mewarisi tahta kerajaannya. Nama
Dewabrata diganti menjadi Bisma karena ia melakukan bhishan
pratigya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan
mewarisi tahta ayahnya. Hal itu dikarenakan Bisma tidak ingin dia dan
keturunannya berselisih dengan keturunan Satyawati, ibu tirinya.
Bisma
memiliki
dua adik
tiri
dari ibu
tirinya yang
bernama
Satyawati. Mereka bernama
Citranggada
dan
Wicitrawirya.
Demi
kebahagiaan adik-adiknya,
ia pergi ke Kerajaan Kasi dan memenagkan
sayembara sehingga berhasil membawa pulang tiga orang puteri
bernama Amba, Ambika, dan Ambalika, untuk dinikahkan kepada adik-
adiknya. Karena Citranggada wafat, maka Ambika dan Ambalika
menikah
dengan
Wicitrawirya
sedangkan
Amba
mencintai
Bisma
namun Bisma
menolak
cintanya
karena terikat oleh
sumpah
bahwa
ia
tidak akan kawin seumur hidup. Demi usaha untuk menjauhkan Amba
dari dirinya, tanpa sengaja ia menembakkan panah menembus
dada
Amba.
Atas
kematian
itu,
Bisma
diberitahu
bahwa
kelak
Amba
|
|
25
bereinkarnasi menjadi seorang pangeran yang memiliki sifat kewanitaan,
yaitu putera
Raja Drupada
yang bernama Srikandi. Kelak kematiannya
juga
berada
di
tangan
Srikandi yang
membantu
Arjuna
dalam
pertempuran akbar di Kurukshetra.
•
KRESNA
Prabu
Kresna
pada
waktu
mudanya bernama Narayana, adalah
putra Prabu
Basudewa,
raja
negara Mandura dengan
permaisuri
Dewi
Mahendra.
Ia
lahir
kembar
bersama kakaknya, Kakrasana, dan
mempunyai adik lain ibu bernama Dewi Sumbadra, putri Prabu
Basudewa dengan permaisuri Dewi Badrahini.
Prabu
Kresna
adalah
titisan Sang
Hyang
Wisnu
yang
terakhir.
Selain sangat sakti dan bertiwikrama, ia juga mempunyai pusaka-pusaka
sakti,
antara
lain;
Senjata Cakra,
Kembang
Wijayakusuma,
Terompet/Sangkala
Pancajahnya,
Kaca
Paesan, Aki
Pameling
dan
Aji
Kawrastawan. Ia mendapat negara Dwarawati setelah mengalahkan
Prabu Kalakresna, kemudian
naik tahta bergelar Prabu Sri
Batara
Kresna.
Prabu Kresna mempunyai empat orang permaisuri:
Dewi Jembawati, berputra Samba dan Gunadewa (berwujud kera)
Dewi
Rukmini, berputra Saradewa (berwujud raksasa), Partadewa dan
Dewi Titisari
Dewi Setyaboma, berputra Arya Setyaka
|
|
26
Dewi Pratiwi, berputra Bambang Sitija dan Dewi Siti Sundari
Ia
wafat
dalam keadaan
bertapa
dengan
perantaraan
panah
seorang
pemburu bernama Ki Jara yang mengenai kakinya.
•
SEMAR
Semar adalah pamong/parampara trah keturunan Witaradya
(sejarah
keturunan
para
raja).
Semar
adalah
puta
Batara
Wungkuam,
yang berarti cucu Sang Hyang Ismaya. Semar juga merupakan
penjelmaan Ang Hyang Ismaya, kakeknya sendiri.
Semar mempunyai sifat dan perwatakan ; sabar, longgar, momong
(menjaga mengasuh), bicaranya mengandung fatwa nasehat. Dalam
cerita pedalangan, Semar dikenal sebagai manusia boga sampir.
Berbadan pendek, rambutnya berkuncung putih, mata rembes, hidung
kecil, bibir cabik. Semar menikah dengan Dewi Kanistri, putri Batara
Hira,
keturunan
Sang
Hyang
Caturwarna,
putra
Sang
Hyang
Caturkanwaka.
Sepanjang hidupnya Semar selalu menjadi
pamong keturunan
witaradya
bersama
dengan
Bagong.
Kemudian
bertambah
dengan
Gareng dan Petruk. Ketiga temannya
itu kemudian diakuinya sebagai
putra angkatnya. Dalam keadaan sehari-harinya, Semar berlaku sebagai
punakawan biasa, tetapi bilamana perlu
ia tidak segan-segan bertindak
untuk
membenarkan hal-hal yang tidak betul.Sebagai penjelmaan Sang
|
|
27
Hyang Ismaya, Semar
juga
memiliki kebebasan dan keleluasaan
untuk
datang ke
Jonggringsaloka
bertemu
dengan Sang
Hyang Manikmaya,
atau menemui Sang Hyang Tunggal di khayangan Alangalangkumitir.
Sebagai
penjelmaan
Sang
Hyang
Ismaya,
Semar
berumur
sangat
panjang,
mencapai
ribuan
tahun,
hidup
dari
jaman
Ramayana,
Mahabrahata dan jaman Parikesit.
Dalam dunia
pewayangan
dikenal
tokoh
punakawan
yang
bernama Semar. Semar adalah punakawan dari para ksatria yang luhur
budinya dan baik pekertinya. Sebagai punakawan Semar adalah abdi,
tetapi berjiwa pamong, sehingga oleh para ksatria Semar dihormati.
Penampilan
tokoh
Semar
dalam pewayangan
sangat
menonjol.
Walaupun
dalam kehidupan
sehari-hari tidak
lebih
dari
seorang
abdi,
tetapi pada saat-saat tertentu Semar sering berperan sebagai seorang
penasehat dan penyelamat para ksatria disaat menghadapi bahaya baik
akibat ulah sesama manusia maupun akibat ulah para Dewa. Dalam
pewayangan tokoh Semar sering
dianggap sebagai Dewa yang
ngejawantah atau Dewa yang berujud
manusia.
Menurut
Serat
Kanda
dijelaskan bahwa Semar sebenarnya adalah anak Syang Hyang Tunggal
yang semula bernama Batara Ismaya saudara tua dari Batara Guru.
Semar sebagai Dewa yang berujud manusia mengemban tugas
khusus
menjaga
ketenteraman
dunia dalam penampilan sebagai
rakyat
biasa. Para ksatria utama
yang berbudi luhur mempunyai keyakinan
bilamana
menurut segala nasehat
Semar
akan
mendapatkan
|
|
28
kebahagiaan. Semar dianggap memiliki kedaulatan yang hadir ditengah-
tengah
para
ksatria
sebagai
penegak
kebenaran
dan
keadilan.
Dengan
kata lain Semar adalah simbul rakyat yang merupakan sumber
kedaulatan bagi para ksatria atau yang berkuasa.
•
PETRUK
Petruk dikenal pula dengan nama Kanthongbolong. Petruk lazim
disebut
sebagai
anak
Semar,
masuk
dalam golongan
punakawan.
Sebelumnya
ia bernama Bambang Pecrukpanyukilan, putra Bagawan
Salantara dari padepokan Kembangsore. Ia sangat gemar bersendagurau,
baik dengan ucapan ataupun tingkah laku dan senang berkelahi.
Bambang Pecrukpanyukilan pergi berkelana untuk menguji
kesaktian. Di tengah jalan ia bertemu dengan Bambang Sukskati,
yang
pergi dari pedepokannya diatas bukit untuk mencoba kekebalannya.
Karena
menpunyai
madsud
yang
sama,
terjadilah perang
tanding.
Mereka berkelahi sangat lama, berhantam, bergerumul, tendang
menendang,
injak menginjak,
hingga
tubuh
mereka
menjadi cacat dan
beda sekali dengan bentuk aslinya. Perkelahian mereka berhenti setelah
dilerai Sang Hyang Ismaya/Semar dan Bagong.
Setelah
diberi
fatwa
dan
nasehat,
keduanya
menyerahkan
diri
dan berguru kepada Semar, dan
mengabdi kepada Sang Hyang Ismaya.
Karena perubahan wujud
tersebut,
mereka
masing-masing
berganti
|
|
29
nama,
Bambang
Sukskati
menjadi
Nala
Gareng,
sedangkan
Bambang
Pecrukpanyukilan menjadi Petruk.
•
GARENG
Gareng lazim disebut sebagai anak Semar dan masu dalam
golongan punakawan. Aslinya, Gareng bernama Bambang Sukskati,
putra Resi Sukskadi dari padepokan Bluluktiba. Bertahun-tahun
Bambang Sukskati bertapa di bukit Candala untuk mendapatkan
kesaktian. Setelah selesai tapanya, ia kemudian minta ijin pada ayahnya
untuk pergi menaklukkan raja-raja.
Di tengah perjalanan Bambang Sukskati bertemu dengan
Bambang Panyukilan, putra Begawan Salantara dari padepokan
Kembangsore. Karena sama-sama congkaknya dan sama-sama
mempertahankan pendiriannya, terjadilah peperangan antara keduanya.
Mereka mempunyai kesaktian yang seimbang sehingga tiada yang kalah
dan menang. Mereka juga tak mau berhenti berkelahi walau tubuh
mereka telah saling cacat tak karuan.
Perkelahian baru berakhir setelah dilerai oleh Semar/Sang Hyang
Ismaya, berubahlah wujud keduanya menjadi sangat jelek. Tubuh
Bambang Sukskati menjadi
cacat, matanya juling, hidung bulat bundar,
tak berleher, perut gendut, kaki pincang, dan tangan bengkok. Oleh Sang
Hyang Ismaya namanya diganti menjadi Nala Gareng, sedangkan
Bambang Panyukilan menjadi Petruk.
|
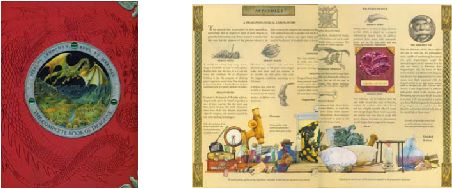 30
Nala Gareng menikah dengan Dewi Sariwati, putri Prabu
Sarawasena dengan permaisuri Dewi Saradewati dari negara Salarengka,
yang siperolehnya atas bantuan Resi Tritusta dari negara Purwaduksina.
Nala Gareng berumur sangat panjang, ia hidup sampai jaman Madya.
2.6
Kompetitor Buku
Judul Buku
: Dragonology
Ukuran
: 25,5 cm X 29,7 cm
Penerbit
: Candlewick Press.
2.7
Target Komunikasi
Psikografi
:
Sudah
mandiri,
sudah dapat
menetapkan
keputusan
untuk
diri
sendiri,
memiliki rasa
ingin tahu
yang
besar,
menyukai
visual
art yang kaya warna, senang melihat hal-hal baru.
Behaviour
:
Menyukai hal-hal menyangkut budaya.
Demografi
: Generasi muda umur 20-30 tahun, SES A dan atau B.
Geografi
: Berdomisili di kota-kota besar.
|
|
31
2.8
Mandatoris
Gramedia Pustaka Utama
Penerbit
Gramedia
mulai
menerbitkan buku sejak tahun 1974. Dengan
misi “Ikut mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa serta masyarakat
Indonesia”, Gramedia
Pustaka
Utama
berusaha
keras
untuk
menjadi
agen
pembaruan bagi bangsa ini dengan memilih dan memproduksi buku-buku yang
berkualitas,
yang
memperluas
wawasan, memberikan pencerahan, dan
merangsang kreativitas berpikir. Gramedia Pustaka
Utama
mengkonsentrasikan
diri untuk menggarap dua bidang utama, yakni fiksi dan non-fiksi. Bidang fiksi
dibagi menjadi fiksi anak-anak dan
pra-remaja, remaja, dewasa. Bidang non-
fiksi dibagi menjadi humaniora, pengembangan diri, bahasa dan sastra
Indonesia, bahasa Inggris/ELT, kamus
dan referensi, sains dan teknologi,
kesehatan, kewanitaan (masakan, busana), dsb.
PT.Gramedia Pustaka Utama
Gedung Gramedia lt. 2-3
Jl. Palmerah Barat 33-37
Jakarta 10270
Telp. (021) 53677834 (hunting) ext. 3251, 3252, 3258
Fax (021) 5360316, 5360315, 5300545
|
|
32
2.9
Analisa SWOT
2.9.1
Strength (Kekuatan/Faktor Pendukung)
•
Buku mengenai wayang sudah banyak yang berupa tulisan, namun buku
yang berupa referensi visual belum begitu banyak.
•
Penggambaran detil
yang
sehingga
target komunikasi dapat
memperhatikan dengan baik ciri dari tiap karakter. Mengingat gambar-
gambar wayang yang beredar secara umum tidak jelas (low ressolution).
2.9.2
Weakness (Kelemahan/Faktor Penghambat)
•
Dikarenakan
target
masih
tergolong
anak muda,
agak
sulit
untuk dapat
selalu memahami target konsumen dalam masalah selera.
•
Publikasi
buku
ilustrasi
memerlukan
biaya produksi yang tidak
sedikit,
oleh karena itu ada kemungkinan harga buku pereksemplar tidak dapat
disanggupi oleh beberapa pihak.
2.9.3
Opportunity (Peluang/Keuntungan)
•
Makin maraknya studi-studi yang menggali kembali kebudayaan lokal.
•
Masih minimnya buku bergambar dengan tema serupa.
•
Pada
masa
modern
ini,
masih ada
kolektor
muda
yang
masih
tertarik
dengan
budaya
wayang
dan
juga
ada yang tertarik dengan ilustrasi
sehingga ikut tertarik untuk membaca lebih lanjut.
•
Bangsa Indonesia dewasa ini banyak menerima ancaman dari dalam
maupun luar negeri tentang kepemilikan sebuah budaya. Dengan
|
|
33
meningkatkan minat pada budaya wayang yang sudah diakui
keberadaannya sebagai warisan dunia, termasuk juga menyelamatkan
salah satu khasanah budaya bangsa.
2.9.4
Threat
•
Hingga saat ini, penggambaran wayang dalam pikiran awam, pusing dan
susah dimengerti penceritaan, karakter yang banyak dan berbelit-belit,
bahkan
beberapa
orang
menganggap
dalam
mengangkat
topik
wayang
itu sudah outdate.
•
Banyaknya
kebudayaan
dari
luar
yang
mendominasi
kehidupan
anak
muda sekarang ini.
•
Buku serupa buatan luar yang lebih menarik.
|