|
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Hujan / Presipitasi
Hujan merupakan
satu bentuk presipitasi,
atau turunan cairan dari angkasa,
seperti salju, hujan es, embun dan kabut. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah
jatuh ke bumi dari awan. Tidak semua air
hujan sampai ke permukaan bumi, sebagian
menguap
ketika
jatuh
melalui
udara kering,
sejenis
presipitasi yang dikenali
sebagai
virga.
Hujan
merupakan salah satu
komponen
input
dalam
suatu
proses
dan
menjadi
faktor pengontrol
yang mudah diamati dalam siklus hidrologi pada suatu kawasan
(DAS). Peran
hujan sangat
menentukan proses
yang akan terjadi dalam suatu kawasan
dalam kerangka satu sistem hidrologi dan mempengaruhi
proses yang terjadi
didalamnya.
Jumlah
air
hujan
diukur
menggunakan
pengukur
hujan.
Ia
dinyatakan
sebagai
kedalaman air yang terkumpul pada permukaan rata, dan diukur kurang
lebih 0.25mm.
Air
hujan sering digambarkan sebagai berbentuk "lonjong",
lebar di bawah dan
menciut
di
atas,
tetapi
ini
tidaklah tepat.
Air
hujan
kecil
hampir
bulat. Air
hujan
yang
besar
menjadi
semakin
leper, seperti roti
hamburger; air
hujan
yang
lebih
besar
berbentuk
|
|
6
payung terjun. Air
hujan yang besar jatuh lebih cepat berbanding air
hujan yang lebih
kecil.
Pada
dasarnya
Hujan
dapat
saja terjadi
di
sembarang
tempat, asalkan
terdapat
dua
faktor,
yaitu
terdapat
massa udara
lembab, dan terdapat sarana
meteorologis yang
dapat mengangkat massa udara tersebut untuk berkondensasi. Hujan terjadi akibat
adanya massa udara yang menjadi dingin, mencapai suhu di bawah titik embunnya yang
memulai
pembentukan molekul
air.
Titik
embun
adalah
temperatur
pada
saat
udara
menjadi
jenuh
apabila
udara
didinginkan pada
temperature
tetap.
Hujan
hanya
akan
terjadi apabila molekul-molekul air
hujan sudah mencapai ukuran
lebih dari 1 mm. Hal
ini
memerlukan waktu
yang cukup
untuk tumbuh
dari
ukuran sekitar 1 –
100
mikron.
Proses gerakan udara keatas disebabkan oleh berbagai sebab, yang kemudian hal
tersebut
menentukan
jenis
genetic
hujan,
yaitu
hujan
konvektif,
hujan
siklonik,
dan
hujan orografik.
Hujan
konvektif
biasanya
terjadi
sebagai
hujan
dengan intensitas
yang
tinggi,
akibat
massa
udara
yang
terangkat
keatas
oleh
pemanasan
lahan,
atau
karena
udara
dingin yang bergerak di atas laut atau dataran yang panas. Hujan jenis ini dapat tejadi di
daerah yang relatif luas, dan bergerak sesuai dengan gerakan angin. Pembentukan hujan
ini dapat dilihat dalam sketsa gambar berikut.
|
 7
(Sumber : Sri Harto BR, Hidrologi, 2000)
Gambar 2.1 Proses Pembentukan Hujan Konvektif
Hujan Siklonik dapat terjadi karena
udara
lembab panas terangkat ke atas oleh
lapisan
udara
yang
lebih
dingin
dan
lebih
rapat.
Penyebaran hujan
jenis
ini
sangat
dipengaruhi oleh
landai bidang pertemuan antara udara panas dan
udara dingin (warm
front
/
cold front)
dan biasanya
merupakan
hujan dengan daerah penyebaran terbatas
dalam waktu pendek. Proses pembentukannya seperti gambar berikut.
(Sumber : Sri Harto BR, Hidrologi, 2000)
Gambar 2.2 Proses Pembentukan Hujan Siklonik
|
 8
Hujan orografik terjadi karena
massa udara
lembab terangkat keatas oleh angin
yang
terangkat
karena
adanya
gunung
/
pegunungan /
dataran
tinggi. Kejadian
yang
sebenarnya tidak sesederhana hal tersebut, karena mekanisme terangkatnya massa udara
dapat
disebabkan
oleh
gabungan
dari
ketiga
hal
tersebut,
yang
menyebabkan hujan
memiliki variabilitas ruang dan variabilitas waktu yang berbeda-beda. Khusus di daerah
tropic
seperti
Indonesia,
variabilitas
tersebut dapat
terjadi
sangat
tinggi.
Sketsa
sederhana yang menunjukkan proses pembentukan hujan orografik dapat dilihat dalam
gambar berikut.
(Sumber : Sri Harto BR, Hidrologi, 2000)
Gambar 2.3 Proses Pembentukan Hujan Orografik
2.1.2
Karakteristik Sungai
Sungai
merupakan
jalan air alami. Laluan
melalui sungai
merupakan cara biasa
air
hujan
yang
turun di daratan
untuk
mengalir ke
laut atau tampungan air
yang besar
seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir
ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama.
Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai.
|
|
9
Sungai
mempunyai
fungsi
mengumpulkan curah
hujan
dalam
suatu
daerah
tertentu
dan
mengalirkannya ke
laut. Sungai
itu
dapat
digunakan
juga
untuk berjenis-
jenis aspek seperti pembangkit tenaga listrik, pelayaran, pariwisata, perikanan, dan lain-
lain.
Dalm bidang pertanian sungai
itu berfungsi sebagai sumber air
yang penting buat
irigasi.
a. Daerah Pengaliran
Daerah
pengaliran
sebuah
sungai
adalah
daerah
tempat
presipitasi itu
mengkonsentrasi ke sungai. Garis batas daerah-daerah aliran yang berdampingan disebut
batas daerah pengaliran. Luas daerah pengaliran diperkirakan dengan pengukuran daerah
itu
pada
peta
topografi.
Daerah
pengaliran,
topografi,
tumbuh-tumbuhan dan
geologi
mempunyai pengaruh terhadap debit banjir, corak banjir, debit pengaliran dasar dan lain-
lain.
b.
Corak dan Karakteristik Daerah Pengaliran
•
Daerah pengaliran berbentuk bulu burung
Jalur daerah di kiri kanan
sungai
utama dimana
anak-anak
sungai
mengalir ke
sungai
utama
disebut
daerah
pengaliran bulu
burung.
Daerah
pengaliran
sedemikian
mempunyai debit banjir yang kecil, oleh karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungai
itu berbeda-beda. Sebaliknya banjirnya berlangsung agak lama.
|
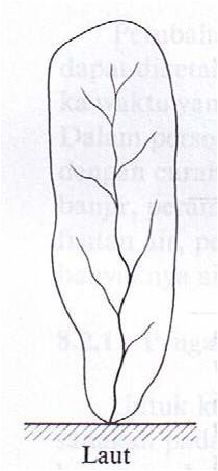 10
(Sumber : Suyono Sosrodarsono, Hidrologi untuk pengairan, 2003)
Gambar 2.4 Daerah Pengaliran Berbentuk Bulu Burung
•
Daerah pengaliran radial
Daerah
pengaliran
yang
berbentuk
kipas
atau
lingkaran
dimana
anak-anak sungainya
mengkonsentrasi
ke
suatu
titik secara
radial
disebut
daerah
pengaliran
radial. Daerah
pengaliran dengan
corak
demikian
mempunyai
banjir
yang
besar
di
dekat
titik
pertemuan anak-anak sungai.
|
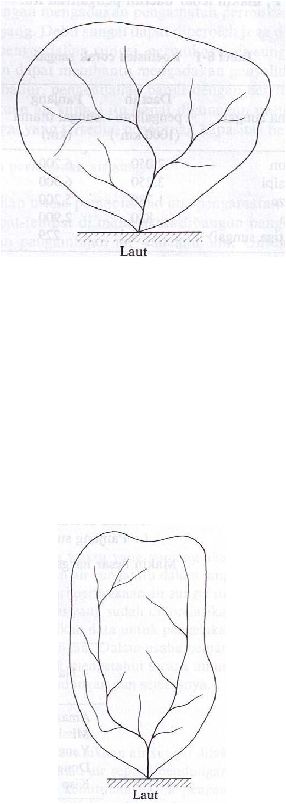 11
(Sumber : Suyono Sosrodarsono, Hidrologi untuk pengairan, 2003)
Gambar 2.5 Daerah Pengaliran Radial
•
Daerah pengaliran paralel
Bentuk ini
mempunyai corak dimana dua jalur daerah pengaliran yang berada di
bagian pengaliran
yang sama, bersatu di
bagian
hilir. Banjir
itu terjadi di
sebelah hilir
titik pertemuan sungai-sungai.
(Sumber : Suyono Sosrodarsono, Hidrologi untuk pengairan, 2003)
Gambar 2.6 Daerah Pengaliran Paralel
|
|
12
2.1.3 Daerah Aliran Sungai (DAS)
Daerah aliran sungai (DAS) menurut definisi adalah suatu daerah yang dibatasi
(dikelilingi) oleh garis ketinggian dimana setiap air yang jatuh di permukaan tanah akan
dialirkan melalui satu outlet. Komponen
yang ada di dalam
sistem DAS secara
umum
dapat
dibedakan dalam
3
kelompok,
yaitu
komponen masukan
yaitu
curah
hujan,
komponen output yaitu debit
aliran dan polusi
/
sedimen,
dan
komponen
proses
yaitu
manusia, vegetasi, tanah, iklim, dan topografi. Setiap komponen dalam suatu DAS harus
dikelola
sehingga dapat
mencapai
tujuan
yang
kita
inginkan.
Tujuan
dari
pengelolaan
DAS
adalah
melakukan pengelolaan sumberdaya alam
secara rasional supaya dapat
dimanfaatkan
secara
maksimum lestari
dan
berkelanjutan sehingga
dapat
diperoleh
kondisi
tata
air
yang
baik. Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan
dan
pengelolaan sumberdaya
alam bagi
kepentingan
umat
manusia pada
saat sekarang
ini dengan masih menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam untuk generasi
yang akan datang.
DAS
ditentukan dengan
menggunakan peta
topografi
yang
dilengkapi dengan
garis-garis
kontur. Untuk maksud tersebut
dapat digunakan
peta topografi
skala 1:
50000. Garis-garis kontur dipelajari
untuk
menentukan arah
dari
limpasan permukaan.
Limpasan
berasal
dari
titik-titik
tertinggi
dan
bergerak
menuju
titik-titik yang
lebih
rendah dalam arah tegak lurus dengan garis kontur. Daerah yang dibatasi oleh garis yang
menghubungkan titik-titik
tertinggi
tersebut
adalah
DAS.
Gambar
2.4
menunjukkan
contoh bentuk DAS. Dalam gambar tersebut ditunjukkan pula penampang pada keliling
DAS. Garis
yang mengelilingi DAS
tersebut
merupakan titik-titik tertinggi. Air
hujan
|
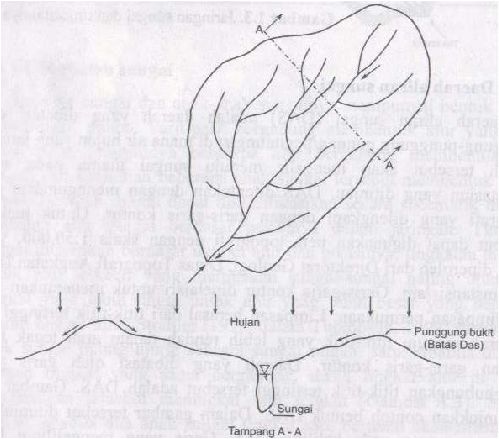 13
yang
jatuh di dalam DAS
akan
mengalir menuju sungai utama
yang ditinjau, sedang
yang jatuh di luar DAS akan mengalir ke sungai lain di sebelahnya.
Luas
DAS
diperkirakan dengan
mengukur
daerah
itu
pada peta topografi.
Luas
DAS
sangat
berpengaruh terhadap
debit
sungai. Pada
umumnya semakin
besar
DAS
semakin
besar
jumlah
limpasan
permukaan
sehingga
semakin
besar pula aliran
permukaan atau debit sungai.
(Sumber : Bambang Triatmodjo , Hidrologi Terapan, 2008)
Gambar 2.7 Daerah Aliran Sungai (DAS)
|
|
14
2.1.4
PMF dan PMP
PMF (Probable Maximum Flood) adalah Banjir maksimum yang dapat terjadi di
suatu daerah dengan durasi tertentu sedangkan PMP (Probable Maximum Precipitation)
didefinisikan sebagai
hujan
maksimum boleh
jadi
di
suatu
pos
hujan
untuk
durasi
tertentu. PMP juga merupakan besaran hujan rancangan
terbesar
yang dapat digunakan
untuk menyelamatkan bangunan hidrolik yang mengandung resiko besar.
Sasaran
utama dari analisis
hidrologi
adalah
menetapkan
nilai
rancangan
debit
sungai
pada
lokasi
tertentu dengan
tingkat resiko
yang
dapat
diterima,
sesuai dengan
tingkat
kerugian
yang
mungkin
dialami.
Untuk
merancang bangunan
dengan
resiko
bencana yang besar, khususnya jika menyangkut korban jiwa manusia, diinginkan debit
rancangan tanpa
resiko
gagal
sama
sekali.
Debit
rancangan tersebut
adalah
PMF
(Probable Maximum Flood) atau Banjir Maksimum Boleh Jadi (BMB).
Banjir Maksimum Boleh Jadi dihitung berdasarkan hasil dari perhitungan Curah
Hujan
Maksimum
Boleh
Jadi.
Jika
data
debit
maksimum
terbesar
untuk
suatu
DAS
dapat diamati dan diukur, maka perhitungan BMB menjadi sederhana. Karena data debit
yang ada di Indonesia sangat jarang dan kurang lengkap, maka perhitungan CMB perlu
dilakukan dan
selanjutnya dapat dilakukan
sintesis
untuk
menghasilkan
BMB
dengan
menggunakan
beberapa
teknik
hubungan
hujan-limpasan. Dengan
pertimbangan-
pertimbangan
demikian penting
sekali diperhitungkan kondisi
objektif
fisik
dari
DAS
bersangkutan yang akan menentukan hubungan hujan-limpasan yang perlu digunakan.
|
|
15
2.1.5
Analisa Konsistensi Data
Satu
seri
data
hujan
untuk
satu
stasiun
tertentu,
dimungkinkan sifatnya
tidak
konsisten. Data semacam ini tidak dapat langsung dianalisis, karena sebenarnya data di
dalamnnya berasal dari populasi data
yang berbeda. Ketidak konsisten data seperti ini
dapat saja terjadi karena berbagai sebab, yaitu :
•
Alat
ukur
yang
diganti
dengan
spesifikasi
yang
berbeda,
atau
alat
yang
sama
akan tetapi dipasang dengan patokan aturan yang berbeda.
•
Alat
ukur
dipindahkan
dari
tempat
semula,
akan
tetapi
secara
administrative
nama stasiun tersebut tidak diubah, misalnya karena masih dalam satu desa yang
sama.
•
Alat ukur sama, tempat tidak dipindakan, akan tetapi
lingkungan
yang berubah,
misalnya semula dipasang di
tempat
yang
ideal, akan tetapi kemudian berubah
karena ada bangunan atau pohon besar yang terlalu dekat.
Untuk menguji Konsistensi data digunakan Metode Double Mass Curve. Metode
ini
digunakan
untuk
menguji
konsistensi data
dari
satu
stasiun
curah
hujan,
dengan
menggunakan acuan data rata-rata stasiun stasiun hujan disekitarnya.
|
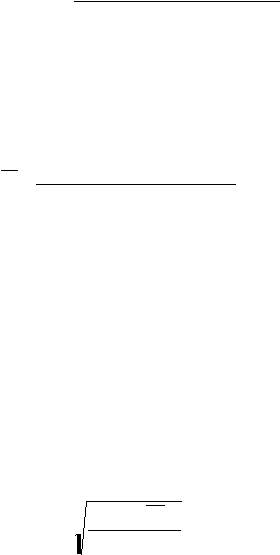 16
2
2.2
Statistik Hidrologi
2.2.1
Rata – Rata Hitung
Rata-rata hitung disebut juga rata-rata
dirumuskan sebagai berikut:
Rata - rata Hitung =
Jumlah Semua Nilai Data
Banyaknya Nilai Data
(2.1)
Perumusan
dan
perhitungan rata-rata
akan
lebih
mudah
dilakukan
dengan
memakai
simbol-simbol dari nilai data kuantitatif, X1,X2
,X3
,...,X
n
.
X
=
X
1
+
X
2
+
X
3
+
... + X
n
n
(2.2)
2.2.2
Simpangan Baku
Simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran sebaran statistik yang paling
lazim.
Singkatnya, ia
mengukur
bagaimana
nilai-nilai
data
tersebar.
Simpangan
baku
didefinisikan sebagai
akar kuadrat
varians.
Simpangan
baku
merupakan bilangan tak-
negatif,
dan
memiliki
satuan
yang
sama
dengan
data.
Rumus
Simpangan Baku
atau
Standar Deviasi adalah:
S
=
S
(
X
-
X
)
(2.3)
n
-1
|
 17
S
=
Standar Deviasi
X
=
Nilai setiap data/pengamatan dalam sample
X
=
Nilai rata-rata hitung dalam sampel
n
=
Jumlah total data/pengamatan dalam sampel
S
=
Simbol operasi Penjumlahan
2.2.3
Metode Double Mass Curve
Metode ini digunakan
untuk menghitung kepanggahan data ( konsistensi data ).
Metode
Double Mass Curve
adalah
metode
yang
membandingkan data
hujan
tahunan
kumulatif stasiun yang akan diuji (sumbu
Y)
dengan kumulatif rata –
rata stasiun
lain
(sumbu X) sesuai dengan kelompok data yang di uji (Searcy dan Hardison, 1982).
Tabel 2.1 Contoh Tabel Konsistensi Data
Rata-Rata Stasiun
Lain
Kumulatif Rata-Rata Stasiun Lain
Kumulatif Stasiun yang Diuji
...
...
...
...
...
...
|
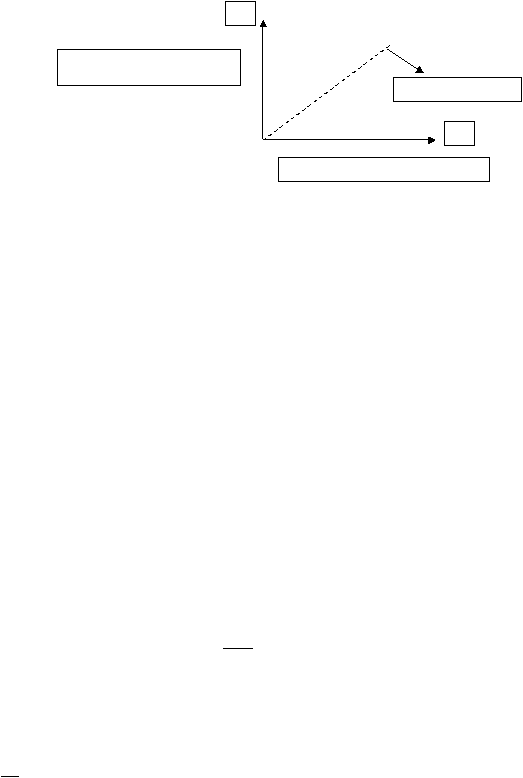 18
Y
Kumulatif Stasiun yang diuji
Garis Konsistensi
X
Kumulatif Rata – rata Stasiun lain
Gambar 2.8 Grafik Konsistensi Data
Dari garis konsistensi dapat diketahui
konsistensi data stasiun curah hujan yang
diteliti. Jika
garis yang dihasilkan berupa garis
lurus,
maka data curah
hujan
tergolong
baik.
2.2.4
Metode Hersfield
Metode
Hersfield
(1961,
1986)
merupakan prosedur
statistik
yang
digunakan
untuk
menghitung
nilai
Curah Hujan
Maksimum
Boleh Jadi.
Metode
ini digunakan
untuk kondisi dimana data Meteorologi sangat kurang atau perlu perkiraan secara tepat.
Hersfield mengembangkan
rumus
frekuensi
Chow. Rumus
Metode
Hersfield adalah
sebagai berikut:
X
cmb
=
X
n
+
K
m
s
n
(2.4)
Xc
mb
=
Curah Hujan Maksimum Boleh Jadi
X
n
=
Rata-rata dari data hujan harian maksimum tahunan
|
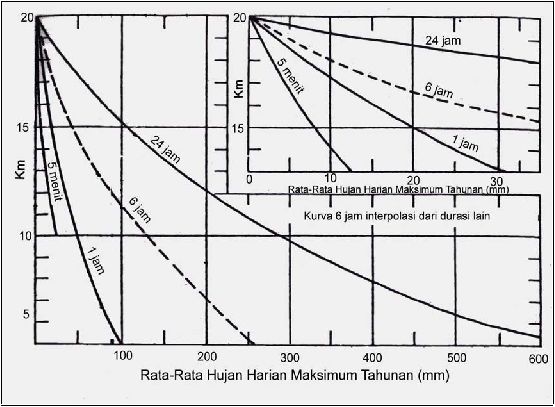 19
s
n
=
Simpangan Baku dari seri data Hujan harian maksimum tahunan
Km
=
Faktor Frekuensi
Faktor frekuensi (Km) dihitung dengan menggunakan tabel. Nilai Km
berbanding terbalik dengan
Hujan Rata-Rata
Harian Maksimum
Tahunan dan
nilainya
bervariasi untuk
berbagai
durasi
seperti
1
jam,
6
jam,
24
jam.
Hersfield
membuat
lengkung
hubungan
antara
Hujan
Rata-Rata
Harian
Maksimum
Tahunan
dengan
Km
dan durasi hujan. Melalui rumus di atas dapat dihitung nilai CMB jika seri data hujan
maksimum tahunan, rata-rata dan simpangan bakunya tersedia.
(
Sumber : Tata Cara Perhitungan Curah Hujan Maksimum BolehJadi dengan Metode Hersfield, 2003)
Gambar 2.9 Grafik Perhitungan Km
|
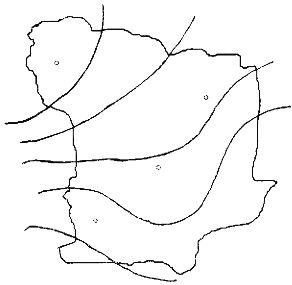 20
2.2.5
Peta Isohyet
Di Indonesia variabilitas ruang hujan sangat besar. Oleh sebab itu, peran masing–
masing
stasiun
hujan
dalam
menentukan besaran
hujan Daerah
Aliran Sungai
(DAS)
menjadi
sangat
penting.
Cara Isohyet
ini
mencoba
menerjemahkan pengertian tersebut
untuk memperoleh hujan DAS, dengan garis isohyet.
Garis
Isohyet
adalah
garis
yang
menghubungkan
titik-titik
dalam
suatu
DAS
yang mempunyai kedalaman hujan yang sama. Garis ini biasanya diperoleh dengan cara
interpolasi data antar stasiun.
(Sumber : Sri Harto BR, Hidrologi, 2000)
Gambar 2.10 Contoh Pembuatan Peta Isohyet
|
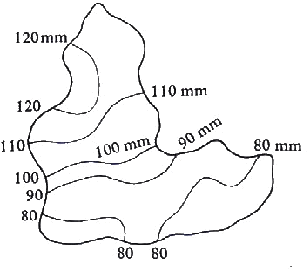 21
(Sumber : Suyono Sosrodarsono, Hidrologi untuk pengairan, 2003)
Gambar 2.11 Contoh Peta Isohyet
Peta Isohyet digambar berdasarkan skala peta
yang disesuaikan dengan
interval
curah hujan
yang diinginkan. Interval curah
hujan
yang dipakai dalam pembuatan peta
Isohyet
disesuaikan
dengan
kebutuhan
gambar
atau
sesuai
dengan data.
Interval
yang
selalu
digunakan
untuk pembuatan peta
isohyet
berkisar antara
10 –
50
mm.
Manfaat
pembuatan peta
Isohyet
adalah
untuk
melihat
tinggi
curah
hujan
pada
daerah
yang
terdapat dalam peta isohyet.
|