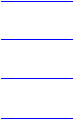 BAB 2
ANALISA DAN DATA
2.1
Sumber Data dan Informasi
Sumber data
dan
informasi
untuk
mendukung
proyek Tugas Akhir
saya diperoleh dari
beberapa
sumber yang terdiri dari:
2.1.1 Website :
•
http://www. my-curio.us
•
•
•
2.1.2
Artikel, literatur dan Buku :
•
Artikel
o
Artikel dari Bapak Prof. Drs. Yongky Safanayong tentang Baduy
o
Artikel dari Bapak Prof.Drs. Don Hasman tentang Baduy
o
Buku
Tata
Kehidupan
Masyarakat Baduy Daerah Jawa
Barat
terbitan Departemen kebudayaan dan pendidikan,1986
o
Buku
Kehidupan
masyarakat
Kanekes
terbitan
Departemen
kebudayaan dan pendidikan, tahun 1986
o
Artikel
Badui
dalam tantangan Modernitas, dari
majalah Prisma
tahun 1993
o
Dan beberapa artikel penunjang dari perpustakaan Kompas.
|
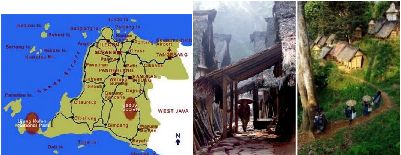 2.2 Data Pendukung
2.2.2.1 Wilayah Badui
Wilayah Kanekes secara
geografis terletak pada koordinat 6°27’27” – 6°30’0” LU dan
108°3’9” – 106°4’55” BT (Permana, 2001). Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan
Kendeng
di desa
Kanekes,
Kecamatan
Leuwidamar, Kabupaten
Lebak-Rangkasbitung, Banten,
berjarak
sekitar
40
km
dari
kota
Rangkasbitung. Wilayah
yang
merupakan
bagian
dari
Pegunungan Kendeng
dengan
ketinggian 300 – 600
m
di
atas
permukaan
laut
(DPL) tersebut
mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai
45%, yang merupakan tanah
vulkanik (di bagian
utara), tanah endapan (di bagian tengah), dan
tanah campuran (di bagian selatan). suhu rata-rata 20°C. Kadang kala suku Badui juga menyebut
dirinya
sebagai
orang
Kanekes, karena
berada
di
Desa
Kanekes.
Mereka
berada
di
wilayah
Kecamatan
Leuwidamar.
Perkampungan mereka
berada
di
sekitar
aliran
sungai Ciujung dan
Cikanekes di Pegunungan Keundeng.Atau sekitar 172 km sebelah barat
ibukota Jakarta dan 65
km
sebelah
selatan
ibu
kota
Serang.
Tidak
begitu
mengherankan, untuk
mencapai
lokasi
diperlukan waktu sekitar 9 jam, baik berkendaran dan berjalan kaki.
Lokasi dan Tempat Demografi Baduy yang berlokasi di desa Kanekes Kecamatan
Leuwidamar
Kabupaten
Rangkasbitung
Banten
terdiri
dari kampung
Gajebo,
Cikeusik,
|
|
Cibeo,dan Cikertawana.dan terbagi atas abaduy
luar dan baduy dalam.Daerah yang berluas 138
ha,
terdiri
atas
117 kk yang
menempati 99 rumah
yang
dinamakan Culah
Nyanda atau
rumah
panggung, sedangkan rumah kokolot atau duku dinamakan Dangka, yang menghadap keselatan.
Masyarakat suku Baduy yang berpenduduk kurang lebih 10 ribu jiwa ini tinggal di wilayah yang
berbukit-bukit, dan berhutan-hutan, dengan
memilki lembah
yang curam sedang, sampai
curam
sekali.
Berdasarkan
hasil
pengukuran
langsung
di
lapangan
wilayah
-
wilayah
pemukiman
Baduy
rata-rata
terletak
pada
ketinggian
250
m
diatas
permukaan laut,
dengan
wilayah
pemukiman di daerah yang cukup rendah 150 m diatas permukaan air laut dan pemukiman yang
cukup
tinggi
pada ketinggian
400
m
diatas permukaaan
laut. Wilayah
Baduy
itu
berdasarkan
lokasi
geografinya terletak
pada
60
27'
27?
-
60
30'
LU
dan
1080
3'
9?
-
1060
4'
55?
BT.
Wilayahnya berbukit - bukit dengan rata -rata terlelak pada ketinggian 250m diatas permukaan
laut.
2.2.2.2 Bahasa
Bahasa
yang
mereka
gunakan
adalah
Bahasa
Sunda
dialek
Sunda–Banten. Untuk
berkomunikasi dengan penduduk luar
mereka lancar menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun
mereka
tidak
mendapatkan pengetahuan
tersebut
dari
sekolah.
Orang
Kanekes
'dalam'
tidak
mengenal
budaya
tulis,
sehingga
adat
istiadat,
kepercayaan/agama, dan
cerita
nenek
moyang
hanya
tersimpan di
dalam
tuturan
lisan
saja.
untuk
terus
mempelajari Bahasa
nasional
yakni
bahasa Indonesia. Terbukti, tidak sedikit masyarakat Baduy yang dapat berbahasa Indonesia.
|
 2.2.2.3 Asal-Usul
Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara
Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal
usul tersebut sering pula
dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka,
Adam
dan
keturunannya, termasuk
warga
Kanekes
mempunyai
tugas
bertapa
atau
asketik
(mandita) untuk
menjaga
harmoni dunia. Pendapat
mengenai asal-usul orang Kanekes berbeda
dengan
pendapat
para
ahli
sejarah,
yang
mendasarkan pendapatnya
dengan cara
sintesis dari
beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta
cerita
rakyat
mengenai
'Tatar
Sunda'
yang
cukup
minim keberadaannya.
Masyarakat Kanekes
dikaitkan dengan
Kerajaan Sunda
yang
sebelum
keruntuhannya pada
abad
ke-16
berpusat di
Pakuan
Pajajaran
(sekitar
Bogor
sekarang).
Sebelum
berdirinya
Kesultanan
Banten,
wilayah
ujung barat pulau Jawa
ini
merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda. Banten
merupakan
pelabuhan dagang
yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan
ramai
digunakan
untuk
pengangkutan hasil
bumi
dari
wilayah
pedalaman.
Dengan
demikian
penguasa wilayah
tersebut,
yang
disebut sebagai
Pangeran
Pucuk
Umum
menganggap
bahwa
kelestarian
sungai
perlu
dipertahankan. Untuk
itu diperintahkanlah
sepasukan tentara kerajaan
yang
sangat
terlatih
untuk
menjaga
dan
mengelola kawasan
berhutan
lebat
dan
berbukit
di
wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut
|
|
tampaknya
menjadi
cikal
bakal
Masyarakat Baduy
yang
sampai
sekarang
masih
mendiami
wilayah
hulu
Sungai
Ciujung
di
Gunung
Kendeng
tersebut
(Adimihardja, 2000).
Perbedaan
pendapat tersebut
membawa kepada dugaan bahwa pada masa
yang
lalu,
identitas dan
kesejarahan mereka sengaja ditutup,
yang
mungkin adalah
untuk melindungi komunitas Baduy
sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran.
Van
Tricht,
seorang
dokter
yang pernah
melakukan riset
kesehatan
pada
tahun
1928,
menyangkal teori tersebut. Menurut dia, orang Baduy adalah penduduk asli daerah tersebut yang
mempunyai daya tolak kuat
terhadap pengaruh luar
(Garna, 1993b: 146). Orang
Baduy sendiri
pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-oraang pelarian dari Pajajaran, ibu
kota Kerajaan Sunda. Menurut Danasasmita dan Djatisunda (1986: 4-5) orang Baduy merupakan
penduduk
setempat
yang
dijadikan
mandala' (kawasan suci)
secara
resmi
oleh
raja,
karena
penduduknya berkewajiban memelihara
kabuyutan
(tempat
pemujaan
leluhur
atau
nenek
moyang), bukan agama Hindu atau Budha. Kebuyutan di daerah ini dikenal dengan kabuyutan
Jati Sunda atau 'Sunda Asli' atau Sunda Wiwitan (wiwitann=asli, asal, pokok, jati). Oleh karena
itulah agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan. Raja yang menjadikan wilayah Baduy
sebagai
mandala adalah
Rakeyan
Darmasiksa.
Ada
pula
yang
mempercayai
awal
kebedaraan
suku
Badui,
merupakan
sisa-sisa
pasukan
Pajajaran
yang
setia pada
Prabu
Siliwangi.
Mereka
melarikan diri dari kejaran pasukan Sultan Banten dan Cirebon. Namun pada akhirnya,
mereka
dilindungi
Kesultanan
Banten
dan
diberi otonomi khusus.
(zal/ken) Mengenai
asal
usul
orang
Baduy, jawaban yang akan diperoleh adalah mereka keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari
tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal
usul tersebut sering pula dihubungkan dengan
Nabi
Adam
sebagai
nenek
moyang
pertama.
Menurut
kepercayaan mereka,
Adam
dan
keturunannya, termasuk warga Baduy mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita)
untuk
|
 menjaga
harmoni dunia. Mereka
juga beranggapan bahwa suku
Baduy merupakan peradaban
masyarakat yang pertama kali ada di dunia.
2.2.2.4 Kepercayaan
Kepercayaan masyarakat
Kanekes
yang
disebut sebagai
Sunda
Wiwitan
berakar
pada
pemujaan kepada arwah
nenek
moyang
(animisme)
yang pada
perkembangan selanjutnya juga
dipengaruhi oleh agama Budha, Hindu, dan Islam. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan
adanya
pikukuh
atau
ketentuan
adat
mutlak
yang
dianut
dalam
kehidupan sehari-hari orang
Kanekes (Garna, 1993). Isi terpenting dari 'pikukuh' (kepatuhan) Kanekes tersebut adalah konsep
"tanpa perubahan apapun", atau perubahan sesedikit mungkin:Objek kepercayaan terpenting bagi
masyarakat
Kanekes
adalah
Arca
Domas,
yang
lokasinya
dirahasiakan dan
dianggap
paling
sakral. Orang
Kanekes mengunjungi lokasi tersebut
untuk
melakukan pemujaan setahun sekali
pada
bulan
Kalima,
yang
pada
tahun
2003
bertepatan dengan
bulan
Juli.
Hanya
puun
yang
merupakan ketua adat tertinggi dan beberapa anggota
masyarakat terpilih saja
yang
mengikuti
rombongan pemujaan tersebut. Di
kompleks
Arca Domas
tersebut terdapat batu lumpang
yang
menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam
keadaan penuh air yang jernih,
maka bagi masyarakat Kanekes itu
merupakan pertanda bahwa
hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila
batu
lumpang kering atau berair keruh,
maka
merupakan pertanda kegagalan panen (Permana,
|
 2003a). Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang
dianut
masyarakat adat
Kanekes
ini
mencerminkan kepercayaan keagamaan
masyarakat Sunda
secara
umum
sebelum
masuknya
Islam.
Masyarakat Baduy
sangat
taat
pada
pimpinan
yang
tertinggi
yang
disebut
Puun.
Puun
ini
bertugas
sebagai
pengendali hukum
adat
dan
tatanan
kehidupan
masyarakat
yang
menganut
ajaran
Sunda
Wiwitan
peninggalan nenek
moyangnya.
Suku
Baduy yang
merupakan suku
tradisional di Provinsi
Banten
hampir mayoritasnya
mengakui kepercayaan sunda
wiwitan.Yang mana kepercayaan
ini
meyakini akan
danya Allah
sebagai
“Guriang Mangtua” atau disebut pencipta alam semesta dan
melaksanakan kehidupan
sesuai ajaran Nabi Adam sebagai leluhur yang
mewarisi kepercayaan turunan ini. Kepercayaan
sunda
wiwitan
berorientasi
pada
bagaimana
menjalani
kehidupan
yang
mengandung
ibadah
dalam berperilaku, pola kehidupan sehari-hari,langkah dan
ucapan, dengan
melalui hidup
yang
mengagungkan
kesederhanaan
(tidak
bermewah-mewah) seperti
tidak
mengunakan
listrik,t
embok, mobil dll.
2.2.2.5 Kelompok-kelompok Baduy
Masyarakat Kanekes
secara
umum
terbagi
menjadi
tiga
kelompok
yaitu
tangtu,
panamping, dan
dangka
(Permana, 2001).
Kelompok
tangtu
adalah
kelompok
yang
dikenal
sebagai
Baduy
Dalam,
yang
paling
ketat
mengikuti
adat,
yaitu
warga
yang
tinggal
di tiga
|
 kampung: Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik). Ciri khas Orang Baduy Dalam adalah pakaiannya
berwarna putih
alami
dan
biru
tua
serta
memakai
ikat
kepala
putih.
Kelompok
masyarakat
panamping adalah mereka yang dikenal sebagai Baduy Luar, yang tinggal di berbagai kampung
yang
tersebar
mengelilingi wilayah
Baduy
Dalam,
seperti
Cikadu,
Kaduketuk,
Kadukolot,
Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian
dan
ikat
kepala
berwarna hitam.
Apabila Baduy
Dalam
dan
Baduy
Luar
tinggal
di
wilayah
Kanekes,
maka
"Baduy Dangka"
tinggal di
luar wilayah
Kanekes,
dan
pada saat
ini
tinggal
2
kampung
yang
tersisa, yaitu
Padawaras (Cibengkung) dan
Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung
Dangka
tersebut
berfungsi
sebagai
semacam
buffer
zone
atas
pengaruh
dari
luar
(Permana,
2001).
Sementara
di
bagian selatannya
dihuni
masyarakat Badui
Dalam
atau
Urang
Tangtu.
Diperkirakan
mereka
berjumlah 800an
orang
yang tersebar
di
Kampung
Cikeusik,
Cibeo dan
Cikartawana.Kedua kelompok ini memang memiliki ciri yang beda. Bila Badui Dalam menyebut
Badui
Luar
dengan sebutan
Urang
Kaluaran, sebaliknya
Badui
Luar
menyebut
Badui Dalam
dengan panggilan Urang Girang atau Urang Kejeroan.
2.2.2.6 Pemerintahan
Masyarakat
Kanekes
mengenal
dua
sistem
pemerintahan, yaitu sistem
nasional,
yang
mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
sistem adat
yang
mengikuti adat
|
|
istiadat
yang
dipercaya
masyarakat. Kedua
sistem
tersebut
digabung
atau
diakulturasikan
sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perbenturan. Secara nasional penduduk Kanekes dipimpin
oleh
kepala
desa yang
disebut sebagai
jaro
pamarentah,
yang ada di bawah
camat,
sedangkan
secara adat
tunduk
pada
pimpinan adat
Kanekes
yang
tertinggi, yaitu
"puun".
Pemimpin
adat
tertinggi
dalam
masyarakat Kanekes adalah
"puun"
yang ada di
tiga
kampung
tangtu.
Jabatan
tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat
juga
kerabat
lainnya.
Jangka
waktu
jabatan
puun
tidak
ditentukan,
hanya
berdasarkan pada
kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut.
Pelaksana
sehari-hari
pemerintahan adat
kapuunan
(kepuunan)
dilaksanakan oleh
jaro,
yang dibagi ke
dalam empat jabatan,
yaitu jaro
tangtu,
jaro
dangka, jaro
tanggungan, dan jaro
pamarentah. Jaro tangtu bertanggung jawab pada pelaksanaan hukum adat pada warga tangtu dan
berbagai
macam
urusan
lainnya.
Jaro
dangka
bertugas
menjaga,
mengurus,
dan
memelihara
tanah
titipan
leluhur
yang ada di dalam
dan
di
luar
Kanekes. Jaro dangka
berjumlah 9 orang,
yang apabila ditambah dengan 3 orang jaro tangtu disebut sebagai jaro duabelas. Pimpinan dari
jaro duabelas ini disebut sebagai jaro tanggungan. Adapun jaro pamarentah secara adat bertugas
sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah
nasional,
yang dalam
tugasnya dibantu oleh pangiwa, carik, dan kokolot lembur atau tetua kampung. Setiap kampung
di
Badui
Dalam
dipimpin
oleh
seorang
Puun,
yang
tidak
boleh
meninggalkan
kampungnya.
Pucuk pimpinan adat dipimpin oleh Puun Tri Tunggal, yaitu Puun Sadi di Kampung Cikeusik,
Puun Janteu di Kampung Cibeo dan Puun Kiteu di Cikartawana. Sedangkan wakilnya pimpinan
adat
ini
disebut
Jaro
Tangtu
yang
berfungsi
sebagai
juru
bicara
dengan
pemerintahan desa,
pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Di Badui Luar sendiri mengenal sistem pemerintahan
|
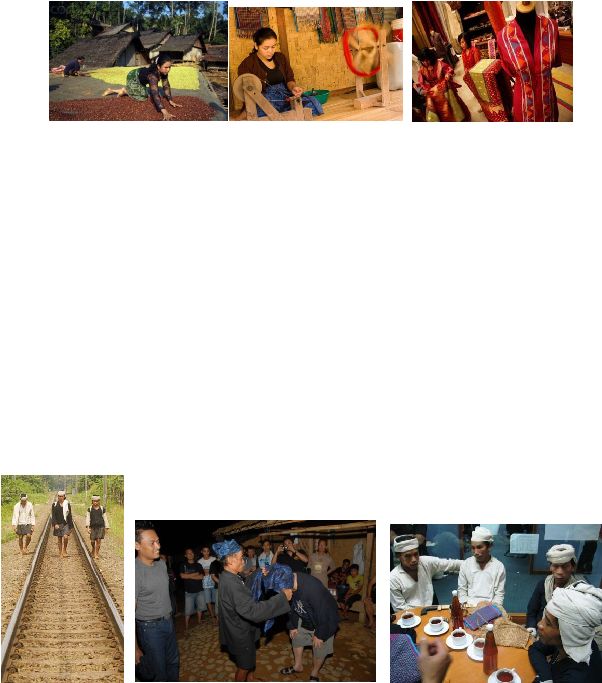 kepala desa
yang
disebut Jaro
Pamerentah
yang
dibantu
Jaro
Tanggungan,
Tanggungan
dan
Baris Kokolot.
2.2.2.7 Mata Pencaharian
Sebagaimana yang
telah
terjadi
selama
ratusan
tahun,
maka
mata
pencaharian
utama
masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain itu mereka juga mendapatkan penghasilan
tambahan dari
menjual
buah-buahan
yang
mereka
dapatkan di
hutan
seperti
durian dan asam
keranji, serta madu hutan. Suku Badui biasa bercocok tanam dan berladang. Selain itu membuat
kerajinan seperti
Koja
dan
Jarog (tas
yang
terbuat
dari
kulit kayu),
tenunan berupa
selendang,
baju, celana, ikat kepala, sarung,
golok, parang dan berburu. Mereka taat pada tradisi lama dan
hukum adat.
2.2.2.8 Interaksi dengan masyarakat luar
|
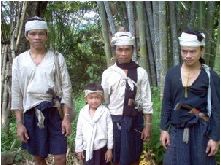 Pada saat ini orang luar yang mengunjungi wilayah Kanekes semakin meningkat sampai
dengan ratusan orang per kali kunjungan, biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa,
dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Mereka menerima para pengunjung tersebut, bahkan
untuk
menginap satu
malam, dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat-istiadat
yang
berlaku di sana.
Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di
wilayah Baduy Dalam,
tidak menggunakan sabun atau odol di sungai. Namun demikian, wilayah Kanekes tetap
terlarang bagi orang asing (non-WNI).
Beberapa wartawan asing yang
mencoba
masuk sampai
sekarang selalu ditolak masuk. Pada saat pekerjaan di
ladang tidak terlalu banyak, orang Baduy
juga senang berkelana ke kota besar sekitar
wilayah
mereka dengan syarat
harus berjalan kaki.
Pada
umumnya
mereka
pergi
dalam
rombongan kecil
yang
terdiri
dari
3
sampai
5
orang,
berkunjung ke
rumah
kenalan
yang
pernah datang ke
Baduy sambil
menjual
madu
dan
hasil
kerajinan
tangan.
Dalam
kunjungan
tersebut
biasanya
mereka
mendapatkan
tambahan
uang
untuk mencukupi kebutuhan hidup.
2.2.2.9 Busana Tradisional Suku Baduy
Ciri khas suku
Baduy
yang tinggal
di pegunungan Kendeng, desa Kanekes, kecamatan
Leuwidamar, Lebak, Banten Selatan adalah masih kokohnya tradisi yang diwariskan oleh
karuhun mereka. Salah satu tradisi yang
masih bertahan adalah menenun dan cara berbusana.
|
|
Oleh karena
itu,
ada
yang
beranggapan bahwa busana
suku Baduy
saat
ini
merupakan bentuk
busana yang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat pada masa silam. Baduy Dalam, untuk laki-
laki
memakai
baju
lengan
panjang
yang
disebut
jamang
sangsang,
karena
cara
memakainya
hanya
disangsangkan atau
dilekatkan
di
badan.
Desain baju
sangsang
hanya
dilobangi/dicoak
pada
bagian
leher
sampai
bagian
dada
saja.
Potongannya tidak
memakai
kerah,
tidak
pakai
kancing dan tidak memakai kantong baju. Warna busana mereka
umunnya adalah serba putih.
Pembuatannya hanya menggunakan tangan dan tidak boleh dijahit dengan mesin. Bahan
dasarnya pun harus terbuat dari benang kapas asli yang ditenun.Bagian bawahnya memakai kain
serupa sarung warna biru kehitaman, yang hanya dililitkan pada bagian pinggang. Agar kuat dan
tidak
melorot, sarung tadi diikat
dengan
selembar kain. Mereka
tidak
memakai celana,
karena
pakaian tersebut dianggap barang tabu.
Selain
baju
dan
kain
sarung
yang
dililitkan tadi,
kelengkapan busana
pada
bagian
kepala
menggunakan ikat
kepala berwarna putih pula.
Ikat
kepala ini berfungsi sebagai penutup rambut mereka yang panjang. Kemudian dipadukan dengan
selendang atau hasduk
yang melingkar di
lehernya. Pakaian Baduy Dalam yang bercorak serba
putih
polos
itu
dapat
mengandung makna
bahwa
kehidupan
mereka
masih
suci
dan
belum
terpengaruh budaya luar. Bagi suku Baduy Luar, busana yang mereka pakai adalah baju kampret
berwarna
hitam.
Ikat kepalanya juga berwarna
biru
tua dengan
corak
batik.
Desain
bajunya
terbelah
dua
sampai
ke
bawah,
seperti
baju
yang
biasa
dipakai
khalayak ramai.
Sedangkan
potongan
bajunya
mengunakan kantong,
kancing
dan
bahan
dasarnya
tidak
diharuskan
dari
benang kapas murni. Cara berpakaian suku Baduy Panamping memamg ada sedikit kelonggaran
bila
dibandingkan
dengan
Baduy
Dalam.
Melihat
warna,
model
maupun
corak busana
Baduy
Luar, menunjukan bahwa kehidupan mereka sudah
terpengaruh oleh budaya
luar. Kelengkapan
busana
bagi
kalangan
kali-laki
Baduy
adalah
amat penting.
Rasanya busana
laki-laki
belum
|
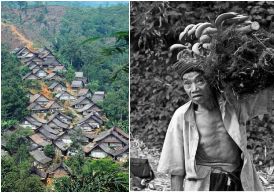 lengkap apabila tidak memakai senjata. Bagi Baduy Dalam maupun Luar kalau bepergian selalu
membawa
senjata
berupa
golok
yang
diselipkan
di
balik
pinggangnya.
Pakaian
ini
biasanya
masih dilengkapi pula dengan tas kain atau tas koja yang dicangklek (disandang) di pundaknya.
Sedangkan, busana yang dipakai di kalangan wanita Baduy, baik Kajeroan maupun Panamping
tidak
menampakkan
perbedaan
yang
mencolok. Model,
potongan dan
warna
pakaian,
kecuali
baju
adalah
sama. Mereka
mengenakan
busana
semacam
sarung
warna biru
kehitam-hitaman
dari
tumit
sampai
dada.
Busana
seperti
ini
biasanya
dikenakan
untuk
pakaian
sehari-hari
di
rumah. Bagi wanita yang sudah menikah, biasanya
membiarkan dadanya
terbuka secara bebas,
sedangkan bagi
para
gadis bagian dadanya
harus
tertutup.
Untuk
pakain
bepergian, biasanya
wanita Baduy memakai kebaya, kain tenunan sarung berwarna biru kehitam-hitaman,
karembong, kain ikat pinggang dan selendang. Warna baju untuk Baduy Dalam adalah putih dan
bahan dasarnya dibuat dari benang kapas yang ditenun sendiri.
2.2.2.10 Pertanian Suku Baduy
Pola
Pertanian
Tradisional
Masyarakat
Baduy
Sistem
perladangan berpindah
atau
perladangan daur
ulang telah
dipraktekkan selama
berabad-abad dan
merupakan bentuk
pertanian yang paling awal di wilayah tropika dan subtropika. Sistem pertanian dilakukan adalah
tanaman pangan dalam waktu dekat (pada umumnya 2 – 3 tahun), dan kemudian diikuti dengan
|
|
fase regenerasi atau masa berakhir yang lebih lama (pada umumnya 10 – 20 tahun). Pembukaan
hutan
biasanya
menggunakan
alat
sederhana,
dilakukan
secara
tradisional,
dan
menggunakan
cara
tebang
bakar (Nair,
1993).Pada
waktu
hutan
dibuka
maka
tumbuhan alam
yang
berguna
biasanya
dibiarkan
atau
sedikit
disiangi
dan
dimanfaatkan
hasilnya.
Lama
waktu
perladangan
dan
masa
bera
atau
masa
lahan
diistirahatkan adalah
sangat bervariasi,
dan
lama
masa
bera
merupakan faktor kritis bagi regenerasi kesuburan tanah, keberlanjutan, dan hasil pertanian yang
didapatkan. Regenerasi kesuburan tersebut melibatkan tumbuh kembalinya tanaman tahunan atau
tumbuhan
asli.
Masyarakat Baduy
yang
masih
mengikuti
pola
pertanian
tradisional
zaman
Kerajaan Sunda
(Pajajaran), telah
mempraktekkan sistem perladangan berpindah tersebut sejak
kurang
lebih
600
tahun
yang
lampau.
Mereka
membuka huma
untuk
ditanami padi
selama
1
sampai
2
tahun,
dan
kemudian
ketika
hasil
panen
telah
menurun
akan
meninggalkan huma
tersebut dan
membuka kembali
huma
baru
dari bagian
hutan
alam
yang
mereka
peruntukkan
bagi
kepentingan
tersebut.
Huma
yang ditinggalkan
pada
suatu
saat
akan
diolah
kembali dan
periode
masa
bera tersebut pada awalnya 7
sampai 10
tahun.Namun demikian, karena wilayah
Baduy yang
semakin sempit ditambah dengan pertambahan penduduk, maka
lahan
huma
yang
tersedia juga semakin sempit sehingga dari
tahun ke tahun masa bera
ladang
menjadi semakin
pendek, yaitu 3 sampai 5 tahun. Hal tersebut merupakan indikator terjadinya penurunan kualitas
lingkungan dan
daya dukung
secara
ekologis.
Pada
saat penelitian dilakukan,
wilayah
Baduy
yang tersisa adalah 5.101
hektar, dengan pembagian peruntukan tanah pertanian 2.585 ha atau
51% (709 ha atau 14% ditanami dan sisanya bera yaitu 1.876,25 ha atau 37%); lahan pemukiman
24,5 ha atau 0,48%; hutan tetap atau
hutan
lindung yang tak boleh digarap 2.492
ha atau 49%
(Purnomohadi, dalam Permana, 2001). Luas tanah yang digunakan untuk bertani dan luas tanah
bera
bervariasi
dari tahun
ke tahun.
Sebagaimana
masyarakat
agraris
lainnya
di Indonesia,
|
|
masyarakat
Baduy
mempunyai
jadwal
pertanian
yang
tertentu
setiap
tahunnya
dan
didasarkan
kepada
letak benda astronomi
tertentu, seperti kemunculan bintang tertentu dan
letak
matahari.
Adapun patokan bintang
yang digunakan adalah
bintang
kidang
(Waluku atau
rasi Orion) dan
bintang Kartika atau bintang Gumarang. Dalam prakteknya bintang kidang lebih banyak dipakai
karena
lebih
jelas
terlihat
(Permana, 2001).
Kemunculan bintang
kidang
tersebut
menandai
dimulainya proses berladang karena
masyarakat mulai bersiap-siap turun
ke
ladang
dan
mulai
mengolah
lahan
pertanian.
Dalam
ungkapan
mereka
disebutkan: “Mun
matapoe
geus
dengek
ngaler,
lantaran
jagad
urang
geus
mimiti
tiis,
tah
dimimitian ti
wayah
eta
kakara
urang
nanggalkeun kidang, tanggal kidang mah laju turun kujang”. (Terjemahan: “Jika
matahari telah
condong ke
utara,
ketika
bumi
kita
telah
mulai
dingin,
mulai
saat
itu
baru
kita
mengamati
penanggalan dengan
munculnya
bintang
kidang,
waktu
muncul
bintang
kidang
kita
mulai
menggunakan alat
pertanian
(kujang)”
(Permana,
2001)Adapun
alat
pertanian
yang
mereka
gunakan adalah terbatas sekali, dan prinsip pengolahan lahan mereka adalah sesedikit
mungkin
mengganggu tanah.
Mereka
membuka
huma
dengan
bedog
atau
parang
panjang
dan
kujang
(parang pendek atau pisau), dan menanam benih padi dengan cara menugal atau melubangi tanah
dengan
sepotong
kayu.
Pengolahan
lahan
dengan
cara
mencangkul atau
membajak
adalah
terlarang.
Kalender
sebagai
penanda
waktu
pada
masyarakat Baduy
adalah
kalender
yang
berpatokan pada perputaran bulan
(komariah). Satu
tahun dibagi
menjadi
12
bulan. Menurut
Narja, seorang penduduk kampung Cibeo,
urutan bulan-bulan tersebut adalah sebagai berikut:
Kapat, Kalima, Kanem, Katujuh, Kadalapan, Kasalapan, Kasapuluh, Hapit Lemah, Hapit Kayu,
Kasa,
Karo, Katiga.
Urutan
bulan
tersebut
juga
mengikuti
tahapan
dalam
proses perladangan.
Bulan Kasa, Karo,
dan
Katiga,
yang
merupakan bulan-bulan akhir
masa
berladang dan
masa
|
 panen
disebut pula
masa
Kawalu
yang dipenuhi
dengan
berbagai
upacara
adat dan berbagai
bentuk larangan. Pada masa tersebut tamu atau pengunjung dari luar biasanya tidak diterima.
2.2.2.11 Upacara-upacara Adat Suku Baduy
Ada beberapa
kegiatan
yang
dilakukan
oleh
masyarakat
Baduy
menurut
kepercayaan
sunda wiwitan:
•
Upacara Kawalu yaitu upacara yang dilakukan
dalam
rangka menyambut
bulan
kawalu
yang dianggap suci dimana pada bulan kawalu masyarakat baduy
melaksanakan ibadah puasa selama 3 bulan yaitu bulan Kasa,Karo, dan Katiga.
•
Upacara
ngalaksa yaitu upacara besar
yang dilakukan sebagain uacapan syukur atas
terlewatinya bulan-bulan kawalu, setelah
melaksanakan puasa
selama
3
bulan.
Ngalaksa atau yang bsering disebut lebaran.
•
Seba yaitu berkunjung ke pemerintahan daerah atau pusat yang bertujuan merapatkan
tali
silaturahmi
antara masyarakat baduy
dengan pemerintah, dan
merupakan bentuk
penghargaan dari masyarakat baduy.
•
Upacara menanam padi dilakukan
dengan
diiringi
angklung
buhun sebagai
penghormatan kepada dewi sri lambing kemakmuran.
|
 Perkawinan, dilakukan berdasarkan perjodohan dan dilakukan oleh
dukun atau
kokolot
menurut
lembaga
adat
(Tangkesan)
sedangkan
Naib
sebagai
penghulunya. Adapun
mengenai
mahar atau seserahan yakni sirih, uang semampunya, dan kain poleng.
Dalam
melaksanakan kegiatan
sehari-hari
tentunya
masyarakat
baduy
disesuaikan
dengan
penanggalan:
Bulan
Kasa,Bulan
Karo,Bulan
Katilu,Bulan
Sapar,Bulan
Kalima,Bulan Kaanem
Bulan
Kapitu,Bulan
Kadalapan,Bulan Kasalapan,bulan
Kasapuluh,Bulan Hapid
Lemah,Bulan
Hapid Kayu Seperti yang telah diuraikan diatas, apabila ada
masyarakat baduy yang melanggar
asalah satu
pantangan
maka
akan
dikenai
hukuman
berupa
diasingkan
ke
hulu atau
dipenjara
oleh pihak polisi byang berwajib.
2.2.2.12 Kesenian dan Kerajinan Suku Baduy
Dalam melaksanakan
upacara
tertentu,
masyarakat Baduy
menggunakan kesenian
untuk
memeriahkannya.
Adapun keseniannya
yaitu: Seni Musi (Lagu daerah yaitu Cikarileu dan
Kidung ( pantun) yang digunakan dalam acara pernikahan). Alat musik (Angklung Buhun dalam
acara
menanan
padi
dan
alat
musik
kecapi)Seni Ukir
Batik.
Bicara
soal
tembakau,
ternyata
tembakau adalah salah satu hasil utama mereka.
|
|
2.3
Spesifikasi Buku
Buku
ini
memiliki
pembahasan utama
mengenai
potret
kehidupan,
adat
istiadat
dan
kebudayaan
orang
Baduy
yang
mampu
diselesaikan secara
baik.
Dan
berikut
spesifikasi dari
buku “ BADUY Jejak Terasing Prajurit Padjajaran”
* Penulis
:
Siti Astari
* Desainer
:
Siti Astari
* Penerbit
:
PT Gramedia
* Tebal
:
128 halaman
* Harga
:
Rp 65.000,-
* Ukuran
:
20 x 20 cm
2.3.1 Struktur Buku :
* Prakata
* Daftar Isi
* Baduy
* Asal-Usul
* Tatanan Masyarakat
* Pemerintahan
* Upacara Adat
|
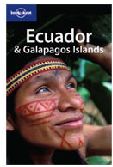 * Arsitektur
* Ekonomi
* Masa Kini
* Penutup
* Daftar Pustaka
2.3.2
Buku Pembanding
Penulis : Wendy Schivour
Penerbit: Lonely Planet
Tebal : 112 Halaman
Harga : Rp 263.000,-
|
|
2.4
Data Penyelenggara
2.4.1
PT Gramedia
Toko Buku Gramedia didirikan 02 Februari 1970 oleh P.K. Ojong, yang juga merupakan
pendiri
KKG,
dengan
misi
turut
serta
menyebarkan produk
pendidikan
dan
informasi,
demi
tercapainya
cita-cita
bersama
mencerdaskan kehidupan
bangsa,
menuju
masyarakat
baru
Indonesia
yang
berkehidupan
Pancasila.
MISI:
Ikut
serta
dalam
upaya
mencerdaskan bangsa
dengan
menyebarluaskan
penegtahuan
plus
informasi
melalui
berbagai
sarana
usaha
ritel
dan
distribusi
buku
,
alat
sekolah
dan
kantor
serta produk
multimedia,
ditandai
dengan pelayanan
unggul, manajemen proaktif dan perilaku bisnis yang sehat.Tak bisa dipungkiri bahwa distribusi
merupakan mata rantai yang lemah dalam dunia bisnis di Indonesia. Penerbit dan percetakan saja
tidaklah cukup untuk dapat mendistribusikan produk secara merata ke seluruh pelosok tanah air.
Itulah sebabnya Kelompok Kompas - Gramedia (KKG)
mendirikan jaringan toko buku, dengan
maksud memperkuat penyebaran produk, tanpa berkeinginan untuk lepas dari jaringan distribusi
yang
ada.Departemen
Impor
bertugas
khusus
untuk
mengelola
dan
mengembangkan
jalinan
kerja sama dengan penerbit luar negeri yang kini berjumlah lebih dari 250 penerbit. Penerbit luar
negeri
yang
aktif
menjalin kerja
sama:
Amerika Serikat:
Simon
&
Schuster, Prentice
Hall,
McGraw
Hill,
Maxwell
Macmillan, Addison
Wesley,
John
Wiley,
Harper
Collins,
Bantam,
Random House,
Baker &
Taylor,
dan
lain-lain.
Eropa:
Penguin, Cambridge, Oxford,
Elsevier,
Grossohaus,
Hachette, Longman,
MacMillan
UK,
dan
lain-lain. Asia:
Kondasha,
Japan
Publication, Toppan, Canfonian, Asiapac, UBSPD, S. Chand, S.S. Mubaruk, Pan Pacific, Mighty
Mind, Federal Publication, dan lain-lain.
|
|
2.5
Target Audience
* Umur
:
Dewasa, 25-45 tahun.
* Gender
:
Pria/Wanita.
* Tingkat Ekonomi
:
Kalangan kelas menegah ke atas.
* Psikografik
:
Pencinta Alam, Para Peneliti, dan para Budayawan.
2.6
Analisa
2.6.1 Strength
•
Dapat menjadi buku pengetahuan baru tentang suku dan kebudayaan yang ada di
Indonesia
2.6.2 Weakness
•
Pembuatan buku tersebut harus disesuaikan dengan daya beli target konsumen
2.6.3 Oppourtunity
•
Belum ada buku yang mengangkat topik tentang suku pendalaman Baduy
•
Banyaknya petualang dan
pelancong
yang
berminat
akan
keasrian
budaya dan
tradisi yang ada di Baduy
2.6.4 Threat
Sudah banyak buku-buku dipasaran
tentang budaya dan suku-suku yang ada di
Indonesia. Contohnya buku tentang suku Asmat.
|