|
BAB 2
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1
Transportasi
2.1.1
Pengertian Transportasi
Menurut
Wikipedia
Indonesia,
transportasi
adalah pemindahan manusia
atau
barang
dari
satu
tempat
ke
tempat
lainnya
dengan
menggunakan
sebuah
wahana
yang
digerakkan oleh manusia atau
mesin. Transportasi digunakan
untuk
memudahkan manusia
dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
Di negara maju, mereka biasanya menggunakan
kereta bawah tanah (
subway)
dan taksi. Penduduk di
negara maju jarang yang mempunyai
kendaraan
pribadi
karena mereka sebagian besar
menggunakan angkutan
umum
sebagai
transportasi
mereka. Transportasi
sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara.
Transportasi
udara
merupakan
transportasi yang
membutuhkan
banyak uang
untuk
memakainya.
Selain
karena
memiliki teknologi
yang
lebih
canggih,
transportasi
udara
merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.
Menurut
Abbas,
(2003,
p6),
transportasi
sebagai dasar
untuk
pembangunan
ekonomi
dan perkembangan
masyarakat serta
pertumbuhan
industrialisasi. Dengan
adanya
transportasi
menyebabkan,
adanya
spesialisasi
atau
pembagian
pekerjaan
menurut
keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.
Pertumbuhan ekonomi
suatu
negara
atau
bangsa
tergantung
pada
tersedianya
pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.
Dalam transportasi kita melihat dua kategori yaitu :
1. Pemindahan
bahan-bahan
dan
hasil-hasil
produksi
dengan
menggunakan
alat angkut.
2. Mengangkut
penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.
6
|
|
7
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa definisi transportasi adalah kegiatan
pemindahan barang
(muatan)
dan
penumpang
dari suatu tempat
ke
tempat
lain.
Dalam
transportasi terlihat ada dua unsur yang
terpenting yaitu :
a. Pemindahan atau pergerakan (movement)
b.
Secara
fisik mengubah
tempat
dari
barang
(komoditi)
dan
penumpang
ke
tempat lain
2.1.2
Pembagian Fungsi Transportasi
Di dalam mempelajari transportasi dapat kita golongkan atas dua bagian:
1. Angkutan penumpang
Untuk
pengangkutan
penumpang
digunakan
mobil
atau
kendaraan
pribadi
dan alat angkut lainnya.
2.
Selain
mobil pribadi
yang
digunakan
untuk
mengangkut
penumpang,
digunakan
pula
kendaraan
untuk
angkutan
umum seperti,
bus,
pesawat
udara, kereta api,
kapal
laut,
kapal penyeberangan dan
pelayaran Samudera
Luar Negeri.
Terutama
untuk
negara
yang
sedang membangun.
Pengangkutan
muatan
lebih
penting dalam dunia bisnis dan perdagangan.
2.1.3
Faktor Penentu Pengembangan Transportasi
Menurut Hay dalam
Nur
Nasution (2004,p24-p25)terdapat beberapa faktor
yang
mempengaruhi perkembangan transportasi di masa akan datang seperti berikut:
1. Ekonomi
Alasan
ekonomi
biasanya
merupakan
dasar
dari
dikembangkannya
sistem
transportasi,
dengan
tujuan
utama
untuk
mengurangi
biaya
produksi
dan
|
|
8
distribusi
serta
untuk
mencari
sumber
daya
alam
dan
menjangkau
pasar
yang lebih luas.
2.
Geografi
Alasan
dikembangkannya
sistem transportasi
pada
awalnyaadalah
untuk
mengatasi
keadaan
alam setempat
dan
kemudian berkembang
dengan
upaya untuk mendekatkan sumber daya dengan pusat produksi dan pasar
3. Politik
Alasan dikembangkannya suatu sistem
transportasi secara politik adalah
untuk
menyatukan
daerah-daerah
dan
mendistribusikan kemakmuran
ke
seluruh pelosok suatu negara tertentu
4. Pertahanan dan Keamanan
Alasan dikembangkannya sistem
transportasi dari
segi pertahanan
keamanan
negara adalah
untuk keperluan pembelaan
diri
dan
menjamin
terselenggaranya pergerakan dan akses yang cepat ke tempat-tempat
strategis,
misalnya
daerah
perbatasan negara ,
pusat-pusat
pemerintahan,
atau instalasi penting lainnya
5. Teknologi
Adanya
penemuan-penemuan
teknologi
baru
tentu
akan mendorong
kemajuan di keseluruhan sistem transportasi
6.
Kompetisi
Dengan adanya
persaingan, baik antarmoda, maupun
dalam bentuk lainnya,
seperti pelayanan,
material
dan
lain-lain,
secara
tidak
langsung
akan
mendorong perkembangan
sistem
transportasi
dalam
rangka
memberikan
pilihan yang terbaik
|
|
9
7.
Urbanisasi
Dengan
makin
meningkatnya
arus
urbanisasi,
maka pertumbuhan kota-kota
akan semakin
meningkat
dan
dengan
sendirinya
kebutuhan jaringan
transportasi
untuk
menampung
pergerakan
warga
kotanya
pun
akan
semakin meningkat
2.1.4
Fungsi Manajemen Dalam Transportasi
Menurut
Nur Nasution
(2004,
p107), bagi
perusahaan-perusahaan
transportasi
umum
yang
menghasilkan
jasa
pelayanan
transportasi
kepada
masyarakat
pemakai
jasa
angkutan
(
users
),
maka
pada
prinsipnya
terdapat
empat
fungsi
produk
jasa
transportasi
yaitu
aman
(safety),
tertib
dan
teratur
(
regularity),
nyaman
(©omfort),
dan
ekonomis.
Untuk
mewujudkan
keempat
fungsi
produk
jasa transportasi
tersebut,
fungsi
manajemen
transportasi bagi perusahaan transportasi pada umumnya adalah:
1. Merencanakan kapasitas dan jumlah armada
2. Merencanakan
jaringan
trayek/lintas/rute
serta
menentukan
jadwal
keberangkatan
3. Mengatur pelaksanaan operasi armada dan awak kendaraan
4. Memelihara dan memperbaiki armada
5. Melaksanakan promosi dan penjualan tiket
6. Merencanakan dan mengendalikan keuangan
7. Mengatur pembelian
suku cadang dan logistik
8. Merencanakan
sistem
dan
prosedur
untuk
meningkatkan
efisiensi
perusahaan
9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perusahaan
|
|
10
10.
Menjalin
hubungan
yang
erat
dengan
instansi-instansi
pemerintah
meupun
instansi lainnya yang terkait
Dengan
memahami
fungsi manajemen
perusahaan
transportasi
umum
tersebut,
maka
sesuai dengan
kondisi
dan
luasnya
operasi
dapatlah
disusun
struktur
organisasi
dengan
deskripsi tugas
dan
tanggung
jawab, wewenang,
dan sistem
manajemennya
yang
jelas dan mudah dilaksanakan.
Dalam
penggunaan
sehari-hari
terdapat
beberapa
istilah
yang
dapat
diartikan
sebagai manajemen,
yakni pengurusan, pengelolaan,
ketatalaksanaan, dan sebagainya.
Dalam
kaitannya
dengan manajemen transportasi, manajemen dari
suatu pengoperasian
angkutan
barang
pada suatu
industri manufaktur,
merupakan
tanggungjawab
lini
karena
sasaran
utama
perusahaan
itu adalah
mencapai keuntungan dari
upaya memuaskan
langganan.
Dinamika
bisnis juga
menghendaki
adanya
fleksibilitas
untuk
fungsi
jasa
angkutan agar
mampu
menangani
masalah-masalah
dan
sekaligus
menentapkan
lini-lini
wewenang dan lini pelaporan
yang
jelas.
Ada tiga
tugas utama
yang harus dihadapi
oleh
manajemen transportasi, yaitu :
1. Menyusun rencana
dan program
untuk
mencapai
tujuan dan
misi
organisasi
secara keseluruhan.
2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.
3.
Dampak sosial dan tanggung jawab sosial dalam mengoperasikan angkutan.
Dari
ketiga
tugas utama tersebut, semuanya haruslah dilaksanakan
secara
bersama-sama, berkesinambungan
dan berkelanjutan.
Ini
berarti bahwa
tugas yang
akan
dilaksanakan tersebut
haruslah
direncanakan terlebih
dahulu
untuk
mencapai hasil
yang
diharapkan.
Untuk
mendukung
suksesnya
pelaksanaan
tugas
tersebut
maka
harus
ada
tugas
dan
wewenang dari masing-masing
pekerja
transportasi dari tingkat
manajer hingga
bawahan. (Nur Nasution,
2004, p104)
|
|
11
2.1.5
Tugas dan Sasaran dalam Manajemen Transportasi
Menurut
Nur Nasution
(2004,
p
109)
untuk
mewujudkan
fungsi
produk
transportasi
seperti
yang telah
dijelaskan,
maka
sasaran
yang
harus
dicapai
dalam
perusahaan pengangkutan
umum adalah:
1. Menjamin
penyelenggaraan
angkutan
yang
aman
dan
menjamin
keselamatan (
safety)
2. Menjamin pengoperasian angkutan yang tertib dan teratur (
regularity
)
3. Mencapai efisiensi pengoperasian angkutan (e©onomy)
Departemen Perhubungan sebagai
instansi
Pemerintah
(regulator)
berkewajiban
untuk membina
terwujudnya sistem
transportasi nasional
(Sistranas)
yang
handal,
efisien,
dan
efektif. Untuk
mewujudkan
hal
tersebut, maka sasaran
Sistranas
adalah terciptanya
penyelenggaraan transportasi
yang efektif dalam arti kapasitas
mencukupi, terpadu,
tertib
dan teratur, lancar, cepat dan
tepat, selamat, aman, nyaman,
biaya terjangkau, dan efisien
dalam arti
beban
publik rendah
dan utilisasi
yang tinggi
dalam
satu
kesatuan
jaringan
transportasi nasional.
Kapasitas
mencukupi,
dalam
arti
bahwa
kapasitas
sarana
dan
prasarana
transportasi
cukup
tersedia untuk memenuhi kebutuhan
maupun
pertambahan permintaan
pengguna jasa. Kinerja kapasitas tersebut dapat diukur berdasarkan indikator sesuai
dengan
karakteristik
masing-masing moda, antara
lain
perbandingan
jumlah
sarana
angkutan dengan
penduduk,
antara
sarana
dan
prasarana,
antara
volume jasa
angkutan
yang
dinyatakan
dalam
penumpang-kilometer
atau
ton-kilometer
dengan
kapasitas
yang
tersedia.
Penyelenggaraan transportasi yang terpadu, dalam arti terwujudnya keterpaduan
antar dan intramoda dalam jaringan
prasarana
dan pelayanan yang meliputi
pembangunan,
pembinaan,
dan
penyelenggaraannya.
Penyelenggaraan
transportasi
yang
|
|
12
tertib,
berupa
terwujudnya
penyelenggaraan
transportasi
yang
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
di
masyarakat.
Keadaan tersebut
dapat
diukur
berdasarkan indikator antara
lain perbandingan
frekuensi
pelanggaran
dengan
jumlah
perjalanan.
Penyelenggaraan
transportasi
yang
aman,
adalah
dapat
terhindarnya
pengoperasian
transportasi dari akibat
faktor eksternal
baik berupa gangguan alam
maupun
manusia.
Keadaan
tersebut
dapat
diukur antara
lain
berdasarkan perbandingan
antara jumlah terjadinya gangguan dengan jumlah perjalanan.
Penyelenggaraan
transportasi
yang
cepat
dan
lancar
berarti pengoperasian
transportasi
dengan
waktu yang singkat
dengan
tingkat keselamatan yang
tinggi.
Keadaan
tersebut
dapat
diukur
berdasarkan
indikator antara
lain
kecepatan arus
perjalanan
per
satuan waktu.
Penyelenggaraan
transportasi
yang selamat,
berarti
terhindarnya
pengoperasian
transportasi dari
kecelakaan
akibat
faktor
internal
transportasi. Keadaan
tersebut
dapat
diukur
antara lain
berdasarkan
perbandingan
antara jumlah
kejadian
kecelakaan
dengan
jumlah perjalanan.
Penyelenggaraan
transportasi
yang
nyaman
,
dalam
arti
terwujudnya
ketenangan
dan
kenikmatan
bagi
penumpang
selama perjalanan
dari
asal
sampai
ke
tujuan
baik
di
dalam
maupun
diluar
sarana
transportasi.
Keadaan
tersebut
dapat
diukur
dari ketersediaan dan kualitas fasilitas dalam maupun diluar sarana transportasi.
Penyelenggaraan
transportasi
dengan
biaya
terjangkau
adalah
keadaan
penyediaan jasa
transportasi
yang
sesuai
dengan
daya
beli
masyarakat
pada
umumnya
dengan memperhatikan tetap dapat berkembangnya kemampuan penyedia jasa
transportasi.
Keadaan
tersebut
dapat
diukur
berdasarkan
indikator
perbandingan
antara
|
|
13
pengeluaran
rata-rata
masyarakat
untuk pemenuhan
kebutuhan
transportasi
dengan
pendapatan.
Penyelenggara
transportasi
yang
efisien,
adalah keadaan
penyelenggaraan
transportasi yang
mempu memberikan manfaat
yang
maksimal dengan
pengorbanan
tertentu
yang
harus
ditanggung
oleh pemerintah,
masyarakat
dan
lingkungan,
atau
memberikan manfaat
tertentu
dengan pengorbanan
minimum. Keadaan
ini dapat
diukur
antara
lain
berdasarkan
perbandingan manfaat
dengan
besarnya biaya
yang dikeluarkan.
Sedangkan utilisasi merupakan tingkat penggunaan
kapsitas sistem transportasi yang
dapat
dinyatakan
dalam
indikator
seperti
faktor
muat
barang
(load factor)
dan
tingkat
penggunaan (utilisasi) sarana dan prasarana angkutan.
2.1.6
Kriteria Kinerja Transportasi
(Rudy Hermawan, 2001, p55) untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja
dari sistem operasi transportasi ada beberapa parameter/indikator yang bisa dilihat, yaitu :
1. Faktor Tingkat Pelayanan
a. Kapasitas
Kapasitas dinyatakan sebagai jumlah
penumpang atau barang
yang bisa
dipindahkan dalam satuan waktu tertentu,
misalnya
orang,
jam,
berat
(ton/kg/dll).
Dalam hal
ini
kapasitas ini merupakan
fungsi
dari
kapasitas
atau
ukuran tempat
atau
sarana
transportasi
dan
kecepatan
serta
mempengaruhi besarnya tenaga gerak
yang dibutuhkan.
b. Aksesibilitas
Aksesibilitas
menyatakan
tentang kemudahan
orang dalam
menggunakan suatu transportasi tertentu dan bisa berupa fungsi dari
jarak
maupun
waktu.
Suatu
sistem
transportasi
sebaiknya
bisa
diakses
|
|
14
dengan
mudah
dari
berbagai
tempat
dan
pada
setiap saat
untuk
mendorong orang menggunakannya dengan mudah.
2. Faktor Kualitas Pelayanan
a. Keselamatan
Keselamatan menyangkut
kemungkinan
adanya
kecelakaan
dan
terutama
berkaitan
erat
dengan
sistem pengendalian
yang
digunakan.
Apabila
suatu
sistem
transportasi
mempunyai
pengendalian
yang ketat,
maka
biasanya
mereka
mempunyai tingkat
keselamatan
dan
keamanan
yang tinggi.
b. Keandalan
Keandalan
berhubungan dengan
faktor-faktor
seperti
ketepatan jadwal
waktu
dan
jaminan
sampai
di
tempat
tujuan.
Suatu sistem
transportasi
yang
andal berarti
bahwa penumpang/barang
yang diangkut bisa
sampai
ke
tempat
tujuan
dengan tepat
waktu dan
tidak
mengalami
gangguan
atau kerusakan.
c.
Fleksibilitas
Fleksibilitas menyangkut
kemudahan yang
ada di dalam
mengubah
segala sesuatu sebagai akibat adanya kejadian
yang berubah tidak
sesuai dengan skenario yang direncanakan.
d. Kenyamanan
Kenyamanan transportasi sangat
berlaku
untuk angkutan
penumpang
yang
erat
kaitannya
dengan
masalah tata
letak
tempat
duduk,
sistem
pengaturan udara
di
dalam
kendaraan,
ketersediaan
fasilitas
khusus
seperti toilet, tempat makan, dan waktu operasi.
|
|
15
e. Kecepatan
Kecepatan
merupakan
faktor
yang sangat
penting dan
erat
kaitannya
dengan masalah
efisiensi sistem
transportasi.
Pada
prinsipnya
pelanggan
selalu
menginginkan
kecepatan
yang tinggi
dalam
transportasi
agar
segera
sampai
di
tempat
tujuan.
Namun
demikian,
keinginan tersebut
kadang-kadang
dibatasi oleh
beberapa
hal,
misalnya
kemampuan mesin
atau
tenaga
penggerak yang
digunakan,
kemacetan
lalu
lintas
dan
kemampuan/kecakapan
manusia
dalam menggunakan
alat
transportasi
tersebut.
f.
Dampak
Dampak
transportasi sangat
beragam
jenisnya,
mulai
dari dampak
lingkungan
(polusi, dan kebisingan), sampai
dengan dampak sosial
politik yang ditimbulkan/diharapkan oleh adanya suatu operasi lalu lintas
serta besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan.
2.2
Manajemen Operasional
2.2.1
Pengertian Manajemen Operasional
Manajemen operasional
memiliki
banyak
arti
meskipun
pada
dasarnya
sama.
Namun, ada
baiknya
bila
kita
melihat
pemahaman
manajemen
operasi
dari
berbagai
sumber, diantaranya:
•
Menurut
Wikipedia
Indonesia,
manajemen
operasional
adalah
bidang
usaha
yang
bersangkutan
dengan mutu
produksi barang
dan jasa,
dan melibatkan
tanggung
jawab
untuk
memastikan
bahwa operasi bisnis
yang
efisien
dan
efektif.
Manajemen
operasional
merupakan
sumber
daya,
distribusi
barang
dan jasa kepada pelanggan.
|
|
16
Operasi
juga
merujuk
pada
produksi
barang
dan
jasa,
kumpulan
dari
nilai
bentuk kegiatan yang ditambahkan ke
dalam banyak masukan keluaran.
•
Menurut
Melnyk
(2002,
p5),
manajemen
operasi
merupakan
pembelajaran
dari
suatu
organisasi
dimana
kita
diharuskan
untuk mengerti,
menjelaskan,
menebak, serta
merubah suatu
organisasi dan
pengaruh strategi dari
proses
transformasi
atau
perubahan.
Dengan kata
lain,
manajemen
operasional
merupakan efektifitas dan efisiensi manajemen
dari suatu proses
perubahan
atau transformasi.
•
Menurut Schroeder
(2007,
p3),
inti dari manajemen operasi
dapat
dijabarkan
sebagai berikut:
9
Operasional
bertanggung
jawab
pada
penyediaan
produk
atau
jasa
dari
suatu organisasi
9
Manajer
operasional
membuat
keputusan
mengenai
fungsi
operasi
dan
hubungannya
dengan fungsi
yang lain.
Manajer operasional
merencanakan
dan
memantau
proses produksi
dan interfensi
itu sendiri
antara organisasi dan dengan pihak luar.
•
Menurut
Constable,
manajemen
operasi
lebih
difokuskan
pada
kebutuhan
untuk
produksi.
Walaupun produk
tersebut
merupakan
produk
manufaktur
maupun
jasa.
Pada
dasarnya,
manajemen operasional termasuk
dalam
manajemen produksi,
namun
lebih
difokuskan
pada
distribusi dan
pada
supply
manajemen. Manajemen operasional pada prinsipnya lebih fokus
pada
arus
fasilitas
yang tersedia
seperti
tenaga
kerja
dan
modal
untuk
menjamin
bahwa
mereka
akan
bertemu
dengan
arus
kebutuhan
pasar.
Hal
ini
juga
difokuskan
oleh
desain
yang
original
atau perluasan
pada
semua
fasilitas dimana selama pengaruh tersebut merupakan sistem operasi.
|
|
17
Berdasarkan
pemahaman-pemahaman
tersebut,
ada
3
poin
penting
dalam
manajemen operasional:
•
Keputusan
Definisi
ini
mengarah pada
‘membuat keputusan’
sebagai elemen terpenting
dari
manajemen
operasional.
Saat manajer
mebuat
keputusan,
langsung
terfokus pada pembuatan keputusan sebagai pokok dari operasional.
•
Fungsi atau kegunaan
Operasional merupakan
fungsi
utama
di
setiap
organisasi
termasuk
bagian
marketing
maupun
keuangan.
Fungsi operasi
bertanggung
jawab
untuk
menyediakan atau memproduksi barang atau jasa untuk bisnis.
•
Proses
Manajer operasional
merencanakan
dan
mengontrol
proses
produksi
dan
hasilnya.
2.2.2
Komponen-komponen
Utama dalam Manajemen Operasional
Menurut
Melnyk
(2002,
p6),
manajemen
operasional
terintegrasi
pada
3
komponen utama yang mendukung dalam proses organisasi, diantaranya:
•
Customer
(Pelanggan)
Customer
merupakan seseorang
yang selalu
mengkonsumsi kebutuhan pada
sistem manajemen operasional. Customer merupakan orang yang memiliki
peran
khusus
dimana selalu memberikan saran serta
pendapat
di
awal
dan
di
akhir
sistem
manajemen
operasional
paling
tidak,
perusahaan
dengan
jelas dapat
diidentifikasikan
pada segmen
pasar dan pada segmen
customer
itu sendiri. Keefektifitas
serta keefisienan fungsi manajemen operasional
tidak dapat terstruktur.
|
|
18
•
Process (Proses)
Sebuah proses dalam perusahaan merupakan hubungan dari semua aktifitas
yang
diperlukan
untuk
mengubah
input
menjadi
output (hasil).
Proses
menggambarkan
keseluruhan
input, aktifitas
perubahan,
dan output
pada
keseluruhan sistem.
Hal
itu
menandakan
hal-hal
yang
dibutuhkan
dalam
sebuah kegiatan serta menspesifikasikan bahan apa yang dibutuhkan
dan
seberapa
besar jumlahnya. Proses
juga
menggambarkan
kegiatan
yang
diperlukan
untuk
mengubah
input
menjadi
output
.
Pada
akhirnya,
seluruh
kegiatan pemeriksaan dilakukan
untuk memastikan bahwa semua
memenuhi
standar kualitas, kuantitas, lead time, atau pembagian waktu.
Proses
manajemen operasional
dapat melibatkan
produksi
pada sebuah
produk atau jasa. Proses juga menghasilkan informasi.
•
Capacity (Kapasitas)
Saat proses menjelaskan bagaimana sistem
manajemen
operasional bekerja,
kapsitas
mendeterminasikan
seberapa
besar sistem
produksi. Untuk
kebanyakan
orang,
kapasitas
mengartikan
seberapa
besar
dari hasil
yang
diproduksi perusahaan,
bahkan membatasi hasil
per unit
dalam satu satuan
waktu.
|
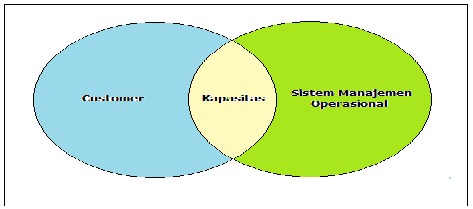 19
Gambar 2.1
Komponen
Utama dalam Sistem Manajemen Operasional
Sumber: Melnyk. Denzler, Operations Management, 2002
2.3
Analytical Hierarchy Process
(AHP)
Menurut Wikipedia
Indonesia,
Analytical
Hierarchy
Process
(AHP)
adalah struktur
teknik
untuk menangani
kompleks
keputusan.
AHP
membantu
mengambil
keputusan
menemukan salah
satu
yang
paling
sesuai dengan kebutuhan dan
pemahaman
mengenai
masalah tersebut.
Berdasarkan
matematika
dan
psikologi,
AHP
dikembangkan
oleh
Thomas
L.
Saaty
pada
tahun 1970an
dimana
AHP
menyediakan kerangka
komprehensif dan rasional
untuk
struktur
keputusan
masalah,
dan
untuk mewakili
unsur
kualifikasinya,
untuk
elemen
terkait
untuk tujuan secara keseluruhan, dan untuk mengevalusi solusi alternative.
Pengguna
dari
AHP
pertama
menguraikan
masalah keputusan mereka
ke
dalam
hirarki
yang lebih
mudah memehami sub
masalah,
masing-masing
yang
dapat
dianalisis
secara
mandiri.
Unsur-unsur
dari
hirarki
dapat
berhubungan
dengan
setiap aspek
dari
keputusan masalah nyata atau hal-hal yang tidak dapat diperkirakan.
|
|
20
2.3.1
Prinsip Kerja AHP
Menurut
Saaty
(1988) dalam Marimin (2004), ide dan
prisip
AHP
adalah sebagai
berikut:
1. Penyusunan Hirarki
Persoalan yang
akan
diselesaikan
diuraikan
menjadi
unsur-unsurnya
yaitu
criteria dan alternatif yang kemudian disusun menjadi struktur hirarki.
2.
Penilaian Kriteria dan Alternatif
Kriteria
dan
alternatif
dinilai
melalui
perbandingan berpasangan. Menurut
Saaty
(1988)
untuk
berbagai
persoalan
skala
1
sampai
dengan
9
adalah
skala terbaik
dalam mengekspresikan pendapat
3.
Penentuan Prioritas
Untuk setiap
kriteria
dan
alternatif
perlu
dilakukan
perbandingan
berpasangan
(pairwise
comparisons). Nilai-nilai
perbandingan
relatif
kemudian
diolah
untuk
menentukan
peringkat
relatif
dari
seluruh alternatif.
Baik
kriteria kualitatif
maupun
kriteria
kuantitatif
dapat
dibandingkan
sesuai
dengan
judgement yang
telah
ditentukan
untuk
menghasilkan
bobot
dan
prioritas. Bobot atau
prioritas
dihitung dengan
manipulasi matriks atau
melalui penyelesaian persamaan matematik.
4.
Konsistensi Logis
Semua elemen
dikelompokkan secara
logis
dan diperingkatkan
secara
konsisten sesuai dengan suatu
Intuitives mencari arti segala hal
dan
berfokus pada
implikasi dan thinkers membuat keputusan
secara
impersonal
dan
logis.
Bila
digabungkan,
kedua
preferensi
ini membentuk
“
Intuitives
Thinkers,” sebuah tipe kepribadian orang yang intelektual dan kompeten.
|
|
21
2.3.2
Keunggulan Analytical Hierarchy Process
Keunggulan AHP adalah memungkinkan
pengguna
untuk
memasukkan semua
aspek permasalahan yang relevan,
baik
yang bersifat objektif,
ke
dalam satu model
dan
keunggulan
utamanya
terletak
pada mekanisme pengujian
konsistensi
dari partisipannya.
Untuk lebih jelasnya, Saaty (1991,p25) menguraikan keuntungan-keuntungan dari AHP :
1. Kesatuan. AHP
memberi suatu model
tunggal
yang
mudah
dimengerti
dan
luwes untuk aneka ragam persoalan tak
terstruktur.
2. Kompleksitas. AHP
memadukan
rancangan deduktif
berdasarkan sistem
dalam memecahkan persoalan kompleks
3. Saling
ketergantungan.
AHP
dapat
menangani
saling
ketergantungan
elemen-elemen dalam suatu sistem dan
tidak memaksakan pemikiran linier.
4. Penyusunan
hierarki.
AHP
mencerminkan
kecenderungan
alami
untuk
memilah-milah
elemen-elemen
suatu sistem dalam berbagai tingkat
berlainan dan mengelompokkan struktur yang serupa dalam setiap
tingkat.
5. Pengukuran.
AHP
memberi
suatu skala
untuk
mengukur hal-hal
dan
wujud.
Suatu metode untuk menetapkan prioritas.
6. Konsistensi.
AHP
melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan
yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
7. Sintesis.
AHP
menuntun
ke
suatu
taksiran
yang
menyeluruh
tentang
kebaikan setiap alternatif.
8.
Tawar-menawar.
AHP mempertimbangkan
prioritas-prioritas relatif
dari
berbagai
faktor sistem
dan
memungkinkan seseorang
memilih alternatif
terbaik berdasarkan tujuan mereka..
9. Penilaian
dan
konsensus.
AHP
memaksakan
konsensus
tetapi
mensintesis
suatu hasil yang representative dari berbagai penilaian yang bebeda-beda.
|
|
22
10.
Pengulangan
proses.
AHP
memungkinkan
orang
memperhalus
definisi
mereka
pada suatu
persoalan
dan memperbaikipertimbangan dan
pengertian
mereka melalui pengulangan.
Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi-
objektif
dan multi-kriteria yang
berdasar pada
perbandingan preferensi
dari setiap
elemen
dalam
hirarki.
Jadi,
model
ini
merupakan suatu
model
pengambilan
keputusan
yang
komprehensif.
Namun
AHP
juga
memiliki
kelemahan
dalam
hal
kemungkinan
terjadinya
perubahan urutan jika muncul alternatif baru dalam permasalahan yang dihadapi.
2.3.3
Tahap-Tahap Analytical Hierarchy Process
AHP
yang
dikembangkan oleh
Thomas Saaty
merupakan
metode
penentuan
rangking
alternatif
keputusan
dan
pemilihan
yang terbaik
dari
alternatif
tersebut
ketika
pengambil
keputusan
memiliki
sasaran
atau
kriteria
multiple
(lebih
dari
satu)
yang
mendasari keputusan.
Dalam menyusun AHP ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
1.
Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang
diinginkan.
2. Membuat
struktur
hirarki
yang
diawali
dengan
tujuan
umum,
dilanjutkan
dengan subtujuan-subtujuan, criteria dan kemungkinan alternatif-alternatif
pada tingkatan kriteria yang paling bawah.
3. Membuat
matriks
perbandingan
berpasangan
yang
menggambarkan
kontribusi
relatif
atau
pengaruh setiap elemen
terhadap masing-masing
tujuan
atau
kriteria
yang
setingkat
diatasnya. Perbandingan
dilakukan
berdasarkan
“
judgement”
dari
pengambil
keputusan
dengan
menilai
tingkat
kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
|
|
23
4. Melakukan perbandingan
berpasangan sehingga
diperoleh “judgement”
seluruhnya sebanyak
n x [(n-1)/2] buah,
dengan n
adalah
banyaknya
elemen yang
dibandingkan.
5.
Menghitung nilai eigen dan menguji
konsistensinya, jika
tidak
konsisten
maka pengambilan data diulang.
6.
Mengulang langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat
hirarki.
7.
Menghitung
vector eigen dari
setiap
matriks
perbandingan
berpasangan.
Nilai
vector eigen
merupakan
bobot
setiap
elemen.
Langkah
ini
untuk
mensitesis
“judgement
”
dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada
tingkat hirarki terendah sampai pencapai tujuan.
8. Memeriksa
konsistensi
hirarki.
Jika
nilainya
lebih
dari
10
persen
maka
penilaian data judgement harus diperbaiki.
Secara
naluri,
manusia
dapat
mengestimasi
besaran sederhana
melalui
inderanya.
Proses
yang
paling mudah
adalah membandingkan dua
hal dengan
keakuratan
perbanding
tersebut
dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk
itu Saaty
(1988)
menetapkan
skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu
elemen terhadap elemen lain.
Adapun prosedur singkat AHP, adaah sebagai berikut : (Rian,p2)
Langkah 1
:Definisikan
masalah
dan
buat
strukturnya
mulai
dari
hirarki
paling
atas
sampai
dengan hirarki paling bawah.
Langkah 2
:Buat matriks perbandingan berpasangan untuk setiap level dan
tentukan nilai untuk setiap perbandingan. Konsistensi ditentukan
dengan menggunakan nilai eigen.
|
|
24
Langkah 3
:Bobot relatif
dihitung dengan melakukan analisis
vector eigen
untuk
setiap
kelompok
kriteria yang
ada
dalam
level
hirarki
yang sama
terkait dengan kriteria yang sama pada level yang tinggi.
Langkah 4
:Konsistensi dari seluruh hirarki ditemukan.
2.4
Teori Sistem Antrian (Waiting Line)
Ilmu pengetahuan
tentang bentuk antrian, yang
sering
disebut
sebagai
teori
antrian
(queueing theory) merupakan
sebuah
bagian
penting
operasi
dan
juga
alat
yang
sangat
berguna
bagi
manajer
operasi.
Menurut
Render
dkk.
(2005,
p418)
antrian
(waiting line
/
queue)
diartikan
sebagai
orang
–
orang
atau
barang
dalam
barisan
yang
sedang
menunggu
untuk
dilayani, sebagai contoh
pasien yang
sedang menunggu
di ruang praktik dokter,
mesin
bor yang sedang menunggu di bengkel untuk diperbaiki, dll.
Antrian
merupakan
aktifitas
yang
tidak lepas
dari
kehidupan
manusia
sehari
–
hari.
Suka
atau
tidak
suka,
manusia
tetap
harus
melakukan
aktifitas
antrian
tersebut.
Menurut
Taha
(1997,
p176),
fenomena
menunggu
atau mengantri
merupakan
hasil
langsung
dari
keacakan
dalam
operasional
pelayanan
fasilitas.
Secara
umum,
kedatangan pelanggan
ke
dalam suatu sistem
dan waktu
pelayanan
untuk
pelanggan
tersebut
tidak
dapat
diatur
dan
diketahui
waktunya
secara
tepat,
namun
sebaliknya,
fasilitas
operasional dapat
diatur
sehingga dapat mengurangi antrian.
Aminudin
(2005,
p169)
juga
menyatakan
terdapat
beberapa
ukuran
kinerja
dari
sistem antrian. Ukuran – ukuran kinerja tersebut antara lain :
•
Lama waktu pelanggan harus menunggu sebelum dilayani
•
Persentase
waktu
fasilitas
pelayanan
yang
tidak
digunakan
atau
menganggur
karena
tidak
ada pelanggan.
|
|
25
Ukuran
–
ukuran
kinerja
tersebut
merupakan
parameter
yang
menentukan
kinerja
dari
suatu
fasilitas.
Semakin
singkat
waktu
bagi
pelanggan
untuk
menunggu
dan
semakin
sedikit waktu menganggur fasilitas pelayanan berarti
kondisi sistem akan semakin optimal.
Penyusunan
teori
antrian
dipelopori
oleh
A.
K.
Erlang,
seorang
insinyur
berkebangsaan
Denmark,
pada
tahun 1909.
Ia
bekerja
di
sebuah
perusahaan
telepon
dan
melakukan
percobaan
yang
melibatkan
fluktuasi permintaan sambungan
telepon serta
pengaruhnya pada
peralatan
switching
telepon. Sebelum
Perang
Dunia
II, studi awal antrian
ini telah berkembang di lingkungan antrian yang lebih
umum.
2.4.1
Karakteristik Sistem Antrian
Ada tiga komponen dalam sistem antrian yaitu :
1.
Kedatangan, populasi yang akan dilayani (calling population)
2. Antrian
3. Fasilitas pelayanan
Masing-masing
komponen
dalam
sistem
antrian
tersebut
mempunyai
karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik dari masing – masing komponen tersebut adalah :
1.
Kedatangan Populasi yang akan Dilayani (calling population)
Karakteristik dari populasi yang akan
dilayani (calling population)
dapat
dilihat
menurut
ukurannya,
pola
kedatangan,
serta
perilaku
dari
populasi
yang
akan
dilayani.
Menurut
ukurannya, populasi
yang
akan
dilayani
bisa
terbatas
(
finite)
bisa
juga
tidak
terbatas (infinite).
Pada
kasus
antrian
busway ini populasi yang akan dilayani tidak terbatas (
infinite).
Pola
kedatangan
bisa
teratur,
bisa
juga
acak
(
random
). Pola
kedatangan
yang sifatnya acak
dapat digambarkan
dengan
distribusi statistik
dan dapat
|
|
26
ditentukan
dua cara
yaitu
kedatangan per satuan waktu
dan
distribusi waktu
antar kedatangan.
Contoh
:
Kedatangan
digambarkan
dalam
jumlah satu waktu,
dan
bila
kedatangan
terjadi
secara
acak,
informasi
yang
penting
adalah
Probalitas n
kedatangan dalam periode waktu tertentu, dimana n
= 0,1,2.
Jika
kedatangan
diasumsikan
terjadi dengan
kecepatan rata
–
rata
yang
konstan dan bebas
satu sama lain disebut
distribusi probabilitas
Poisson.
Ahli
matematika dan
fisika Simeon Poisson (1781
–
1840),
menemukan sejumlah
aplikasi
manajerial,
seperti
kedatangan
pasien di
RS, sambungan
telepon
melalui
central switching system,
kedatangan
kendaraan
di
pintu
tol,
dll.
Semua
kedatangan
tersebut
digambarkan
dengan
variabel
acak
yang
terputus – putus dan
non – negative integer
(0, 1, 2, 3, 4, 5, dst). Selama 10
menit mobil yang antri di pintu toll bisa 3, 5, 8, dst.
Ciri distribusi poisson :
1. Rata
–
rata
jumlah
kedatangan
setiap
interval
bisa
diestimasi
dari
data
sebelumnya
2. Bila
interval
waktu
diperkecil
misalnya
dari
10
menit
menjadi
5
menit,
maka pernyataan ini benar :
Probabilita bahwa
seseorang
pengguna
jasa
datang
merupakan
angka
yang
sangat kecil dan konstan untuk setiap interval.
a)
Probabilita
bahwa
2 atau lebih
pengguna
jasa akan
datang
dalam
waktu
interval
sangat
kecil
sehingga
probabilita
untuk
2
atau
lebih
dikatakan
nol
(0).
b)
Jumlah
pengguna
jasa
yang
datang
pada
interval
waktu
bersifat
independent.
|
 27
c)
Jumlah pengguna jasa yang
datang pada satu interval tidak tergantung pada
interval yang lain.
Probabilita
n
kedatangan dalam waktu
T
ditentukan dengan rumus :
P(n, T ) =
e
-
?T
(?T )
n
n!
Gambar 2.2 Distribusi Poisson
Sumber:Jay Heizer, Operations Management,
2001
Dimana :
?
=
rata – rata kedatangan per satuan waktu
T
=
periode waktu
n
=
jumlah kedatangan dalam waktu T
P
(n,T) = probabilitas n kedatangan
dalam waktu T
Jika kedatangan mengikuti
Distribusi Poisson
dapat
ditunjukkan
secara
matematis bahwa
waktu
antar
kedatangan
akan
terdistribusi
sesuai
dengan
distribusi
eksponensial.
Populasi panggilan.
P(T = t) = 1- e
-?
t
,
0
=
t
=
8
Gambar 2.3
Populasi Panggilan
Sumber: Jay Heizer, Operations Management,
2001
Dimana :
P(T=t) =probabilitas dimana waktu antar kedatangan T = suatu
waktu tertentu
?
=rata –rata kedatangan
per satuan waktu
T
=suatu waktu tertentu
|
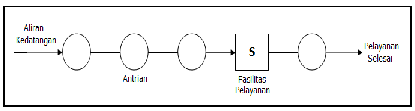 28
2. Antrian
Batasan
panjang
antrian
bias
terbatas
(limited)
bisa
juga
tidak
terbatas
(
unlimited
). Pengguna
jasa
busway
mempunyai
panjang
antrian
yang
tidak
terbatas (unlimited).
3. Fasilitas Pelayanan
Karakteristik fasilitas pelayanan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu
a. Tata Letak (
lay out)
Tata letak
fisik
dari sistem
antrian
digambarkan dengan jumlah
saluran,
juga
disebut
sebagai
jumlah
pelayanan.
Proses antrian secara
umum
dikategorikan menjadi
empat
struktur dasar
menurut
fasilitas
pelayanan
(Kakiay, 2004, p13). Keempat struktur antrian dasar tersebut adalah :
1.
Single Channel Single Phase
Pada struktur antrian
ini, subjek
pemanggilan
populasi
yang
dilayani
akan
datang, masuk dan
membentuk antrian pada satu
baris
/
aliran
pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas
pelayanan.
Contoh dari struktur antrian ini
adalah sebuah
kantor
pos
yang
hanya mempunyai
satu
loket
pelayanan
dengan
satu
jalur
antrian.
Gambar
berikut ini akan menunjukkan struktur
antrian
single channel single phase.
Gambar 2.4
Single Chanel Single Phase
Sumber: Jay Heizer, Operations Management, 2001
|
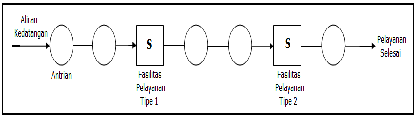 29
2.
Single Channel Multiple Phase
Pada struktur antrian
ini, subjek
pemanggilan
populasi
yang
dilayani
akan datang, masuk dan membentuk antrian pada
beberapa aliran
pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas
pelayanan sampai
pelayanan selesai. Contoh dari struktur antrian ini
adalah seorang
pasien
yang
berobat
ke
rumah
sakit,
mereka
harus
antri
untuk mendaftar
di loket
pendaftaran
terlebih dahulu,
setelah
selesai
mendaftar
pasien masuk ke
ruangan
periksaan awal,
dan
setelah
menerima
catatan diagnosa
dari
perawat
maka
pasien akan
antri
kembali
utnuk
diperiksa
oleh
dokter.
Gambar
2.5
berikut
ini
akan menunjukkan struktur antrian single channel multiple phase.
Gambar 2.5 Single Chanel Multiple Phase
Sumber: Jay Heizer, Operations Management, 2001
3.
Multiple Channel Single Phase
Pada struktur antrian
ini, subjek
pemanggilan
populasi
yang
dilayani
akan
datang, masuk dan
membentuk antrian pada satu
baris
/
aliran
pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan beberapa
fasilitas
pelayanan identik yang
pararel. Contoh
dari
struktur
antrian
ini
adalah
sebuah
kantor
pos
yang mempunyai
beberapa
loket
|
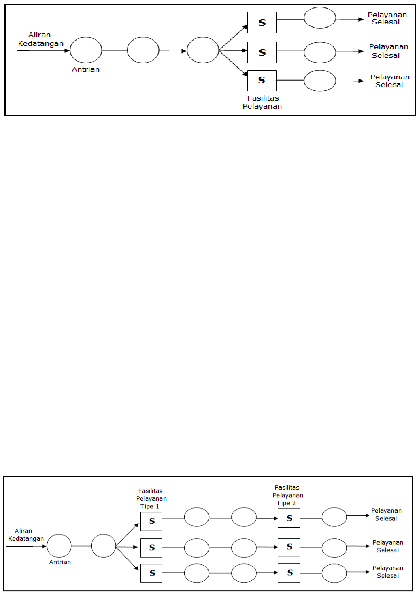 30
pelayanan dengan satu jalur antrian. Gambar 2.6 berikut ini akan
menunjukkan struktur antrian multiple ©hannel single phase.
Gambar 2.6 Multiple Chanel Single
Phase
Sumber: Jay Heizer, Operations Management,
2001
4. Multiple Channel Multiple Phase
Pada struktur antrian
ini, subjek
pemanggilan
populasi
yang
dilayani
akan datang dan
masuk
ke
dalam sistem pelayanan
yang
dioperasikan oleh
beberapa
fasilitas
pelayanan
pararel
yang
identik
menuju ke fasilitas pelayanan setelahnya samapi pelayanan selesai.
Contoh
dari struktur antrian ini
adalah seorang
pasien
yang
berobat
ke
rumah sakit,
dimana
terdapat beberapa
perawat
dan
beberapa
dokter.
Gambar
2.7
berikut
ini
akan menunjukkan struktur
antrian
multiple channel multiple phase
.
Gambar 2.7
Multiple Chanel Multiple Phase
Sumber: Jay Heizer, Operations Management,
2001
|
|
31
b.
Disiplin Antrian
Ada
dua
klasifikasi
yaitu
prioritas
dan first
come
first
serve.
Disiplin
prioritas
dikelompokkan
menjadi
dua,
yaitu
preemptive dan
non
preemptive.
Disiplin
preemptive menggambarkan
situasi di mana
pelayan
sedang
melayani
seseorang,
kemudian
beralih
melayani orang
yang
diprioritaskan meskipun
belum
selesai
melayani orang
sebelumnya.
Sementara disiplin non
preemptive
menggambarkan situasi di
mana
pelayan
akan
menyelesaikan
pelayanannya
baru kemudian
beralih
melayani
orang
yang
diprioritaskan.
Sedangkan
disiplin
first come first
serve menggambarkan bahwa orang yang lebih dulu dating akan dilayani
terlebih dahulu. Bila dilihat di lapangan disiplin antrian yang digunakan di
setiap
shelter – shelter busway
adalan
first come first serve
.
Tidak
ada
pengguna jasa yang diprioritaskan.
c.
Waktu Pelayanan
Waktu
yang dibutuhkan
untuk
melayani
bisa
dikategorikan
sebagai
konstan dan
acak. Waktu pelayanan konstan, jika waktu
yang
dibutuhkan untuk melayani sama untuk setiap pelanggan. Sedangkan
waktu pelayanan acak,
jika
waktu
yang
dibutuhkan
untuk
melayani
berbeda –
beda untuk setiap
pelanggan. Jika waktu pelayanan acak,
diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial.
Dalam pelayanannya para
pengguna
jasa
busway biasanya dilayani
secara
konstan.
Setiap
pengguna
jasa
menunggu
dalam
waktu
yang
sama
untuk
naik
ke
dalam
busway.
|
|
32
2.4.2
Perilaku kedatangan.
Populasi
yang
akan
dilayani
mempunyai
perilaku yang
berbeda
–
beda
dalam
membentuk
antrian.
Menurut
Aminudin
(2005,
p174)
ada
tiga
jenis
perilaku
: bulk,
reneging, balking,
dan
jockeying. Bulk, merupakan
tingkah
laku
pemanggilan
populasi
dimana
kedatangan
terjadi
bersama
–
sama (berkelompok)
ketika
memasuki
sistem.
Reneging menggambarkan
situasi di
mana
seseorang masuk dalam
antrian,
namun belum
memperoleh
pelayanan,
kemudian
meninggalkan
antrian
tersebut. Balking
menggambarkan
orang
yang
tidak
masuk
dalam antrian
dan
langsung
meninggalkan
tempay antrian.
Joekeying menggambarkan orang yang pindah – pindah antrian.
2.4.3
Perilaku
Biaya
Dalam sistem antrian ada dua jenis biaya yang timbul. Yaitu biaya karena
orang
mengantri
dan
di
sisi
lain biaya
karena
menambah fasilitas
layanan.
Biaya
yang
terjadi
karena orang
mengantri,
antara
lain berupa
waktu
yang
hilang
karena menunggu.
Sementara
biaya
menambah
fasilitas
layanan berupa
penambahan
fasilitas
layanan
serta
gaji
tenaga
kerja
yang
memberi
pelayanan.
Tujuan
dari
sistem
antrian
adalah
meminimalkan
biaya
total,
yaitu
biaya
karena mengantri
dan
biaya
karena menambah
fasilitas layanan.
2.4.4
Mekanisme Pelayanan
Ada 3 aspek
yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu:
1. Tersedianya Pelayanan
Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia untuk setiap saat. Misalnya
dalam
pertunjukan
bioskop,
loket
penjualan
karcis masuk hanya
dibuka
pada
waktu
tertentu
antara
satu
pertunjukan
dengan
pertunjukan
|
|
33
berikutnya. Sehingga pada
saat loket ditutup, mekanisme pelayanan
terhenti dan petugas pelayanan (pelayan) istirahat.
2. Kapasitas Pelayanan
Kapasitas
dari
mekanisme
pelayanan
diukur berdasarkan jumlah
langganan yang dapat dilayani secara bersama –
sama. Kapasitas
pelayanan
tidak selalu sama
untuk setiap
saat, ada
yang tetap, tapi
ada
juga yang
berubah
–
ubah.
Karena
itu, fasilitas
pelayanan dapat memiliki
satu atau
lebih
saluran,
fasilitas
yang mempunyai satu saluran
disebut
saluran
tunggal atau sistem
tunggal dan fasilitas yang
mempunyai lebih
dari satu saluran disebut saluran ganda atau pelayanan ganda.
3. Lamanya Pelayanan
Lamanya
pelayanan
adalah
waktu
yang
dibutuhkan
untuk melayani
seorang
langganan
atau
satu
–
satuan.
Ini
harus
dinyatakan
secara
pasti.
Oleh karena
itu,
waktu
pelayanan boleh
tetap
dari
waktu
ke waktu
untuk
semua
langganan
atau
boleh
juga
berupa
variable
acak.
Umumnya dan untuk keperluan analisis, waktu pelayanan dianggap
sebagai variable acak
yang
terpencar secara
bebas dan sama serta
tidak
tergantung pada waktu pertibaan.
2.4.5
Model – Model Antrian
Pada pengelompokkan model –
model antrian yang berbeda –
beda akan
digunakan suatu
notasi
yang disebut dengan
Notasi Kendall. Notasi ini sering dipergunakan
karena
beberapa
alasan.
Di antaranya,
karena
notasi tersebut merupakan alat
yang efisien
untuk
mengidentifikasi tidak
hanya
model-model antrian, tetapi
juga
asumsi –
asumsi
yang
harus dipenuhi (Subagyo, 2000).
|
|
34
Format umum model :
(a/b/c/);(d/e/f)
di mana :
a
=distribusi
pertibaan
/
kedatangan
(
arrival distribution),
yaitu
jumlah
pertibaan pertambahan waktu.
b
=ditribusi
waktu
pelayanan
/
perberangkatan,
yaitu
selang
waktu
antara
satuan-satuan yang dilayani.
c
=jumlah saluran pelayanan pararel dalam system.
d
=disiplin pelayanan.
e
=jumlah
maksimum
yang
diperkenankan
berada
dalam
sistem
(dalam
pelayanan ditambah garis tunggu)
f
=besarnya populasi masukan.
Keterangan :
1.
Untuk
huruf a dan
b,
dapat
digunakan
kode –
kode
berikut sebagai
pengganti :
M
=Distribusi
pertibaan Poisson atau distribusi
pelayanan
(perberangkatan)
eksponensial, juga
sama dengan
distribusi
waktu antara
pertibaan
eksponensial atau distribusi satuan yang dilayani Poisson.
D
=Antarpertibaan atau waktu pelayanan
tetap.
G
=Distribusi umum perberangkatan atau waktu pelayanan.
2.
Untuk
huruf c,
dipergunakan
bilangan bulat positif
yang
menyatakan
jumlah
pelayanan pararel.
3.
Untuk huruf d, dipakai kode-kode pengganti :
FIFO atau FCFS = First In First Out atau First Come First Served.
LIFO atau LCFS =
Last In First Out atau Last Come First Served.
|
|
35
SIRO = Service In Random Order
G D =
General Service Disciplint
4. Untuk huruf e
dan f, dipergunakan kode N (untuk menyatakan jumlah
terbatas)
atau
8
(tak
berhingga
satuan
–
satuan
dalam
sistem antrian
dan
populasi masukan).
Misalnya, model (M/M/1);(FIFO/8/8), berarti bahwa model menyatakan
pertibaan didistribusikan secara Poisson,
waktu pelayanan didistribusikan secara
eksponensial, pelayanan adalah satu atau seorang, disiplin antrian adalah First In First Out,
tidak
berhingga
jumlah
langganan
boleh
masuk dalam sistem
antrian,
dan
ukuran
(besarnya) populasi masukan adalah tak berhingga.
Maka untuk model antrian busway ini dapat dinotasikan menjadi :
(M/M/2);(FIFO/8/8)
M
yang
pertama
untuk menunjukkan bahwa
model
menyatakan
pertibaan
didistribusikan
secara
Poisson, waktu pelayanan didistribusikan
secara
eksponensial,
pelayanan adalah dua atau dua saluran pelayanan, disiplin antrian adalah First In First Out,
tidak
berhingga
jumlah
langganan
boleh
masuk dalam sistem
antrian,
dan
ukuran
(besarnya) populasi masukan adalah tak berhingga.
2.4.6
Notasi Parameter
Parameter model antrian ditentukan dengan notasi sebagai berikut :
?
=rata –rata kecepatan kedatangan (jumlah kedatangan persatuan waktu)
1/
?
=rata – rata waktu antar kedatangan.
µ
=rata
–
rata
kecepatan
pelayanan
(jumlah
satuan
yang
dilayani
persatuan
waktu bila pelayan sibuk).
1/µ
=rata – rata waktu yang dibutuhkan pelayan.
|
|
36
P
=faktor penggunaan pelayan (proporsi waktu pelayan ketika sedang sibuk).
Pn
=probabilita bahwa n satuan (kedatangan) dalam sistem.
Lq
=rata – rata jumlah satuan dalam antrian (rata – rata panjang antrian).
Ls
=rata – rata jumlah satuan dalam sistem.
Wq
=rata – rata waktu tunggu dalam antrian.
Ws
=rata – rata waktu tunggu dalam sistem.
2.4.7
Asumsi
Dalam skripsi ini permasalahan antrian didasarkan pada asumsi berikut ;
1. Satu pelayanan dan dua
tahap.
2. Jumlah
kedatangan
per
unit
waktu
digambarkan
oleh distribusi
Poisson,
dengan ?
= rata – rata kecepatan kedatangan.
3. Waktu pelayanan eksponensial dengan µ = rata – rata kecepatan pelayanan.
4. Disiplin antrian adalah First Come Firs
Served (aturan antrian pertama
datang, pertama dilayani) seluruh kedatangan dalam
barisan hingga dilayani.
5.
Dimungkinkan panjang barisan
yang tak terhingga.
6. Populasi yang dilayani tidak
terbatas.
7. Rata-rata kedatangan lebih kecil dari rata – rata waktu pelayanan.
8. Rata-rata
tingkat
kedatangan lebih kecil
dari tingkat
pelayanan semua
channel
(=
jumlah
channel
dikalikan
rata-rata
tingkat
pelayanan
per
channel)
|
 37
2.4
KERANGKA
PEMIKIRAN
Menurut
Sugiyono
(2004, p1),
metodologi penelitian merupakan suatu
langkah
–
langkah sistematis
yang akan
menjadi pedoman dalam
menyelesaikan masalah.
Diagram
di
bawah
ini
merupakan
langkah
–
langkah
yang
diambil
untuk
menunjang
penelitian
sistem
antrian
pada
Bus
Transjakarta.
Dengan
berdasarkan
pada
metodologi
ini
maka
penelitian
akan
berjalan
lebih
terarah
dan sistematis
sehingga
memudahkan
proses
analisa
dan
pemecahan masalah yang ada.
(gambar diagram)
Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran
Sumber:Peneliti
|