|
11
BAB II
TINJAUAN DAN LANDASAN TEORI
II.1
Tinjauan Umum
II.1.1
Tinjauan Mengenai Perlunya Dilakukan Konservasi
Mengapa konservasi perlu dilakukan? Alasannya adalah karena
bangunan dan kawasan kota tua dapat menjadi ikon promosi identitas nasional
suatu
bangsa,
memiliki
kualitas
untuk
menjadi
potensi
pariwisata
loal dan
mancanegara. Bangunan bersejarah adalah bagian tak terpisahkan dari
lingkungan
yang telah
terbangun.
Sejarah
membentuk
wajah
kota,
dan
sebagian masih dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi sekarang. Ironisnya
nilai usia dan sejarah bangunan yang bertambah berbanding terbalik dengan
kondisi fisiknya bila tidak dilakukan konservasi.
Setiap hal, termasuk bangunan, memiliki zamannya sendiri dan akan
berganti baru sesuai perkembangan zaman. Namun bangunan-bangunan
kontemporer yang dibangun dengan sesuai pertimbangan
masa kini terbukti
memiliki
usia
yang
tidak
panjang. Rata-rata
hanya
20
tahun.
Sementara
bangunan tua yang dibangun pada
masa lampau memiliki ketahanan dan
kesinambungan yang lebih besar, yang dengan perawatan yang cukup, dapat
digunakan untuk waktu yang sangat lama. Perawatan dan pemanfaatan tepat
bangunan
tua
dapat
menjadi
solusi ekonomis
dan
rasional
ketimbang
membangun bangunan baru yang tidak tahan lama. Asumsi bahwa biaya
perawatan
bangunan
tua
sangat
besar
perlu
diimbangi
dengan
pemahaman
|
|
12
bahwa biaya perawatan bangunan baru pun tidak sesedikit yang diduga.
(Orbasli, 2008, pp3-4)
II.1.2
Tinjauan Mengenai Kota Tua dan Konservasi di Dunia
Tumbuhnya perhatian lebih pada
warisan budaya dan rasa
nasionalisme
pada akhir Perang Dunia, serta
kesadaran
bahwa
pariwisata
budaya dapat bernilai ekonomi menjadi penyebab dimulainya gerakan
konservasi di
Eropa pada akhir abad XX. Setelah perang, penting bagi suatu
bangsa untuk membangun kembali monumen-monumen yang hancur atau
rusak berat.
Pusat sejarah yang dibangun di Warsawa untuk melakukan
dokumentasi pra Perang Dunia, kemudian dikenal sebagai UNESCO World
Heritage List. Beberapa konvensi diadakan, menghimpun negara-negara di
dunia, mensahkan piagam-piagam yang
menjadi ketentuan global bagaimana
seharusnya
konservasi dilakukan. Beberapa
ketentuan
seperti
Piagam Nara
yang khusus membahas konservasi di belahan dunia timur menekankan
pentingnya
aset
tidak
berwujud
seperti
adat
dan
kepercayaan
sebagai
salah
satu elemen konservasi.
Konservasi
sudah
umum dilakukan
di
negara-negara
di
dunia.
Contohnya Jerman sebagai negara yang banyak menderita kehilangan dan
kerusakan selama Perang Dunia. Salah satu kotanya, Heidelberg, tampak terisi
seluruhnya dengan bangunan tua, padahal sebenarnya
hanya
empat bangnan
yang tersisa setelah perang, sisanya direkonstruksi sesuia keadaan sebelum
masa
perang.
Sementara
Singapura
memberikan
perhatian
khusus pada
|
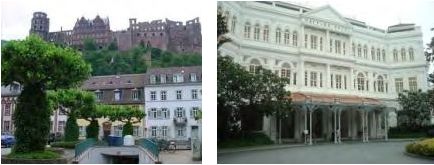 13
konservasi, salah satunya dengan melibatkan emosi masyarakat dalam
pengolahan
kawasan
kota
tua
dan memberi
penghargaan
tahunan
bagi
bangunan-bangunan yang dinilai dikonservasi dengan baik.
Gambar II.1.2.1 P®aktek konservasi di Je®man dan Singapura
Sumber : Dokumentasi pribadi dan Google image search
II.1.3
Definisi Hotel
Menurut
Dictionary
of Architecture
and
Building
Construction
(Davies dan Jokiniemi, 2008, p193), hotel is an establishment providing
temporary residential accommodation and communal facilities, primarily for
travelers, tourists and those on holiday or business. Dapat diartikan sebagai
berikut : hotel adalah sebuah tempat usaha yang menyediakan akomodasi
hunian
bersifat
sementara
dan
fasilitas bersama,
terutama
bagi
orang-orang
dalam perjalanan, wisatawan, dan mereka yang sedang berlibur atau berbisnis.
II.1.4
Sejarah Hotel
Hotel
mulai dikenal sejak permulaan abad masehi, dengan adanya
usaha penyewaan kamar untuk orang yang melakukan perjalanan. Hotel
berasal dari kata ”inn”, dapat diartikan sebagai
usaha
menyewakan sebagian
|
|
14
dari rumahnya kepada orang lain yang
memerlukan
kamar
untuk
menginap.
Pada umumnya kamar yang disewakan dihuni beberapa orang bersama-sama.
Pada
mulanya
inn,
sering juga disebut dengan lodge, hanya
menyediakan tempat beristirahat bagi mereka yang melakukan perjalanan.
Peradaban semakin maju, maka terdapat
berbagai peningkatan : fasilitas
penyediaan bak air untuk mandi, kemudian disusul penyediaan makanan dan
minuman, walaupun masih dalam tahap yang sangat sederhana. Pada abad ke-
6
masehi, mulai diperkenalkan uang sebagai alat penukar yang sah, maka jenis
usaha
penginapan
ini
semakin
berkembang
dan
mencapai
puncaknya
pada
masa Revolusi Industri di Inggris pada tahun 1750 hingga tahun 1790.
Salah satu dampak revolusi adalah lebih banyak lagi orang
melakukan perjalanan. Pada zaman itu, ketertiban dan keamanan belum sebaik
saat
ini, sehingga para pejalan kaki memilih
untuk beristirahat di penginapan
yang dianggap dapat memberikan rasa aman kepada mereka saat bermalam,
dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan.
Pada tahun 1129 telah tercatat adanya
inn di Kota Canterburry,
Inggris, sedangkan di Amerika Serikat inn tertua dibangun pada tahun 1607.
Pada tahun 1794 di Kota New York dibangun sebuah hotel yang diberi nama
City
Hotel yang
mempunyai
kamar
sebanyak
73
kamar.
Walaupun
pada
awalnya
pengoperasian
Hotel City
dirasa
janggal,
akhirnya
hotel
tersebut
dengan cepat menjadi buah bibir yang pada gilirannya menjadi pusat kegiatan
segala acara di kota tersebut.
|
 15
Pada tahun 1829 dibangun hotel dengan
nama The Tremont House
yang kemudian oleh
sebagian para ahli dianggap sebagai cikal
bakalnya
perhotelan
modern.
Hotel tersebutlah yang
pertama kali memperkenalkan
jenis-jenis kamar single dan double, yang pada setiap kamar dilengkapi kunci
masing-masing,
air
minum
di setiap
kamar,
pelayanan
oleh
bellboy,
serta
memperkenalkan masakan Perancis ke dunia perhotelan. Hotel inipun menjadi
sangat terkenal dan
menjadi tempat persinggahan yang
sangat
ramai.
Yang
terpenting, mulai disadari bahwa industri hotel adalah industri penjualan jasa.
Pada
saat
itu hotel
belum
menyediakan
layanan kamar
mandi
dan
pendingin atau penghangat
untuk setiap kamar. Sekarang
hal tersebut sudah
menjadi keharusan. Setelah 20 tahun beroperasi, hotel Tremont ditutup untuk
diperbarui.
Tidak disangsikan lagi bahwa
keberasilan
The Tremont telah
mendorong lahirnya
hotel-hotel baru
yang
kemudian
saling
bersaing
dalam
meningkatkan mutu, baik dalam pelayanan maupun pengadaan fasilitas.
Gambar II.1.4.1 Hotel The Tremont House
Sumber : Akomodasi Perhotelan Jilid 1
Pada permulaan abad XX mulai terjadi perubahan yang cukup berarti
pada
industri perhotelan
yaitu
mulai diperkenalkannya hotel-hotel kelas
|
|
16
menengah yang tidak begitu mewah dan mahal bagi para pengusaha atau
wisatawan, berciri lebih mengutamakan kepraktisan, yang berkembang dengan
pesatnya.
Tercatat
seorang
yang
bernama
Ellswort
M. Statler
yang berjasa
dalam menemukan
ide-ide
baru
seperti
penyediaan
koran
pagi,
cermin
di
kamar,
dan
lain-lain.
Dalam
kurun
waktu
40
tahun
berikutnya,
hotel-hotel
milik Statler menjadi
contoh dalam pembangunan konstruksi
hotel-hotel baik
di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Industri perhotelan pernah
mengalami kejayaannya selama dan sesudah Perang Dunia II dimana banyak
sekali orang yang melakukan perjalanan dan memerlukan jasa perhotelan.
II.1.5
Studi Hotel
Untuk lebih memahami karakteristik dan kebutuhan hotel, penyusun
melakukan studi terhadap beberapa proyek sejenis.
1. Studi Hotel Salak The Heritage Bogor
Penyusun memilih Hotel Salak untuk studi karena hotel ini
memiliki beberapa kesamaan dengan proyek city hotel yang akan
dirancang. Hotel ini merupakan bangunan tua yang dikonservasi dan
dijadikan hotel bintang empat. Penyusun juga menjadikan Hotel Salak
sebagai salah satu rujukan studi luasan dan fasilitas.
Hotel Salak The Heritage dibangun pada tahun 1856 dengan
nama Hotel Bellevue-Dibbets, dan dikategorikan sebagai hotel khusus
bagi Kalangan Istana Bogor dan dimiliki oleh seorang Belanda yang
memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Jenderal.
|
 17
Gambar II.1.5.1 Foto semasa hotel masih bernama Hotel Dibbet
Sumber : Website Hotel Salak
Hotel Salak The
Heritage adalah
hotel
cagar budaya yang
bertempat di seberang Istana Kepresidenan Bogor di samping City Hall di
Jalan Ir. H. Juanda No. 8 Bogordi atas area seluas 8,227 m².
Hotel ini terdiri dari empat bagian utama. Pertama, bagian depan
yang
dikenal
dengan
nama
Heritage
Building
–
berupa
dua bangunan
bersejarah yang direnovasi. Dua bagian lagi adalah sayap kiri dan kanan
dengan dua dan empat
lantai.
Bagian
keempat adalah bagian
belakang
hotel
yang berlantai
lima, dilengkapi dua
lift tamu dan satu
lift service.
Hotel Salak terus meningkatkan layanan dan fasilitasnya hingga mencapai
standar klasifikasi hotel bintang empat.
Gambar II.1.5.2 Hotel Salak saat ini
Sumber : Website Hotel Salak
|
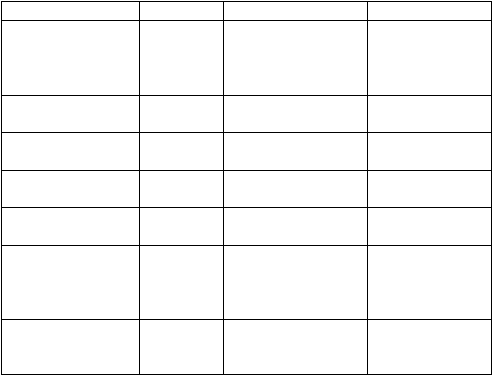 18
Ruang-ruang yang tersedia di hotel Salak dibagi menjadi
beberapa tipe sesuai luasan, fasilitas, dan pemandangan yang dimiliki.
Tabel II.1.5.1 Tipe kamar Hotel Salak
Nama Ruang
Luasan
Fasilitas/fitur
View
Colonial Presidential Suite
10 x 8 m
Double bed
Interior bergaya kolonial
Butler service 24jam
Koneksi internet
Istana Bogor
Colonial Super Executive
Double bed
Interior bergaya kolonial
Istana Bogor
Inner garden
Salak View Room
7,2 x 6 m
Double bed
Interior bergaya modern
Gunung Salak
Colonial Executive Heritage
4
x
8 m
Double bed
Interior bergaya kolonial
Istana Bogor
Inner garden
Deluxe Suite Room
Double bed room
Living room + dining set
Kolam renang
Inner garden
Deluxe Room
Twin room
Double bed room
Connecting room
Extra Wi-Fi Internet Access
Kolam renang
Inner garden
Jalan Kota Bogor
Superior Room
Twin room
Double bed room
Connecting room
Kolam renang
Inner garden
Jalan Kota Bogor
Sumber : Website Hotel Salak
Fasilitas penunjang yang tersedia di Hotel Salak :
1.
Business Center
2.
Fitness Center
3.
Paradise Travel
4.
Smart Kids Planet & Children Playground
5.
Swimming Pool & Inner Garden
6.
Bellevue Wellness Salon, Spa and Barbershop
7.
Herbal Place
8.
Drugstore & Art shop
|
 19
9.
Internet Corner
10.
Aesthetic Dentist
11.
ATM Center
12.
Security & Safety System
Hotel Salak memiliki 6 restoran dan café dengan kuliner
bervariasi dan 12 ruang
pertemuan
berkapasitas
10-1500
orang.
Keterangan mengenai ruang-ruang pertemuan diuraikan dalam tabel :
Tabel II.1.5.2 Tipe ruang pertemuan Hotel Salak
Room
Size
U-shape
Class Room
Round Table
Theater
Padjadjaran I
12.5m x 10.5m
20 – 40
40 – 70
30 – 50
70 – 100
Padjadjaran II
11m x 7m
20 – 30
40 – 60
20 – 40
50 – 80
Padjadjaran III
11m x 7m
20 – 30
40 – 60
20 – 40
50 – 80
Batutulis I
7.5m x 8.2m
10 – 25
10 – 20
10 – 20
20 – 30
Batutulis II
7m x 8.2m
15 – 20
15 – 18
15 – 20
20 – 30
Batutulis III
7m x 7m
10 – 15
10 – 16
10 – 18
10 – 20
Batutulis IV
5.5m x 4.5m
4
–
8
4
–
8
4
–
6
8
–
10
Galuh
14.4m x 8m
20 – 40
30 – 70
30 – 50
70 – 100
Pakuan
14.4m x 8m
25 – 40
50 – 70
30 – 50
50 – 100
Burangrang
8.5 m x 9.5 m
15 - 25
20 - 25
20 - 25
30 - 50
Istana
28.8m × 18m
50 – 100
75 – 150
100 –150
150 – 400
Sumber : Website Hotel Salak
Gambar II.1.5.3 ©afe Kanari dan Ballroom Istana
Sumber : Website Hotel Salak
|
 20
2. Studi The Scarlet Hotel Singapura
The Scarlet dipilih sebagai salah satu studi karena hotel ini
dinilai memiliki kualitas desain yang baik yang dapat
dicontoh, serta
pendekatan pencapaian standar hotel bintang lima tidak
melalui kuantitas
(jumlah
dan
luasan
kamar
dan
fasilitas),
tapi
melalui
kualitas
(tampilan
dan performa desain interior dan fasilitas). Hotel ini juga merupakan
proyek konservasi bangunan tua yang disesuaikan dengan fungsi baru dan
hasilnya cukup baik, ramai pengunjung.
Hotel The Scarlet dengan total 84 kamar terletak di sudut Erskine
Road, membentang sepanjang 12 ruko (shophouse) yang direstorasi,
termasuk satu bangunan bergaya Art Deco dari tahun 1924. Hotel dengan
konsep boutique hotel berbintang lima ini didesain amat mewah dengan
perabot dan elemen dekorasi berkelas.
Gambar II.1.5.4
Eksterior dan lobi The Scarlet
Sumber : Website Hotel Scarlet, Google image search
The
Scarlet
memiliki 5 suite
yang
masing-masing
didesain
dengan tema, skema warna, dan gaya
tersendiri : Splendour, Passion,
Opulent, Lavish, dan Swank.
|
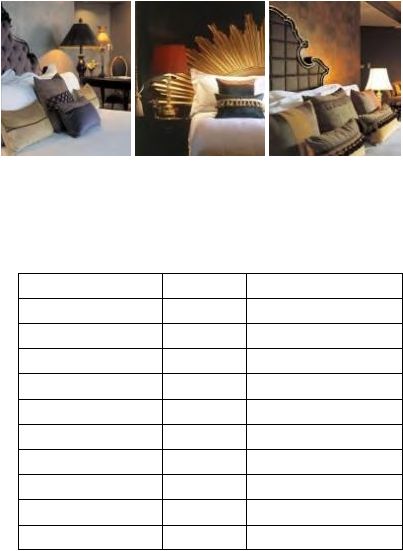 21
Gambar II.1.5.5 Suite Splendour, Opulent, dan Lavish
Sumber : Website Hotel Scarlet
Konfigurasi seluruh ruangnya sebagai berikut :
Tabel II.1.5.3 Tipe kamar Hotel Scarlet
Tipe Ruang
Jumlah
Luasan
Standard Room
8
15-20 sqm
Deluxe Room
28
16-20 sqm
Executive Room
17
16-20 sqm
Executive Room with balcony
8
18-24 sqm
Premium Room
14
26-30 sqm
Opulent Suite
1
36 sqm
Lavish Suite
1
42 sqm
Swank Suite
1
33 sqm
Passion Suite
1
25 sqm, Terrace Area 32 sqm
Splendour Suite (2 br)
1
51 sqm
Sumber : Website Hotel Scarlet
The Scarlet memiliki 3 restoran dan bar : Bold, Desire, dan
rooftop
restaurant
bertajuk
Breeze. Juga terdapat
2
fasilitas
kesehatan
:
Soda Spa dan Flaunt Fitness, dan
satu
ruang pertemuan yaitu
The
Sanctum. Semua fasilitas ini menerapkan desain interior yang menawan,
kuliner kelas satu, dan fasilitas lengkap. Salah satu restorannya, Desire,
bahkan mendapat penghargaan Singapore’s Top restaurant 2008.
|
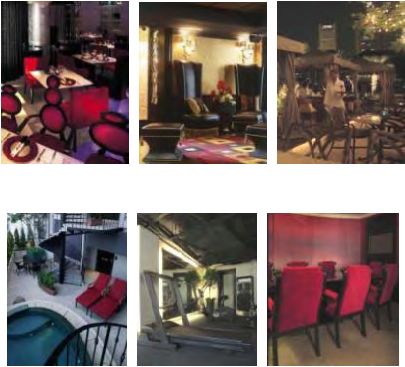 22
Gambar II.1.5.6 Restoran dan ba® Desi®e, Bold, dan B®eeze
Gambar II.1.5.7 Spa Soda, Fitness Flaunt, dan ruang pertemuan Sanctum
Sumber : Website Hotel Scarlet
Fasilitas yang dimiliki The Scarlet boleh jadi relatif sedikit dari
segi kuantitas, tapi sangat maksimal dari segi kualitas, selain aspek sejarah
dan lokasinya yang strategis. Inilah
yang menyebabkan
hotel ini
diklasifikasikan sebagai hotel bintang lima.
3.
Studi Tune Hotels Bali
Tune Hotel menjadi
acuan penyusun untuk lebih memahami
konsep limited service pada tipe compact hotel yang memungkinkan tarif
menginap dapat jauh ditekan hingga lebih terjangkau bagi sebagian besar
kalangan wisatawan, terutama di masa krisis ekonomi.
|
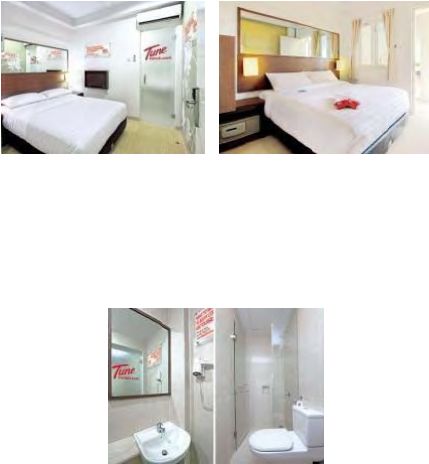 23
Hotel ini berslogan ‘pengalaman tidur bintang lima dengan harga
bintang
satu’.
Kualitas
tempat
tidur
dan
showernya baik.
Fasilitas
tambahan
tidak
disediakan
atau
diperoleh
dengan
sistem
‘bayar
sesuai
yang digunakan’. 5 fitur yang disediakan Hotel Tune antara lain :
•
Tempat tidur standar hotel bintang lima – spring bed King Koil ukuran
single untuk kamar tunggal dan queen size
untuk kamar ganda, serta
perlengkapan seperti bantal, selimut, dan sprei dengan kualitas sama
Gambar II.1.5.8 Tipikal kamar ganda Tune Hotel
•
Setiap
kamar
dilengkapi
kamar
mandi
di
dalam
dengan
shower
air
panas bertekanan kuat
Gambar II.1.5.9 Tipikal kamar mandi Tune Hotel
|
 24
•
Berada di lokasi yang strategis – semua Hotel
Tune terletak strategis,
berdekatan dengan pusat perbelanjaan, pusat bisnis, atau wisata. Tune
Hotel Kuta berjarak 6 menit jalan kaki ke Pantai Kuta, Tune Legian
berjarak 3
menit dari pantai. Keduanya berada pada jalan yang terisi
tempat makan dan pusat hiburan seperti spa, factory outlet, dan club.
Gambar II.1.5.10 Peta lokasi Tune Hotel Kuta
•
Bersih – layanan kebersihan tersedia setiap hari, penggantian bed linen
dapat dipilih untuk diganti setiap hari atau beberapa hari sekali.
•
Pengamanan
24
jam
–
kartu
elektronik
akses
masuk
kamar,
kamera
CCTV di seluruh hotel, petugas jaga bergilir, dan lobby utama tidak
dapat diakses tanpa kartu selewat tengah malam.
Gambar II.1.5.11 Akses kartu elektronik dan lobby resepsionis
|
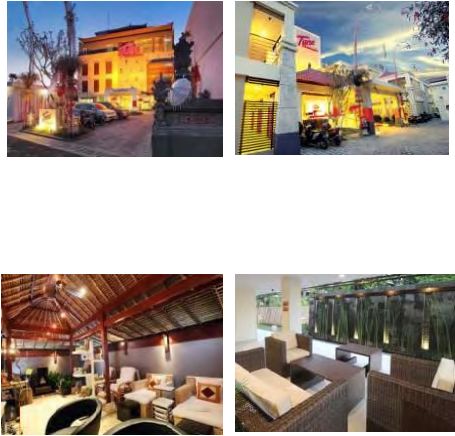 25
Karakteristik dan kualitas pelayanan Tune Hotels :
•
Rancangan tampak bangunan cukup
baik
Gambar II.1.5.12 Tampilan eksterior Tune Hotel Kuta dan Legian
•
Rancangan interior pada ruang publik seperti lobby cukup baik
Gambar II.1.5.13 Interior lobby Tune Hotel Legian
•
Layout kamar sangat efisien, luasan 9.6 m² untuk kamar tunggal dan
11 m²
untuk
kamar
ganda,
semua
dengan
kamar
mandi
di dalam.
Kekurangannya, ada beberapa kamar tidak berjendela. Tune Kuta
memiliki 55 kamar tunggal dan 84 kamar ganda, 4 lantai. Tune Legian
memiliki 170 kamar ganda, 4 lantai.
|
 26
Gambar II.1.5.14 Layout kamar tipikal Hotel Tune
•
Perabot
dalam kamar minim. AC dapat digunakan
dengan
membayar
biaya tambahan. Tidak ada
lemari,
hanya disediakan hanger. Tersedia
ceiling fan, side table dan safety box, serta pengering rambut.
Gambar II.1.5.15 Perlengkapan standa® yang tersedia di tiap kamar
•
Tidak ada room service dan sarapan pagi. Terdapat Mini Mart 24 jam
di Tune Kuta dan
Legian.
Restoran Es
Teler 77 dan Well
Being Spa
hanya ada di Tune Legian.
•
Bangunan bebas asap rokok, tersedia smoking area di lobby
•
Tersedia lift dan akses internet gratis di lobby
•
Fasilitas
yang dapat diperoleh dengan biaya tambahan : pick up
service, perlengkapan mandi, sarapan, wi-fi, AC, dan TV
•
Tidak ada fasilitas olahraga dan kesehatan, kecuali mungkin yang
skala kecil seperti spa di beberapa cabang. Fasilitas seperti kolam
|
 27
renang dianggap tidak perlu disediakan karena belum tentu digunakan
oleh semua tamu yang menginap.
•
Tarif semalam bervariasi Rp 120.000,- hingga Rp 300.000,-. Semakin
jauh tanggal reservasi, semakin murah. Reservasi dapat dilakukan
online via web. Tersedia tarif promo, seperti promo Hari Kemerdekaan
yang menawarkan harga Rp 1.700,- semalam.
4. Studi W Hotel Bali
W hotel
merupakan
resort
hotel bergaya
modern
karya
SCDA.
Dari tinjauan ini, penyusun bermaksud mengambil masukan dari gambar
kerja proyek berupa contoh layout kamar, pembagian ruang dan struktur,
serta dimensi dan organisasi ruang.
Gambar II.1.5.16 Perspektif W Hotel
Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA
|
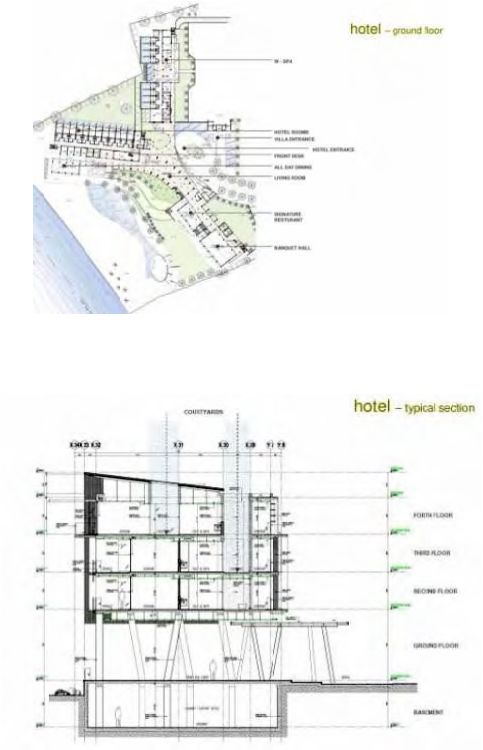 28
Gambar II.1.5.17 G®ound Plan W Hotel
Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA
Gambar II.1.5.18 Potongan W Hotel
Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA
|
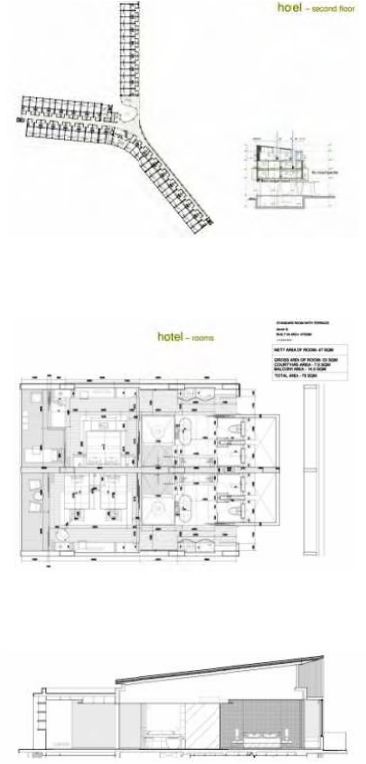 29
Gambar II.1.5.19 Denah lantai tipikal
Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA
Gambar II.1.5.20 Denah unitkamar
Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA
Gambar II.1.5.21 Potongan unit kamar
Sumber : Presentasi W Hotel Concept dari SCDA
|
|
30
II.1.6
Tinjauan Umum Terhadap Topik dan Tema
1. Arsitektur Kontekstual
Arsitektur kontekstual merupakan sebuah pendekatan terpadu
dengan
mengikutsertakan pertimbangan kualitas lingkungan
fisik dan
aspek nir-fisik ke dalam proses perancangan arsitektur.
Brent C. Brolin dalam bukunya
Architecture
in Context (1980),
menyatakan bahwa yang dimaksud architecture in context adalah
kemungkinan perluasan bangunan dan keinginan mengaitkan bangunan
baru dengan lingkungan sekitarnya. Dapat dijabarkan beberapa pendekatan
desain arsitektur kontekstual yang bervariasi atau tidak sekedar meniru:
1. Mengambil
motif-motif
desain
setempat, seperti bentuk
massa,
pola
atau irama bukaan, dan ornamen desain yang digunakan
2. Kedua,
menggunakan
bentuk-bentuk
dasar
yang
sama,
tetapi
mengaturnya kembali sehingga tampak berbeda
3. Ketiga,
melakukan pencarian bentuk-bentuk baru
yang memiliki efek
visual sama atau mendekati yang lama
4. Keempat, mengabstraksi bentuk-bentuk asli (kontras)
Beberapa
terminologi
umum dalam
arsitektur
kontekstual
yang
juga dapat menjadi pendekatan perancangan :
•
Alteration/alterasi :
Adaptasi bangunan lama untuk fungsi baru dengan
perubahan. Salah satu contoh alterasi
misalnya
Governent
Bunker
Documentation
Site
di
Bad
Neuenahr-Ahrweiler,
Jerman.
Dibangun
|
 31
pada 1960-1972 sebagai bunker perlindungan terhadap serangan udara,
kini
sisa
terowongan
tersebut
direnovasi
dan
ditambah
fungsi
baru
berupa museum dan pusat dokumentasi.
Gambar II.1.6.1 Bunke® yang dialterasi menjadi museum dan pusat dokumentasi
Sumber : The Architecture of Democracy
•
Addition :
-
Pengulangan bangunan asli
-
Abstraksi bangunan asli
-
Latar
belakang
(background)
bagi
bangunan
asli
dengan
pengaturan jarak dan kaitan visual (massa bangunan, dll.)
Contoh addition : bangunan baru Grand Hotel Preanger Jalan
Asia
Afrika
Nomor
81,
bersebelahan
dengan
bangunan
lama.
Bangunan
tersebut bergaya
Art
Deco disesuaikan dengan
bangunan
lama dengan tambahan fasilitas modern dalam unsur lansekap.
Gambar II.1.6.2 G®and Hotel Preanger, bangunan lama dan baru (kanan)
Sumber : Solusi Desain Arsitektur Kontekstual
|
|
32
•
Infill :
Pengertiannya tidak
terbatas pada
penyisipan satu
bangunan
saja, namun lebih kepada penyisipan berbagai aktivitas baru yang
dibarengi dengan penyediaan wadah/fasilitas fisik kegiatan, berupa
(kelompok) bangunan.
Pendekatan arsitektur kontekstual juga dapat dilakukan
melalui konsep harmonis dan kontras:
•
Harmonis
Pengulangan pola-pola dari bangunan lama dalam skala
tata
bangunan (gubahan massa, siluet bangunan, jarak antarbangunan,
setback, dan skala bangunan)
•
Kontras
Gubahan massa ‘sesuai’ dengan skala bangunan lama, tetapi
menggunakan unsur-unsur bangunan yang memperkuat keberadaan
(signifikasi) bangunan lama (struktur, konstruksi, bahan, langgam,
tekstur, warna, dll.)
Contoh infill yang bersifat kontras misalnya bangunan baru
German Oceanographic Museum yang dari bentuknya tampak organik,
kontras dengan sekitarnya,
warnanya
pun
putih
cemerlang
yang
berbeda dengan bangunan-bangunan tua di kawasan tersebut yang
digolongkan dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO.
|
 33
Bila diperhatikan, tampak ada garis-garis bangunan baru yang
selaras dengan bangunan tua di sebelahnya, sehingga tetap terasa
saling menunjang walaupun fisiknya sangat berbeda.
Gambar II.1.6.3 Ge®man Oceanographic Museum
Sumber : The Architecture of Democracy
Brolin
mendorong
kreativitas
dalam arsitektur
dalam
melahirkan bentuk-bentuk baru yang berbasis
pada
perbendaharaan
arsitektural dengan pengendalian (pedoman/panduan) yang ketat dalam
evaluasi hasil perancangan. (Martokusumo, 2005, ppV-6 – V-8)
Kontekstualisme
merupakan sebuah
ide
tentang
perlunya
tanggapan terhadap lingkungannya serta bagaimana menjaga dan
menghormati
jiwa dan karakter suatu tempat. Sering orang
beranggapan kontekstualisme hanya berusaha meniru bangunan lama
sehingga terlihat sama dengan bangunan baru atau hanya untuk
mempopulerkan
langgam historis
arsitektur
tertentu.
Namun,
sebenarnya tidaklah seperti itu. (Hertanto, 2005)
|
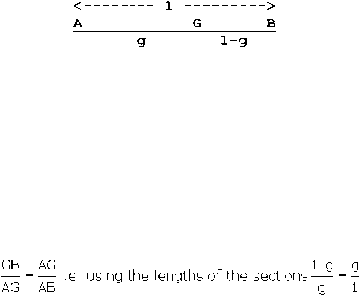 34
2.
Golden Section dan Spiral Fibonacci
Pada perkembangannya, akan digunakan teori yang lebih spesifik
dalam
menggarap
fisik bangunan agar
kontekstual
dengan sekitarnya.
Teori yang
dipilih
merupakan
tatanan
proporsi
yang
umum
digunakan
perencana bangunan pada masa lalu, yaitu golden section.
Euclid, seorang ahli matematika Yunani, pada sekitar tahun 300
SM menulis Elements, sebuah kumpulan dari 13 buku mengenai geometri.
Dalam Buku 6,
Proposisi 30, Euclid menunjukkan
bagaimana membagi
sebuah
garis
dalam
rasio
nilai
tengah
dan
nilai
ujung.
Berikut
penggambaran Euclid secara geometris.
Euclid
untuk
menunjukkan bahwa perbandingan antara bagian
yang lebih kecil dari sebuah garis, GB terhadap bagian yang lebih besar
AG
(GB/AG)
adalah
SAMA
dengan
perbandingan
antara
bagian
yang
lebih besar, AG, terhadap keseluruhan panjang garis AB
(AG/AB). Beri
panjang AB nilai 1, sementara panjang AG diberi nilai g sehingga menjadi
Bila disusun ulang secara aljabar menjadi g
2
=
1–g atau g²
+g=1,
berkaitan dengan definisi Phi²
=
Phi+1.
Banyak analisa
menyimpulkan
bahwa
Parthenon dan
Pantheon
dirancang
menggunakan
golden
section
(sekitar
500
SM).
Namun
tidak
|
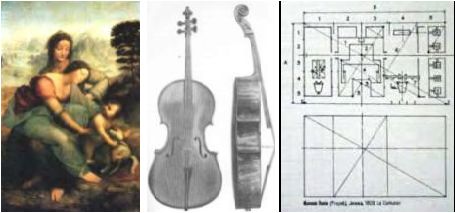 35
ada yang tersisa
dari gambar-gambar
rancangan arsitek Yunani untuk
bangunan tersebut. Sehingga tidak diketahui apakah
mereka benar-benar
menggunakan golden section dalam perancangan.
Theano of
Thurii
(500
SM),
istri Phytagoras diasumsi
pernah
menulis
buku
Teorem
of
Golden
Mean.
Nama
golden
section
kemungkinan pertama digunakan Martin Ohm dalam bukunya (1835). Ada
pendapat
lain
menyatakan
Leonardo
da
Vinci
(1412-1519) adalah
yang
pertama menggunakan nama section aurea (bahasa Latin golden section).
Leonardo
da Vinci
banyak
menerapkan
golden
section
dalam
lukisan dan sketsa-sketsanya. Dalam dunia arsitektur yang
lebih
modern,
Le Corbusier menerapkan golden section dalam rancangannya, antara lain
Museum Dunia dan Villa Garches. Selain dalam arsitektur, golden section
dipakai dalam berbagai cabang seni dari
musik,
puisi,
hingga film.
Stradivari juga menggunakan rasio ini utuk menentukan letak f-hole pada
biola Stradivarius.
Gambar II.1.6.4 ©ontoh ka®ya seni yang mene®apkan ®asio golden section
Sumber : Google image search; Bentuk, Ruang, dan Tatanan
|
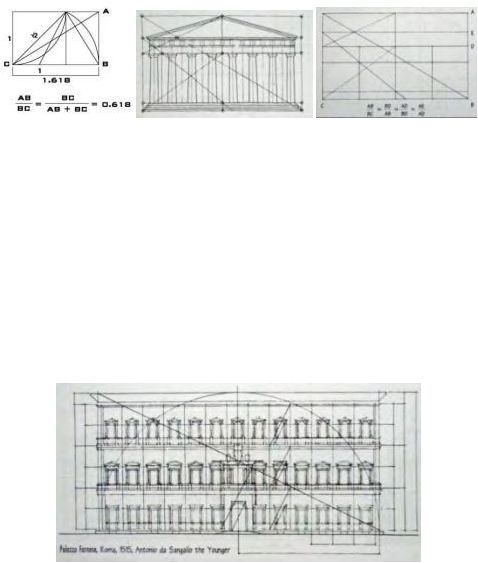 36
Golden
section adalah
pembagian
sebuah
garis
menjadi
dua
sehingga rasio antara bagian yang lebih panjang terhadap keseluruhan
sama dengan rasio antara bagian yang lebih pendek terhadap bagian yang
lebih panjang (sekitar 1:1.618); perancangan berdasarkan tatanan ini
disebut memiliki komposisi yang baik. (Davies, 2008, p 642)
Gambar II.1.6.5 ©ontoh terapan golden section pada fasad
Sumber : Bentuk, Ruang, dan Tatanan
Selain
aturan
perbandingan
panjang,
dalam golden
section
juga
dibahas
ketentuan
mengenai
garis
pengatur.
Jika
diagonal-diagonal
dari
dua
persegi panjang
saling
sejajar
atau tegak
lurus
satu sama
lain,
akan
menunjukkan bahwa kedua persegi panjang tersebut mempunyai proporsi
yang serupa. Diagonal-diagonal ini disebut juga garis pengatur.
Gambar II.1.6.6 Garis-garis pengatur fasad
Sumber : Bentuk, Ruang, dan Tatanan
|
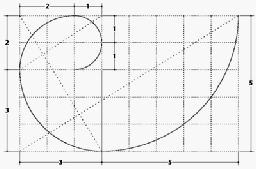 37
Dari arsitek dan ahli matematika yang melakukan observasi
terhadap golden section, ditemukan hal-hal menarik lain yang terkait
golden section. Salah satunya deret Fibonacci yang dapat digambarkan
menjadi spiral Fibonacci.
Deret Fibonacci : deret angka dimana
tiap
angka
selanjutnya
merupakan penjumlahan dari dua angka di depannya (2,3,5,8,13,21, dst.),
yang dinamakan mengikuti nama ahli matematika Tuscan Leonardo
Fibonacci
(c. 1170-1230),
yang
menemukan bahwa dalam deret tersebut,
rasio antara dua angka yang bersebelahan cenderung menyerupai golden
section (1 : 1.618). (Davies dan Jokiniemi, 2008, p 640)
Spiral
Fibonacci
adalah
sebuah
spiral
yang terbentuk dari
gabungan lengkung seperempat lingkaran
yang terus bertambah besar
sesuai angka-angka dalam deret Fibonacci.
Gambar II.1.6.7
Spiral Fibonacci
Sumber : Dictionary of Architecture and Building Construction
3. Pendekatan Experiental Landscape
Pendekatan arsitektur kontekstual tidak
terbatas
pada
tampilan
fisik bangunan, tetapi dapat dilakukan juga dengan menerapkan teori
|
|
38
untuk menganalisa kesesuaian bangunan dengan lingkungan sekitar baik
karakter yang bersifat fisik maupun nonfisik. Salah satunya
experiental
landscape (saujana pengalaman) yang menganalisa fungsi dan karakter
suatu tempat serta hubungan antara satu tempat dengan yang lain.
Konsep
experiental
landscape
mengkategorikan
sebuah
tempat
ke dalam empat elemen
:
C-center (pusat), D-direction (arah, tujuan), T-
transition (batas), dan A-area, masing-masing dibagi lagi menurut fungsi
dan
karakter
yang
lebih
spesifik,
misalnya center – pusat
–
dapat
dibedakan
menjadi
pusat
yang
berkarakter social
imageability,
social
interaction, atau restorative benefit tergantung pada elemen apa saja yang
membentuk pusat tersebut dan sekitarnya.
4. Revitalisasi Kawasan
Revitalisasi berarti
upaya untuk
menghidupkan kembali sebuah
distrik/kawasan kota yang telah mengalami
degradasi melalui intervensi
fisik dan nir-fisik (sosial dan ekonomi). Keberhasilan revitalisasi sebuah
kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik,
bukan sekedar menciptakan beautiful place. Harus berdampak positif serta
dapat
meningkatkan
dinamika
dan
kehidupan sosial
masyarakat
dan
warga. (Martokusumo, 2005, pp III-12 dan III-16)
Merujuk pada tulisan Arkeolog Djauhari Sumintardja (2009), arti
revitalisasi kawasan perkotaan adalah upaya untuk mencegah hilangnya
asset-aset kota yang
menandai rangkaian riwayat panjang perjalanan kota
beserta masyarakat di dalamnya. Penataan dan revitalisasi kawasan tidak
|
|
39
hanya mencakup masalah konservasi kawasan kota lama (urban heritage),
tetapi lebih sebagai upaya mengembalikan kawasan-kawasan strategis di
perkotaan yang mengalami penurunan vitalitas. Variabel pemilihan
kawasan dapat berupa variabel vitalitas ekonomi dan nonekonomi.
5. Istilah-istilah Konservasi
Berikut
beberapa
definisi
istilah
dalam kegiatan
konservasi
bangunan
menurut
piagam-piagam
ICOMOS
(International
Council of
Monument
and Site). Diharapkan salah tafsir makna istilah-istilah
konservasi
secara
global
yang mungkin
disebabkan
perbedaan
bahasa
antarnegara dapat dihindari. Definisi yang dicantumkan dibatasi pada
poin-poin konservasi yang diterapkan dalam proyek.
• Adaptasi
Disebut juga pemanfaatan kembali secara adaptif. Mengubah
bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru seringkali merupakan
cara agar bangunan bersejarah dapat tetap bermanfaat, perlu
diperhatikan kesesuaian fungsi baru dengan selubung eksisting.
• Konservasi
The Burra Charter (1999) mendefinisikan konservasi sebagai
semua proses pemeliharaan yang dilakukan pada suatu tempat untuk
mempertahankan makna
budayanya. Konservasi
meliputi
perawatan
dan tergantung keadaannya dapat meliputi preservasi, restorasi,
|
|
40
rekonstruksi, dan adaptasi; dan pada umumnya merupakan gabungan
lebih dari satu upaya.
•
Preservasi
Mempertahankan sebuah bangunan dalam bentuk dan kondisi
aslinya dan melakukan perawatan sejauh itu perlu.
•
Restorasi
Restorasi adalah mengembalikan bangunan atau bagian-
bagiannya kepada bentuk tampilannya di satu waktu pada
masa
lampau.
Saat
restorasi
perlu
dilakukan, sangat penting bahwa setiap
intervensi didasari bukti otentik.
(Orbasli, 2008, pp46-50)
6. Teori Pokok Perancangan Kota
Bila
berbicara
mengenai
revitalisasi
kawasan, tidak
dapat
terlepas dari konteksnya sebagai bagian dari tata ruang perkotaan. Selain
itu, kontekstualitas suatu bangunan terhadap kawasan sekitarnya berarti
kontekstual terhadap elemen dan pola ruang kota, tidak hanya terhadap
bangunan fisik dan langgam arsitekturnya.
•
Figure / Ground
Inti teori
ini adalah hubungan antara bentuk
yang dibangun
(building mass/figure) dan ruang terbuka (open space/ground).
|
 41
Gambar II.1.6.8 Figure/g®ound
Sumber : Perancangan Kota Secara Terpadu
•
Linkage
Teori linkage menegaskan hubungan-hubungan dan gerakan-
gerakan
(dinamika)
sebuah
tata ruang perkotaan, sebagai
komplementer bagi teori figure/ground yang cenderung bersifat dua
dimensi dan relatif statis.
Gambar II.1.6.9 Linkage
Sumber : Perancangan Kota Secara Terpadu
•
Place
Teori place menyoroti keterkaitan sejarah, budaya, dan
sosialisasinya.
Menekankan
pada
makna sebuah kawasan sebagai suatu
tempat perkotaan secara arsitektural.
|
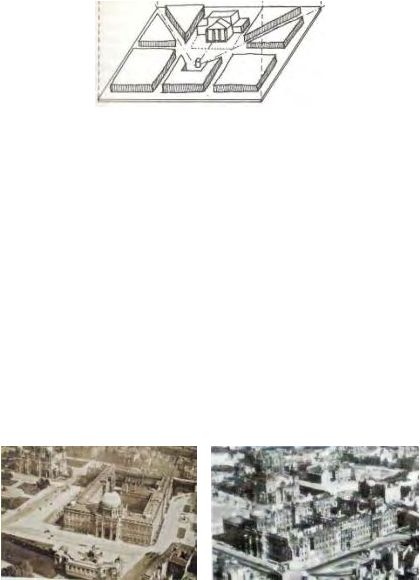 42
Gambar II.1.6.10 Place
Sumber : Perancangan Kota Secara Terpadu
II.1.7
Studi Proyek dengan Topik dan Tema yang Sama
1. Rekonstruksi Berlin Palace
Rekonstruksi
Berlin
Palace
dan penambahan
gedung
sayapnya
yang
bergaya
kontemporer
dijadikan sebagai
studi
konsep
arsitektur
kontekstual. Berlin Palace merupakan hasil perluasan pada tahun 1699 dari
rumah keluarga kerajaan zaman Barok. Bangunan ini mengalami
kerusakan parah selama Perang Dunia II dan diruntuhkan pada 1950-51.
Gambar II.1.7.1 Berlin Pala©e sebelum dan sesudah Perang Dunia II
Sumber : The Architecture of Democracy
Masyarakat kemudian mengharapkan bangunan ini untuk
dibangun kembali. Kompetisi internasional diadakan, dan dimenangkan
oleh biro arsitek Italia Francesco Stella Architects yang kemudian mulai
mengerjakan rekonstruksi pada 2007.
|
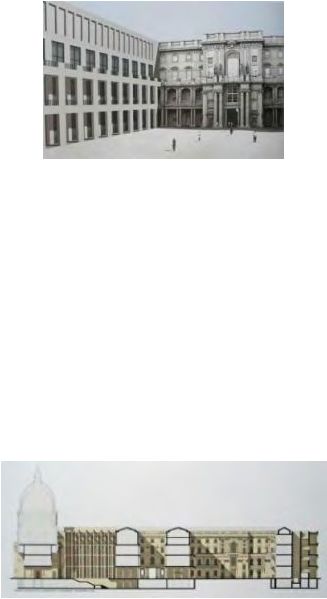 43
Gambar II.1.7.2 View bangunan rekonst®uksi dan tambahan konstruksi baru
Sumber : The Architecture of Democracy
Pada gambar terlihat bangunan di sebelah kanan adalah bangunan
asli
dari
abad
pertengahan
yang direkonstruksi,
sedangkan
bangunan
sebelah kiri merupakan penambahan bagian sayap bergaya kontemporer
yang disebut sayap Apotheker pada sisi timur.
Tiga sisi bergaya Barok dan satu sisi bergaya kontemporer
mengelilingi halaman tengah yang disebut Schluterhof/historic courtyard.
Gambar II.1.7.3 Potongan facade gaya Barok yang direkonstruksi sesuai aslinya
Sumber : The Architecture of Democracy
Mengikuti salah satu kriteria kompetisi, keseluruhan proyek
harus memperlihatkan hubungan dengan desain kawasan yang bernilai
historis. Bangunan baru yang ditambahkan harus berkaitan dengan bentuk
asli Palace
yaitu kotak/cubic form. Mengikuti aturan
ini, Stell
mengolah
|
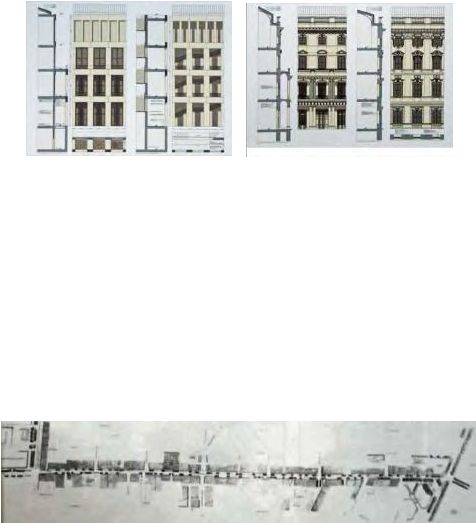 44
façade sisi timur dengan gaya geometris kontemporer tanpa ornamen,
dengan garis-garis utama – jendela, pintu, atap – mengikuti bangunan asli.
Gambar II.1.7.4 Harmonisasi garis pembentuk facade bangunan baru dan asli
Sumber : The Architecture of Democracy
Dari studi ini, penyusun memperoleh contoh penerapan arsitektur
kontekstual dengan pendekatan harmonis
yang
mengambil
garis-garis
bangunan lama untuk panduan olahan façade bangunan baru, tanpa meniru
atau mereplikasi bentuk dan ornamen pada bangunan lama.
2. Revitalisasi dan Konservasi Joo Chiat Singapura
Gambar II.1.7.5 Site Plan Desain Usulan
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
Penyusun mengambil studi ini sebagai contoh kasus revitalisasi
kawasan yang sudah dilaksanakan secara serius dengan program-program
yang
terencana
matang,
serta
solusi permsalahan
yang
dapat
dijadikan
acuan.
Tujuan
revitalisasi
ini adalah
untuk
menguatkan
karakter
tempat
|
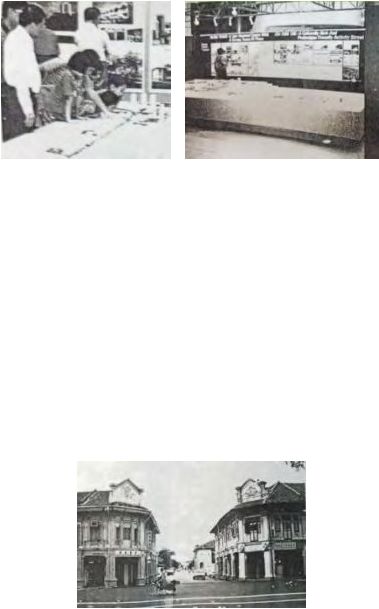 45
dan mengembalikannya menjadi kawasan yang hidup dan aktif.
Masyarakat diajak terlibat melalui pameran dan dialog publik.
Gambar II.1.7.6 Pameran maket dan panel untuk publik
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
Kawasan Joo Chiat membentang sepanjang jalan bernama
serupa,
membentuk
koridor
yang
menghubungkan
dua
pusat
komersial
:Geylang East –
kios makanan dan pasar dengan Marine Parade –
pusat
komersial dengan view ke arah East Coast Park dan Selat Singapura. Jalan
ini sendiri aktif dengan adanya usaha penjualan makanan, bunga, dan
bumbu-bumbu.
Gambar II.1.7.7 Gaya arsitektur khas dapat dijumpai di Jalan Joo Chiat
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
Pokok-pokok
revitalisasi
Jalan Joo
Chiat
terbagi
menjadi
lima
poin utama:
|
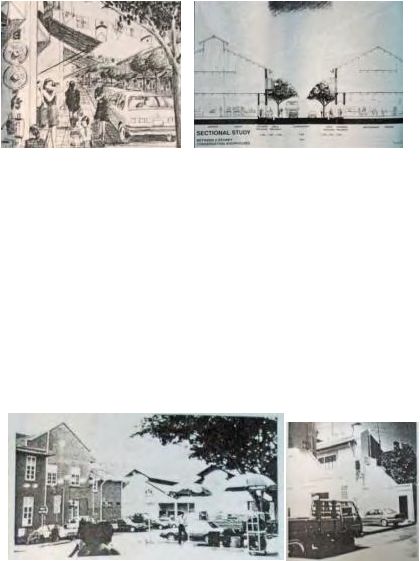 46
1. Jaringan pedestrian
Aplikasinya
adalah
menempatkan
sistem
pedestrian
yang
terlindungi
di sepanjang Jalan Joo Chiat. Studi potongan dilakukan untuk
menggambarkan hubungan antara bangunan, pedestrian, dan jalan.
Gambar II.1.7.8 Sketsa suasana dan studi potongan sistem pedestrian
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
2. Akses kendaraan
Aplikasinya adalah dengan memperluas lahan khusus kendaraan servis
untuk bongkar muat barang sehingga tidak mengganggu pandangan ke
bangunan. Juga disediakan area parkir yang sudah tetap agar tidak ada
lagi kendaraan yang parkir sembarangan.
Gambar II.1.7.9 Penyediaan area pa®kir dan area khusus kendaraan servis
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
|
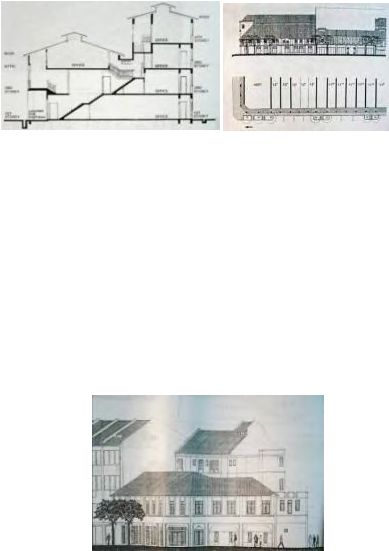 47
3. Bentuk bangunan
Permasalahan yang ditemui adalah variasi GSB, ketinggian, dan
selubung bangunan. Aplikasi desain yang dilakukan yaitu memastikan
bangunan
baru
(infill)
dapat
meningkatkan
tampilan
sepanjang
Jalan
Joo Chiat dengan penerapan aturan semacam guidelines.
Gambar II.1.7.10 Potongan tipikal bangunan dan ©ontoh penerapan infill
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
4. Roofscape
Permasalahan
yang
ditemui
adalah roofscape
yang
tidak
konsisten.
Aplikasi desain adalah dengan mengupayakan terciptanya roofscape
yang dapat menunjang karakter eksistng, bentuk, skala, dan material
bangunan di sepanjang jalan.
Gambar II.1.7.11 Atap bangunan empat lantai menunjang tampilan atap dua lantai
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
|
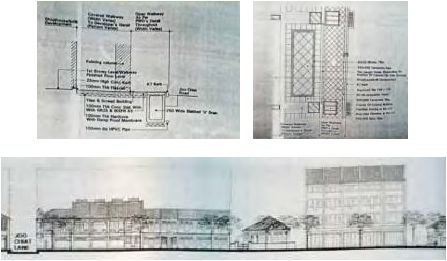 48
5. Streetscape
Permasalahan utama yang ditemui adalah kurangnya penghhijauan dan
tatanan lansekap di sepanjang
jalan. Solusinya dengan
menanam
pohon
pada
jarak
yang
teratur
dan
mengaplikasikan
paving sebagai
finishing badan jalan.
Gambar II.1.7.12 Detail aplikasi paving pada badan jalan dan simulasi streetscape
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
Sebagai salah satu upaya melibatkan peran warga, dibentuk
rangkuman
aturan
mengenai
apa
yang harus
dan
tidak
boleh
dilakukan
(Do’s and Don’ts) untuk meningkatkan
tampilan dan kinerja
kawasan.
Misalnya
perletakan
AC tersembunyi
dari
pandangan
sangat
dianjurkan,
sementara tidak
diperbolehkan
bila barang-barang
yang
dipajang
di
toko
menyebar ke pedestrian hingga mengganggu jalur pedestrian.
|
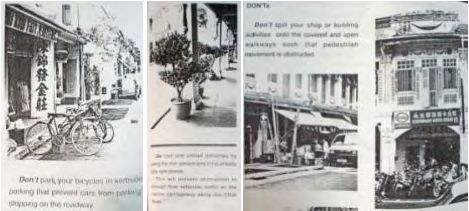 49
Gambar II.1.7.13 DO’s and DON’Ts
Sumber : Enhancing the Charms of Joo Chiat
II.2
Tinjauan Khusus
II.2.1
Sejarah dan Perkembangan Fisik Kota Tua Jakarta
Sejarah sebagai potensi terbesar Kota Tua
merupakan tema general
yang akan mendasari setiap perancangan yang dilakukan di kawasan ini.
Apresiasi kesejarahan kawasan diharapkan
dapat
dimulai
dari
menghayati
sejarah perkembangannya. Melalui penafsiran sejarah dan apresiasi kritis
terhadap
warisan
budaya
urban
ini, diharapkan
komunitas
semakin
mampu
menghargai eksistensi warisan budaya. (Martokusumo, 2005, pIII-17). Berikut
uraian singkat sejarah dan perkembangan fisik kawasan Kota Tua Jakarta.
Nama
tertua Jakarta adalah Sunda Kalapa, sebuah pelabuhan dari
kerajaan
Pakuan Pajajaran
yang
masih dikuasai seorang raja Hindu
hingga
1522. Pasukan Fatahillah dan pasukan-pasukan lain berhasil mempertahankan
Sunda Kalapa dari pendudukan bangsa asing, termasuk Portugis. Hubungan
niaga dengan bangsa-bangsa asing tetap berjalan baik.
|
|
50
Berdasarkan sumber dokumen, nama Jayakarta mulai digunakan
pada
1560,
tapi
sebutan
Sunda
Kalapa
masih
belum hilang,
sehingga
sulit
ditentukan kapan tepatnya nama Jayakarta mulai menggantikan Sunda Kalapa.
Belanda pertama kali masuk pelabuhan Jayakarta pada 13 November
1596.
Sejak saat
itu
kapal-kapal
Belanda
mulai
singgah
di
Pelabuhan
Jayakarta. Armada Belanda yang dipimpin Cornelis Matelief de Jonge singgah
di Jayakarta pada 1607. Ia mengusulkan pendirian VOC di Asia, di Jayakarta,
yang mesti menjadi sebuah kota Belanda. Perjanjian Pangeran Jayakarta-VOC
menghasilkan beberapa keputusan penting,
salah satunya penjualan sebidang
tanah di sebelah timur
mulut Ciliwung seluas 50 x 50 depa yang menjadi
pijakan pertama VOC di Pulau Jawa dan cikal bakal Batavia.
J.P. Coen merebut Jayakarta pada 30 Mei 1619. Namanya diganti
menjadi Batavia, dan peran bandar ini semakin meningkat sebagai pusat
politik dan ekonomi. Benteng
VOC pertama dibangun pada 1618, dan pada
1628 dibangun benteng kedua seluas 9 kali benteng pertama untuk
menampung semua aktivitas dagang, dengan empat bastion di sudut-sudutnya.
Kota Batavia dirancang dan dibangun dengan pola kotak-kotak yang
dibentuk kanal-kanal melintang dan membujur tegak lurus. Pengkaplingan
kota juga berkotak-kotak, dibentuk oleh jalan-jalan. Sungai Ciliwung
kemudian diluruskan, membelah kota menjadi dua di timur dan barat. Pola
penataan kota berbentuk grid ini dianggap sebagai perencanaan kota modern
yang sudah maju pada zamannya, berlatar efisiensi pengolahan lingkungan.
|
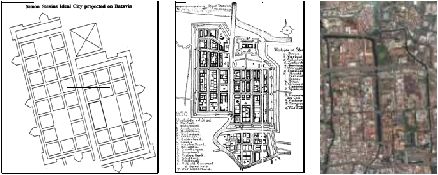 51
Gambar II.1.1.1 Pola grid Kota Tua sebagai salah satu bentukan fisik sejarah
Sumber : Presentasi Deputi Gubernur DKI Bidang Budpar : Jakarta (Bangga) Punya Kota Tua
Batavia kemudian disebut Ratu dari Timur karena keindahan alam
dan kemewahan permukimannya. Kota dibangun menyerupai Amsterdam
abad XVII. Batavia pada masa ini merupakan pusat perdagangan ramai. Tata
kota teratur rapi, di tepian kanal dan parit kota ditanami pepohonan rindang, di
tepian air kemudian dibangun rumah dan gedung, dihuni warga Belanda.
Kanal-kanal di Batavia menarik para imigran Cina dan Eropa untuk
bermukim di daerah sepanjang alirannya. Namun tumbuhnya populasi Cina di
Batavia dan kota-kota pesisir Jawa lain
menimbulkan
reaksi keras dari
Belanda. Peraturan imigrasi Belanda untuk membatasi populasi Cina berujung
pada
meletusnya pemberontakan orang-orang
Cina pada
tahun
1740.
5000
orang
Cina
dibunuh
di
halaman
belakang
balai
kota
dan
rumah-rumahnya
dibakar. Setelahnya, orang-orang Cina pindah ke selatan, keluar tembok kota.
Permukiman
mereka
berkembang
menjadi
Chine Kwartier atau Kampung
Cina, daerah yang kita kenal sebagai pecinan saat ini.
Sejak pembunuhan massal tersebut, wajah VOC menjadi buruk.
Situasi diperburuk dengan meluasnya wabah malaria, pes, dan kolera di muara
|
|
52
Sungai Ciliwung dan sekitarnya. Parit yang digali tak mampu lagi
menampung luapan air dari rawa-rawa, penuh endapan lumpur, tersumbat dan
berbau busuk, menjadi sumber penyakit. Pembangunan kota yang tidak
memperhitungkan iklim tropis juga membawa dampak buruk bagi
penduduknya baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan.
Sejak 1730-an hingga akhir abad
ke-18, di Batavia terjadi
perpindahan besar-besaran ke daerah yang lebih tinggi dan lebih jauh dari
rawa-rawa;
yaitu
Weltevreden
yang dibatasi Jalan Dr.
Soetomo,
Gunung
Sahari, Pasar Senen; dan Molenvliet – Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk.
Pada 1791 negeri Belanda jatuh ke
tangan Perancis dan menjadi
negara
kesatuan.
Pada
1799
VOC dibubarkan. 1807, Daendels diangkat
menjadi
Gubernur
Jenderal
dengan
salah satu tugasnya untuk memperbaiki
kesehatan kota. Kota lama yang disebut juga kota bawah yang berada dalam
tembok ditinggalkan. Bangunan-bangunan dirombak dan digusur. Parit-parit
ditimbun untuk meniadakan sumber penyakit, digantikan jalan-jalan darat.
Pusat pemerintahan ikut berpindah ke daerah selatan, kawasan
Weltevreden yang disebut sebagai “kota atas” dengan pusatnya di sekitar
Waterlooplein
(Lapangan
Banteng),
dan
hal
ini
berlanjut
hingga
sekarang.
Kota
lama
kemudian
menjadi downtown
yang
berfungsi
sebagai
pusat
perdagangan, jasa, dan pelabuhan kapal-kapal kecil.
Setelah Inggris menang atas Perancis, kekuasaan atas Indonesia pun
berpindah ke tangan Inggris. Pada 1811, Thomas Stanford Raffles diangkat
sebagai Gubernur Jenderal. Setelah kekuasaan Inggris berakhir, pembangunan
|
|
53
Batavia dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Paruh abad XIX
merupakan
periode
kedamaian
dalam sejarah
Batavia,
ditandai
dengan
pemerintahan stabil, perluasan ekonomi dan usaha, serta pembangunan dan
pengadaan infrastruktur seperti tramway.
Kota Batavia sejak 1920-an cenderung berkembang menjadi kota
modern. Banyak bangunan asli abad XIX, bercampur dengan yang dirombak
menjadi modern sesuai perkembangan arsitektur di Eropa abad XX. Coraknya
eklektik. Ada yang menggunakan menara dan kubah model Byzantium, hiasan
model Art Deco, dan model khas arsitektur Belanda yang bercampur elemen
bangunan tropikal.
Namun keadaan kota lama yang sekarang kita kenal dengan nama
Kota Tua sudah banyak berubah. Kota lama
ditinggalkan
karena
terjadi
perpindahan ke pusat-pusat lain yang tersebar di seluruh Kota Jakarta.
Saat ini bangunan-bangunan di kawasan Kota Tua dapat dibagi
menjadi lima kategori : sudah musnah atau berganti bangunan baru, hampir
musnah atau
mulai runtuh,
utuh
namun
kosong
tidak
terpelihara
dan
tidak
lama akan mulai runtuh, masih cukup baik namun tidak digunakan; dan ada
pula dalam jumlah terbatas yang masih baik, terpelihara, dan digunakan.
II.2.2
Peraturan Bangunan di Kota Tua Jakarta
Peraturan bangunan di Kota
Tua terangkum dalam peraturan khusus
yang
disusun
oleh
Unit
Penataan
Teknis
yang
berkantor
di
Museum
Fatahillah. Peraturan ini berlaku bersama peraturan lain seperti Undang-
undang dan SK Gubernur yang mengatur penentuan, pemugaran/
|
 54
pemeliharaan, dan pemanfaatan benda dan bangunan cagar budaya. Peraturan
yang terkait dengan kawasan Kota Tua dan bangunan cagar budaya cukup
banyak dan detil. Maka pada bahasan ini
akan
dicantumkan
ketentuan
yang
paling utama saja dan dipersempit wilayahnya sebatas tapak terpilih.
Upaya
pelestarian
di
Jakarta
didasarkan
kepada
UU
No.
5
tahun
1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan
Daerah No. 9 tahun 1999,
yang menggolongkan kawasan cagar budaya menjadi 3 golongan : kawasan
cagar budaya golongan I-III, dan menggolongkan bangunan cagar budaya
menjadi 3 golongan : bangunan cagar budaya golongan A, B, dan C.
Berdasarkan
Rencana Induk Kotatua
Jakarta (Dinas Tata Kota,
2007), di tengah-tengah Kawasan Cagar Budaya Kota Tua terdapat zona inti,
yaitu
area
yang
memiliki
nilai
sejarah
yang
lebih
bernilai, yang
dahulunya
sebagian besar adalah kota di dalam dinding. Kawasan Cagar Budaya Kotatua
dibagi
menjadi 5 (lima)
zona yaitu kawasan Sunda Kelapa, Fatahillah,
Pecinan, Pekojan, dan Peremajaan.
Gambar II.2.2.1 Peta selu®uh kawasan Kota Tua dan Zona Inti seluas 87 Ha
Sumber : Guidelines Kotatua dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemprov DKI Jakarta
|
 55
Tapak terpilih
terletak di dalam
zona
inti
yaitu
zona
2
atau
zona
Fatahillah,
tepatnya
di blok utara jalan Kali Besar
Timur bagian utara.
Menurut
guidelines,
pada tapak
ini terdaftar
satu bangunan
cagar
budaya
golongan B. Dari
survey
tapak,
didapati bahwa nilai
sejarah
dan
arsitektur
bangunan
di
sepanjang Jalan
Kali
Besar Timur
bagian
utara ternyata
tidak
terlalu
terjaga dibanding bagian
selatan.
Banyak bangunan yang sudah
dirombak atau dihancurkan dan diganti dengan bangunan-bangunan baru.
Gambar II.2.2.2 Bangunan sekitar tapak yang tidak kontekstual dengan kawasan
Sumber : Dokumentasi pribadi
Penyusun
memilih
tapak
ini dengan
konsekuensi mempertahankan
façade dan selubung bangunan yang memang harus dipertahankan. Penyusun
mendata
setiap bangunan
yang
ada di tapak, menyusun
gambaran
façade
eksisting dan
membandingkannya
dengan
data
foto/lukisan/gambar otentik
yang menunjukkan kondisi asli pada
masa setidaknya 50 tahun
silam.
Data
yang
ada
kemudian
dianalisa
untuk
memutuskan
mana
yang
harus
dipertahankan dan mana yang dapat dibongkar/dipugar atau dibangun kembali
baik sesuai kondisi asli sebelum diganti.
Merujuk
pada
Guidelines
Kotatua
(2007),
beberapa
ketentuan
pembangunan yang berlaku di tapak terpilih antara lain :
|
|
56
•
Intensitas bangunan atau koefisien lantai bangunan
mengacu kepada
aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota
•
Pemanfaatan intensitas bangunan di kavling bangunan cagar budaya
Golongan A dimungkinkan sebatas
tidak merubah tampak, selubung
bangunan, dan interior bangunan yang dilestarikan
•
Untuk memenuhi ketentuan butir (2),
luas lantai total bangunan cagar
budaya Golongan A beserta bangunan tambahannya merupakan resultante
dari luas lantai asli/eksisting, serta penambahan lantai bangunan di luar
masa bangunan asli dengan nilai tidak melebihi ketentuan KLB yang
dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota
•
Pemanfaatan intensitas bangunan di kavling bangunan cagar budaya
Golongan
B
dan C dimungkinkan sebatas tidak merubah
masa bangunan
yang dilestarikan. Pada Golongan B, tampak dan selubung bangunan
dipertahankan,
sedangkan bagian dalamnya diperbolehkan berubah,
kecuali
bagian interior yang penting. Pada Golongan C, façade
bangunannya saja yang harus dipertahankan.
•
Untuk memenuhi ketentuan butir (4),
luas lantai total bangunan cagar
budaya Golongan B dan C merupakan resultante dari
luas lantai di dalam
masa bangunan asli/eksisting, serta penambahan lantai bangunan di luar
masa bangunan asli dengan nilai tidak melebihi ketentuan KLB oleh DTK
•
Pada bangunan cagar budaya Golongan A, B, dan C, sebagai akibat tidak
dapat dimanfaatkannya secara penuh KLB maksimal yang ditetapkan oleh
|
|
57
Dinas Tata Kota, maka sebagai kompensasi diterapkan prinsip alih
intensitas (Transfer of Development Right) sebagaimana diatur oleh Dinas
Tata Kota
•
Untuk kavling dengan bangunan bukan bangunan cagar budaya, nilai KLB
sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota
Dalam mengadakan
pemugaran
dan
penambahan
bangunan
baru,
Penyusun akan merujuk pada Peraturan DKI Jakarta No. 9 Tahun 1999
tentang
Pelestarian
dan
Pemanfaatan
Lingkungan
dan
Bangunan Cagar
Budaya dan Guidelines Kotatua. Beberapa ketentuan umum mengenai
penambahan bangunan baru antara lain :
•
Letaknya tersembunyi dari sisi depan jalan bangunan eksisting.
•
Terpisah dengan bangunan asli dengan
jarak minimal 3
(tiga)
meter dari
tampak belakang bangunan asli.
•
Menghargai
bentuk,
ukuran,
proporsi
dan
material
bangunan
asli
tanpa
harus meniru gaya bangunan asli
•
Dirancang dengan gaya sederhana dan tidak mencolok sehingga tidak
bersaing dengan bangunan asli
•
Perubahan
dan
penambahan
yang
dilakukan
secara
visual
tidak
tampak
atau tidak berpotensi untuk tampak dari sisi jalan dan ketinggiannya tidak
melebihi ujung atap bangunan asli
•
Bangunan tambahan dapat dihubungkan dengan bangunan asli dengan
selasar, lebar maksimal 3 meter dan tidak merusak arsitektur bangunan asli
|
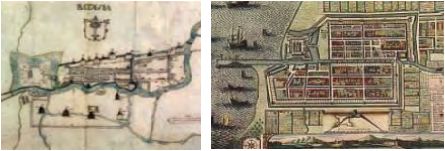 58
•
Upaya
rehabilitasi
dan
revitalisasi
melalui
perubahan
tata
ruang
dalam
diperbolehkan untuk bangunan golongan B selama tidak merubah struktur
yang utuh dengan bangunan utama (sesuai Perda No. 9/ 1999 ps. 20)
•
Perubahan
tata ruang
dalam
bangunan
golongan
B
tidak berlaku
bagi
ruang yang
harus dilestarikan seperti
lobby dan hall utama, serta ruang-
ruang lain yang merupakan bagian arsitektur yang penting dari bangunan
yang bersangkutan.
II.2.3
Sejarah Kawasan Kali Besar
Kali
Besar
adalah ‘jantung’ Batavia, satu
fragmen dari
Sungai
Ciliwung yang
dipilih
Belanda sebagai
lahan
untuk
mendirikan kota. Kali
Besar memiliki
peranan
penting
dalam sejarah
Batavia selama tiga abad.
Sungai
ini diluruskan pada 1631 dan
1632
atas perintah
Gubernur
Jenderal
Jacques Specx untuk mewadahi aktivitas perkapalan.
Gambar II.2.3.1 Kali Besar sebelum dan sesudah diluruskan pada 1631-1632
Sumber : Koleksi Mahandis Yoanata
Pada abad 17 dan 18, di sepanjang tepi Kali Besar berdiri bangunan
yang bervariasi : gudang, rumah-rumah mewah,
gereja, dan pasar. Awalnya
|
 59
warga Eropa dan Cina tinggal di sepanjang Kali Besar, tapi setelah peristiwa
1740, warga Cina dilarang tinggal di dalam tembok kota.
Gambar II.2.3.2 Portugeesche Kerk dan Pembantaian 1740
Sumber : Koleksi Mahandis Yoanata
Paruh
akhir abad ke-19, gereja dan pasar
tidak ada
lagi, Kali Besar
menjadi pusat bisnis dan perdagangan berkarakter dominan Eropa. Perubahan
yang terjadi pada Kali Besar salah satunya dipicu pengesahan Hukum Agraria
di Belanda pada 1870 yang mengakhiri
sistem kultivasi yang diterapkan
pemerintah dan mengizinkan pengembangan perusahaan pribadi atau swasta.
Dampaknya adalah pertambuhan pesat jumlah bank, perusahaan
dagang, agen perkapalan, broker asuransi, dan usaha dagang yang berlokasi di
kawasan Kali Besar. Ekspor gula dan
kopi
yang
mendominasi
perdagangan
Batavia pada 1870-1880 banyak ditangani perusahaan di kawasan ini.
Pada 1900-an, perusahaan-perusahaan secara bertahap memindahkan
kantor
pusatnya
ke
Molenvliet
(Jalan
Gajah
Mada-Hayam Wuruk)
dan
sepanjang Noordwijk (Jalan Juanda) dan Rijswijk (Jalan Veteran).
|
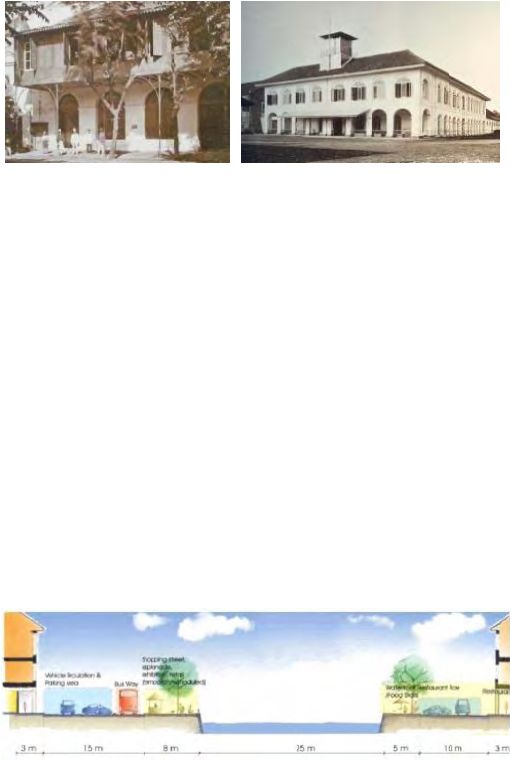 60
Gambar II.2.3.3 : Kanto®-kanto® dagang di Kali Besar
Sumber : Koleksi Mahandis Yoanata
II.2.4
Masa Lalu-Masa Kini-Masa Depan Kawasan Kali Besar
Mengacu
pada
guidelines
Kota
Tua
pada
subbab
Pelestarian
dan
Pemanfaatan
Ruang-ruang
Kota
Cagar
Budaya,
ruang
terbuka
disepanjang
Kali Besar bagian utara harus diolah sebagai berikut :
Sepanjang Kali
Besar
Timur Utara
difungsikan
sebagai
ruang
terbuka aktif dalam bentuk kaki lima tepi air (waterfront food stalls). Tempat-
tempat makan ini dapat terpisah atau
menjadi bagian perluasan dari restoran
dan tempat makan yang ada pada lantai
dasar bangunan-bangunan
yang
menghadap
Kali Besar. Area ini juga berfungsi sebagai jalur pedestrian,
tempat parkir, dan sirkulasi kendaraan bermotor terbatas.
Gambar II.2.4.1 Pemanfaatan ruang te®buka di sepanjang Kali Besar
|
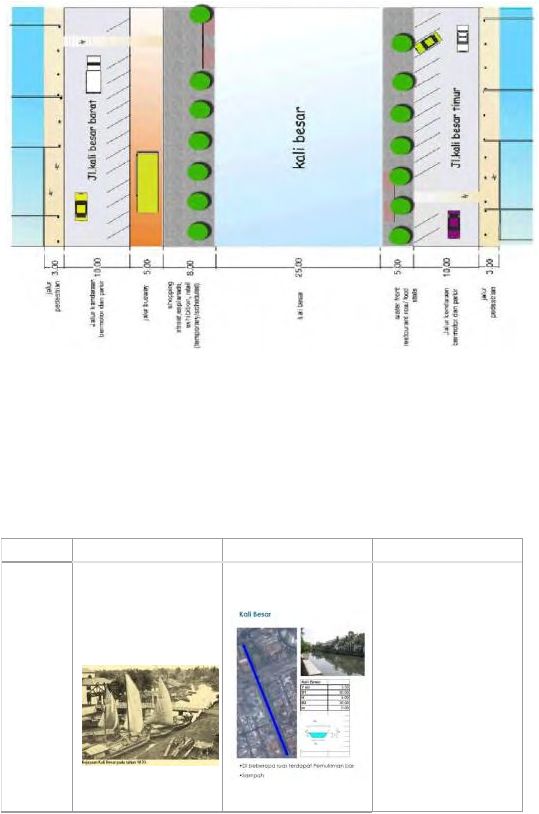 61
Sumber : Guidelines Kotatua dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemprov DKI Jakarta
Berikut perkembangan kawasan Kota Tua, khususnya daerah sekitar
tepi Kali Besar, dikemukakan dalam tabel sebagai batasan sekaligus pedoman
perencanaan dan perancangan :
Tabel II.2.4.1 Tinjauan masa lalu, masa kini, dan masa depan kawasan Kali Besar
Masa Lalu/Sejarah
Realitas/Masa Kini
Rencana Masa Depan
Peruntukan/
fungsi sungai
Aktivitas kapal-kapal
dagang/kapal barang, sirkulasi
air
Tidak berfungsi
Menghadirkan kembali peran
elemen lingkungan ‘air’
termasuk ‘waterfront’ dalam
pengembangan kawasan,
memperbaiki
infrastruktur tata
air, meningkatkan kualitas air
melalui program kali bersih,
meningkatkan kapasitas &
intensitas drainase melalui
sistem polder untuk mengatasi
dan mencegah banjir
|
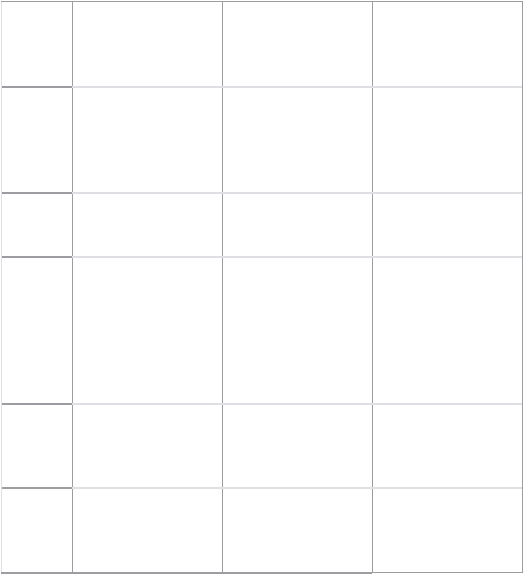 62
Peruntukan/
fungsi tepi
sungai
Gudang-gudang untuk
penyimpanan barang
sementara
Pedestrian, terminal
Sebagai waterfront
restaurant/food stalls,
shopping street, esplanade,
jalur busway, parkir
Fungsi
bangunan di
kiri-kanan
sungai
Abad 17-18 : gudang, hunian
mewah, gereja, pasar
Abad 19 : Bank, kantor
dagang, agen pengapalan,
broker asuransi, pedagang
Kantor, hotel Banyak yang
kosong/tidak digunakan
Lantai bawah untuk restoran,
toko/retail,
galeri, hiburan
Lantai atas untuk galeri,
pendidikan, perkantoran,
hotel, apartemen
Fungsi jalan
di tepi sungai
Jalan bagi pejalan kaki,
transportasi manual, dan
kendaraan
Jalan kendaraan
Jalan kendaraan
Akses dan
sirkulasi
Arah tidak diatur, sebagian
besar masih berjalan kaki,
menggunakan sepeda, kereta
kuda
Sebagian besar ruas jalan
diatur satu arah, kendaraan
bermotor sangat umum,
beberapa ruas jalan ditutup
untuk dijadikan pedestrian
Memindahkan arus jalur
pintas ke lingkar luar,
mengusulkan underpass agar
kendaraan tidak melewati,
memperkecil volume
kendaraan,orientasi pada
pejalan kaki
Pedestrian
Cukup teratur, kontinu,
beberapa dilindungi arkade
atau kanopi
Kurang kontinu, di beberapa
ruas hilang, terganggu
tumbuhnya pohon atau
keberadaan PKL
Kontinyu, terintegrasi dengan
jaringan
jalan, berarkade,
berkanopi, perabot jalan
bersifat festive
Tata hijau dan
ruang terbuka
Sepanjang tembok kota, tepian
kanal dan parit ditanai pohon
palem dan kenari yang
rindang
Di beberapa ruas jalan besar
cukup teduh, di jalan-jalan
kecil masih terasa
gersang
RTH aktif, formal, pohon
bersifat pengarah
II.2.5
Sejarah Perhotelan di Indonesia
Pada zaman penjajahan
Belanda dan
masa sebelum kemerdekaan di
tahun 1945 telah banyak didirikan hotel besar berskala internasional, terutama
di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan,
Semarang, dan Yogyakarta. Tercatat beberapa hotel yang ternama seperti
Hotel Des Indes di Jakarta dan Hotel Savoy Homann di Bandung, serta Hotel
Bali Beach di Bali yang sering digunakan untuk menerima tamu-tamu negara.
|
 63
Gambar II.2.5.1 Hotel-hotel besar pertama di Indonesia
Sumber : Dok. Savoy Homann untuk Aga Khan Award dan dokumentasi pribadi
Perkembangan hotel-hotel bersejarah di Indonesia dapat dicatat
setelah Indonesia merdeka. Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno
membangun
beberapa
hotel
atas
kepemilikan
pemerintah yang
kemudian
menjadi
hotel
di
bawah
BUMN.
Hotel-hotel
tersebut
antara
lain Hotel
Indonesia di Jakarta, Bali Beach Bali, dan Samudra Beach Hotel Yogyakarta.
Saat
ini
telah
umum
dijumpai
berbagai
tipe
hotel
dari
hotel
melati
atau losmen yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kelas mengah ke
bawah sampai hotel berbintang lima, dan diamond yang paling tinggi.
II.2.6
Definisi City Hotel di Indonesia
Menurut Peraturan gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No. 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel pasal 1 ayat (10),
Hotel yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas
kamar
untuk
menginap
dengan
perhitungan pembayaran harian serta dapat
menyediakan berbagai jenis fasilitas
pelayanan
seperti
fasilitas
penyediaan
makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan
hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan bisnis dan
perkantoran,
fasilitas jasa layanan keuangan,
fasilitas perbelanjaan, serta
|
|
64
pengembangan
fasilitas
penunjang
lainnya
yang
diperlukan
untuk
aktivitas
tamu dan pengunjung.
SK Menparpostel No. KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan
usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan
bahwa
hotel
adalah
suatu
jenis
akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk
menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang
lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
Merujuk
pada
Akomodasi
Perhotelan
Jilid
I
(Suwithi,
2008,
p51),
city hotel adalah salah satu jenis hotel, diklasifikasikan berdasarkan faktor
lokasi. Definisinya adalah hotel yang terletak di dalam kota, dimana sebagian
besar tamu
yang menginap memiliki kegiatan berbisnis. Dalam sumber
yang
sama
(p42), city
hotel berciri terletak
di
tengah
kota
besar
yang
digunakan
oleh kebanyakan usahawan.
II.2.7
Klasifikasi Hotel Bintang Empat dan Compact Hotel
Dalam perancangan
city
hotel,
dibuat
satu
hotel
dengan
rentang
layanan
yang
lebar.
Secara
keseluruhan,
hotel
dan fasilitasnya
dirancang
menurut standar klasifikasi hotel bintang empat, tapi disediakan juga paket
kamar hotel berkonsep compact hotel dengan layanan yang terbatas.
Layanan hotel dan fasilitas berstandar bintang empat ditargetkan bagi
tamu dari kalangan wisatawan yang ingin berwisata di kawasan Kota Tua
dalam waktu
yang
lama
dan
menikmati
fasilitas
lengkap
dan
lebih
mewah,
wisatawan bisnis kelas atas, wisatawan mancanegara, serta untuk mengadakan
|
|
65
event besar seperti konferensi atau pernikahan
yang
membutuhkan hall yang
besar dan kamar yang banyak untuk tamu rombongan.
Pemilihan
lokasi
yang menghadap
Kali
Besar
dan
Jembatan
Kota
Intan, dekat dengan objek-objek wisata, serta akses jalan besar dianggap
cukup layak untuk perancangan hotel bintang empat. Potensi wisata dan
kesejarahan kawasan juga menjadi nilai positif.
Unit kamar
dan fasilitas hotel berstandar bintang empat ini
dikombinasi dengan kamar-kamar hotel berkonsep compact
hotel di area
terpisah
dengan
tarif
yang
lebih
terjangkau
dan
fasilitas yang
jauh
lebih
sederhana – cukup akomodasi untuk beristirahat/tidur.
Fasilitas tambahan
dapat
diperoleh
dengan
membayar
biaya
tambahan (layanan terbatas). Targetnya adalah tamu dari kalangan pelajar dan
mahasiswa,
wisatawan low
cost dan
backpacker, serta wisatawan dengan
tempat
tujuan
spesifik yang
cukup
membutuhkan
tempat
bermalam,
yang
umumnya membutuhkan fasilitas penginapan tidak lebih dari dua hari.
Penyusun memutuskan untuk merancang dua jenis layanan hotel
dalam satu proyek ini dengan beberapa pertimbangan :
1. Tapak sangat potensial untuk pengadaan proyek berskala besar yang
mampu menghidupkan kawasan; memenuhi persyaratan perancangan hotel
bintang
empat dari segi
lokasi –
nilai
sejarah
dan
arsitektural
kawasan,
luasan, view, dan akses.
2. Hasil survey BPS dalam Jakarta dalam Angka menunjukkan bahwa pada
hotel bintang empat dan
lima, rasio tamu asing terhadap tamu Indonesia
|
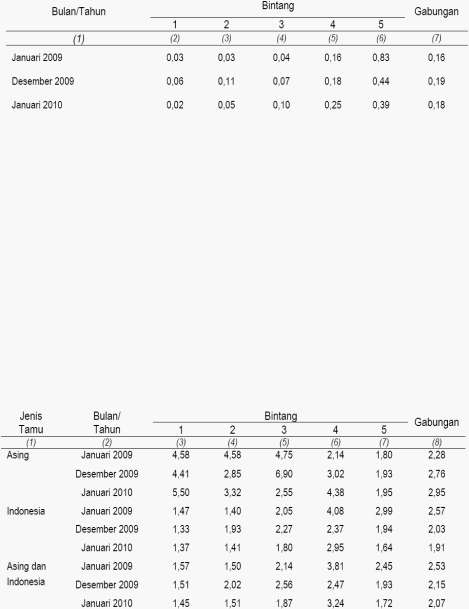 66
relatif
tinggi
dibanding
hotel
berbintang rendah. Disimpulkan bahwa
pengadaan hotel bintang empat ke atas dapat menarik
lebih banyak tamu
asing yang dapat menjadi wisatawan Kota Tua yang potensial. Kompetitor
yang lokasinya paling dekat, Hotel Batavia, juga berbintang empat.
Tabel II.2.7.1 Rasio tamu asing terhadap tamu Indonesia hotel berbintang di DKI Jakarta
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta No 09/03/31/Th. XII, 1 Maret 2010
3. Poin survey BPS lainnya menunjukkan bahwa lama menginap tamu asing
di hotel bintang empat paling panjang. Sama halnya tamu asal Indonesia.
Diasumsikan bahwa hotel bintang empat berpotensi untuk menjadi tempat
singgah untuk waktu lama, yang berarti wisatawan juga berkesempatan
menjelajah kawasan Kota Tua dalam waktu yang lebih panjang.
Tabel II.2.7.2 Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia hotel berbintang
di Jakarta menurut klasifikasi hotel (hari)
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta No 09/03/31/Th. XII, 1 Maret 2010
|
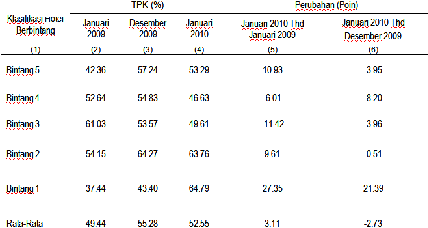 67
4. Melalui
pengamatan
dan
data, disimpulkan
bahwa
pengadaan
hotel
bintang
empat
saja
tidak
akan cukup
menarik
banyak
wisatawan
dan
memenuhi tujuan
utama pengadaan proyek
yaitu
menghidupkan kawasan.
Untuk menarik banyak tamu, khususnya mayoritas tamu lokal atau dari
ekonomi menengah ke bawah, perlu menyediakan satu fasilitas akomodasi
bertarif
murah.
Maka
disediakan
juga
fasilitas kamar
hotel
berkonsep
compact hotel dengan limited service dalam bangunan yang sama.
5.
Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat penghunian kamar hotel
berbintang
rendah
(1-2)
mengalami peningkatan
dari
tahun
ke
tahun
dibanding hotel berbintang tinggi (4-5).
Tabel II.2.7.3 Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang menurut klasifikasi hotel di
Jakarta bulan Januari 2009, Desember 2009, dan Januari 2010
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta No 09/03/31/Th. XII, 1 Maret 2010
Disimpulkan bahwa untuk menarik banyak pengunjung perlu
disediakan akomodasi bertarif murah. Namun, penyusun berpendapat bahwa
hotel bertarif murah tidak selalu didapat dengan desain yang sederhana, lokasi
|
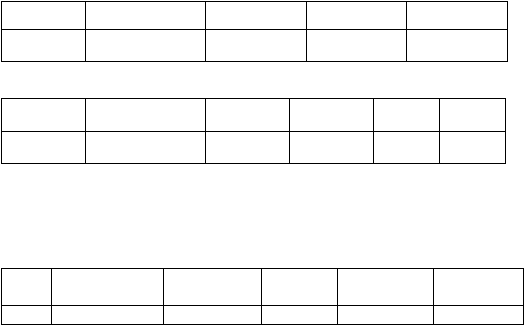 68
yang sulit dijangkau, apalagi fasilitas dan pelayanan berstandar buruk. Bahkan
sampai
mendapat label hotel ‘esek-esek’
seperti
yang
banyak
dijumpai
di
kawasan Kota Tua, padahal notabene Guidelines melarang usaha tersebut.
Maka
penyusun
cenderung
merujuk
pada
limited
service
atau
compact
hotel
yang
tetap
menyediakan
akomodasi untuk kebutuhan paling
minimal, seperti tidur dan mandi, yang baik; serta berada pada lokasi strategis,
sambil
meminimalkan
harga
dengan
meminimalkan
luasan
unit kamar
dan
meniadakan
fasilitas
tambahan,
seperti
tidak
mendapat
sarapan dan
penggunaan AC, kecuali bila
tamu bersedia membayar tambahan biaya
sejumlah yang ditetapkan.
Klasifikasi
hotel bintang empat
merujuk pada Surat Keputusan
Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi :
Tabel II.2.7.4 Klasifikasi hotel bintang empat menu®ut SK Menpa®postel
Fasilitas
Kamar Tidur
Luas Kamar
Ruang Makan
(Restoran)
Bar dan
Coffee Shop
Minimal 50 kamar, 3
kamar suite
18-28 m²
Wajib minimal 2
Wajib minimal 1
Fasilitas
Rekreasi dan Olah
Raga
Function
Room
Ruang yang
disewakan
Lounge
Taman
Wajib perlu + 2 jenis
fasilitas lain
Wajib
minimal 1
Perlu
Minimal 3
Wajib
Perlu
Klasifikasi hotel bintang empat merujuk pada Akomodasi Perhotelan
Jilid 1 antara lain :
Tabel II.2.7.5 Klasifikasi hotel bintang empat menu®ut buku teks pe®hotelan SMIP
Jumlah kamar standar
Jumlah kamar suite
Kamar mandi
Luas kamar
standar
Luas kamar suite
****
Minimum 50 kamar
Minimum 3 kamar
Di dalam
minimum 24 m²
minimum 48 m²
|
 69
Belum ada
standar
klasifikasi
yang
resmi
mengenai compact hotel.
Terminologi
ini
digunakan
penyusun
merujuk
pada
artikel
Compact
Hotels
Big
on
Style
(Lee,
2009,
p1)
yang
memakai
istilah compact
hotel
untuk
menyebut hotel yang menarik pengunjung dengan memadukan kualitas desain
yang baik dan harga murah; dengan meminimalkan luasan unit kamar dan
mengurangi biaya untuk fasilitas yang tidak selalu dimanfaatkan oleh tamu
hotel seperti fasilitas olahraga, sarapan, dan room service.
Standar luasan dan fasilitas yang diterapkan penyusun dalam
perancangan tipe compact
hotel ini
mengacu
pada
studi
banding
proyek-
proyek yang sudah ada, salah satunya telah diuraikan pada subbab II.1.5.3.
Hotel-hotel
yang
digolongkan
ke
dalam
compact
hotel
contohnya
easy Hotel London, Yotel Amsterdam, dan CitizenM Amsterdam yang
menawarkan
kamar-kamar
berluasan
sangat
rendah
(7-12
m²
)
dengan
tarif
yang murah menurut standar Eropa – 30-100 US$ semalam.
Gambar II.2.7.1 Kamar di easy Hotel, Yotel, dan CitizenM
Sumber : fastcompany.com
II.2.8
Tinjauan Khusus Terhadap Topik dan Tema
Penerapan tema arsitektur kontekstual pada rancangan fisik
bangunan
city
hotel
dan
lingkungan
sekitarnya
dapat
diekspresikan
dengan
|
|
70
bermacam-macam
cara
yang
beberapa
di antaranya telah penyusun uraikan
dalam subbab
II.1.6.
Konsep
ini
berlaku
bagi
penambahan
bangunan
baru,
sementara bangunan eksisting yang tergolong bangunan cagar budaya yang
bernilai sejarah akan dikonservasi. Pendekatan kontekstual yang dipilih untuk
mengolah fisik bangunan akan dianalisa lebih lanjut pada bab IV.
Revitalisasi atau upaya menghidupkan kembali Kota Tua yang mulai
kehilangan produktivitasnya akan dilakukan sesuai strategi revitalisasi
menurut Rencana Induk Kota Tua Jakarta :
•
Revitalisasi ekonomi, sosial & kegiatan
:
mencari alternatif untuk menarik
kegiatan ke Kota Tua, menggali potensi lokal melalui survey sosial
ekonomi dan budaya masyarakat, mengkaji ekonomi kawasan secara rinci,
dan menarik investor masuk ke Kota Tua
• Revitalisasi kelembagaan : mencari terobosan bentuk kelembagaan.
Birokrasi
yang
terlalu panjang
dan
berbelit-belit,
program yang
berganti
setiap ganti pejabat –
harus diakhiri. Pemerintah dan lembaga perlu
konsisten pada aturan yang dibuat sendiri. (Dundu dan Urbaidi, 2009, p19)
• Revitalisasi fisik : Kerangka Pengembangan Kawasan
Pelestarian Kota Tua merupakan
kegiatan yang sangat mendesak,
hanya
dapat terlaksana dengan
rancangan
revitalisasi
yang
bijak,
melibatkan
semua
unsur
baik pemerintah,
pemilik
bangunan,
dan
seluruh
masyarakat.
Mengingat
dalam kajian
ini
Kota
Tua
Jakarta
telah
mengalami
berbagai
perubahan, perombakan, pembongkaran baik tembok, benteng, kanal, gedung-
|
 71
gedung, dan elemen-elemen konstruksi
lainnya,
maka
revitalisasi khususnya
pembangunan
kembali
dan
pembongkaran
seharusnya
diadakan
sejalan
dengan penelitian arkeologis. (Guidelines Kotatua, 2007, p90)
Gambar II.2.8.1 T®ansfo®masi kawasan Kali Besar : tahun ¹775 Æ 1875 Æ 2008
Sumber : koleksi Mahandis Yoanata
Di kawasan yang dikaji (zona 2), dapat disimpulkan terdapat empat
tipologi bangunan, yang dibedakan sesuai masyarakat dan zamannya, yaitu:
1. Bangunan masyarakat kolonial
Eropa
(Colonial
Indische, Neo-Klasik
Eropa, Art Deco, dan Art Nouveau)
2.
Bangunan
masyarakat Cina
(Gaya
Cina
Selatan dan campuran
dengan
gaya kolonial Eropa)
3.
Bangunan masyarakat pribumi (Colonial Indische)
4.
Bangunan modern Indonesia (International Style)
Dengan
tipologi
bangunan
bervariasi
sesuai
zamannya,
tentu
Penyusun harus menghargai keragaman bangunan eksisting di atas dan sekitar
tapak. Penyusun
mengupayakan
keberadaan hotel dapat
menjadi infill
yang
menghormati keragaman tersebut. Misalnya dengan
mengikuti ketentuan
dalam Guidelines Kotatua
yang menganjurkan pembagian
lebar
façade agar
tidak
monoton, dapat selaras dengan skala
manusia dan
bangunan eksisting
|
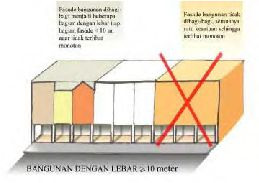 72
pada umumnya, serta pemakaian arkade yang menjadi salah satu elemen
penyatu bangunan-bangunan yang berbeda gaya dan zaman.
Gambar II.2.8.2 Jajaran facade bangunan dibuat berirama dengan leba® = 10 meter
Sumber : Guidelines Kotatua dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemprov DKI Jakarta
II.2.9
Kesimpulan Hasil Studi Proyek Sejenis
Dari tinjauan lapangan dan literatur proyek sejenis yang telah
diuraikan pada subbab II.1.5 dan II.1.7, dapat disimpulkan beberapa hal yang
menjadi pedoman dalam perancangan selanjutnya :
1. Perancangan hotel terbagi menjadi tiga bagian besar : kamar-kamar tipikal,
fasilitas
penunjang,
dan
kantor pengelola –
front
office,
dan
back office
atau service.
2. Hotel dapat diklasifikasikan
menjadi bintang 1-5 berdasarkan
luasan
kamar;
kelengkapan
fasilitas seperti
restoran,
ruang pertemuan,
dan
fasilitas olahraga atau kesehatan; kualitas desain dan fasilitas; akses dan
lokasi. Aspek ekonomis, sosial budaya, atau kesejarahan juga dapat
menjadi nilai tambah lokasi.
3. Fasilitas penunjang yang umumnya tersedia di hotel :
|
|
73
•
Kuliner : restoran, café, bar, wine & dine, grille
•
Fasilitas bisnis : meeting room, business center
•
Function room : gathering lounge dan hall serbaguna untuk
menyelenggarakan event-event
•
Fasilitas olahraga : kolam renang atau fasilitas lain seperti lapangan
•
Fasilitas kesehatan dan kecantikan : spa, fitness, salon
•
Drugstore yang menyediakan barang-barang keperluan khas
wisatawan
•
Toko benda seni atau souvenir, khususnya bila berlokasi di pusat
wisata
•
Area bermain dan penitipan anak
•
Miscelanneous : travel, internet corner, mini market, ATM Center
•
Security & Safety System
4. Hotel bertarif
murah tetap dapat dirancang dengan baik, sambil
menekan
harga dengan strategi kreatif seperti
self service dan
sistem ‘bayar
sesuai
yang digunakan’ – limited service concept.
5.
Setiap hotel memiliki standar masing-masing dalam menentukan
konfigurasi atau penamaan kamar, tapi tidak lepas dari aturan yang
berlaku. Penamaan dapat dilakukan berdasakan besaran ruang, fasilitas
yang tersedia, besaran tempat tidur, atau view yang dapat dinikmati dari
kamar.
|
 74
6. Penerapan konsep arsitektur kontekstual dan kepedulian terhadap desain
kawasan
menjadikan
bangunan
lebih
membaur
dengan
kawasan
sekitarnya. City hotel yang akan dirancang tidak harus menggunakan gaya
dan ornamen bangunan
lama, tetap dapat tampil modern dan harmonis
dengan konteks kawasan.
II.2.10 Tinjauan Terhadap Kondisi Tapak
1. Lokasi tapak
: Jalan Kali Besar Timur, Jakarta Barat
Gambar II.2.10.1 Peta lembar rencana sekitar tapak
Sumber : Dinas Tata Kota
|
|
75
2.
Luas lahan
: 22823.22 m²
3.
KDB
: 75% x 22823.22 m² = 17117.42 m²
4.
KLB
: 3 x 22823.22 m²
= 68469.66 m²
5.
GSB
: 0 di semua sisi
6.
Ketinggian maksimum
: 4 lantai
7.
Lebar jalan
:
-
Sebelah timur
: 21 meter
-
Sebelah barat
: 25 meter
-
Sebelah utara
: 10 meter
-
Sebelah selatan
: 10 meter
8.
Batas tapak
:
-
Sebelah timur
: Jalan Cengkeh, perkantoran, dan pertokoan
-
Sebelah barat
: Jalan Kali Besar Timur dan Sungai Kali
Besar selebar 30 meter
-
Sebelah utara
: Jalan Nelayan Timur, usaha dan permukiman
penduduk
-
Sebelah selatan
: Jalan Kali Besar Timur 1, bangunan kosong,
perkantoran
|
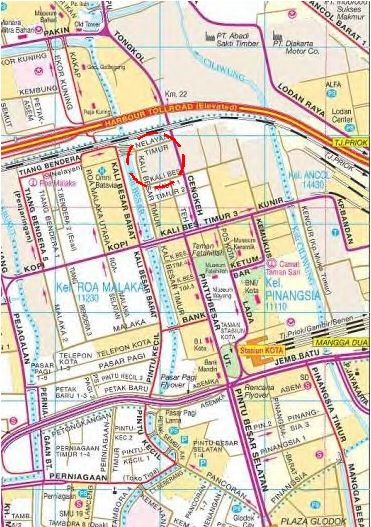 76
9. Peta lokasi
Gambar II.2.10.2 Peta lokasi tapak
10. Deskripsi tapak
Proyek
direncanakan
untuk
dibangun
di
atas
lahan
seluas
22823.22
m² di blok
utara Kali
Besar Timur bagian
utara. Tapak dipilih
dengan pertimbangan letak dan lokasinya yang sangat strategis, dapat
diakses dari Jalan Kali Besar
Timur sebagai
jalan kolektor selebar 21 m,
dengan view ke arah Kali Besar yang potensial untuk dijadikan waterfront.
|
 77
Gambar II.2.10.3 View Kali Besar dengan Jembatan Kota Intan di kejauhan
Sumber : Dokumentasi pribadi
Potensi positif tapak ini selain jalannya yang besar dan viewnya
yang baik ke arah sungai, juga
terletak dekat dengan objek-objek wisata
sejarah seperti Jembatan Kota Intan
yang terletak
tepat di sebelah barat
laut tapak. Selain itu, banyak bangunan bersejarah lain di sepanjang Kali
Besar, dan Museum Fatahillah hanya terpisah dua blok jauhnya.
Akses jalannya
relatif mudah
dan tidak
macet,
walaupun
diberlakukan peraturan one way. Dengan kendaraan bermotor, tapak dapat
dicapai dalam
20
menit
dari Bandara Internasional
Soekarno-Hatta
via
Sunda Kelapa, Pluit, dan tol Bandengan. Dari Stasiun Kota dan Terminal
Busway Kota memerlukan waktu 5 menit. Sementara dari tapak, jarak ke
Glodok, Mangga Dua, Sunter, dan Ancol dapat ditempuh dalam 15 menit.
Terdapat
sejumlah
besar objek
wisata
yang dapat
ditempuh
dengan berjalan kaki, sehingga pemanfaatan sepeda atau pedestrian perlu
diperhatikan selain pengolahan jalan kendaraan bermotor.
|
 78
Selain potensi positif, tapak juga memiliki beberapa
kendala
yang
harus
dicari
solusinya,
selain
masalah
eksistensi
bangunan
cagar
budaya yang telah dibahas sebelumnya :
1.
Tapak berada pada daerah yang relatif sepi. Ini tidak terlalu
menjadi
masalah, karena hotel dirancang dengan konsep untuk menghidupkan
kembali kawasan, dan diharapkan dapat menjadi
magnet
penarik
wisatawan selain Museum Fatahillah.
2.
Lingkungan tapak berkesan kumuh karena ada bangunan yang kosong
dan dihuni tunawisma. Di atas tanah kosong
milik Pemprov
ini juga
didirikan
banyak
perumahan
kumuh
atau hunian
liar yang
bersifat
temporer. Selain itu,
fungsi lainnya sebagai parkir truk kontainer dan
penumpukan barang seperti gulungan tali kapal, peti kemas, dan terpal.
Pemanfaatan
yang
menurut penyusun kurang produktif dan
tidak
sesuai dengan nilai sejarah tapak yang cukup tinggi.
Gambar II.2.10.4 Bangunan kosong diisi tunawisma dan tumpukan peti kemas
Sumber : Dokumentasi pribadi
3.
Satu bangunan cagar budaya
yang tersisa di atas tapak berada dalam
kondisi
rusak
berat.
Ini
berarti
upaya
konservasi
bangunan
tersebut
|
 79
memerlukan pencarian sumber gambar
otentik
untuk
merestorasinya
sesuai
keadaan
asal.
Contohnya
gedung
Tata
Sastra,
dahulu
pabrik
kertas
karbon.
Kini digolongkan
sebagai cagar
budaya
golongan
B,
namun kondisinya rusak berat dan sebagian atapnya hilang. Penyusun
kemudian mencari foto kondisi asalnya untuk panduan restorasi.
Gambar II.2.10.5 Tata Sastra saat tampilannya masih baik dan tampilannya saat ini
Sumber : Presentasi Kuliah Danang Priatmodjo dan dokumentasi pribadi
4.
Keberadaan
terminal
kota
yang
mengganggu
view,
menciptakan
daerah
kumuh,
dan
mengurangi
jatah
lahan
yang
seharusnya
diperuntukkan menjadi restoran dan café waterfront.
Gambar II.2.10.6 Te®minal Kota
Sumber : Dokumentasi pribadi
|