|
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Jalan Raya
Jalan
raya
merupakan
jalan
utama
yang menghubungkan
suatu
kawasan
dengan
kawasan
lainnya
yang meliputi
segala
bagian
jalan
termasuk
bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik yang
berada di permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
Biasanya memiliki ciri-ciri:
-
Dipergunakan untuk kendaraan bermotor.
-
Dipergunakan oleh masyarakat umum.
-
Dibiayai oleh negara.
-
Penggunaannya diatur oleh undang - undang.
Pada dasarnya pembangunan jalan raya merupakan proses pembukaan
ruang lalu lintas dengan mengatasi berbagai masalah geografis. Proses ini berkaitan
dengan penggalian dan pengurugan, seperti menimbun
lembah dan atau menggali
bukit untuk keperluan pembangunan jalan raya.
Untuk
perencanaan
jalan
raya
yang baik,
bentuk
geometriknya
harus
ditetapkan sedemikian rupa agar
jalan
raya tersebut dapat
memberikan pelayanan
yang optimal bagi penggunanya sesuai dengan fungsi dasarnya.
6
|
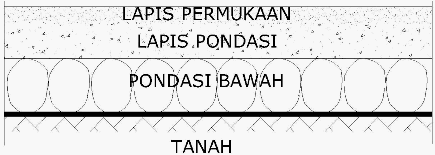 7
2.2. Perkerasan Lentur
Aspal merupakan salah satu jenis material yang sering dipergunakan dalam
perkerasan jalan
raya karena memiliki
ikatan yang kuat dengan
agregat dan keras
dalam suhu kamar, selain itu juga memiliki tekstur yang lunak/cair pada suhu tinggi
sehingga mudah membalut agregat dan mengisi rongga-rongga diantara agregat.
Aspal
merupakan
senyawa hidrokarbon dengan
sedikit kandungan
sulfur,
oksigen dan klor, berbentuk cairan kental
yang bersifat melekat (adhesive),
berwarna hitam kecoklatan serta memiliki ketahanan terhadap air.
Perkerasan
lentur
lebih
sering dipergunakan
untuk
konstruksi jalan
dibandingkan dengan perkerasan kaku. Perkerasan ini memiliki 3 lapisan dimana
lapisan
permukaannya terdiri
dari agregat
dan
aspal,
lapisan pondasi
atas
terdiri
dari batu pecah dan
lapisan pondasi bawah
terdiri dari sirtu. Pada lapisan pondasi
atas dan bawah dapat diisi dengan material lain seperti semen Portland, kapur dan
aspal. Semua lapisan ini harus dibangun diatas tanah yang telah dipadatkan.
Gambar 2.1 Lapisan Perkerasan Lentur
|
|
8
Adapun fungsi dari tiap-tiap lapisan itu adalah:
-
Lapisan permukaan:
o
Bagian perkerasan untuk menahan beban roda
o
Lapis kedap air sebagai pelindung badan jalan
o
Lapisan aus
o
Menyebarkan
beban
ke
lapisan
dibawahnya
yang
memiliki
daya
dukung lebih rendah
-
Lapisan pondasi atas:
o
Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan
menyebarkannya ke lapisan dibawahnya
o
Lapisan peresapan lapis pondasi bawah
o
Sebagai bantalan terhadap lapis permukaan
-
Lapis pondasi bawah:
o
Bagian
dari
konstruksi
perkerasan
untuk
mendukung
dan
menyebarkan beban roda ke tanah dasar
o
Untuk mencapai efisiensi penggunaan
material
yang relatif
lebih
murah guna penghematan biaya konstruksi
o
Lapis peresapan agar air tanah tidak berkumpul pada pondasi
o
Mencegah
partikel
halus
dari
tanah
dasar
masuk
ke dalam
lapis
pondasi atas
o
Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan dapat berjalan dengan
lancar.
|
|
9
Perkerasan lentur ini memiliki beberapa kelebihan seperti:
-
Waktu konstruksinya yang relatif singkat.
-
Tidak memiliki
lapisan
granular
yang dapat
ditembus oleh
air sehingga
kwalitas dapat terjaga.
-
Dapat mengalirkan air yang tergenang.
-
Memiliki gaya gesek yang tidak terlalu besar.
-
Lentur (fleksibel).
-
Baik untuk kondisi lalu lintas yang lancar.
-
Biaya konstruksinya relatif murah dibanding perkerasan kaku.
Kekurangan yang dimiliki oleh perkerasan lentur ini yaitu:
-
Tidak tahan terhadap beban diam.
-
Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan berkala menyebabkan biaya
investasinya relatif lebih mahal.
-
Lemah terhadap air.
2.2.1. Perencanaan
Tebal Perkerasan
Lentur Untuk Jalan
Baru
dengan
Metode
Bina Marga
Data lalu lintas harian rata-rata dapat diperoleh dengan cara:
LHR
Jumlah
kendaraan
tertinggi
k
………..………………(2.1)
Dimana:
k = 0,09
|
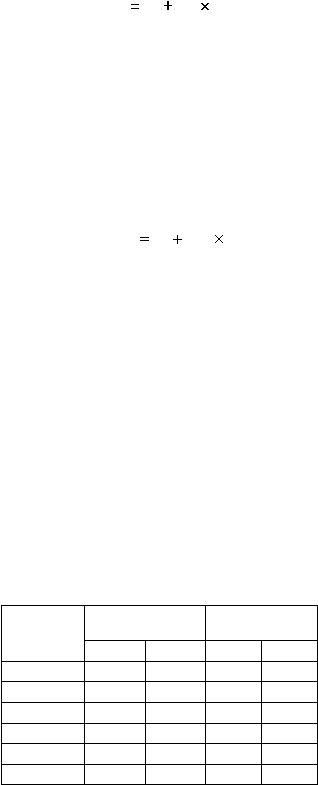 10
2.2.1.1.
Lintas Harian Rata-Rata Awal
Rumus:
LHR
awal umur rencana
(1
i)
n
Volume
kendaraan
………..……..(2.2)
Dimana:
i = Angka pertumbuhan lalu lintas pada masa pelaksanaan
n = Masa pelaksanaan
2.2.1.2.
Lintas Harian Rata-Rata Akhir
Rumus:
LHR
akhir umur rencana
(1
i)
n
Volume
kendaraan
………..…(2.3)
Dimana:
i = Angka pertumbuhan lalu lintas pada masa operasional
n = Masa operasional jalan
2.2.1.3.
Koefisien Distribusi Untuk Masing-Masing Kendaraan
Berdasarkan Daftar
II
SNI-1732-1989-F
tentang “TATA CARA
PERENCANAAN
TEBAL PERKERASAN
LENTUR
JALAN
RAYA
DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN”,
nilai koefisien masing-
masing kendaraan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 2.1.
Koefisien Distribusi Kendaraan
Jumlah
Jalur
Kendaraan
Ringan
Kendaraan
Berat
1 arah
2 arah
3 arah
4 arah
1 Jalur
1,00
1,00
1,00
1,00
2 Jalur
0,60
0,50
0,70
0,50
3 Jalur
0,40
0,40
0,50
0,475
4 Jalur
-
0,30
-
0,45
5 Jalur
-
0,25
-
0,425
6 Jalur
-
0,20
-
0,40
|
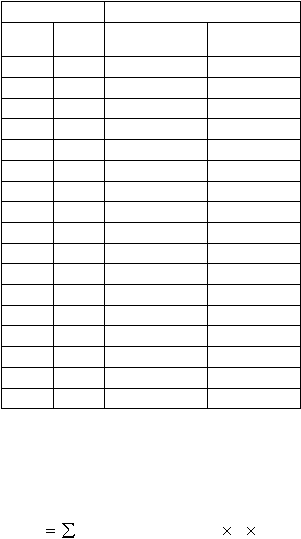 11
2.2.1.4.
Angka Ekivalen Masing-Masing Kendaraan
Berdasarkan
Daftar
III SNI-1732-1989-F
tentang “TATA
CARA
PERENCANAAN
TEBAL PERKERASAN
LENTUR
JALAN
RAYA
DENGAN METODE
ANALISA KOMPONEN”, nilai
ekivalen masing-
masing kendaraan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 2.2.
Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan
Beban Sumbu
Angka Ekivalen
Kg
Lb
Sumbu
Tunggal
Sumbu
Ganda
1000
2205
0,0002
-
2000
4409
0,0036
0,0003
3000
6614
0,0183
0,0016
4000
8818
0,0577
0,0050
5000
11023
0,1410
0,0121
6000
13228
0,2933
0,0251
7000
15432
0,5415
0,0466
8000
17637
0,9328
0,0794
8160
18000
10,000
0,0860
9000
19841
1,4798
0,1273
10000
22046
2,2555
0,1940
11000
24251
3,3022
0,2840
12000
26455
4,6770
0,4022
13000
28660
6,4419
0,5540
14000
39864
8,6447
0,7452
15000
33069
11,4184
0,9820
16000
35276
14,7815
12,712
2.2.1.5.
Lintas Ekivalen Permulaan (LEP)
Rumus:
LEP
(
LHR
awal umur rencana
c
E )
……………..…………(2.4)
Dimana:
c
=
Koefisien distribusi masing-masing kendaraan
E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan
|
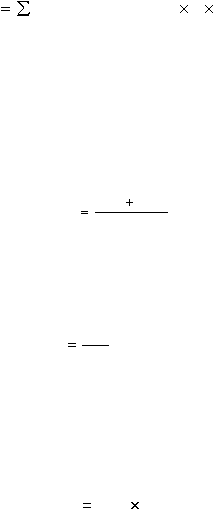 12
2.2.1.6.
Lintas Ekivalen Akhir (LEA)
Rumus:
LEA
(
LHR
akhir umur rencana
c
E )
...……………...(2.5)
Dimana:
c
=
Koefisien distribusi masing-masing kendaraan
E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan
2.2.1.7.
Lintas Ekivalen Tengah (LET)
Rumus:
LET
LEP
LEA
2
....................................……….(2.6)
2.2.1.8.
Faktor Penyesuaian
Rumus:
FP
UR
………………………..……………...(2.7)
10
Dimana:
UR = Umur Rencana/masa operasional jalan
2.2.1.9.
Lintas Ekivalen Rencana (LER)
Rumus:
LER
LET
FP
……………………………….(2.8)
2.2.1.10.
Analisa Daya Dukung Tanah
1. Nilai Daya Dukung Tanah Dasar
Untuk menentukan nilai daya dukung tanah dasar, digunakan
nomogram kolerasi antara nilai CBR dan nilai daya dukung tanah dasar
pada
SNI-1732-1989-F
tentang
“TATA CARA
PERENCANAAN
|
|
13
TEBAL
PERKERASAN
LENTUR
JALAN
RAYA
DENGAN
METODE ANALISA KOMPONEN”.
|
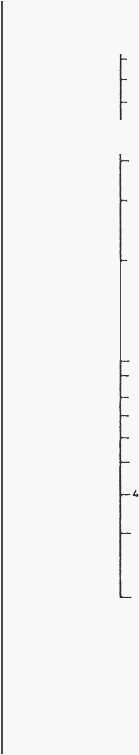 14
DDT
CBR
100
10
90
eo
70
60
9
so
UJ
8
30
20
7
6
10
9
8
7
s
6
s
3
J
2
2
Gambar
2.2.
Korelasi
Nilai
Daya Dukung
Tanah
Dengan
Nilai
CBR
(Sumber:
Direktorat
Jendral
Bina
Marga, SNI
1732-1989-F)
|
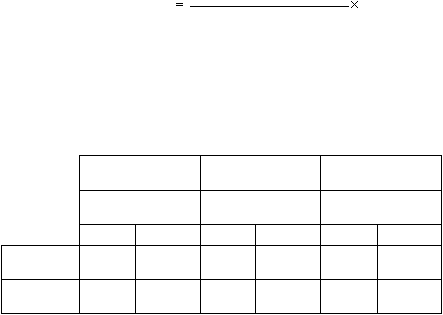 15
2.2.1.11.
Analisa Tebal Perkerasan Lentur
1. Faktor Regional
Rumus:
Persentase Kendaraan Berat
Jumlah Kendaraan Berat
100% ………
Jumlah Kendaraan
………………………………………………………………….…(2.9)
Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melihat tabel dibawah ini:
Tabel 2.3.
Faktor Regional (FR)
Kelandaian I (<
6%)
Kelandaian II (6
-
10%)
Kelandaian III >
10%)
%
kendaraan
berat
%
kendaraan
berat
%
kendaraan
berat
=
30%
> 30%
=
30%
> 30%
=
30%
> 30%
Iklim I <
900mm/th
0,5
1,0 - 1,5
1,0
1,5 - 2,0
1,5
2,0 - 2,5
Iklim I >
900mm/th
1,5
2,0 - 2,5
2,0
2,5 - 3,0
2,5
3,0 - 3,5
Catatan: Pada bagian
tertetu
jalan,
seperti persimpangan,
pemberhentian atau tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR
ditambah 0,5, Pada daerah raw, FR ditambah 1,0
2. Indeks Permukaan
Dalam
menentukan indeks permukaan awal umur rencana (IPo) perlu
diperhatikan
jenis
lapis
permukaan
jalan
(kerataan/kehalusan serta
kekokohan) pada awal umur rencana. Besarnya nilai indeks permukaan
pada awal umur rencana dapat dilihat dari tabel dibawah:
|
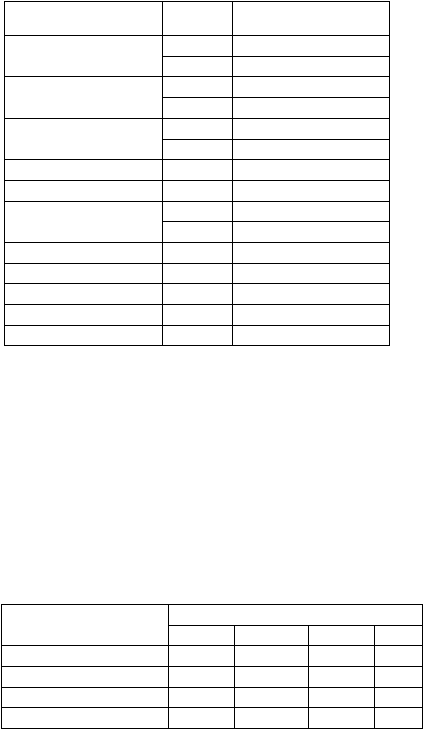 16
Tabel 2.4.
Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (IPo)
Jenis Lapis
Permukaan
IPo
Roughness (mm/km)
Laston
=
4
=
1000
3,9 - 3,5
> 1000
Lasbutag
3,9 - 3,5
=
2000
3,4 - 3,0
> 2000
HRA
3,9 - 3,5
=
2000
3,4 - 3,0
> 2000
Burda
3,9 - 3,5
< 2000
Burtu
3,4 - 3,0
< 2001
Lapen
3,4 - 3,0
=
3000
2,9 - 2,5
> 3000
Latasbum
2,9 - 2,5
Buras
2,9 - 2,5
Latasir
2,9 - 2,5
Jalan Tanah
=
2,4
Jalan Kerikil
=
2,4
3. Indeks permukaan akhir
Untuk menentukan
indeks permukaan pada akhir umur rencana, perlu
dipertimbangkan
faktor
klasifikasi
fungsional
jalan
dan
jumlah lintas
ekivalen
rencana (LER).
Adapun
kisaran
nilai
indeks
tersebut
dapat
dilihat dari tabel ini:
Tabel 2.5. Indeks Permukaan Akhir (IP)
Lintas Ekivalen
Rencana
Klasifikasi Jalan
Lokal
Kolektor
Arteri
Tol
< 10
1 - 1,50
1,50
1,50 - 2
-
10 - 100
1,50
1,50 - 2
2
-
100 - 1000
1,50 - 2
2
2 - 2,50
-
>1000
-
2 - 2,5
2,50
2,50
|
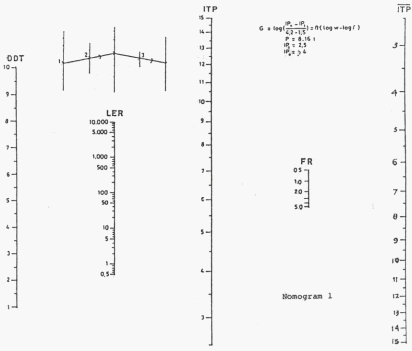 17
4. Indeks tebal perkerasan
Adalah suatu
angka
yang
berhubungan
dengan
penentuan
tebal
perkerasan. Penentuan nilai
indeks tebal
perkerasan dapat
dilakukan
dengan menggunakan nomogram yang ada di bawah ini:
Gambar 2.3. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 2,5 dan IPo = 4
|
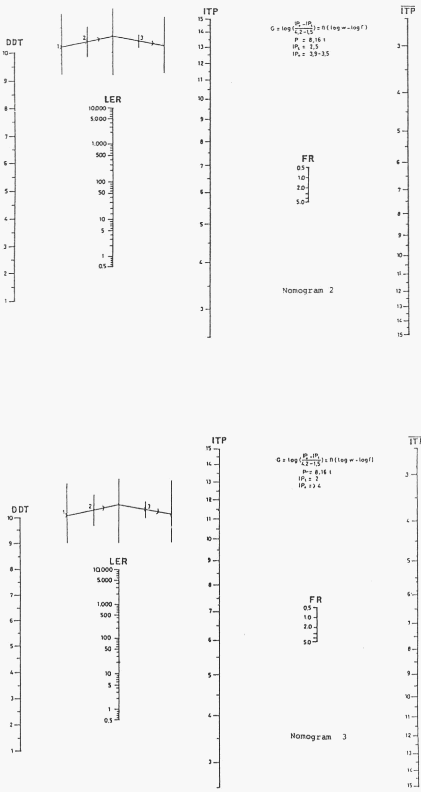 18
Gambar 2.4. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 2,5 dan IPo =
3,9 – 3,5
Gambar 2.5. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 2 dan IPo = 4
|
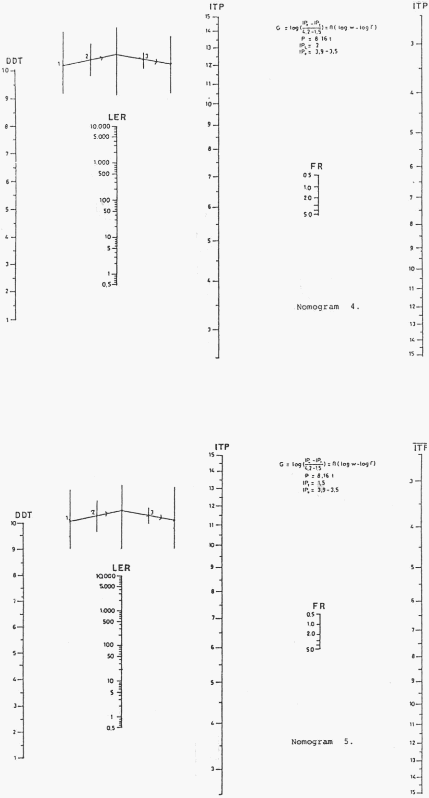 19
Gambar 2.6. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 2 dan IPo =
3,9 – 3,5
Gambar 2.7. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1,5 dan IPo =
3,9 – 3,5
|
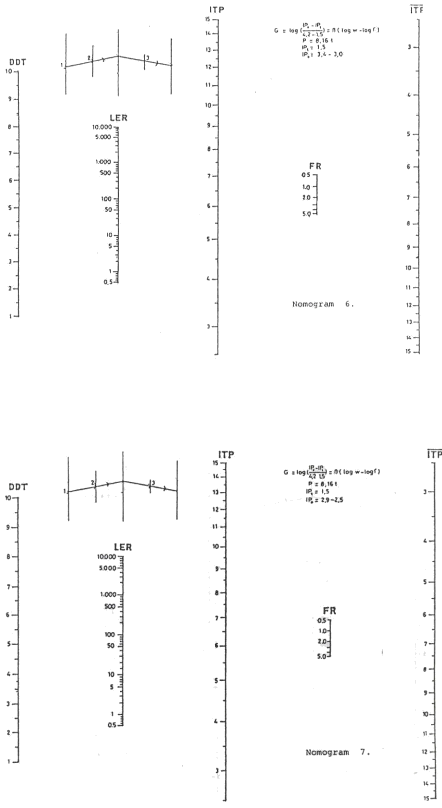 20
Gambar 2.8. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1,5 dan IPo =
3,4 – 3,0
Gambar 2.9. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1,5 dan IPo =
2,9 – 2,5
|
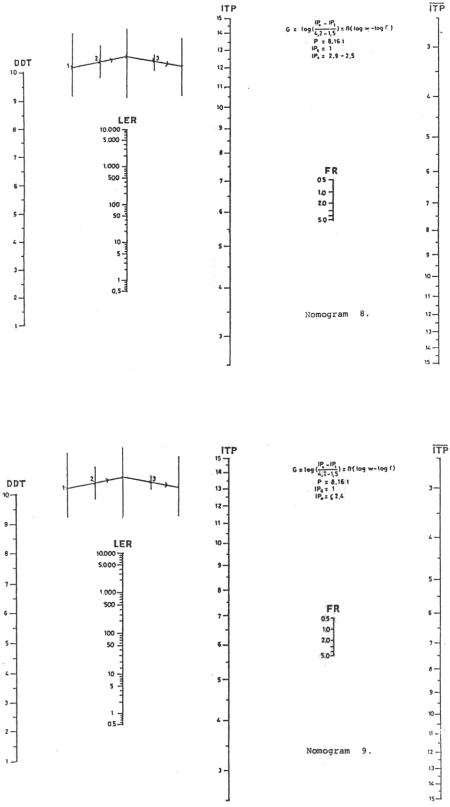 21
Gambar 2.10. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1 dan IPo =
2,9 – 2,5
Gambar 2.11. Nomogram Indeks Perkerasan untuk IPt = 1 dan IPo =
2,4
|
|
22
5. Koefisien kekuatan relatif
Koefisien kekuatan relatif
(a)
masing-masing bahan dan kegunaannya
sebagai
lapis
permukaan,
lapis
pondasi
atas
dan lapis pondasi
bawah
ditentukan
secara korelasi
sesuai
nilai
Marshall
Test
(untuk
bahan
dengan aspal), kuat tekan (untuk bahan yang diperkuat dengan semen
atau
kapur) atau
CBR
(untuk
bahan
lapis
pondasi
bawah).
Jika
alat
Marshall Test
tidak tersedia,
bahan beraspal bias diukur dengan cara
lain
seperti
Hveem Test,
Hubbard Field,
dan
Smith Triaxial.
Berikut
adalah
beberapa
material
yang umum
digunakan
sebagai
bahan
lapis
perkerasan:
|
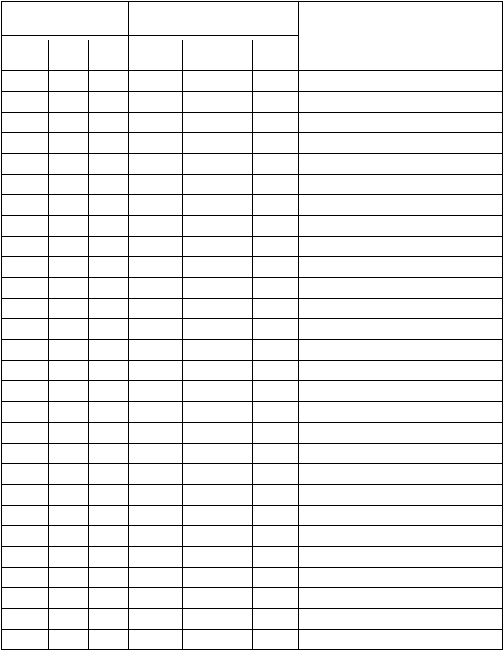 23
Tabel 2.6.
Koefisien Kekuatan Relatif
Koefisien
Kekuatan Relatif
Kekuatan Bahan
Jenis Bahan
a
1
a2
a3
MS
(kg)
KT
(Kg/cm²)
CBR
(%)
0,40
-
-
744
-
-
Laston
0,35
-
-
590
-
-
0,32
-
-
454
-
-
0,30
-
-
340
-
-
0,35
-
-
744
-
-
Lasbutag
0,31
-
-
590
-
-
0,28
-
-
454
-
-
0,26
-
-
340
-
-
0,30
-
-
340
-
-
HRA
0,26
-
-
340
-
-
Aspal Macadam
0,25
-
-
-
-
-
Lapen (mekanis)
0,20
-
-
-
-
-
Lapen (manual)
-
0,28
-
590
-
-
-
0,26
-
454
-
-
Laston Atas
-
0,24
-
340
-
-
-
0,23
-
-
-
-
Lapen (mekanis)
-
0,19
-
-
-
-
Lapen (manual)
-
0,15
-
-
22
-
Stabilisasi tanah dengan semen
-
0,13
-
-
18
-
-
0,15
-
-
22
-
Stabilisasi tanah dengan kapur
-
0,13
-
-
18
-
-
0,14
-
-
-
100
Batu pecah (kelas A)
-
0,13
-
-
-
80
Batu pecah (kelas B)
-
0,12
-
-
-
60
Batu pecah (kelas C)
-
-
0,13
-
-
70
Sirtu/pitrun (kelas A)
-
-
0,12
-
-
50
Sirtu/pitrun (kelas B)
-
-
0,11
-
-
30
Sirtu/pitrun (kelas C)
-
-
0,10
-
-
20
Tanah/lempung berpasir
|
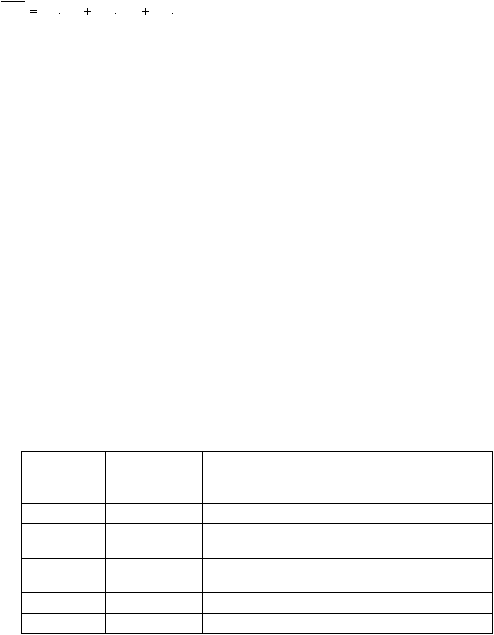 24
6. Susunan lapisan perkerasan
Dalam
menentukan tebal
lapisan perkerasan, dipergunakan persamaan
ini:
Rumus:
ITP
a
1
D
1
a
2
D
2
a
3
D
3
………...………..…….……..(2.10)
Dimana:
ITP
a1
=
Indeks tebal perkerasan
=
koefisien kekuatan relatif lapis permukaan
a2
=
koefisien kekuatan relatif lapis pondasi atas
a3
=
koefisien kekuatan relatif lapis pondasi bawah
D1
=
tebal lapis permukaan
D2
=
tebal lapis pondasi atas
D3
=
tebal lapis pondasi bawah
Berikut adalah batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan:
1. Lapis Permukaan
Tabel 2.7.
Batas Tebal Minimum Lapis Permukaan
ITP
Tebal
Minimum
(cm)
Bahan
< 3,00
5
Lapis pelindung : (Buras / Burtu / Burda)
3,00 - 6,70
5
Lapen / Aspal Macadam, HRA, Lasbutag,
Laston
6,71 - 7,49
7,5
Lapen / Aspal Macadam, HRA, Lasbutag,
Laston
7,50 - 9,99
7,75
Lasbutag, Laston
=
10,00
10
Laston
|
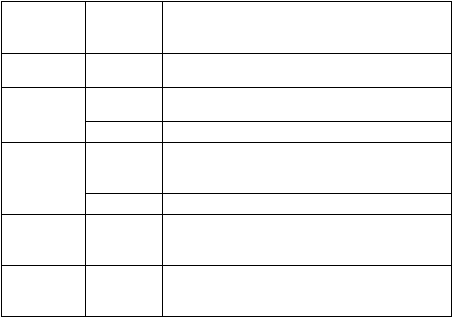 25
2. Lapis Pondasi
Tabel 2.8.
Batas Tebal Minimum Lapis Pondasi
ITP
Tebal
Minimum
(cm)
Bahan
< 3,00
15
Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,
stabilisasi tanah dengan kapur
3,00 - 7,49
20*
Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,
stabilisasi tanah dengan kapur
10
Laston Atas
7,50 - 9,99
20
Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,
stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi
macadam
15
Laston Atas
10 - 12,14
20
Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,
stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi
macadam, Lapen, Laston Atas
=
12,25
25
Batu pecan, stabilisasi tanah dengan semen,
stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi
macadam, Lapen, Laston Atas
*) Batas
20
cm
tersebut
dapat
diturunkan
menjadi 15
cm bila
untuk pondasi bawah digunakan material berbutir kasar.
3. Lapis Pondasi Bawah
Untuk
setiap
nilai
ITP
bila
digunakan
pondasi
bawah,
tebal
minimum adalah 10 cm.
2.2.2. Perawatan Perkerasan Lentur
Jenis perawatan yang ada dalam perkerasan lentur ini ada dua, yaitu:
-
Perawatan rutin.
-
Perawatan berkala.
|
|
26
2.2.2.1.
Perawatan Rutin
Perawatan
rutin
bertujuan
untuk
menjaga agar
umur
layan
perkerasan
lentur
dapat sesuai dengan umur layan rencana awalnya. Analisa
perawatan rutin
ini
diasumsikan
sebesar 20
%
dari
total
volume lapis
permukaan perkerasan lentur. Perawatan ini dilakukan setiap tahun.
2.2.2.2.
Perawatan Berkala
Perawatan berkala bertujuan
untuk
menjaga agar
umur
layan perkerasan
lentur dapat sesuai dengan umur layan rencana awalnya. Proses perawatan
berkala ini
dilakukan dengan
cara
melapis
ulang permukaan perkerasan
lentur setebal ± 5 cm. Perawatan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali.
2.3. Perkerasan Kaku
Beton
merupakan
salah
satu
bahan
konstruksi
umum
yang sering
dipergunakan untuk
membangun
gedung, jalan,
dan lain-lain. Beton
ini
bersifat
homogen yang diperoleh dengan cara mencampur agregat
halus, agregat kasar, air
dengan semen Portland yang terkadang diberi campuran bahan tambahan (additive)
yang bersifat kimiawi maupun fisikal.
Beton
yang sudah
mengeras
dapat
dikatakan
juga
sebagai
batuan
tiruan,
dengan rongga antara agregat kasar yang diisi oleh agregat halus, serta semen dan
air sebagai
pengisi
pori-porinya. Pasta semen berfungsi
sebagai
pengikat
dalam
proses pengerasan
agar
butiran dapat
terikat dengan
kuat sehingga menjadi
satu
kesatuan yang padat dan tahan lama.
|
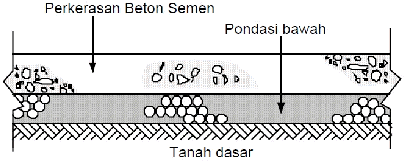 27
Perkerasan kaku terdiri dari pelat beton dengan atau tanpa lapisan pondasi
bawah
(diatas
tanah
dasar).
Dalam
perkerjaan konstruksi
perkerasan kaku,
plat
beton sering dianggap sebagai lapisan pondasi jika diatasnya ada lapisan aspal.
Pelat
beton
yang kaku
memiliki
modulus
elastisitas
yang tinggi,
dimana
pendistribusian beban
lalu
lintas
ke tanah dasar yang melingkupi area
yang luas.
Sehingga kapasitas struktur perkerasan akan diperoleh dari pelat beton itu sendiri.
Berbeda dengan perkerasan lentur yang kekuatan perkerasannya diperoleh dari
lapis permukaan, lapis pondasi dan lapis pondasi bawah.
Secara umum ada empat jenis perkerasan kaku, yaitu:
-
Perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan
-
Perkerasan kaku bersambung dengan tulangan
-
Perkerasan kaku menerus dengan tulangan
-
Perkerasan kaku prategang
Gambar 2.12. Tipikal Struktur Perkerasan Kaku
Pada perkerasan kaku, daya dukung
utama diperoleh dari pelat beton. Sifat, daya
dukung dan
keseragaman
tanah
sangat
mempengaruhi
umur
dan
kekuatan
perkerasan kaku ini. Lapis pondasi bawah pada perkerasan kaku ini memiliki
fungsi:
|
|
28
-
Mengendalikan pengaruh kembang susut tanah
-
Mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retakan dan tepi pelat
-
Memberi dukungan yang mantap dan seragam pada pelat
-
Sebagai perkerasan lantai kerja selama masa konstruksi
Pelat beton semen ini
memiliki kekakuan untuk
menyebarkan beban pada bidang
yang
luas dan
menghasilkan tegangan yang rendah pada lapisan dibawahnya. Bila
diperlukan untuk memberi kenyamanan yang tinggi, lapisan permukaan perkerasan
kaku ini dapat diberi campuran beraspal setebal 5 cm.
Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh perkerasan kaku yaitu:
-
Memiliki
kemampuan
menahan
gaya
tekan
yang
baik,
sehingga
cocok
untuk kondisi lalu lintas yang lambat.
-
Dalam keadaan segar beton dapat dengan mudah dicetak.
-
Beton
segar dapat
disemprotkan
pada
retakan
beton
dalam
proses
perbaikannya.
Kekurangan yang dimiliki oleh perkerasan kaku yaitu:
-
Biaya konstruksinya relatif lebih mahal dibanding perkerasan lentur.
-
Proses pengerjaannya membutuhkan ketelitian yang lebih.
-
Waktu konstruksinya yang lebih lama.
|
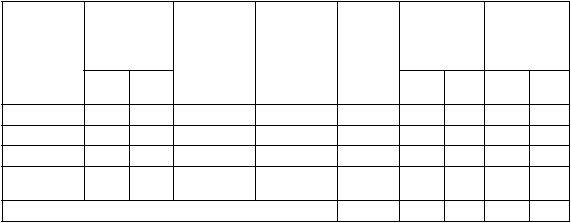 29
2.3.1. Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku Untuk Jalan Baru dengan Metode
Bina Marga
2.3.1.1.
Analisa Lalu Lintas Kendaraan
Tabel 2.9.
Perhitungan Jumlah Sumbu Berdasar Jenis dan Bebannya
Jenis
kendaraan
Konfigurasi
beban
sumbu (ton)
Jumlah
kendaraan
(bh)
Jumlah
sumbu
kendaraan
(bh)
Jumlah
sumbu
(bh)
STRT
STRG
RD
RB
BS
(ton)
JS
(bh)
BS
(ton)
JS
(bh)
MP
1
1
-
-
-
-
-
Bus
3
5
2
3
5
Truk 2as
4
6
2
4
6
Bus Trans
Jakarta
7
13
2
7
13
Total
Keterangan:
RD
=
roda depan
RB
=
roda belakang
RGD
=
roda gandeng depan
RGB
=
roda gandeng belakang
JSKN
=
jumlah sumbu tiap kendaraan
JSKNH
=
jumlah sumbu kendaraan harian
STRT
=
sumbu tunggal roda tunggal
STRG
=
sumbu tunggal roda ganda
BS
=
beban sumbu
JS
=
jumlah sumbu
Setelah
itu
hitung
pertumbuhan
lalu
lintas
kendaraan
dengan
menggunakan rumus:
|
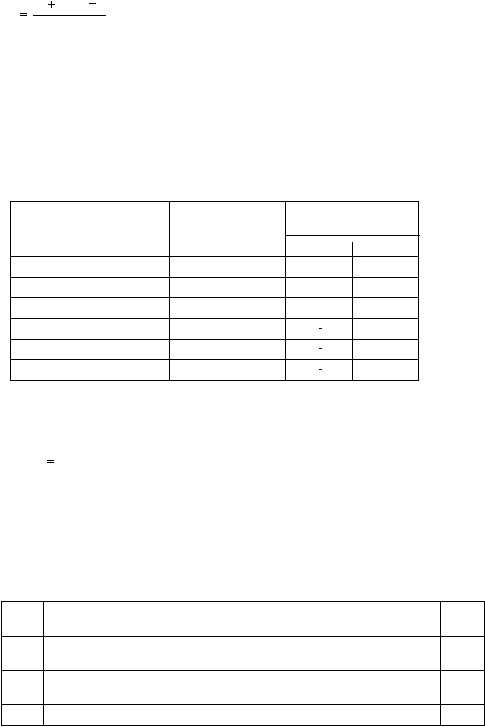 30
UR
R
(1
i)
1
.…………………..……….………………... (2.11)
i
2.3.1.2.
Lajur Rencana dan Koefisien Distribusi
Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 2.10.
Jumlah Lajur Berdasar Lebar Perkerasan dan Koefisien
Distribusi (C)
Lebar perkerasan (Lp)
Jumlah Lajur
(n)
Koefisien
distribusi
1 arah
2 arah
Lp < 5,50 m
1
1
1
5,50 m = Lp < 8,25 m
2
0,70
0,50
8,25 m = Lp < 11,25 m
3
0,50
0,475
11,25 m = Lp < 15 m
4
0,45
15 m = Lp < 18,75 m
5
0,425
18,75 m = Lp < 22 m
6
0,40
Jumlah sumbu kendaraan yang bekerja adalah:
JSKN
365 x JSKHN x R x c ……...…………………………..….. (2.12)
2.3.1.3.
Faktor Keamanan Beban
Tabel 2.11.
Faktor Keamanan Beban
No
Penggunaan
Nilai
F
KB
1
Jalan bebas hambatan utama, berjalur banyak, dengan aliran
lalu
lintas tidak terhambat dengan volume kendaraan niaga tinggi
1,2
2
Jalan bebas hambatan dan jalan arteri dengan volume kendaraan
menengah
1,1
3
Jalan dengan volume kendaraan
rendah
1
|
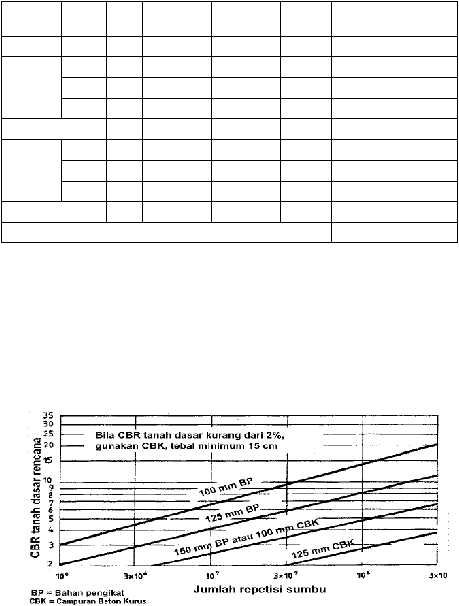 31
2.3.1.4.
Repetisi Sumbu Rencana
Dengan diperolehnya jumlah sumbu
untuk setiap
jenis dan beban sumbu
kendaraan serta jumlah sumbu kendaraan, maka besarnya repetiri rencana
untuk setiap jenis dan beban sumbu kendaraan dapat diketahui, dengan
tabel dibawah ini:
Tabel 2.12.
Perhitungan Repetisi Sumbu Rencana
Jenis
sumbu
BS
(ton)
JS
bh)
Proporsi
beban
Proporsi
sumbu
JSKN
Repetisi yang
terjadi
1
2
3
4
5
6
7 = (4) × (5) × (6)
STRT
7
4
3
jumlah
STRG
13
6
5
jumlah
Komulatif
2.3.1.5.
Analisa Tebal Lapisan Pondasi
Menurut
“PERATURAN PERENCANAAN PERKERASAN JALAN
BETON
SEMEN”,
tebal
lapisan
pondasi
perkerasan
kaku
dapat
dilihat
dari grafik dibawah ini:
Gambar 2.13. Tebal Pondasi Minimum Untuk Perkerasan Kaku
|
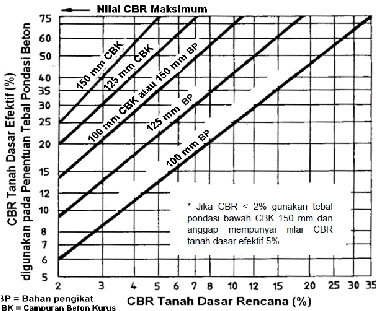 32
2.3.1.6.
Analisa CBR Tanah Dasar Efektif
Berdasar
“PERATURAN PERENCANAAN PERKERASAN JALAN
BETON
SEMEN”,
besarnya
nilai
CBR
tanah
efektif dapat
dilihat
dari
grafik ini:
Gambar 2.14. CBR Tanah Dasar Efektif
2.3.1.7.
Analisa Tebal Minimum Pelat Beton
Nilai
tebal minimum pelat beton yang akan digunakan dapat dilihat dari
grafik dibawah ini:
|
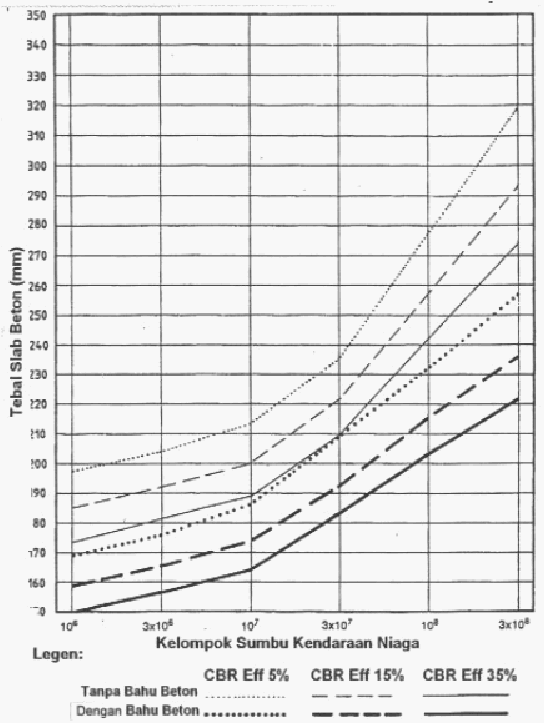 33
Gambar 2.15. Grafik Perencanaa fc
f
=
4,25 MPa, Lalu Lintas Dalam Kota,
Tanpa Ruji, FKB = 1,1
|
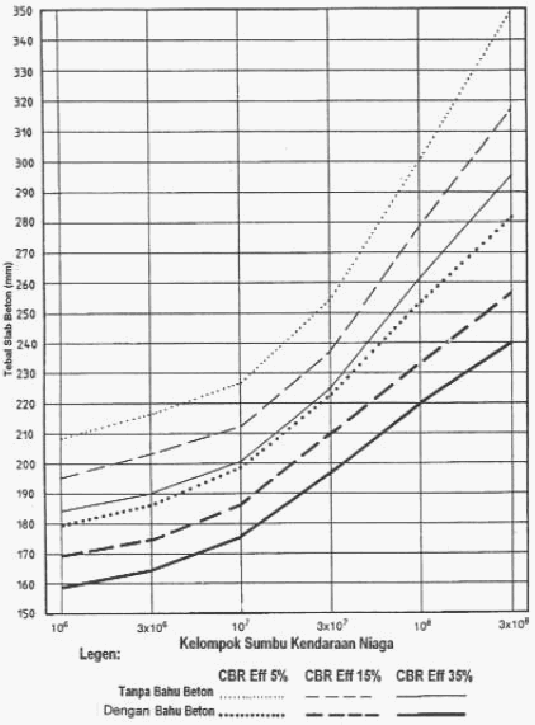 34
Gambar 2.16. Grafik Perencanaa fc
f
=
4,25 MPa, Lalu Lintas Dalam Kota,
Tanpa Ruji, FKB = 1,2
|
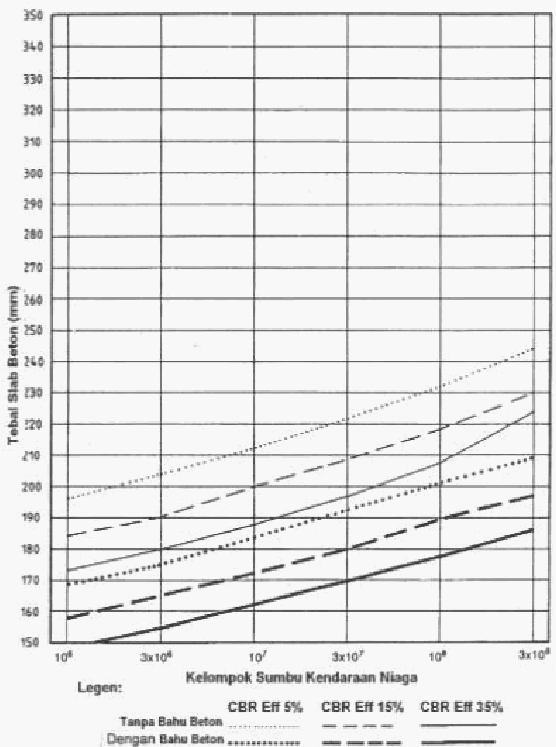 35
Gambar 2.17. Grafik Perencanaa fc
f
=
4,25 MPa, Lalu Lintas Dalam Kota,
Dengan Ruji, FKB = 1,1
|
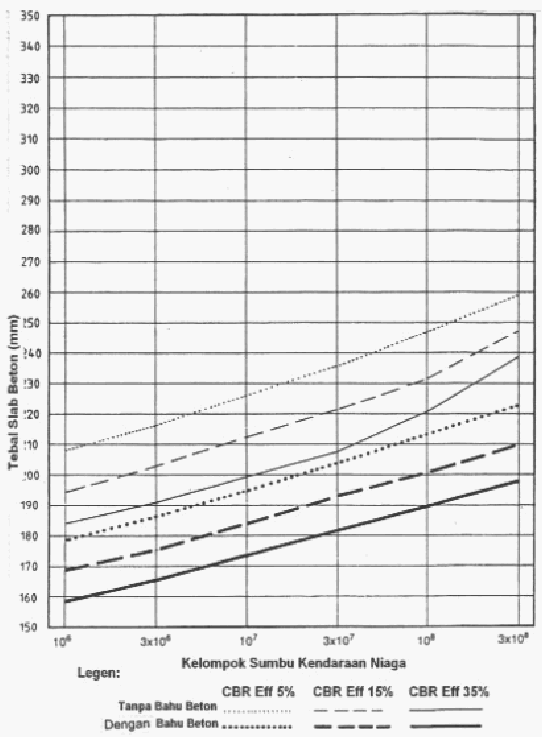 36
Gambar 2.18. Grafik Perencanaa fc
f
=
4,25 MPa, Lalu Lintas Dalam Kota,
Dengan Ruji, FKB = 1,2
|
|
37
Dengan menggunakan rumus empiris sebagaimana diberikan pada
“PERATURAN
PERENCANAAN
PERKERASAN
JALAN
BETON
SEMEN” maka kuat tarik lentur beton dapat dihitung dengan rumus:
f
cf
K
f'
c
……….……………………..……………….(2.13)
Tebal pelat beton dapat ditentukan dengan menggunakan analisa fatik dan
erosi,
dimana tingkat kerusakan
yang terjadi dari
hasil analisa
fatik
dan
erosi
lebih
kecil dari 100%. Adapun
cara menentukan
tebal
pelat
beton
pada perkerasan kaku dilakukan secara iterasi dengan menggunakan Tabel
2.14, Gambar 2.19, dan Gambar 2.20 di bawah ini.
|
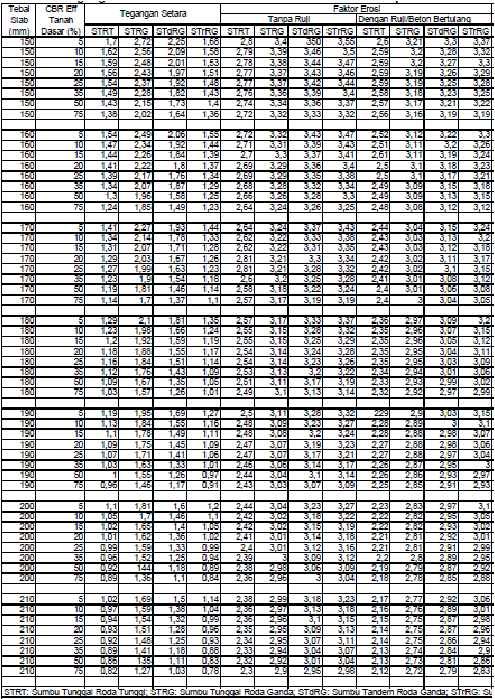 38
Tabel 2.13.
Tegangan Ekivalen dan Faktor
Erosi untuk Perkerasan
Tanpa Bahu Beton
|
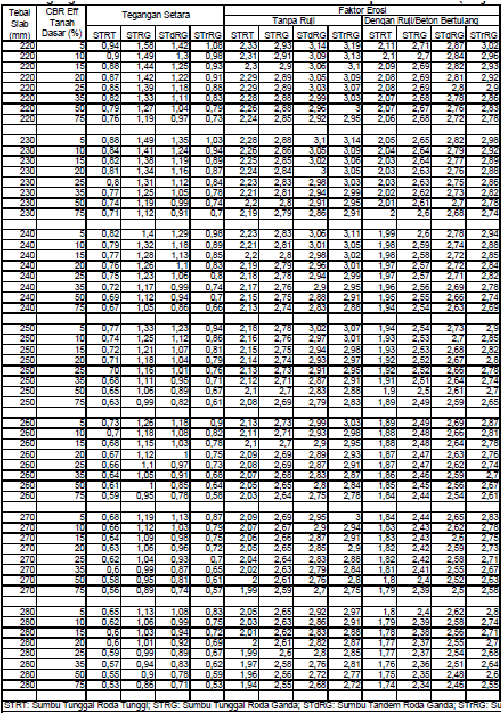 39
Tabel 2.13.
Tegangan Ekivalen dan Faktor
Erosi untuk Perkerasan
Tanpa Bahu Beton (lanjutan)
|
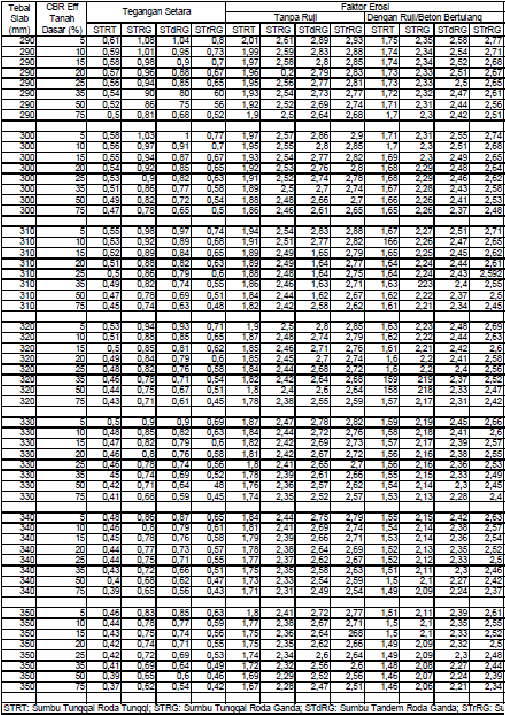 40
Tabel 2.13.
Tegangan Ekivalen dan Faktor
Erosi untuk Perkerasan
Tanpa Bahu Beton (lanjutan)
|
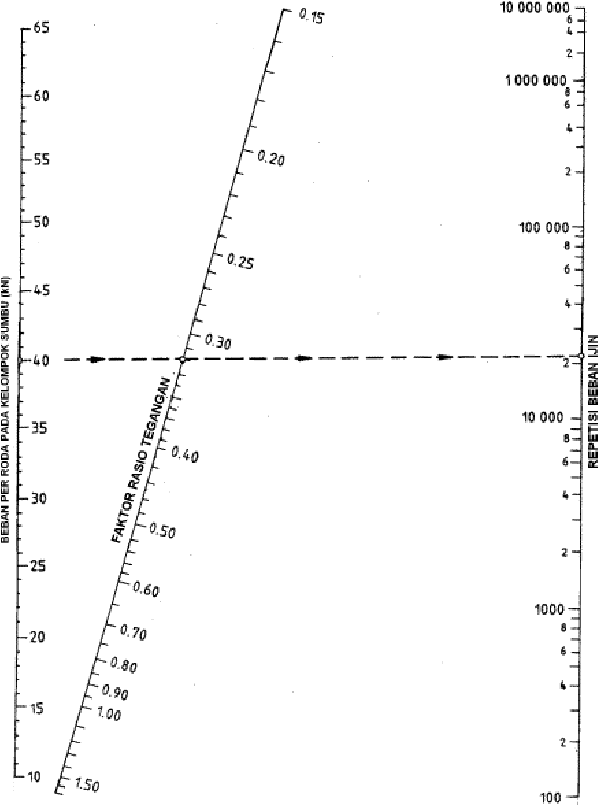 41
Gambar 2.19 Analisa Fatik dan Beban Ijin Berdasarkan Rasio Tegangan
dengan atau Tanpa Bahu Beton
|
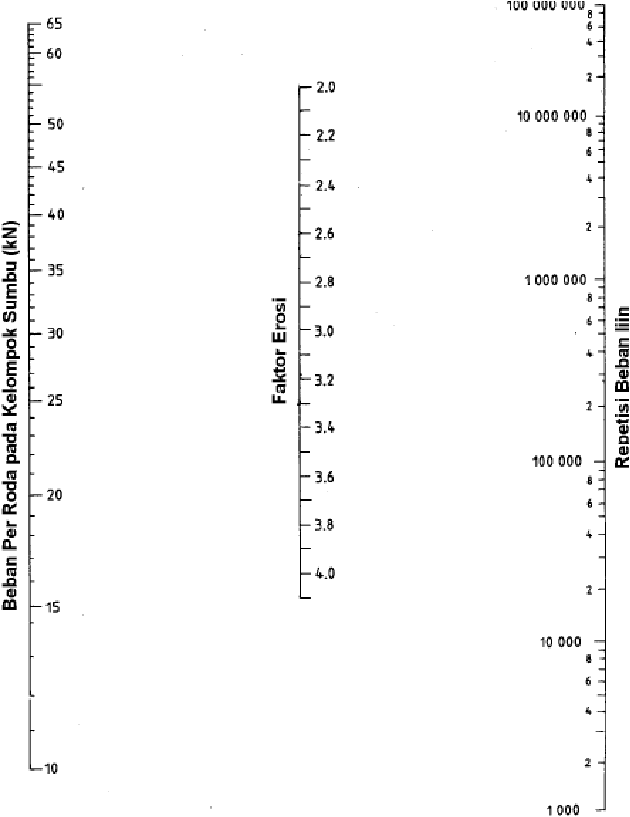 42
Gambar 2.20 Analisa Erosi dan Jumlah Repetisi Beban Ijin Berdasarkan
Faktor Erosi Tanpa Bahu Beton
|
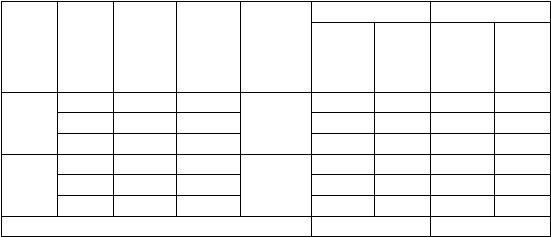 43
Dimana:
TE
=
tegangan ekivalen
FRT
=
faktor rasio tegangan
FE
=
faktor erosi
2.3.1.8.
Analisa Fatik dan Erosi
Tabel 2.14.
Analisa Fatik dan Erosi
Jenis
sumbu
Beban
sumbu
(kN)
Beban
rencana
per roda
(kN)
Repetisi
yang
terjadi
Faktor
tegangan
dan erosi
Analisa fatik
Analisa erosi
Repetisi
ijin
Persen
rusak
(%)
Repetisi
ijin
Persen
rusak
(%)
STRT
70
TE =
FRT =
FE =
40
30
STRG
130
TE =
FRT =
FE =
60
50
Total
2.3.1.9.
Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan
Pada perkerasan
beton
semen
bersambung
tanpa tulangan,
ada
kemungkinan
penulangan perlu dipasang guna
mengendalikan
retak.
Bagian
–
bagian
pelat
yang diperkirakan
akan
mengalami
retak
akibat
konsentrasi
tegangan yang
tidak
dapat
dihindari dengan
pengaturan
pola
sambungan, maka pelat harus diberi tulangan:
a. Pada pelat bentuk tidak lazim (Odd Shaped Slabs).
Pelat disebut tidak lazim bila pola sambungan pada pelat tidak benar –
benar berbentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang.
b. Pelat dengan sambungan tidak sejalur (Mismatched Joints).
c. Pelat berlubang (Pits or Structures)
|
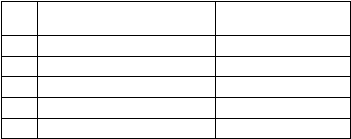 44
2.3.1.10.
Sambungan Susut Melintang
Kedalaman sambungan kurang lebih mencapai seperempat dari tebal pelat
untuk
perkerasan
dengan
lapis
pondasi berbutir atau sepertiga dari
tebal
pelat untuk lapis pondasi stabilisasi semen.
Jarak
sambungan
susut melintang
untuk
perkerasan
beton
bersambung
tanpa
tulangan sekitar 4 – 5 m,
sedang untuk perkerasan beton
bersambung dengan tulangan 8 – 15 m dan untuk sambungan perkerasan
beton menerus dengan tulangan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan.
Sambungan
ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, jarak
antar ruji 30 cm lurus dan bebas tonjolan tajam yang akan mempengaruhi
gerak bebas pada saat beton menyusut.
Diameter ruji tergantung pada tebal pelat beton seperti tabel di bawah ini:
Tabel 2.15.
Diameter Ruji
No.
Tebal pelat beton, h (mm)
Diameter ruji
(mm)
1
125 < h = 140
20
2
140 < h = 160
24
3
160 < h = 190
28
4
190 < h = 220
33
5
220 < h = 250
36
2.3.2. Perawatan Perkerasan Kaku
Jenis perawatan yang ada dalam perkerasan kaku ini yaitu:
2.3.2.1.
Perawatan Berkala
Perawatan
berkala
yang
dilakukan
pada
jalur busway
yaitu
berupa
penambalan
lobang dengan menggunakan bahan Laston lapis aus (AC –
|
|
45
WC) yang diasumsikan sebesar 10 % dari volume pelat beton perkerasn
kaku tersebut. Perawatan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali.
2.4. Bus Trans Jakarta
Bermula dari
gagasan perbaikan sistem angkutan
umum DKI Jakarta yang
mengarah
pada
kebijakan
prioritas
angkutan
umum,
maka perlu
dibangun
suatu
sistem angkutan umum yang dapat mengakomodasi pengguna dari segala golongan.
Pemerintah
DKI Jakarta
menyusun
Pola
Transportasi
Makro
(PTM)
sebagai
perencanaan umum
mengembangkan sistem transportasi di wilayah
DKI
Jakarta
yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun
2007, yang mengacu pada
PTM tersebut
untuk tahap awal
realisasinya dibangun
suatu
jaringan
sistem
angkutan
umum
massal
yang mempergunakan jalur
khusus
(Bus Rapid Transit/BRT).
BLUD Transjakarta Busway adalah lembaga pemerintah DKI Jakarta yang
mengelola layanan angkutan umum
massal dalam moda bus.
Hal
ini dimaksudkan
agar pemerintah dapat
meningkatkan pelayanan dan
penyediaan
jasa
transportasi
yang aman, tertib, lancar, nyaman, ekonomis dan terjangkau oleh masyarakat.
Pada pelaksanaaannya, pelayanan
angkutan
ini
memiliki
satu
lajur
sendiri
yang diambil dari jalur umum dan hanya boleh dipergunakan oleh kendaraan selain
bus
Transjakarta,
dengan
tujuan
agar
tidak
terjadi
kemacetan
yang dapat
mengganggu jalannya moda transportasi ini.
Saat
ini jumlah armada bus
mencapat 426 unit yang dioperasikan berdasar
rencana operasi yang terjadwal di sepuluh koridor. Bus
yang diberangkatkan pada
titik awal diatur sesuai dengan
waktu
yang telah ditentukan baik pada jam sibuk
|
|
46
maupun pada
jam tidak
sibuk. Untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi
kepadatan penumpang di halte transit, BLU Transjakarta Busway menambah rute -
rute langsung berdasar sistem jaringan yang dapat diakses penumpang sesuai
dengan tujuan perjalanannya.
2.5. Biaya Investasi
2.5.1. Pengertian Biaya
Besarnya laba atau
rugi
perusahaan
pada periode tertentu
merupakan
perbedaan
antara
penghasilan
yang direalisasikan
yang timbul
dari
transaksi
dengan biaya – biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.
Definisi
biaya menurut
Standar Akutansi
Keuangan
(1999:12)
adalah
penurunan
manfaat
ekonomi
selama satu
periode akutansi
dalam
bentuk
arus
keluar
atau
berkurangnya
aktiva
atau terjadinya kewajiban
yang
mengakibatkan
penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
The Commite on
Cost
Concepts
and
Standards
of
The American
Accounting Association
memberikan definisi
Cost
sebagai berikut: “Cost is
foregoing measured in monetary terms incurred or potenntially to be incurred to
achive
a
specific
objective”,
yang berarti
biaya
merupakan
pengeluaran
–
pengeluaran
yang diukur secara
terus
menerus
dalam
uang atau
yang potensial
harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan.
Jadi
menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya
merupakan kas atau nilai ekuovalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
mendapatkan barang atau
jasa
yang
diharapkan
guna
untuk
memberikan
suatu
manfaat yaitu peningkatan laba.
|
|
47
2.5.2. Pengertian Investasi
Bagi
masyarakat
modern, kata
investasi
tentu tidak asing
lagi. Bisa jadi
setiap hari kita
mendengar kata itu. Sebab, semakin tinggi pendidikan seseorang
semakin tidak bersedia membiarkan asetnya menjadi tidak berkembang dan untuk
mengembangkan
aset
tersebutlah
maka diperlukan
investasi.
Bagi
sebagian
masyarakat lainnya, barangkali
telah melakukan investasi tetapi
tidak
menyadarinya, seperti para petani dan peternak di pedesaan.
Reilly dan
Brown,
yang
mengatakan bahwa
investasi
adalah
komitmen
mengikatkan
aset
saat
ini
untuk beberapa
periode waktu ke
masa
depan
guna
mendapatkan penghasilan
yang mampu
mengkompensasi
pengorbanan
investor
berupa keterikatan
aset pada waktu
tertentu,
tingkat
inflasi
dan
ketidaktentuan
penghasilan pada masa mendatang.
Dari
definisi
yang disampaikan pakar
investasi
tersebut
kita
bisa
menarik
pengertian investasi, bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur
ketersediaan
dana (aset)
pada saat
sekarang,
kemudian komitmen
mengikatkan
dana tersebut pada obyek investasi (bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa
periode
(untuk
jangka
panjang lebih
dari
satu
tahun)
di
masa
mendatang.
Selanjutnya,
setelah
periode
yang diinginkan
tersebut
tercapai
(jatuh
tempo)
barulah investor bisa mendapatkan kembali asetnya, tentu saja dalam jumlah yang
lebih
besar,
guna mengkompensasi
pengorbanan
investor seperti
yang
diungkapkan
Reilly dan
Brown.
Namun,
tidak
ada
jaminan
pada akhir
periode
yang ditentukan
investor pasti
mendapati asetnya lebih besar dari saat memulai
|
|
48
investasi. lni terjadi karena selama periode waktu menunggu itu terdapat kejadian
yang menyimpang dari yang diharapkan. lnilah, yang disebut risiko.
Dalam pembangunan jalan yang mempergunakan perkerasan lentur, biaya
yang dibutuhkan
untuk
konstruksinya
lebih
murah
dibanding dengan
mempergunakan beton.
Tetapi karena
sifat
lentur yang tidak terlalu tahan
terhadap lingkungan menyebabkan proses perawatan harus sering dilakukan. Hal
ini
menyebabkan biaya
investasi
yang
dibutuhkan
kelihatannya menjadi
lebih
mahal.
Lain
hal
nya
dalam
perkerasan
jalan
yang
mempergunakan
beton.
Biaya
konstruksinya termasuk
mahal,
tetapi
karena
sifatnya
yang
tahan
terhadap
lingkungan sehingga perawatannya dapat dilakukan
jika diperlukan saja. Hal ini
menyebabkan biaya investasi yang dibutuhkan kelihatannya menjadi lebih murah
jika dibandingkan dengan perkerasan lentur.
2.5.3. Perhitungan Biaya Investasi
Perhitungan biaya
investasi
terbagi
atas biaya
konstruksi dan biaya
perawatannya.
Biaya
konstruksi
yang dimaksud
adalah
jumlah
biaya
yang
dibutuhkan selama masa pembangunan suatu proyek. Sedangkan pengertian dari
biaya perawatan yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menunjang umur rencana dari
suatu
proyek
dengan
tujuan
mencapai
umur
yang diinginkan.
Dimana
dalam
perhitungan biaya ini dipergunakan
Buku Acuan
Harga Satuan Bahan dan Upah
Pekerjaan Bidang / Jasa Pemborongan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Periode Januari 2010 sebagai acuannya.
|
|
49
2.5.4. Present Value
Cost Benefit Analysis (CBA) atau yang sering disebut Benefit Cost
Analysis
(BCA)
adalah
suatu pendekatan
yang
digunakan
dalam
pengambilan
keputusan ekonomi yang biasanya digunakan oleh pemerintah
atau pebisnis. Ini
merupakan
suatu
analisa
biaya
yang bertujuan
untuk
mengetahui
apakah
keuntungan lebih besar dari biaya dan berapa besarnya.
Keuntungan
dan
biaya
dinyatakan
dalam
nilai
uang
yang disesuaikan
terhadap waktu. Dimana semua keuntungan dan biaya proyek tiap waktu tertentu
(biasanya
waktunya
berbeda) dinyatakan
dalam
nilai sekarang (present
value),
dengan mengubah
nilai yang
akan datang
menjadi nilai
sekarang
menggunakan
tingkat
diskon tertentu.
Tingkat
diskon ini
dimaksudkan untuk
mengantisipasi
perubahan nilai
uang yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh banyak faktor,
seperti terjadinya inflasi, keadaan politik dan lain – lain.
Ada beberapa metoda dalam menganalisa biaya proyek seperti:
-
NPV (Net Present value),
merupakan metode standar yang
menggunakan
nilai uang terhadap waktu untuk menilai suatu proyek dalam jangka panjang.
Biasanya
digunakan untuk
menganggarkan
modal awal,
keuangan
dan
akutansi.
-
PV
(Present Value),
adalah
nilai
uang
di
waktu
tertentu
(waktu
yang
akan
datang) yang dikonversikan menjadi nilai uang di waktu sekarang. Metoda ini
banyak digunakan dalam bisnis guna
mengetahui besaran dana
yang harus
disiapkan dalam untuk melaksanakan suatu proyek.
|
|
50
-
Cash
Back
Period,
merupakan
suatu
metoda
yang
digunakan
dalam
bisnis
untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan sampai seluruh modal yang
telah dikeluarkan dapat kembali.
Dalam penelitian ini digunakan metoda present value dikarenakan proyek
ini
masih
dalam tahap perencanaan dimana
biaya
yang diketahui
hanya
berupa
biaya
awal
(modal) dan
biaya
yang akan
datang dalam
waktu
tertentu
(biaya
perawatan). Sehingga dengan menggunakan metoda Present Value ini, nilai uang
yang
ada
di
waktu
tertentu
dapat
dikonversikan
menjadi
nilai
uang di
waktu
sekarang.
Nilai sekarang (present value)
merupakan nilai
yang dimiliki suatu mata
uang dimana jumlahnya akan lebih kecil
dari pada
nilai uang disaat
yang akan
datang. Besarnya selisih atas nilai uang tersebut kurang lebih sama dengan bunga
bank (discount rate)
yang berlaku saat ini
dan
tergantung jumlah tahun dimana
uang tersebut diperhitungkan.
Bila diketahui besarnya penerimaan pada waktu yang akan datang dalam
bentuk arus kas, maka kita dapat memperhitungkan besarnya nilai penerimaan itu
pada
saat
sekarang.
Jika
demikian
halnya,
maka
untuk
mencari
nilai
sekarang
(present value) dari jumlah tersebut dapat digunakan rumus sebagai berikut:
P
F
(1
i)
n
………………………………..……………………………..(2.14)
Dimana:
P
=
Nilai uang dimasa sekarang
F
=
Nilai uang dimasa yang akan datang
i
=
Nilai suku bunga (discount rate)
n
=
Waktu
|