|
7
Bab 2
Landasan Teori
Pada bab dua, penulis akan membahas teori-teori yang akan digunakan untuk
menganalisis unsur afeksi dan konsep
ii chichioya
dalam lagu Aitai
karya Yuujin
Kitagawa. Pertama, penulis akan memaparkan teori semantik, karena lagu ini
dipenuhi dengan kata-kata yang penuh dengan makna
tersirat, maka dari itu penulis
akan menggunakan teori semantik untuk mengungkap makna yang terdapat dalam
lagu Aitai ini.
2.1 Teori Semantik
Untuk menemukan makna sesungguhnya dari setiap kata-kata dalam lagu,
diperlukan studi pencarian makna. Dalam hal ini, proses pencarian makna akan
dilakukan melalui teori semantik.
Seperti yang dikatakan oleh Ikegami (1991):
??????????????(semantiks)????????????
??????????????????????????(‘The
study of meaning’ –The Random House Dictionary) ???????
????????(hal. 3)
Terjemahan:
Bila dilihat dari kamus biasa, semantik didefinisikan sebagai dasar ilmu
linguistik yang digunakan dalam studi yang berkaitan dengan penelitian makna.
Sedangkan menurut Hiejima (1991):
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
????(hal. 3)
|
|
8
Terjemahan:
“Hal yang berkaitan dengan makna, lebih baik dilihat secara prinsipal, daripada
secara objektif. Hal itu karena, makna lahir berdasarkan individu-individu.”
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, makna dari sebuah kata memang
tergantung dari sudut pandang orang.
Ketika seseorang memaknai sebuah kata,
bukan berarti pikirannya akan sama seperti orang lain, karena setiap orang memiliki
cara pandang mereka masing-masing.
2.1.2 Konsep Makna Kata
Makna sebuah kata dibedakan menjadi dua, yaitu makna yang bersifat denotatif
dan makna yang bersifat konotatif (Keraf, 2007, hal. 27)
a.
Makna denotatif
Chaer (2007, hal.
292) mengungkapkan bahwa makna denotatif adalah
makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah
leksem. Jadi, makna denotatif ini sebenarnya sama dengan makna leksikal.
Harley (1995, hal. 178) menyatakan bahwa denotatif dari sebuah kata
merupakan intinya, makna yang paling mendasar, semua orang mengerti dan
setuju dengan makna kata denotatif.
Dari semua pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa makna denotatif
adalah makna yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Keraf (2007, hal.
27), kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan
disebut kata denotatif, atau maknanya disebut makna denotatif.
b.
Makna Konotatif
Menurut Parera (2004,
hal. 99) makna konotatif bersifat merangsang dan
menggugah panca
indera, perasaan, sikap, dan keyakinan dan keperluan
|
|
9
tertentu. Rangsangan-rangsangan ini dapat bersifat individual dan kolektif.
Arah rangsangan pun dapat ke arah positif dan negatif. Klasifikasi rangsangan
ini bersifat tumpang tindih dan bergantian berdasarkan pengalaman dan
asosiasi yang muncul dan hidup pada individu dan masyarakat pemakai
bahasa dan pemanfaatan makna. Jadi, tidak ada konotasi yang baku dan tetap.
Ada makna konotasi yang pada suatu saat bersifat positif.
Sedangkan menurut Chaer (2007, hal. 292) makna konotatif adalah makna
lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai
rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut.
Pendapat tersebut dikuatkan oleh Keraf (2007, hal. 29), ia mengemukakan
bahwa makna konotasi adalah makna yang mengandung arti tambahan,
perasaan tertentu, atau nilai rasa
tertentu disamping makna dasar
yang
umumnya. Makna tersebut sebagian terjadi karena pembicara ingin
menimbulkan perasaan stuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan
sebagainya pada pihak pendengar dengan orang lain, sebab itu, bahasa
manusia tidak hanya menyangkut masalah makna denotatif atau ideasional
dan sebagainya.
setelah melihat pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa makna denotasi
adalah makna yang sesungguhnya dari sebuah kata. Sedangkan, makna konotasi
adalah makna yang memiliki arti lain dari kata sebenarnya, atau sering kita sebut
dengan makna kiasan.
2.1.3 Teori Medan Makna
Kata-kata memiliki asosiasi antara sesamanya. Berdasarkan hal tersebut
Ferdinand de Saussure
memulai konsep asosiasi makna
(2004, hal. 137). Ia pun
|
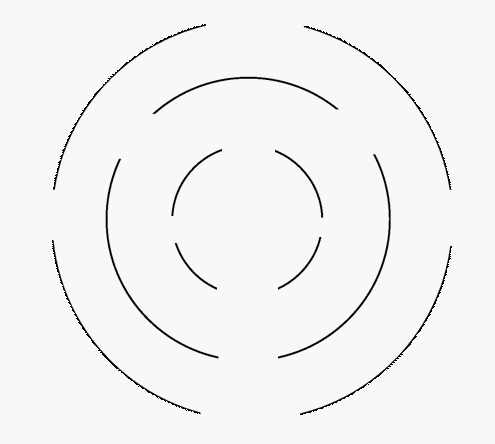   10
membedakan hubungan asosiatif menjadi empat, yaitu kesamaan formal
dan
semantik, similaritas semantik (butir umum), similaritas sufiks-umum biasa, serta
similaritas kebetulan.
Konsep tersebut lalu diperbaiki oleh Bally yang melihat medan asosiatif sebagai
satu lingkaran yang mengelilingi satu tanda dan muncul ke dalam lingkaran
leksikalnya (Parera, 2008, hal.
138). Berikut adalah skema medan asosiatif dari
Bally
Skema 2.1 Skema Medan Asosiatif Bally (Sumber: Parera, 2004, hal. 139)
Secara singkat, konsep medan makna yang diperbaiki oleh C. Bally dapat
disimpulan sebagai berikut:
“Medan makna adalah suatu jaringan asosiasi yang rumit berdasarkan pada
similaritas atau kesamaan, kontak atau hubungan dan hubungan-hubungan asosiatif
dengan penyebutan satu kata.” (hal. 139)
SLOWNESS
ENDURANCE
YOKE
STRENGTH
PATIENT
WALK
PLOUGH
TILLING
CALF
BULL
COW
HORNS
|
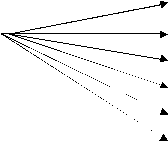 11
Sedangkan, Parera (2009) menggambarkan skema medan makna sebagai berikut:
Melirik
Melihat
Mengintip
Memandang
Menatap
Meninjau
Melotot
Skema 2.2 Medan makna menurut Parera (sumber: Parera, 2004, hal. 140)
Dalam Bahasa Indonesia, medan makna dari kata melihat dibedakan atas melirik,
mengintip, memandang, menatap, meninjau, melotot dan lainnya (Parera, 2004, hal.
140).
Sedangkan, menurut Chaer (2007) medan makna adalah seperangkat unsur
leksikal yang maknanya saling berhubungan (hal. 316)
2.2 Teori Afeksi
Menurut Meadow, dalam bukunya Other People
yang telah diterjemahkan dalam
Bahasa Indonesia berjudul “Memahami Orang Lain” (2006, hal. 96), afeksi adalah
cinta kepada orang yang paling dekat dengan kita. Biasanya anggota keluarga dan
mereka yang telah dianggap seperti keluarga sendiri. Afeksi tumbuh dari hubungan
dekat secara fisik, dan biasanya, orang tidak dapt mengatakan secara pasti kapan
mulainya. Kita menyadarinya: “Sejak kecil saya telah mengenal wajahnya…”
Dirinya juga berpendapat, bahwa afeksi adalah cinta yang dibutuhkan dalam
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Biasanya kita memperoleh afeksi dari
orangtua, dan juga kemudian kita memberikan afeksi kita kepada orang tua, saudara
|
|
12
dan anak-anak kita. Afeksi bersifat menyenangkan, sopan tanpa basa-basi. Bila
diliputi dengan afeksi, kita dengan mudah dapat bersikap santai.
Menurut Gonzalez, Barull, Pons dan Marteles dalam jurnal mereka “What is
Affection” (1998, para. 1), afeksi sering disamakan dengan emosi, padahal keduanya
merupakan fenomena yang sangat berbeda, meskipun memiliki kaitan
yang sangat
erat.
Emosi adalah respon individual dalam diri yang menunjukkan pertahanan diri
kita dalam kemungkinan yang selalu ada dalam situasi yang konkret. Sedangkan
afeksi adalah proses interaksi sosial antara dua organisme atau lebih.
Akan tetapi, terlepas dari perbedaan antara emosi dan afeksi, keduanya memang
memiliki kaitan yang sangat erat dan memberikan situasi yang sama untuk
mengekspresikan satu dan lainnya. Contohnya, kita mengatakan “Aku merasa sangat
aman” untuk emosi dan “Dia mendukungku penuh” untuk afeksi. Tampaknya kita
akan menunjuk afeksi yang diterima melalui emosi yang kita rasakan.
Mereka juga mengungkapkan karakteristik dari afeksi, yaitu:
1.
Afeksi adalah sesuatu yang terjadi diantara manusia, dan sesuatu yang
bersifat memberi dan menerima.
Kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan afeksi adalah
‘menerima’
dan ‘memberi’. Contohnya adalah “dia memberiku perasaaan
cintanya” atau
“aku memberinya kepercayaanku”. Dengan hal tersebut, kita
dapat mengatakan bahwa afeksi bersifat memberi dan menerima. Karena
itulah, afeksi merupakan sesuatu yang mengalir dan berpindah dari satu orang
ke orang lain.
Disamping itu, afeksi juga dapat terakumulasikan. Contohnya saat liburan
dalam rangka beristirahat dari rutinitas kerja yang padat, disaat itu kita masih
dapat memikirkan untuk menolong anak, teman, klien, murid,
pasangan dan
|
|
13
lainnya, ini berarti ada afeksi yang telah terakumulasi dalam diri kita
sehingga kita dapat memberi afeksi kembali kepada mereka.
2.
Untuk menghasilkan afeksi dibutuhkan usaha.
Pengalaman kita mengajarkan bahwa memberi afeksi kepada seseorang
memerlukan usaha.
Ada banyak usaha yang dapat mengekspresikan afeksi.
Sebagai contoh, menjaga seseorang yang sedang sakit, memahami seseorang
yang sedang dalam masalah, berusaha membahagiakan serta
menghormati
kebebasan orang lain, ataupun memberikan hadiah, semua hal tersebut adalah
tindakan yang memerlukan usaha.
3.
Afeksi adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, terutama di masa
kanak-kanak dan ketika sakit.
Pada akhirnya, kita dapat mengatakan bahwa afeksi adalah hal yang sangat
penting bagi manusia. Kita juga tidak akan mendengar seseorang mengatakan
bahwa dirinya tidak memerlukan kasih sayang. Dalam hal ini kita tahu bahwa
manusia membutuhkan kasih sayang. Tidak seperti spesies lain,
misalnya
kucing atau ular, manusia membutuhkan afeksi yang sangat besar, dan hal ini
dapat menjadi maksimum disaat-saat tertentu seperti ketika sakit atau masa
kanak-kanak.
Selain itu, menurut Murray (dalam Lorento & Gouaïch, 2010), terdapat 5 hal yang
dibutuhkan untuk menghasilkan afeksi, yaitu
1.
Afiliation
: meluangkan waktu dengan orang lain
2.
Nurturance
: merawat orang lain
3.
Play
: bermain dan bersenang-senang dengan orang lain
4.
Rejection
: menolak orang lain atau sesuatu demi sebuah
kebaikan
|
|
14
5.
Succorance
: ditolong atau dilindungi oleh orang lain
2.3. Konsep Fushi Kankei
Pada tahun 1970-an muncul frasa baru tentang sosok ayah di Jepang saat itu.
“Seorang ayah akan sangat diapresiasi ketika dia sehat dan berada di luar rumah.”
Ayah di Jepang memang kehidupannya didominasi pekerjaan, karena hal tersebutlah,
banyak keluarga di Jepang dianggap kehilangan sosok ayah. Bahkan ayah-ayah
disana sering disebut “Suami 7-11” hal ini merujuk pada jam saat mereka berangkat
kerja pukul 07:00 pagi dan pulang ketika waktu menunjukkan pukul 11:00 malam.
(Christiansen, 2009, para. 2).
Masalah kehilangan sosok ayah dalam keluarga, yang di Jepang dikenal dengan
istilah ‘chichi oya fuzai’ ini didasari atas pandangan orang Jepang, bahwa prioritas
utama seorang laki-laki adalah kesuksesan mereka dalam ekonomi. Bahkan definisi
maskulin untuk seorang pria pun sangat ditentukan dengan kesuksesan mereka di
tempat kerja. (Tamura, 2001, hal. 10).
Akan tetapi, tidak semua anak yang kehilangan sosok seorang ayah tidak dekat
dengan sang ayah. Meski mereka terpisah dan jarang bertemu, mereka tetap terikat
secara psikologis satu sama lainnya. Memang dibandingkan seorang ibu, ayah
memiliki waktu yang lebih sedikit bersama anak, namun dengan kesempatan yang
singkat tersebut, anak-anak menganggap ayah mereka sebagai sosok yang dapat
diandalkan. (Christiansen, 2001, para. 3)
Mengutip dari jurnal berjudul ????
????
??
??????
?
??tulisan Nagai (2004)
??(1997)???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????(2003)?Amato(1994)?????????(????
???????????)??????????(??????)???
|
|
15
?????????
Terjemahan:
Menurut Fuyuki (1997), cara seorang ayah mendidik anak, dan bagaimana image
yang tercipta, hal tersebut sama sekali tidak melibatkan seorang anak dalam
prosesnya. Jadi, masih banyak kesempatan bagi ayah itu sendiri menjadi ‘ayah
yang baik’. Ishikawa (2003) sama seperti Amato (1994) berpendapat bahwa
dukungan dari seorang ayah dapat menurunkan tingkat stres.
Usui (2009), seorang Doktor di bidang psikologi, dalam jurnalnya berjudul??
?????????????? ?????????????????
mengatakan:
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????!
?????????!
??????!
????!
??????
?????!???????????
Terjemahan
Singkatnya, dapat dikatakan ‘pria yang lembut tapi kuat”. Misalnya, ketika didalam
tiupan badai yang sangat dahsyat, seluruh anggota keluarga berkumpul
dibelakangnya. Dia berdiri paling depan sebagai penghalang angin bagi
keluarganya. Ketika anggota keluarga dibelakangnya cemas, didepannya ada sosok
kuat yang melindungi. “semuanya, tenang saja! Ada ayah disini, jangan khawatir.
Ayah tidak akan kalah, terus berada dibelakang ayah.”
Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ayah yang baik menurut
Mafumi
Usui adalah ayah yang melindungi. Ia mencontohkannya dengan seorang
ayah yang melindungi keluarganya, ketika terjadi badai.
Sedangkan Shwalb (1993, hal. 13), menyatakan bahwa ii chichioya terdiri dari 14
karakteristik, yaitu
1.
Lembut
dan terpercaya:
Bersikap lembut dalam pengasuhan sehingga anak
menjadi percaya.
|
|
16
2.
Pusat keluarga: Dominan dalam keluarga
3.
Tegas: Tegas dan jelas mendidik anak
4.
Pengertian: Memahami perasaan anak
5.
Pintar/toleran: Berpengetahuan luas, sehingga dapat mengajarkannya pada anak
6.
Pekerja keras: Berusaha dalam pekerjaannya demi kesejahteraan keluarga
7.
Kuat: Kuat, agar dapat melindungi keluarga
8.
Andalan keluarga: Dapat menjadi andalan atau tumpuan bagi keluarga
9.
Serius: Sungguh-sungguh dalam melakukan sebuah hal, dan tetap konsisten
10.
Bertanggung jawab:
Melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah.
bertanggung jawab atas keberadaan anak, ikut membantu dalam pengasuhan
11.
Berpengetahuan luas: Pintar agar dapat mengajarkannya kepada anak
12.
Berempati: Saling memahami dengan anak
13.
Dapat dipercaya: Dapat dipercaya sebagai pemimpin keluarga
14.
Layak dihormati: pantas untuk dihormati sebagai pemimpin keluarga.
2.4 Teori Pengkajian Puisi
Menurut Pradopo (1990, hal. 3) mengemukakan bahwa puisi adalah struktur yang
tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan. Lalu menurut
Wellek dalam Pradopo (1990, hal. 14), puisi merupakan sebab yang emmungkinkan
timbulnya pengalaman. Altenbernd dalam Pradopo (1990, hal. 5) mengemukakan
bahwa puisi adalah pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran dalam bahasa.
Dari ketiga makna tersebut, dapat dikatakan bahwa puisi mempunyai sifat, struktur
dan konvensi-konvensi puisi apapun pada umumnya.
Pradopo juga mengemukakan bahwa pengkajian puisi terbagi dalam dua bagian,
yaitu:
|
|
17
1.
Analisis struktur puisi berdasarkan lapis-lapis normanya yang merupakan
fenomena puisi yang ada. Arti lapis disini, berupa rangkaian fonem, suku kata,
kata, frasa dan kalimat. Rangkaian satuan-satuan arti ini menimbulkan lapis
ketiga yang berupa latar, pelaku, objek-objek yang dikemukakan dan dunia
pengarang yang berupa cerita atau lukisan (Pradopo, 1990, hal. 15)
2.
Analisis sajak satu persatu yang membicarakan kaitan antar unsur dan sarana-
sarana kepuitisan yang menyeluruh. Dalam analisis ini, lapis-lapis norma puisi
di lihat hubungan keseluruhannya dalam sebuah sajakyang utuh. Hal ini
disebabkan norma-norma puisi itu saling berhubungan erat dan saling
berhubungan maknanya (Pradopo, 1990, hal. 117).
|