|
3
BAB 2
DATA DAN ANALISA
2.1
Sumber Data
Data dan informasi untuk mendukung proyek Tugas Akhir ini diperoleh dari
berbagai sumber, antara lain :
1. Literatur
Penulis memakai banyak buku untuk mengetahui tokoh-tokoh Ramayana
seperti dari buku Atlas Tokoh-Tokoh Wayang dari Riwayat sampai Silsilahnya
karya Bendung Layung Kuning dan Sendratari Ramayana Prambanan Seni dan
Sejarahnya karya Drs. Moehkardi.Selain itu buku yang digunakan adalah komik
Ramayana karya R.A Kosasih.
Selain itu penulis juga menggunaka buku ilustrasi kontemporer sebagai
referensi, seperti Overkill karya Tomer Hanuka, Rebus karya James Jean dan
buku kumpulan ilustrasi kontemporer Illustrator’s Unlimited the Essence of
Contemporary Illustration.
2. Sarana entertainment
Untuk lebih mengenal kisah dan tokoh Ramayana, penulis memakai saran
entertainment berupa film.Film yang dimaksud adalah film animasi Ramayana:
The Epic yang diproduksi oleh produser India dan ditayangkan perdana pada tahun
2010. Selain itu penulis juga menggunakan film animasi festival Sita Sings the
Blues karya Nina Paley, film tersebut memadukan kisah Ramayana dengan konten
modern.
3. Survey
Penulis juga melakukan survey ke berbagai tempat untuk memperkuat data
dalam pengenalan tokoh Ramayana.Tempat yang penulis kunjungi adalah
Museum Wayang Jakarta dan pertunjukkan Sendratari Ramayana di Purawisata
Yogyakarta, yang diselenggarakan setiap hari.Selain itu penulis juga melakukkan
survey ke komunitas ilustrasi Kopi Keliling.
4. Kuesioner
Penulis menyebarkan kuesioner melalui internet untuk mengetahui
pandangan publik mengenai tokoh-tokoh dalam Ramayana dan bagaimana
tanggapan mereka. Berdasarkan kuesioner yang penulis sebarkan kepada 100
responden berusia 18 tahun hingga 25 tahun keatas dan berjenis kelamin pria
maupun wanita golongan A-B menunjukkan sebesar 86% responden pernah
mendengar kisah Ramayana namun tidak begitu jelas dan sebesar 69%
responden hanya mengetahui beberapa tokoh saja dalam kisah Ramayana. Selain
|
|
itu penulis mendapatkan 74% responded kesusahan dalam menentukan tokoh
dalam kisah Ramayana dikarenakan penggambaran visualnya yang serupa dan
sering tertukar dengan kisah pewayangan lainnya.
2.2
Data Umum Ilustrasi
2.2.1
Sejarah Ilustrasi
Ketika kita membicarakan gambar dalam konteks Ilustrasi berarti
memperbincangkan gambar dalam bingkai fungsi.Sisi fungsi sangat melekat
dalam kata ‘Ilustrasi’.Hal ini terjadi karena dalam sejarahnya
kata “Illustrate” muncul akibat pembagian tugas fungsional antara teks dan
gambar. Dari etimologinya Illustrate berasal dari kata ‘Lustrate’ bahasa Latin
yang berarti memurnikan atau menerangi. Sedangkan kata‘Lustrate’ sendiri
merupakan turunan kata dari * leuk- (bahasa Indo-Eropa) yang berarti ‘cahaya’
(Grolier Multimedia Encyclopedia 2001).Dalam konteks ini Ilustrasi adalah
gambar yang dihadirkan untuk memperjelas sesuatu yang bersifat tekstual.
Ilustrasi adalah anak industrialisasi yang mendambakan spesialisasi
dalam mekanisme kerjanya. Pada awal abad pertengahan terjadi pembagian tugas
kerja antara seorang ’Scrittori’ dan seorang ’Illustrator’ dalam pembuatan
sebuah illuminated manuscript.Posisi seorang Scrittori bertugas untuk
menyiapkan dan mendesain huruf atau kaligrafi dari teks sebuah buku atau
manuskrip. Sedangkan seorang Ilustrator bertugas untuk memproduksi ornamen
dan gambar yang memperjelas isi teks.Pemilahan tersebut mengawali dan
mempertegas istilah Ilustrasi menjadi selalu berdimensi fungsi.
Fungsi memperjelas sebuah teks atau bahkan memberi sentuhan dekorasi
pada lembar-lembar teks memberi gambaran bahwa saat itu gambar (ilustrasi)
adalah subordinan dari teks.Gambar adalah pelengkap teks.Gambar hanyalah
wahana untuk mengantarkan pemahaman secara lebih utuh dari sebuah
teks.Seorang Ilustrator harus dapat memahami isi teks dan kemudian
mengilustrasikannya dalam bentuk gambar.Kemampuan mentranslasikan dari
sesuatu yang tekstual ke dalam bentuk yang visual menjadi poin penting sebagai
seorang Ilustrator.Ilustrator berperan sebagai penerjemah (interpreter) ke pada
pembaca dari sesuatu yang abstrak (wilayah bahasa/tekstual) ke dalam sesuatu
yang konkret sifatnya (wilayah rupa).Tuntutan kepiawaiannya tidak berhenti
pada tataran olah rupa (visualisasi) saja, tetapi juga mencakup wawasan
(pemahaman terhadap teks) dan olah komunikasinya (bagaimana cara
menyampaikan kepada pembacanya melalui rupa).Posisi Ilustrator dalam hal ini
adalah sebagai visual interpreter.Secara fungsional Ilustrator berada di posisi
antara (in between) penulis dan pembacanya. Di sisi lain posisi seorang Ilustrator
adalah sebagai seorang visual dekorator. Menyiapkan iluminasi sebagai bingkai
penghias ataupun mengisi ruang-ruang kosong dalam sebuah manuskrip.
Era illuminated manuscript ini berakhir ketika gambar yang sebelumnya
dieksekusi melalui teknik manual, mulai dicetak dengan teknik woodcut.
|
|
Selanjutnya mekanisasi dan massalisasi sebuah buku menjadi semakin
menemukan bentuknya dengan penemuan movable type (1451).Walaupun
penyajiannya tidak terlalu beranjak jauh dari era illuminated manuscript; unsur
dekorasi dalam bentuk ornamen membingkai tiap halamannya dan gambar
kadang tampil penuh satu halaman sebagai penjelas teks.
Pada akhir abad 18, muncul sebuah Gerakan Romantik yang kemudian
mempengaruhi pergeseran posisi seorang Ilustrator dan fungsi dari
Ilustrasi.Gagasan baru yang ditawarkan adalah seorang ilustrator selayaknya
bebas dalam menginterpretasikan sebuah teks dengan keliaran
imajinasinya.Ilustrator menjadi lebih mandiri.Posisi yang pada awalnya
subordinan dari teks, kini memiliki nilai tawar dan tempatnya sendiri.Kebebasan
berkreasi tersebut menjadikan ilustrator bagai seorang seniman.Konsep ini
sebenarnya telah muncul lebih dulu pada abad 6 SM di Cina.Pada masa itu,
seorang pelukis juga seorang penyair.Dengan demikian, karyanya mencerminkan
gabungan dari keduanya.
Perkembangan selanjutnya mencapai titik puncak pergeseran fungsi
Ilustrasi adalah pada abad 19 di Perancis.Penanda penting adalah dengan
munculnya Livre De Peintre (painter’s book).Ilustrasi tidak hanya menjadi
bagian atau pelengkap sebuah buku, tetapi menjadi sesuatu yang sifatnya lebih
dominan. Buku –
buku tersebut di desain oleh para seniman dan diproduksi
dalam jumlah terbatas. Livre yang cukup berpengaruh adalah Pararellment karya
Pierre Bonnard yang ditulis oleh Paul Verlaine.Seniman-seniman lain yang juga
menghasilkan livre adalah Henry Matisse, Marc Chagall dan Pablo Picasso.
Kemandirian Ilustrasi bahkan kemudian semakin dikukuhkan dengan
aktifitas-aktifitas jurnalisme visual oleh para seniman yang terjun langsung di
daerah peperangan untuk mengabadikan secara on the spot melalui sketsa dan
gambar, ataupun para Kartunis dengan komentar-komentar visualnya melalui
kartun opininya.Dalam konteks ini Ilustrasi sudah tidak berfungsi sebagai
penjelas teks, tetapi sebagai teks (visual) yang berdiri sendiri. Ilustrasi tidak
sebagai perantara dari penulis kepada pembacanya, tetapi posisi Ilustrator
sebagai author itu sendiri. Ilustrasi menemukan otonominya sendiri.
2.2.2
Ilustrasi di Indonesia
Di Indonesia, sejarah tradisi ilustrasi dapat merujuk kepada lukisan gua
yang terdapat di Kabupaten Maros, provinsi Sulawesi Selatan dan di pulau
Papua.Jejak ilustrasi yang berumur hampir 5000 tahun itu menggambarkan
tumpukan jari tangan berwarna merah terakota. Selain lukisan gua, wayang beber
dalam hiburan tradisional Jawa dan Bali dilihat sebagai ilustrasi yang
merepresentasikan alur cerita kisah Mahabarata, tradisi yang kira-kira muncul
bersamaan dengan berdirinya kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Hindu di
Pulau Sumatera bagian Selatan.
|
|
Sejarah panjang Ilustrasi tidak bisa dilepaskan dari dunia buku.
Pemahaman kita terhadap fungsi Ilustrasi sebagai penjelas, memperindah atau
bahkan pemahaman fungsi yang lebih avant garde tidak terpisah dari
perkembangan dan pemaknaan ulang media
di mana ilustrasi tersebut
diaplikasikan. Pergulatan panjang posisi Ilustrator melalui cara ungkap visual
maupun pesan tidak lepas dari semangat jamannya.
Di Indonesia karya Ilustrasi dapat kita jejak melalui artifak-artifak visual
naratif yang ada.Merunut khasanah visual naratif di Indonesia tidak kalah
panjang dengan sejarah visual naratif di belahan dunia lainnya.Catatan-catatan
visual di garca-garca goa yang bertebaran dari Leang-leang di Sulawesi sampai
goa Pawon di Jawa Barat menjadi penanda bertutur
visual era pra
sejarah.Gambar-gambar pada lembar-lembar lontar ataupun pada media Wayang
Beber menandai era pra modern. Di era kolonialisasi muncul media-media
modern seperti majalah atau surat kabar. Melalui media surat kabar ataupun
majalah tersebut terjadi transfer ilmu (ilustrasi) baik teknis maupun gagasan dari
Ilustrator asing (penjajah) kepada para Ilustrator bumi putra. Walaupun istilah
’Ilustrasi’ bukan dari kamus bahasa kita sendiri, secara subtantif artifak-artifak
visual/gambar tersebut memiliki kesamaan secara fungsional, menjelaskan atau
menerangkan.
Dari rentang waktu antara th 1920-1960 (di Indonesia) dari artifak yang
berhasil dikumpulkan (dalam media massa) akan memberi gambaran dinamika
Ilustrator dan karya Ilustrasinya. Pengklasifikasian artifak temuan terdiri dari dua
jenis: ilustrasi untuk rubrikasi dan ilustrasi yang menjelaskan cerita atau artikel.
Ilustrasi pada rubrikasi secara fungsi menjelaskan atau memberi
gambaran umum tentang isi rubrik yang diwakilinya.Wakil-wakil visual adalah
resonansi dari judul-judul rubrikasi.Sebagai contoh, judul sebuah rubrikasi
”PAGERAKAN” atau pergerakan wakil visual yang hadir adalah sosok pemuda
berjas dan berpeci dengan gestur bergerak dinamis sebagai foreground.Ikon
catatan-catatan dan suluh lilin menjadi pelengkap penjelas rubrikasi tersebut
dalam background nya.Ada korelasi yang jelas antara gambar dan teks.Gambar
berfungsi memperjelas teks.Ilustrasi sebagai interpretasi visual terhadap teks.
Beberapa artifak rubrikasi dijumpai juga gambar-gambar memiliki
korelasi terasa jauh atau bahkan tidak berhubungan sama sekali dengan rubrik
yang diwakilinya. Teks bertuliskan ”Panjebar Semangat” sedangkan wakil visual
yang hadir adalah gambar pegunungan dengan sawah dan petani, atau stilasi
Kala menyerupai ukiran pintu gerbang.Pemilihan wakil-wakil visual tersebut
dapat kita baca lebih simbolis.Gambar landscape gunung beserta sawah dan
petani ataupun stilasi Kala tersebut sebagai subtitusi Nasionalisme atau Negara
Indonesia.Relasi antara gambar dan teks melalui pendekatan simbolis seperti itu-
pun masih terasa jauh.Relasi gambar dan teks tidak langsung menjelaskan,
terkadang malah terjebak sebagai dekorasi saja.Fungsi gambar pada ilustrasi
rubrikasi jenis ini memiliki kecenderungan besar kearah ilustrasi sebagai
dekorasi visual, walaupun tidak menutup kecenderungan lainnya.
|
|
Kategori lainnya adalah gambar–gambar yang menyertai teks di dalam
media massa. Artifak visual biasanya muncul mengiringi teks pada cerpen dan
tajuk utama atau editorial.Seorang Ilustrator dalam menanggapi teks melalui
gambar atau wakil visual yang dihadirkannya dapat kita klasifikasikannya dalam
dua pola; pertama, bagaimana Ilustrator mengolah pesan (what to say), kedua,
adalah bagaimana cara Ilustrator mengolah rupa (how to say).Hampir sebagian
besar artifak visual yang telah dikumpulkan bersifat Naratif dalam olah
pesannya.Dalam hal ini berarti Ilustrator memposisikan dirinya sebagai
interpreter visual.Modusnya mencoba menterjemahkan teks dengan mencari
moment yang paling menarik dan mewakili
dari naskah tersebut, kemudian
mencari wakil visualnya yang paling gamblang/jelas dalam menyampaikan
pesan.Beberapa artifak tampil unik dengan menggunakan pendekatan olah pesan
yang lebih metaforik. Artifak yang muncul di harian Fikiran Ra’jat (1932),
menggambarkan permasalahan imperialisme dengan metafora seekor anjing
berjenis Bulldog berkalung leher bertuliskan “Imperialisme“, dengan ujung ekor
muncul sosok kepala priyayi jawa yang bertuliskan “boeroeh imperialisme”.
Permainan subtitusi visual menghasilkan kiasan-kiasan tak langsung menguatkan
pesan yang disampaikannya.Ilustrator dengan pendekatan metafora, sedikit atau
banyak telah memasukkan opini pribadinya dalam menanggapi teks yang
ada.Gambar tidak hanya sebagai penjelas teks, tetapi sudah bergeser pada opini
visual yang lebih personal.Ilustrasi mulai mencari ruang-ruang otonominya.
Pada wilayah olah rupa, terjadi eksplorasi yang cukup luas (dalam
keterbatasan teknis yang ada) dari gaya visual yang rumit, realis, obyektif dan
khusus sampai ke wilayah ujung paradoksnya yang sederhana, ikonis atau
abstrak, subyektif dan umum. Rentang waktu antara tahun 1929 sampai 1951/53,
sebagian besar ilustrator menggali potensi garis, outline, dan bidang-bidang
datar.Garis-garis liris maupun ekspresif melalui media gambar pena, tinta dengan
kuas menghasilkan kualitas visual yang khas.Garis arsir membentuk tonal
gradasi maupun gelap terang dari obyek-obyek yang dihadirkannya.Di tahun
1956 ditemukan artifak ilustrasi bernada penuh dengan gradasi yang halus.
Kecenderungan tersebut dihadirkan melalui pendekatan teknis hitam putih media
cat air. Gaya gambar yang muncul lebih realis mendekati karya fotografis.Di
akhir 60-an muncul kecenderungan baru dalam mengolah huruf sebagai bagian
dari gambar.Tipografi sebagai gambar (type as image) adalah sebuah kesadaran
baru dari para ilustrator di era tersebut.Kemampuan olah huruf sebagai
pendukung resonansi visual, mengingatkan kita pada Onomatopea di ranah seni
sekuensial.
2.3
Data Umun Seni Tradisional
2.3.1
Seni Tradisional
Seni Tradisional merupakan unsur budaya yang sudah menjadi bagian
hidup masyarakat Indonesia. Berbicara tentang seni tradisional tentu merupakan
|
|
kaarya seni budaya yang sangat dikagumi oleh bangsa Indonesia, karena
mempunyai keunikan yang beragam
Setiap pulau atau wilayah di Indonesia memiliki seni tradisional atau
kebudayaan yang memberikan ciri khas wilayah tersebut.Beberapa seni
tradisional di Indonesia terkadang bukan asli berasal dari wilayah tersebut
sehingga terjadi kemiripan seni tradisional di beberapa tempat. Contohnya adalah
wayang, di Indonesia sendiri seni pertunjukan wayang berasal dari dari beberapa
wilayah sekaligus, tapi dengan adanya diferensiasi kebudayaan di setiap wilayah,
wayangpun memiliki banyak variasi dan memiliki ciri khas tersendiri di setiap
wilayah masing-masing seperti wayang golek asal Jawa Barat dan wayang purwa
asal Jogjakarta.
2.3.2
Wayang di Indonesia
Seni pertunjukan wayang sangat berkembang di Indonesia khususnya di
pulau Jawa dan Bali.Wayang adalah pertunjukkan bayangan boneka tersohor dari
Indonesia, dan sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni
bertutur.Bukan cuma di Indonesia yang memiliki seni pertunjukan boneka
namun banyak negara memiliki pertunjukkan boneka
sejenis. Pertunjukkan
bayangan boneka (Wayang) di Indonesia memiliki gaya tutur dan keunikkan
tersendiri, yang merupakan mahakarya asli dari Indonesia. Dan untuk itulah
UNESCO memasukannya ke dalam Daftar Warisan Dunia pada tahun 2003.
Tak ada bukti yang menunjukkan wayang telah ada sebelum agama
Hindu menyebar di Asia Selatan.Diperkirakan seni pertunjukkan dibawa masuk
oleh pedagang India.Namun demikian, kejeniusan local, kebudayaan yang ada
sebelum masuknya Hindu menyatu dengan perkembangan seni pertunjukkan
yang masuk memberi warna tersendiri pada seni pertunjukkan di Indonesia.
Sampai saat ini, catatan awal yang bisa didapat tentang pertunjukkan wayang
berasal dari Prasasti Balitung di Abad ke 4 yang berbunyi “si Galigi mawayang”
Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan kebudayaan
yang sudah ada, seni pertunjukkan ini menjadi media efektif menyebarkan agama
Hindu, dimana pertunjukkan wayang menggunakan cerita Ramayana dan
Mahabharata.
Demikian juga saat masuknya Islam, ketika pertunjukkan yang
menampilkan “Tuhan” atau “Dewa” dalam wujud manusia dilarang, munculah
boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, dimana saat pertunjukkan yang
ditonton hanyalah bayangannya saja, yang sekarang kita kenal sebagai wayang
kulit.
Untuk menyebarkan Islam, berkembang juga wayang Sadat yang
memperkenalkan nilai-nilai Islam.
Pun ketika misionaris Katolik, Pastor Timotheus L. Wignyosubroto SJ
pada tahun 1960 dalam misinya menyebarkan agama Katolik mengembangkan
Wayang Wahyu, yang sumber cerita berasal dari Alkitab.
|
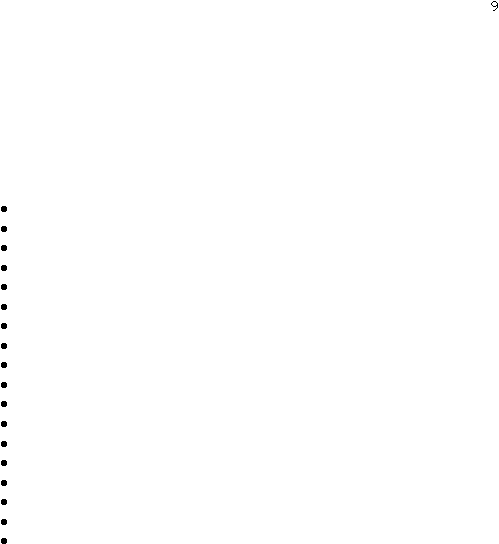 2.3.3
Jenis Wayang
Selama berabad-abad, budaya wayang berkembang menjadiberagam
jenis.Kebanyakan jenis jenis wayang itu tetap nenggunakanMahabarata dan
Ramayana sebagai induk ceritanya. Sedangkan alat peraganya pun berkembang
menjadi beberapa macam, antara lain yangterbuat dari kertas, kain, kulit, kayu,
dan juga WayangOrang.Perkembangan jenis wayang ini juga dipengaruhi oleh
keadaanbudaya daerah setempat.
Wayang Kulit
Wayang Wahyu
Wayang Golek/ Wayang ThengulBojonegoro
Wayang Menak
Wayang Krucil
Wayang Klitik
Wayang Purwa
Wayang Suluh
Wayang Beber
Wayang Papak
Wayang Orang
Wayang Madya
Wayang Gedog
Wayanng Parwa
Wayang Sasak
Wayang Sadat
Wayang Calonarang
Wayang Kancil
2.3.4
Sendratari
Arkeologi Belanda terkenal, Dr AJ Bernet Kempers, dalam bukunya
Ancient Indonesia Artmengatakan bahwa memiliki bakat kodrati dalam bidang
seni dan kerajinan tangan merupakan cirri khas bangsa Indonesia. Salah satu
cabang seni yang berkembang cukup subur adalah seni tari. Menurut Dr
Soedarsono, pakar tari Indonesia terkemuka, tari
adalah ekspresi jiwa manusia
melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Bangsa Indonesia, yang terdiri atas
berpuluh-puluh suku bangsa dan masing-masing memiliki adat dan tradisi sendiri
itu, sangat kaya dengan berbagai jenis tari.
Drama tari adalah karya tari yang berpijak pada alur cerita tertentu
misalnya Ramayana.Dipandang dari jumlah penarinya, missal tari tunggal atau
tari duet, drama tari dapat digolongkan sebagai tari massal karena jumlah
penarinya yang banyak. Drama tari bisa digolongkan menjadi tiga macam, yaitu
tari berdialog prosa, contohnya wayang wong, drama tari berdialog tembang
(drama tari opera), contoh langendarian Jawa Tengah, dan tari drama tari tanpa
dialog yang disebut sendratari (seni drama tari), contohnya Sendratari Ramayana
di Prambanan.Berdasarkan uraian di atas, Sendratari Ramaya bila dipandang dari
|
|
1
segi isi dan temanya tergolong sebagai drama tari, dari fungsinya adalah tarian
pertunjukan, dari segi bentuk koreografinya berupa tarian klasik, dan bila
ditinjau dari jumlah penarinya termasuk tarian massal.
2.4
Data Umum Ramayana
2.4.1
Sejarah Ramayana
Ramayana adalah epos India yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat
Asia Tenggara.Di Indonesia, kita mengenalnya melalui komik, prosa, drama dan
wayang, bahkan serialnya pernah disiarkan di televisi.Kisah tersebut rupanya
berkenan di hati orang Indonesia.Bahkan bila dilihat dari bukti-bukti arkeologi
dan sastra kuno, Ramayana telah dikenal dan digemari nenek moyang kita sejak
abad ke-9. Sementara di kawasan Asia Tenggara lainnya,
seperti Burma,
Thailand, Laos, Kamboja, dan Malaysia, Ramayana sudah dikenal sejak kurun
waktu yang lebih tua, yaitu abad pertama masehi.
India, negri asal Ramayana, memiliki dua epos termahsyur, yaitu
Ramayana dan Mahabarata.Kedua epos tersenut disebarluaskan lewat sastra tulis
dan lisan dari generasi ke generasi.Di India, kedua epos tersebut tidak hanya
dipandang sebagai karya sastra tulis, melainkan buku keagamaan karena isinya
yang sarat ajaran moral.Ramayana menceritakan kisah Rama dan Sita dari
kerajaan Kosala di India utara yang beribukota Ayodya, melawan Ravana, Raja
Lanka (sekarang Sri Lanka).
Ramayana disusun dari 200 SM hingga 200 M. Pengarangnya bernama
Valmiki, atau di Indonesia dikenal dengan Walmiki.Ramayana terdiri dari 24.000
sloka dan terbagi menjadi 7 kanda (jilid), dan sisipan hanya terdapat pada kanda
pertama dan terakhir. Ditinjau dari segi sastra, mutu penulisan setiap kanda
Ramayana relatif sama karena pengarangnya satu orang, sedangkan Mahabarata
berbeda-beda, pertanda bahwa buku tersebut ditulis oleh lebih satu orang. Di
Indonesia Mahabarata lebih populer dibandingkan Ramayana, namun begiru, di
Asia Tenggara lainnya, epos Ramayana lebih digemari daripada Mahabarata.
2.4.2
Kisah Ramayana
Dikisahkan di sebuah negeri bernama Mantili ada seorang puteri nan
cantik jelita bernama Dewi Shinta. Dia seorang puteri raja negeri Mantili yaitu
Prabu Janaka. Suatu hari sang Prabu mengadakan sayembara untuk mendapatkan
sang Pangeran bagi puteri tercintanya yaitu Shinta, dan akhirnya sayembara itu
dimenangkan oleh Putera Mahkota Kerajaan Ayodya, yang bernama Raden
Rama Wijaya. Namun dalam kisah ini ada juga seorang raja Alengkadiraja yaitu
Prabu Rahwana, yang juga sedang kasmaran, namun bukan kepada Dewi Shinta
tetapi dia ingin memperistri Dewi Widowati. Dari penglihatan Rahwana, Shinta
dianggap sebagai titisan Dewi Widowati yang selama ini diimpikannya.
Dalam sebuah perjalanan Rama dan Shinta dan disertai Lesmana adiknya, sedang
|
|
1
melewati hutan belantara yang dinamakan hutan Dandaka, si raksasa Prabu
Rahwana mengintai mereka bertiga, khususnya Shinta. Rahwana ingin menculik
Shinta untuk dibawa ke istananya dan dijadikan istri, dengan siasatnya Rahwana
mengubah seorang hambanya bernama Marica menjadi seekor kijang
kencana.Dengan tujuan memancing Rama pergi memburu kijang ‘jadi-jadian' itu,
karena Dewi Shinta menginginkannya.Dan memang benar setelah melihat
keelokan kijang tersebut, Shinta meminta Rama untuk menangkapnya. Karena
permintaan sang istri tercinta maka Rama berusaha mengejar kijang seorang diri
sedang Shinta dan Lesmana menunggui.
Dalam waktu sudah cukup lama ditinggal berburu, Shinta mulai
mencemaskan Rama, maka meminta Lesmana untuk mencarinya.Sebelum
meninggalkan Shinta seorang diri Lesmana tidak lupa membuat perlindungan
guna menjaga keselamatan Shinta yaitu dengan membuat lingkaran
magis.Dengan lingkaran ini Shinta tidak boleh mengeluarkan sedikitpun anggota
badannya agar tetap terjamin keselamatannya, jadi Shinta hanya boleh bergerak-
gerak sebatas lingkaran tersebut.Setelah kepergian Lesmana, Rahwana mulai
beraksi untuk menculik, namun usahanya gagal karena ada lingkaran magis
tersebut. Rahwana mulai cari siasat lagi, caranya ia menyamar yaitu dengan
mengubah diri menjadi seorang brahmana tua dan bertujuan mengambil hati
Shinta untuk memberi sedekah. Ternyata siasatnya berhasil membuat Shinta
mengulurkan tangannya untuk memberi sedekah, secara tidak sadar Shinta telah
melanggar ketentuan lingkaran magis yaitu tidak diijinkan mengeluarkan
anggota tubuh sedikitpun! Saat itu juga Rahwana tanpa ingin kehilangan
kesempatan ia menangkap tangan dan menarik Shinta keluar dari lingkaran.
Selanjutnya oleh Rahwana, Shinta dibawa pulang ke istananya di Alengka.Saat
dalam perjalanan pulang itu terjadi pertempuran dengan seekor burung Garuda
yang bernama
Jatayu yang hendak menolong Dewi Shinta.Jatayu dapat
mengenali Shinta sebagai puteri dari Janaka yang merupakan teman baiknya,
namun dalam pertempuan itu Jatayu dapat dikalahkan Rahwana.
Disaat yang sama Rama terus memburu kijang kencana dan akhirnya
Rama berhasil memanahnya, namun kijang itu berubah kembali menjadi raksasa.
Dalam wujud sebenarnya Marica mengadakan perlawanan pada Rama sehingga
terjadilah pertempuran antar keduanya, dan pada akhirnya Rama berhasil
memanah si raksasa.Pada saat yang bersamaan Lesmana berhasil menemukan
Rama dan mereka berdua kembali ke tempat semula dimana Shinta ditinggal
sendirian, namun sesampainya Shinta tidak ditemukan. Selanjutnya mereka
berdua berusaha mencarinya dan bertemu Jatayu yang luka parah, Rama
mencurigai Jatayu yang menculik dan dengan penuh emosi ia hendak
membunuhnya tapi berhasil dicegah oleh Lesmana. Dari keterangan Jatayu
mereka mengetahui bahwa yang menculik Shinta adalah Rahwana! Setelah
menceritakan semuanya akhirnya si burung garuda ini meninggal.
Mereka berdua memutuskan untuk melakukan perjalanan ke istana
Rahwana dan ditengah jalan mereka bertemu dengan seekor kera putih bernama
Hanuman yang sedang mencari para satria guna mengalahkan Subali.Subali
|
|
1
adalah kakak dari Sugriwa paman dari Hanuman, Sang kakak merebut kekasih
adiknya yaitu Dewi Tara.Singkat cerita Rama bersedia membantu mengalahkan
Subali, dan akhirnya usaha itu berhasil dengan kembalinya Dewi Tara menjadi
istri Sugriwa. Pada kesempatan itu pula Rama menceritakan perjalanannya akan
dilanjutkan bersama Lesmana untuk mencari Dewi Shinta sang istri yang diculik
Rahwana di istana Alengka. Karena merasa berutang budi pada Rama maka
Sugriwa menawarkan bantuannya dalam menemukan kembali Shinta, yaitu
dimulai dengan mengutus Hanuman persi ke istana
Alengka mencari tahu
Rahwana menyembunyikan Shinta dan mengetahui kekuatan pasukan Rahwana.
Taman Argasoka adalah taman kerajaan Alengka tempat dimana Shinta
menghabiskan hari-hari penantiannya dijemput kembali oleh sang suami. Dalam
Argasoka Shinta ditemani oleh Trijata kemenakan Rahwana, selain itu juga
berusaha membujuk Shinta untuk bersedia menjadi istri Rahwana. Karena sudah
beberapa kali Rahwana meminta dan ‘memaksa' Shinta menjadi istrinya tetapi
ditolak, sampai-sampai Rahwana habis kesabarannya yaitu ingin membunuh
Shinta namun dapat dicegah oleh Trijata. Di dalam kesedihan Shinta di taman
Argasoka ia mendengar sebuah lantunan lagu oleh seekor kera putih yaitu
Hanuman yang sedang mengintainya. Setelah kehadirannya diketahui Shinta,
segera Hanuman menghadap untuk menyampaikan maksud kehadirannya
sebagai utusan Rama.Setelah selesai menyampaikan maskudnya Hanuman
segera ingin mengetahui kekuatan kerajaan Alengka. Caranya dengan membuat
keonaran yaitu merusak keindahan taman, dan akhirnya Hanuman tertangkap
oleh Indrajid putera Rahwana dan kemudian dibawa ke Rahwana. Karena
marahnya Hanuman akan dibunuh tetapi dicegah oleh Kumbakarna adiknya,
karena dianggap menentang, maka Kumbakarna diusir dari kerjaan Alengka.
Tapi akhirnya Hanuman tetap dijatuhi hukuman yaitu dengan dibakar hidup-
hidup, tetapi bukannya mati tetapi Hanuman membakar kerajaan Alengka dan
berhasil meloloskan diri.Sekembalinya dari Alengka, Hanuman menceritakan
semua kejadian dan kondisi Alengka kepada Rama.Setelah adanya laporan itu,
maka Rama memutuskan untuk berangkat menyerang kerajaan Alengka dan
diikuti pula pasukan kera pimpinan Hanuman.
Setibanya di istana Rahwana terjadi peperangan, dimana awalnya pihak
Alengka dipimpin oleh Indrajid.Dalam pertempuran ini Indrajid dapat dikalahkan
dengan gugurnya Indrajit.Alengka terdesak oleh bala tentara Rama, maka
Kumbakarna raksasa yang bijaksana diminta oleh Rahwana menjadi senopati
perang.Kumbakarna menyanggupi tetapi bukannya untuk membela kakaknya
yang angkara murka, namun demi untuk membela bangsa dan negara
Alengkadiraja.Dalam pertempuran ini pula Kumbakarna dapat dikalahkan dan
gugur sebagai pahlawan bangsanya. Dengan gugurnya sang adik, akhirnya
Rahwana menghadapi sendiri Rama. Pad akhir pertempuran ini Rahwana juga
dapat dikalahkan seluruh pasukan pimpinan Rama. Rahmana mati kena panah
pusaka Rama dan dihimpit gunung Sumawana yang dibawa Hanuman.
Setelah semua pertempuran yang dasyat itu dengan kekalahan dipihak
Alengka maka Rama dengan bebas dapat memasuki istana dan mencari sang istri
|
|
1
tercinta. Dengan diantar oleh Hanuman menuju ke taman Argasoka menemui
Shinta, akan tetapi Rama menolak karena menganggap Shinta telah ternoda
selama Shinta berada di kerajaan Alengka. Maka Rama meminta bukti
kesuciannya, yaitu dengan melakukan bakar diri. Karena kebenaran kesucian
Shinta dan pertolongan Dewa Api, Shinta selamat dari api. Dengan demikian
terbuktilah bahwa Shinta masih suci dan akhirnya Rama menerima kembali
Shinta dengan perasaan haru dan bahagia.Dan akhir dari kisah ini mereka
kembali ke istananya masing-masing.
2.4.3
Tokoh-tokoh Wayang Ramayana
Anggada
Anila
Anjani
Anoman ( Hanuman )
Aswanikumba
Barata
Bisawarna
Bukbis
Dasarata
Gunawan Wibisana
Guwarsa ( Subali )
Guwarsi ( Sugriwa )
Indrajid
Jambumangli
Janaka
Jatasura
Jatayu
Jembawan
Jembawati
Kalamarica
Kapi Menda
Kapi Saraba
Kapi Suweda
Kekayi
Kumba-kumba
Kumbakarna
Lawa dan Kusya
Laksmana Widagda ( Laksmana )
Lembusura
Mahesasura
Prahasta
Rahwana
Raghu ( Sukasalya )
Rama Wijaya ( Rama )
|
|
1
Sarpakenaka
Sayempraba
Sempati
Sinta
Sumitra
Tara dan Tari
Trijata
2.4.4
Ramayana di Indonesia
Naskah Ramayana tertua di Indonesia adalah Ramayana,
yang ditulis dalam bahasa Jawa Kuno dalam bentuk kakawin, yaitu
syair yang dilagukan (selanjutnya kita sebut Ramayana
Kakawin).Menurut cerita di Bali, Ramayana Kakawin ditulis oleh
Yogiswara.Tapi pendapat tersebut disangkal oleh Prof. Dr RM
Ng.Poerbatjaraka, pakar epigraf pertama Indonesia. Menurut
Poerbatjaraka, kata Yogiswara yang tertera di bagian akhir naskah
tersebut bukan nama orang melainkan istilah yang berarti pendeta.
Pengarang kitab tersebut hingga kini belum diketahui dengan pasti.
Mengenai kapan Ramayana Kakawin ditulis, masih terdapat
perbedaan di antara para ahli. Prof. Dr H Kern, sarjana Belanda
yang pada 1906 menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Jawa,
menduga Kakawin ditulis pada abad ke-13. Poerbatjaraka, yang
melakukan penelitian mendalam pada naskah tersebut, berpendapat
bahwa Ramayana Kakawin ditulis pada zaman Raja Mataram Rakai
Watukara Dyah Balitung (900-908 M). Hasil penelitian terakhir dari
sarjana Jerman, W Archele, menyatakan tahun yang lebih awal,
yaitu tahun 850, pada zaman Raja Mataram Rakai Pikatan.Kalau
pendapat kedua sarjana terakhir itu benar, berarti Ramayana
Kakawin merupakan karya sastra Jawa Kuno tertua.
Poerbatjaraka memuji Ramayana Kakawin sebagai karya
sastra Jawa Kuno terindah. Ucapnya, "Seumur hidup belum pernah
saya membaca kitab Jawa yang memadai kitab Ramayana Kakawin
dalam hal bahasanya. Betapa pandainya sang pujangga menyusun
kata dan bermain metafora, seperti terlihat dalam cuplikan bait 24
dan 25 dari sarga VIII Ramayana Kakawin, yang melukiskan
kesedihan dan rindu dendam Rama setelah kehilangan Sinta:
"Bila kulihat kijang,
kuterkenang kan pandang matamu yang jelita.
Bila ku melihat gajah,
Sadarlah aku betapa besar keterlibatanmu dalam kesusahan.
Air dalam kedalaman telaga berombak-ombak,
|
|
1
Bagaikan gerak lunglai lenganmu.
Sayap merak mengingal bersinar mengkilap,
Bagaikan gemerlapnya tata rias rambutmu."
Ramayana Kakawin memiliki kisah yang agak berbeda dari
Ramayana versi Walmiki. Pada Ramayana Kakawin tidak terdapat
Kanda Pertama dan Kanda Ketujuh dan cerita berakhir setelah
Sinta, melalui api unggun, terbukti kesuciannya. Hasil penelitian
Poerbatjaraka dan sarjana-sarjana setelahnya, seperti C Hooykaas,
menunjukkan bahwa sumber Ramayana Kakawin bukanlah
Ramayana Walmiki, melainkan Ravanavadha karangan pujangga
Bhatti dari India yang ditulis sekitar 500-600 M. Perbandingan
secara mendetail antara Ramayana Kakawin, Ravanavadha, dan
Ramayana Walmiki yang dilakukan oleh Hooykaas mengungkapkan
bahwa sampai dengan syair XVI penggubah Ramayana Kakawin
mengikuti Ravanavadha dengan menyisipkan hal-hal yang dianggap
perlu, sesuai seleranya, misalnya uraian tentang Nitisastra,
Percandian Siwa, dan adegan Rama menerima dan membaca surat
dari Sinta. Namun mulai sarga XVII sampai akhir (sarga XXVI),
Kakawin sangat menyimpang dari Ravanavadha.Beberapa bagian
dari sarga XVII sampai dengan XXVI ditemukan kembali dalam
karya Walmiki.Sarga adalah satu kelompok syair yang mengisahkan
peristiwa tertentu.
Uraian tentang Nitisastra terdapat pada Sarga III, bait 53-
85, ketika Rama menyuruh Barata, adiknya, untuk memerintah di
Ayodya mewakili dirinya, dan membekalinya dengan ajaran tentang
tingkah laku dan kewajiban seorang raja. Uraian tentang Nitisastra
yang termasuk ajaran abstrak terdapat juga pada sarga XXIV, bait
43-86, yaitu ajaran Rama kepada Wibisana, yang ditetapkan sebagai
raja Alengka untuk menggantikan kakaknya, Rahwana.
Sedangkan uraian tentang Percandian Siwa terdapat dalam
sarga XVIII, bait 43-58. Poerbatjaraka berpendapat bahwa sang
pujangga, dalam membuat
uraian itu, membayangkan Percandian
Siwa di Prambanan berada di depan matanya. Atas dasar analisa itu,
ia berpendapat bahwa Ramayana Kakawin dibuat sezaman atau
setelah Candi Prambanan berdiri. Karena itu relief Ramayana di
Candi Prambanan tidak bersumber kepada Ramayana Kakawin;
versi Ramayana Prambanan lebih mirip dengan Hikayat Sri Rama
yang ditulis dalam bahasa Melayu.
2.4.5
Ramayana di Negara lain
Ramayana memang punya banyak versi. Di India sendiri, di
luar Ramayana Walmiki, terdapat berpuluh-puluh versi cerita Rama
seperti Adhyatma Ramayana, Adbhuta Ramayana, Vishnu Purana,
Mahi Ravaner Pala, dan masih banyak lagi. Hampir tiap suku dan
|
|
1
golongan agama Hindu di India memiliki versi sendirisendiri
tentang cerita Rama, ada yang sedikit perbedaannya, tapi ada pula
yang besar.Sementara tokoh Rama sendiri lama kelamaan memiliki
rupa yang beragam. Ada yang menganggap Rama sekadar raja yang
gagah berani dan baik pekertinya, ada yang menganggap ia sebagai
awatara (titisan) Dewa Wisnu; bah-
kan ada yang menganggap
Rama sebagai Dewa Tertinggi yang menguasai alam semesta dan
abadi.
Di luar India, selain di Indonesia, terdapat pula berbagai
versi cerita Rama, seperti Rama Jataka di Laos, Riemkerr di Kam-
boja, bermacam cerita Ramakien di Thailand, beberapa versi Rama
di Vietnam dan Myanmar, Hikayat Sri Rama di Malaysia, serta
Anamaka Jataka dan Dasaratha Jataka di Cina dan Tibet. Berbeda
dengan versi Asia Tenggara, versi Ramayana di Cina dan Tibet
telah berbaur menjadi satu dengan ajaran Buddha.Kedua cerita
Rama di
Cina tertuang dalam Budhis Mahavibhara.Di buku itu
Rama dianggap sebagai Bodhisattva yang telah men-
capai
paramitas (kesempurnaan) dan musuh Rama bukanlah Rahwana,
melainkan pamannya sendiri yang berusaha merebut takhta.Sinta
juga tidak diculik oleh Rahwana, melainkan oleh seekor naga yang
menjelma menjadi resi atau pendeta.
Versi Ramayana yang amat menyimpang, bahkan bertolak
belakang dengan versi Ramayana India, adalah versi Ramayana dari
Sailan (Sri Lanka).Tokoh Rahwana yang biasanya digambarkan
sebagai raja yang lalim, angkara murka, dan sebagainya, justru
berbudi luhur dan agung.Ia dipuja sebagai raja patriotik yang berani
menentang ekspansi Hindu (Rama) ke Sailan.Pada masa
pemerintahan Rahwana, Langkapura mengalami zaman
keemasan.Ia dikenang sebagai
raja yang arif bijaksana dan
wibawanya sampai ke daratan India selatan.Ia juga dikenang
sebagai cendekiawan yang berwawasan luas, penulis buku ilmu
pengetahuan, penyair, serta pemusik.Di Sailan kisah Ramayana
tidak berpusat pada permasalahan erotis, tapi lebih berlatar
belakang pada segi politis-religius. Rahwana, yang memerintah
Langkapura tahun 2554-2517 SM, ialah raja yang progresif, berani
menentang ritual pengorbanan hewan, bahkan manusia, yang
terdapat dalam upacara Hindu.
Rama sebaliknya adalah raja yang konservatif, mati-matian
membela tradisi lama ritual keagamaan Hindu, bahkan terkadang
kejam. Secara politis, Rama digambarkan cemburu terhadap
popularitas Rahwana dan khawatir Rahwana akan mengancam
kedaulatan kerajaannya di India. Lesmana diceritakan menikah dan
bahagia bersama Sarpokenoko, adik Rahwana, tapi ditentang oleh
rakyat India yang dihasut Rama. Rahwana yang prihatin akan nasib
adiknya lalu datang ke Ayodya untuk menjemputnya. Pada
|
|
1
kesempatan itulah Rahwana bertemu dengan Sinta yang sedang
kesepian ditinggalkan Rama berburu.Ringkas cerita, Sinta jatuh
cinta kepada Rahwana dan mengikuti Rahwana pulang ke
Langkapura.Akibatnya bisa ditebak, Rama marah dan cemburu lalu
mengumumkan perang melawan Langkapura.Dalam perang itu
Ramaberhasil menjalinhubungan dengan Wibisana, adik Rahwana
yang berkhianat dan berambisi merebut takhta kakaknya. Rahwana
akhirnya tewas, bukan di tangan Rama, melainkan di tangan
Wibisana yang kemudian menggantikannya menjadi Raja
Langkapura.
2.4.6
Alternatif Cerita Ramayana di Indonesia
Di Indonesia, selain Ramayana Kakawin dan Hikayat Sri
Rama, terdapat pula Serat Rama, Uttara Rama, Uttara Kanda Jawa,
Cerita Rama, Serat Kanda, Rama Keling, dan berbagai lakon
wayang purwa yang terhimpun dalam Serat Padalangan Ringgit
Purwa. Hikayat Sri Rama sendiri juga masih terbagi dalam
beberapa versi, yaitu versi PP Roarda van Eysinga yang terbit tahun
1843, versi WE Maxwell yang terbit tahun 1886, dan versi WG
Shellabean, terbit tahun 1917.
Dengan adanya berbagai versi dan penyimpangan cerita
Rama dari Ramayana Walmiki yang dianggap sebagai versi
orisinal, sejak 100 tahun lalu, di Indonesia, berbagai sarjana menco-
ba mengungkap sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.
Semula orang berpendapat bahwa berbagai cerita Ramayana di
Indonesia adalah hasil perombakan dan atau perusakan yang di-
lakukan para pengarang karena mereka tak menguasai bahasa
Sansekerta.Pendapat demikian kemudian ditinggalkan oleh para
ahli.
WH Ressers, dalam disertasinya "De Pandji Roman" (1922),
berpendapat bahwa berbagai cerita Ramayana di Indonesia ber-
sumber pada Ramayana Walmiki, tapi para pengarang Indonesia
sengaja membuat perbedaan agar cerita Rama sesuai struktur cerita
Panji, dengan demikian cocok dengan alam pikiran dan tata nilai
bangsa Indonesia.Cerita Panji terjadi pada pertengahan zaman
Majapahit.Salah satu cerita Panji yang terkenal adalah cerita Panji-
Anggraeni.Ceritanya mengisahkan Raden Panji Wanengpati, putra
Raja Jenggala yang ditunangkan de-
ngan Dewi Sekartaji, putri
Raja Kediri.Masalah timbul karena Raden Panji jatuh cinta kepada
Dewi Anggraeni, putri Patih Jenggala.Mengetahui hal itu, Raja
Jenggala memerintahkan agar Anggraeni dibunuh.Keindahan cerita
Panji memunculkan berbagai versi cerita di Bali, Melayu, bahkan
sampai ke Siam dan Kamboja.
WF Stutterheim menganalisa berbagai cerita Rama dengan
panjang lebar dalam disertasinya "Rama Legenden und Rama
|
|
1
Reliefs in Indonesia" (1925).Ia menolak pokok pendapat
Ressers.Stutterheim membuktikan bahwa sumber semua
penyimpangan harus dicari terutama dalam cerita-cerita Rama yang
terdapat di India selatan; bukti-bukti yang dikemukakannya cukup
meyakinkan.Dia juga menegaskan bahwa kisah Rama dan Rahwana
dalam sastra Jawa dan Melayu mempunyai hubungan organis yang
erat dan lebih luas dibandingkan cerita
dewa dan raja dalam
berbagai versi cerita Rama di India.Perbandingan sepintas saja
sudah dapat mengungkapkan hubungan berbagai versi cerita Rama
di Indonesia dengan berbagai versi cerita di India selatan.Teori
Stutterheim mirip dengan teori Poerbatjaraka dalam mengaitkan
Ramayana Kakawin dengan versi Bhattikavya.
Dra. Edi Sedyawati, dalam kata pengantar Ramadewa karya
Herman Pratikto, mencoba mengaitkan penyimpangan cerita Rama
dengan tradisi sanggit dalam kebudayaan tradisional Indonesia,
khususnya di Jawa dan Bali. Sanggit adalah penyusunan suatu
cerita yang telah dikenal secara khas, yang dilakukan oleh seorang
seniman atas dasar pandangan hidup, pendirian, selera, maupun
tujuan-tujuan tertentu yang mungkin dimiliki seniman tersebut
dalam menampilkan suatu cerita. Kepribadian sang seniman
menentukan watak karya-karyanya; ada yang suka menekankan
pada unsur dramatis, ada yang suka pada unsur kelembutan yang
menyentuh perasaan, ada yang cenderung pada pendalaman nilai-
nilai hidup yang menyangkut kebenaran, hakikat ketuhanan, cara
hidup yang tepat, dan sebagainya.
Akibatnya dalam dunia wayang purwa lahirlah berbagai
cerita carangan atau lakon cabang kreasi para dalang dari generasi
ke generasi.Lakon carangan adalah lakon yang ditambahkan pada
lakon-lakon pokok.Lakon ini terutama terdapat dalam Mahabharata,
namun di Ramayana juga ada. Dari 149 lakon wayang yang dicatat
oleh J Kats, 117 di antaranya adalah lakon carangan. Kebanyakan
lakon carangan mengisahkan peristiwa ketika Pandawa berkuasa di
Amarta, suatu
periode yang jauh lebih pendek daripada periode
sebelumnya.
Contoh cerita yang menyimpang dari induk cerita Ramayana
di karya sastra dan pewayangan di Jawa adalah Rama Nitik dan
Rama Nitis.Tokoh-tokoh Ramayana, yang tentu lebih tua, diper-
temukan dengan tokoh-tokoh Mahabharata. Dikisahkan Rama,
sebagai awatara Wisnu, pada akhirnya menitis pada Kresna, sedang
Lesmana menitis pada Arjuna. Hanuman sebagai tokoh populer
dalam Ramayana juga ditampilkan kembali.Hanuman yang sudah
berusia lanjut tapi masih sakti itu kadang-kadang dipanggil Kresna
jika negeri Dwarawati dan keluarga Pandawa menghadapi kesulitan
yang tak teratasi.
|
|
1
Di antara cerita Rama versi Jawa, yang paling populer di
kalangan rakyat adalah Serat Rama karya Jasadipura I (1729-
1802).Jasadipura I dan Jasadipura II ialah ayah dan anak, dua
pujangga istana Surakarta yang dianggap sebagai pelopor pem-
bangunan kepustakaan Jawa pada zaman Surakarta awal (abad
XVIII-XIX).Serat Rama digubah ke dalam bentuk macapat, yaitu
syair yang dilagukan (tembang).Poerbatjaraka menyebut kitab
Rama Jarwa (terjemahan Serat Rama) sebagai kitab Jawa terbaik
masa sekarang.Pujangganya juga pandai menyusun kalimat
berkidung sehingga sedap dibaca. Namun demikian Poerbatjaraka
secara kritis menilai kelemahan sang pujangga yang dianggap
kurang menguasai bahasa Jawa Kuno sehingga sering meraba-raba,
bagian yang tak dipahami dihilangkan dan diganti bagian yang
dianggap patut yang tidak merusak jalan cerita. Ada kalanya bagian
yang tak dipahami itu diringkas sehingga keliru mengartikan.
Berbeda dengan Ramayana Kakawin, Serat Rama diawali
adegan istana dan asal-usul keluarga Rahwana, sedang cerita
Ramayana dimulai dari bait ke-13 bagian I. Kisah Rahwana tersebut
adalah kutipan dari Kitab Arjuna Wijaya (Arjuna Sasrabahu) karya
Empu Tantular dari masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit
(abad ke-14).Akhir Serat Rama sama dengan Ramayana Kakawin,
yaitu kisah pensucian Sinta lewat api unggun.
Sendratari Ramayana Prambanan (STRP) menggunakan
Serat Rama sebagai sumber cerita.Serat Rama yang bersumber
kepada Ramayana Kakawin, dan Ramayana Kakawin yang
bersumber kepada Ravanavadha, berbeda dengan kisah Rama di
relief Candi Prambanan.Karena itu sering turis mempertanyakan
mengapa kisah Rama dalam Sendratari tersebut berbeda dengan
kisah Ramayana dalam relief Candi Prambanan, terutama di bagian
akhir kisah.Sumber Ramayana relief Prambanan memang belum
bisa secara pasti ditelusuri asal-usulnya, namun versinya mirip
Hikayat Sri Rama.
Prof. Dr Poerbatjaraka pada masa revolusi fisik (1945-49)
telah berhasil menerjemahkan naskah Ramayana Kakawin ke ba-
hasa Indonsia pada 1950.Usaha tersebut sebenarnya telah selesai,
tapi amat disayangkan sampai beliau wafat tahun 1964 naskah
berharga itu tak kunjung berhasil diterbitkan.
vSatu disertasi berbahasa Indonsia tentang Ramayana tulisan
Achdiati Ikram diterbitkan oleh Universitas Indonsia, Jakarta, pada
1980 dengan judul Hikayat Sri Rama. Achdiati yang mendalami
sastra Melayu Lama pada Universitas Leiden, mempelajari secara
intensif naskah Hikayat Sri Rama dari struktur dan amanat yang
terkandung dalam naskah tersebut.
|
 2
2.5
Data Hasil Survey
Penulis juga melakukan survey ke berbagai tempat untuk memperkuat
data dalam pengenalan tokoh Ramayana.Tempat yang penulis kunjungi
adalah Museum Wayang Jakarta dan pertunjukkan Sendratari Ramayana di
Purawisata Yogyakarta, yang diselenggarakan setiap hari.
2.5.1
Museum Wayang Jakarta
Museum wayang memiliki berbagai jenis wayang dalam negri maupun
mancanegara.Dalam museum wayang terdapat wayang yang
menvisualisasikan tokoh dalam Ramayana.Setiap daerah mempunyai cirri
khas wayang tersendiri, dan membuat adanya diferensiasi tokoh
Ramayana.Berikut contoh wayang-wayang tersebut.
Gambar 2.1Wayang Purwa Surakarta Rama dan Rahwana
Gambar 2.2
(kiri) Wayang Kulit Kamboja Sita dan Ganesha,
(kanan) Wayang Kulit Malaysia Hanoman
|
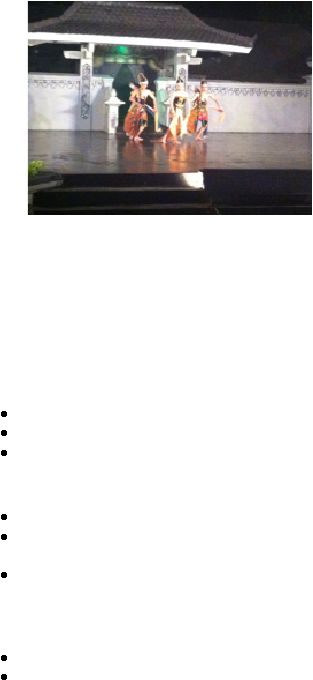 2
2.5.2
Sendratari Ramayana Purawisata
Penulis menonton pergelaran sendratari Ramayana di Purawisata
Yogyakarta untuk memberikan refernsi visual berupa kostum yang dipakai
dan suasana budaya dari tempat tersebut. Berikut adalah dokumentasi dari
sendratari tersebut.
Gambar 2.3 Adegan Rama, Sita dan Lesmana di hutan Dandaka
2.6
Data Khalayak Sasaran
2.6.1
Targer Primer
Demografi
Pria & wanita
Umur 18-25 tahun
Status sosial pelajar, mahasiswa, sudah kerja
Psikografi
Hobi membaca, menonton tv/bioskop, jalan-jalan
Sikapnya bersosialisasi, suka membagi wawasan, tertarik dengan
kebudayaan lokal
Minat ingin lebih mengetahui perkembangan kebudayaan lokal di
jaman sekarang
Geografi
Berdomisili di perkotaan, Jakarta
Kelas A & B
|
 2
2.6.2
Target Sekunder
Target sekunder dalam buku ilustrasi pengenalan tokoh dalam kisah
Ramayana ini adalah Art Student( pelajar/mahasiswa yang bersekolah/kuliah di
sekolah/institut seni ) usia 18 hingga 25 tahun dengan kelas sosial A dan B, baik
pria dan wanita, menyukai ilustrasi dan budaya lokal.
2.7
Data Penerbit
Kompas Gramedia, disingkat KG, adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di
bidang media massa yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1965
Oleh P.K. Ojong dan
Jakob Oetama.Pada tahun 1980-an perusahaan ini mulai berkembang pesat, terutama
dalam bidang komunikasi. Saat ini, KG memiliki beberapa anak perusahaan/bisnis unit
yang bervariatif dari media massa, toko buku, percetakan, radio, hotel,
lembaga
pendidikan, event organizer, stasiun TV hingga universitas.Pada tahun 2005, perusahaan
ini mempekerjakan sekitar 12.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Gambar 2.4Logo Gramedia Pustaka Utama
Gramedia Pustaka Utama adalah anak perusahaan dari Kelompok Kompas
Gramedia yang bergerak di bidang penerbitan buku yang mulai menerbitkan buku sejak
tahun 1974. Buku fiksi pertama yang diterbitkan penerbit ini adalah novel Karmila,
karya Marga T, yang disusul dengan buku seri anak-anak seperti Cerita dari Lima
Benua, Album Cerita Ternama, dll. Terbitan buku non-fiksi pertama Gramedia adalah
Hanya Satu Bumi karya Barbara Ward dan René Dubois dengan bekerjasama dengan
Yayasan Obor.
Gramedia Pustaka Utama selalu menerbitkan buku-buku bermutu baik
terjemahan maupun karya asli dalam negeri, diantaranya untuk jenis fiksi adalah Harry
Potter karya JK. Rowling, novel2 karya Sidney Sheldon, Agatha Christie, Marry Higgins
Clark, Sandara Brown, novel2 Mira W, Maria A. Sardjono, Hilman, dan masih banyak
lagi. Untuk nonfiksi ada karya2 Robert Kiyosaki, Stephen Covey, Vincent Gasperz,
Tung Desem Waringin, Rhenald Kasali, Adi Gunawan, dan lain-lain.
|
|
2
2.8
Analisa Kasus
2.8.1
Faktor Pendukung
Faktor pendukung dalam buku ilustrasi mengambil tema kisah atau
legenda nusantara yang dikemas dalam ilustrasi yang digarap menggunakan
pendekatan ilustrasi yang bergaya kontemporer.Dimana style
ilustrasi yang
dipakai sesuai dengan jiwa anak muda sekarang.
2.8.2
Faktor Penghambat
Faktor penghambat buku ilustrasi ini adalah prasangka masyarakat yang
menganggap tema yang diambil sudah terlalu kuno ( basi ), karena sudah banyak
versi yang telah di terbitkan sebelumnya. Selain akan adanya pihak kontra yang
bertanggapan bahwa budaya tradisional tidak boleh dicampur tangankan dengan
hal yang berbau modern karena dapat merusak nilai etnik dan sakral di
dalamnya.
2.9
S.W.O.T
2.9.1
Strenght( Kekuatan )
Kisah Ramayana sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat
Indonesia terutama yang tinggal di Pulau Jawa dan Bali.
Ilustrasi di Indonesia sudah berkembang cukup lama.
2.9.2
Weakness( Kelemahan )
Penggambaran atau visualisasi tokoh Ramayana dalam wayang masih
serupa dengan satu sama lain, membuat masyarakat yang awam akan
dunia pewayangan kesulitan membedakan tokoh-tokohnya.
Perkembangan jaman membuat kisah pewayangan semakin menurun
popularitasnya.
2.9.3
Oppurtunity( Kesempatan )
Peminat buku ilustrasi masih banyak peminatnya.
Masih banyak masyarakat yang ingin melestarikan kebudayaan lokal
yang diajaman yang sudah memasuki era westernisasi.
2.9.4
Thread( Ancaman )
Segmen pembaca atau pembeli kemungkinan akan terbatas, dikarenakan
harga buku relatif mahal bila dibandingkan buku pengenalan tokoh
wayang dan sejenisnya.
|
|
2
Adanya pihak yang menentang kalau penggambaran tokoh wayang yang
dikemas modern akan mengurangi nilai etniknya.
|