|
3
BAB 2
DATA & ANALISA
2.1 Sumber Data
2.1.1 Literatur Buku
1.
"Monarki Yogyakarta Inkonstitusional?" penerbit PT. Kompas Media Nusantara.
2.
"Takhta untuk Rakyat" penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
3.
"Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya" oleh Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo.
4.
"Doorstoot Naar Djokja, Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer" karya Julius Pour.
5.
“3D Human Modeling and Animation” oleh Peter Ratner.
2.1.2 Literatur Artikel
1.
2.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hamengku Buwono_IX
3.
4.
5.
6.
7.
|
 4
2.2 Asal Usul Yogyakarta
2.2.1 Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
adalah negara dependen
yang berbentuk
kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut
perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara
dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan
kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan
yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara
dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten
Pakualaman) diturunkan menjadi daerah istimewa
dengan nama Daerah
Gambar 2.1 Kraton Yogyakarta
Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti
dan VOC
Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram
dibagi dua. Pangeran Mangkubumi
diangkat sebagai Sultan
dengan gelar Sultan Hamengku
dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Paku
Buwono III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta
dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC.
kemudian segera membuat ibukota kerajaan beserta
istananya yang baru dengan membuka daerah baru di Hutan Paberingan
yang terletak antara
aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan
|
|
5
Ngayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober
1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono.
Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum,
digunakan frasa " ingkang jumeneng kaping .... ing Ngayogyakarto
" ("yang bertahta ke .... di
Yogyakarta"). Selain itu ada beberapa nama khusus antara lain Sultan Sepuh
(Sultan yang Tua)
untuk Hamengku Buwono II
Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta
mulanya diselenggarakan dengan menggunakan
susunan pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan menjadi dua urusan besar
yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga disebut Parentah Ageng Karaton, dan Parentah
Jawi
(urusan luar) yang juga disebut Parentah Nagari. Sultan
memegang seluruh kekuasaan
pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan
dibantu lembaga
Pepatih Dalem yang bersifat personal.
Setidaknya sampai 1792
secara de facto
merupakan negara
merdeka dan VOC
hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin posisinya maka VOC
menempatkan seorang Residen
untuk mengawasi Kesultanan. Kedudukan
ini mulanya berada di bawah Sultan
dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels
dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.
Dengan kedatangan Raffles
sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan
tidak
diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan berada ditangan
pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder),
diangkat dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris
dan dalam menjalankan
pekerjaannya harus sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen
mulai
dibebaskan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh
Perubahan besar dalam pemerintahan terjadi pada saat Sultan Hamengkubuwono IX
perlahan namun pasti, Sultan
melakukan restorasi. Sultan
membentuk badan-badan
pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara
yang masing-masing dikepalai oleh
tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pepatih Dalem
melainkan
|
|
6
kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.
Pada pertengahan 15 Juli
terakhir, KPHH Danurejo VIII,
mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan
tidak menujuk lagi
sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan
pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan menjadi dua bagian
yaitu urusan dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana
ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor
pemerintahan yang berada di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Semuanya di
pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan.
dipimpin oleh Bupati. Daerah di sekitar istana dibagi menjadi lima kabupaten yang administrasi
lokalnya dipimpin oleh Bupati. Setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan
pada Republik, status dan posisi serta administrasi
dijalankan berdasar peraturan
diubah menjadi daerah administrasi
khusus dan Sultan
menjadi
Daerah Istimewa. Kesultanan menjadi bagian dari republik modern.
Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX
dan Sri Paduka
Paku Alam VIII mengirim telegram kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kesultanan
Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta
bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang bersifat
kerajaan. Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alamku Alam VIII kemudian
menjadi Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
ini, bersama-sama
dengan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah berotonomi
khusus setingkat provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara berakhir dan menjelma menjadi
pemerintahan daerah berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kemudian dipisahkan dari
negara dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.
|
|
7
2.3 Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia
setelah
Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki
status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum
kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta
dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal
atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state”
dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-
Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda
(Kerajaan Nederland), dan
terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut
disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status
ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus
wilayah sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang
kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia, Soekarno
Sebelum Indonesia merdeka,
Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai
pemerintahan sendiri atau disebut Zelfbestuur landschappen/Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun
1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan
Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia
Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah
tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir
Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad
1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik
Pakualaman dalam Staatsblaad
1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah
maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap
menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan
asli), wilayah dan penduduknya.
|
|
8
Setelah Proklamasi
(RI), Sri Sultan Hamengku
dan KGPAA (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya) Paku Alam VIII menyatakan
kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi
wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Hal
tersebut dinyatakan dalam:
1.
Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam
VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
2.
Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII
tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
3.
Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII
tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).
Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat
Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur
tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan
Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-
undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan
Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir
dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
|
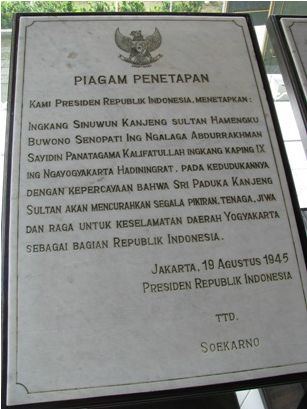 9
Gambar 2.2 Piagam Penetapan 19 Agustus 1945
Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
sampai dengan tanggal 27 Desember
pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia. Tanggal 4 Januari
inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota
Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh
dipimpin oleh KGPAA Paku
Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya
memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa
dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.
|
 10
2.3.1 Sambutan Proklamasi di Yogyakarta
Tanggal 18 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) dan Sri Paduka Paku
(PA VIII) mengirimkan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan
Indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain itu
juga dikirimkan ucapan terima kasih kepada KRT Rajiman Wediodiningrat (mantan ketua
Nampoo-Gun Sikikan Kakka
dan Jawa Saiko Sikikan
beserta
stafnya. Pada 19 Agustus
Yogyakarta Kooti Hookookai
mengadakan sidang dan
mengambil keputusan yang pada intinya bersyukur pada Tuhan atas lahirnya Negara Indonesia,
akan mengikuti tiap-tiap langkah dan perintahnya, dan memohon kepada Tuhan agar Indonesia
kokoh dan abadi
.
2.3.2 Amanat 5 September 1945
Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta
dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. Pada hari yang sama
juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat
(BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sri Sultan
Hamengku Buwono IX mengadakan pembicaraan dengan KGPAA Paku Alam VIII dan Ki
serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap
Proklamasi, barulah Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang
dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki
Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh
KGPAA Paku Alam VIII pada hari yang sama. Isi dari amanat 5 September 1945 adalah sebagai
berikut :
Gambar 2. 3 Amanat 5 September 1945
|
|
11
Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX
1.
Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah
istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2.
Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri
Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa
ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini
berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.
3.
Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat
Negara Republik Indonesia,
bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas
Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Amanat KGPAA Paku Alam VIII
1.
Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara
Republik Indonesia.
2.
Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku
Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan
pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan
kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.
3.
Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara
Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami
langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
2.3.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Sementara Yogyakarta
Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh dan wakil ketua
S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo, sehari sesudahnya Sri Sultan Hamengku Buwono
IX dan KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama (dikenal dengan
Amanat 30 Oktober 1945 ) yang isinya menyerahkan kekuasaan Legislatif pada BP KNI Daerah
Yogyakarta. Isi dari amanat 30 Oktober 1945 adalah sebagai berikut :
|
|
12
Mengingat:
1.
Dasar-dasar jang
diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
ialah kedaulatan rakjat dan keadilan sosial.
2.
Amanat Kami berdua pada tgl.28 Puasa, Ehe 1876 atau 5-9-1945
3.
Bahwa kekuasaan-kekuasaan jang dahulu dipegang oleh Pemerintah djadjahan (dalam
djaman
Belanda didjalankan
oleh Gubernur dengan kantornja, dalam djaman Djepang
oleh Koti Zimu Kyoku Tyokan dengan kantornja) telah direbut oleh rakjat dan
diserahkan kembali kepada Kami berdua.
4.
Bahwa Paduka Tuan Komissaris Tinggi pada tanggal 22-10-1945 di Kepatihan
Jogjakarta dihadapan Kami berdua dengan disaksikan oleh para Pembesar dan para
Pemimpin telah menjatakan tidak perlunja akan adanja Sub-comissariat dalam Daerah
Kami berdua.
5.
Bahwa pada tanggal 19-10-1945 oleh Komite National Daerah Jogjakarta telah dibentuk
suatu Badan Pekerdja jang dipilih dari antara anggauta-anggautanja, atas kehendak
rakyak dan panggilan masa, jang diserahi untuk mendjadi Badan Legeslatif (Badan
Pembikin Undang-undang) serta turut menentukan haluan djalannja Pemerintah Daerah
dan bertanggung djawab kepada Komite National Daerah Jogjakarta,
maka Kami Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan
Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran
Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa
Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan
Pekerja Komite Nasional Daerah
Jogjakarta, dengan ini menyatakan:
Supaya jalanya Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerdja tersebut adalah suatu
Badan Legeslatif
(Badan Pembikin Undang-undang) jang dapat dianggap
sebagai wakil rakyat
dalam Daerah Kami berdua untuk membikin undang-undang dan menentukan haluan jalanya
Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat.
Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dari segala bangsa dalam Daerah Kami berdua
mengindahkan Amanant kami ini.
Mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan memulai persatuan
kembali kedua kerajaan yang telah terpisah selama lebih dari 100 tahun. Sejak saat itu dekrit
|
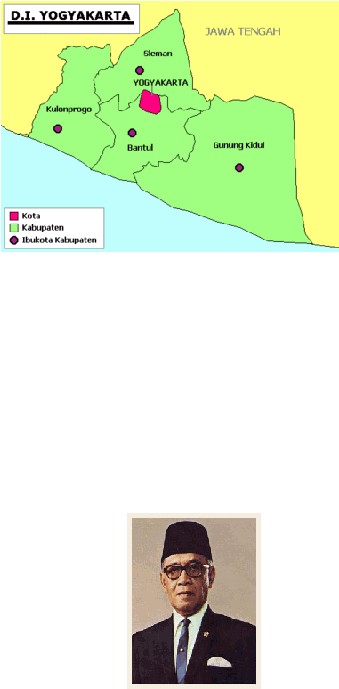 13
kerajaan tidak dikeluarkan sendiri-sendiri oleh masing-masing penguasa monarki melainkan
bersama-sama dalam satu dekrit. Selain itu dekrit tidak hanya ditandatangani oleh kedua
penguasa monarki, melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta yang
dirangkap oleh Ketua KNI Daerah Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh rakyat Yogyakarta.
Gambar 2.4 Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2.4 Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Lahir di Yogyakarta dengan nama Bendoro Raden Mas Dorodjatun di Ngasem,
Hamengku Buwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dan Raden Ajeng
Kustilah. Di umur 4 tahun Hamengku Buwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia
memperoleh pendidikan di HIS
di Yogyakarta, MULO
di Bandung.
Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang Universiteit Leiden), Belanda.
Gambar 2.5 Sri Sultan Hamengku Buwono IX
|
|
14
Hamengku Buwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret
dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono
Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng
Kaping Sanga". Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda
dan mendorong
kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status
khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa".
Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia
28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr.
mengenai otonomi Yogyakarta. Di masa Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha
dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam
VIII adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia.
2.5 Sejarah Yogyakarta Pasca Kemerdekaan RI
2.5.1 Yogyakarta Ibukota Negara
Yogyakarta pernah menjadi Ibukota pemerintahan Republik Indonesia, ketika Agresi
Militer Belanda I. Saat itu Jakarta diduduki oleh Belanda, sehingga Soekarno dan Hatta harus
diungsikan pada awal tahun 1946. Pada waktu itu bung Karno segera mengirimkan telegram
kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menanyakan apakah Yogyakarta sanggup menerima
Pemerintahan RI karena situasi di Jakarta yang sudah tidak memungkinkan lagi. Sri Sultan
menyatakan sanggup dan bahkan segenap rakyat Yogyakarta sanggup untuk membela
kewibawaan Pemerintahan RI.
Akhirnya pada , 4 Januari 1946, Yogya resmi menjadi Ibukota Republik Indonesia.
Pagi-pagi benar, Bung Karno, Bung Hatta, dan segenap kerabat mengungsi ke Yogya. Segenap
menteri juga hijrah secara diam-diam ke Yogya. Namun, Perdana Menteri Syahrir tetap tinggal
di Jakarta.
Mengenai keputusan untuk menjadikan Yogya sebagai ibukota RI, Wakil menteri
penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo
menyampaikan berita ini melalui RRI Yogya (Radio
Republik Indonesia).
|
|
15
Yang menarik adalah mengenai alasan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogya
tersebut. Dalam pidatonya, Mr. Ali Sastroamidjojo mengatakan ada dua alasan, pertama alasan
keadaan tidak aman yang terjadi di Jakarta. Alasan kedua adalah untuk menyempurnakan
Organisasi dalam Negeri. Mr. Ali mengatakan,"Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan
yang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat senentara kedudukan Pemerintahan Agung.
Alasan
itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan
dari revolusi rakyat Indonesia apda masa ini. Sebab Pemerintah Agung mulai sekarang dari
kedudukannya yang baru, ialah kota Matara akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan
cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintah di daerah-
daerah...."
Jadi, Yogya dipilih menjadi ibukotya RI karena alasan untuk mempercepat proses
penyempurnaan organisasi negara. Hal itu hjelas menunjukkan bahwa Yogya
dinbilai mampu
memberi legitimasi dan kontribusi bagi pengembangan Pemerintah RI. Para pemimpin Pusat
melihat bahwa kondisi pemerintahan dan kepemimpinan di Yogya sangat kuat karena
merupakan kerajaan di bawah dwitunggal yang kuat pula.
Pemindahan ibukota
dari Jakarta ke Yogya jelas menunjukkan keyakinan Pemerintah
Pusat akan komitmen Yogya kepada NKRI. Dalam hal ini Indonesia bergantung harap kepada
Yogya. Yogyakarta menjadi Ibukota RI hingga 27 Desember 1949.
2.5.2 Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta
Setelah berakhirnya agresi militer Belanda yang pertama terhadap Republik Indonesia.
Belanda mendapat protes keras dari Dewan Keamanan PBB sehingga Belanda dipaksa
berunding dengan Indonesia melalui perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) yang diadakan di
Kaliurang, Yogyakarta, dengan topik membahas perundingan damai antara kedua negara.
Namun pihak Belanda telah bermaksud untuk menghancurkan Republik lewat jalan perang.
Sehingga ketika KTN masih berlangsung, Belanda secara sepihak kembali menyatakan perang
kepada Republik Indonesia.
Dengan keberadaan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, maka Yogyakarta
menjadi target penyerangan tentara Belanda dalam agresi militernya yang kedua. Pada tanggal
19 Desember 1948, pasukan Belanda melancarkan Operasi Kraai atau operasi gagak dan
|
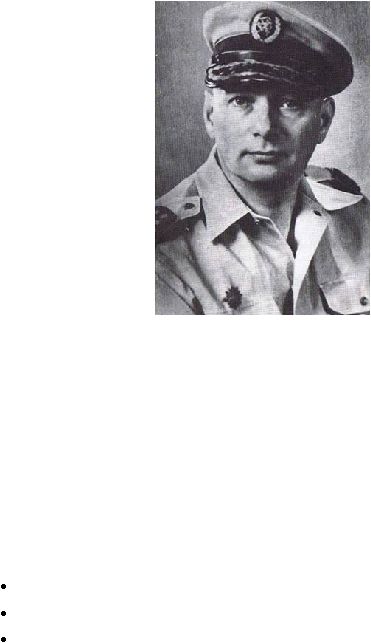 16
berhasil menguasai Landasan Udara Maguwo di bawah pimpinan Letnan Jenderal Simon Spoor
yang membawahi pasukan Baret Merah KST (Korps Speciale Troepen) dan Pasukan Baret
Hijau, yang juga dipimpin oleh pimpinan komando KST, Letnan Kolonel Van Beek.
Penyerangan ini menewaskan 40 orang prajurit TNI. Kemudian setelah menguasai landasan
udara Maguwo, pasukan Belanda berhasil menyerang dan menguasai Yogyakarta pada tengah
hari. Yang menyebabkan Presiden Soekarno ditahan di Brastagi.
Gambar 2.6 Letnan Jenderal pasukan Belanda, Simon Spoor
Menurut Jenderal Spoor, keberhasilan dari serangan ini terletak pada elemen serangan
mendadak, akibat diputusnya komunikasi dari Batavia ke Yogyakarta, maka kaum Republiken
tidak mendapatkan informasi akan adanya penyerangan Belanda ke Yogyakarta. Sementara
pasukan Belanda yang telah disiapkan semenjak Agresi Militer Pertama dapat segera menyerang
Yogyakarta, aksi ini merupakan tanggapan militer Belanda yang mendapat informasi dari
intelijennya bahwa Presiden Soekarno hendak melarikan diri ke India. Adapun Spoor
menetapkan tiga sasaran dalam Operasi Kraai :
Pertama, menangkap pimpinan sipil dan militer Republik.
Kedua, menguasai sentra politik dan militer.
Ketiga, melakukan aksi pengepungan sekaligus menghancurkan konsentrasi perlawanan
bersenjata lawan.
|
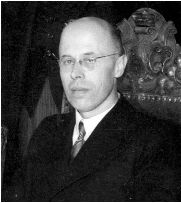 17
Operasi ini dimulai dengan dilakukannya penyerangan di Landasan Udara Maguwo.
Kesuksesan serbuan ini bertumpu sepenuhnya pada pukulan pertama, serangan udara mendadak.
Menurut catatan, di Pangkalan Udara KaliJati, Bogor, dipersiapkan sebuah pesawat Lockhead L-
12 dan enam buah pesawat tempur Harvard. Kemudian di Cililitan, Batavia, empat pesawat
pengebom Mitchell B-25 bersama dua pesawat Mustang P-51. Di landasan Andir, Bandung, 16
pesawat angkut Dakota C-47, pesawat pengebom Mitchell B-25 bersama empat pesawat
pengintai Piper Club. Dalam rencana Operasi Kraai, setelah serangan udara ke Maguwo
berlangsung, akan segera disusul penerjunan pasukan payung baret merah KST yang
diterbangkan dari Andir. Setelah landasan berhasil diamankan, segera dilanjutkan pembuatan
jembatan udara, yang akan dipakai pasukan komando baret hijau KST mendarat di Maguwo,
sebelum menyerbu masuk ke Yogyakarta. Oleh karena itu, mendukung rencana tersebut di
Landasan Udara Kalibanteng, Semarang telah disiapkan 20 pesawat pemburu Spitfire, lima buah
pengebom B-25, berikut empat pesawat Auster. Sebagai pendukung operasi, di Landasan Udara
Surabaya juga disiapkan empat pesawat
Auster, enam pesawat Fireflikes
dan tiga pesawat
angkut ringan Catalina.
Pada pukul 02.00, dua kompi pasukan baret merah KST yaitu grup tempur Para I, mulai
melakukan embarkaasi di Andir dengan menggunakan 18 pesawat Dakota C-7, untuk mengawali
operasi Kraai. Pada pukul 04.30 Dakota pertama telah tinggal landas, setelah itu tiap selang satu
menit, menyusul pesawat-pesawat berikutnya. Mereka semua berangkat ke arah Timur,
menyusuri pesisir selatan Pulau Jawa. Armada angkutan udara tersebut kemudian melakukan
holding di atas korvet Hr. Ms. Torenvalk, kapal perang Angkatan Laut Belanda yang sejak dua
hari lalu telah sengaja lego jangkar, tiga kilometer di arah Selatan Pantai Parangkusuma,
Yogyakarta.
Gambar 2.7 Wakil Agung Mahkota, Dr. Louis Beel
|
|
18
Pada pukul 08.00 pagi, Wakil Agung Mahkota Dr. LJM Beel tampil di depan corong
Radio Batavia, membacakan pernyataan "...kami merasa tidak terikat lagi oleh persetujuan
gencatan senjhata dengan Republik Indonesia. Mereka sama sekai tidak pernah bersedia
menghormati gencatan senjata dan malahan berkali-kali melakukan pelanggaran, dengancara
mengirim gerombolan-gerombolan bersenjata, menyebarkan teror, pembunuhan dan aksi
perampokan masuk ke dalam wilayah Federal."
"Mengingat gerombolan-gerombolan tersebut berpangkalan di daerah Republik, yang
sama sekali tidak dikuasai oleh Kerajaan Belanda, maka kami bertekad mengerahkan seluruh
kekuatan untuk bisa menduduki daerah-daerah yang menyebarkan kekacauan, sekaligus
melakukan gerakan pembersihan secara consequent en zonder voobehoud, konsekuen dan tanpa
tersisa, agar rust and orde, keamanan dan ketertiban, bisa tercapai."
Dengan demikian Belanda, melalui Beel, telah menyampaikan pernyataan pemberlakuan
agresi militer yang kedua. Padahal sebenarnya sekitar tiga jam 45 menit sebelum Louis Beel
membacakan pernyataan di Radio Batavia,
tepat pukul 05.15 Landasan Udara Maguwo sudah
dihujani bom oleh tiga pesawat pengebom taktis B-25 Mitchell. Serangan pengecut yang dengan
jelas mendahului dikeluarkannya pernyataan perang.
Setelah sortie
pertama pengeboman selesai, segera disusul oleh siraman hujan roket
dilengkapi tembakan senapan mesin, yang dimuntahkan dari lima pesawat tempur F-51 Mustang
didukung sembilan P-401. Kittyhawks. Pesawat-pesawat terbang tersebut tinggal landas dari
Kalibanteng, Semarang. Sedang dua puluh menit kemudian, setelah menerima kode aman, dari
wilayah holding di atas Lautan Hindia, 18 pesawat angkut Dakota, langsung menyusul terbang
ke arah Utara.
Tepat pukul 06.45, sesudah pertahanan di Maguwo berhasil dilumpuhkan, armada
Dakota tersebut menerjunkan dua kompo pasukan baret merah KST, mengarah ke landasn pacu.
Selama operasi penerjunan berlangsung, Jenderal Spoor berada dalam kokpit pesawat pengebom
B-25 Mitchell
melakukan holding di dropping sone
sebelum nantinya pindah ke atas
Yogyakarta. Dalam rencana operasi yang telah disusun, Spoor selalu menegaskan, kunci sukses
Operasi Kraai terletak pada strategische berassing, pendadakan strategis.
Dengan demikian, demi menjamin terlaksananya semua upaya "sapu bersih" ke
Maguwo, dia sengaja menerjunkan dua kompi pasukan para yang diangkut pesawat C-47 Dakota
|
|
19
dari Andir. Sementara bantuan tembakan udara, secara terus menerus dilakukan oleh pesawat
pengebom B-25 Mitchell didukung pesawat tempur P-51 Mustang bersama P-40 Kittyhawk.
Sesudah menerjunkan pasukan baret merah KST, semua pesawat angkut Dakota menuju
ke Landasan Udara Kalibanteng, Semarang. Mereka mendarat, melakukan pengisian bahan
bakarn kemudian siap terbang kembali menuju Maguwo, untuk membuat jembatan udara yang
akan dipakai pasukan baret hijau Batalyon 5 Resimen Stootroepen, di bawah komando Letnan
Kolonel WCA Van Beek.
Pasukan baret hijau didaratkan sesudah mereka menerima isyarat aman dari pasukan
baret merah KST, yang telah selesai menangani Maguwo. pasukan penyerbu ke Yogyakarta
menurut rencana akan diperkuat dengan dua batalyon pasukan infantri, didukung satuan Artileri,
Kavaleri, dan Zeni, yang melakukan gerak melambung dari Salatiga lewat Kartasura, kemudian
berbelok ke kanan untuk melakukan link-up
di Maguwo, sebelum nantinya mereka membantu
mendobrak masuk ke Yogyakarta.
Menghadapi serangan dadakan ke Meguwo, prajurit Angkatan Udara Republik tidak
mau menyerah. Dalam hujan tembakan serangan udara, mereka tetap berusaha memberikan
perlawanan, meski pertempuran berlangsuing tidak seimbang. Baret merah KST adalah pasukan
yang sudah kenyang dengan pengalaman bertempur serta selalu siap berperang. Sementara
pasukan Republik, banyak dia antaranya belum sempat beristirahat, oleh karena sudah dua
malam berturut-turut kurang tidur.
Maguwo saat itu hanya dipertahankan oleh 150 anggota Pasukan Pertahanan Pangkalan
dan 34 teknisi udara, di bawah pimpinan Kadet Udara Kasmiran. Persenjataan yang melengkapi
Maguwo tercatat dua pucuk penangkis serangan udaraberukuran 40mm dan 20mm milik
Angkatan Darat serta senapan mesin 12,7 mm milik Angkatan Udara. Sayangnya peralatan
tersebut diangkut keluar pangkalan untuk persiapan pelatihan militer. Selain pasukan Angkatan
Udara penjaga landasan, juga tinggal di Maguwo para kadet Akademi Udara. Mereka adalah
para pelajar yang sedang dipersiapkan untuk pendidikan terbang.
Dalam kondisi demikian, perlawanan gigih pasukan Angkatan Udara memang tidak
sanggup bertahan lama. Mereka hanya memakai senapan ringan, tanpa memiliki persenjataan
penangkis serangan udara sekaligusjuga masih miskin pengalaman bertempur. Kopral Udara
Tohir dan 30 prajurit Angkatan Udara lainnya, langsung gugur disapu tembakan payung pasukan
Belanda. Pertempuran tidak seimbang ini berlangsung selama kurang dari setengah jam. Pagi itu
|
|
20
sesuai catatan, empat puluh prajurit Republik gugur di Maguwo. Selain itu, pasukan payung
Belanda juga berhasil menghancurkan pesawat angkut ringan Avro Anson
dengan nomor
registrasi RI-004. Selain itu, ikut juga dihancurkan hanggar, berisi sejumlah pesawat terbang
yang sedang dalam perbaikan.
Pukul 06.45, operasi penerjunan merebut Maguwo dimulai, dengan perlindungan
pesawat tempur Mustang serta
Kittyhawk. Mereka terus-menerus menyambar ke segala arah
dengan suara melengking, semain menambah kekacauan suasana di darat.
Pukul 07.04, penerjunan selesai, tanpa jatuh korban seorangpun dari pihak Belanda.
Kemudian kedua kompi pasukan KST segera bergerak meninggalkan dropping zone
untuk
memperluas kawasan tyumpuan udara, sekaligus menyerang sisa-sisa pasukanRepublik yang
masih selamat dari tembakan udara.
Pukul 07.10, mereka sudah berhasil menyusun pertahanan di sekeliling kompleks
Maguwo, melaksanakan konsolidasi berikut menutup jalan raya antara Yogyakarta-Prambanan.
Termasuk meminta bantuan tembakan udara, untuk membungkam tembakan senapan mesin,
yang datang dari arah Desa Tlogowono, Selatan Maguwo.
Pukul 07.55, Kapten Cox, perwira pengendali operasi penerjunan telah menyatanan,
seluruh landasan sudah dibersihkan dari ranjau dan aneka ragam bahan peledak, yang
sebelumnya dipasang pasukan Republik, tetapi belum sempat mereka ledakkan.
Pukul 08.00, pos pengendali udara mengirim kode
all clear
kepada armada pesawat
tempur yang masih meraung-raung di atas Maguwo. Kode tersebut segera di-relay
ke
Kalibanteng, diterima langsung Jenderal Spoor, yang sudah selesai memeriksa embarkasi
Batalyon KST, di bawah pimpinan Letnan Kolonel, berikut Batalyon I Resimen Infantri 15,
dengan komandan Mayor JF Scheers. Kedua pasukan tersebut sekaligus ditugaskan mengawal
komandan Brigade Tjiger, Kolonel Van Langen. Dan pada pukul 08.10 pesawat angkut C-47
pertama berhasil mendarat di Maguwo
Operasi penerjunan pasukan baret merah KST untuk merebut Landasan Udara Maguwo
berlangsung lancar. Begitu juga pembuatan jembatan udara yang dilakukan dengan 126 sortie
penerbangan pesawat DC-3 Dakota
dari Kalibanteng-Semarang ke Maguwo-Yogyakarta,
berjalan mulus. Sampai tengah hari, telah bisa diterbangkan 2.600 prajurit, termasuk pasukan
komando baret hijau dari Batalyon 5 Resigment Stootroepen, 80 jip tempur, amunisi berikut
persediaan perbekalan untuk pertempuran selama tiga hari.
|
|
21
Pada saat itu , Kolonel Van Langen sebenarnya masih menunggu datangnya
kelengkapan pasukan berikut senjata bantuan pasukan Kavaleri serta peralatan Zeni tempur,
untuk bisa memperbesar daya dobrak, dalam usaha menjebol pertahanan TNI di Yogyakarta.
Tetapi pasukan berikut persenjataan bantuan yang berangkat dari Salatiga pagi hari
lewat jalan darat, ternyata terhambat oleh hujan lebat, jembatan hancur berikut perlawanan
sengit dari anak buah Letnan Kolonel Slamet Riyadi, Komandan Wehrkreise I Surakarta, di
sebelah Utara Boyolali. Dengan demikian, mereka menyatakan tidak akan mungkin bisa tepat
waktu untuk sampai di Maguwo.
Sambil melihat jarum jam yang sudah menunjuk ke angka 11, Kolonel Van Langen
kemudian memerintahkan Letnan Kolonel Van Beek bersama Batalyon KST anak buahnya,
bergerak meninggalkan Maguwo. Dia memutuskan memulai serangan, mengingat unsur
pendadakan yang sudah berhasil menyergap TNI, harus tetap dipertahankan momentumnya.
Pasukan komando baret hijau KST diperintahkan tidak memakai jalan raya, melainkan
lewat jalan alternatif, dengan sasaran wilayah Yogyakarta sebelah Selatan rel kereta api.
Sementara Batalyon Infantri dari Resimen 15, menyusul bergerak 30 menit kemudian, melewati
jalan raya Yogyakarta-Solo dengan daerah sasaran bagian kota sebelah Utara rel kereta api.
Sesaat sebelum pasukannya bergerak, Van Langen berbisik kepada Van Beek, "Overste tangkap
Soekarno, Hatta dan Soedirman. Mereka bertiga masih berada di Istana-nya."
Komandan Brigade X/Divisi III Diponegoro, Letnan Kolonel Soeharto sejak tanggal 15
Dsember sudah mengelar induk pasukannya di sebelah Barat kota Yogyakarta. Penempatan
pasukan tersebut dalam rangka melakukan persiapan untuk mengikuti latihan perang, yang
dijadwalkan akan dimulai empat hari lagi. Penempatan pasukannya di sana sekaligus untuk
menanggapi perkiraan intelijen TNI, yang secara jelas telah menyebutkan bahwa jika Belanda
melakukan serangan pasti akan menerobos garis demarkasi di Gomong, barat Yogyakarta,
karena disitulah jalan terdekat dari wilayah Federal, daerah yang sudah berhasil dikuasai
Belanda seusai mereka melakukan aresi militer tahun 1947 di, sebuah jalan luru, langsung
menuju Yogyakarta.
Menurut Soeharto, serangan dari arah Timur, yang
diawali serbvuan udara pasukan
payung, merupakan sebuah pendadakan tidak terduga. Perlawanan di Maguwo dan di dalam kota
sangat menyedihkan. Sebelum pasukan Belanda mendarat, para anggota Angkatan Udara sudah
bekerja keras selama 2 hari, sampai pukul 02.00 dini hari, untuk memberangkatkan para perwira
|
|
22
remaja ke Sumatera. Pagi harinya dalam keadaan masih sangat lelah, mereka malahan mendapat
serangan mendadak, sehingga bisa dimaklumi kalau perlawanan di Maguwo sedikit sekali.
Soeharto mengemukakan bahwa setelah tentara Belanda berhasil mendarat di Maguwo,
sudah bisa kita duga, mereka pasti akan segera meneruskan gerakan ke Yogyakarta, yang
jaraknya hanya enam kilometer. Malang bagi pihak kita, tetapi untung bagi Belanda, pada waktu
itu kekuatan TNI di dalam
kota sudah tidak bayak. Brigade X/Divisi III yang bertugas
mempertahankan Ibu Kota hanya tersisa dua Seksi. Terdiri dari satu dekking
(pengawal) Staff
Brigade dan satu dekking Staf Batalyon 4. Pasukan lain, semuanya sudah berada di luar kota.
Polisi Negara dan Polisi Militer yang berada di dalam kota berjumlah tiga kompi. Mereka secara
taktis berada di bawah Komando Militer Kota, untuk menjaga keamanan serta mengadakan
perlawaan dalam kota, Sejak pukul 07.15, mereka bersama dua seksi dari Brigade X sudah saya
perintahkan untuk mengadakan penghambatan terhadap gerak maju Belanda dari arah Maguwo.
Sekitar pukul 09.00, mereka mendapat bantuan dua seksi kadet Akademi Militer. Dengan
kekuatan sebesar itu, tent saja sangat sulit bagi kami untuk bisa mempertahankan frontbreedete
(Kelebaran Front) sepanjang empat kilometer. Akhirnya pasukan Belanda dapat mengepung
Istana pada pukul 01.30.
Bung Karno kemudian memerintahkan Letnan I Soesatio menghentikan perlawanan.
Sekitar 80 pucuk senapan Lee Enfield
beserta seluruh persenjataan anggota Kompi II Polisi
Militer, diletakkan di halaman rumput depan Istana. Dengan kedua tangan di atas kepala, seluruh
anggota Polisi Militer keluar dari halaman Istana, berbelok ke kanan, berbaris ke arah simpang
empat ujung Malioboro. Kemudian sekali lagi belok ke kanan, masuk ke Jalan Kauman.
Kemudian Bung Karno menyuruh Letnan I Kemal Toping, Komandan Peleton I, Kompi II,
Batalyon Mobil II Polisi Militer untuk mengibarkan bendera putih. Dengan demikian, Bung
Karno, Bung Hatta, dan anggota kabinet lain yang tetap berada diIstana telah resmi ditangkap
oleh pasukan Belanda.
|
 23
Gambar 2.8 Presiden Soekarno
Dibawah pengawasan tentara Belanda, Bung Karno ditetapkan sebagai tahanan rumah,
selama 3 hari hingga kemudian pada tanggal 22 Desember
1948, Beliau beserta Agoes Salim
dan Sutan Syahrir diterbangkan ke Medan, kemudian di tahan di Brastagi. Sedangkan Bung
Hatta dan para tokoh sisanya dityahan di Menoembing, sebuah tempat peristirahatan di puncak
bukit, dekat Moentok, Pulau Bangka.
2.5.3 Proposal Negara Bagian Jawa Tengah
Komitmen Sri Sutan Hamengku Buwono IX dan Kasultanan kepada RI tak sebatas
ucapan, tetapi berwujud karya nyata dan pengorbanan tanpa pamrih. Sejak Ibukota RI berpindah
ke Yogya, Kasultanan memberikan banyak dukungan fasilitas dan juga finansial untuk
memperlancar jalannya pemerintahan RI di Yogya.
|
|
24
Ketika keadaan menjadi sangat genting karena belanda melancarkan agresinya, Sri
Sultan Hamengku Buwono IX memainkan peran sangat penting. Dalam serbuan Belanda sejak
19 Desember 1948 itu, Presiden RI dan Wakil Presiden RI ditangkap. Penduduk pun panik dan
mengungsi ke Keraton Yogya. Dalam situasai perang, Sri Sultan Hamengku Buwono IX
memberi pesan khusus kepada Walikota Yogya, Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, pertama,
kalau kondisi benar-benar gawat, maka Sultan akan mengambil alih. Kedua, Walikota harus
tetap di tempat, jangan pergi. Ketiga, Walikota harus berusaha supaya tidak ikut ditangkap
Belanda.
Setelah Presiden RI dan wakilnya ditangkap, terjadi kevakuman kekuasaan di Yogya.
Dalam kondisi demikian, Sidang Kabinet RI menunjuk Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin
Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat .
Sementara itu, dalam kondisi kevakuman tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX
menjadi
tumpuan harapan bagi eksistensi RI di mata dunia internasional.
Belanda tahu bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan benteng pertahanan
bagi berdirinya RI. Karena itu, Belanda berusaha membujuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Bahkan, Belanda
memberi iming-iming untuk menjadikannya sebagai "Super Wali Nagari" atas
Jawa dan Madura dalam rangka negara federal yang sedang direncanakan oleh Belanda. Karena
komitmen kepada RI sudah membaja, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertekad untuk tidak
pernah ingkar janji kepada RI. Apapun janji setia yang telah diucapkannya tidak diingkarinya,
sabda pandhito ratu tan kena wola-wali. Sri Sultan Hamengku Buwono IX pun menolak semua
bujukan itu. Semua utusan Belanda yang antara lain adalah Residen E.M. Stock, Dr.
Berkhuis,
Kolonel Van Langen, Sultan Hamid II, dan Prof. Husein Djajadiningrat ditolaknya mentah-
mentah.
Dalam bersikap anti-kompromi itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX pun bertaruh
nyawa. Jenderal Spoor sudah mengancam untuk mendobrak pintu gerbang Keraton Yogya
dengan tank. Pada waktu Jenderal Meyer datang ke Yogya dan ingin masuk Keraton untuk
mencoba membujuuk agara memihak kepada Belanda, dijawabnya dengan singkat,"Over mijn
link heen!"
Artinya, "Bila itu maksud tuan, maka tuan hanya bisa masuk Keraton ini dengan
melangkahi mayat saya dulu!"
|
 25
2.4.4 Serangan Umum 1 Maret 1949
Sri Sultan Hamengku Buwono IX, merupakan penggagas dari Serangan 1 Maret 1949,
Ide ini beliau dapatkan ketika mendengarkan siaran radio BBC pada akhir Februari 1949
mengenai masalah antara Indonesia-Belanda akan dibicarakan di forum PBB. Ide ini segera
disampaikan kepada Panglima Besar, Jenderal Soedirman, yang saat itu sedang ikut bergerilya.
Hingga akhirnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat mendatangkan Letnan Kolonel Suharto
dan melakukan pertemuan rahasia pada tanggal 13 Februari 1949, untuk menanyakan
kesanggupannya menjalankan siasat ini.
di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibukota Republik,
Yogyakarta, serta koar-besaran oleh pasukan Brigade X
yang diperkuat dengan satu Batalyon
dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda
di Magelang
dan
penghadangan di jalur Magelta-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai Instruksi
Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng
kepada
Komandan Wehrkreis I, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini. Pada saat
yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan
adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat
mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.
Gambar 2.9 Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949
|
|
26
Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum
itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam
kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke
segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari
sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan
kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil
menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah
ditentukan semula, pasukan TNI mengundurkan diri.
Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih Yogyakarta
sebagai sasaran utama adalah:
1.
Yogyakarta adalah Ibukota RI, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa
jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda.
2.
Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya
3.
Langsung di bawah wilayah Divisi III/GM III sehingga tidak perlu persetujuan
Panglima/GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerah operasi.
2.6 Keistimewaan Yogyakarta
Berdasarkan data-data di atas, Penulis menyimpulkan bahwa, keistimewaan Yogyakarta,
terletak pada sejarahnya, mengingat :
1.
Pada waktu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan Republik
Indonesia, saat itu Yogyakarta telah layak untuk mendirikan negara sendiri atau
memiliki syarat-syarat dasar untuk menjadi sebuah negara, yaitu memiliki wilayah,
memiliki rakyat, dan memiliki sistem pemerintahan. Namun Yogyakarta justru
menggabungkan diri di bawah pemerintahan Republik Indonesia, sehigga Yogyakarta
menerima predikat 'istimewa', langsung dari Presiden Soekarno lewat piagam 19 agustus
1945.
2.
Yogyakarta pernah menjadi pusat pemerintahan RI, sebagai ibukota pada tanggal 4
Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Saat itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX
|
|
27
bahkan memberikan beberapa properti pribadi miliknya untuk menjadi Istana Negara,
serta membongkar tabungan Kraton untuk menggaji staff Republik.
3.
Yogyakarta terlibat dan berperan aktif mendukung perjuangan RI, sehingga turut
mengalami masa-masa peperangan, mulai dari bombardir tentara Inggris, agresi militer
Belanda II dan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dimana Yogyakarta mengalami
kerusakan yang parah karena menjadi pusat daerah peperangan.
4.
Sikap dan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menolak segala iming-
iming
dari Belanda akan pembentukan NegaraWilayah Jawa Tengah dengan Sultan
sebagai kepala pemerintahannya, dan malah membantu RI untuk mencapai kemerdekaan
sejati.
Dengan fakta-fakta sejarah ini, penulis bertujuan mengingatkan akan sejarah yang terlupakan
mengenai asal-usul keistimewaan Yogyakarta.
2.7 Analogi Perbandingan dengan Aceh
Menurut Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo dalam bukunya yang berjudul Catatan
Perjalanan Keistimewaan Yogya, untuk memahami kelahiran DIY, perlu diperhatikan
bagaimana perbedaannya dengan kelahiran Daerah Istimewa Aceh. Yogya disebut istimewa
karena sebelum bergabung dengan RI sudah memiliki sistem pemerintahan tersendiri atau apa
yang disebut dalam pasal 18 UUD 1945 sebagai "susunan asli". Hal itu jelas karena Yogya
merupakan sebuah kerajaan atau "nagari" tersendiri. Adapun Aceh, pada waktu bergabung
dengan RI, bukan merupakan penerus langsung dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di
daerah itu (Sujamto, 1988).
Pada jaman Hindia Belanda, Aceh merupakan sebuah karesidenan. Pada masa itu,
Karesidenan Aceh terdiri dari beberapa kabupaten (afdeling). Di kawasan Aceh tersebut ada
beberapa daerah Zelfbestruurd gebied. Ada pula beberapa daerah yang diperintah langsung oleh
Pemerintah Hindia Belanda, disebut sebagai daerah rechstreeks bestruud gebied.
Proses sampai akhirnya menjadi Daerah Istimewa Aceh, menurut Sujamto (1988),
merupakan proses panjang dan melelahkan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut :
|
|
28
Pertama, pada saat RI merdeka, Aceh mendapatkan status baru sebagai sebuah
karesidenan di dalam Provinsi Sumatera.
Kedua, Pada masa revolusi kemerdekaan, Aceh menjadi sebuah Daerah Militer. Aceh
bersama dengan Langkat dan Tanah Karo merupakan Daerah Militer di dalam Provinsi
Sumatera.
Ketiga, daerah Aceh disebut Presiden Soekarno sebagai "daerah modal" bagi Republik.
Kemudian, dibentuklah Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat dan Tanah Karo.
Keempat, Banda Aceh (Kutaraja) menjadi tempat kedudukan (kantor) Wakil Perdana
Menteri RI. Pada waktu itu rakyat Aceh menyatakan aspirasi untuk menjadikan Aceh sebagai
Provinsi Otonom.
Kelima, Wakil Perdada Menteri menetapkan Peraturan Perdana Menteri Pengganti
Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh. Wilayahnya
agak lebih luas dari wilayah Provinsi DI Aceh yang sekarang ini.
Keenam, karena rakyat terus-menerus bergejolak dan menuntut supaya Aceh diberi
otonomi secara khusus, akhirnya diputuskan bahwa Aceh merupakan sebuah Daerah Istimewa.
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959 No.1/Misi/1959
menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut sebagai Daerah Istimewa
Aceh.
Proses itu berbeda dengan Yogyakarta. Ketika RI merdeka, Yogya merupakan sebuah
kerajaan (Kasultanan dan Pakualaman) yang berdaulat penuh. Yogya memiliki sistem
pemerintahannya sendiri. Namun, pemimpin pemerintahan (raja) di Yogya memutuskan untuk
bergabung dengan RI.
2.8 Animasi Dokumenter
Animasi Dokumenter adalah sebuah genre film yang mengkombinasikan genre animasi
dan dokumenter. Karya pertama yang diakui sebagai animasi dokumenter adalah karya Winsor
McKay pada tahun 1918, sebuat film dengan durasi 12 menit yang berjudul The Sinking of the
|
|
29
Lusitania, yang menggunakan
animasi untuk menggambarkan RMS Lusitania yang tenggelam
pada 1915 akibat terkena 2 tembakan torpedo yang ditembakan oleh German U-boat, ini
merupakan sebuah even yang tidak memiliki rekaman footage apapun. Contoh lain dari film
Animasi Dokumenter adalah Abductees (2005) karya Paul Vester, film ini menampilkan
wawancara dengan beberapa orang yang mengaku pernah diculik oleh makhluk luar angkasa,
dari wawancara tersebut pengalam mereka ditampilkan kembali dalam bentuk animasi. Selain itu
ada juga Waltz With
Bashir (2008) yang masuk dalam nominasi Academy Awards sebagai Best
Foreign Languages Film menceritakan tentang perang Libanon di tahun 1982. Dengan ini dapat
disimpulkan bahwa pembuatan film dokumenter yang menggunakan pendekatan teknik animasi
dapat digunakan ketika:
Tidak ada rekaman nyata dari kejadian yang akan di dokumentasikan.
Hal yang akan didokumentasikan, merupakan hal yang mustahil atau memakan biaya
yang sangat besar untuk direka ulang.
Selain itu, penggunaan animasi akan memungkinkan penulis
untuk meningkatkan ketertarikan
serta memudahkan audiens dalam mempelajari isi dari film. Sesuai dengan kategori dari tugas
akhir ini, Penulis menggunakan teknik animasi untuk memberikan gambaran tentang hal-hal
yang pernah terjadi dalam sejarah, terutama
yang tidak mungkin untuk direka ulang, serta
dengan menggunakan penggambaran yang menarik untuk menarik minat audiens dalam
memahami konten dari film animasi dokumenter ini.
2. 9 Target Audiens
2.8.1 Target Primer
Target audiens primer dari film Animasi Dokumenter Asal-usul Keistimewaan
Yogyakarta ini adalah audiens dengan usia 17-25 tahun, laki-laki maupun perempuan, yang
tinggal di kota-kota besar, khususnya yang berada di kota Yogyakarta. Dengan pendidikan
minimal SMA atau Sarjana. Memiliki ketertarikan di bidang sejarah terutama sejarah kota
Yogyakarta, film, dan animasi. Dengan tingkat kemampuan ekonomi menengah ke atas.
2.8.2. Target Sekunder
Target audiens sekunder dari film Animasi Dokumenter Fajar di Yogyakarta adalah
audiens dengan usia diatas 25 tahun, laki-laki maupun perempuan, yang tinggal di kota-kota
besar, khususnya yang berada di kota Yogyakarta. Dengan pendidikan minimal SMA atau
|
|
30
Sarjana. Dan memiliki ketertarikan mengenai polemik keistimewaan Yogyakarta. Dengan
tingkat ekonomi menengah ke atas.
2.9.3 Analisa Kasus
2.9.3.1 Faktor Pendukung
1.
Tema yang diangkat dapat menjadi referensi dan
reminder, bagi permasalahan yang
sedang terjadi mengenai polemik keistimewaan Yogyakarta.
2.
Tema yang diangkat dapat mengangkat rasa nasionalisme masyarakat, khususnya
masyarakat Yogyakarta agar dapat lebih mencintai kotanya.
3.
Tema yang diangkat dapat memberikan pengetahuan mengenai sejarah Yogyakarta.
4.
Penggunaan teknik animasi dapat merekonstruksi kejadian-kejadian sejarah yang pernah
terjadi dan yang tidak dapat direka ulang secara nyata.
2.9.3.2 Faktor Penghambat
1.
Tema yang diangkat memiliki kontroversi dan berbagai versi mengenai pemrakarsa dan
pelaku serangan umum 1 maret 1949.
2.
Banyak masyarakat yang kurang tertarik untuk mengetahui sejarah atau kisah
kepahlawan para pahlawan bangsa.
3.
Tidak semua data mengenai sejarah Yogyakarta dapat dibahas karena keterbatasan
dalam segi waktu.
2.9.3.3 Analisa Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta dan Penetapan-penetapannya
Berdasarkan data-data yang penulis
miliki, yaitu dari buku-buku dan literatur mengenai
sejarah berdirinya Yogyakarta, keterlibatan Yogyakarta pasca kemerdekaan hingga
keistimewaan Yogyakarta, mengenai tokoh-tokoh yang terlibat, peristiwa-perstiwa pentingnya
serta keterkaitannya dengan Polemik Keistimewaan Yogyakarta, maka akan dibuat film animasi
dokumenter Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta.
|