|
12
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1
Kerangka Teori dan Literatur
II.1.1
Pengertian Aset Tetap
Pada umumnya, konsep utama dari aset tetap adalah semua harta
berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk
membantu/menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan
produk – produk, baik barang maupun jasa.
Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011: 510), aset tetap adalah:
“tangible assets that are held for use in production or supply of goods and
services, for rentals to others, or for administrative purposes; they are expected
to be used during more than one period.”
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pengertian aset tetap dalam
PSAK No.16 (2007: 2.6) adalah sebagai berikut:
“Aset tetap adalah aset berwujud yang:
(a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa
untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif; dan
(b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”
Sedangkan menurut Hery (2011: 148), Aktiva tetap (fixed assets) adalah
aktiva yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif
permanen serta memiliki masa kegunaan (useful life) yang panjang.
|
|
13
II.1.1.1 Jenis – jenis Aset Tetap
Menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2009: 439), aset tetap dibagi
menjadi dua kategori, yakni aset berwujud (tangible assets)
dan aset tak
berwujud (intangible assets). Adapun aset berwujud adalah sebagai berikut:
1.
Tanah (land)
Tanah merupakan aset yang dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai lokasi
guna membangun pabrik manufaktur atau kantor. (Pada tugas akhir ini,
penulis hanya membahas terkait pengakuan dan penurunan nilainya, karena
komponen-komponen tanah lainnya telah diatur secara khusus pada PSAK
47: Tanah).
2.
Gedung (buildings)
Gedung merupakan fasilitas yang digunakan untuk operasi
perusahaan,
seperti toko, kantor, pabrik, gudang, dan hanggar pesawat.
3.
Peralatan (equipments)
Peralatan meliputi aset yang digunakan dalam operasi perusahaan, seperti
counter kasir suatu toko, furnitur kantor, mesin pabrik, truk pengangkut, dan
pesawat.
Adapun aset tak berwujud yang dikemukakan oleh Weygandt, Kieso, dan
Kimmel (2009: 455) adalah sebagai berikut:
1.
Paten (patents)
Paten merupakan hak eksklusif yang dikeluarkan oleh Kantor Paten Amerika
Serikat yang mengijinkan para penerima paten tersebut untuk memproduksi,
menjual atau pun mengontrol sebuah temuan untuk periode 20 (dua puluh)
|
|
14
tahun dari tanggal diberikannya paten. Paten bersifat tidak dapat diperbaharui
(nonrenewable).
2.
Hak Cipta (copyrights)
Pemerintah memberikan hak cipta yang mana memberikan pemilik (owner)
memperoleh hak eksklusif untuk memproduksi ulang dan menjual atau
mempublikasikan hasil karya artistik.
3.
Merek atau Nama Dagang (trademarks atau trade names)
Merek atau nama dagang merupakan suatu kata, frasa, sebutan, atau simbol
yang menandai suatu perusahaan atau produk tertentu, seperti Game Boy,
Coca – Cola, Windows, Pepsi, dan Jeep.
4.
Waralaba dan Lisensi (franchises dan licenses)
Waralaba merupakan suatu bentuk pengaturan atau susunan kontraktual
antara franschisor dan franchisee. Franschisor memberikan franchisee hak
untuk menjual produk tertentu, penyediaan jasa tertentu, atau penggunaan
merek atau nama dagang, biasanya dalam area geografis yang sudah
ditentukan. Lisensi merupakan suatu hak eksklusif untuk menggunakan
properti publik dalam menjalankan operasi atau jasa lainnya. Bentuk dari
lisensi adalah hak operasi seperti siaran radio, siaran televisi, dan jasa taksi.
5.
Goodwill
Goodwill menggambarkan nilai semua atribut baik atau menguntungkan yang
berhubungan dengan perusahaan, seperti manajemen yang luar biasa, lokasi
idaman, hubungan baik dengan pelanggan, karyawan terlatih, produk
berkualitas tinggi, dan hubungan harmonis dengan serikat pekerja.
|
|
15
II.1.1.2 Karakteristik Aset Tetap
Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi aset tetap agar dapat
tergolong dalam aset berwujud, antara lain;
1.
Aset dibeli untuk digunakan dalam memproduksi barang atau jasa, untuk
disewakan ke pihak ketiga atau untuk digunakan kebutuhan administrasi,
2.
Merupakan elemen yang dikontrol perusahaan dan seharusnya mampu
menghasilkan manfaat ekonomi selama masa manfaat,
3.
Biasanya digunakan dalam jangka waktu yang lama.
Pengakuan aset tetap diwujudkan dengan memperkirakan manfaat
ekonomi di masa depan sebagai pengaruh penggunaan, sewa atau kepemilikan,
proyeksi terkait aset tersebut untuk faktanya adalah perusahaan dapat
memperoleh manfaat dari aset tersebut, juga mempertimbangkan risiko
potensialnya.
Aktiva tetap merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan baik
ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan, maupun
pengawasannya. Menurut Hery (2012: 272), terdapat ciri – ciri tambahan yang
membedakan aset tetap dari aset lainnya, antara lain:
1.
Merupakan barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi
barang atau jasa dalam operasi normal.
2.
Memiliki umur yang terbatas (kecuali tanah).
3.
Pada akhir masa manfaatnya harus dibuang atau diganti.
4.
Nilainya berasal dari kemampuan dalam memperoleh hak – haknya yang sah
atas pemanfaatan aset tersebut.
5.
Seluruhnya bersifat non – moneter.
|
|
16
6.
Umumnya jasa atau manfaat yang diterima dari aset tetap meliputi periode
yang panjang, lebih dari satu tahun.
II.1.1.3 Pengeluaran Aset Tetap
Menurut Temy Setiawan (2012: 119), pengeluaran atas aset tetap selama
umur ekonomisnya terbagi menjadi dua kategori, antara lain:
1.
Pengeluaran Modal (capital expenditures)
Pengeluaran modal merupakan pengeluaran atas aset tetap dalam jumlah
uang yang besar dan biasanya berupa:
a.
Penambahan pada Aset Tetap
Pengeluaran untuk penambahan aset tetap yang terjadi sehingga
menambah saldo perkiraan aktiva tetap (perlakuan yang sama dengan
akuisisi/perolehan aset tetap). Biaya penambahan akan disusutkan selama
sisa umur ekonomis dari aset tetap. Berikut adalah contoh penambahan
pada aset tetap:
1)
Biaya penambahan sistem komputer pada operasional perusahaan.
2)
Penambahan ruangan pada bangunan.
3)
Penambahan kendaraan bermotor.
Asumsi pada 1 Januari 2011, perusahaan membeli aset (peralatan)
seharga Rp. 15.000.000. Maka ayat jurnal yang disajikan adalah;
Peralatan
15.000.000
Kas
15.000.000
(untuk mencatat pembelian aset tetap secara tunai)
|
|
17
Asumsi, pembelian aset secara kredit, pada tanggal 1 Januari 2011,
perusahaan membeli aset seharga Rp. 15.000.000, perusahaan membayar
Rp. 2.000.000 secara tunai, dan sisanya adalah dibayar secara kredit.
Maka akun yang terkait adalah sebagai berikut:
Peralatan
15.000.000
Kas
2.000.000
Hutang
13.000.000
(untuk mencatat pembelian aset secara kredit)
b.
Perbaikan
Perbaikan adalah pengeluaran untuk meningkatkan efisiensi atau
kapasitas operasi. Pengeluaran ini dikapitalisasi dengan menambah ke
harga perolehan aset tetap dan disusutkan menurut estimasi umur
manfaatnya.
Asumsi, pada tanggal 1 Februari 2011, sebuah peralatan
membutuhkan perbaikan atas komponen yang rusak sebesar Rp. 450.000.
Maka jurnal yang harus dicatat adalah:
Beban Perbaikan
450.000
Kas
450.000
(untuk mencatat kas yang keluarkan atas perbaikan peralatan)
c.
Reparasi besar – besaran
Reparasi besar – besaran dapat memperpanjang umur manfaat aset tetap
namun tidak memperpanjang umur aset tetap. Jika reparasi besar-besaran
dapat menambah umur manfaat aset tetap, maka pengeluaran reparasi ini
dibukukan sebagai pengurang perkiraan akumulasi penyusutan.
Akibatnya, penyusutan periodik untuk periode yang
akan datang
|
|
18
ditentukan kembali dasar nilai buku baru aset tetap tersebut dan estimasi
baru dari umur manfaat yang tersisa. Jika tidak memperpanjang umur
manfaat, maka pengeluaran reparasi besar-besaran ini dibukukan sebagai
penambah harga perolehan aset tetap. Asumsi, pada tanggal 15 Juni 2011,
perusahaam melakukan reparasi besar-besaran terhadap aset sebesar Rp.
3.000.000. Maka ayat jurnal yang dicatat adalah:
Akumulasi Depresiasi – mesin
3.000.000
Kas
3.000.000
(untuk mencatat pengeluaran atas reparasi aset)
2.
Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditures)
Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran untuk memelihara dan reparasi
biasa yang sering terjadi agar aset tetap berada dalam kondisi operasi yang
baik dan harus digolongkan sebagai beban, seperti pengeluaran untuk
perawatan rutin kendaraan dan pembelian spareparts, serta biaya pengecatan
dan perbaikan gedung.
II.1.1.4 Komponen Biaya Perolehan
Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi agar dapat diakui sebagai aset
pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Adapun biaya perolehan
yang dijabarkan dalam PSAK No.16 (2007: 7.16) antara lain:
1.
Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh
dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
|
|
19
2.
Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset
ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan
intensi manajemen;
3.
Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi
lokasi aset.
PSAK No.16 (2007: 8.19) juga memberikan contoh biaya-biaya yang
bukan merupakan biaya perolehan aset tetap, antara lain:
1.
Biaya pembukaan fasilitas baru;
2.
Biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi);
3.
Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru
(termasuk biaya pelatihan staf); dan
4.
Administrasi dan biaya overhead umum lainnya.
Pada dasarnya, biaya –
biaya yang dikeluarkan atas aset tetap dapat
diklasifikan menjadi empat tahap, yaitu tahap pendahuluan, sebelum perolehan,
perolehan atau konstruksi, dan pemakaian.
Tahap pendahuluan terjadi sebelum pihak perusahaan yakin atas
kemungkinan dilakukannya pembelian aset tetap. Selama tahap ini, perusahaan
biasanya akan melakukan studi kelayakan dan analisis keuangan untuk
menentukan kemungkinan diperolehnya aset tetap. Biaya –
biaya yang
dikeluarkan dalam tahap pendahuluan ini tidaklah dapat dikaitkan dengan aset
tetap tertentu, sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan.
|
|
20
Pada tahap pra perolehan, keputusan untuk membeli aset tetap telah
menjadi mungkin, namun belum terjadi. Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam
tahap ini, seperti biaya survey, sudah dapat dikaitkan dengan aset tetap tertentu
yang akan dibeli sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal.
Dalam tahap perolehan atau konstruksi, pembelian aset tetap terjadi atau
konstruksi telah dimulai, namun aset tersebut belum siap untuk digunakan. Biaya
–
biaya yang terkait langsung dengan aset yang dibeli harus dikapitalisasi dalam
akun aset tetap tersebut. Contohnya adalah harga beli mesin, pajak, ongkos
angkut, asuransi pengangkutan, instalasi, dan biaya uji coba.
Dalam tahap pemakaian, aset tetap telah siap digunakan. Sepanjang tahap
ini, aset tersebut seharusnya disusutkan. Segala aktifitas perbaikan dan
pemeliharaan atas aset yang sifatnya normal dan rutin harus dicatat langsung ke
dalam akun beban untuk periode bersangkutan. Sedangkan biaya yang terjadi
untuk memperoleh tambahan komponen aset atau mengganti komponen yang
sudah ada, haruslah
dikapitalisasi sepanjang biaya –
biaya ini dapat
meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap atau
memperpanjang masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
II.1.1.5 Pengukuran Aset Tetap
PSAK No.16 memberikan pilihan kepada perusahaan dalam menentukan
kebijakan akuntansi untuk menerapkan metode atau model pengukuran aset
tetap. Model manapun yang akan diadopsi oleh suatu perusahaan, maka harus
menerapkan kebijakan tersebut bagi seluruh kelompok dari aset tetap (plant,
property, equipment). Terdapat dua macam metode atau model pengukuran yang
|
|
21
dapat diterapkan oleh perusahaan guna melakukan pengukuran terhadap aset
tetapnya seperti yang diungkapkan oleh Surya (2012) dengan dasar model pada
PSAK No.16 tahun 2007 sebagai berikut:
a.
Model Biaya (cost model)
Aset tetap dapat diperoleh dari pembelian, pembangunan, hibah, dan
pertukaran dengan aset yang lainnya. IAS 16 dan PSAK 16 mengatur bahwa
suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada
awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Rumus yang digunakan dalam
menghitung cost model adalah: biaya perolehan – (akumulasi penyusutan +
akumulasi penurunan nilai).
b.
Model Revaluasi (revaluation model)
Setelah pengakuan sebagai aset tetap, perusahaan harus menilai kembali aset
tetapnya secara berkala sesuai dengan nilai pasar wajar. Frekuensi revaluasi
aset tetap dilakukan tergantung pada materialitas perbedaan nilai aset tetap
yang direvaluasi.
Asumsi perusahaan melakukan revaluasi atas suatu aset dengan
carrying amount sebesar Rp. 10.000.000 dengan masa manfaat aset tersebut
adalah 5 tahun dan tanpa nilai residu. Maka jurnal yang akan dicatat oleh
perusahaan adalah:
Beban depresiasi
2.000.000
Akumulasi depresiasi – mesin
2.000.000
(untuk mencatat beban depresiasi satu tahun)
Lalu dengan carrying amount
sebesar Rp. 8.000.000 pada tahun
berikutnya, penilai memastikan bahwa aset tersebut memiliki nilai pasar
|
|
22
sebesar Rp. 8.500.000. Sehingga perusahaan memperoleh surplus revaluasi
sebesar Rp. 500.000. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
Akumulasi depresiasi – mesin
500.000
Surplus revaluasi
500.000
(untuk mencatat penyesuaian terhadap nilai wajarnya)
II.1.1.6 Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan bukanlah proses dimana perusahaan mengakumulasikan dana
(kas) untuk mengganti aset tetapnya. Penyusutan juga bukanlah cara untuk
menghitung nilai yang berlaku saat ini atas aset tetap. Penyusutan adalah alokasi
secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode – periode
berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset bersangkutan.
Penyusutan umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan
beban bagi periode dimana aset dimanfaatkan. Pengurangan nilai aset tersebut
dibebankan secara berangsur – angsur atau proporsional ke masing –
masing
periode yang menerima manfaat.
Metode penyusutan (depresiasi) ditentukan guna memiliki alokasi
semantik dari nilai aset yang disusutkan. Pola ini harus mencerminkan pada nilai
manfaat ekonomis aset di masa depan yang diharapkan dapat digunakan oleh
perusahaan.
Berbagai macam metode depresiasi yang dapat diterapkan oleh
perusahaan untuk mengalokasikan besarnya nilai yang disusutkan atas suatu aset
secara semantik selama masa manfaatnya. Pada dasarnya, PSAK No.16 (revisi
2007) tidak menetapkan metode mana yang wajib untuk ditetapkan oleh entitas
|
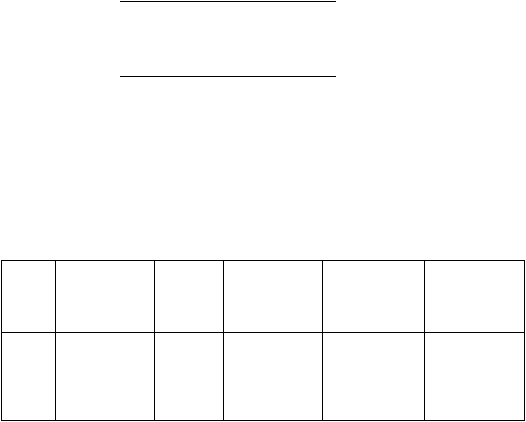 23
selama metode tersebut sesuai dengan keputusan entitas dan tidak menyalahi
prinsip penyusutan pada PSAK No.16. Berikut adalah metode depresiasi yang
dikemukakan oleh Lam dan Lau (2009: 63):
1.
Metode garis lurus (the straight line method)
Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat
apabila nilai residunya tidak berubah. Asumsi, perusahaan membeli aset
sebesar Rp. 35.000.000 dengan masa manfaat 5 tahun, dan nilai
residu
sebesar Rp. 1.500.000. Maka depresiasi metode straight-line selama 1 tahun
adalah sebagai berikut:
Depresiasi
=
Harga perolehan – nilai residu
Masa manfaat
=
35.000.000 – 1.500.000
5
=
Rp. 6.700.000
2.
Metode saldo menurun (the diminishing balance method)
Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama
umur manfaat aset.
Tahun
Nilai Buku
Aset Tahun
Pertama
Tingkat
Bunga
Saldo
Menurun
Beban
Depresiasi
Saldo
Akumulasi
Depresiasi
Nilai Buku,
Akhir Tahun
1
2
3
4
5
Rp. 35.000.000
21.000.000
12.600.000
7.560.000
4.536.000
40%
40%
40%
40%
-
Rp. 14.000.000
8.400.000
5.040.000
3.024.000
3.036.000
Rp. 14.000.000
22.400.000
27.440.000
30.464.000
33.500.000
Rp. 21.000.000
12.600.000
7.560.000
4.536.000
1.500.000
*) tingkat bunga depresiasi diperoleh dari depresiasi per tahun dibagi dengan
harga perolehan dikurangi nilai residu.
|
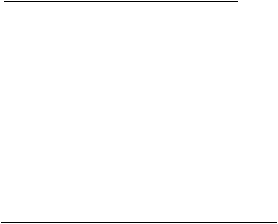 24
3.
Metode jumlah unit (the production of units method)
Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada
penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Dalam menghitung
nilai depresiasi, metode ini dapat menghitung nilai depresiasi untuk per
unitnya atau per jamnya. Adapun penghitungan depresiasi dengan metode
jumlah unit dapat dilakukan melalui dua tahap seperti di bawah ini:
Depresiasi per unit:
Tahap 1.
Depresiasi per unit
Depresiasi per unit
=
Harga Perolehan – Nilai Residu
Jumlah Unit Produksi
Tahap 2.
Menghitung nilai depresiasi
Beban Depresiasi
=
Depresiasi per unit × total unit
produksi yang digunakan
Depresiasi per jam:
Tahap 1.
Depresiasi per jam
Depresiasi per jam
=
Harga Perolehan – Nilai Residu
Jam Operasi Aset Selama Masa Manfaat
Tahap 2.
Menghitung nilai depresiasi
Beban Depresiasi
=
Depresiasi per jam × jam operasi aset
Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tepat dari
pemakaian suatu aset, terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan yang
dikemukakan oleh Weygandt, Kieso & Kimmel (2011: 393), antara lain:
1.
Biaya
|
|
25
Nilai perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait
dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan. Jadi,
disamping harga beli, pengeluaran – pengeluaran lain yang diperlukan untuk
mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga
perolehan. Nilai perolehan aset umumnya mencerminkan nilai pasar pada
saat aset diperoleh.
2.
Masa manfaat
Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, masa manfaat dapat
diartikan sebagai suatu periode atau umur fisik dimana perusahaan dapat
memanfaatkan aset tetapnya dan dapat juga berarti sebagai jumlah unit
produksi atau jumlah jam operasional yang diharapkan diperoleh dari aset.
Faktor –
faktor fisik yang membatasi umur ekonomis suatu aset mencakup
pemakaian, penurunan nilai (berhubungan dengan berlalunya waktu, dimana
suatu aset tetap baik digunakan atau tidak digunakan akan mengalami
penurunan nilai), dan kerusakan (penyebabnya dapat berupa kebakaran,
banjir, gempa bumi, atau kecelakaan yang cenderung mengurangi atau
mengakhiri masa manfaat suatu aset).
3.
Nilai residu
Nilai residu merupakan estimasi nilai aset pada
akhir masa manfaat.
Besarnya estimasi nilai residu sangat tergantung pada kebijakan manajemen
mengenai penghentian aset tetap dan juga tergantung pada kondisi pasar serta
faktor –
faktor lainnya. Apabila perusahaan menggunakan asetnya hingga
secara fisik benar – benar usang dan tidak dapat memberikan manfaat lagi,
maka aset tersebut dapat dikatakan tidak memiliki nilai sisa atau nilai residu.
|
|
26
II.I.1.7 Penurunan Nilai Aset Tetap
Penurunan nilai (impairment) terjadi setelah aset dibeli dan sebelum umur
ekonomisnya berakhir, serta memerlukan penghapusan segera atas nilai aktiva
yang mengalami penurunan. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai
penurunan nilai aset menurut Hery (2011: 187):
1.
Kapan seharusnya aset ditinjau ulang atas kemungkinan terjadinya penurunan
nilai?
Perusahaan perlu melakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya
penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam
penggunaan aset atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Di samping itu,
apabila manajemen memperoleh informasi
bahwa harga pasar aktiva
mengalami penurunan, maka peninjauan ulang atas kemungkinan terjadinya
penurunan nilai dilakukan.
2.
Kapan suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai?
Perusahaan seharusnya mengakui kerugian penurunan nilai (impairment loss)
hanya ketika jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang
akan datang (yang belum didiskontokan) lebih kecil dibandingkan dengan
nilai buku aktiva bersangkutan. Besarnya estimasi arus kas masuk bersih dari
aset di masa yang akan datang (yang belum didiskontokan) ini belum
memperhitungkan nilai waktu atas uang, dan nilainya akan selalu lebih besar
dari nilai wajar aset.
3.
Bagaimana kerugian penurunan nilai aset seharusnya diukur?
Kerugian atas penurunan nilai diukur atau ditentukan sebesar selisih antara
nilai buku aset dengan nilai wajarnya. Nilai wajar di sini dapat ditaksir
|
|
27
dengan menggunakan nilai sekarang (present value) dari jumlah estimasi arus
kas masuk bersih aktiva di masa yang akan datang.
4.
Informasi apa yang seharusnya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan
mengenai penurunan nilai aktiva?
Pengungkapan seharusnya meliputi penjelasan atau uraian mengenai aset
yang mengalamai penurunan nilai, alasan penurunan nilai, dan deskripsi
mengenai asumsi pengukuran. Kerugian penurunan nilai akan dilaporkan
dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari laba operasi berlanjut, yaitu pada
bagian beban dan kerugian lain.
Asumsi, perusahaan membeli aset senilai Rp. 50.000.000 dengan masa
manfaat 5 tahun, nilai residu Rp. 5.000.000, dan akumulasi depresiasi seniai Rp.
9.000.000. Apabila aset tersebut dijual pada fair value senilai Rp. 35.000.000,
maka ayat jurnal penurunan nilai aset akan dicatat oleh perusahaan adalah
sebagai berikut:
Kerugian pada Penurunan Nilai
6.000.000
-
Akumulasi Depresiasi – peralatan
-
6.000.000
(untuk mencatat penurunan nilai aset: (carrying amount Rp. 41.000.000
- harga
jual fair value Rp. 35.000.000))
Menurut PSAK No.16 (revisi 2007), dalam menentukan apakah suatu
aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48: Penurunan
Nilai Aset. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana entitas me-review jumlah
tercatat asetnya, bagaimana menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali dari
aset dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai.
|
|
28
II.1.1.8 Penghentian Aset Tetap
Jika suatu aset sudah tidak bermanfaat dan tidak memiliki
nilai residu,
maka aset tersebut harus dihentikan atau dijual. Apabila aset masih digunakan,
biaya dan akumulasi depresiasi masih dalam buku besar harus disusutkan secara
penuh. Hal tersebut memelihara akuntabilitas aset dalam buku besar. Data atas
biaya dan akumulasi depresiasi pada suatu aset dibutuhkan untuk pajak properti
dan laporan pajak penghasilan.
Asumsi sebuah aset dibeli sebesar Rp. 25.000.000 telah disusutkan secara
penuh pada 31 Desember 2010. Pada 14 Februari 2011, aset dihentikan. Maka
jurnal pengahapusan aset pada 14 Februari 2011 adalah sebagai berikut:
Akumulasi Depresiasi – peralatan
25.000.000
Peralatan
25.000.000
(untuk menghapus peralatan yang dihentikan)
Pada PSAK No.16 (revisi 2007), jumlah tercatat aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat:
1.
Dilepaskan; atau
2.
Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan
atau pelepasannya.
Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus
dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan
pengakuannya (kecuali PSAK No.30 mengharuskan perlakuan yang berbeda
dalam hal transaksi jual dan sewa – balik). Laba tidak boleh diklasifikasikan
sebagai pendapatan.
|
|
29
Dalam menentukan tanggal pelepasan aset, entitas menerapkan kriteria
dalam PSAK No.23: Pendapatan, untuk mengakui pendapatan dari penjualan
barang. PSAK No.30 diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa – balik.
II.1.1.9 Pertukaran Aset Tetap
Akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset tetap sifatnya kontroversial.
Karena beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan harus mencatatnya
berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima,
dengan untung atau rugi yang diakui. Beberapa pihak lain juga yakin bahwa
perusahaan harus mencatatnya berdasarkan nilai buku atas aset yang diserahkan,
tanpa untung atau rugi yang diakui.
Umumnya perusahaan mencatatnya berdasarkan nilai wajar aset yang
diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, manapun selama terbukti lebih
jelas. Perusahaan harus mengakui keuntungan dan kerugian secepatnya. Alasan
dari pengakuan secara cepat adalah dikarenakan banyak transaksi yang memiliki
substansi komersil dan terdapat keuntungan atau kerugian yang harus diakui
perusahaan.
Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011: 416), terdapat dua
kondisi yang terkait dengan pengakuan keuntungan dan kerugian atas pertukaran
aset, antara lain:
1.
Pertukaran aset – gain recognition
Apabila aset yang dipertukarkan memiliki substansi komersil, perusahaan
mencatatkan harga perolehan aset yang diserahkan pada nilai wajar dan
segera mengakui keuntungannya. Untuk aset pertukaran yang diterima,
|
|
30
perusahaan menggunakan nilai wajar apabila terlihat atau diketahui lebih
jelas dari nilai wajar yang diserahkan.
Kondisi lainnya adalah apabila aset
yang dipertukarkan tidak memiliki substansi komersil. Perusahaan mengakui
keuntungan di
saat perusahaan menjual aset tersebut, bukan di waktu
terjadinya transaksi pertukaran aset.
2.
Pertukaran aset – loss recognition
Saat perusahaan melakukan pertukaran aset dan menghasilkan kerugian,
perusahaan mengakui kerugian dengan segera. Perusahaan tidak seharusnya
menghargai aset di atas harga setara kas, apabila kerugian ditahan
pengakuannya, maka aset tersebut dinyatakan lebih catat. Oleh karena itu,
perusahaan segera mengakui kerugian atas pertukaran meskipun aset tersebut
memiliki substansi komersil atau pun tidak.
II.1.1.10 Pengungkapan Aset Tetap
Perusahaan seharusnya menyajikan berbasis valuasi –
biasanya dengan
historical cost –
untuk bangunan, pabrik, dan peralatan selama sesuai dengan
perjanjian, hak gadai, dan kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan aset
tersebut. Hal tersebut tidak akan menutupi segala kewajiban yang dijamin oleh
bangunan, pabrik, dan peralatan terhadap aset tersebut. Hutang tersebut harus
dilaporkan dalam bagian kewajiban. Perusahaan harus memisahkan bangunan,
pabrik, dan peralatan yang saat ini tidak digunakan sebagai aset dalam
berproduksi atau operasi bisnis (seperti bangunan atau tanah yang hanya dimiliki
sebagai suatu bentuk investasi).
|
|
31
Saat menyusutkan aset, perusahaan mengkreditkan akun penilaian
(akumulasi depresiasi). Dengan mencantumkan akumulasi depresiasi di laporan
keuangan, artinya pembaca laporan keuangan dapat melihat harga asli aset dan
jumlah yang disusutkan oleh perusahaan sebagai bentuk beban dalam tahun yang
telah berjalan.
Terkait dengan aset tetap, PSAK 16 (revisi 2007) menjabarkan hal-hal
yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan, antara lain:
1.
Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
2.
Metode penyusutan yang digunakan;
3.
Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4.
Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dijumlahkan dengan
akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode; dan
5.
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan;
a.
Penambahan;
b.
Aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam
kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual
sesuai dengan paragraf 45 dan/atau pelepasan lainnya;
c.
Akuisisi melalui penggabungan usaha;
d.
Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai paragraf 31, 39,
dan 40 serta dari penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik secara
langsung pada ekuitas sesuai PSAK 48;
e.
Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi sesuai PSAK
48;
|
|
32
f.
Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan laba rugi sesuai
PSAK 48, jika ada;
g.
Penyusutan;
h.
Selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan
dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda,
termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang
pelaporan dari entitas pelapor; dan
i.
Perubahan lain.
Laporan keuangan juga mengungkapkan:
1.
Keberatan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan
untuk utang;
2.
Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang
dalam pembangunan;
3.
Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap; dan
4.
Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami
penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi,
jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporang laba rugi.
Jika aset tetap disajikan pada jumlah setelah dilakukan revaluasi, hal
berikut adalah hal – hal yang perlu disajikan:
1.
Tanggal efektif revaluasi;
2.
Pihak independen dilibatkan;
|
|
33
3.
Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai
wajar aset;
4.
Penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung
berdasar harga yang dapat diobservasi (observable price) dalam suatu pasar
aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan
teknik penilaian lainnya;
5.
Untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset
tersebut dicatat dengan model biaya; dan
6.
Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan
pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham.
II.1.2
Pengertian PSAK
PSAK merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana
uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan
akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan
kemampuan dalam akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang
dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK No. 16 adalah Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur mengenai akuntansi terkait aset
tetap entitas dan diperbaharui secara terus menerus sejak tahun 1994.
Perkembangan dan perubahan kondisi pasar dapat menyebabkan suatu prinsip
tidak lagi dapat diterapkan seperti sedia kala. Dengan melakukan revisi – revisi
terhadap PSAK, diharapkan perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan
yang lebih memenuhi standar – standar akuntansi.
|
|
34
PSAK berperan dalam penetapan dasar –
dasar penyajian laporan
keuangan, atau dengan kata lain peranan PSAK mengarah pada perlakuan
pencatatan akuntansi terhadap sumber –
sumber ekonomi agar tiap bagiannya
berada pada posisi yang benar dan tepat. PSAK juga dapat member pedoman
bagi entitas dalam mengenai bagaimana seharusnya sumber ekonomi dicatat dan
bila terjadi perubahan, bagaimana mencatatnya serta kapan perubahan tersebut
dicatat dan disusun dalam laporan keuangan. PSAK juga membantu
menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pengungkapan apabila terjadi
penyimpangan dalam laporan keuangan yang disajikan. PSAK akan menjadi alat
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mengantar kepada
terciptanya sistematis informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya
sehingga dapat membantu para penentu keputusan dalam mengambil keputusan
yang tepat bagi kelangsungan usahanya.
Seiring dengan diberlakukannya standar internasional, yaitu IFRS, kini
PSAK No.16 (revisi 2011) telah mengadopsi prinsip –
prinsip pada IAS 16
(revisi 2011) yang mana sudah diberlakukan mulai tanggal
1 Januari 2012.
Sedangkan PSAK No.16 tahun 2007 telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.
II.1.2.1 Tujuan PSAK No.16 (revisi 2007)
Berikut adalah tujuan PSAK No.16 (2007: 1.1) membuat pernyataan atau
standar akuntansi terkait dengan Aset Tetap:
“Pernyataan ini (PSAK No.16) bertujuan untuk mengatur perlakuan
akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami
informasi mengenai investasi aset di aset tetap, dan perubahan dalam investasi
|
|
35
tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan
jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai aset tetap.”
II.1.2.2 Ruang Lingkup PSAK No.16 (revisi 2007)
Suatu aturan akan berjalan baik apabila memiliki ruang lingkup yang
tidak terlalu luas agar memiliki nilai pengendalian dan pengawasan yang baik.
Sehubungan dengan itu pula, PSAK No.16 tentunya telah menentukan ruang
lingkup yang akan dikuasainya, antara lain:
1.
Pernyataan ini (PSAK No.16) harus diterapkan dalam akuntansi aset tetap
kecuali Pernyatan lain menetapkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi
yang berbeda.
2.
Pernyataan ini (PSAK No.16) tidak berlaku untuk hak penambangan dan
reservasi tambang, seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis
yang tidak dapat diperbaharui. Namun demikian, Pernyataan ini (PSAK
No.16) berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau
memelihara aset yang terkait dengan hak penambangan dan reservasi
tambang di atas.
3.
Penyataan lain bisa saja mensyaratkan pengakuan aset tetap berdasarkan
pendekatan
yang berbeda dari Pernyataan ini (PSAK No.16). Misalnya,
PSAK 30: Sewa mensyaratkan suatu entitas untuk mengevaluasi pengakuan
aset tetap sewaan atas dasar pemindahan risiko dan imbalan. Namun
demikian, dalam aspek perlakuan akuntansi lain tertentu untuk aset tersebut,
termasuk penyusutan, diatur oleh Pernyataan ini (PSAK No.16).
|
|
36
4.
Entitas harus menerapkan Pernyataan ini (PSAK No.16) untuk properti yang
dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan di masa depan sebagai
properti investasi dalam PSAK No.13: Properti Investasi. Ketika konstruksi
atau pengembangan selesai, maka properti tersebut menjadi properti investasi
dan entitas diharuskan menerapkan PSAK No.13. PSAK No.13 juga
diterapkan untuk properti investasi yang sedang dikembangkan ulang
(redevelopment)
untuk dilanjutkan penggunaannya di masa depan sebagai
properti investasi. Entitas yang menggunakan model biaya untuk properti
investasi sesuai PSAK No.13 harus menggunakan model biaya ini dalam
Pernyataan ini (PSAK No.16).
II.1.2.3 Definisi – definisi
Berikut adalah pengertian istilah – istilah yang digunakan dalam PSAK
No.16 (revisi 2007), antara lain:
1.
Aset tetap adalah aset berwujud yang:
a.
dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif;
dan
b.
diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
2.
Biaya perolehan (cost)
adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah
yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan
persyaratan tertentu dalam PSAK lain.
|
|
37
3.
Jumlah tercatat (carrying amount) adalah nilai yang disajikan dalam neraca
setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
4.
Jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) adalah nilai yang
lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai (value in use) suatu aset.
5.
Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan
suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan,
dikurangi nilai residunya.
6.
Nilai khusus aset (entity specific value) adalah nilai kini dari arus kas suatu
entitas yang diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelepasannya
pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian
kewajiban.
7.
Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat
ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset
tesebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur
manfaatnya.
8.
Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset
antara pihak – pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai
dalam suatu transaksi dengan wajar (arm’s length transaction).
9.
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu
aset selama umur manfaatnya.
10. Rugi penurunan nilai (impairment loss)
adalah selisih dari jumlah tercatat
suatu aset dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
11. Umur manfaat (useful life) adalah:
a.
suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas; atau
|
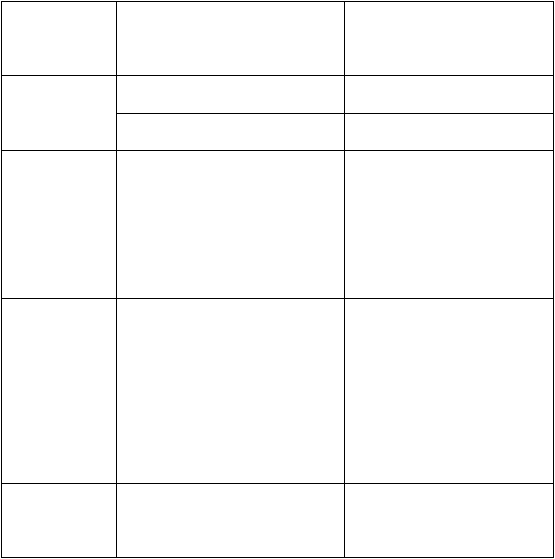 38
b.
jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari
aset tersebut oleh entitas.
II.1.2.4 Perbedaan PSAK No.16 (1994) dengan PSAK No.16 (Revisi 2007)
Secara umum perbedaan antara PSAK No.16 (1994): Aset Tetap dengan
PSAK No.16 (revisi 2007): Aset Tetap adalah sebagai berikut:
TABEL 1
PERBEDAAN PSAK No.16 (1994) DENGAN PSAK No.16 (revisi 2007)
Perihal
PSAK 16
(1994)
PSAK 16
( revisi 2007)
Penggunaan
istilah
Aktiva tetap
Aset tetap
Nilai sisa
Nilai residu
Jumlah tercatat
(Carrying
Amount)
Nilai buku yaitu biaya perolehan
suatu aktiva setelah dikurangi
akumulasi penyusutan.
Nilai disajikan dalam neraca
setelah dikurangi akumulasi
penyusutan dan akumulasi
penurunan nilai.
Jumlah yang
dapat diperoleh
kembali
(Recoverable
Amount)
Jumlah yang diharapkan dapat
diperoleh kembali dari
penggunaan suatu aktiva di masa
yang akan datang termasuk nilai
sisanya atas pelepasan aktiva.
Nilai yang lebih tinggi antara
harga jual neto dan nilai pakai
suatu aset.
Biaya
perolehan
Jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar
Jumlah kas atau setara kas
yang dibayarkan atau nilai
|
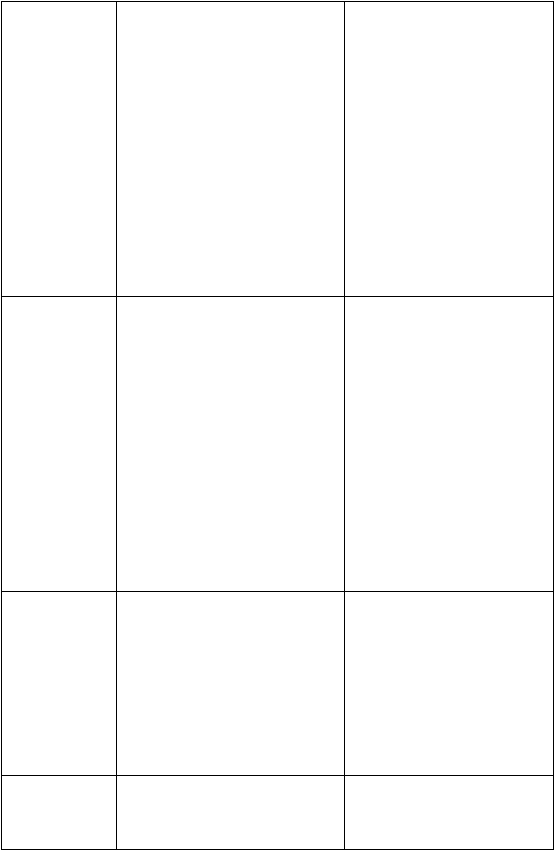 39
imbalan lain yang diberikan
untuk memperoleh suatu aktiva
pada saat perolehan/konstruksi
sampai dengan aktiva tersebut
dalam kondisi dan tempat yang
siap untuk dipergunakan.
wajar dari imbalan lain yang
diserahkan untuk memperoleh
atau konstruksi atau, jika
dapat diterapkan jumlah yang
dapat diatribusikan ke aset
pada saat pertama kali diakui
sesuai dengan persyaratan
tertentu dalam PSAK lain.
Nilai residu
Nilai sisa adalah jumlah neto
yang diharapkan dapat diperoleh
pada akhir masa manfaat suatu
aktiva setelah dikurangi taksiran
biaya pelepasan.
Nilai residu adalah jumlah
perkiraan akan diperoleh
entitas saat ini dari pelepasan
aset, setelah dikurangi
taksiran biaya pelepasan jika
aset telah mencapai umur dan
kondisi yang diharapkan pada
akhir masa manfaatnya.
Jumlah
yang
dapat
disusutkan
Biaya perolehan suatu
aktiva/jumlah lain yang
disubstitusikan untuk biaya
dalam laporan keuangan
dikurangi nilai sisanya.
Biaya perolehan suatu aset,
atau jumlah lain yang menjadi
pengganti biaya perolehan,
dikurangi nilai residunya.
Nilai wajar
Suatu jumlah untuk semua aktiva
mungkin ditukar atau suatu
Suatu jumlah yang dapat
dipakai untuk
|
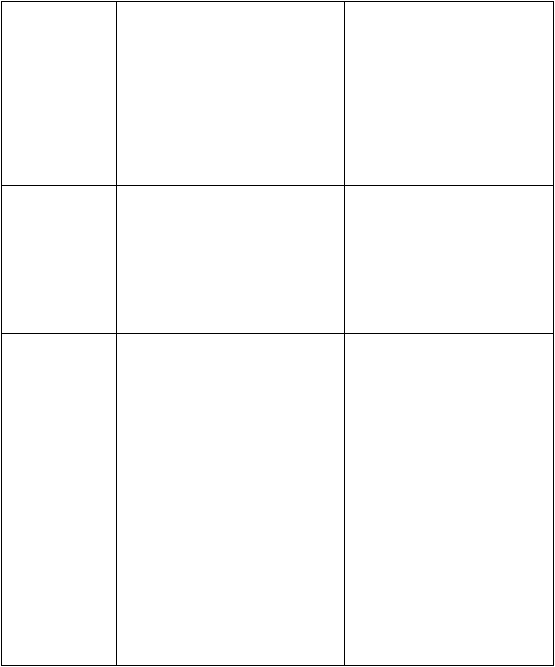 40
kewajiban diselesaikan antara
pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar.
mempertukarkan suatu aset
antara pihak –pihak
yang
berkepentingan dan memiliki
pengetahuan memadai dalam
suatu transaksi dengan wajar.
Rugi
penurunan
-
Selisih atau jumlah tercatat
suatu aset tetap dengan
jumlah yang dapat diperoleh
kembali dari aset berwujud.
Pengakuan
awal
-
Pengakuan awal terhadap
biaya –
biaya dalam jumlah
tercatat suatu aset akan
dihentikan ketika aset tersebut
berada pada lokasi dan
kondisi yang diinginkan agar
aset tersebut digunakan sesuai
dengan keinginan dan maksud
manajemen.
II.1.2.5 Perbedaan PSAK No.16 (revisi 2007) dengan PSAK No.16 (revisi 2011)
Selain perbedaan –
perbedaan yang telah dijabarkan pada tabel
sebelumnya, terdapat pula perbedaan – perbedaan terkait dengan hal – hal yang
|
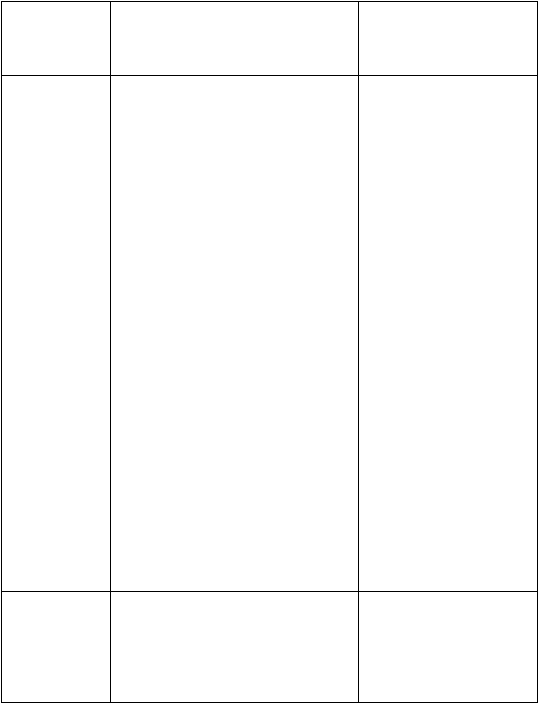 41
dilingkupi oleh PSAK No.16 (revisi 2007) dan PSAK No.16 (revisi 2011) antara
lain:
TABEL 2
PERBEDAAN PSAK No.16 (2007) – PSAK No.16 (revisi 2011)
Perihal
PSAK 16
(Revisi 2011)
PSAK 16
(2007)
Pengecualian
terhadap
ruang lingkup
Menambahkan pengecualian ruang
lingkup untuk:
a.
Aset tetap diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual
sesuai dengan PSAK 58 (Revisi
2009): Aset Tidak Lancar yang
Dimiliki untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan.
b.
Pengakuan dan pengukuran aset
eksplorasi dan evaluasi (Lihat
PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi
dan Evaluasi Pada
Pertambangan Sumber Daya
Mineral)
Hanya mengatur
pengecualian ruang
lingkup untuk hak
penambangan dan
reservasi tambang,
seperti minyak, gas alam,
dan sumber daya alam
jenis yang tidak dapat
diperbaharui.
Ruang lingkup
Tidak mengatur lagi mengenai
properti investasi yang sedang
dibangun atau dikembangkan.
Ruang lingkup mencakup
properti yang dibangun
atau dikembangkan
|
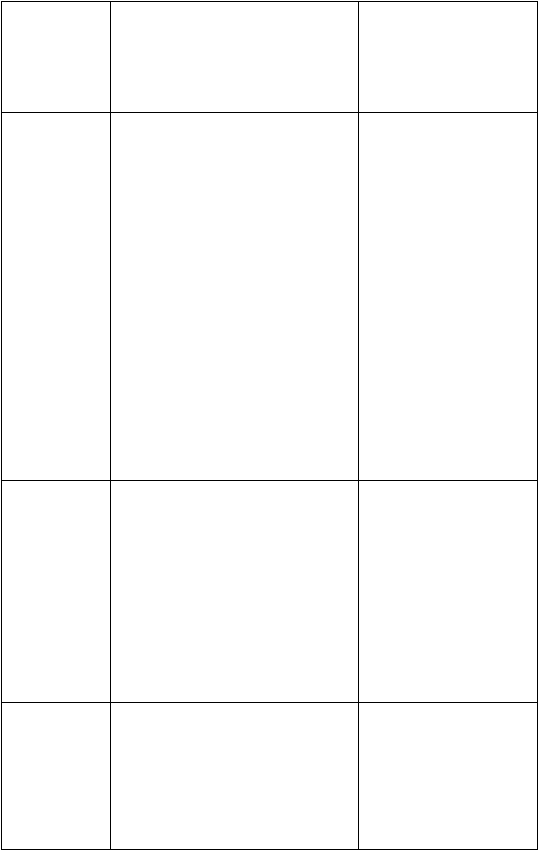 42
untuk digunakan di masa
depan sebagai properti
investasi.
Hibah
pemerintah
Tidak mengatur syarat pengakuan
tetap yang berasal dari hibah. Hanya
mengatur nilai tercatat aset tetap
yang
dapat dikurangi dari hibah
pemerintah.
Pengakuan aset tetap
yang berasal dari hibah
pemerintah mempunyai
syarat bahwa:
a.
Entitas telah
memenuhi kondisi
atau prasyarat hibah
tersebut;
b.
Hibah akan
diperoleh.
Aset tetap
yang tersedia
untuk dijual
Pengaturan aset tetap yang tersedia
untuk dijual harus dihapus karena
sudah diatur dalam PSAK 58
(Revisi 2009): Aset Tidak Lancar
yang Dimiliki untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan.
Mengatur perlakuan
akuntansi terhadap suatu
aset tetap yang tersedia
untuk dijual.
Depresiasi
atas tanah
Menjelaskan bahwa pada umumnya
tanah memiliki umur ekonomis
tidak terbatas sehingga sulit untuk
disusutkan, kecuali entitas meyakini
Perlakuan akuntansi
untuk tanah yang
diperoleh dengan Hak
Guna Usaha, Hak Guna
|
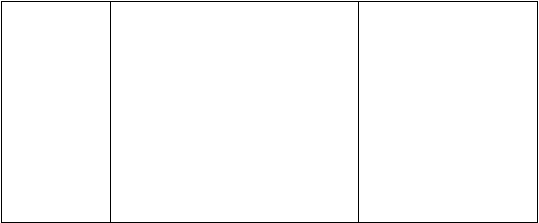 43
umur ekonomis tanah terbatas.
Perlakuan akuntansi tanah yang
diperoleh dengan Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan lainnya
mengacu pada PSAK 25: Hak Atas
Tanah.
Bangunan dan lainnya
mengacu pada PSAK 47:
Tanah.
II.1.2.6 Perbedaan PSAK No.16 tahun 2007 dengan IAS No.16 tahun 2003
PSAK No.16 (2007) mengadopsi seluruh paragraf IAS (2003); Property,
Plant and Equipment kecuali untuk paragraf – paragraf berikut:
1.
IAS 16 paragraf 3 (a), (b) dan (c) tentang ruang lingkup tidak diadopsi karena
IFRS No.5: Non – current Assets Held for Sale and Discontinued Operations,
IAS No.41: Agriculture dan IFRS No.6: Exploration for and Evaluation of
Mineral Resources belum diadopsi.
2.
IAS No.16 paragraf 58 –
59 tentang tanah tidak diadopsi seluruhnya dan
diatur berbeda oleh paragraf 61-62 PSAK No.16 yang mengacu ke PSAK
No.47: Akuntansi Tanah.
3.
IAS No.16 paragraf 81 –
81A tentang tanggal efektif yang kemudian
pengaturannya dalam PSAK No.16 diatur dalam paragraf 85 tidak
mengadopsi IAS No.16 paragraf 81A karena IFRS No.6; Exploration for and
Evaluation of Mineral belum diadopsi.
4.
IAS No.16 paragraf 82 – 83 tentang penarikan standar akuntansi lain yang
kemudian pengaturannya dalam PSAK diatur dalam paragraf 86, hanya
mengadopsi IAS No.16 paragraf 82, sedangkan paragraf 83 tidak diadopsi
|
|
44
karena SIC No.6: Cost of Modifying Existing Software; SIC No.14: Property,
Plant and Equipment – Compensation for the Impairment or Loss of Items;
dan SIC No.23: Property, Plant and Equipment
–
Major Inspection of
Overhaul Costs belum diadopsi.
Selain itu, ada beberapa tambahan paragraf di PSAK 16 (revisi 2007)
yang tidak diatur di IAS 16 (2003), antara lain:
1.
Tambahan paragraf 43 dan 44 dalam PSAK 16 tentang perubahan kebijakan
akuntansi dari model biaya ke model revaluasi.
2.
Tambahan paragraf 45 dalam PSAK 16 tentang perlakuan akuntansi untuk
aset tetap yang tersedia untuk dijual (mengacu ke paragraf 6, 15 dan 30, IFRS
5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations).
3.
Tambahan paragraf 83 dan 84 dalam PSAK 16 tentang ketentuan transisi.
|