|
8
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1
Kerangka Teori dan Literatur
2.1.1
Audit Internal
A.
Definisi Auditing dan Audit Internal
Definisi auditing menurut Boynton (2003:5) yang diterjemahkan oleh
Paul A. Rajoe, adalah:
“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta
mengevaluas bukti secara objektif mengenai asersi-asersi
kegiiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan
derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian
hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Sementara pengertian lain auditing menurut Sukrisno Agoes (2004:3)
adalah sebagai berikut :
“Suatu pemeriksaaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta
catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengtan
tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.”
Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing
merupakan proses pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi
terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut yang dimaksudkan untuk
menetapkan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah
ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut
|
|
9
dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil audit
disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan.
Definisi Audit Internal menurut Boynton (2003:8) yang diterjemahkan
oleh Paul A. Rajoe, adalah:
“Auditor Internal adalah pegawai dari organisasi yang diaudit”
Sementara pengertian Audit Internal menurut Tunggal (2005:3)
adalah sebagai berikut :
“Audit Internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas
(independen) didalam suatu organisasi meninjau kegiatan-
kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan.”
Melalui definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal
adalah kegiatan yang memberikan kepastian dan konsultasi yang independen
dan objektif guna membantu organisasi mewujudkan tujuannya dengan cara
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, perencanaan
pengendalian dan tata kelola perusahaan.Selain itu audit internal juga
diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah di dalam organisasi.
B.
Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal
Fungsi audit internal dalam perusahaan relatif besar, pimpinan
perusahaan membentuk banyak departemen, seksi atau satuan organisasi yang
lain dan sebagian wewenangnya kepada kepala unit organisasi tersebut.
Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang
mendorong perlunya dibentuk fungsi audit internal.
|
|
10
Pengertian fungsi menurut Mulyadi (2002:211) adalah sebagai
berikut :
“Menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan
efesiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi.
Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bagian
bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk
mengukur dan menilai keefektivitasan unsur-unsur
pengendalian internal yang lain.”
Sedangkan pengertian tanggung jawab audit internal menurut Arens
dan Loebbecke (2003:757) adalah sebagai berikut :
“Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi
apakah struktur pengendalian internal perusahaan telah
dirancang dan berjalan efektif dan apakah laporan
keuangan telah disajikan dengan wajar.”
2.1.2
Audit Operasional
A.
Definisi Audit Operasional
Menurut Boynton, W.C. dan Kell W.G. (2003:4) menyatakan bahwa;
“Auditing Operasional adalah suatu proses sistematis yang
mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi
organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen
serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat
hasil-
hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi.”
B. Manfaat Audit Operasional
Laporan audit operasional dapat dijadikan sebagai informasi
pelengkap laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa manfaat yang
bisa diperoleh, yaitu:
1.
Penyelenggaran perusahaan akan makin transparan sehingga pihak lu
ar perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan dengan lebih baik.
2.
Audit operasional dapat memicu manajemen perusahaan untuk lebih b
erhati-hati dalam mengelola perusahaan.
3.
Terlindunginya Kepentingan masyarakat (terutama investor)
|
|
11
C.
Keterbatasan Audit Operasional
Menurut Nugroho Widjayanto (1985:23-24) terdapat beberapa
keterbatasan audit operasional, yaitu :
1.
Waktu: Waktu menjadi faktor yang dapat membatasi, karena auditor
harus memberikan informasi kepada manajemen secara cepat dan tepat
waktu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sebaiknya audit
operasional dilakukan secara teratur untuk menjamin bahwa
permasalahan yang penting dapat diselesaikan.
2.
Keahlian Auditor: Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan para
auditor operasional karena tidak mungkin bagi seorang auditor dapat
mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis.
3.
Biaya: Biaya juga merupakan salah satu factor yang dapat membatasi
audit. Oleh karena itu auditor harus mengabaikan
jia ada masalah kecil
yang mungkin dapat memakan banyak biaya jika diselidiki lebih lanjut.
Sehingga tidak setiap permasalahan mampu diselesaikan dengan adanya
audit operasional ini.
D.
Struktur Audit Operasional
Menurut Guy dkk. (2003:421-424) struktur umum
dari audit
operasional adalah proses yang terdiri dari lima tahap, yaitu :
1.
Pengenalan
Pertama-tama dalam suatu audit operasional, auditor terlebih dahulu harus
mengenali kegiatan atau fungsi yang akan diaudit. Untuk melaksanakan
hal ini, auditor menelaah latar belakang informasi, tujuan, struktur
organisasi, dan pengendalian kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit,
serta menentukan hubungannya dengan kegiatan atau fungsi yang sedang
diaudit serta menentukan hubungannya dengan entitas secara
keseluruhan.
2.
Survei
Sebelum melakukan suatu audit maka lebih dahulu dilakukan survei
pendahuluan (preliminary
survey),auditor harus berusahauntuk mengidentifikasi
bidang masalah dan bidang penting yang menjadi kunci keberhasilan kegi
atan atau fungsi yang sedang diaudit.
3.
Pengembangan Program
Yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyusun program pekerjaan,
berdasarkan tujuan audit, yang merinci pengujian dana analisis yang
harus dilaksanakan atas bidang-bidang yang dianggap penting dari hasil
|
|
12
survey pendahuluan. Selain itu auditor juga diharapkan dapat
menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan staf yang sesuai, menentukan
keterlibatan staf lainnya dalam penugasan, serta menelaah kertas kerja
audit.
4.
Pelaksanaan Audit
Pelaksanaan audit merupakan tahap penting dari audit operasional karena
dalam pelaksanaan audit, auditor dituntut untuk melaporkan fakta-fakta
tentang masalah-masalah yang ada dalam perusahaan. Auditor
melaksanakan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti,
melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan mengembangkan
rekomendasi. Selama melakukan pekerjaan lapangan, auditor harus
menyelesaikan setiap langkah audit yang spesifik dan mencapai tujuan
audit secara keseluruhan untuk mengukur efektivitas, efesiensi, dan
ekonomisasi.
5.
Pelaporan
Tahap pelaporan merupakan bagian terpenting bagi keberhasilan
keseluruhan audit operasional yang dilakukan. Laporan audit operasional
mengandung dua unsure utama, yaitu :
a)
tujuan penugasan, ruang lingkup, dan pendekatan, serta
b)
temuan-temuan khusus dan rekomendasi.
E.
Kesimpulan Audit Operasional
Audit operasional memang diperlukan dalam rangka meningkatkan
kinerja perusahaan. Karena melalui audit ini perusahaan dapat
mengevaluasi keekonomisan, keefektivitasan dan keefisiensian kinerjanya
sehingga pemakai laporan keuangan dapat meyakini kinerja perusahaan.
Hal ini juga akan membuat auditor memiliki nilai tambah dengan tidak
hanya mengeluarkan opini saja, tetapi juga perbaikan terhadap internal
control perusahaan.
F.
Perbedaan Audit Operasional Dengan Audit Manajemen
Audit manajemen berbeda dengan pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan operasional perusahaan. audit manajemen merupakan salah
satu bagian dari pemeriksaan kinerja yang mana memberikan penekanan
|
|
13
pada segi efisiensi dan ekonomi/kehematan pelaksanan fungsi
manajemen, sedangkan pemeriksaan operasional merupakan
perkembangan dari pemeriksaan intern.
Menurut Tunggal (1999:3)
menjelaskan bahwa audit manajemen
adalah
“Mempunyai tujuan untuk melaksanakan penilaian atas usaha
pencapaian tujuan organisasi oleh manajemen. Tekanannya
terletak pada kemampuan para manajer dalam mengelola
organisasi”.
Perlu dibedakan antara audit manajemen dengan pemeriksaan
operasional. Perbedaan tersebut adalah terletak pada titik berat
pemeriksaan, dimana audit manajemen menitikberatkan pada aspek
kualitas atau kemampuan para pengelola/manajer dalam mengelola
sedangkan dalam pemeriksaan operasional titik berat pemeriksaan terletak
pada aspek kualitas yang dijalankan.
Sementara pemeriksaan kinerja sendiri terbagi atas dua tipe yaitu;
pemeriksaan pegelolaan (management audit) dan pemeriksaan hasil
program (program result audit). Arti pengelolaan dalam konteks
pemeriksaan pengelolaan meliputi semua operasi intern suatu organisasi
yang harus dipertanggungjawabkan kepada beberapa pihak yang
mewakili wewenang yang lebih tinggi.
2.1.3
Sistem Pengendalian Manajemen
A.
Definisi Sistem Pengendalian Manajemen
Menurut Boynton etall, yang dialih bahasakan oleh Paul A. Rajoe
(2003:371) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :
“Pengendalian internal adalah suatu
proses yang
dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel
lainnya dalam suatu entitas yang dirancan untuk
|
|
14
memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan
pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan
terhadap hukum yang berlaku, serta efektivitas dan efesiensi
operasi.”
Sedangkan pengertian lain sistem pengendalian manajemen menurut
Anthony dan Govindarajan (2003 ; 20) menyebutkan sebagai berikut:
“Suatu sistem merupakan cara tertentu untuk melaksanakan
suatu atau serangkaian aktivitas. Sistem yang digunakan oleh
manajemen untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi
disebut sistem pengendalian manajemen”.
Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem
pengendalian
manajemen berhubungan dengan cara yang dapat
dilakukan oleh para manajer dalam merancang dan menggunakan sistem
perencanaan dan pengendalian untuk menerapkan strategi.
Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission
(COSO) memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang
dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan
pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima komponen
pengendalian intern tersebut adalah:
1.
Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
2.
Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment)
3.
Sistem Komunikasi dan Informasi (Information and Communication
Sistem)
4.
Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
5.
Monitoring
Konsep COSO ini kemudian diadopsi oleh pemerintah dengan
melakukan modifikasi pada sub-subkomponen di atas dengan berbagai
referensi lain sehingga lahirlah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
|
|
15
sebagai ketentuan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58.SPIP
menetapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam5
(lima) unsur, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Aktivitas Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern.
B.
Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Manajemen
Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai definisi-definisi
pengendalian internal/manajemen, diketahui bahwa terdapat 2 (dua)
pendekatan yang dikembangkan untuk menilai efektivitas sistem
pengendalian manajemen. Pada awalnya sarana yang digunakan untuk
menilai efektivitas pengendalian manajemen menggunakan konsep GAO,
yang menyatakan terdapat 8 (delapan) unsur sistem pengendalian, yaitu:
pengorganisasian, kebijakan, prosedur, personel,perencanaan,
akuntansi/pencatatan, pelaporan, dan review intern.
Dalam perkembangan terakhir, konsep sistem
pengendalian
manajemen mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP sebagai tindak lanjut dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang memperkenalkan
5 (lima)
unsur.Konsep ini sesuai dengan konsep COSO yang meliputi: lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
|
|
16
2.1.4
Akuntansi Pemerintahan
A.
Definisi Akuntansi Pemerintahan
Definisi Akuntansi Pemerintahan menurut Baswir (1998:7) adalah
sebagai berikut:
“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi
untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba
lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan
lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak
bertujuan mencari laba”.
Kemudian Bastian (2001:6) menjelaskan tentang pengertian/definisi
Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:
“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan
analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana
masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan
departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah,
BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada
proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi
Pemerintahan merupakan akuntansi yang digunakan dalam suatu
organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari
laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh.
Ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan adalah :
1.
Non-Profit Motive
2.
Sumber Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah,
laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb
3.
Pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat
(publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
4.
Struktur Organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis
5.
Karakteristik anggaran terbuka untuk publik
|
|
17
B.
Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995
Sejauh ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di
Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit
Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) tahun 1995. SAP tersebut merupakan buku standar untuk
melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah yang meliputi
pelaksanaan APBN, APBD, pefaksanaan anggaran tahunan BUMN dan
BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN
dan BUMD atau badan hukum lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan
pemerintah.Standar-standar
yang menjadi pedoman dalam audit kinerja
terhadap lembaga pemerintah menurut Standar Audit Pemerintahan
adalah sebagai berikut:
1.
Standar Umum
a)
Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif
memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang
disyaratkan.
b)
Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit,
organisasi/ lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun
akuntan publik, harus independen (secara organisasi maupun
secara pribadi), bebas dari gangguan independensi yang
bersifat
pribadi dan yang di luar pribadinya (ekstern), yang dapat
|
|
18
mempengaruhi independensinya, serta harus dapat
mempertahankans ikap dan penampilan yang independen.
c)
Dalam pelaksanaan
audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan
seksama.
d)
Setiap organisasi/lembaga audit yang melaksanakan audit yang
berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern
yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di-
review oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu
ekstern).
2.
Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja
Standar pekerjaan lapangan untuk audit kinerja terdiri atas tiga
hal, yaitu:
a)
Perencanaan, Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.
b)
Supervisi, Staf harus diawasi (disupervisi) dengan baik.
c)
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Apabila
hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan
kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuan
audit, auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan
keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. Dalam
semua audit kinerja, auditor harus waspada terhadap situasi atau
transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsur perbuatan
melanggar/melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.
d)
Pengendalian
Manajemen, Auditor harus benar-benar memahami
pengendalian manajemen yang relevan dengan audit. Apabila
|
|
19
pengendalian manajemen signifikan terhadap tujuan audit, maka
auditor harus memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung
pertimbangannya mengenai pengendalian tersebut.
3.
Standar Pelaporan Audit Kinerja
Standar pelaporan audit kinerja berisi lima hal, yaitu:
a)
Bentuk, Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk
dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit.
b)
Ketepatan Waktu, Auditor harus dengan semestinya menerbitkan
laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan
secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang
berkepentingan.
c)
Isi Laporan, Standar pelaporan ketiga untuk audit kinerja
mencakup isi laporan. Isi laporan audit meliputi:
i.
Tujuan, Lingkup, dan Metodologi Audit, Auditor harus
melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit.
ii.
Hasil
Audit, Auditor harus melaporkan temuan audit yang
signifikan, dan jika mungkin melaporkan kesimpulan auditor.
iii.
Rekomendasi, Auditor harus menyampaikan rekomendasi
untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang
bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan
entitas yang diaudit.
iv.
Pernyataan Standar Audit, Auditor harus melaporkan bahwa
audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan.
v.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
|
|
20
vi.
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
penyalahgunaan wewenang.
vii.
Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan
melanggar/melawan hokum
viii. Pengendalian manajemen
d)
Penyajian Laporan, Laporan harus lengkap, akurat, obyektif,
meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini
dimungkinkan.
e)
Distribusi Laporan, Laporan tertulis audit diserahkan oleh
organisasi/lembaga audit kepada:
i.
pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit,
ii.
kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang
meminta audit,termasuk organisasi luar yang memberikan dana,
kecuali jika peraturan perundang-undangam melarangnya,
iii.
kepada pejabat lain yang mempunyai tanggungjawab atas
pengawasan secara hukum atau pihak yang bertanggungjawab
untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan
rekomendasi audit, dan
iv.
kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang
diaudit untuk menerima laporan tersebut.
C.
Organisasi Sektor Publik Vs Organisasi Sektor Swasta
Oleh karena adanya perbedaan signifikan antara Laporan Keuangan
Perusahaan Non Pemerintah/swasta dengan Laporan Keuangan Sektor
|
|
21
Publik, maka tentunya kegiatan audit yang dilaksanakan sedikit banyak
juga mengalami perbedaan signifikan.
Contohnya Laporan Keuangan
bagi perusahaan swasta yang bersifat profit oriented tentunya memiliki
Laporan Laba Rugi, sementara pada sektor publik
berupa Laporan
Realisasi Anggaran.Selain perbedaan yang cukup signifikan tersebut,
keduanya juga memiliki persamaan-persamaan tertentu.
Perbedaan dan
persamaan antara kedua organisasi tersebut menurut Mardiasmo (2004:8)
adalah sebagai berikut;
1.
Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta
a.
Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di
suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang
sama untuk mencapai tujuan organisasi.
b.
Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah
kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik
sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan
sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.
c.
Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan,
pada dasarnya sama di kedua sektor. Keduanya sama-sama
membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk
melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: perencanaan,
pengorganisasian, dan pengendalian.
d.
Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang
sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama
|
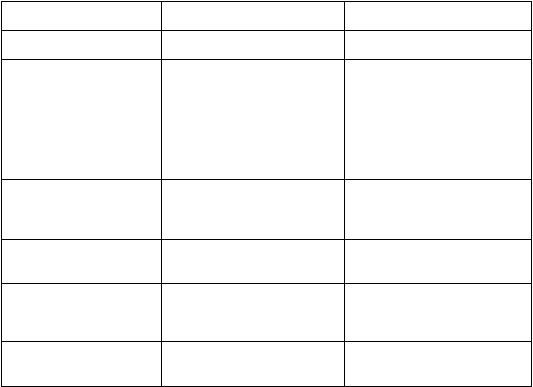 22
bergerak dibidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan,
penyediaan energi, dan sebagainya.
e.
Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan
hukum lain yang disyaratkan.
2.
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta
Sementara perbedaan-perbedaan mengenai sifat dan
karakteristik organisasi sektor publik dan swasta akan diulas melalui
table berikut;
TABEL II.1
PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA
Perbedaan
Sektor Publik
Sektor Swasta
Tujuan organisasi
Nonprofit motive
Profit Motive
Sumber pendanaan
Pajak, retribusi, utang, obligasi
pemerintah, laba
BUMN/BUMD, penjualan aset
negara, dsb.
Pembiayaan internal: Modal
sendiri, laba ditahan, penjualan
aktiva
Pembiayaan eksternal: utang
bank, obligasi, penerbitan
saham
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban kepada
masyarakat (publik) dan
parlemen (DPR/DPRD)
Pertanggungjawaban kepada
pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi
Birokratis,kaku, dan hierarkris
Fleksibel: datar, piramid, lintas
fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran
Terbuka untuk publik
Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi
Lebih banyak menggunakan
sistem akuntansi berbasis kas
Akuntansi berbasis akrual
Sumber : Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
.
|
|
23
D.
Audit Kinerja Pemerintah
Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya
kepemerintahan yang baik (Good governance)
manurut Mardiasmo
(2008), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal
tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya.
Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh
pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPR/DPRD) untuk turut
mengawasi
kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah
mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintalr) untuk menjamin
dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan
organisasi tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki
kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah
telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.Pada tataran teknis
aplikatif juga berbeda, pengawasan oleh DPR/DPRD dilakukan
pada
tahap awal. Pengendalian dilakukan terutama pada tahap menengah
(operasionalisasi anggaran), yaitu level pengendalian manajemen
(management control) dan pengendalian tugas (task control), sedangkan
pemeriksaan dilakukan pada tahap akhir. Objek yang diperiksa berupa
kinerja anggaran (anggaran policy), dan laporan pertanggung jawaban
keuangan yang terdiri atas laporan dan nota perhitungan APBN/APBD,
neraca, dan laporan aliran kas.
Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang
disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif (abuse
|
|
24
of power), maka pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan
pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan
dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPR/DPRD sebagai kekuatan
penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif, dan partisipasi
masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan
organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk social control.
Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem
pengendalian intern yang memadai dan pemberdayaan auditor internal
pemerintah.
Pengawasan oleh DPR/DPRD dan masyarakat tersebut harus sudah
dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan
dan pelaporan saja. Apabila DPR/DPRD lemah dalam tahap perencanaan,
maka sangat mungkin pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak
penyimpangan. Akan tetapi, harus dipahami bahwa pengawasan
DPR/DPRD terhadap eksekutif adalah pengawasan terhadap kebijakan
(policy) yang digariskan, bukan pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan
hendaknya diserahkan kepada lembaga pemeriksa yang memiliki otoritas
dan keahlian profesional, misalnya BPK, BPKP,atau akuntan publik yang
independen. Jika DPR/DPRD menghendaki dewan dapat meminta BPK
atau auditor independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap
kinerja keuangan eksekutif.
|
|
25
2.1.5
PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ini
terdiri dari 61 pasal yang dibagi menjadi 4 Bab, yaitu (1.)Ketentuan Umum,
(2.)Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (3.)Penguatan Efektivitas
Penyelenggaraan SPIP, dan (4.)Ketentuan Penutup. Berikut ini akan diuraikan
keempat bab yang ada pada PP No.60 Tahun 2008 (SPIP), yaitu:
A. Bab 1 Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
2.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya
disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5.
Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan
lembaga.
6.
Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
7.
Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah
yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
|
|
26
8.
Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik
Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam
bidang tertentu.
9.
Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
10.
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11.
Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pasal 2
(1)
Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan.
(2)
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)
SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
B.
Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1)
SPIP terdiri atas unsur:
a.
lingkungan pengendalian;
b.
penilaian risiko;
c.
kegiatan pengendalian;
d.
informasi dan komunikasi; dan
e.
pemantauan pengendalian intern.
(2)
Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi
Pemerintah.
|
|
27
Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian
Pasal 4
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif
untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya,
melalui:
a.
penegakan integritas dan nilai etika;
b.
komitmen terhadap kompetensi;
c.
kepemimpinan yang kondusif;
d.
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e.
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f.
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;
g.
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h.
hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Pasal 5
Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
a.
menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
b.
memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat
pimpinan Instansi Pemerintah;
c.
menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap
kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
d.
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau
pengabaian pengendalian intern; dan
e.
menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku
tidak etis.
Pasal 6
Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
a.
mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam
Instansi Pemerintah;
b.
menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada
masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
c.
menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu
pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;
dan
|
|
28
d.
memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi
Pemerintah.
Pasal 7
Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:
a.
mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
b.
menerapkan manajemen berbasis kinerja;
c.
mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
d.
melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang
tidak sah;
e.
melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang
lebih rendah; dan
f.
merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan
keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
Pasal 8
(1)
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya
dilakukan dengan:
a.
menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
b.
memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi
Pemerintah;
c.
memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam
Instansi Pemerintah;
d.
melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur
organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
e.
menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi
pimpinan.
(2)
Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-
kurangnya dilaksanakan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.
wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat
tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi
Pemerintah;
b.
pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait
dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
|
|
29
c.
pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait
dengan penerapan SPIP.
Pasal 10
(1)
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f
dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-
kurangnya hal-hal
sebagai berikut:
a.
penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan
pemberhentian pegawai;
b.
penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
c.
supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
(2)
Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang- undangan.
Pasal 11
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:
a.
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah;
b.
memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c.
memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Pasal 12
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya
mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.
Bagian Ketiga
Penilaian Risiko
Pasal 13
(1)
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
(2)
Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
identifikasi risiko; dan
b.
analisis risiko.
|
|
30
(3)
Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
a.
tujuan Instansi Pemerintah; dan
b.
tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Pasal 14
(1)
Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat
dicapai, realistis, dan terikat waktu.
(2)
Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
(3)
Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
a.
strategi operasional yang konsisten; dan
b.
strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
Pasal 15
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf b sekurang-
kurangnya dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.
berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
b.
saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu
dengan lainnya;
c.
relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
d.
mengandung unsur kriteria pengukuran;
e.
didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
f.
melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
Pasal 16
Identifikasi
risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
a.
menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b.
menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari
faktor eksternal dan faktor internal; dan
c.
menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
|
|
31
Pasal 17
(1)
Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b
dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
(2)
Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18
(1)
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
(2)
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.
kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi
Pemerintah;
b.
kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
c.
kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus
Instansi Pemerintah;
d.
kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
e.
prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang
ditetapkan secara tertulis; dan
f.
kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang
diharapkan.
(3)
Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
b.
pembinaan sumber daya manusia;
c.
pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d.
pengendalian fisik atas aset;
e.
penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f.
pemisahan fungsi;
g.
otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h.
pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i.
pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j.
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k.
dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta
transaksi dan kejadian penting.
|
|
32
Pasal 19
Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja
dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.
Pasal 20
(1)
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.
(2)
Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-
kurangnya:
a.
mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi
kepada pegawai;
b.
membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia
yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
c.
membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan
pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan
fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja,
serta rencana pengembangan karir.
Pasal 21
(1)
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan
akurasi dan kelengkapan informasi.
(2)
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
pengendalian umum; dan
b.
pengendalian aplikasi.
Pasal 22
Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a.
pengamanan sistem informasi;
b.
pengendalian atas akses;
c.
pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak
aplikasi;
d.
pengendalian atas perangkat lunak sistem;
e.
pemisahan tugas; dan
f.
kontinuitas pelayanan.
|
|
33
Pasal 23
Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a sekurang-kurangnya mencakup:
a.
pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
b.
pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program
pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
c.
penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola
program pengamanan;
d.
penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
e.
implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait
dengan program pengamanan; dan
f.
pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan
program pengamanan jika diperlukan.
Pasal 24
Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
b sekurang-kurangnya mencakup:
a.
klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan
sensitivitasnya;
b.
identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi
secara formal;
c.
pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan
mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
d.
pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran,
serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.
Pasal 25
Pengendalian atas pengembangan dan perubahan
perangkat lunak
aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang-
kurangnya mencakup:
a.
otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
b.
pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan
yang dimutakhirkan; dan
c.
penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian
atas kepustakaan perangkat lunak.
Pasal 26
Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
|
|
34
a.
pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung
jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
b.
pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat
lunak sistem; dan
c.
pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak
sistem.
Pasal 27
Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e
sekurang-kurangnya mencakup:
a.
identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan
untuk memisahkan tugas tersebut;
b.
penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
c.
pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur,
supervisi, dan reviu.
Pasal 28
Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f
sekurang-kurangnya mencakup:
a.
penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya
pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
b.
langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan
terhentinya operasi komputer;
c.
pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk
mengatasi kejadian tidak terduga; dan
d.
pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak
terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Pasal 29
Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf b terdiri atas:
a.
pengendalian otorisasi;
b.
pengendalian kelengkapan;
c.
pengendalian akurasi; dan
d.
pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.
Pasal 30
Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a
sekurang-kurangnya mencakup:
a.
pengendalian terhadap dokumen sumber;
|
|
35
b.
pengesahan atas dokumen sumber;
c.
pembatasan akses ke terminal entri data; dan
d.
penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa
seluruh data yang diproses telah diotorisasi.
Pasal 31
Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
b sekurang-kurangnya mencakup:
a.
pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke
dalam komputer; dan
b.
pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
Pasal 32
Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c
sekurang-kurangnya mencakup:
a.
penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
b.
pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
c.
pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan
segera; dan
d.
reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas
data.
Pasal 33
Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
a.
penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file
data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
b.
penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi
bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
c.
penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal
file header labels sebelum pemrosesan; dan
d.
penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.
Pasal 34
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik
atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan,
mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh
pegawai:
|
|
36
a.
rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
b.
rencana pemulihan setelah bencana.
Pasal 35
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator
dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf
e.
(2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi
Pemerintah harus:
a.
menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
b.
mereviu dan melakukan validasi secara
periodik atas ketetapan dan
keandalan ukuran dan indikator kinerja;
c.
mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
d.
membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan
sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
Pasal 36
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.
(2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh
aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu)
orang.
Pasal 37
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi
dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3) huruf g.
(2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan
dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh
pegawai.
Pasal 38
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat
dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h.
(2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu
mempertimbangkan:
a.
transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat
segera; dan
|
|
37
b.
klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh
siklus transaksi atau kejadian.
Pasal 39
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya
dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf
i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.
(2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan
pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi
Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang
berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara
berkala.
(3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan
pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi
Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan
reviu atas penugasan tersebut secara berkala.
Pasal 40
(1) Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi
yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.
(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki,
mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi
yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan
kejadian penting.
Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi
Pasal 41
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Pasal 42
(1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib
diselenggarakan secara efektif.
|
|
38
(2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-
kurangnya:
a.
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana
komunikasi; dan
b.
mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi
secara terus menerus.
Bagian Keenam
Pemantauan
Pasal 43
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem
Pengendalian Intern.
(2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi
terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Pasal 44
Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(2) diselenggarakan melaluikegiatan pengelolaan rutin, supervisi,
pembandingan,
rekonsiliasi,
dan tindakan lain yang terkait dalam
pelaksanaan tugas.
Pasal 45
(1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian
efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
(2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
(3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji
pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 46
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya yang ditetapkan.
|
|
39
C.
Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47
(1)
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung
jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di
lingkungan masing-masing.
(2)
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian
Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a.
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
b.
pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Instansi Pemerintah
Pasal 48
(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf
a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melakukan pengawasan intern melalui:
a.
audit;
b.
reviu;
c.
evaluasi;
d.
pemantauan; dan
e.
kegiatan pengawasan lainnya.
Pasal 49
(1)
Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
a.
BPKP;
b.
Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern;
c.
Inspektorat Provinsi; dan
d.
Inspektorat Kabupaten/Kota.
(2)
BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
|
|
40
a.
kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b.
kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
c.
kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan
melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah
lainnya.
(4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
(5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah provinsi.
(6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
Pasal 50
(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:
a.
audit kinerja; dan
b.
audit dengan tujuan tertentu.
(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi,
dan efektivitas.
(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Pasal 51
(1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan
oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang
telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
(2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program
sertifikasi.
(3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan
fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
|
|
41
Pasal 52
(1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati
kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi
profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan
pemerintah.
Pasal 53
(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan
intern pemerintah, disusun standar audit.
(2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib
melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Pasal 54
(1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern
pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan
menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.
(2) Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan
kebendaharaan umum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) huruf b, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan
Instansi Pemerintah yang diawasi.
(3) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan
hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
(4) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil
pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya
dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara.
|
|
42
Pasal 55
(1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah,
secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
(2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh organisasi profesi auditor.
Pasal 56
Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
harus independen dan obyektif.
Pasal 57
(1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu
atas laporan
keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan
menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.
(2) Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah
daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.
(3) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4) BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
(5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar
reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Pasal 59
(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (2) huruf b meliputi:
a.
penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
|
|
43
b.
sosialisasi SPIP;
c.
pendidikan dan pelatihan SPIP;
d.
pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
e.
peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh BPKP.
D.
Ketentuan Penutup
Pasal 60
Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah
diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 61
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
2.2
Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis hasil audit
ini adalah berupa penelitian deskriptif, yang meneliti masalah berupa fakta-
fakta saat ini dari suatu populasi .Tujuan penelitian deskriptif adalah menguji
hipotesis dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari
subyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 1999:28).
2.2.1
Populasi dan Sampel
A.
Populasi
Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau
sesuatu yang menarik yang dikehendaki peneliti untuk diteliti (Sekaran, 2000:
|
|
44
266). Populasi dalam studi ini adalah laporan hasil audit yang berada di
Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
B.
Sampel dan teknik pengambilan sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri atas beberapa
anggota atau elemen yang diseleksi (Sekaran, 2000: 267).Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan
tipe judgement sampling. Purposive sampling adalah metode pengumpulan
data dari target grup atau orang yang spesifik yang mempunyai informasi atau
karena mereka sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran,
2000: 278).
Sementara Judgement Sampling sendiri adalah teknik
pengambilan sampel yang meliputi pemilihan subyek yang paling tepat untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 2000: 278).
Pemilihan
sampel akan dilakukan sebagai berikut;
a)
Mengidentifikasi laporan hasil audit dan dokumen pendukung terkait
pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan Inspektorat
Depdiknas selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012
semester I.
b)
Melakukan wawancara dengan beberapa auditor dan pegawai yang
terkait untuk mendapatkan informasi yang relevan dan dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya tentang pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal di Lingkungan Kantor Inspektorat Jenderal
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
|
|
45
c)
Melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung apabila pada
hasil perbandingan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian
Internal terdapat kelemahan-kelemahan terkait pelaksanaan
pengendalian internal di Lingkungan Kantor Inspektorat Jenderal
Kemdikbud.
2.2.2
Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar
pertanyaan-pertanyaan mengenai pendekatan pelaksanaan pengendalian
internal di Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
berdasarkan 5 komponen pengendalian internal yang ada di SPIP. Daftar
pertanyaan tersebut akan diajukan melalui wawancara kepada pegawai yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal di Inspektorat
Jenderalmen Kegiatan penyusunan hasil wawancara dilakukan setelah hasil
analisis penyebab disusun.
2.3
Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian Santoso (2012) yang berjudul “Evaluasi
Penerapan Internal Control Berdasarkan Kerangka COSO 2012 Pada Divisi
Kartu Kredit Di Bank ‘X’”, Setiap badan usaha pasti memiliki internal
control yang digunakan sebagai sarana pengendalian. Hal tersebut bertujuan
agar kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta mendukung
pelaporan dan kepatuhan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Seringkali badan usaha menerapkan internal control
berdasarkan kerangka
COSO.
|
|
46
Berdasarkan
penelitian Rivai (2011) yang berjudul “Analisis Dan
Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi akuntansi
Terkomputerisasi Pada PT Transavia Otomasi Pratama”, Pengendalian intern
terhadap sebuah sistem informasi merupakan hal yang penting dan bersifat
strategis. Oleh karena itu pemahaman dan kesadaran akan hal ini sangat perlu
diperhatikan oleh seganap pemilik serta pengguna aplikasi.
Dengan
pengendalian intern yang memadai maka diharapkan akan menjamin
bahwa
informasi yang dihasilkan memang bermutu dan sesuai dengan apa yang
diharapkan
Menurut Lestariyo (2009) didalam jurnal penelitiannya yang berjudul
“Pengawasan Internal Dan Kinerja”, berpendapat bahwa pengawasan internal
berpengaruh terhadap kinerja
inspektorat jenderal
departemen dalam negeri.
Program
pengawasan internal dan
kondisi
sumber daya berpengaruh negatif
terhadap kinerja pengawasan, baik pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan sarana dan prasarana.
Menurut
Sihwahjoeni (2011) dalam penilitiannya yang berjudul
“Evaluasi Kualitas Fungsi Internal Auditor Dalam Meningkatkan Efektivitas
Bank” tersebut memiliki tujuan untuk mengevaluasi fungsi internal auditor
dalam membantu manajemen meningkatkan efektivitas bank yang nantinya
bisa digunakan sebagai referensi bagi auditor eksternal dalam mengaudit
bank yang bersangkutan.
Didalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Konflik Peran Dan
Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal
Pemerintah Daerah” yang dilakukan oleh Chariri (2010),
menyimpulkan
|
|
47
bahwa konflik peran serta ambiguitas peran yang terjadi pada auditor internal
pemerintah (aparat Inspektorat) di tingkat kota memiliki pengaruh negatif
yang signifikan terhadap komitmen independensi.
Perbedaan penelitian ini dengan penilitian
terdahulu adalah bahwa
pada penelitian ini penulis tidak melakukan evaluasi pengendalian
internal
pada perusahaan-perusahaan profit-oriented, melainkan perusahaan
nirlaba/non-profit oriented. Selain itu pada penelitian-penelitian terdahulu
diatas, variable yang diteliti seperti sistem pengendalian internal perusahaan
menggunakan teori-teori dari COSO, sementara pada penelitian ini
menggunakan SPIP karena obyek yang diteliti adalah perusahaan sektor
publik/Instansi Pemerintah. Mengingat banyaknya Instansi Pemerintahan di
Indonesia yang dapat dijadikan obyek penelitian, penulis
membatasi lingkup
penelitian hanya pada Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan.
|