|
8
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
2.1.1 Pengertian Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
Menurut Mcleod
(2001, p88), analisa sistem adalah penelitian suatu sistem
yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui.
Sedangkan menurut Jeffrey L. Whitten, et al
(2004, p165-166), analisa sistem
adalah teknik pemecahan masalah dengan cara memecahkan sistem ke dalam
komponen-komponen dengan tujuan mempelajari komponen tersebut bekerja dan
berinteraksi untuk menyelesaikan tujuan mereka. Perancangan sistem merupakan
pelengkap dari analisa
sistem ke dalam suatu sistem yang utuh dengan tujuan
mendapatkan sistem yang lebih baik.
Ada enam tahap analisis sistem:
1.
Mengumumkan penelitian sistem.
Ketika perusahaan menerapkan sistem baru, manajemen bekerja sama dengan
pekerja perihal sistem baru tersebut.
2.
Mengorganisasikan tim proyek.
3.
Mendefinisikan kebutuhan informasi.
Melalui wawancara perorangan, pengamatan, pencarian catatan dan survey.
4.
Mendefinisikan kriteria kinerja sistem
Setelah kebutuhan informasi manajer didefinisikan, langkah selanjutnya adalah
menspesifikasi secara tepat apa yang harus dicapai oleh sistem.
5.
Menyiapkan usulan rancangan
|
|
9
Analisa sistem memberikan kesempatan bagi para manajer untuk membuat
keputusan terusan atau hentikan untuk kedua kalinya.
6.
Menyetujui atau menolak rancangan proyek
Manajer dan komite pengarah sistem informasi manajemen mengevaluasi
usulan rancangan dan menentukan apakah memberi persetujuan atau tidak.
Sedangkan menurut McLeod (2001, p238), perancangan sistem adalah
penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru, jika sistem itu berbasis
komputer, perancangan dapat menyertakan spesifikasi peralatan yang akan
digunakan.
Tahap perancangan sistem:
1.
Menyiapkan rancangan sistem yang terinci.
Analis bekerjasama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan
sistem baru dengan alat-alat yang dijelaskan dalam modul teknis.
2.
Mengidentifikasikan berbagai alternatif sistem.
Analis harus mengidentifikasikan konfigurasi peralatan komputer yang akan
memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan.
3.
Mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem.
Analis bekerjasama dengan manajer mengevaluasi berbagai alternatif.
Alternatif yang dipilih adalah yang paling memungkinkan subsistem memenuhi
kriteria kinerja, dengan kendala-kendala yang ada.
|
|
1
4.
Memilih konfigurasi terbaik.
Analis mengevaluasi konfigurasi subsistem dan menyesuaikan dengan
kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi
tunggal. Setelah selesai analis membuat rekomendasi kepada manajer untuk
disetujui.
5.
Menyiapkan usulan penerapan.
Analis menyiapkan ikhtisar tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan.
6.
Menyetujui atau menolak penerapan sistem.
Jika keuntungan yang diharapkan dari sistem melebihi biayanya, penerapan
akan disetujui.
Dari kutipan-kutipan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan
sistem merupakan proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam
suatu rancangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan memberi gambaran yang
lebih jelas untuk dijadikan pertimbangan.
Fact-finding technique
adalah teknik yang digunakan untuk menguraikan
semua perkembangan siklus tetapi sangat kritis dalam keperluan fase analisis.
Setelah fact finding diselesaikan tools seperti use cases data models, process models
dan objects models akan digunakan dalam fakta dokumen dan akhirnya digambarkan
melalui fakta-fakta tersebut (Bentley, 2004, p239)
2.1.2 Software Development Life Cycle (SDLC)
Software development life cycle
(SDLC)
adalah sumber daya yang bisa
mengumpulkan, mengatur , mengontrol dan menyebarkan dari suatu informasi
menuju suatu organisasi. Database
adalah suatu komponen pokok dari suatu
|
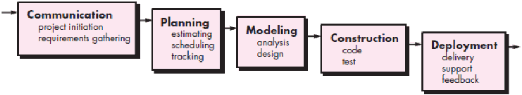 1
sistem informasi dan dikembangkan dan digunakan untuk menunjukkan dari
perspektif
luas dari suatu syarat organisasi. Oleh karenanya siklus dari suatu
sistem informasi organisasi merupakan turunan yang dihubungkan ke siklus
sistem database
yang mendukung. Tahap dari SDLC termasuk diantaranya :
perencanaan, mengumpulkan persyaratan dan analisis, desain , prototyping
,
implementasi, uji coba , konversi dan pemeliharaan operasional .(Conolly , 2006,
p282-283)
Waterfall model
terkadang disebut classic life cycle, menganjurkan secara
sistematis pendekatan sekuensial
pada perkembangan software
yang diawali
keperluan spesifikasi pelanggan dan perkembangan melalui planning, modeling,
construction, dan deployment yang diakhiri dengan dukungan langsung dari software
secara menyeluruh (Pressman, 2008, p79).Berikut ini ada dua gambaran
dari
waterfall model.
Fase-fase dalam model waterfall menurut referensi Pressman:
Gambar 2.1 Waterfall Pressman
1. Communication
Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap untuk
mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan
|
|
1
customer,maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal,
artikel,maupun dari internet.
2. Planning
Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis
requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user
requirement atau bisa
dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam
pembuatan
software, termasuk rencana yang akan dilakukan.
3. Modeling
Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah
perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini
berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan
detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut
software requirement.
4. Construction
Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean
merupakan penerjemahan desain dalam
bahasa yang bisa dikenali oleh
komputer.Programmer akan menerjemahkan transaksi yang
diminta oleh
user.Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu
software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan
ini.Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang
telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap
sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki.
|
|
1
5. Deployment
Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau
sistem.Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah
jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan
pemeliharaan secara berkala.Kelebihan dari model ini adalah selain karena
pengaplikasian menggunakan model ini mudah, kelebihan dari model ini adalah
ketika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar
di awal proyek, maka Software Engineering (SE) dapat berjalan
dengan baik dan
tanpa masalah.Meskipun seringkali kebutuhan sistem tidak dapat didefinisikan se-
eksplisit yang diinginkan, tetapi paling tidak, problem pada kebutuhan sistem di awal
proyek lebih ekonomis dalam hal uang (lebih murah), usaha, dan waktu yang
terbuang lebih sedikit jika dibandingkan problem yang muncul pada tahap-tahap
selanjutnya.
Kekurangan yang utama dari model ini adalah kesulitan dalam mengakomodasi
perubahan setelah proses dijalani. Fase sebelumnya harus lengkap dan selesai
sebelum mengerjakan fase berikutnya.
Masalah dengan waterfall :
1. Perubahan sulit dilakukan karena sifatnya yang kaku.
2. Karena sifat kakunya, model ini cocok ketika kebutuhan dikumpulkan secara
lengkap sehingga perubahan bisa ditekan sekecil mungkin. Tapi pada
kenyataannya jarang sekali konsumen/pengguna yang bisa memberikan
kebutuhan secara lengkap, perubahan kebutuhan adalah sesuatu yang wajar
terjadi.
|
|
1
3. Waterfall pada umumnya digunakan untuk rekayasa sistem yang besar yaitu
dengan proyek yang dikerjakan di beberapa tempat berbeda, dan dibagi
menjadi beberapa bagian sub-proyek.
2.1.3 Database life cycle (DBLC)
Database life cycle
(DBLC) merupakan komponen pokok dari suatu sistem
informasi organisasi yang luas dan merupakan turunan yang berhubungan
dengan software development life cycle (SDLC). Tahapan dari DBLC yaitu :
1.
Perencanaan database yaitu merencanakan bagaimana tahapan dari
siklus yang bisa dicapai seefisien dan seefektif mungkim
2.
Definisi sistem yaitu menspesifikasikan ruang lingkup dan batasan dari
sistem database termasuk pandangan pengguna, penggunanya sendiri,
dan area aplikasi
3.
Pengumpulan persyaratan dan analisis yaitu mengumpulkan dan
menganalisis syarat yang diperlukan untuk system database yang baru
4.
Desain database
yaitu desain konseptual, logikal dan fisikal dari suatu
database
5.
Seleksi DBMS (opsional) yaitu memilih DBMS yang cocok dengan system
database
6.
Desain aplikasi yaitu mendisain user interface dan program –program
aplikasi yang digunakan dan memproses database
7.
Prototyping(opsional) yaitu membangun sebuah model kerja dari suatu
system database, yang menerima pendesain atau pengguna untuk
|
|
1
memvisualisasi dan mengevaluasi bagaimana system final bekerja dan
berfungsi
8.
Implementasi yaitu membuat definisi database fisikal dan program-
program aplikasi
9.
Konversi datan dan loading yaitu data diambil dari system lama ke
system yang baru memungkinkan konversi aplikasi yang sudah ada
untuk bekerja di system yang baru
10. Uji coba yaitu system database harus telah di uji coba terhadap error dan
telah di validasi sesuai dengan syarat yang dispesifikasikan oleh user
11. Pemeliharaan operasional yaitu sistam database harus telah
dilaksanakan seluruhnya. System akan terus di monitor dan di pelihara.
Bila perlu persyaratan baru yang tergabung ke dalam system databse
melalui tahap awal dari siklus (life cycle). (Conolly , 2006, p283-285)
2.2 Sistem Informasi Geografis
2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG)
Menurut ESRI tahun 1990
dalam Hardi et al, (2010), SIG
adalah kumpulan
yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan
personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengubah,
memanipulasi dan menampilkan semua bentuk informasi yang berkaitan dengan
geografi.
Menurut Bernhardsen (1992)
dalam Hardi et al, (2010), SIG
adalah sistem
komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini
diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
|
|
1
berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data,
perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data,
pemanggilan dan persentasi data dan analisa data.
Sedangkan menurut Prahasta
(2005, P49)
dalam Hardi et al, (2010),
SIG
merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan
logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi.
Jadi SIG merupakan kumpulan data geografi (spasial) dan data dokumen (non-
spasial) yang terorganisir dan dapat dimanipulasi.
2.2.2 Subsistem Sistem Informasi Geografis (SIG)
Sistem Informasi Geografis
dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem
(Prahasta, 2005, P56) dalam Hardi et al, (2010), yaitu :
1. Data Input
Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan
atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam
mengkonversi atau mentranformasikan format-format yang dapat digunakan oleh
sistem informasi geografi.
2. Data Output
Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis
data baik dalam bentuk softcopy
maupun dalam bentuk hardcopy
seperti tabel,
grafik, peta, dan lain-lain.
3. Data Management
Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah
basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diperbaharui, dan diperbaiki.
|
 1
4. Data Manipulation and Analysis
Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem
informasi geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan
pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.
Uraian dari subsistem-subsistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.2 Uraian Subsistem-subsistem SIG
2.2.3 Komponen Sistem Informasi Geografis (SIG)
Komponen-komponen SIG terdiri dari :
1.
Perangkat Keras (hardware)
SIG membutuhkan komputer untuk menyimpan dan memproses data. SIG dengan
skala yang kecil membutuhkan PC (Personal Computer) yang kecil untuk
menjalankannya, namun ketika sistem menjadi besar dibutuhkan komputer yang
lebih besar serta host
untuk client machine
yang mendukung penggunaan
multiple
user. Perangkat keras yang digunakan dalam SIG memiliki spesifikasi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya. Ini dikarenakan penyimpanan
|
|
1
data yang digunakan dalam SIG baik data raster
maupun data vector membutuhkan
ruang yang besar dan dalam proses analisisnya membutuhkan memori yang besar
dan processor yang cepat. Selain itu diperlukan juga digitizer untuk mengubah peta
ke dalam bentuk digital.
2.
Perangkat Lunak (software)
Perangkat lunak dalam SIG haruslah mampu menyediakan fungsi dan tool untuk
melakukan penyimpanan data, analisis dan menampilkan informasi geografi.
Dengan demikian, elemen yang harus terdapat dalam komponen perangkat lunak SIG
adalah :
a.
Tool untuk melakukan input dan transformasi data geografi.
b.
Sistem manajemen basis data.
c.
Tool yang mendukung manipulasi geografi, analisa dan visualisasi.
Graphical User Interface (GUI) untuk memudahkan akses pada tool geografi.
Ada banyak perangkat lunak SIG yang dapat kita gunakan, diantaranya adalah Map
Info, Arc Info, Arc View, Arc GIS dan masih banyak lainnya.
3.
Data
Menurut McLeod (2004, P12) dalam Hardi et al, (2010), data merupakan fakta-fakta
dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan Laudon (2003,
P8)
dalam Hardi et al, (2010),
mendeskripsikan data sebagai berkas-berkas fakta
yang masih mentah yang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam
perusahaan/organisasi atau di lingkungan fisik sebelum di susun dalam bentuk yang
dapat dimengerti dan digunakan oleh pemakai. Jenis data yang digunakan dalam
sistem informasi geografi adalah data spasial (peta) dan data non-spasial
(keterangan/atribut).
|
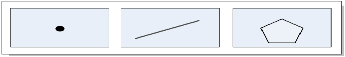 1
Perbedaan antara 2 jenis data tersebut adalah sebagai berikut :
a. Data Spasial
Data spasial adalah data sistem informasi yang terpaut pada dimensi ruang dan
dapat digambarkan dengan berbagai komponen data spasial, yaitu :
1.
Titik
Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana untuk suatu
objek. Representasi ini tidak memiliki dimensi tetapi dapat diidentifikasi di
atas peta dan dapat ditampilkan pada layar monitor dengan menggunakan
simbol-simbol. Titik dapat mewakili objek-objek tertentu berdasarkan skala
yang ditentukan, misalnya letak bangunan, kota, dan lain-lain.
2.
Garis.
Garis adalah bentuk linier yang akan menghubungkan paling sedikit dua
titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek-objek satu dimensi.
Batas-batas poligon merupakan garis-garis, demikian pula dengan jaringan
listrik, saluran buangan, jalan, sungai, dan lain sebagainya.
3.
Poligon
Poligon digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dua dimensi. Suatu
danau, batas propinsi, batas kota, batas-batas persil tanah milik adalah tipe-
tipe entitas
yang pada umumnya direpresentasikan sebagai poligon. Suatu
poligon paling sedikit dibatasi oleh tiga garis yang saling terhubung diantara
ketiga titik tersebut.
Gambar 2.3 Komponen-komponen Data Spasial
|
|
2
b. Data Non-spasial (atribut)
Data atribut adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau fenomena
yang dikandung pada suatu objek data dalam peta dan tidak mempunyai
hubungan dengan posisi geografi. Contoh : data atribut suatu sekolah berupa
jumlah murid, jurusan, jenis kelamin, agama, beserta atribut-atribut lainnya
yang masih mungkin dimiliki dan diperlukan. Atribut dapat dideskripsikan
secara kualitatif dan kuantitatif. Pada pendeskripsian secara kualitatif, kita
mendeskripsikan tipe, klasifikasi, label suatu objek agar dapat dikenal dan
dibedakan dengan objek lain, misalnya : sekolah, rumah sakit, hotel, dan
sebagainya. Bila dilakukan secara kuantitatif, data objek dapat diukur atau
dinilai berdasarkan skala ordinat atau tingkatan, interval atau selang, dan rasio
atau perbandingan dari suatu titik tertentu. Contohnya, populasi/jumlah siswa
di suatu sekolah 500-600 siswa, berprestasi, jurusan, dan sebagainya.
4. Metode
Untuk menghasilkan SIG sesuai dengan yang diinginkan, maka SIG harus
direncanakan dengan matang dengan menggunakan metologi yang benar. SIG
yang baik memiliki keserasian antara rencana desain yang baik dan aturan
dunia nyata, yaitu metode, model dan implementasi akan berbeda-beda untuk
setiap permasalahan.
5. Manusia
Teknologi SIG tidak akan bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem
dan membangun perencanaan untuk diaplikasikan sesuai dunia nyata. Sumber
daya manusia sangat diperlukan untuk mendefinisikan, menganalisa,
mengoperasikan serta menyimpulkan masalah yang sedang dihadapi dalam
pembuatan SIG. Pemakai pada SIG terdiri dari beberapa tingkatan, dari
|
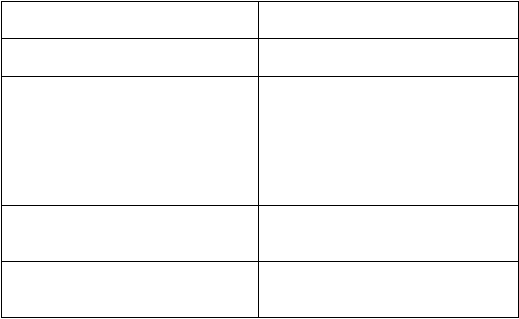 2
tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada
pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari.
2.2.4 Analisa Data Pada Sistem Informasi Geografis (SIG)
Ada berbagai macam jangkauan fungsi untuk analisa data yang tersedia dalam
kebanyakan paket SIG, termasuk didalamnya adalah teknik pengukuran
(measurement technique), query atribut (attribute query), analisa
kedekatan
(proximity analysis), operasi overlay (overlay operation), dan analisa
model
permukaan (surfaces) serta jaringan (networking).
Langkah awal untuk memahami analisa
data spasial dalam SIG adalah
mengetahui tentang terminologi yang digunakan. Mencari istilah standard menjadi
hal yang sulit sejak berbagai paket perangkat
lunak SIG sering kali menggunakan
kata yang berbeda-beda untuk menjelaskan suatu fungsi yang sama, dan individu
dengan latar belakang suatu bidang tertentu cenderung lebih senang menggunakan
istilah-istilah sendiri. Adapun terminolgi yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Terminologi SIG
Istilah
Definisi
Entitas
Titik, garis, area indifidual dalam
suatu database SIG.
Atribute
Data tentang entitas. Dalam SIG
vector dapat disimpan dalam
database, sedangkan dalam SIG raster
nilai suatu sel dalam grid raster
merupakan kode numeric yang
digunakan untuk mewakili ada
tidaknya suatu attribute.
Fitur
Suatu objek dalam dunia nyata yang
akan diterjemahkan dalam database
Sistem Informasi Geografi.
Layer Data
Suatu set data untuk kepentingan SIG.
Layer data dalam SIG biasanya
mengandung data dari satu tipe entitas
|
 2
saja.
Gambar
Layer data dalam SIG raster harus
diingat bahwa setiap sel dalam
gambar raster akan membawa suatu
nilai tunggal yang berfungsi sebagai
kunci attribute yang ada didalamnya.
Sel
Suatu titik atau pixel
tunggal dalam
gambar raster.
Fungsi atau Operasi
Prosedur analisis data yang dilakukan
oleh SIG.
Algoritma
Implementasi komputer sebagai
urutan aksi yang dirancang untuk
memecahkan suatu masalah.
2.2.5 Format Penyajian Data Peta
Bentuk penyajian data peta geografi dalam Sistem Informasi Geografi (SIG),
antara lain :
1.
Format Vector
Menurut Eddy Prahasta(2001, p158) dalam Hardi et al, (2010),
format vector
adalah format yang menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan
menggunakan titik, garis, poligon beserta atributenya. Bentuk-bentuk dasar
representasi data spasial dalam format vector didefinisikan oleh sistem kordinat dua
dimensi. Istilah-istilah dalam format vector adalah :
a.
Titik (Point)
Digunakan untuk mereprensentasikan fitur yang terlalau kecil untuk dapat
direpresentasikan sebagai area yang terdiri dari lokasi geografi dan rincian dari
fitur tersebut. Contoh : Lokasi gunung berapi, hotel, rumah sakit, restoran dan
sebagainya.
|
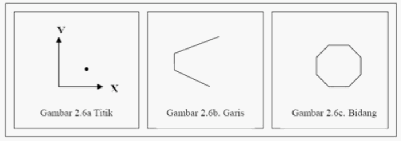 2
b.
Garis (line)
Garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Digunakan untuk merepresentasikan
batas wilayah sungai dan jalan.
c.
Bidang (area)
Merupakan bidang tertutup oleh garis, biasanya disajikan dalam bentuk poligon
digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah.
Gambar 2.4 Format Data Vektor
2.
Format Raster
Menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan
menggunakan struktur matrix
atau pixel
(Picture Element) yang membentuk grid.
Setiap pixel memiliki attributenya masing-masing termasuk kordinatnya yang unik.
Format ini sangat tergantung pada resolusi atau ukuran pixelnya dipermukaan bumi.
Menurut Eddy Prahasta(2001, p146) dalam Hardi et al, (2010), entitas spasial
raster disimpan dalam layer secara fungsionalitas direalisasikan dengan unsur-unsur
petanya. Contoh sumber entitas
spasial raster adalah citra satelit, citra radar dan
model ketinggian.
Kelebihan format raster yaitu dalam memperoleh data raster
lebih mudah dan
cepat serta memiliki struktur data
yang lebih sederhana. Kekurangannya adalah
memerlukan memori yang besar, transfer kordinat dan proyeksi serta representasi
hubungan topologi lebih sulit dilakukan.
|
|
2
2.2.6 Fungsi Analisis SIG
Hampir semua software SIG menyediakan fasilitas untuk membangun
model
yang rumit (komplek) dengan mengkombinasikan fungsi-fungsi analitis. Sistem
menyediakan berbagai fungsi pemodelan spasial yang rumit sampai fungsi yang
spesifik. Meskipun demikian, hampir semua sistem software SIG penyediakan
seperangkat fungsi analisis standar yang memungkinkan pengguna meng-akses data
secara logical. Aronoff membagi 4 kategori fungsi analisis SIG, yaitu:
1. Retrieval, Reclassification and Generalization
a.
Operasi retrieve data
Operasi retrieval dapat dilakukan pada data spasial dan data atribut. Seringkali
data di-retrieve secara selektif berdasarkan sebagian dari data atribut dan ditampilkan
secara spasial. Meliputi pencarian data, manipulasi data, dan keluaran data tanpa
merubah lokasi feature geografi atau membuat entiti baru
b.
Reklasifikasi (Reclasification)
Reklasifikasi
adalah mengklasifikasi kembali data spasial (atribut) menjadi
data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Misalnya dengan data
spasial ketinggian permukaan bumi (topografi), dapat diturunkan data spasial
kemiringan.
Reklasifikasi melibatkan pemilihan dan penyajian dari layer layer data yang
dipilih berdasarkan kelas-kelas atau nilai-nilai dari atribut tertentu, misalnya
reklasifikasi layer Tutupan Lahan, dimana area hutan dan area semak dikelaskan
menjadi area non budidaya (satu layer data dikelaskan berdasarkan kisaran nilai-nilai
atribut tertentu). Dengan demikian maka reklasifikasi adalah suatu teknik
mengeneralisir atribut. Tipe dari fungsi ini adalah dengan menggunakan teknik
pemolaan polygon seperti pengarsiran dan atau pewarnaan auntuk penyajian
|
|
2
spasialnya.
Pada SIG yang berbasis vektor, batas-batas antar polygon umumnya nilai-
nilai reklasifikasi dengan operasi penggabungan (dissolved) untuk membentuk suatu
peta yang kontinyu dan seragam. Pada reklasifikasi raster pada dasarnya melibatkan
penggabungan batas-batasnya. Penggabungan batas-batas peta yang didasarkan atas
suatu nilai atribut tertentu seringkali dilakukan untuk membuat satu layer data baru.
Hal ini sering dilakukan untuk kejelasan visual didalam pembuatan peta turunannya.
Hampir semua software SIG menyediakan kemampuan untuk secara mudah
penggabungan batas-batas berdasarkan hasil suatu reklasifikasi. Beberapa sistem
memungkinkan pengguna membuat satu layer data baru untuk reklasifikasi saat yang
lainnya melakukan penggabungan batas-batas selama output data.
Satu yang dapat dilihat bagaimana kemampuan query DBMS adalah suatu
kebutuhan didalam proses reklasifikasi. Kemampuan didalam memproses dan
menyajikan hasil reklasifikasi berupa sebuah peta atau laporan sangat tergantung
pada SIG. Pada beberapa software, proses query tidak tergantung dari fungsi
penyajian, sedangkan software lainnya terintegrasikan / terpadu dilakukan bersama
dalam mode grafis. Proses yang pasti untuk melakukan suatu reklasifikasi sangat
bermacam-macam dari satu SIG ke SIG lainnya. Beberapa akan menyimpan hasil
querynya didalam sekumpulan query yang terbebas dari DBMS sedangkan yang
lainnya menyimpan hasilnya pada suatu kolom atribut yang baru didalam DBMS.
Adanya berbagai macam perbedaan pendekatan sangat tergantung pada arsitektur
software SIGnya
|
|
2
2.
Topological Overlay
Kemampuan untuk melakukan tumpang tindih (overlay) dari beberapa layer
data secara vertical merupakan kebutuhan dan teknik yang umum dipakai dalam
pemrosesan data geografi. Pada kenyataannya, penggunaan struktur data topologi
dapat ditelusuri kembali terhadap keinginan untuk menumpang-tindihkan layer layer
data vektor. Dengan menggunakan konsep matematis overlay polygon topology
menjadi sangat popular dalam geoprocessing dan menjadi dasar dari setiap paket
software SIG.
Overlay topology didominasi oleh overlay data polygon dengan data polygon,
seperti tutupan hutan dan tanah. Walaupun demikian, kebutuhan overlay titik, garis
dan polygon diatas polygon sangat umum dijumpai. Untuk data vektor dan data
raster, pertimbangannya berbeda didalam overlay topology.
Dalam sistem yang berbasis raster, operasi tumpang-tindih (overlay)
dilakukan secara aritmatik, seperti penambahan (addition), penguranga (subtraction),
pembagian (division), perkalian (multiplication) dari layer-layer data. Pendekatan
satu peta atribut, khususnya pada model data raster, seringkali menjadikan
kemampuan overlay lebih fleksibel dan efisien. Model data raster memberikan
kemampuan pemodelan numerik (analisis kuantitatif) yang sangat baik. Pemodelan
spasial yang sangat baik adalah apabila dilakukan dengan menggunakan data raster.
Dalam sistem yang berbasis vektor, operasi tumpang-tindih topologi dilakukan
dengan membuat kerangka jaringan topologi (topological network) dari dua atau
lebih kerangka jaringan yang sudah ada. Hal ini diperlukan untuk membangun
kembali tabel-tabel topologi, seperti garis (arc), node, polygon, dan proses ini
membutuhkan waktu yang cukup lama serta kerja CPU yang cukup berat. Hasil dari
overlay topologi pada data vektor merupakan suatu kerangka jaringan topologi baru
|
|
2
yang berisi atribut-atribut yang berasal dari layer-layer data input aslinya. Dalam hal
ini pemilihan query dapat dilakukan pada layer asli, seperti tutupan hutan dan tanah,
untuk menentukan situasi tertentu yang terjadi, misalnya bagaimana tutupan hutan
apabila drainase buruk.
3. Buffering and Neighbourhood Functions
Ada berbagai fungsi dalam SIG yang memungkinkan entitas
spasial
mempengaruhi sekitarnya, ataupun sebaliknya dimana lingkungan sekitar
mempengaruhi karakteristik entitas.Fungsi neighbourhood
lainnya termasuk
penyaringan data (data filtering) yang melibatkan rekalkulasi sel dalam gambar
raster didasarkan pada karakteristik sekitarnya.
Jika suatu titik dijadikan buffer (bufffering) maka akan terbentuk area
lingkaran, buffering
pada garis atau area akan menghasilkan suatu area yang baru
(gambar). Buffering merupakan suatu konsep yang sederhana namun dengan operasi
perhitungan yang rumit dan juga beragam.
Metode daerah buffer sering dipergunakan dalam SIG vector. Sedangkan untuk
SIG raster
digunakan metode lainnya yaitu dengan memperhitungkan pendekatan
dan akana menghasilkan suatu layer data raster baru dimana atribut dari setiap sel
merupakan suatu pengukuran jarak. Operasi lainnya dalam SIG raster
dimana nilai
dari sel tunggal dirubah sebagai dasar pendekatan disebut fungsi tetangga
(Neighbourhood Function). Penyaringan (filtering) merupakan contoh yang
digunakan untuk memproses perbandingan terpisah (remotely sensed imagery).
Filterisasi akan mengubah suatu sel didasarkan pada attribute sel sekitarnya. Ukuran
dan bentuk penyaringan ditentukan operator. Umumnya untuk filter berapa kotak,
lingkaran dan bentuk tiga dimensi penyaringan menentukan banyaknya sel sekitar
yang digunakan dalam proses penyaringan.
|
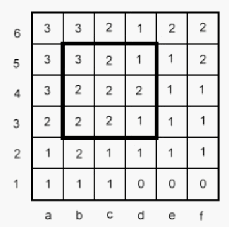 2
Filter akan disebarkan ke seluruh bagian data raster dan digunakan untuk
kalkulasi ulang nilai dari sel target yang ada dipusatnya. Nilai baru yang diberikan
pada sel target diperhitungkan dengan menggunakan berbagai algoritma, misalnya
nilai terbesar sel dan nlai yang sering muncul.
Gambar 2.5 Operasi Filter Raster GIS
2.3 Pemetaan
2.3.1 Pengertian Peta
Peta adalah sekumpulan titik, garis dan wilayah yang digunakan untuk
mendefinisikan lokasi dan tempat yang mengacu pada sistem
koordinat. Peta
biasanya direpresentasikan ke dalam dua dimensi, tetapi juga tidk menutup
kemungkinan untuk dapat direpresentasikan dalam bentuk tiga dimensi (Burrough,
1986, p13) dalam Hardi et al, (2010).
Peta Topografi adalah peta dengan tujuan utama adalah mengiindikasikan data
rekaan dari sebuah permukaan tanah. Peta ini biasanya menampilkan tanah lapang,
keadaan tanah, jaringan transportasi, batas administrasi dan
bentuk-bentuk buatan
yang lain (Heywood, 2002, p290) dalam Hardi et al, (2010).
Kemajuan dalam ruang teknologi yang berbasiskan komputer memperluas
|
|
2
wahana dan wawasan mengenai peta. Peta tidak hanya dikenali sebagai gambar pada
lembar kertas, tetapi juga sebagai penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, analisis
dan penyajiannya dalam bentuk digital terpadu antara gambar, citra dan teks. Data
yang terkelola dalam model digital memiliki keuntungan penyajian dan penggunaan
secara konvensional serta garis cetakan
(Hardcopy) dan keluwesan, kemudahan,
penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, analisis dan penyajian secara interaktif
bahkan realtime pada media computer (Softcopy).
2.3.2 Jenis peta
Peta dapat dijeniskan berdasarkan isi, skala, objek serta kegunaannya.
A. Peta Berdasarkan Isi:
Peta umum melukiskan semua kenampakan suatu wilayah
secara umum.
Kenampakan adalah keadaan alam atau daerah dalam berbagai bentuk permukaan
bumi, yaitu gunung, daratan, lembah, sungai dan sebagainya yang merupakan satu
kesatuan. Contoh : Peta Indonesia, Peta Eropa, Peta Dunia.
Peta Umum terbagi dalam dua jenis (http://e-dukasi.net), yaitu :
1.
Peta Topografi : Peta topografi adalah peta yang menampilkan, semua unsur
yang berada di atas permukaan bumi, baik unsur alam maupun buatan manusia,
sehingga disebut juga peta umum. Unsur alam antara lain meliputi: relief muka
bumi, unsur hidrografi (sungai, danau, bentuk garis pantai), tanaman,
permukaan es, salju, dan pasir
(Prihandito 1989: 23; Hascaryo dan Sonjaya
2000: 10).
|
|
3
2.
Peta Chorografi : Peta yang menggambarkan keseluruh atau sebagian
permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil antara 1:250.000 – 1:1.000.000
atau lebih. Peta ini menggambarkan daerah yang luas, menampilkan semua
kenampakan yang ada pada suatu wilayah. Atlas merupakan kumpulan dari
peta Chorografi.
3.
Peta Tematik
(Peta khusus) : Melukiskan kenampakan tertentu atau
menonjolkan satu macam data pada wilayah yang dipetakan. Contoh : Peta
Iklim dan Peta Perhubungan.
4.
Peta Kadaster : Peta Kadaster merupakan peta berskala ekstra besar,
sebagai sumber data dan informasi dasar yang berguna dalam berbagai
kepentingan.
B. Peta Berdasarkan Skala :
1.
Peta Kadaster(Peta Teknik) : Skala peta antara 1:100 – 1:5.000.
2.
Peta skala besar : Skala peta antara 1:5.000 – 1:250.000.
3.
Peta skala sedang : Skala peta antara 1:250.000 – 1:500.000.
4.
Peta skala kecil(Peta Geografi) : Skala peta antara 1:500.000 –
1:1.000.000 atau lebih besar.
C. Peta Berdasarkan Objek:
1.
Peta Stationer : Menggambarkan keadaan atau objek yang dipetakan
dalam keadaan tetap atau stabil. Contoh : Peta persebaran gunung berapi.
2.
Peta Dinamik : Menggambarkan bahwa keadaan atau objek yang
dipetakan mudah berubah. Contoh : Peta Urbanisasi dan peta arah angin.
|
|
3
D. Peta berdasarkan kegunaannya(The World Book Encyclopedia, 2006, p177):
1.
General Reference Map(Peta referensi umum)
Merupakan peta yang digunakan untuk mengidentifikasi dan
memverifikasi berbagai macam bentuk geografi, termasuk fitur tanah,
badan air, perkotaan, jalan dan lain sebagainya.
2.
Mobility Map(Peta Mobilitas)
Merupakan peta yang bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam
menentukan jalur dari satu tempat ke tempat lainnya. Peta ini biasa
digunakan untuk perjalanan di darat, laut dan udara.
3.
Thematic Map(Peta Tematik)
Merupakan peta yang menunjukkan penyebaran dari objek tertentu,
seperti populasi, curah hujan dan sumber daya alam.
4.
Inventory Map(Peta Inventaris)
Merupakan peta yang menunjukkan lokasi dari fitur khusus, misalnya :
posisi semua gedung di wilayah Jakarta Timur.
2.3.3 Skala Peta
Skala Peta merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya
yang dinyatakan dengan angka atau garis atau gabungan keduanya(Badan
Standarisasi Nasional).
Skala dapat digambarkan dalam salah satu dari tiga cara, yaitu sebagai skala
angka, skala verbal(Nominal), atau skala grafis (Heywood, 2002, p23).
|
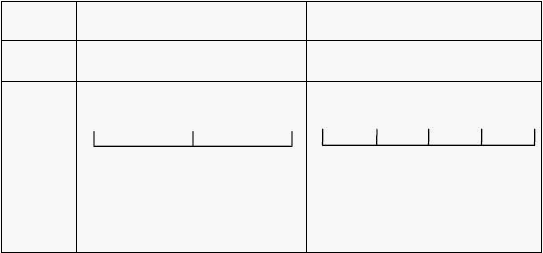 3
Tabel 2.2 Penggambaran Skala.
Angka
1 : 5000
1 : 1 000 000
Verbal
1 cm merepresentasikan 50 m
1 cm merepresentasikan 10 km
Grafis
0
100 200
Km
0
10 20 30 40
Km
Peta Topografi yang standar mengandung contoh dari skala verbal, rasio dan grafis.
Harus diingat bahwa peta skala kecil
(Contohnya 1:250.000 atau 1:1.000.000)
adalah peta yang mencakup area luas. Sedangkan peta skala besar (Contohnya 1:
10.000 atau 1:25.000) mencakup area kecil dan banyak rincian. Skala juga penting
saat entitas
spasial digunakan (Titik, garis dan area) untuk mempresentasikan versi
umum dua dimensi dari fitur dunia nyata (Heywood, 2002, p24).
2.3.4 Komponen Peta
Komponen peta terdiri dari :
1.
Isi Peta
Isi peta menunjukkan makna ide penyusun peta yang akan disampaikan
kepada pengguna peta. Kalau ide yang disampaikan mengenai perbedaan
curah hujan, isi peta tentunya berupa isohyet.
2.
Judul Peta
Judul peta harus mencerminkan isi peta berupa isohyet, tentu judul
petanya menjadi “Peta Distribusi Curah Hujan”.
|
|
3
3.
Skala Peta dan Simbol Arah
Skala peta sangat penting dicantumkan untuk melihat tingakat ketelitian
dan kedetailan objek yang dipetakan. Sebuah belokan sungai akan
tergambar jelas pada peta dengan skala 1 : 10.000 dibandingkan dengan
peta berskala 1 : 50.000. Kemudian bentuk-bentuk pemukiman akan
terlihat lebih rinci dan detail pada peta berskala 1: 10.000 dibandingkan
dengan peta berskala 1 : 50.000. Simbol arah dicantumkan dengan tujuan
untuk orientasi peta. Arah utara lazim nya mengarah pada bagian atas
peta. Kemudian berbagai tata letak tulisan mengikuti arah tadi, sehingga
peta menjadi nyaman untuk dibaca. Lebih jauh, arah juga penting
sehingga pemakai
peta dapat dengan mudah menyamakan objek dipeta
dengan objek sebenarnya di lapangan.
4.
Legenda atau Keterangan Peta
Agar pembaca peta dapat dengan mudah memahami isi peta, seluruh
bagian dalam isi peta harus dijelaskan dalam legenda atau keterangan.
5.
Inzet dan Index Peta
Peta yang dibaca harus diketahui dari bagian bumi sebelah mana area
yang dipetakan tersebut. Inzet peta merupakan peta yang diperbesar dari
bagian belahan bumi. Sebagai contoh pada saat pembuat peta ingin
memetakan Pulau Jawa, Pulau Jawa merupakan bagian dari Kepulauan
Indonesia yang di Inzet. Sedangkan index peta merupakan sistem
tata
letak peta, dimana menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap
peta yang lain di sekitarnya.
|
|
3
6.
Grid
Dalam selembar peta sering terlihat dibubuhi semacam jaringan kotak-
kotak atau grid sistem.
Tujuan pembuatan grid adalah untuk memudahkan penunjukan lembar
peta dari sekian banyak lembar peta dan untuk memudahkan
penunjukkan letak sebuah titik diatas lembar peta.
Cara pembuatan grid yaitu adalah untuk membagi-bagi wilayah dunia
yang luas ke dalam beberapa kotak. Tiap kotak diberi kode. Tiap kotak
dengan kode tersebut kemudian diperinci dengan kode yang lebih
terperinci lagi dan begitu juga dengan kode seterusnya.
Salah satu jenis grid pada peta-peta dasar (peta topografi) di Indonesia
antara lain :
Kilometering
(kilometer fiktif) yaitu lembar peta dibubuhi jaringan
kotak-kotak dengan satuan kilometer. Disamping itu ada juga grid yang
dibuat oleh Tentara Ingggris dan grid yang dibuat oleh Amerika
(American Mapping Sistem). Untuk menyeragamkan sistem
grid,
Amerika Serikat sedang berusaha membuat sistem
grid yang seragam
dengan sistem UTM Grid Sistem dan UPS Grid Sistem.
7.
Nomor Peta
Penomoran peta penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan
seluruh lembar peta terangkai dalam satu bagian muka bumi.
8.
Sumber / Keterangan Riwayat Peta
Sumber ditekankan pada pemberian identitas peta, meliputi penyusun
peta, percetakan, sistem proyeksi peta, penyimpangan deklinasi magnetis,
tanggal / tahun pengambilan data dan tanggal pembuatan / pencetakan
|
|
3
peta dan lain sebagainya yang memeperkuat identitas penyusunan peta
yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.4 Basis Data (Database)
2.4.1 Pengertian Basis Data
Basis data adalah penggabungan dari sekumpulan unsur data yang berhubungan
secara
logika. Basis data menggabungkan catatan lama yang disimpan dalam arsip
terpisah ke dalam unsur data yang biasa menyediakan data untuk
banyak aplikasi
(O’Brien, 2003 p145).
Basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling
berhubungan
secara logika dan saling berbgi serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Basis
data merupakan sebuah penyimpanan data yang besar yang dapat digunakan oleh
pemakai dan departemen secara simultan (Connolly, 2002, p14-p15).
2.4.2 Pengertian Table
Table
adalah suatu relasi data yang digambarkan dalam kolom dan baris
(Connolly, 2002, p72).
2.4.3 Pengertian Field
Field
dalam konteks database biasanya sering disebut dengan atribut. Field
merupakan nama kolom dari sebuah tabel atau relasi (Connolly, 2002, p72).
2.4.4 Pengertian Record
Record
adalah suatu baris data atau informasi dalam sebuah tabel. Record
sering juga disebut dengan tuple (Connolly, 2002, p73).
2.4.5 Pengertian Primary Key
Primary key adalah sebuah atribut atau himpunan atribut yang dipilih untuk
mengindentifikasikan tuple-tuple
atau record dalam tabel yang bersifat unik. Unik
|
|
3
memiliki arti tidak boleh ada duplikat atau key yang untuk dua atau lebih tuple atau
record dalam sebuah table (Connolly, 2002, p79).
2.4.6 Pengertian Foreign Key
Foreign Key adalah sebuah atribut atau himpunan atribut dalam suatu tabel
yang menunjuk pada key yang terdapat pada tabel lain. Foreign Key berfungsi untuk
menunjukan hubungan antar satu tabel dengan tabel yang lainnya
(Connolly, 2002,
p79).
2.4.7 Queries
Melakukan query dalam database SIG untuk menampilkan data adalah bagian
dasar dan penting dalam proyek SIG. Query
menawarkan metode untuk
mendapatkan data, dapat dilakukan pada data yang menjadi bagian database SIG
ataupun pada data prosedur baru hasil dari hasil analisis data. Query berguna pada
setiap tahapan analisis SIG untuk memeriksa kualitas dan pengukuran SIG raster.
Secara umum ada dua tipe query yang dapat dilakukan SIG, yaitu spasial dan
non-spasial. Query
non-spasial merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan attribute suatu fiture. Merupakan suatu query
non-spasial karena baik
pertanyaan ataupun jawabannya tidak melibatkan komponen analisa dari komponen
spasial data. Query
ini dapat dilakukan oleh komponen perangkat lunak database
sendiri.
Metode menspesifikasi query pada SIG dapat menjadi suatu hal yang sangat
interaktif. Pengguna dapat memberikan pertanyaan pada peta lewat layar komputer
atau menjelajah database lewat serangkaian pertanyaan didalam query. Query dapat
menjadi kompleks dengan kombinasi pertanyaan mengenai area, keliling ataupun
jarak terutama dalam SIG vector dimana data disimpan sebagai atribut dalam
database.
|
|
3
Query
tunggal dapat dikombinasikan untuk mengindetifikasi entitas dalam
database yang bisa memenuhi kebutuhan dua atau lebih criteria spasial ataupun non-
spasial. Operator Boolean seperti and, or, not, xor, juga bisa digunakan.
2.4.8 Entitas Relationship Diagram (ERD)
Entitas
Relationship Diagram (ERD) adalah pendekatan top-down
untuk
mendesain basis data yang dimulai dengan mengidentifikasikan data yang penting,
yang disebut sebagai entitas dan hubungan antara data harus digambarkan (Connolly,
2002, p330).
Batasan utama dalam relasi disebut multiplicity. Multiplicity adalah jumlah
kejadian
yang mungkin muncul dari entitas satu ke entitas lainnya yang mempunyai
hubungan khusus.
Hubungan yang paling umum adalah berpasangan (Connolly, 2002, p344-
p348) seperti :
1.
one-to-one(1:1)
Sebuah entitas di A hanya dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di
B.
2.
one-to-many (1:*)
Sebuah entitas di A dapat diasosiasikan dengan satu atau lebih entitas di B, namun
entitas di B hanya dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A.
3.
many-to-many (*:*)
Sebuah entitas di A dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih entitas di B dan
sebuah entitas di B dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih entitas di A.
|
|
3
2.4.9 Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu gambaran garis dari suatu sistem
yang menggunakan sejumlah bentuk simbol untuk menggambarkan aliran data
melalui suatu proses yang saling berkaitan. Simbol menggambarkan hubungan antar
elemen prose’s, aliran data dan penyimpanan data (McLeod, 2004, p171).
Proses adalah sesuatu yang mengubah masukan menjadi keluaran. Aliran data
mengandung sekelompok elemen data yang saling berhubungan secara logika.
Penyimpanan data bertugas mengambil data atau meng-update (O’Brien, 2007,
p115).
Dengan pemakain DFD, pengguna dapat memahami aliran data dalam sebuah sistem.
Ada tiga keuntungan pemakaian DFD:
1.
Terhindar dari satu usaha untuk mengimplementasikan sistem yang
terlalu dini.Pengguna perlu memikirkan secara cermat aliran-aliran data
sebelum memakai keputusan untuk merealisasikannya secara teknis.
2.
Dapat mengerti lebih dalam hubungan
sistem dengan subsistemnya.
Pengguna dapat membedakan sistem dari lingkungan beserta batasan-
batasannya.
3.
Dapat menginformasikan sistem yang berlaku kepada dunia. DFD dapat
digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bentuk
representasi simbol-simbol yang digunakan.
Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD adalah sebagai berikut :
1.
Entitas Eksternal
Entitas eksternal adalah entitas yang berada di luar sistem yang memberi data ke
sistem atau menerima keluaran dari sistem dan tidak termasuk dalam bagian sistem.
Entitas ini digambarkan dengan symbol
|
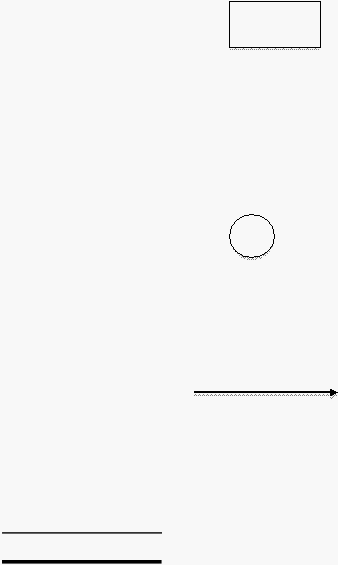    3
2.
Proses
Menggambarkan apa yang dilakukan sistem. Berfungsi mentransformasikan satu atau
beberapa data input menjadi satu atau beberapa output sesuai dengan spesifikasi yang
diinginkan. Dalam penamaan suatu proses digunakan kata kerja dan kata benda.
Digambarkan dengan simbol
3.
Aliran Data
Menggambarkan aliran data dari suatu entitas ke entitas lain. Simbol anak panah
menggambarkan arah aliran data. Digambarkan dengan simbol
Penyimpanan Data(Storage)
Merupakan data untuk menyimpan data. Proses dapat mengambil data dari atau
memberikan data ke data store. Digambarkan dengan
Tingkatan dalam DFD ada tiga, yaitu :
1.
Diagram Konteks
a.
Merupakan level tertinggi yang menggambarkan masukan dan keluaran
sistem
b.
Terdiri dari suatu prose’s yang tidak memiliki data store.
2.
Diagram Nol
a.
Memiliki data store.
b.
Diagram tidak rinci, diberikan tanda bintang pada akhir nomor.
|
|
4
3.
Diagram Rinci
a.
Merupakan rincian dari diagram nol atau diagram level di atasnya.
b.
Proses yang ada sebaiknya tidak lebih dari tujuh titik.
2.5 ArcGIS
ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI
(Environment Science & Research Institute) yang merupakan kompilasi fungsi-
fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server,
engine dan mobile. Software ini mulai dirilis oleh ESRI pada tahun 2000. Produk
utama dari ArcGIS adalah ArcGIS desktop, dimana arcGIS desktop merupakan
software GIS professional yang komprehensif dan dikelompokkan atas tiga
komponen yaitu
: ArcView (komponen yang focus ke penggunaan data yang
komprehensif, pemetaan dan analisis), ArcEditor (lebih fokus ke arah editing data
spasial) dan ArcInfo (lebih lengkap dalam menyajikan fungsi-fungsi GIS termasuk
untuk keperluan analisis geoprosesing).
1) ArcGIS Desktop
ArcGIS desktop sendiri terdiri atas 5 aplikasi dasar yakni:
a.
ArcMap
ArcMap merupakan aplikasi
utama yang digunakan dalam ArcGIS yang
digunakan untuk mengolah (membuat (create), menampilkan (viewing), memilih
(query), editing, composing dan publishing) peta.
b.
ArcCatalog
ArcCatalog adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengatur/ mengorganisasi
berbagai macam data spasial yang digunakan dalam pekerjaan SIG. Fungsi ini
|
|
4
meliputi tool untuk menjelajah (browsing)
, mengatur (organizing), membagi
(distribution) dan menyimpan (documentation) data – data SIG.
c.
ArcToolbox
Terdiri dari kumpulan aplikasi yang berfungsi sebagai tools/perangkat dalam
melakukan berbagai macam analisis keruangan.
d.
ArcGlobe
Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkanpeta-peta secara 3D ke dalam bola
dunia dan dapat dihubungkan langsung dengan internet.
e.
ArcScene
ArcScene merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan
menampilkan peta-peta kedalam bentuk 3D.
2.6 Teori Khusus
2.6.1 Pengertian Pemadam
Pengertian dari pemadam yaitu alat untuk memadamkan api dan
sebagainya.
2.6.2 Pengertian Kebakaran
Kebakaran adalah suatu nyala api,baik kecil atau besar pada tempat yang
tidak kita kehendaki,merugikan pada umumnya sukar dikendalikan (Perda
DKI,1992)
Kebakaran merupakan bencana yang paling sering dihadapi dan bisa
digolongkan sebagai bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia.
Bahaya kebakaran dapat terjadi setiap saat ,karena banyak peluang yang dapat
memicu terjadinya kebakaran.
|
|
4
Definisi kebakaran menurut Depnaker : “ Suatu reaksi oksidasi
eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai
dengan timbulnya api atau penyalaan.”
Definisi kebakaran menurut pengertian
Asuransi secara umum :” Sesuatu yang benar-benar terbakar yang seharusnya tidak
terbakar dan dibuktikan dengan adanya nyala api secara nyata,terjadi secara tidak
sengaja, tiba-tiba serta menimbulkan kecelakaan atau kerugian.”
2.6.3 Pengertian Pemadam Kebakaran
Pemadam kebakaran atau branwir adalah petugas atau dinas yang dilatih
dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Dinas pemadam kebakaran adalah
unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-
tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat.
Biasanya para pemadam kebakaran memakai baju anti api agar tidak mudah tebakar
dan juga mereka memakai bagian baju yang mengkilat agar mudah terlihat.
2.6.4 Klasifikasi Kebakaran
Yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau
pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda / bahan yang terbakar.
Dengan adanya klasifikasi kebakaran tersebut diharapkan akan lebih mudah atau
lebih cepat dan lebih tepat mengadakan pemillihan media pemadaman yang akan
dipergunakan untuk melaksanakan pemadaman (Perda DKI,1992).
Menurut Perda DKI (1992) klasifikasi kebakaran sesuai dengan bahan
bakar yang terbakar dan bahan pemadaman untuk masing-masing kelas yaitu:
|
|
4
a.
Kelas A
Termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah
terbakar biasa, misalnya: kertas,kayu,maupun plastic. Cara mengatasinya
yaitu bisa dengan menggunakan air untuk menurunkan suhunya sampai
dibawah titik penyulutan, serbuk kering untuk mematikan proses pembakaran
atau menggunakan halogen untuk memutuskan reaksi berantai kebakaran.
b.
Kelas B
Kebakaran pada kelas ini adalah yang melibatkan bahan seperti cairan
combustible
dengan cairan flammable, seperti bensin, minyak tanah, dan
bahan serupa lainnya. Cara mengatasinya dengan bahan foam.
c.
Kelas C
Kebakaran yang disebabkan oleh listrik yang bertegangan untuk
mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadaman kebakaran non
kondusif agar terhindar dari sengatan listrik.
d.
Kelas D
Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium,
alumunium, magnesium, dan kalium. Cara mengatasinya yaitu powder
khusus kelas ini.
2.6.5 Kerugian Akibat Kebakaran
Kerugian akibat kebakaran menurut Depnaker ILO,(1980) meliputi:
a)
Asap
b)
Gas beracun
c)
Kekurangan oksigen
d)
Panas
e)
Terbakar
|
|
4
Menurut Depnaker UNDP ILO,(1987) menyebutkan kerugian akibat
kebakaran dan segala akibat yang ditimbulkan disebabkan adanya
ketimpangan sebagai berikut:
a)
Tidak adanya sarana deteksi / alarm
b)
Sistim deteksi / alarm tidak berfungsi
c)
Alat pemadam Api tidak sesuai / tidak memadai
d)
Alat pemadam Api tidak berfungsi
e)
Sarana evakuasi tidak bersedia
f)
Dan banyak faktor lain seperti manajemen K3, program inpeksi, dan
pemeliharaan
2.6.6 Penyebab Kebakaran
Berikut ini penyebab terjadinya kebakaran yaitu :
a.
Bahan yang mudah terbakar. Barang padat, cair atau gas
(kayu,kertas,textile,bensin,minyak,acetelin dll)
b.
Panas (suhu) –
pada lingkungannya memiliki suhu yang demikian
tingginya,(sumber panas dari Sinar Matahari,Listrik (kortslutinng,panas
energimekanik (gesekan),Reaksi Kimia,Kompresi Udara)
c.
Oksigen (O2) adanya zat asam (O2) yang cukup. Kandungan (kadar) O2
ditentukan dengan presentasi (%),makin besar kadar oksigen maka api akan
menyala makin hebat, sedangkan pada kadar oksigen kurang dari 12 % tidak
akan terjadi pembakaran api. Dalam keadaan normal kadar oksigen diudara
bebas berkisar 21%, maka udara memiliki keaktifan pembakaran yang cukup
|
|
4
Dari ketiga faktor tersebut saling mengikat dengan kondisi yang cukup
tersedia. Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam bentuk hubungan segitiga
kebakaran sebagai berikut :
Perlu diperhatikan apabila salah satu dari sisi dari sisi segitiga teersebut diatas tidak
ada, maka tidak mungkin terjadi kebakaran. Jadi,setiap kebakaran yang terjadi dapat
dipadamkan dengan tiga cara yaitu :
1.
Dengan menurunkan suhunnya dibawah suhu kebakaran
2.
Menghilangkan zat asam
3.
Menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar
2.6.7 Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Dalam upaya prosedur tanggap darurat secara garis besar meliputi
rencana / rencana dalam menghadapi keadaan darurat, pendidikan dan latihan
penanggulangan keadaan darurat serta proses evakuasi atau pemindahan dan
penutupan (Jusuf,1999).
Pencegahan kebakaran dan penangulangan korban kebakaran tergantung
lima (5) prinsip pokok(Suma’mur,1996) sebagai berikut:
1)
Pencegahan kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atas keadaan
panic
2)
Pembuatan bangunan tahan api
3)
Pengawasan yang teratur dan berkala
4)
Penemuan kebakaran pada tingkat awal dan pemadamannya
5)
Pengendalian kerusakan untuk membatasi kerusakan sebagai
akibat kebakaran
|
|
4
Sedangkan menurut suprapto,(1995) ketentuan dan persyaratan teknis
dalam proteksi kebakaran pada bangunan meliputi:
1)
Melakukan pemeriksaan dan pengecekan kondisi dan keandalan
sarana dan peralatan sistem proteksi kebakaran
2)
Melengkapi sarana dan peralatan proteksi didasari atas analisis
risiko bahaya dan standar serta ketentuan yang berlaku
3)
Standar dan ketentuan teknis proteksi kebakaran harus diterapkan
dan disebarluaskan
4)
Setiap gedung harus dilengkapi dengan sarana pengamanan
terhadap kebakaran secara lengkap dan memenuhi standard dan
ketentuan teknis yang berlaku
5)
Perlu dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala
untuk menjamin agar sarana dan peralatan proteksi kebakaran
dalam kondisi siap pakai
2.6.8 Fasilitas Penanganan Kebakaran
Sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan
mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun
manual,digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam
melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistim itu digunakan dalam
melaksanakan penanggulangan awal kebakaran (Perda DKI Jakarta, 2008). Sarana
yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa
dari kebakaran dan bencana lain(Perda DKI Jakarta,2008).
Sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kep Men PU No.
10/KPTS/2000), setiap bangunan gedung harus melaksanakan pengaturan
|
|
4
pengamanan terhadap bahaya kebakaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan
pembangunan sampai tahap pemanfaatan sehingga bangunan gedung senantiasa
aman dan berkualitas sesuai dengan fungsinya. Salah satu dari pelaksanaan
pengamanan ini adalah melengkapi gedung dengan sarana proteksi aktif kebakaran,
yang terdiri dari:
1)
Sarana pendeteksi dan peringatan kebakaran
1.1 Detektor dan alarm Kebakaran
Berdasarkan SNI 03-3985-2000 Alarm kebakaran adalah
komponen dari sistem yang memberikan isyarat/tanda setelah kebakaran terdeteksi.
Komponen dari sistem deteksi dan alarm kebakaran yang
berfungsi untuk mengontrol bekerjanya sistem, menerima dan menunjukkan adanya
isyarat kebakaran, mengaktifkan alarm kebakaran, melanjutkan ke fasilitas lain
terkait, dan lain-lain. Panel kontrol dapat terdiri dari satu panel saja, dapat pula
terdiri dari beberapa panel kontrol.
Titik panggil manual adalah alat yang dioperasikan secara
manual guna memberi isyarat adanya kebakaran. Untuk kepentingan standar ini,
detektor kebakaran otomatik diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya seperti tersebut
di bawah ini:
a.
Detektor panas yaitu alat yang mendeteksi temperatur tinggi atau laju
kenaikan temperatur yang tidak normal
b.
Detektor asap yaitu alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau yang
tidak terlihat dari suatu pembakaran
c.
Detektor nyala api yaitu alat yang mendeteksi sinar infra merah, ultra
violet,atau radiasi yang terlihat yang ditimbulkan oleh suatu kebakaran
|
|
4
d.
Detektor gas kebakaran yaitu alat untuk mendeteksi gas-gas yang
terbentuk oleh suatu kebakaran
e.
Detektor kebakaran lainnya yaitu alat yang mendeteksi suatu gejala
selain panas,asap, nyala api,atau gas yang ditimbulkan oleh kebakaran
2)
Sarana pemadam kebakaran
2.1 Hidran Kebakaran
Instalasi Hidran kebakaran adalah suatu sistim pemadam kebakaran tetap
yang menggunakan media pemadam air bertekanan yang dialirkan melalui pipa –
pipa dan selang kebakaran. Sistim ini terdiri dari persediaan air,pompa perpipaan,
kopling outlet dan inlet serta selang dan nozzle (SNI 225-1987).
Sedangkan berdasarkan jenis dan penempatannya hidran menurut SNI
225-1987 terdiri dari:
1)
Hidran gedung
Hidran gedung terdiri dari dua persyaratan yaitu:
a)
Persyaratan teknis
1.
Diameter selang maksimal 1,5 inci
2.
Minimal debit air 380 liter/menit
3.
Tekanan air maksimal 4,5 kg/cm 2
4.
Diameter pipa (kopling) 2,5 inci
b)
Persyaratan umum
1.
Letak kotak hidran dalam gedung mudah dilihat
2.
Letak kotak hidran dalam gedung mudah dicapai, tidak
terhalang
3.
Kotak hidran mudah dibuka
|
|
4
4.
Panjang selang maksimal 30 m
5.
Selang dalam kondisi baik (tidak membelit bila di
tarik)
6.
Pipa pemancar (nozzel) terpasang pada selang
7.
Pipa hidran bercat merah
8.
Kotak hidran bercat merah
9.
Kotak hidran diberi tulisan “hydrant”berwarna putih
2)
Hidran halaman
a)
Persyaratan teknis
1.
Debit air hidran 950 liter/menit
2.
Tekanan maksimal 7kg/cm²
dan tekanan minimum 4,5
kg/cm²
3.
Diameter selang 2,5 inci
b)
Persyaratan umum
1.
Pilar hidran di pasang pada ketinggian 50 cm dari
pemukaan tangga
2.
Jarak pilar hidran dari pagar 1 m
3.
Hidran halaman mudah terlihat, mudah dicapai, tidak
terhalang oleh benda-benda lain
4.
Pilar hidran harus dicat merah
5.
Selang hidran dalam keadaan baik
3)
APAR
Berdasarkan Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No:PER.04/MEN/1980, Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah
dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
|
|
5
Kebakaran dapat digolongkan:
1.
Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A);
2.
Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan
B);
3.
Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Golongan C);
4.
Kebakaran logam (Golongan D).
Jenis alat pemadam api ringan terdiri:
a.
Jenis cairan(air);
b.
Jenis busa;
c.
Jenis tepung kering;
d.
Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya)
4)
Alat pemercik air otomatis (Springkler)
Sprinkler
adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang
mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air
dapat memancar kesemua arah secara merata(Kep Men PU No.10/KPTS/2000).
2.6.9 Sarana Penyelamatan Jiwa
Pada
saat kebakaran, sarana penyelamatan jiwa merupakan hal yang
penting dilakukan, mengingat jiwa manusia tidak bisa dinilai dengan harta ataupun
yang lainnya. Upaya penyelamatam jiwa merupakan upaya untuk membimbing
orang menuju jalan keluar, mengarah jauh dari daerah bahaya dan mencegah agar
|
|
5
tidak terjadi panik. Rute penyelamatan terdiri dari tiga tipe yang dapat digunakan
untuk melarikan diri dari bahaya kebakaran,yaitu:
1.
Langsung menuju tempat terbuka
2.
Melalui koridor atau gang
3.
Melalui terowongan atau tangga kedap asap/api
A.
Rumah Sakit
Rumah Sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat
menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan
personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik
untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Rumah sakit sebagai salah
satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan, merupakan bagian dari sumber daya
kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya
kesehatan.
Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian
integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan
pelayanan paripurna(komprehensif), penyembuhan penyakit(kuratif) dan pencegahan
penyakit(preventif) kepada masyarakat.
B.
Kantor Polisi
Kantor polisi adalah kantor tempat mengerjakan urusan kepolisian.
|