|
3
BAB 2
DATA DAN ANALISA
2.1. Metode Penelitian
Dalam proses pembuatan laporan ini, diperlukan beberapa metode penelitian,
yaitu:
1. Kajian pustaka
2. Survey Lapangan
3. Wawancara atau focus group discussion.
4. Penyebaran kuisioner atau angket.
2.1.1. Refrensi Buku “Peranakan Tionghoa di Nusantara”
Buku ini menyajikan kumpulan tulisan jurnalistik wartawan senior Iwan
Santosa mengenai Peranakan Tionghoa yang berada dari Barat hingga
Timur Indonesia, buku ini diterbitkan tahun 2012 oleh Kompas Penerbit
Buku.
Dalam buku ini penulis mendapatkan catatan jurnal Pecinan Jakarta
yaitu Glodok, seputar perjalanan masa lalu, hingga masa saat ini secara
garis besar. Penulis mendapatkan banyak informasi kebudayaan seputar
Kampung Cina Glodok dari masa ke masa.
2.1.2. Refrensi Buku “Peranakan Tionghoa: Sebuah Perjalanan Budaya”
Buku oleh Lily Wibisono yang diterbitkan oleh Intisari Mediatama
tahun 2006 menjabarkan secara lengkap kebudayaan – kebudayaan yang
dihasilkan oleh kaum Peranakan Tionghoa di Indonesia.
Penulis memperoleh banyak sekali informasi kebudayaan Peranakan
Tionghoa di Indonesia mulai dari arsitektur bangunan, interior, literatur,
kuliner, perabotan dan ragam pakaian peranakan yang dapat menjadi
dasar informasi penjelajahan budaya Peranakan Tionghoa di Glodok.
2.1.3. Refrensi Buku “Tempat – Tempat Bersejarah di Jakarta”
Buku oleh Adolf Heuken SJ yang diterbitkan tahun 1997 oleh Cipta
Loka Caraka berisikan kumpulan bukti peta dan foto-
foto tempat
bersejarah di Jakarta di mulai pada masa perdagangan VOC di Batavia.
Melalui buku ini penulis mendapatkan informasi tempat dan bangunan
Tionghoa di kawasan Pemukiman Cina di Glodok pada masa kolonial
|
|
4
Belanda berikut dengan foto tua tempatnya dan kisah sejarah yang ada
di dalamnya, yaitu Klenteng Jin De Yuan.
2.1.4. Refrensi Buku “Batavia In Nineteeth Century Photograph”
Buku oleh Scott Merrillees yang diterbitkan tahun 2001 oleh
Archipelago Press berisikan kumpulan foto kota Batavia pada abad ke
19.
Penulis memperoleh foto lama kawasan Glodok dan sekitarnya pada
abad ke 19, di sertai dengan deskripsi informasi pada setiap lokasi,
mulai dari gedung bekas Kedutaan RRC, Klenteng Jin De Yuan,
landscape Toko Tiga dan Pancoran.
2.1.5. Refrensi Buku “Batavia: Masyarakat kolonial abad XVII”
Buku oleh Henderik
E Niemeijer, yang diterbitkan tahun 2012 oleh
Masup Jakarta, menceritakan lengkap sejarah dan kehidupan masyarakat
di Batavia di masa kolonial Belanda pada abad 17 secara menyeluruh
dan berurutan sesuai tahun peristiwa.
Dari buku ini penulis memperoleh sejarah terbentuknya kawasan
Glodok secara runut, apa yang melatarbelakangi peristiwa 1740, penulis
juga memperoleh gambaran kehidupan masyarakat Tionghoa pada abad
17, bahwa saat itu sebagian dari masyarakat Tionghoa masih
mempertahankan gaya rambut taucang.
2.1.6 Refrensi Buku “Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740”
Buku oleh Johannes Theodorus Vermeulen, yang diterbitkan oleh
Komunitas Bambu sesuai judulnya spesifik menceritakan kehidupan
etnis Tionghoa di Batavia dan latar belakang yang menenggarai huru
hara pembantaian kaum Tionghoa di tahun 1740.
2.1.7. Refrensi Buku “Hari – Hari Raya Tionghoa”
Buku oleh Marcus A.S. berisikan secara khusus kebudayaan hari raya
Tionghoa secara lengkap dengan asal – usul hari raya terjadi.
Dalam buku ini penulis mendapatkan kejelasan kedatangan etnis
Tionghoa ke Indonesia, dan informasi hari raya yang dilakukuan
penduduk Tionghoa secara umum.
2.1.8. Refrensi Laporan Tugas Akhir “Perancangan Publikasi Buku
Pecinan
Semarang: Sepenggal Kisah, Sebuah Perjalanan”
Laporan Tugas Akhir mahasiswi Desain Komunikasi Visual Ananda
|
|
5
Astrid Adriane pada tahun 2012 membahas topik Pecinan Semarang
sebagai tujuan wisata budaya, penulis memperoleh refrensi kajian
pustaka yang digunakan untuk memperoleh informasi seputar Pecinan
dan Peranakan Tionghoa Indonesia.
2.1.9 Literatur Internet
Beberapa refrensi literatur yang di ambil dari internet antara lain:
Blog ini merupakan kumpulan dari kliping serta materi-materi
menarik yang penulisnya, Utamin Irfan kumpulkan dari hasil
pencarian asal-usul dari berbagai hal mengenai budaya masyarakat
Tionghoa. Blog ini juga berisi tentang cerita rakyat dan legenda mulai
zaman dinasti pertama sampai dengan asal mula perayaan masyarakat
Tionghoa, terlepas dari kepercayaan dan unsur keagamaan yang
dianut.
Situs ini membahas tentang pecinan, bukan saja hanya pada
pengertiannya, tetapi juga perkembangan dan penyebarannya di
Indonesia, hingga keberadaan kawasan Pecinan di beberapa negara di
belahan dunia.
3. http://web.budaya-tionghoa.net
Situs ini cukup aktif membahas informasi secara lengkap kebudayaan
dan sejarah Tionghoa dari negara asalnya dan juga informasi
kebudayaan dan sejarah Tionghoa di Indonesia.
4. http://nationalgeographic.co.id
Situs National Geographic Indonesia membahas berbagai segi
kehidupan lingkungan sosial budaya ekologi di Indonesia, terdapat
beberapa artikel yang membahas kawasan Glodok, dan kiltur orang
Tionghoa di Indonesia.
Penulis
mendapatkan bentangan peta kawasan Glodok dan sekitarnya
yang terbaru dari jangkauan Google.
2.1.10. Survey Lapangan
Penulis melakukan survey lapangan di kawasan Glodok dan sekitarnya
secara langsung untuk memperoleh informasi;
Foto dan rekomendasi tempat -
tempat di Glodok yang memiliki
keunikan untuk diangkat ke dalam buku.
Mengamati gaya hidup, keseharian, keramahan penduduk yang tinggal
di Area Glodok.
|
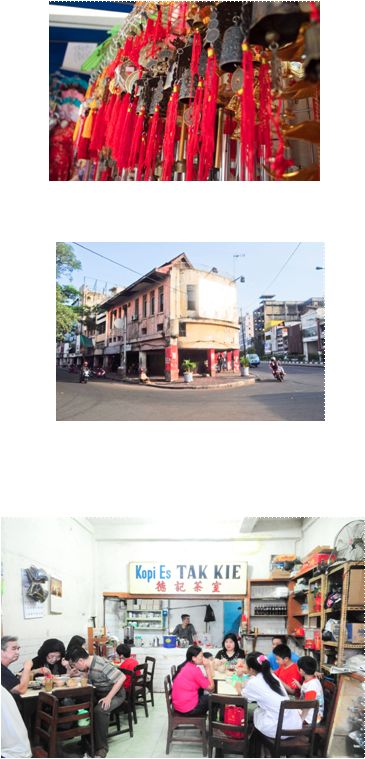 6
Gambar 2.1 Foto Suasana Pecinan Glodok 1
Gambar 2.2 Foto Suasana Pecinan Glodok 2
Gambar 2.3 Foto Suasana Pecinan Glodok 3
|
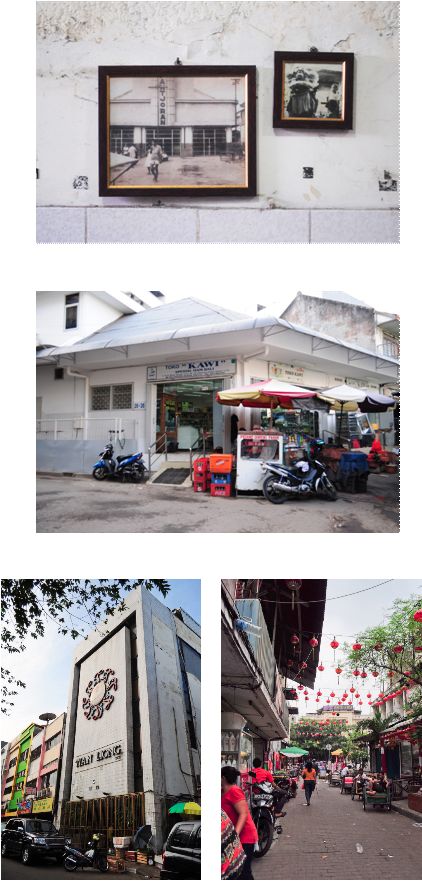 7
Gambar 2.4 Foto Suasana Pecinan Glodok 4
Gambar 2.5 Foto Suasana Pecinan Glodok 5
Gambar 2.6 Foto Suasana Pecinan Glodok 6(sebelah kiri) dan Gambar
2.7 Foto Suasana Pecinan Glodok 7(sebelah kanan)
|
 8
Gambar 2.8 Foto Suasana Pecinan Glodok 8
Gambar 2.9. Foto Suasana Pecinan Glodok 9
|
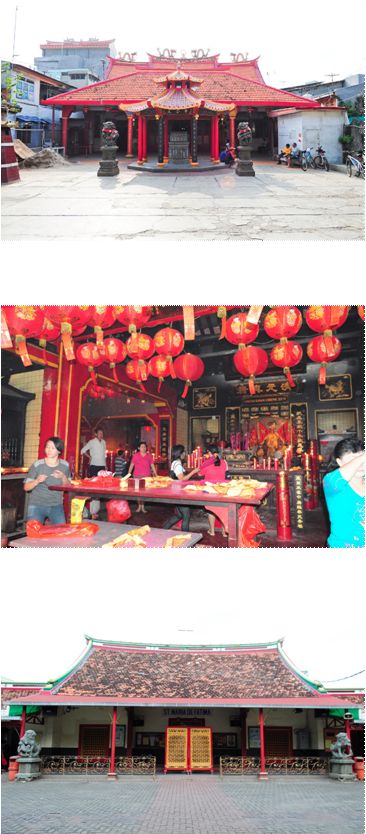 9
Gambar 2.10. Foto Suasana Pecinan Glodok 10
Gambar 2.11. Foto Suasana Pecinan Glodok 11
Gambar 2.12Foto Suasana Pecinan Glodok 12
|
|
10
2.1.11. Wawancara
Dalam menyusun laporan ini, penulis memerlukan informasi dari
berbagai narasumber yang memahami pembahasan topik tugas akhir
penulis atau sumber lain yang berhubungan dengan informasi konten
buku.
1.
David Kwa, pengamat Budaya Tionghoa di Indonesia yang sangat
memahami budaya Tionghoa di Indonesia.
2.
Kartum Setiawan, pengurus Komunitas Jelajah Budaya yang sudah
sejak tahun 2007 melakukan tur wisata budaya ke berbagai tempat
kebudayaan di Jakarta dan sekitarnya, salah satunya adalah Pecinan
Jakarta yang diakuinya memiliki peserta jelajah terbanyak
dibanding lokasi lain.
3.
Penduduk yang tinggal di Glodok, sebagai sumber informasi
Glodok dari dalam.
2.1.12. Kuisioner atau Angket
Kuisioner atau angket ditujukan untuk:
1. Mengetahui pandangan masyarakat umum tentang Glodok.
2. Kebutuhan visual target market untuk buku publikasi.
2.1.12.1 Kuisioner Untuk Mayarakat Umum
Dari total 137 pengisi kuisioner, dengan batasan umur 16 hingga di atas
30 tahun, dan 80% tinggal di Jakarta, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1.
Pecinan paling dikenali oleh mereka adalah Kampung Cina Glodok,
setelahnya menyusul Kampung Cina Mangga Dua, Kampung Cina
Pasar Baru, Kampung Cina Pasar Senen dan Tanah Abang, Pecinan
Medan, Pecinan Semarang, Pecinan Bandung, Pecinan Magelang.
3.
Tiga kegiatan paling banyak yang dilakukan saat berada di Glodok
adalah untuk berbelanja produk elektronik, wisata kuliner, dan
wisata kota tua.
4.
2 dari 137 orang melakukan wisata budaya seharian di Glodok
(wisata kota tua, wisata kuliner, perayaan hari raya Tionghoa).
5.
Sedangkan wisata budaya yang dilakukan 19 orang yang
menghabiskan waktu selama 5-6 jam di Glodok mencakup wisata
kota tua, kuliner, perayaan hari raya Tionghoa.
6.
Wisata budaya yang dilakukan 76% dari total pengisi kuisioner
menghabiskan waktu kurang dari 1 jam hingga 2 jam di Glodok
umumnya wisata kuliner.
7.
Dari 137 orang, tidak ada yang mengatakan budaya Tionghoa
di
Glodok sudah tidak terasa lagi saat ini. 89% mengatakan budaya
Tionghoa masih sangat terasa di Glodok, 39% mengatakan biasa
|
|
11
saja.
8.
8 dari 137 memilih selain ”setuju” jika Glodok menjadi tempat
penting yang perlu diperhatikan di Jakarta sebagai tempat
bersejarah bagi perkembangan budaya Tionghoa di Jakarta (2
menyatakan tidak setuju, 6 kurang setuju, kurang mengerti, 50-50)
1. Karena tidak merasa Glodok itu unik secara sejarah dan budaya.
2. Tidak tahu kalau Glodok itu pecinan.
3. Sama dengan Pecinan di daerah lain
4. Tidak tahu sejarah dan budaya di Glodok, karena dikenal hanya
ekonominya saja.
5. Yang sering diekspos hanya klenteng dan pasar, tidak ada publi-
kasi sejarahnya.
6. Budaya Tionghoa hanya terasa saat ada hari raya Tionghoa saja.
7. Masih banyak daerah lain yang harus diperhatikan.
8. 2 dari 137 orang menyatakan tidak perlu dibuat publikasi bu-
ku yang berisi segala informasi dan keunikan Glodok, padahal
memberi nilai 8 & 9 untuk pernyataan Pecinan Glodok adalah
salah satu tempat unik di Jakarta dan wajib menjadi lokasi wi-
sata bagi para turis.
9. Secara garis besar,3 hal positif yang diperoleh setelah berkun-
jung ke Glodok;
1. Merasakan budaya Tionghoa yang ada di Glodok (82 orang)
2. Wajah Indonesia yang beragam suku bangsa (13 orang)
3. Mempelajari nilai hidup seperti keuletan orang Tionghoa
yang bekerja di sana. (6 orang)
4. 19 sisanya tidak ada pengalaman positif berkaitan budaya
Tionghoa di Glodok.
10. 21 dari 137 berpendapat area Glodok masih perlu diperbaiki
melalu ekspos atau publikasi ke luar yang baik.
2.2. Definisi Peranakan Tionghoa
Menurut salah satu literatur
http://asalusulbudayationghoa.blogspot.com, Tionghoa atau tionghwa,
adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang keturunan Cina di
Indonesia, yang berasal dari kata zhonghua dalam Bahasa Mandarin.
Zhonghua dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa.
Sedangkan istilah peranakan Tionghoa pertama kali digunakan oleh
Bangsa Belanda di abad ke 18 untuk menyebut para keturunan imigran
Tionghoa yang datang dari Tiongkok beberapa waktu sebelumnya.
Seiring dengan berjalannya waktu, istilah peranakan Tionghoa disingkat
menjadi peranakan saja. Dalam bahasa Indonesia, semua sudah seperti
|
|
12
sepakat bahwa sebutan Tionghoa adalah yang paling menyenangkan.
Tionghoa sudah berarti ‘’orang dari ras Cina yang memilih tinggal dan
menjadi warga negara Indonesia’’. Kata Tionghoa sudah sangat enak
bagi suku Cina tanpa terasa ada nada, persepsi, dan stigma mencina-
cinakan.
Masyarakat Tionghoa di Indonesia pernah terbagi dalam tiga golongan
besar: totok, peranakan, dan hollands spreken.
Yang tergolong totok adalah mereka yang baru satu turunan di
Indonesia (orang tuanya masih lahir di Tiongkok) atau dia sendiri masih
lahir di sana lalu ketika masih bayi diajak xia nan yang, atau istilah
totok juga disebutkan kepada mereka yang saat ini masih memegang
teguh adat istiadat leluhurnya. Sama seperti suku lainnya di Indonesia
misalnya yang
masih memegang teguh urutan upacara pernikahan,
persalinan ataupun aturan kebudayaan lainnya.
Yang hollands spreken adalah yang dimana pun lahirnya- menggunakan
bahasa Belanda, mengenakan jas dan dasi, kalau makan pakai sendok
dan garpu, dan ketika Imlek tidak mau menghias rumah dengan pernik-
pernik yang biasa dipergunakan oleh peranakan maupun totok karena
dianggap kuno atau tidak sesuai atau tidak logis akibat tidak memahami
sama sekali arti dibalik asal usul tersebut.
Sedangkan yang disebut peranakan adalah yang sudah beberapa
keturunan lahir di tanah yang kini bernama Indonesia, kebanyakan tidak
lagi menggunakan bahasa suku (Hokkian, Hakka atau lainnya) ataupun
Bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu yang dipercakapkan dirumah.
(Irfan Utamin, http://asalusulbudayationghoa. blogspot.com, 2012)
Berdasarkan Volkstelling (sensus) pada masa Hindia Belanda, populasi
Tionghoa-
Indonesia mencapai 1.233.000 (2,03%) dari penduduk
Indonesia di tahun 1930. Tidak ada data resmi mengenai jumlah
populasi Tionghoa di Indonesia dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia
merdeka. Namun ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam
risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di
Indonesia mencapai 2.505.000 (2,5%) pada tahun 1961.
(Wikipedia, Tionghoa-Indonesia, 2012)
2.3. Sekilas mengenai Pecinan dan Kampung Cina
Menurut David Kwa, Dalam Pecinan dan Kampung Cina merupakan 2
nama yang digunakan untuk menyebut pemukiman orang Tionghoa di
Indonesia. Istilah Pecinan dipakai di Jawa. Sedangkan untuk wilayah
|
|
13
Jakarta orang dulu menyebut pemukiman orang Tionghoa dengan
sebutan Chineeseche Wijk atau Kampung Cina. Setelah Batavia
terbentuk barulah muncul pemukiman orang Tionghoa di Jakarta.
Menurut David Kwa, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai Pecinan
atau Kampung Cina jika memiliki beberapa hal berikut ini:
1. Klenteng
Klenteng merupakan tempat bersembahyang bagi orang Tionghoa,
sebenarnya Klenteng memiliki arti yang berbeda dengan Vihara.
Klenteng berkaitan langsung dengan budaya Tionghoa, sedangkan
vihara merupakan tempat ibadah agama Buddha, pada masa Orde
Baru, kegiatan yang berbau budaya Tionghoa ditekan dan dilarang
oleh pemerintah, menurut PP yang dikeluarkan.
Akhirnya klenteng –
klenteng yang berada di nusantara, di Glodok
khususnya memilih untuk bernaung menggunakan sebutan vihara
agar memperoleh ijin beribadah.
Klenteng:
a. Tempat sembahyang orang Tionghoa, Konghucu, Tao
b. Menyembah Dewa lokal sebagai pusat ibadah
Vihara:
a. Tempat ibadah agama Buddha
b. Sang Buddha Sidarta Gautama sebagai sumber ajaran agama.
Berubahnya klenteng –
klenteng di berbagai Pecinan membuat
banyak persepsi yang mengidentikan Vihara –
Buddha –
China.
Bahwa Buddha adalah agama bagi orang Cina/ Tionghoa. Padahal
masuknya agama Buddha di Indonesia berasal dari zaman Kerajaan
Buddha, jaman dibangunnya candi – candi, seperti: Candi Borobudur.
2. Rumah – rumah yang masih berciri khas Tionghoa
Rumah warga Tionghoa memiliki ciri khas klasik.
Ciri yang paling sederhana yang masih dapat dijumpai hingga tahun
2013 ini yaitu dipasangnya Cermin bundar di bagian depan rumah
yang dipercaya sebagai penolak bala.
Masih banyak juga ciri klasik lainnya;
3. Penduduk yang mayoritas Tionghoa.
4. Bahasa yang ada di lingkungan sehari – hari.
5. Toko dan usaha warga sekitar.
a. Dagangan barang / peralatan Tionghoa.
b. Toko obat Cina.
c. Kuliner, tempat jajanan masakan Cina / Peranakan.
|
|
14
d. Toko Alat Sembahyang.
2.4. Sekilas Sejarah Glodok
Kawasan Pemukiman Tionghoa di Glodok terbentuk setelah terjadi
peristiwa pembantaian 10.000 orang Tionghoa
di Angke pada tahun
1740.
Sebelum Tragedi Pembantaian di Angke 1740
Sejak zaman sebelum Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Coen
berkuasa, orang Tionghoa tinggal di berbagai area di sekitar Batavia,
tidak ada larangan karena orang Tionghoa memiliki jasa membangun
kota Batavia. Banyak gedung –
gedung peninggalan zaman belanda
yang dibangun oleh orang Tionghoa, dapat dilihat dari berbagai bentuk
arsitekturnya, warnanya, seperti Gedung Arsip yang ada di jalan Gajah
Mada misalnya., bentuk dan keindahan ukiran,
warna yang dipakai
merupakan karya orang Tionghoa pada zaman itu.
Pada zaman itu, orang Tionghoa mampu mengerjakan banyak hal,
berbagai jasa pertukangan saat itu dikerjakan orang Cina. Belanda yang
ketika itu memegang kuasa atas kota selama penjajahan sangat
membutuhkan keberadaaan orang Tionghoa utuk membangun kota
Batavia.
Kota Batavia
Pengertian Kota yang benar adalah kawasan Betawi / Batavia yang
berada di dalam benteng di masa itu. Mencakup Pintu Besar Utara, Kali
Besar, Museum Bank Indonesia, hingga kawasan Beos. Yang menjadi
batas dalam kota: Pintu Besar Selatan ke Utara. Pintu Besar Selatan
terletak di luar benteng, sering disebut juga Pintu Baru disebut juga
Nieuedietspoort. Ada juga Pintu Kecil yang merupakan akses kecil
untuk masuk ke Pintu Besar, bernama Dietspoort, oleh karena
bentuknya yang berupa pintu kecil, maka penduduk sekitar
menyebutnya Pintu Kecil.
Tragedi Pembataian Angke 1740
Seiring majunya Batavia di Indonesia, hingga tahun 1740 warga
Tionghoa ikut menyumbang kepadatan penduduk
di Batavia, jumlah
warga Tionghoa semakin banyak jumlahnya, namun tidak selaras
dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Akibatnya banyak sekali
pengangguran dan warga Tionghoa yang mengalami kemiskinan.
Sedikitnya lapangan pekerjaan, selisih paham sesama kaum Tionghoa,
|
|
15
kondisi kawasan luar tembok kota yang tidak aman, merosotnya wibawa
Kapiten Cina karena tidak becus membenahi berbagai permasalahan,
serta perlakuan tidak adil pemerintahan kolonial lewat peraturan yang
menyulitkan kehidupan warga Tionghoa, dikhawatirkan pemerintahan
kolonial Belanda akan memicu pemberontakan warga Tionghoa kepada
pemerintahan.
Jika pemberontakan itu terjadi maka pemerintahan dapat ditundukkan
oleh warga Tionghoa karena jumlah warga yang sangat banyak dan
kepandaian yang dimiliki warga Tionghoa menimbulkan ketakutan
pemerintahan Belanda. Akhirnya Belanda memutuskan untuk
melakukan pembantaian massal warga Tionghoa secara membabi buta,
siapapun yang ditemui, segala umur, dibunuh dan jasad warga Tionghoa
dibuang ke kali.
Saat itu pemandangan yang terlihat adalah kali yang berwarna merah
karena bercampur dengan darah 10.000 orang Tionghoa yang dibantai
saat itu. Peristiwa memilukan ini kemudian dikenang oleh warga
Tionghoa yang tersisa dengan menamai kali tersebut Kali Angke.
Setelah Tragedi Pembantaian Angke tahun 1740
Seluruh warga Tionghoa kemudian diusir dari dalam kota Batavia dan
diisolasi di sebuah wilayah di luar tembok yang berada di area jarak
tembak meriam Belanda di pusat Kota Batavia. Wilayah tersebut
kemudian menjadi pemukiman utama warga Tionghoa di Jakarta dan
saat ini dikenal dengan nama Glodok.
Asal Usul Nama Glodok
Ada berbagai versi tentang asal usul nama Glodok yang ditemukan;
1.
Menurut Wikipedia, kata Glodok berasal dari Bahasa Sunda
“Golodog”. Golodog berarti pintu masuk rumah, karena Sunda
Kalapa(Jakarta) merupakan pintu masuk ke kerajaan Sunda.
2.
Menurut Wikipedia, nama Glodok juga berasal dari suara “grojok
grojok”, yaitu suara air yang keluar dari air pancuran di halaman
dari pusat kota (Stadhuis), kini Museum Fatahillah Jakarta. Pancuran
tersebut terdapat waduk penampungan air kali Ciliwung dan
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari penduduk. Oleh karena lidah
orang Tionghoa yang sulit melafalkan kata “Grojok” maka
kemudian lebih sering disebut Glodok.
3.
Dalam buku yang diterbitkan Dinas Museum dan Sejarah DKI tahun
1988 menyebut kemungkinan nama Glodok berasal dari seorang
Kapiten Bali bernama Tjirra Glodok yang memiliki tanah di
|
|
16
kawasan tersebut.
4.
Glodok berasal dari nama orang Bali I Gde Glodok (Ridwan Saidi ;
Profil Orang Betawi, 1997).
5.
Dalam buku nama Glodok karena area tersebut bekas tanah milik
Arya Glitok seorang bangsawan asal Bali (Thomas Ataladjar ; Anzis
Kleden ; Toko Merah; Saksi Kejayaan Batavia Lama, 2003).
Masa Keemasan Glodok
Pada tahun 1940-an hingga 1970-an kawasan Pancoran – Glodok adalah
surga untuk jajanan dan melepas penat di Jakarta. Pada masa jayanya,
sejumlah restoran di sana menjadi tempat kuliner favorit. Masakan Cina
(Chinese food) seperti nasi ayam Hainan, sup bulus (pi oh), kwetiau
sapi, babi panggang, sek ba, sop kambing, hingga soto betawi menjadi
ikon dunia kuliner Jakarta tempo dulu. Tahun 1960-an hingga 1970-an
seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia masa Soeharto, popularitas
restoran di Glodok dikenal hingga ke mancanegara.
Kerusuhan Mei 1998
Kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia juga
terjadi di Glodok. Kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang kacau
membuat golongan masyarakat Indonesia tertentu melakukan kerusuhan
di tempat –
tempat yang sudah direncakan untuk dijadikan target
penjarahan. Dapat dikatakan kerusuhan 98 berdampak besar dalam
perkembangan Glodok. Akhirnya Glodok kini sepi, banyak sekali rumah
tua yang ditinggalkan tak berpenghuni. Kebanyakan warga Tionghoa
yang masih tinggal di Glodok hidup dengan kondisi ekonomi menengah,
yang memiliki perekonomian lebih baik memutuskan untuk pindah ke
tempat lain yang lebih aman.
2.5. Sekilas Budaya Peranakan Tionghoa di Glodok
Kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddhayah, yang
merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai
hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, budaya berarti pikiran dan akal budi, adat
istiadat, sesuatu yang sudah menjadi
kebiasaan yang sudah sukar
diubah.
Pengertian budaya sangatlah luas, banyak hal yang disebut kategori
budaya. Adapun menurut Koentjaraningrat, unsur –
unsur kebudayaan
meliputi sistem religi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial,
sistem pengetahuan, bahasa komunikasi, kesenian, sistem mata
pencaharian hidup atau sistem ekonomi, sistem peralatan hidup atau
teknologi.
Glodok yang telah memiliki sejarah panjang hingga saat ini, memiliki
|
|
17
keunikan budaya yang hanya dapat ditemukan di Glodok. Salah satunya
interaksi budaya sesama penduduk di Glodok baik Tionghoa totok
maupun Tionghoa Peranakan. Adapun arti Tionghoa Peranakan saat ini
berbeda dengan Tionghoa Peranakan zaman dahulu, Tionghoa
Peranakan sekarang ini lebih mengarah kepada warga Tionghoa yang
telah mengalami pembauran budaya asli dengan budaya lokal,
contohnya seperti jenis kuliner yang ada di pasar, bisa dari tata cara
merayakan hari raya Tionghoa.
Adapun budaya Tionghoa yang masih dapat dilihat di Glodok dapat
dijabarkan sebagai berikut;
1. Klenteng.
2. Rumah – rumah yang masih memiliki ciri khas Tionghoa.
3. Aktivitas keseharian warga Tionghoa yang ada di Glodok.
4. Bahasa keseharian yang digunakan warga Tionghoa di Glodok.
5. Toko dan usaha warga sekitar;
a. Toko Obat.
b. Rumah makan yang menjual makanan khas Tionghoa.
c. Pasar yang juga menjual bebagai jajanan hingga barang kebutuhan
khas Tionghoa.
d. Toko yang menjual keperluan sembahyang.
e. Studio kaligrafi
f. Toko Mebel
Keunikan budaya Tionghoa di Glodok belum mendapat kepedulian baik
dari pemerintahan maupun masyarakat umum, hal ini terbukti dengan
kondisi beberapa bangunan tua, yang memiliki khas nilai budaya
Tionghoa sejak ratusan tahun lalu, yang kondisinya memprihatinkan,
banyak rumah tua yang telah dihancurkan dan dibangun gedung modern
di atasnya, banyak gedung tua yang dibiarkan saja tak berpenghuni dan
tak terawat selama bertahun – tahun.
Terdapat banyak kesalahpahaman dan rendahnya pengetahuan
masyarakat umum akan budaya Tionghoa yang ada di Glodok, seperti;
1.
Gereja Santa Maria de Fatima di Jalan Kemenangan yang dikira
banyak orang bekas klenteng, padahal ciri khas atap bangunan
Tionghoa menandakan status penghuni yang tinggal di dalamnya.
Atap lengkung dengan naga di atasnya menandakan bangunan
klenteng, sedangkan Santa Maria de Fatima memiliki ekor walet
pada ujung samping kiri kanan lengkung atap yang menandakan
bahwa rumah tersebut adalah rumah orang Tionghoa yang memiliki
status bangsawan, kapiten, maupun orang kaya.
2.
Pemotongan ekor walet pada ujung
lengkung atap rumah tua
Tionghoa di Jalan Perniagaan karena pemilik rumah yang sekarang
malu kalau rumahnya disebut sebagai klenteng, padahal ciri khas
atap bangunan Tionghoa menandakan status penghuni yang tinggal
di dalamnya. Atap lengkung dengan naga di atasnya.
3.
Pemahaman budaya Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan dari
segi makanan, seperti ragam Kue Mangkok yang dijual sepanjang
|
|
18
jalan Kemenangan dan Pasar Petak Sembilan, warna kue mangkok
pink dan merah merupakan makanan peranakan, yang asli adalah
kue mangkok coklat dengan kelapa parut di atasnya.
Bagi sekelompok masyarakat yang menyadari kekayaan budaya bangsa,
Glodok pun memiliki perjalanan sejarah yang panjang, sebenarnya
memiliki keunikan budaya yang khas yang hanya dapat ditemui di
Kampung
Cina Glodok, tidak pada Pecinan lain di nusantara maupun
Chinatown di luar negeri. Budaya peranakan yang hanya dimiliki di
Indonesia dengan perpaduan budaya Tionghoa asli dengan budaya lain
yang ada di Glodok sejak terbentuknya kawasan Glodok.
Seiring majunya waktu, budaya Tionghoa di Glodok terancam
menghilang karena bukti –
bukti sejarah yang ada sejak dulu kini
dihancurkan dan tidak dirawat lagi, generasi yang ada baik tua maupun
muda tidak lagi memilki rasa kepedulian untuk mau memahami budaya
Tionghoa yang ada di Glodok.
Glodok hanya dianggap tempat berdagang, kumuh, banyak pedagang
kaki lima, kawasan perekonomian dan tidak memiliki nilai bersejarah,
seperti kawasan pemukiman warga di Jakarta pada umumnya.
2.6. Sekilas Tempat - Tempat di Glodok
Glodok sekarang ini memiliki batasan area secara administratif, berbeda
dengan pengertian Kampung Cina Glodok di kala awal yang hanya
berbatas diluar benteng, tidak ada batas pasti saat itu. Hingga area
Pinangsia, Pasar Pagi, Perniagaan, bahkan Tambora juga tersebar
pemukiman Tionghoa.
Untuk itu berikut peta administrasi kelurahan Glodok berdasarkan data
terakhir November, 2012, dari Kantor Kelurahan Glodok, DKI Jakarta.
Keadaan dan gambaran Umum:
Luas wilayah
37,6Ha
Jumlah Rukun Warga
5 RW
Jumlah Rukun Tetangga
61 RT
Batas Wilayah:
Utara
Jl. Pinangsia Raya, berbatasan dengan kelurahan Pinangsia
Selatan
Jl. Keadilan Raya, berbatasan dengan kelurahan Keagungan
Timur
Jl. Gajah Mada, berbatasan dengan kelurahan Mangga Besar
Barat
Kali Krukut, berbatasan dengan Kelurahan Tambora.
|
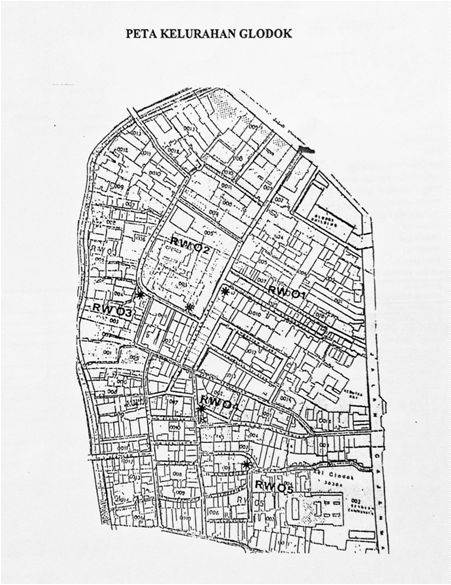 19
Gambar 2.13. Peta Area Kelurahan Glodok
Sampai saat ini masih terdapat banyak tempat di Glodok yang masih
dapat dirasakan budaya Tionghoa saat kita berkunjung. Sebagian tempat
di Glodok seperti klenteng, toko obat, pasar yang menjual kuliner
Tionghoa, sudah dikenal luas oleh masyarakat hingga wisatawan asing.
Untuk mengetahui seberapa banyak area yang harus ditelusuri untuk
menemukan tempat khas yang ada di Glodok, dibutuhkan rute
perjalanan dan batasan – batasan wilayah yang termasuk dalam budaya
Tionghoa di Glodok. Dibuatlah peta area Glodok dan sekitarnya, yang
bersumber dari Google Maps, sebagai basis rute napak tilas, dan rute
ditentukan dari hasil diskusi dengan nara sumber dari Komunitas jelajah
Budaya dan riset lapangan.
|
|
20
Torenlaan
Dulunya merupakan tempat observatorium pertama di Batavia. Pada
masa ketika rumah sekaligus observatorium Mohr masih berdiri
bagaikan menara (toren), kawasan ini bernama Torenlaan. Toren
dilafalkan warga lokal sebagai torong jadilah Gang Torong. Gang
Torong cukup tenar setidaknya sering disebut dalam koran lokal di masa
tersebut.
Rutenya berawal dari Gang Torong, alasannya:
1.
Pertama, dalam konteks sejarah, Gang Torong merupakan sebuah
landmark di Batavia, di mana terdapat Observatorium Bintang yang
dibangun di abad 17, jauh sebelum terbentuknya Pecinan di kawasan
Glodok.
2.
Kedua dari konteks ide buku, Penulis melalui buku ini mengajak
pembaca mengobservasi Glodok dari sudut yang berbeda, dari
kesederhanaan penduduknya, sejarah dan kebudayaan Glodok, tidak
berdasar sisi kemajuan ekonomi saja.
3.
Ketiga dari segi akses mudah untuk dijangkau publik umum karena
tepat di depan Gang Torong terdapat halte Bus TransJakarta di Jalan
Raya Gajahmada.
Kisah yang diteropong di Gang Torong dan Kebun Torong:
1.
Bakmi Naga, usaha bakmi dan bakso yang telah berjalan selama 3
generasi, dan menjadi legenda di Glodok.
2.
Tukang Gado –
Gado yang menjadi titik berkumpul di kawasan
Gang Torong
3.
Cobra 68, usaha makanan kesehatan yang telah 2 generasi lamanya,
menjual daging dan darah ular, daging biawak, dan hewan langka
untuk kesehatan.
Jalan Kemenangan Raya
Berbagai pedagang daging dan ayam, pertokoan alat sembahyang yang
sanagat strategis karena dekat dengan Jin De Yuan, pedagang kue
mangkok, dan pedagang bunga, dan rumah warga yang sudah berbentuk
ruko.
Kisah yang diteropong di Jalan Kemenangan:
1. Klenteng Jin De Yuan
2. Toko Sembahyang dekat klenteng Jin De Yuan
3. Sinshe Auw Kan
4. Rutinitas kehidupan di sekitar
|
|
21
Gang Jago dan Pasar Asem
Pasar yang selalu ramai, terdapat berbagai jenis kuliner yang lengkap
dan enak. Kini lebih sering ditemui rumah makan, pedagang sayur dan
buah, rumah modern. Bakmi Icen, Rumah Makan Linda, Bubur Ayam,
Nasi Ulam, Panggang Babi, masih banyak lainnya.
Kisah yang dapat diteropong di Pasar Asem:
1. Kehidupan sekitar Pasar Asem
2. Rumah Ex Perkumpulan Barongsai
Gang Jago adalah gang kecil yang menghubungkan Pasar Asem dengan
Jalan Kemenangan 3, merupakan tempat pemukiman warga. Terdapat
rumah abu, vihara, dan tukang bakcang.
Kisah yang dapat diteropong di Gang Jago:
1. Rumah Abu Loe
2. Rumah Tukang Bakcang
Jalan Kemenangan 3
Pemukiman Tionghoa yang memiliki banyak tempt yang dapat
dikunjungi. Ada vihara Toa Se Bio, Gereja Santa Maria de Fatima,
berbagai usaha dan rumah makan warga Tionghoa, jalan ini terhubung
dengan Jalan Kemenangan 8, Gang Pancoran, gang Ucha/ Kemenangan
1, dan Toko Tiga.
Kisah yang dapat diteropong di Jalan Kemenangan 3:
1. Vihara Toa Se Bio
2. Gereja Santa Maria De Fatima
3. Rumah Makan Wengkim
4. Bakmi Akwet
5. Fat Cu Kung Bio
Jalan Toko Tiga
Jalan berbatasan dengan Kali Belandongan. Ke utara menuju Gedung
Chandra ada Toko Obat Cina yang cukup tua. Ke arah selatan terdapat
Vihara dan usaha dagang bakmi warga Tionghoa.
Kisah yang diteropong di Jalan Toko Tiga:
1. Toko Obat Shin Shen Tong
2. Klenteng Tan Se Ong
3. Kehidupan sekitar Klenteng, sepanjang pinggir Kali Krukut.
Pasar Petak Sembilan dan Gang Kalimati
Merupakan terusan Jalan Kemenangan yang menyambung ke Jalan
Pancoran, kondisi pasar cukup padat, berbagai rumah warga dari yang
modern hingga kumuh dapat dijumpai sepanjang perjalanan. Berbagai
|
|
22
barang kebutuhan dijual di Pasar Petak 9, mulai dari sembako, ikan,
sayur, daging, kemudian toko sembahyang, manisan, kain dan kancing,
toko obat, semuanya ada di sini. Petak 9 terhubung dengan banyak gang
yang terkenal yaitu di antaranya Gang Tikar, Gang Kecap, Gang
Kalimati.
Kisah yang dapat diteropong:
1 Toko Alat Sembahyang Hokie
2. Toko Obat Hok Sen Thong
3. Toko Sembako Tek Seng
4. Toko KueFay Kie
5. Toko Bunga (Kaligrafi) Sanjaya
6. Toko Jaya Abadi
Jalan Pancoran dan Gang Gloria
Merupakan pusat kehidupan orang Tionghoa Glodok pada jaman dulu,
berbagai kemajuan ekonomi, wisata kuliner, hingga gedung bioskop
rakyat ada di sini. Berbagai atraksi silat dan obat Cina menghiasi pasar
malam Pacoran. Sekarang padat akan pedagang kaki lima, mobil yang
lewat, terasa sempit dan kacau. Banyak gedung tua bersejarah yang
hangus terbakar di antaranya Glodok Building, dan Gedung Gloria.
Terdapat batu tanda batas wilayah Kelurahan Glodok dan Kelurahan
Tambora. Di penghujung menuju Kali Besar, terdapat tanda Pintu Kecil
yang bersejarah.
Kisah yang dapat diteropong:
1. Pempek dan Rujak Juhi
2. Toko obat Tay Seng Ho
3. Toko Obat Kupu Kupu
4. Gedung Chandra
5. Apotik Ben Seng
6. TokoTian Liong
7. Glodok Plein
8. Es Kopi Takkie
Jalan Gajah Mada (keluar Gang Torong)
Jalan besar yang dulunya berjejer 3 rumah besar Tionghoa yang sangat
megah dan tidak dimiliki di Pecinan Malaka dan Singapura, yaitu Bekas
Gedung Kedutaan RRC; kini Glodok city, Bekas Rumah besar yang kini
SMAN2, Gedung Candranaya yang kini bernaung di bawah Novotel.
Sepanjang jalan ini banyak usaha tempat makan yang dibuka hanya saat
malam hari.
1. Gedung Candranaya
|
|
23
Demikian juga akan diangkat cerita yang berkaitan dengan keberadaan
etnis Tionghoa dari area Glodok lama yang menjangkau area lebih luas
dari area Glodok saat ini.
Jalan Pintu Besar Selatan dan Pinangsia
Sepanjang jalan raya Pintu Besar dipenuhi pelukis jalanan, gedung
perkantoran, dan toko mebel. Mengingatkan bahwa banyak suku
Konghu Kayu yang menjadi penduduk Tionghoa di Glodok dengan
keahlian ukir yang luar biasa dikenal. Juga mengangkat Dewa yang
dipuja oleh suku Konghu Kayu di klenteng Lu Pan Bio di Pinangsia
1. Klenteng Lu Pan Bio
2. Toko Mebel 77
Jalan Jelangkeng
Banyak terdapat rumah Tionghoa tua yang masih berdiri, namun dalam
keadaan yang sangat tua atau kotor, ada gang Jelangkeng yang memiliki
sisa bangunan pemukiman Tionghoa kumuh yang menjadi bukti sejarah
yang ada.
Jalan Perniagaan
Dulu disebut jalan Petekwan, area jalan yang luas, banyak terdapat
rumah Tionghoa yang sudah diganti dengan gedung baru. Melewati
jalan Perniagaan sangat membangkitkan kenangan tempoe doeloe di
Glodok.
1.Vihara Budhi Dharma
2. Rumah Souw
3. SMU 19/THHK
4. Klenteng Arya Marga.
2.7. Spesifikasi Buku
Naskah
: Penulis
Penyelenggara
: Aspertina
Penerbit
: Afterhours Book
Kerangka buku
: 1. Sampul Buku
2. Halaman judul dalam
3. Pembuka
4. Daftar Isi
5. Petunjuk Membaca
6. Isi
7. Penutup
8. Pengakuan
|
|
24
9. Daftar Pustaka
2.8. Profil Target
Target Primer
Geografis
Domisili
: Perkotaan
Wilayah
: Kota besar di Indonesia
Demografis
Target Audience
Jenis Kelamin
: Pria dan Wanita
Usia
: 20 s.d 45 tahun
Ekonomi
: menengah ke atas (A-B)
Profesi
: berpenghasilan sendiri
Psikografis
Kepribadian:
1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal baru.
2. Memiliki apresiasi terhadap desain visual.
3. Tertarik pada budaya Tionghoa di Jakarta.
4. Pola pikir terbuka akan keanekaragaman budaya di Indonesia.
5. Memiliki minat dan apresiasi terhadap budaya negeri sendiri.
6. Menyukai petualangan dan menjelajahi tempat baru.
7. Memiliki keinginan berpartisipasi melestarikan budaya.
8. Menyukai hal-hal yang otentik dan antik.
Gaya Hidup:
1. Mengikuti perkembangan jaman.
2. Suka mencari informasi.
3. Suka membaca dan mengoleksi buku.
4. Suka berdiskusi, berbagi informasi.
5. Memiliki relasi yang cukup luas.
6. Mau berpartisipasi dalam event – event sosial dan budaya.
Target Sekunder
Geografis
Domisili : Perkotaan
Wilayah
: Kota besar di Indonesia
Demografis
Target Audience
Jenis Kelamin
: Pria dan Wanita
|
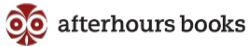 25
Usia
: 20 s.d 45 tahun
Ekonomi
: menengah ke atas (A-B)
Profesi
: berpenghasilan sendiri
Psikografis
Kepribadian:
1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
2. Memiliki minat dan apresiasi terhadap budaya negeri sendiri.
3. Pola pikir terbuka akan keanekaragaman budaya di Indonesia.
Gaya Hidup:
1. Mengikuti perkembangan jaman.
2. Suka membaca buku.
3. Suka berdiskusi, berbagi informasi.
2.9. Data Penerbit
Buku ini rencananya akan diterbitkan oleh Afterhours Books yang
dikelola oleh Lans Brahmantyo yang fokus menerbitkan buku -
buku
visual arts
bersubjek tentang seni budaya dan kearifan Indonesia.
Penerbit yang sejak dulu mendesain buku terbitan Red & White
Publishing memang memfokuskan diri untuk mempromosikan seni
budaya dan sejarah Indonesia ke dunia internasional.
Melalui wawancara singkat melalui surrel dengan Lans Brahmantyo,
diketahui Afterhours Books berencana akan mendesign dan menerbitkan
beberapa topik etnis Tionghoa.
Maka berdasarkan informasi di atas Afterhours Book merupakan
penerbit yang tepat untuk menjadi penerbit dari publikasi ini karena
sesuai dengan fokus buku yang mengangkat salah satu kekayaan budaya
di Indonesia yaitu budaya Tionghoa di Glodok, yang tentunya menjadi
bagian dari budaya Batavia hingga Jakarta sekarang.
2.10. Kompetitor
2.10.1. Kompetitor Langsung
Belum ada buku publikasi dalam kategori Kebudayaan yang
mengangkat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Glodok
|
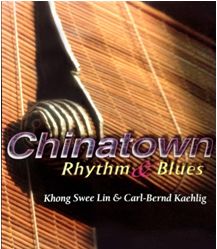 26
sebagai fokus buku.
2.10.2. Kompetitor Tidak Langsung
Terdapat buku publikasi dalam kategori Kebudayaan yang
mengangkat Kebudayaan secara khusus dan memiliki olah
visual yang memanjakan mata. Di antaranya adalah;
2.10.2.1. Buku “Chinatown: Blues & Rythm”
Judul
: Chinatown: Blues & Rythm
Penulis
: Khong Swee Lin, Carl-Bernd Kaehlig
Penerbit
: Times Edition – Marshall Cavendish
Tahun Terbit
: 2001, Singapura
Harga Buku
: US$38.13
Jumlah Halaman : 137 halaman
Sebuah buku fotografi yang mencoba mengangkat
keberagaman dan harmonisasi jiwa dari Chinatown Singapura
sekrang ini. Yang lama dan yang baru secara tematis
berjukstaposisi, memfokuskan pada arsitektur, umat dan
kepercayaannya, kuliner dan keseniannya.
Secara visual, foto –
foto yang ada di dalamnya sangat
memanjakan mata, informatif secara visual, 1 gambar
mewakili ribuan kata.
2.10.2.2. Buku “Balinese Dance, Drama, and Music : A Guide to the
Performing Arts of Bali”
|
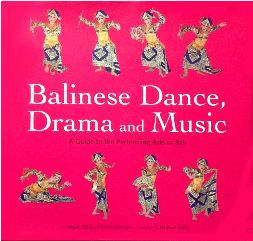 27
Judul
: Balinese Dance, Drama, and Music (A
Guide
to the Performing Arts of Bali)
Penulis
: I Wayan Dibia, Rucina Ballinger
Penerbit
: Periplus
Tahun Terbit
: 2004, Singapura
Harga Buku
: US$35.00
Jumlah Halaman : 112 halaman
Secara garis besar, buku ini memperkenalkan seni budaya
pertunjukan tradisional yang paling sering ditemukan di Bali.
Musik gamelan, tari, drama dan boneka dibahas di sini
diyakinkan untuk memikat pembaca dari belahan dunia Barat.
Bacaan yang ideal bagi pengunjung ke pulau serta untuk siapa
saja yang tertarik dalam budaya Bali, buku ini sepenuhnya
menjelaskan sejarah dan fungsi atau tujuan setiap genre
pertunjukan seni di Bali. Kenikmatan membaca ditingkatkan
dengan bibliografi, discography, dan lebih dari 150 ilustrasi
cat air yang khusus disiapkan mengenai artis dan pertunjukan
Bali.
2.11. SWOT
2.11.1. Strength
1.
Memberikan informasi mengenai keunikan dan warisan
budaya Tionghoa di Glodok melalui visual buku yang tidak
terpaku dengan teks, seperti kebiasaan membaca pada
umumnya.
2.
Buku dapat digunakan sebagai media publikasi informasi
warisan kebudayaan Glodok di Jakarta.
3.
Mudah dipahami oleh target market buku yang sudah pernah
|
|
28
ke Glodok atau bahkan belum pernah ke Glodok.
4.
Didukung visualisasi berupa foto montage dari fotografi.
2.11.2. Weakness
Tidak semua tempat di Glodok dimuat dalam buku.
2.11.3. Opportunity
1.
Terdapat perkumpulan seperti Komunitas Jelajah Budaya,
Sahabat Museum, dan organisasi Koko
Cici Jakarta juga
forum budaya_Tionghoa yang masih aktif hingga saat ini,
sehingga menambah besar potensi pasar target yang
membutuhkan informasi dari buku ini.
2.
Belum ada kompetitor buku lokal yang secara khusus
mengangkat tema budaya Tionghoa di Glodok Jakarta
dalam media publikasi buku.
3.
Glodok merupakan salah tempat bersejarah dan bernilai
kebudayaan di Jakarta yang masih memiliki warisan budaya
Tionghoa sejak ratusan tahun lalu, sehingga buku ini dapat
dijadikan salah satu wadah informasi budaya yang akan
menginspirasi pembacanya.
2.11.4. Threat
1.
Kurangnya kepedulian pemerintahan dan masyarakat
umum di Indonesia terhadap pentingnya mengenal dan
mencintai budaya bangsa sendiri.
2.
Kebanyakan mencari informasi tentang Glodok lewat buku
guide book atau travel book.
3.
Terdapat buku – buku guide atau travel yang lebih praktis
dibawa untuk dibaca di mana saja kapan saja.
4.
Tata kota Glodok yang sekarang belum menarik untuk
dikenal dari segi pariwisata
|