|
3
BAB 2
LANDASAN PERANCANGAN.
2.1 Tinjauan Umum.
Data – data dan literatur didapat dari berbagai media seperti buku, internet, dan foto
riset lapangan. Semua sumber merupakan bahan –
bahan untuk membantu memperkuat
data untuk fakta dan visual dalam pembuatan animasi edukasi “History of Legacy – A
Brief History of Kris.”
2.1.1 Animasi Edukasi.
Animasi Edukasi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan jasa atau alat
bantu elektronika sebagai media penyampaiannya. Dikutip dari (Clark, R., & Mayer, R., E-
Learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of
multimedia learning,
2003, p.8) e-learning didefinisikan sebagai atau pengajaran atau
informasi yang disampaikan lewat perangkat elektronik seperti computer atau perangkat
elektronik lainnya yang bertujuan untuk mendukung proses belajar.
2.1.2
Keris.
Dalam ("Malay World Edged Weapons", 2007), dan ("Keris", 2005) keris dari masa
pra –
Kadiri – Singasari dikenal sebagai Keris Buda. Keris Buda dianggap sebagai bentuk
pengawal keris modern. Keris Buda pada awalnya dibuat seperti belati dengan pamor yang
masih sederhana. Kemudian muncul sebuah keris pusaka dari Kerajaan Majapahit yang
dikenal dengan sebuatan Keris Buda dengan relief epic Ramayana. Keris Buda ini dimiliki
oleh keluarga Knaud dari Batavia yang didapat Charles Knaud, seorang Belanda peminat
mistisisme Jawa, dari Sri Paku Alam V. Keris ini memiliki relief tokoh epik Ramayana pada
permukaan bilahnya dan mencantumkan angka tahun Saka 1264 (1342 Masehi), sezaman
dengan Candi Penataran, meskipun ada yang meragukan penanggalannya.
2.1.3
Perkembangan Fungsi Keris.
Dalam ("Malay World Edged Weapons", 2007) dan menurut penelitian di Museum
Pusaka, Taman Mini Indonesia Indah, keris memiliki fungsi yang beragam dan hal
ini
ditunjukkan oleh beragamnya bentuk keris yang ada.
1.
Keris sebagai atribut keprajuritan.
|
|
4
Di Surakarta dan Yogyakarta keris biasa digunakan sebagai atribut keprajuritan.
Mulai dari perwira tinggi sampi prajurit –
prajurit biasa diharuskan menyandang keris
dalam upacara adat, pisowangan
(apel), ketika berperang, dan upacara lainnya. Seorang
perwira tinggi bisa menyandang 3 keris sekaligus untuk atribut keprajuritannya.
2.
Keris sebagai kelengkapan busana adat.
Keris merupakan salah satu kelengkaan busana adat baik di Jawa bahkan sampai
keluar Pulau Jawa. Biasa dipakai pada upacara adat, ketika menghadap raja, perkawinan,
dan lain sebagainya.
3.
Keris sebagai senjata.
Fungsi ini adalah fungsi yang paling dangkal dan paling dasar dalam sebuah
adat terutama adat jawa. Keris tergolong sejanta ruket atau senjata perkelahian jarak
dekat. Contohnya dalam perang melawan Belanda di Bali dalam Perang Puputan dan
Klungkung pada abad ke – 20.
4.
Keris sebagai alat hukuman mati.
Ketika para Raja masih berkuasa di Pulau Jawa beratus –
ratus tahun yang
lalu, keris biasa juga digunakan untuk mengeksekusi kriminal kerajaan. Biasanya
menggunakan keris keraton. Keris itu ditusukkan dari punggung dibawah tulang
belikat hingga menembus jantung dan dada.
5.
Keris sebagai Wakil Pribadi.
Dalam upacara perkawinan adat Jawa, apabila seorang calon mempelai pria
tidak dapat hadir karena sakit atau berhalangan akibat tugas Negara, maka upacara
perkawinan antara sang mempelai pria dan wanita tetap bisa berlangsung dengan
catatan saang mempelai pria diwakilkan oleh keris nya. Tetapi adat ini sudah jarang
dilakukan.
6.
Manifestasi Falsafah.
Suku Jawa tergolong gemar berfalsafah dan berolah batin. Oleh karena itu
bentuk – bentuk keris dan perlengkapannya hamper selalu dikaitkan dengan berbagai
nilai falsafah.
|
|
5
7.
Keris sebagai Atribut Utusan Raja.
Apabila seorang mendapat tugas dari Raja, misalnya untuk mewakilinya hadir
dalam suatu penting atau tugas kenegaraan yang berat dan mengandung resiko, maka
kepada orang tersebut dipinjamkan salh satu keris milik Raja, yang bobot spritualnya
sepadan dengan tugas yang diberikan.
8.
Keris sebagai Lambang Persaudaraan dan Perkawinan.
Cinderamata yang dianggap paling bermakna pada zaman dulu adalah keris.
Karena itu para pejabat Negara Republik Indonesia biasanya menggunankan keris
sebagai tanda mata bagi sesame pejabat dari negara sahabat.
2.1.4
Pentingnya Keris bagi Masyarakat Jawa.
Perkembangan budaya keris selalu berjalan seirang denga meningkatnya penghayatan
terhadap keberadaan keris itu sendiri dalam tata niali kehidupan pada zaman itu. Dalm
masyarakat Jawa, keris adalah lambing pelengkap jati diri seorang lelaki dewasa. Mengutip
dalam bukunya (Sir Thomas Stamford Raffles, The History of Java,
1830), menulis :
“….seorang lelaki Jawa yang tidak menyandang keris ibarat telanjang…” senada dengan
kalimat itu ada pula semacam pegangan hidup yang mengatakan bahwa seorang lelaki jawa
belum lengkap hidupnya bilamana belum memiliki curiga (keris), turangga (kuda), wisma
(rumah), wanita (istri) dan kukila (burung).
2.1.5
Keris dan Bagian – bagiannya.
Menurut penelitian dan observasi yang penulis lakukan di Museum Pusaka, Taman
Mini Indonesia Indah, berikut adalah bagian – bagian keris.
a.
Jejeran.
Jejeran (istilah Surakarta) atau deder (Yogyakarta) atau hulu keris banyak
macamnya, terbuat dari kayu, tulang, tanduk, atau gading. Tetapi yang paling banyak
dijumpai adalah dari kayu.
|
 6
Gambar 2.1 Jejeran Keris dari Kayu.
N0PCvE/s1600/_DSC0916.JPG
b.
Gandik
Salah satu bagian bawah atau pangkal bilah (sor – soran) ragam bentuknya antara
lain : lugas, lugas panjang, laler mengeng, panji penganten, kembar, kikik, singa, barong,
dan lain lain.
Gambar 2.2 Gandhik Keris Parung Sari.
Sumber Gambar : http://s691.photobucket.com/albums/vv273/sinomku/Parungsari2.jpg
c.
Mendak.
Mendak atau uwer adalah betuk cincin yang dipasang melingkari pesi, terletak
antara jejeran dan ganja. Ada teori menyebutkan bahwa mendak ini adalah perkembangan
dari kegunaan karah, yakni cincin logam yang dipasang pada tangkai pisau, arit, dan
semcamnya untuk meperkuat tangkai kayu agar tidak pecah.
|
 7
Gambar 2.3 Mendak Keris.
Sumber Gambar :
_1_thumb2_lgw.jpg
d.
Pamor.
Pamor adalah hiasan tau motif atau ornament yang terdapat pada bilah tosan aji.
Hiasan ini terbentuk bukan karena diukir atau diserasah, atau dilapis tetapi karena teknik
tempaan yang menyatukan beberapa unsur logan berlainan. Teknik ini hanya bisa
dikuasai oleh para Mpu di wilayah Nusantara saja.
Gambar 2.4 Pamor Pedaringan Kebak Ngawat.
Sumber Gambar : http://2.bp.blogspot.com/-J3NPqaoCAT0/T5orpuoUbjI/AAAAAAAAC-
w/jtyB_S1Jxcg/s1600/pamor+keris.JPG
e.
Ganja.
Bagian alas/ dasar disebut ganja, yang posisinya memang hamper seperti ganjal,
serta dapat muncul dalam beberapa variasi bentuk, menurut penampangnya. Dari samping
dikenal bentuk : sebit rontal, wilut, dhungkul, kelab lintah, dan, sepang. Dari atas dikenal
: nguceng mati, nyebit ron tal, nyirah cecak, nyirah tekek, nyangkem kodhok.
|
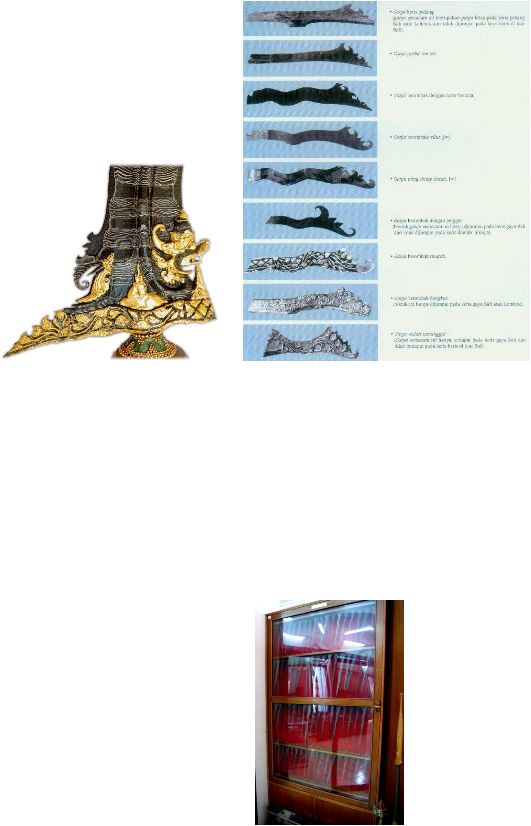 8
Gambar 2.5 Keris Nagasasra dengan Ganja Berombak Tinatah dan bentuk – bentuk ganja.
Sumber Gambar : https://s3.amazonaws.com/images.ecwid.com/images/1231108/161130266.jpg dan
f.
Bilah Keris.
Bilah keris sebenarnya terdiri dari tiga bagian : badan bilah (awak –
awak atau
wilah), ganja, dan pesi. Dan terdiri atas 3 unsur logam, yakni besi, bahan pamor, dan baja.
Dan ketiga bahan tersebut yang menjadi dasar ketika seseorang ingin menilai mutu
sebuah keris.
Gambar 2.6 Foto Bilah – Bilah Keris koleksi Museum Pusaka, TMII.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
|
 9
g.
Warangka.
Bagi orang Jawa warangka dan perabot keris yang lain hamper sama pentingnya
dengan bilah keris sendiri. Keris ligan atau keris telanjang tanpa warangka tidak bisa
disebut keris dalam keadaan utuh. Begitu pula sebaliknya.
Gambar 2.7 Warangka Keris.
Sumber Gambar : http://4.bp.blogspot.com/-
7R9BjdjvKIo/UBC5ikKRLWI/AAAAAAAABR4/zUxU7GD7e1o/s1600/IMG_2674.JPG
h.
Pendok.
Hampir semua keris warangka Surakarta dan Yogyakarta (kecuali sandhang
walikat) dilengkapi dengan pendhok, semacam sarung logam pembungkus gandar
sehingga sering pula disebut kandelan (penebal atau pelapis). Pendhok dibuat dari
lembaran logam yang dibentuk menyerupai pipa yang pipih dan meruncing kea rah ujung
(methit) sehingga dapat disarungkan pada gandar.
Gambar 2.8 Pendok Keris.
Sumber Gambar : http://www.geocities.ws/javakeris/images/Pendok.jpg
|
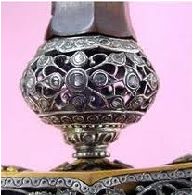 10
i.
Selut.
Selut adalah cincin ekstra untuk menambah keindahan jejeran, namun bukan
merupakan suatu keharusan.
Gambar 2.9 Selut Keris.
Sumber Gambar : http://4.bp.blogspot.com/-DRuujsYg7-
E/T0lQIEN2hEI/AAAAAAAAAGc/Hrp5xOe5YM4/s1600/e993n.jpg
2.1.6
Ragam Keris Pusaka Indonesia.
Menurut penelitian dan observasi yang penulis lakukan di Museum Pusaka, Taman
Mini Indonesia Indah, berikut adalah ragam keris pusaka.
a.
Keris Pusaka Nagasasra dan Sabuk Inten.
Keris Pusaka Nagasasra dan Sabuk Inten adalah dua benda pusaka peninggalan
Raja Majapahit. Nagasasra adalah nama salah satu dapur (bentuk) keris luk tiga belas dan
ada pula yang luk-nya berjumlah sembilan dan sebelas, sehingga penyebutan nama dapur
ini harus disertai dengan menyatakan jumlah luk-nya. Salah satu pembuat keris dengan
dapur Nagasasra terbaik, adalah karya mpu Ki Nom, merupakan seorang empu yang
terkenal, dan hidup pada akhir zaman kerajaan Majapahit sampai pada zaman
pemerintahan Sri Sultan Agung Anyokrokusumo di Mataram, tetapi ada sebagian ahli lain
yang mengatakan bahwa Ki Supo Anom pada zaman kerajaan Mataram, sebenarnya
adalah cucu dari empu Supo Anom yang hidup pada zaman Majapahit, dan golongan ini
menyebut Ki Nom dengan sebutan Ki Supo Anom II, dan yang hidup di zaman Majapahit
disebut Ki Supo Anom I. Dapur Sabuk Inten, seperti juga dapur Nagasasra mempunyai
luk tiga belas dengan ciri-ciri yang berbeda yaitu mempunyai sogokan, kembang kacang,
lambe gajah dan greneng.
|
 11
Gambar 2.10 Keris Pusaka Nagasasra
Gambar 2.11 Keris Pusaka Sabuk Inten.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
b.
Keris Mpu Gandring.
Keris Mpu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat
berdirinya Kerajaan Singhasari di daerah Malang, Jawa Timur sekarang. Legenda ini
tercatat dalam Kitab Pararaton. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan
korban dari kalangan elit Singasari termasuk pendiri dan pemakainya, Ken Arok.
Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama
Mpu Gandring, atas pesanan Ken Arok, salah seorang tokoh penyamun yang menurut
seorang brahmana bernama Lohgawe adalah titisan Dewa Wisnu. Ken Arok memesan
Keris ini kepada Mpu Gandring dengan waktu lima bulan, yang merupakan pekerjaan
hampir mustahil dilakukan oleh para mpu (gelar bagi seorang pandai logam yang sangat
sakti) pada masa itu. Namun Mpu Gandring menyanggupinya kaerna yakin dengan
kemampuan yang dimilikinya. Setelah selesai membuat Keris dengan bentuk dan wujud
yang sempurna bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan
melebihi senjata apa pun dimasa itu, namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat,
Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah lima bulan dan harus
diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut dan terakhir Keris tersebut
ditusukkannya pada Mpu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji (karena
sarung keris atau Warangkanya itu belum selesai dibuat)
Dalam keadaan sekarat, Mpu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa Keris
tersebut akan meminta korban nyawa keturunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya,
keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singhasari yang
merupakan keturunan Ken Arok. Dan sampai saat ini, menurut beberapa artikel, Keris
buatan Mpu Gandring itu tidak ditemukan keberadaannya.
|
 12
c.
Keris Kala Munyeng.
Keris Kala Munyeng adalah salah satu keris legendaris di bumi Nusantara ini.
Satu peninggalan sejarah di Gresik yang diyakini oleh masyarakat sebagai benda pusaka
adalah Keris Kyai Kala munyeng. Menurut kepercayaan masyarakat keris ini merupakan
keris mistik. Konon, menurut cerita sejarah, keris ini adalah penjelamaan dari pena
(kalam) milik Kanjeng Sunan. Keris ini pernah dibawa ke Negeri Belanda pada akhir
abad ke-17 M, karena dianggap mampu melahirkan semangat resistensi terhadap kompeni
Belanda, kemudian dikembalikan ke Gresik pada tahun 1772. Keris ini sampai sekarang
tersimpan di makam Sunan Giri dan replikanya tersimpan di Museum Daerah Kabupaten
Gresik.
Gambar 2.12 Foto Keris Kala Munyeng, TMII.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
d.
Keris Pusaka Condong Campur.
Keris pusaka ini adalah salah satu keris pusaka milik Kerajaan Majapahit yang
banyak disebut dalam legenda dan folklor. Keris ini dikenal dengan nama Kanjeng Kyai
Condong Campur. Keris ini merupakan salah satu dapur keris lurus. Panjang bilahnya
sedang dengan kembang kacang, satu lambe gajah, satu sogokan di depan dan ukuran
panjangnya sampai ujung bilah, sogokan belakang tidak ada. Selain itu, keris ini juga
menggunakan gusen dan lis-lis-an. Condong Campur merupakan suatu perlambang
keinginan untuk menyatukan perbedaan. Condong berarti miring yang mengarah ke suatu
titik, yang berarti keberpihakan atau keinginan. Sedangkan campur berarti menjadi satu
atau perpaduan. Dengan demikian, Condong Campur adalah keinginan untuk menyatukan
suatu keadaan tertentu.
|
 13
Gambar 2.13 Keris Pusaka Condong Campur
.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
e.
Keris Pusaka Setan Kober.
Kyai Setan Kober adalah nama keris milik Adipati Jipang, Arya Penangsang.
Keris ini dikenakan pada waktu ia perang tanding melawan Sutawijaya. Sama seperti
Keris Mpu Gandring tidak diketahui sesungguhnya dapur atau bentuknya seperti apa.
Keris Pusaka Setan Kober dibuat oleh Mpu Supo Mandrangi , putra seorang mpu di
Tuban , Jawa Timur. Supo Mandrangi kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi
murid Sunan Ampel, dengan tetap membawa kemampuannya membuat Keris. Keris
Pusaka Setan Kober, aslinya bernama Bronggot Setan Kober, dibuat pada awal kerajaan
Islam Demak Bintoro. Dan Keris tersebut kemudian dimiliki oleh Djafar Shodiq atau
Sunan Kudus yang kemudian diberikan pada murid kesayangannya Arya Penangsang,
Adipati Jipang Panolan.
Keris Pusaka Setan Kober sangat ampuh, tapi membawa hawa
panas, sehingga yang membawa keris tersebut akan mudah marah. Sifat pemarah Arya
Penangsang pun sebenarnya terbawa oleh hawa pusakanya itu. Sampai sekarang
keberadaan keris ini tak diketahui, seperti halnya Keris Mpu Gandring yang misterius.
Padahal keris –
keris maupun pusaka –pusaka legendaris pada masa kuno diwarisi oleh
Keraton Surakarta maupun Keraton Yogjakarta tapi untuk Keris Setan Kober ini tidak
pernah diceritakan setelah kematian Arya Penangsang. Demikian juga dapur Keris Setan
Kober juga tidak di tiru oleh para mpu keris.
f.
Keris Sengkelat.
Keris Sengkelat adalah keris pusaka luk tiga belas yang diciptakan pada zaman
Majapahit (1466 –
1478), yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabhumi (Brawijaya
V) karya Mpu Supa Mandagri. Sedikt cerita tentang keris ini. Mpu Supa adalah salah satu
santri Sunan Ampel. Konon bahan untuk membuat Kyai Sengkelat adalah cis, sebuah besi
|
 14
runcing untuk menggiring onta. Konon, besi itu didapat Sunan Ampel ketika sedang
bermunajat. Ketika ditanya besi itu berasal darimana, dijawablah bahwa besi itu milik
Muhammad SAW. Maka diberikanlah besi itu kepada Mpu Supa untuk dibuat menjadi
sebilah pedang. Namun sang mpu merasa sayang jika besi tosan aji ini dijadikan pedang,
maka dibuatlah menjadi sebilah keris luk tiga belas dan diberi nama Kyai Sengkelat.
Setelah selesai, diserahkannya kepada Sunan Ampel. Sang Sunan menjadi kecewa karena
tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Menurutnya, keris merupakan budaya
Jawa yang berbau Hindu, seharusnya besi itu dijadikan pedang yang lebih cocok dengan
budaya Arab, tempat asal agama Islam. Maka oleh Sunan Ampel disarankan agar Kyai
Sengkelat diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Ketika Prabu Brawijaya V menerima
keris tersebut,
sang Prabu menjadi sangat kagum akan kehebatan keris Kyai Sengkelat.
Dan akhirnya keris tersebut menjadi salah satu piyandel (maskot) kerajaan dan diberi
gelar Kangjeng Kyai Ageng Puworo, mempunyai tempat khusus dalam gudang pusaka
keraton.
Gambar 2.14 Keris Sengkelat.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
2.1.7
Beberapa Keris dari pelosok Nusantara.
Menurut penelitian dan observasi yang penulis lakukan di Museum Pusaka, Taman
Mini Indonesia Indah, berikut adalah ragam keris dari beberapa provinsi.
a.
Sumatera Barat.
Keris Bahari adalah salah satu keris asal Sumatera Barat. Keris Bahari bentuk
bilahnya lebih kecil dan panjang. Keris ini memiliki dhapur (bentuk) Bahari, tangguh
(pembuat) keris berasal dari Majapahit abad ke – 13. Memiliki Pamor Pendaring Bebas.
|
 15
Gambar 2.15 Foto Keris Bahari Sumatera Barat, TMII.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
b.
Riau.
Dari Provinsi Riau ada Keris Bahari. Memiliki dhapur Sepang, tangguh Mataram,
Pamor Sanak. Dapur Sepang dalam keyakinan para pecinta keris kebanyakan mempunyai
tuah/ angsar., membantu membina kerukunan suami istri.
Gambar 2.16 Foto Keris Bahari Riau, TMII.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
c.
Bali.
Bali juga memiliki kerisnya sendiri. Keris di Bali terkenal pada saat Perang
melawan Penjajah Belanda. Perang tersebut adalah Perang Puputan dan Perang
Klungkung sekitar abad ke – 20. Dibawah ini adalah keris dengan dhapur Sinom Wora
Wari (kiri) dan dhapur Kolowijo.
|
 16
Gambar 2.17 Foto Keris Bali, TMII.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
d.
Sulawesi Tengah.
Ini adalah keris dari Sulawesi Tengah. Keris ini adalah keris yang biasa digunakan
pada zaman kerajaan – kerajaan masih berjaya di Sulawesi.
Gambar 2.18Foto Keris Sulawesi Tengah, TMII.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
e.
Sulawesi Tenggara.
Keris ini berasal dari Sulawesi Tenggara. Keris ini memiliki luk-9. Juga dipakai
oleh para perwira tinggi untuk upacara dan acara penting di kerajaan pada zaman dulu.
Gambar 2.19 Foto Keris Sulawesi Tenggara, TMII.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
|
 17
2.1.8
Keris Indonesia diakui dunia international.
Gambar 2.20 Foto Penghargaan UNESCO untuk Keris Indonesia, TMII.
Sumber Gambar : foto observasi lapangan di Museum Pusaka, TMII.
Melihat begitu banyak bukti sejarah mengenai keris dan adanya keterkaitan yang kuat
antara benda pusaka ini dengan denyut nadi masyarakat Indonesia, akhirnya pemerintah
Indonesia mengajukan Keris sebagai salah satu warisan dunia kepada Badan Perserikatan
Bangsa –
Bangsa melalu UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural
Organization). Tentu melalui proses yang panjang dan penantian yang lama. Akhirnya pada
tanggal 25 November 2005 di Paris dengan ditanda tangani oleh Koichiro Maatsura, Director
–
General of UNESCO, Keris Indonesia diakui menjadi karya agung warisan kemanusiaan
oleh dunia international.
2.1.9 Film Pendek Sejenis.
Animated Series Anak Bangsa “Keris Sakti”.
Animated Series Anak Bangsa episode Keris Sakti menceritakan tentang 5 orang anak
kecil yang menemukan sebuah keris yang tertancap ditanah. Mereka satu per satu berusaha
mencabut keris itu namun tidak berhasil. Akhirnya dengan bekerja sama
mereka berhasil
mencabut keris itu. Pada akhir dari animasi tersebut muncul sebuah trivia mengenai keris
secara umum.
Gambar 2.21 Animated Series Anak Bangsa “Keris Sakti”.
Sumber Video : https://www.youtube.com/watch?v=KuV2yuScpdE.
|
 18
2.2 Landasan Teori.
2.2.1 Teori Prinsip Dasar Animasi.
Bedasarkan buku (Thomas, Disney animation: the illusion of life, 1981, p.48),
fundamental prinsip animasi terdiri dari 12 yaitu :
Straight ahead action and pose to pose.
Timing.
Secondary action.
Ease In and Out.
Anticipation.
Follow through and overlapping action.
Arc.
Exaggeration.
Squash & Strech.
Staging.
Appeal.
Solid Drawing.
2.2.2
Teori Warna.
Pada buku (Color Basic, 2007, p.10) “color is a visual sensation that involves three
elements : a light source, an object , a viewer”.
Pemilihan warna bukanlah sebuah hal yang bisa dilakukan secara sembarangan.
Ketika membangun suatu identitas visual, salah satu hal yang penting adalah mengetahui
bagaimana warna mempengaruhi audience dan hasil desain kita.
2.2.2.1 Arti dan Fungsi Warna.
Berikut adalah asosiasi dan psikologi warna bedasarkan buku (Color Basic, 2007, p.29 –
50).
Biru
Hijau
Kuning
Hitam
Positif : kuat, kreativtas, magis, idealis, fokus
Negatif : terlalu kuat , superior, merusak, menekan.
|
|
19
Hitam dapat menggambarkan keheningan, kematangan berpikir dan kedalaman akal. Hitam
juga menampilkan kesan elegan dan mewah.
Ungu
Pink
Orange
Merah
Coklat
Warna coklat dihubungkan dengan kesederhanaan yang abadi. Coklat identik dengan
tanah dan kayu, sehingga penggunaan warna coklat memberi perasaan dekat dengan
lingkungan alam. Coklat juga mencerminkan tradisi dan segala sesuatu yang berbau
kebudayaan.
Netral
Warna netral tidak bersifat dominan dan apabila dipadukan dengan warna lain, warna
netral akan menjadi warna latar belakang. Ada beberapa warna yang dapat dikategorikan
sebagai warna netral : abu –
abu, krem, beige (cokelat keabu –
abuan), cokelat, hitam dan
putih.
Putih
Positif : jujur, bersih, polos, higienis
Negatif : monoton, kaku
Putih adalah warna yang melambangkan kesucian. Secara psikologis, putih melambangkan
kejujuran, ketulusan dan keiklasan. Warna putih cenderung seperti tanpa warna, sehingga
setiap warna yang berada diatas putih menjadi warna yang menonjol karena putih berperan
sebagai latar belakangnya.
2.2.3
Teori Teknik dan Komposisi Fotografi / Sinematografi.
Dikutip dari (Teknik dan Komposisi Fotografi / Sinematografi, 2014), Fotografi
adalah kegiatan mengambil dan Sinematografi adalah fotografi gambar bergerak.
2.2.3.1 Teori Komposisi.
Komposisi dalam menurut (Arbain Rambey, 2005) adalah masalah menempatkan
berbagai benda yang ada dalam frame sebuah scene. Komposisi bisa dibuat dengan mengatur
|
|
20
benda yang ada dalam sebuah frame, atau mengatur angle (sudut pengambilan) dan pilihan
lensa untuk obyek yang bergerak.
2.2.3.2 Dasar - Dasar Sinematografi.
Dikutip dari (Teknik dan Komposisi Fotografi / Sinematografi, 2014), dasar – dasar
sinematografi yaitu :
Framing : Kegiatan membatasi adegan atau mengatur kamera sehingga mencakup ruang
penglihatan yang diinginkan
Angle : Sudut pengambilan Gambar
Shot size : Cara pengambilan gambar
Komposisi : Penyusunan elemen –
elemen dalam sebuah pengambilan gambar, termasuk
didalamnya adalah warna dan objek.
2.2.3.3 Kamera Subjektif / Objektif.
Kamera S. : Cara pengambilan gambar, seolah – olah audiens menjadi bagian dari peran
tertentu
Kamera O. : Cara pengambilan gambar, dimana audiens hanya menjadi pengamat.
2.2.3.4 Shot Size.
Extreme Long Shot
Medium Close Up
Long Shot
Close Up
Medium Long Shot
Big Close Up
Medium Shot
Extra Close Up
2.2.4 Pengertian Typografi.
Tipografi (dalam bahas inggris : Typography) adalah perpaduan antara ilmu seni dan
teknik mengatur tulisan, agar maksud serta arti tulisan dapat tersampaikan dengan baik secara
|
|
21
visual kepada pembaca. Menurut (Roy Brewer, 1971) dapat memiliki pengertian luas yang
meliputi penataan dan pola halaman, atau setiap barang cetak. Selanjutnya beliau
menjelaskan bahwa
“Tipografi dapat didefinisikan sebagai keterampilan mengatur bahan
cetak secara baik dengan tujuan tertentu; seperti mengatur tulisan, membagi-bagi ruang/
spasi, dan menata/
menjaga huruf untuk membantu secara maksimal agar pembaca
memahami teks.
2.2.4.1 Jenis – Jenis Huruf.
Berikut ini beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh (James
Craig, 2004) antara lain :
Roman
Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip pada
ujungnya. memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya.
Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai dan feminim.
Egyptian
Jenis huruf yang memiliki ciri kaki/sirip/serif yang berbentuk persegi seperti papan
dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulakn adalah
kokoh, kuat, kekar dan stabil.
Sans Serif
Pengertian San Serif adalah tanpa sirip/serif, jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip
pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama.
Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer sama.
Script
Huruf Script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau
pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah sifast
pribadi dan akrab.
Miscellaneous
Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada.
Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah
dekoratif dan ornamental.
2.2.5 Teori dan Fungsi Edukasi.
|
|
22
Menurut dalam bukunya (Stella van Petten Henderson, Introduction to Philosophy of
Education, 1990) , pengertian pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri
dan warisan sosial. Menurut beliau pendidikan memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan
dengan perkembangan sosial seseorang seperti sumber inovasi sosial, sarana pengajaran
tentang adanya berbagai corak dan kultur kepribadian, transmisi kebudayaan, menjamin
integrasi sosial dan memilih serta mengajarkan berbagai peranan dalam kehidupan sosial.
2.2.6 Teori Taxonomi Bloom.
Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu tassein yang berarti
mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan.
(Benjamin Samuel Bloom, 1956) berhasil mengenalkan kerangka konsep
kemampuan berpikir yang dinamakan Taxonomy Bloom. Jadi, Taksonomi Bloom adalah
struktur hierarkhi yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang
tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi
lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi tiga
domain/ ranah kemampuan intelektual (intellectual behaviors) yaitu :
Ranah Kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti
pengetahuan, dan keterampilan berpikir.
Ranah Afektif mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai,
minat, motivasi, dan sikap.
Ranah Psikomotorik berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan
keterampilan motorik/ kemampuan fisik, berenang, dan mengoperasikan mesin.
Salah seorang murid Bloom, (Lorin Anderson Krathwohl, 1994) dan para ahli
psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan
zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi
Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif.
Ranah Kognitif Revisi Taxonomi Bloom sendiri dibagi menjadi 6 yaitu :
Remembering (mengingat).
Understanding (memahami).
Applying (menerapkan).
Analyzing (menganalisis).
Evaluating (menilai).
Creating (mencipta).
|
|
23
Dalam pembuatan film ini penulis menggunakan pendekatan kognitif sebagai dasar dalam
memperkenalkan Keris Indonesia kepada generasi muda bangsa.
2.3 Analisa.
2.3.1
Faktor Pendukung dan Penghambat.
2.3.1.1 Faktor Pendukung.
i.
Animasi kini banyak diminati masyarakat sehingga membuat sumber pengetahuan
dengan media animasi dapat menjadi daya tarik dalam masyarakat terutama generasi
muda.
ii.
Masih jarang edukasi animasi yang mengangkat tentang keris Indonesia.
iii.
Masih sedikit generasi muda yang tahu banyaknya ragam dan jenis keris yang ada di
Indonesia.
iv.
Dengan media animasi, pesan dari anmasi edukasi ini dapat diterima dan dipahami
oleh para penonton khususnya generasi muda.
2.3.1.2 Faktor Penghambat.
Sedikitnya minat masyarakat terutama generasi muda untuk mengunjungi Museum
untuk mempelajari dan mengenalkan nilai – nilai historis kepada anak – anak mereka.
Kurangnya sumber informasi yang didapat untuk mengenal lebih dalam mengenai
Keris – Keris Pusaka.
Kurang diperkenalkan Keris ini sebagai suatu senjata asli nusantara yang sudah diakui
dunia.
|