|
BAB II TINJAUAN
TEORI
2.1. Terminal Peti Kemas
Terminal peti
kemas berfungsi
sebagai transfer
interface
antara
kapal
pengangkut
peti
kemas dengan
moda transportasi lainnya. Selain itu terminal peti kemas juga berfungsi
sebagai tempat penyimpanan sementara peti kemas dan menangani semua data yang
terkait
dengan
status
peti
kemas
yang
diperlukan oleh semua pihak yang terkait
dengannya.
Peti
kemas
(containerization)
telah
menjadi
salah
satu
pilihan
utama
dalam
pengiriman
kargo
dalam
perdagangan
dunia.
Data
statistik
yang
menunjukkan
bahwa
lebih dari 90% kargo internasional diangkut melalui moda laut dengan pelabuhan sebagai
transfer
interfacenya (Winklemans, 2002). Selain itu kargo dan pelayaran dari seluruh
dunia juga
mengalami kecenderungan peningkatan secara eksponensial (Henesey et al.,
2003). Dalam rangka ini terminal peti kemas berusaha mangatasi berbagai hambatan agar
produktivitas operasional meningkat dan akhirnya kapasitas terminal menjadi lebih
tinggi. Mempercepat vessel turn-around time dan pertukaran informasi merupakan usaha
riil untuk meningkatkan kapasitas terminal tersebut.
Sebuah
terminal
peti
kemas
memerlukan
seperangkat
peralatan
dimana
pelabuhan
laut tradisional tidak memerlukannya. Peralatan tersebut terdiri atas:
|
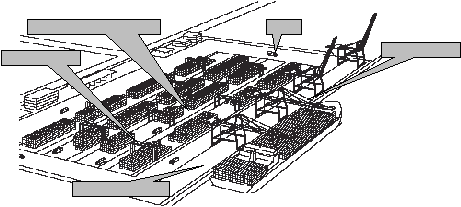 1. Shore (quay) crane yang diperlukan untuk membongkar atau memuat peti kemas
dari atau ke dalam kapal.
2. Spreader, yaitu peralatan yang merupakan bagian dari quay crane yang berfungsi
untuk mengangkat peti kemas dalam berbagai ukuran.
3.
Truk untuk mengangkut peti kemas dari kapal yang ada di dermaga yang
dipindahkan melalui quay crane ke
lapangan penumpukan (container yard; CY)
atau sebaliknya.
4. Transtainer atau Rubber Tyre Gantry Crane (RTG) yang memindahkan peti
kemas dari truk dan menumpuknya (stack) di lapangan penumpukan atau
sebaliknya.
5. Sistem informasi untuk mencatat dan merekam lokasi dan semua proses transaksi
yang telah dilakukan terhadap semua peti kemas. Proses ini dilakukan melalui
Hand
Held
Terminal
(HHT)
dan Vehicle Mounted
Terminal
(VMT)
yang
terhubung dengan Sistem LAN melalui gelombang RF.
Lap. Penumpukan / CY
Truk
Transtainer
Quay Crane
Dermaga / Berth
Gambar 2.1. Tata Letak Terminal Peti Kemas.
|
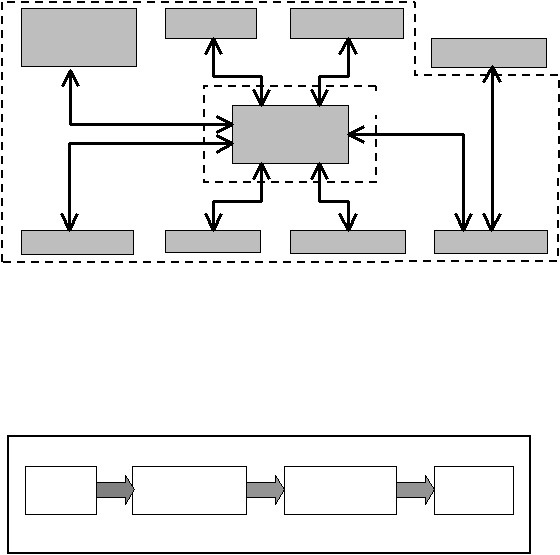 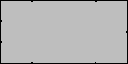 Dalam melaksanakan jasa pelayanan bongkar muat, terminal peti kemas memiliki
berbagai fungsi pelayanan seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2.
Penyusunan /
Pembongkaran
muatan
Parkir
Penahanan
Fungsi antarterminal
Angkutan
Fungsi intern terminal
Transfer
Pemeliharaan
Perbaikan
Penimbangan
Pemeriksaan
(
Sumber: Dirgahayu, 1999, “Petunjuk Penanganan Kapal dan Barang di Pelabuhan”)
Gambar 2.2. Diagram Antar Fungsi Terminal Peti Kemas
2.1.1. Pelayanan Terminal Peti Kemas
Proses
Kontrak
Persiapan
Bongkar muat
Operasional
Bongkar Muat
Penagihan
Ga
mba
2.3. Alur Proses Bisnis Terminal Peti Kemas.
r
Sumber : TPK Koja
Proses bisnis bongkar muat di terminal peti kemas secara umum digambarkan seperti
ditunjukkan pada Gambar 2.3. Proses bisnis dimulai dengan proses kontrak, lalu
|
|
dilanjutkan dengan persiapan bongkar muat, operasional bongkar muat, dan terakhir
penagihan.
Untuk melaksanakan proses bisnis tersebut, maka terminal peti kemas memiliki
berbagai jenis pelayanan, yaitu :
1. Penyandaran kapal (berthing service)
2. Pengeluaran peti kemas (container delivery)
3. Pemasukan peti kemas (container entry)
4. Over brengen (OB)
5. Pemeriksaan Bea dan Cukai (behandle)
6. Ubah status peti kemas (status changing)
7. Alih kapal (transhipment)
8. Penumpukan awal (entry stacking)
Untuk
melaksanakan berbagai pelayanan tersebut, terminal peti kemas
memerlukan
pengelolaan terminal yang dilaksanakan oleh bagian pelayanan yang terdiri atas:
1. Account service
2. Front office
3. Rencana dan pengendalian (planning & controlling)
4. Pintu (gate)
5. Pelayanan fiat bea cukai (custom approval)
6. Pelayanan di lapangan (yard service)
7. Pelayanan klaim (claim service)
8. Ketersediaan peralatan (readiness equipment)
9. Keamanan
|
|
Sebagai penghubung antara terminal peti kemas dengan pihak yang berkepentingan
dengan peti kemas, khususnya perusahaan pelayaran atau cargo owner, maka terminal
peti kemas menyediakan berbagai informasi yang meliputi:
1. Permintaan open stack
2. Permintaan closing time
3. Informasi kapal
4. Hasil rapat kapal
5. Pengaduan
2.1.2. Dimensi Pelayanan Peti Kemas
Pelayanan peti kemas memiliki 5 dimensi pelayanan yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Tangible,
yaitu
dimensi
terminal
peti
kemas
yang
meliputi keberadaan
fasilitas
fisik, sumber daya manusia, dan material komunikasi.
2. Reliability, yaitu dimensi yang menggambarkan kemampuan terminal peti kemas
dalam melakukan pelayanan secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
3.
Responsiveness, yaitu respon yang cepat terhadap permintaan atau keluhan
pelanggan.
4.
Assurance, yaitu dimensi yang menunjukkan pengetahuan dan kemampuan staf
dalam melaksanakan pelayanan secara meyakinkan.
5. Empathy, yaitu dimensi yang
menggambarkan tentang kepedulian dan perhatian
terminal
peti
kemas
terhadap
masalah
yang dihadapi
oleh pengguna jasa
atau
pihak yang berkepentingan.
|
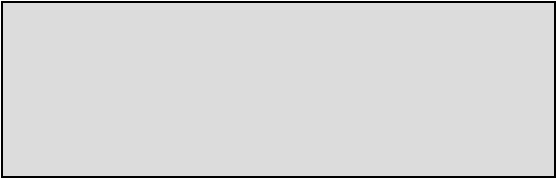 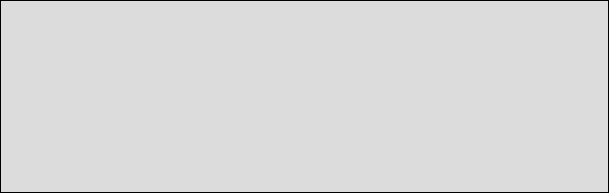 Peti
Kemas
Ship to
Shore
Transfer
Storage
Delivery/
Cycle
Receipt
Peti
Kemas
2.1.3. Operasional Bongkar Muat
Proses bongkar muat peti kemas di terminal menurut Henesey et al. (2003) secara umum
terdiri dari 4 sub sistem yaitu :
1. Kapal sandar ke dermaga (Ship to shore system)
2. Sistem Pemindahan Peti Kemas (Transfer Cycle System)
3. Sistem Penyimpanan Peti Kemas (Storage System)
4. Sistem Penerimaan dan Penyerahan Peti Kemas (Delivery/Receipt System)
Aliran masing-masing sistem pada realisasinya tidak seimbang bahkan terjadi proses
penyempitan (bottle neck) seperti tampak pada Gambar 2.4.
Sumber : Henesey et al. (2003)
Gambar 2.4. Subsistem Proses Operasional Bongkar Muat Peti Kemas.
Kinerja
masing-masing
subsistem sangat
dipengaruhi
oleh berbagai
faktor
yang
perlu dibahas secara terpisah, sehingga dapat diketahui faktor apa saja
yang hanya
berpengaruh pada masing-masing subsistem atau yang mempengaruhi subsistem lainnya.
Proses
bongkar
muat
peti
kemas pada subsistem Transfer Cycle
pada
dasarnya
dibedakan menjadi kegiatan bongkar dan kegiatan muat. Secara umum kegiatan tersebut
melibatkan 3 unit kerja terminal yaitu Pengendalian, Operasional Terminal, dan Billing.
|
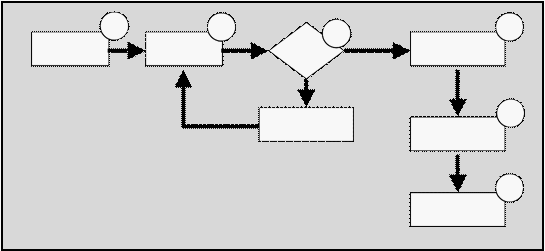 Bagian Operasional terminal terdiri dari dua
unit
yaitu
unit kerja Dermaga (Berth) dan
unit kerja Penumpukan Peti Kemas (Container Yard).
Alur kerja kegiatan bongkar dan kegiatan muat ditunjukkan seperti pada Gambar 2.5 dan
2.6.
Operasional
Terminal
1
Dokumen
Dermaga
2
Proses
Dermaga
3
T
Lap. Penumpukan
4
Bay plan
Sumber : TPK Koja
Bongkar
Problem
?
Y
Lapor sesuai
prosedur
Pengendalian
Penyimpanan
5
Laporan
Kegiatan
Pengendalian
6
Penagihan
Billing
Gambar 2.5. Kegiatan Bongkar Peti Kemas.
Alur kerja kegiatan bongkar dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.
Supervisor / KOL
menerima dan
mempelajari dokumen
yang
meliputi bayplan,
rencana crane, dan profil bongkar serta menyiapkan personil dan peralatan.
2.
Operator crane melaksanakan tugas bongkar peti kemas sesuai dengan rencana
crane
dan bayplan serta bekerja sama
dengan operator Solo dan Whiskey
khususnya
dalam pengecekan
peti
kemas
(segel
dan
kondisi)
yang
datanya
diperbarui (update) melalui Hand Held Terminal (HHT)
3.
Apabila ada masalah mengenai peti kemas, segera lapor ke Pengendalian
menggunakan prosedur yang sudah ada.
|
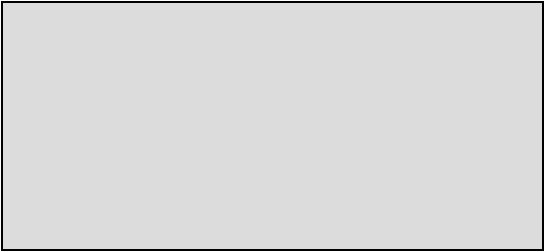 4. Kalau tidak ada masalah, peti kemas selajutnya disimpan di lapangan
penumpukan
menggunakan transtainer (RTG) sekaligus memperbarui datanya
melalui VMT sehingga dapat dimonitor oleh bagian Pengendalian.
5. Laporan yang dibuat meliputi:
a. Operasi per shift dan time sheet yang diverifikasi oleh KOL.
b.
Laporan
Realisasi
Bongkar
Muat
yang disesuaikan dengan Rekapitulasi
Bongkar
Muat.
Laporan
tersebut
harus
diparaf oleh
Supervisor
Operasional terminal dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak pelayaran
dan Manajer Operasi.
6. Laporan diserahkan ke Billing untuk dapat dilaksanakan penagihan jasa.
Operasional
Terminal
1
Dokumen
Bay plan
Lap. Penumpukan 2
Pengiriman
ke Dermaga
Lap. Penumpukan
3
T
Problem
?
Dermaga
4
Pemuatan
Peti Kemas
Sumber : TPK Koja
Y
Lapor sesuai
prosedur
Pengendalian
5
Laporan
Kegiatan
Pengendalian
6
Penagihan
Billing
Gambar 2.6. Kegiatan Muat Peti Kemas.
Alur kerja kegiatan muat dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Supervisor/Kolonel menerima dan mempelajari dokumen yang meliputi bayplan,
rencana crane, dan profil muat serta menyiapkan personil dan peralatan.
|
|
2. Operator RTG (Tango) menerima job list dan mengirimkan peti kemas ke
dermaga secara berurutan dan sekaligus melakukan proses update.
3.
Apabila ada masalah mengenai peti kemas, segera lapor ke Pengendalian
menggunakan prosedur yang sudah ada.
4. Kalau tidak ada masalah, operator
crane
melaksanakan
pemuatan
peti
kemas
sesuai
dengan
bayplan muat dengan berkoordinasi dengan Solo dan Whiskey,
dimana posisi peti kemas secara aktual akan diperbarui oleh Solo menggunakan
HHT.
5. Laporan yang dibuat meliputi:
a. Operasi per shift dan time sheet yang diverifikasi oleh Kolonel
b.
Laporan
Realisasi
Bongkar
Muat
yang disesuaikan dengan Rekapitulasi
Bongkar
Muat.
Laporan
tersebut
harus
diparaf oleh
Supervisor
Operasional terminal dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak pelayaran
dan Manajer Operasi.
6. Laporan diserahkan ke Billing untuk dapat dilaksanakan penagihan jasa.
2.1.4. Produktivitas
Proses
bongkar
muat
peti
kemas
memiliki indikator yang berfungsi untuk mengukur
produktivitas
sekaligus
menjadi
indikator
kualitas pelayanan peti kemas. Secara umum
kualitas
pelayanan
peti
kemas
diukur
sampai seberapa
lama
proses
bongkar
muat
peti
kemas tersebut dilaksanakan. Semakin cepat pelaksanaan bongkar dan muat, maka akan
membuat pihak pelayaran akan puas. Menurut
Rebollo et al. (2000), biaya
yang harus
|
|
dikeluarkan oleh
pihak
pelayaran
selama
bersandar
di
dermaga
adalah
sebesar $1.000
atau lebih per jam.
Selain
itu
kualitas peti kemas
juga
sangat dipengaruhi
oleh
ketepatan
dan
akurasi
bongkar muat. Hal-hal yang menurunkan kualitas bongkar muat adalah:
1.
Penandatanganan realisasi bongkar muat. Masalah yang dihadapi antara lain:
a. Kesesuaian jumlah box peti kemas.
b.
Penanganan terhadap peti kemas yang meliputi proses bongkar, muat,
shifting, dan lain-lain.
c. Penanganan terhadap jenis peti kemas, yang meliputi peti kemas 20’, 40’,
45’, OD, MI, Reefer, dan lain-lain.
2.
Masalah di gate, yang antara lain:
a. Dokumen peti kemas tidak lengkap
b.
Closing time terlampaui
c. Kelebihan berat
d.
Peti kemas rusak
e. Segel rusak
f.
Antrian panjang
3.
Kejadian terhadap peti kemas, yang meliputi:
a. Kehilangan isi peti kemas
b.
Kerusakan atau perubahan segel pengaman peti kemas
c. Kehilangan peti kemas
d.
Kecelakaan
|
|
Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas terminal dalam
melakukan proses bongkar muat adalah:
1. Box Crane per Hour (BCH) yaitu banyaknya box peti kemas yang dilaksanakan
oleh satu buah crane dalam waktu 1 (satu) jam. Indikator ini lebih ditujukan untuk
kepentingan pihak internal terminal.
2. Box Ship per Hour (BSH) yaitu banyaknya box peti kemas yang mampu
dibongkar dan/atau dimuat oleh pihak terminal terhadap satu buah kapal dalam
waktu satu jam. Indikator ini lebih ditujukan untuk kepentingan pihak pelayaran,
karena
semakin
tinggi
BSH
berarti
waktu
pelayanan
menjadi
semakin
pendek
yang
tentu
saja
akan
mempengaruhi turn-around time
dan mengurangi ongkos
sandar kapal.
3. Turn Round
Time (TRT) merupakan waktu yang diperlukan oleh sebuah kapal
dalam melakukan
proses
bongkar
muat
peti
kemas,
mulai
dari
saat
datang
ke
terminal hingga keluar dari terminal.
4. Berth
Ocupancy
Ratio
(BOR)
adalah
indikator pemanfaatan dermaga
(berth);
yang
dihitung
dengan
membagi
jumlah berthing
time (selang waktu yang
diperlukan untuk bongkar
muat) dengan dua kali jumlah jam dalam
satu tahun.
Semakin tinggi nilai BOR (dalam satuan presentase), semakin tinggi pemanfaatan
dermaga.
Kaitan antara BCH, BSH, dan TRT adalah:
Dengan
meningkatnya
BCH,
maka
peluang
untuk
meningkatkan
BSH
menjadi
semakin besar.
|
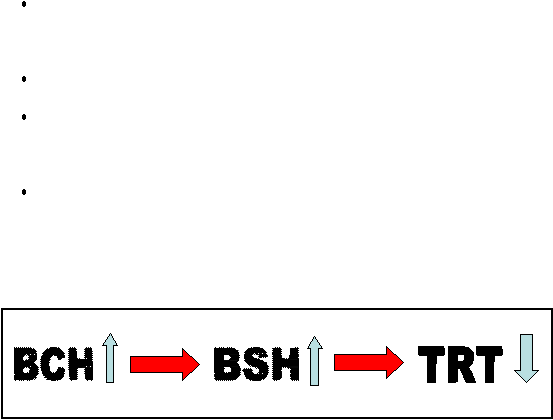 Dengan nilai BSH yang makin besar akan menyebabkan TRT menjadi lebih
rendah.
TRT yang lebih rendah menyebabkan berthing window menjadi semakin terbuka.
Dengan adanya tambahan berthing window
maka
terbuka peluang berthing
contract baru untuk shipping line yang secara reguler sandar di terminal.
Tambahan berthing contract berarti tambahan pendapatan.
Gambar 2.7. Kaitan antara Indikator Operasional BCH, BSH, dan TRT.
Indikator
BCH
dan
BSH
sangat
dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang dapat
dikendalikan oleh pihak terminal maupun
yang tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi
indikator tersebut adalah:
1. Faktor Kapal, yang meliputi jenis kapal dan jenis pelayaran.
2. Faktor Muatan, yang meliputi susunan peti kemas, variasi jenis peti kemas, dan
jumlah palka yang digunakan.
3. Faktor
Dermaga,
berapa
panjang
dermaga
yang
digunakan
oleh
kapal
(kade
meter) dan jumlah dermaga yang digunakan pada saat yang bersamaan.
|
|
4. Faktor Personil, yaitu jumlah personil yang tersedia dan terlibat dan kemampuan
personil.
5. Faktor Administrasi, yang terdiri dari closing time penerimaan peti kemas dan
pemeriksaan kepabeanan.
6. Faktor
Crane, yang terdiri dari jenis crane, ketersediaan crane, kondisi crane,
kondisi spreader, dan jumlah crane yang digunakan.
7. Faktor Truk, yang terdiri dari ketersediaan dan jumlah truk, baik untuk bongkar
maupun muat, serta kondisi truk.
8.
Faktor Teknologi Informasi, yang terdiri atas kesesuaian rencana bongkar
dan/atau muat, ketersediaan sistem, ketersediaan dan kondisi HHT.
9. Faktor Metoda Penanganan Peti Kemas, yang terdiri atas ketersediaan metoda
atau
SOP
baik
untuk
penanganan
kapal,
penanganan crane, penanganan truk,
maupun penanganan jenis peti kemas.
10. Faktor Alam, yang terdiri dari hujan, gelombang laut, dan angin.
2.1.5. Peralatan Bongkar Muat Peti Kemas
Terdapat tiga peralatan utama yang digunakan (terlibat) pada proses bongkar muat, yaitu
quay crane, transtainer, headtruck dan chassis.
-
Quay Crane atau Container Crane (CC)
Quay
crane
merupakan
alat
untuk
memindahkan peti kemas dari/ke kapal.
Terdapat
tiga
jenis
crane
yang
umum dan
masih
sama-sama
dipakai,
yaitu
Panamax, Post Panamax, dan Super Post Panamax. Masing-masing jenis crane ini
|
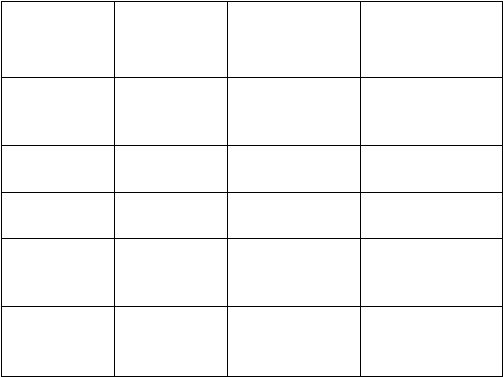 dibedakan dari kemampuan atau kinerjanya. Pada Tabel 2.1 ditunjukkan kinerja
dan spesifikasi ketiga jenis quay crane.
Saat ini TPK Koja memiliki enam buah quay crane, yang terdiri atas tiga
crane dari jenis Panamax, dua crane Post Panamax, dan satu crane Super Post
Panamax.
Pada
crane
terdapat
spreader, yaitu bagian yang mengaitkan peti kemas
pada
crane.
Jenis
spreader dapat
diganti untuk disesuaikan dengan jenis peti
kemas. Peti kemas khusus, seperti OD, akan menggunakan spreader yang berbeda
dengan yang digunakan untuk peti kemas standar.
Tabel 2.1. Perbandingan Data Kinerja Quay Crane Panamax, Post Panamax, dan
Super Post Panamax.
Deskripsi
Panamax
Post Panamax
Super Post
Panamax
Rows on ship
deck
Max 13
Max 18
22 -24
Lifted load
40 ton
51 – 66 ton
65 – 66 ton
Outreach
36; 38,5; 41 m
51; 53,5; 56 m
61; 63.5; 66 m
Hoisting speed
60/120 –
75/150 m/min
75/150 –
90/180 m/min
75/150 m/min –
90/180 m/min
Trolley travel
speeds
150 – 180 m/min
180 – 210 m/min
180; 210;
240 m/min
|
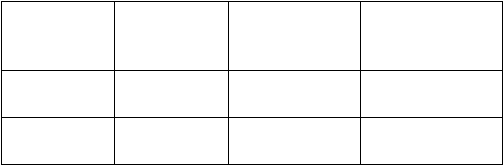 Gantry travel
speeds
45 – 60 m/min
45 – 60 m /min
45 – 60 m/min
Boom hoist
5
min
5
min
5
min
Trim/List/Skew
±5° /±5°/ ±5°
±3° /±3° /±3°
±3° /±3° /±3°
Sumber: Bagian Teknik TPK Koja.
-
Transtainer atau Rubber Tyre Gantry Crane (RTG)
Transtainer merupakan crane yang terdapat di lapangan penumpukan peti kemas.
Crane
ini
memindahkan
peti
kemas
dari
penumpukan ke
truk
dan
sebaliknya.
TPK Koja memiliki 21 transtainer.
-
Head Truck dan Chassis
Truk
pengangkut
peti
kemas
mengantarkan
peti
kemas
dari quay crane ke
lapangan
penumpukan
pada proses
bongkar. Sebaliknya, truk ini juga
mengangkut peti kemas dari lapangan penumpukan ke quay crane pada proses
muat.
Truk
terdiri
atas dua bagian,
yaitu head
truck
dan
chassis.
Head
truck
merupakan bagian depan (penarik) truk dan chassis merupakan bagian belakang
yang
memuat
peti
kemas.
Terdapat
dua
jenis chassis, yaitu yang memuat peti
kemas 20 kaki dan 40 kaki.
2.1.6. Kualitas Bongkar Muat
|
|
Kualitas pelayanan terminal peti kemas perlu ditingkatkan, bahkan secara terus-menerus,
agar memenuhi kebutuhan pelanggan. Peningkatan kualitas pelayanan pada akhirnya
akan meningkatkan nilai kompetitif perusahaan di industri terminal peti kemas.
Agar peningkatan kualitas dapat dilaksanakan, maka perlu dibuat definisi kualitas
termasuk pengukurannya. Secara lebih lengkap, pengukuran kualitas dapat digunakan
untuk:
1. Memahami kondisi terminal secara umum.
2. Menetapkan sasaran yang ingin dicapai oleh terminal, terutama di bidang operasional
bongkar muat.
3. Meningkatkan kinerja (performance) terminal, terutama kinerja bongkar muat.
4. Merencanakan dan mengembangkan terminal.
2.1.6.1.
Indikator Kualitas
Pengukuran
kualitas
dapat
dilaksanakan
melalui
indikator
kualitas.
Terdapat dua
indikator kualitas untuk operasi bongkar
muat
(transfer
cycle),
yaitu
BCH (Box Crane
per Hour) dan BSH (Box Ship per Hour).
2.1.6.1.1. BCH (Box Crane per Hour)
BCH
menunjukkan
kinerja
sebuah quay
crane
melakukan
bongkar
muat.
Satuannya
adalah
box crane per hour, yaitu jumlah petikemas
yang dapat dibongkar/muat dalam
satu jam oleh sebuah crane. Semakin tinggi angka BCH, semakin tinggi kualitas kinerja
crane melaksanakan bongkar muat.
|
|
2.1.6.1.2. BSH (Box Ship per Hour)
BSH
menunjukkan kinerja operasi bongkar
muat. Satuannya adalah box ship per hour,
yaitu
jumlah
peti
kemas
yang
dapat
dibongkar/muat
oleh
satu crane
atau
lebih
pada
sebuah kapal. Semakin tinggi angka BSH, semakin tinggi kualitas operasi bongkar muat,
dan semakin cepat kapal dapat dilayani.
2.2. Process Quality Model (PQM)
Peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan secara terus-menerus pada terminal peti
kemas
perlu
dilaksanakan
mengingat
persaingan
yang
semakin
ketat.
Pelanggan
menuntut
kualitas pelayanan
yang tinggi. Dalam hal
ini,
kecepatan
pelayanan
bongkar
muat
sangat
berarti
bagi
perusahaan shipping
line
yang
menjadi
pelanggan
langsung
terminal peti kemas.
2.2.1. Peningkatan Pelayanan Terus-menerus
Peningkatan kualitas pelayanan secara terus-menerus dapat diterjemahkan menjadi
peningkatan
proses.
DeToro
dan
Tenner (1977)
mengajukan
pendekatan
peningkatan
proses tahap demi tahap. Tahapan peningkatan proses secara terus-menerus meliputi:
1. Memahami pelanggan. Memahami kebutuhan (persyaratan) pelanggan dan
mencari
tahu kemampuan perusahaan untuk memenuhi persyaratan tersebut.
|
|
2. Menganalisa proses. Menentukan efisiensi dan efektivitas dari proses. Pada tahap ini,
metode peningkatan yang tepat perlu diidentifikasi.
3. Meningkatkan
proses.
Plan-Do-Study-Act
(Merencanakan-Mengerjakan-
Mempelajari-Bertindak) digunakan sebagai pendekatan untuk meningkatkan proses.
4. Menenerapkan perubahan. Membuat penyesuaian-penyesesuaian yang diperlukan.
5. Menstandarkan dan memonitor. Melacak kinerja, mengawasi proses dan peningkatan
secara terus-menerus.
2.2.2. Tahapan PQM
Beamon (1998) menerapkan teori peningkatan proses DeToro dan Tenner tersebut di atas
untuk
mendukung
risetnya
mengenai penjembatanan kesenjangan antara analisa sistem
supply chain dan kontrol kualitas dengan mengembangkan Process Quality Model
(PQM).
PQM
digunakan
Beamon
untuk
assesment,
peningkatan
dan
kontrol
kualitas
pada
sistem dan
subsistem supply
chain,
membantu
mengidentifikasi
masalah,
dan
menyajikan kerangka kerja
untuk peningkatan secara
terus-menerus sistem suply chain.
Khususnya, PQM pada supply chain untuk menjawab pertanyaan berikut:
a)
Aspek kualitas mana yang harus diukur?
b)
Bagaimana aspek kualitas ini diukur?
c)
Bagaimana
hasil pengukuran
ini
digunakan
untuk
mengevaluasi,
meningkatkan
dan mengontrol kualitas sistem supply chain secara keseluruhan?
Beamon mengembangkan PQM yang terdiri atas tujuh modul yang terintegrasi. Kerangka
dasar PQM dapat dilihat pada Gambar 2.8.
|
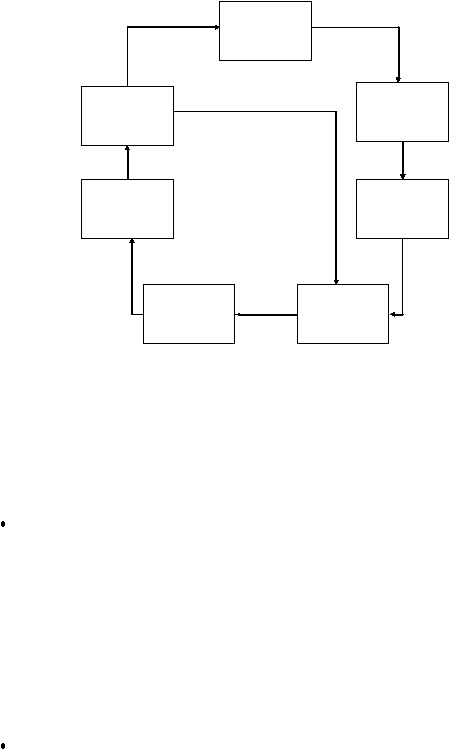 Modul 1: Identifikasi
proses, teknologi
dan tugas yang
dilaksanakan
Modul 7:
Kontrol
dan monitor proses
Modul 6:
Meningkatkan proses
Modul 2: Identifikasi
pelanggan &
persyaratan, ekspektasi,
dan persepsi
mereka
Modul
3:
Mendefinisikan kualitas
Modul 5:
Evaluasi proses saat
ini dan
mengeset standar kualitas
Modul
4:
Identifikasi pengukuran
kinerja kualitas saat
ini
Gambar 2.8. Kerangka Dasar Process Quality Model.
Pentahapan kerangka PQM adalah sebagai berikut:
Modul
1:
Mendefinisikan
proses
dan aktivitas
yang sedang
dilaksanakan.
Terdapat sejumlah
tool
grafis
yang
dapat digunakan untuk mendefinisikan atau
menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilaksanakan, seperti
flowchart,
flow
process
charts,
Gantt
charts,
dan
relation
diagram. Setelah
mengidentifikasi aktivitas ini, maka selanjutnya aktivitas diterapkan pada
tahapan-tahapan proses.
Modul 2: Mengetahui kebutuhan, harapan (eskpektasi), dan persepsi pelanggan.
Tujuan dari tahapan ini adalah untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas
pelayanan
kepada pelanggan.
Yang
dimaksud
dengan pelanggan
di
sini
adalah
|
|
pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan eksternal adalah konsumen dari
produk akhir. Sedangkan pelanggan internal adalah bagian (departemen) yang
membutuhkan
barang
atau pelayanan
dari
departemen
lain
di
dalam organisasi
(perusahaan).
Modul 3: Mendefinisikan kualitas. Terdapat berbagai macam definisi tentang
kualitas. Oleh sebab itu setiap perusahaan/organisasi perlu menciptakan definisi
kualitas berdasarkan kebutuhan pelanggannya. Definisi seharusnya merupakan
refleksi dari jenis pekerjaan (tugas) yang berkaitan dan juga merupakan cerminan
dari kebutuhan serta ekspektasi pelanggan.
Modul 4: Mengidentifikasi pengukuran kinerja kualitas yang ada. Tujuannya
adalah
untuk
mengidentifikasi
biaya sekarang, produktivitas, dan pengukuran
layanan, serta mengidentifikasi kesenjangan (gap) pengukuran yang ada sekarang.
Modul 5: Mengevaluasi proses yang ada sekarang dan mengeset standar kualitas.
Pada modul ini dikembangkan standar kualitas secara kuantitatif. Sebelum standar
dibangun, proses harus terkendalikan. Sebuah proses terkendalikan bila tidak ada
fluktuasi yang besar akibat dari hal-hal khusus. Dengan kata lain, variasi atau
fluktuasi ekstrim harus diatasi (dihilangkan) sebelum standar kualitas dibangun.
Modul
6:
Meningkatkan
proses.
Tujuannya
adalah
untuk
mengidentifikasi
dan
menerapkan
perubahan
untuk
meningkatkan kinerja
secara
keseluruhan.
Tahap
pertama
adalah
mengidentifikasi
dan
memprioritaskan peningkatan pada bidang
tertentu. Setelah bidang ini diprioritaskan, bidang yang harus menerima perhatian
diidentifikasi, dengan mempertimbangkan kendala waktu dan biaya. Maksud dari
peningkatan terus-menerus adalah mengurangi tingkat variasi dari penyebab yang
|
|
biasa
(bukan
penyebab
khusus)
yang
ada
di
dalam proses.
Pada
perencanaan
peningkatan, hipotesa harus dibuat yang berkaitan dengan penyebab variasi.
Setelah penyebab ditemukan, maka perencanaan harus diterapkan untuk
mengurangi penyebabnya. Kemudian penyebab ini harus diuji untuk mengetahui
apakan solusi tersebut dapat mengurangi variasi. Setelah pengujian dilaksanakan,
peningkatan harus diterapkan ke seluruh proses. Proses ini harus diuji lagi untuk
mengetahui apakah masih terkendali; setelah proses terkendali, kemudian standar
kualitas diset kembali untuk proses yang ditingkatkan.
Modul 7: Mengendalikan dan mengawasi proses.
Tujuannya adalah untuk
mengendalikan
dan
mengawasi
produktivitas dan kinerja pelayanan untuk
memastikan bahwa proses telah memenuhi standar. Terdapat sejumlah tool yang
dapat digunakan pada tahapan
ini, yaitu control chart (untuk analisa variabilitas
proses),
diagram cause
and
efect
(analisa
troubleshooting
proses),
histogram
(analisa
frekuensi
variabel proses),
diagram scatter (analisa
hubungan
variabel
proses), dan run chart (analisa kecendrungan proses).
2.3. Analisa Statistik
Seperti dikemukakan pada pengendalian kualitas proses pada metode PQM, menurunkan
tingkat
variabilitas
sangatlah
penting.
Seperti dikemukakan oleh Montgomery (2001),
peningkatan kualitas adalah penurunan variabilitas di dalam proses atau produk. Sebagai
contoh, untuk
meningkatkan kualitas bongkar
muat yang diukur melalui indikator BSH,
maka variabilitas nilai BSH harus dikurangi.
|
|
Pada konsep variabilitas dikenal istilah upper specification limit (USL) dan lower
specification
limit (LSL). USL adalah nilai paling tinggi yang diijinkan untuk sebuah
karakteristik kualitas. Sedangkan LSL adalah nilai terendah yang diijinkan. Jadi nilai
karakateristik kualitas di antara USL dan LSL adalah yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Karena variabilitas hanya dapat dijelaskan secara statistik, maka metode
statistiklah
yang berperan dalam usaha peningkatan kualitas. Secara keseluruhan dalam
penelitian ini, analisa statistik yang digunakan untuk keperluan analisa dan peningkatan
kualitas pelayanan dimaksudkan untuk:
1. Melakukan
analisa
pemecahan
masalah
suatu
proses
kegiatan. Perangkat
yang
digunakan antara lain diagram cause and effect (diagram Ishikawa).
2. Melakukan
analisa
frekuensi
variabel proses.
Perangkat
yang digunakan
antara
lain Histrogram.
|