|
7
BAB 2
LANDASAN TEORI
Pada dasarnya, bab ini berisi dua hal penting yaitu kerangka teori dan kerangka
berfikir :
2.1 Kerangka
Teori
Disini disajikan teori yang relevan, lengkap, mutakhir dan urut sejalan dengan
permasalahan.
Teori-teori yang dikemukakan berasal dari sumber-sumber teori dan dari hasil
penelitian.
Semen merupakan perekat anorganik
hidrolik,
yang berarti bahwa senyawa-
senyawa
yang
terkandung di
dalam
semen
tersebut
dapat
bereaksi
dengan
air
membentuk
zat baru
yang
kuat
dan
kompak. Oksida silika
yang terdapat di
dalam
komponen semen memberikan kekuatan dalam pemakaiannya. Dikutip dari Cement-
Data-Book Vol 1
:
International
Process
Engineering
in the Cement Industry
Third
edition karya Walter H. Duda.
2.1.1 Macam-macam Semen :
2.1.1.1 Semen Portland
( Portland Cement
); terdiri atas 5 tipe,
yaitu
:
1. Semen tipe I ( Ordinary Portland Cement )
Semen
tipe
I
paling
banyak
di produksi. Pengerasan
hingga kekuatan
penuhnya selama 28 hari, dengan komposisi C3
S
40 – 60 %, C2
S
10 – 30
%, dan C3A
7
–
13
%.
Kegunaann-nya
untuk konstruksi
umum yang
tidak memerlukan sifat khusus dan pekerjaan beton.
|
|
8
2. Semen tipe II ( Moderate Heat of Handening )
Komposisi semen tipe II
mengandung lebih banyak C2S dan sedikit C3S.
Semen
ini
mempunyai
panas
hidrasi
yang
rendah
dan
kuat
tekan
yang
tinggi. Kegunaannya untuk pembuatan
jalan, bendungan, pelabuhan, dan
pondasi raksasa.
3. Semen tipe III ( High Early Strength )
Semen
ini memiliki ukuran partikel lebih halus, kadar C3S
lebih
tinggi,
sehingga pengerasannya dapat
dalam 3
hari
saja. Kandungan
C3
S
yang
tinggi akan memberikan kekuatan awal yang besar. Kegunaan semen ini
untuk
pembuatan beton pada musim dingin, konstruksi darurat,
pembangunan
gedung-gedung besar,
dan
produksi
beton
tekan
dalam
pabrik.
4. Semen tipe IV ( Low Heat of Hidration )
Kandungan C3
S
dan C3
A
sangat rendah dan tahan terhadap sulfat. Semen
ini
membebaskan
panas
hidrasi
yang
rendah saat
dicampur dengan
air.
Kegunaanya terutama untuk konstruksi yang massif.
5. Semen tipe V ( High Sulfate Resistance )
Semen
tipe
ini
memiliki kadar C3
A
dan
C
4
AF
agak
tinggi.
Semen
ini
mempunyai
ketahanan
yang
tinggi
terhadap
sulfat.
Kegunaannya
untuk
konstruksi
bawah
tanah
yang
banyak
mengandung senyawa
sulfat,
pengeboran minyak bumi, dan gas alam.
|
|
9
2.1.1.2 Semen Abu
Terbang ( Fly Ash Cement )
Semen
ini
termasuk
semen
Portland
pozzoland yang
terdiri
dari
campuran semen
Portland
tipe
I
dan
abu
terbang
yang
dihasilkan dari
pembakaran batu bara. Semen
tipe
ini mempunyai panas
hidrasi rendah dan
tahan terhadap sulfat sehingga cocok digunakan untuk konstruksi bawah laut
dan daerah yang mengandung kadar sulfat tinggi.
2.1.1.3 Semen Putih
( White Cement
)
Semen ini merupakan semen Portland dengan kadar besi oksida yang
rendah ( 0.3 % ). Selama proses produksi berlangsung diperlukan
pengawasan
tambahan
afar
semen
tidak
terkontaminasi dengan
Fe
2
O3.
Penggunaan semen untuk beton cord an barang-barang seni.
2.1.1.4 Semen Sumur Minyak ( Oil Well Cement )
Penyemenan
sumur
minyak
merupakan
proses
pencampuran dan
pengisian adukkan
lumpur
semen
ke
dalam selongsong
dan
pipa
serta
dibiarkan
mengikat
sehingga
membentuk sumur.
Semen
sumur
minyak
mempunyai waktu
pengikatan
pada
temperature
dan
tekanan
tinggi
serta
memiliki
ketahanan
terhadap
sulfat.
Kegunaan semen
ini
terutama
dalam
usaha
pengeboran
minyak bumi dan gas
alam
baik di pantai
maupun
lepas
pantai.
2.1.1.5 Blended Cement
Semen
ini
hanya
sedikit
diproduksi karena
mutunya
yang
rendah.
Pembuatan
semen
ini
memerlukan energi
per
unit
volume
yang
rendah
sehingga harganya murah. Semen ini digunakan untuk bangunan sederhana.
|
|
10
2.1.2 Bahan
Baku
Pembuatan
Semen
Bahan baku yang digunakan dalam industri semen dibedakan menjadi
tiga,
yaitu
bahan
baku
utama,
bahan
baku
korektif, dan
bahan
tambahan.
Bahan
baku
utama
ialah
batu
kapur
(
limestone
)
dan
tanah
liat
(
clay
).
Gabungan
batu
kapur
dan
tanah
liat
mengandung empat
senyawa
yang
dibutuhkan dalam
pembuatan semen,
yaitu
kalsium oksida
dalam
bentuk
kalsium karbonat, aluminat, silikat, dan ferrit.
Keempat
senyawa
tersebut
komposisinya tidak
selalu
tetap
karena
lokasi penambangan
yang berpindah-pindah.
Untuk
itu digunakan bahan
baku
korektif
untuk
menutupi
kekurangan ini.
Bahan
baku
korektif
yang
digunakan adalah
pasir silika,
iron sand
dan
kaolin.
Bahan-bahan
tersebut
berfungsi untuk mengatur kandungan silikat, ferrit, dan aluminat.
Bahan tambahan yang digunakan gypsum. Gypsum ditambahkan pada
klinker untuk memperlambat proses pengerasan semen.
Mineral-mineral kristal
dalam
semen,
yaitu
tricalcium
silicate,
dicalcium silicate, tricalcium alumina, dan tetracalcium alumina ferrit.
2.1.3
Sifat-sifat
Semen
2.1.3.1 Hidrasi Semen
Kekuatan
semen
tergantung
pada
reaksi
komponen-komponen penyusun
semen
dengan
air. Reaksi
ini disebut
reaksi
hidrasi.
Reaksi
hidrasi
dipengaruhi oleh kehalusan semen, jumlah air, dan temperature. Reaksi
hidrasi didominasi oleh hidrolisis komponen silikat membentuk kalsium
silikat hidrat (tubermorite gel) dalam bentuk gel dan larutan lime, Ca(OH)2
.
|
|
11
2.1.3.2 Panas
Hidrasi
Reaksi
hidrasi
membebaskan panas
yang
disebut
panas
hidrasi.
Pada
konstruksi beton,
panas
hidrasi
tidak
dapat
dilepaskan ke
udara
karena
konduktivitas beton
yang
kecil.
Akumulasi
panas
dapat
meretakkan
konstruksi.
2.1.3.3 Setting dan
Hardening
Penambahan air pada semen mula-mula akan membentuk suatu pasta semen.
Dalam
jangka
waktu
tertentu
pasta
tersebut
akan
mengalami setting
atau
pengerasan.
Ada
dua
teori
yang
menerangkan tentang sifat-sifat pengerasan
semen, yaitu;
a. Crystaline Theory.
Teori ini menerangkan bahwa sifat mengerasnya semen ( pasta semen )
bergantung kepada pertumbuhan kristal-kristal yang terbentuk.
b. Gel atau Colloidal Theory.
Sifat
pasta
semen
dapat
dianggap larutan
yang
lewat
jenuh
dari
persenyawaan
yang
terhidrasi,
lama-kelamaan akan
mengumpal
membentuk
massa
yang
amorphous,
disebut
gel. Setelah
kering
gel
ini
mengeras menjadi beton.
2.1.3.4 Hubungan antara
kekuatan dan
komposisi
semen
Kekuatan
tekan
adalah
kemampuan untuk
menahan
suatu
beban.
Semen
dengan kadar C3S
tinggi akan
memberikan kekuatan
tekan awal
yang besar
sedangkan
C2S
akan
memberikan kekuatan awal
yang
tinggi
untuk
waktu
yang lama. Untuk selanjutnya C3A dan C
4
AF tidak begitu berpengaruh.
|
|
12
2.1.3.5 Kelembaban
Sifat
ini
harus
diperhatikan selama
penyimpanan dan
transportasi
semen.
Semen
mudah
menyerap
air
dan
CO2
dari
udara.
Kelembaban akan
menurunkan
kualitas
semen
seperti
berkurangnnya specific gravity,
terbentuknya gumpalan-gumpalan, terjadinya false set, bertambahnya loss of
ignition,
berkurangnnya
kekuatan,
dan
betambahnya
setting
time dan
hardening.
2.1.3.6 Pengkerutan ( shrinkage
)
Pengkerutan semen
dibedakan
menjadi
tiga,
yaitu
hydration
shrinkage,
carbonation shrinkage, dan drying shrinkage.
Drying
shrinkage disebabkan
oleh menguapnya air bebas, yaitu air
yang terdapat diantara fasa cair, padat,
dan
pasta.
Faktor
yang
mempengaruhi shrinkage
yaitu
komposisi
semen,
jumlah air pencampur, dan kandungan C3A tinggi.
2.1.3.7 Daya tahan terhadap
sulfat
Mineral C3A dalam semen dapat beraksi dengan senyawa sulfat
membentuk
high
calcium sulfoaluminate
hydrate
(C3
A,
3
CaSO
4
,
31
H2
O
).
Hal
ini
menyebabkan jumlah
air
kristal
dalam
C3A
bertambah
sehingga
menyebabkan ekspansi volume dan akhirnya menyebabkan keretakan beton.
2.1.4
Raw
Material
Mineral sebagai bahan
alami
dan
juga
sebagai produk
industri dapat
digunakan untuk memproduksi semen. Materi dasar untuk pembuatan semen
adalah komposisi mineral yang
mengandung bahan dasar dari
semen :
lime,
silica,
alumina
and
iron
oxide. Sangat jarang sekali komponem-komponem
|
|
13
ini
ditemukan dalam kebutuhan proporsisi
kecuali satu
material dasar. Oleh
karena itu adalah penting
untuk memilih
takaran campuran terhadap sebuah
komponem
lime dengan
sebuah
komponem
dimana
takaran
yang
rendah
dalam
lime, mengandung
lebih banyak silica, alumina dan
iron oxide ( clay
component ). Kedua komponem dasar ini biasanya
gabungan dari
limestone
dan clay atau limestone dan marl.
2.1.4.3 Komponem
Lime
1. Limestone
Calcium carbonate (CaCO3) banyak terdapat di alam. Calcium carbonate
yang terbentuk secara alami terpilih sebagai bahan produksi Semen
Portland. Peringkat
terpercaya
dari
limestone
adalah calcspar (calcite)
dan aragonite. Calcite crystallizes hexagonally,
dan aragonite
is
rhombic.
Jenis
marcroscopic-granular
dari
calcite
adalah
marble.
Tidaklah menguntungkan menggunakan marble untuk pembuatan semen.
Bentuk umum yang banyak dijumpai dari calcium carbonat, yang paling
menyerupai
marble, adalah limestone dan chalk.
Limestone
merupakan
struktur crystal yang terdominan dan
terbaik. Kekerasan dari
limestone
tergantung
dari
usia
geologinya;
biasanya,
semakin
tua
formasi
geologinya, semakin keras pula limestone tersebut. Kekerasan limestone
berkisar
antara 1.8
dan
3.0
pada
skala
Moh’s
untuk kekerasan;
lebih
spesifik adalah 2.6 sampai 2.8. Hanya jenis-jenis tertentu dari limestone
yang putih.
Limestone biasanya mengandung campuran dari bahan clay atau takaran
besi, dengan warna yang berbeda-beda pula.
|
|
14
2. Chalk
Chalk
merupakan batuan
sedimen
yang
terbentuk
sebelum
zaman
Cretaceous pada waktu
geologi;
secara
geologi
itu
masih relatif
muda.
Dibandingkan
dengan
limestone, chalk
dikategori
sebagai
texture
bumi
yang
lembut;
inilah
yang
membuat chalk
terpilih
sebagai
raw
material
terutama pada process
basah dalam pembuatan semen. Sejak pengguaan
ledakan
tidak
diijinkan
dalam
penambangan chalk,
dan
proses
penghancuran juga
dapat
diabaikan,
materi
dasar
jenis
ini
sangat
mengurangi biaya
produksi
semen.
Dalam
beberapa
endapan,
Calcium
carbonate mengandung chalk sekitar 98 – 99 %, dengan sedikit campuran
SiO2, Al2O3, dan MgCO3
.
Dalam material-material dasar semen komponem lime
umumnya
terkandung sekitar 76 – 80 % didalamnya. Oleh sebab itu, sifat kimia dan
fisika dari
komponem ini sebagai penentu pengaruh, ketika
tiba
saatnya
untuk
menentukan metode
mana
yang
akan
digunakan
dalam
proses
produksi semen sama halnya seperti pada produksi mesin-mesin.
3. Marl
Limestone dengan campuran silica, bahan clay, dan iron oxide dinamakan
marls. Marl
membentuk
elemen
transisi
menuju
ke
clay.
Dikarenakan
marl
mudah
dijumpai,
mereka
sering
digunakan
sebagai
material
dasar
untuk produksi semen.
Secara
geologi,
marl
merupakan batuan
sedimen
yang
terbentuk
secara
pengendapan berkala
dari
calcium
carbonate
dan
bahan
clay.
Tingkat
kekerasan dari marl lebih rendah jika dibandingkan dengan
limestone;
|
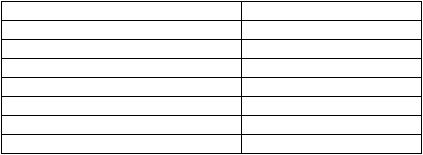 15
semakin
tinggi
kandungan bahan
clay,
semakin
rendah
pula
tingkat
kekerasannya. Kadang-kadang marl juga
mengandung
unsur batubara muda.
Warna
dari
marl
tergantung
dari
bahan
clay
dan
dibagi
dalam
tingkatan
kuning
sampai
hitam
–
keabu-abuan. Marl
merupakan
material
dasar
terunggul
untuk
membuat
semen,
karena
mereka
mengandung bahan
komponem lime
dan
clay
yang
dalam
kondisi
siap
dicampur.
Marl
jaman
carcareous ditinjau
dari
komposisi
kandungan kimianya
setara
dengan
campuran material semen portland, digunakan untuk membuat apa yang kita
sebut sebagai semen alami; bagaimanapun, endapan
material dasar
ini tidak
umum.
Seperti
pada
perbandingan
banyaknya
jumlah
dari komponem
lime
dan clay dalam material dasar semen, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Kandungan CaCO3 dalam berbagai jenis material
Kandungan CaCO3
High grade limestone
96 – 100 %
Marlaceous limestone
90 – 96 %
Marlstone or calcareous marl
75 – 90 %
Marl
40 – 75 %
Clayey marl
10 – 40 %
Marlaceous clay
4 – 10 %
Clay
0 – 4 %
Tabel dibawah ini menampilkan kandungan komposisi kimia dari jenis-jenis
limestone
dan
marl
yang
berbeda-beda, digunakan
untuk
membuat
semen
portland.
|
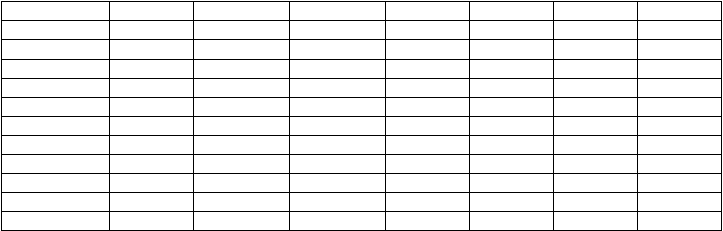 16
Tabel 2.2 Kandungan bahan kimia dalam limestone
1
2
3
4
5
6
7
Komponem %
Limestone
Limestone
Limestone
Limestone
Limestone
Limestone
Limestone
SiO2
3.76
6.75
4.91
4.74
27.98
33.20
21.32
Al2
O3
1.10
0.71
1.28
2.00
10.87
8.22
4.14
Fe2O3
0.66
1.47
0.66
0.36
3.08
4.90
1.64
CaO
52.46
49.80
51.55
51.30
30.12
27.30
39.32
MgO
1.23
1.48
0.63
0.30
1.95
1.02
0.75
K2
O
0.18
Menyusut
Menyusut
0.16
0.20
0.12
0.06
Na
2
O
0.22
Menyusut
Menyusut
0.28
0.33
0.18
0.08
SO3
0.01
1.10
0.21
-
0.70
0.37
-
LOI
40.38
39.65
40.76
40.86
24.68
24.59
32.62
Total
100.00
99.96
100.00
100.00
99.91
99.90
99.93
2.1.4.3 Komponen Clay
Material
dasar
penting
dari
pembuatan semen
adalah
clay.
Clay
terbentuk
dari weathering ( kerusakan akibat kena hujan dan angin ) alkali dan alkaline
tanah yang mengandung aluminium silika dan kaidah produk kimia mereka,
sebagian besar feldspar dan mica.
Komponem
utama
dari clay
terbentuk
dari
hydrous
aluminium silika.
Clay
dapat dibagi dalam tingkatan mineral:
Kaolin group
Kaolinite
Al2O3 . 2 SiO2
. 2 H2O
Dickite
Al2O3 . 2 SiO2
. 2 H2O
Nacrite
Al2O3 . 2 SiO2
. 2 H2O
Halloysite
Al2O3 . 2 SiO2
. 2 H2
O
Montmorillonite group
Montmorillnite
Al2O3 . 4 SiO2
. H2
O
+
nH2O
Beidellite
Al2O3 . 3 SiO2
. nH2O
|
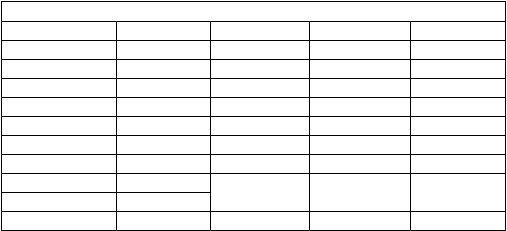 17
Nontronite
(AL, Fe)
2
O3 . 3 SiO2
. nH2O
Saponite
2 MgO . 3 SiO2 . nH2O
Group of alkali bearing clays
Clay mica including Illite
K2O-MgO-Al2
O3
-SiO2-H2O
dalam
jumlah yang Bervariasi
Mineral dari
kaolin
group
bebeda
dalam
kandungan SiO2nya
sama
halnya
jika
ditampilkan dalam
struktur kristal dan
sifat
optiknya. Penandaan
kaolinite
dihubungkan dengan
kemurnian
mineral
kaolin.
Berdasarkan
susunan,
clay
sangat
mudah
berkembang; partikel clay
biasanya dibawah 2
micron dalam diameter.
Tabel 2.3 Komposisi kimiawi dari clay
Komposisi kimiawi dari clay
Komponem %
Clay 1
Clay 2
Clay 3
Clay 4
LOI
7.19
8.67
10.40
6.40
SiO2
67.29
62.56
52.30
60.10
Al2O3
8.97
15.77
24.70
18.00
Fe
2
O3
4.28
4.47
6.10
8.20
CaO
7.27
4.80
4.40
0.80
MgO
1.97
1.38
0.10
0.20
SO3
0.32
-
1.10
3.80
K2
O
1.20
}
2.35
}
0.80
}
2.50
Na
2
O
1.51
Total
100.00
100.00
99.90
100.00
Secara khusus laposan mineral clay terbagi atas:
( satuan dalam meter kuadrat per gram )
Kaolin
kurang lebih
15 m²
/g
Halloysite kurang lebih
43 m²
/g
Illite kurang lebih
100 m²
/g
Montmorillnite kurang lebih
800 m²
/g
|
|
18
Berdasarkan berat secara khusus : ( gram per cm³ )
Kaolin
2.60 – 2.68
Halloysite
2.0 – 2.20
Illite
2.76 – 3.00
Titik peleburan dari clay sekitar 1150
C
sampai 1785
C.
Komposisi kimia dari clay mungkin berubah-ubah dari yang terdekat ke clay
murni, bagi
yang
mengandung jumlah
sesungguhnya
dari
campuran kimia
seperti
iron
hydroxide, iron
sulfide,
pasir,
calsium carbonat,
dll.
Iron
hydroxide merupakan alat pewarna pokok dalam clay; juga masalah organik
mungkin memberi
warna
yang
berbeda
pada
clay. Clay
yang
tidak
murni
berwarna
putih.
Unsur
utama
dari
alkali
dalam
semen
ditemukan dalam
komponem argillaceous pada raw mix.
Pengolahan dibawah menunjukkan komposisi kimia dari berbagai jenis clay,
digunakan untuk membuat semen portland.
2.1.4.3 Bahan
/
unsur perbaikan
Jika sifat-sifat dasar komponem kimia yang dibutuhkan dalam pencampuran
semen
tidak
ditampilkan dalam
jumlah
yang
ditentukan, bahan
perbaikan
digunakan sebagai
tambahan.
Sebagai
contoh,
untuk
penyempurnaan
kandungan silica,
pasir,
high
silica
clay,
diatomite, dll,
digunakan sebagai
bahan tambahan atau bahan perbaikan. Untuk
mengimbangi kekurangan iron
oxide, material perbaikan seperti pyrite cinders, iron
ore, dll, ditambahkan.
|
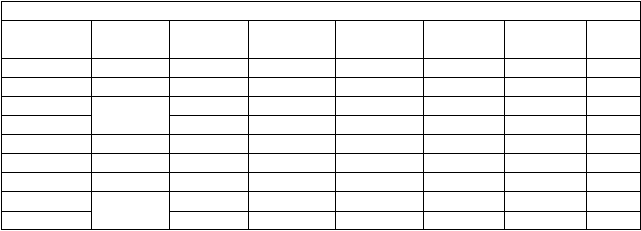 19
Tabel 2.4 Komposisi Kimia dari bahan perbaikan
Komposisi kimia dari bahan perbaikan
Komponem
%
Diatomite
Bauxite
Pyrites
cinders
Iron ore
Flue dust
Flue dust
Sand
LOI
6.2
15 – 20
-
5 - 12
5 - 15
0.2 – 4.0
0.2
SiO2
77.0
16 – 22
6.6 – 25.0
20 – 25
11 – 22
26 – 36
99.2
Al2O3
}
9.6
44 – 58
2 – 16
3 – 9
5 – 14
6.5 – 9.5
-
Fe
2
O3
10 – 16
62 – 87
45 – 60
54 – 69
5 – 8
0.5
CaO
0.3
2 – 4
0.7 – 0.9
0.5 – 2.5
1 – 9
42 – 50
-
MgO
0.9
0.2 – 1.0
0.2 – 2
1.5 – 7
0.5 – 2.5
3 – 4
-
SO3
-
-
0.8 – 8
0.3 – 0.6
0.2 – 2.5
2.5 – 3
-
Na
2
O
}
1.5
-
-
-
-
0.8 – 3.5
-
K2O
-
-
-
-
-
-
2.1.4.4 Campuran Komponem
dari
Materi Dasar
Semen
Disini, beberapa komponem dibahas, kualitas mana dalam semen sebagai tiap
batas dengan standar khusus atau pengalaman dalam pembuatan.
2.1.4.4.1
Magnesium
Oxide
Komponem ini dikombinasikan mencapai 2 % berdasarkan berat dengan
tahapan cliker
utama;
dibalik jumlah
tersebut ia
muncul
dalam clinker
sebagai
MgO
(periclase) bebas.
Periclase
bereaksi
dengan
air
menjadi
Mg(OH)
2
:
MgO + H2O = Mg(OH)
2
,
tetapi reaksi ini berlangsung lambat
sekali, ketika reaksi keras lainnya telah berakhir. Sejak Mg(OH)
2
bekerja
dalam jumlah lebih besar dari MgO dan dibentuk dari tempat yang sama
dimana
partikel
periclase
berada,
ia
dapat
membagi
pinggiran secara
terpisah
dari
pasta
semen
yang
keras,
hasil
dalam
perluasan cracks
(
perluasan magnesia).
MgO
muncul
dalam
limestone umumnya sebagai
dolomite
(CaCO3
,
MgCO3 ).
|
|
20
Juga
tanur
(tinggi)
ampas
bijih
kadang
mengandung
kandungan
MgO
yang
tinggi.
Ketika penyeleksian
seperti
ampas bijih
sebagai
pengganti
dari clay seperti komponem argillaceous pada
raw
mix,
harus dilakukan
ketelitian, untuk menjaga kandungan MgO pada clinker dalam batas yang
diijinkan.
2.1.4.4.2
Alkalies
K2O dan Na2
O
bermula dari material dasar seperti clay dan marl, dimana
kandungan
ini
ditampilkan dalam peredaran
felspar,
mica, dan partikel
illite yang baik, dan dalam jumlah kecil – ketika menggunakan batubara
sebagai bahan bakar – dari debu batubara. Di
Eropa tengah, kandungan
K2O merepresentasikan kandungan Na2O yang berbeda-beda. Di daerah
lain sebagai
contoh USA, kandungan
Na2O lah yang utama.
Setelah
process pembakaran
dalam
rotary
kiln, sebagian
dari alkali
menguap
dalam zona pembakaran, menghasilkan yang disebut sirkulasi alkali.
Beberapa
kumpulan-kumpulanfondasi,muncul
sebagai
contoh
dibeberapa area USA,
Denmark dan Jerman bagian
utara,
mengandung
komponem
alkali
yang
sensitif
sebagai
contoh
opal
(hydrated
silica),
bereaksi
dengan
alkali
yang ada pada
semen, dalam
beberapa kondisi
yang
tidakmenguntungkan
dapat
menghasilkan
fenomena
yang
berkelanjutan (pemuaian alkali).
Berdasarkan pengalaman, pemuaian
alkali dapat dicegah dengan menggunakan
semen dengan kandungan
alkali rendah; dalam kasus
ini
total alkali, dapat dihitungkan Na2O (%
berdasarkan berat Na2
O
+
0.659 % K2O) tidak boleh melebihi 0.6 % dari
total berat. Dengan refrensi pembatasan ditambahkan di beberapa negara,
|
|
21
Jerman juga memutuskan 0.6 % Na2O sebagai batas, tetapati hanya untuk
semen
portland.
Pengalaman
praktek
menunjukkan yakni
dalam
tanur
ampas
bijih semen, batas alkali
yang
dapat
diterima
dapat
lebih
tinggi;
walau
semen
dengan
kandungan alkali
aktif
yang
rendah
(NA-semen)
dengan
komponem ampas
bijih
paling
sedikit
50
%
mempunyai
kandungan alkali
maksimum 0.9 %.
Selanjutnya, batas total
maksimum
alkali
2
%
diperbolehkan
untuk
semen
dengan komponem
ampas
bijih
lebih kurang 65 %.
Dalam
kasus
dimana
ada
NA-semen,
tetapi
kandungan alkali
dalam
pembakaran clinker dari material dasar yang tersedia melebihi batas yang
ditentukan,
beberapa
bagian
dari
kiln
yang
menghasilkan gas
harus
dihindari
sebelom
masuk
dalam
tahap
pemanasan, untuk
memisahkan
bagian dari alkali yang mudah menguap.
Disini
ia
harus disebutkan bahwa
syarat pemerintah SS-C-192 b, syarat
AASHO, juga syarat ASTM memiliki pilihan batas alkali 0.6 % sebagai
Na2
O
dalam
semen
portland.
Ini
berarti
pelanggan harus
menetapkan
bahwa alkali
yang dia
inginkan dibawah batas
ini, sebaliknya tidak ada
batas untuk kandungan alkali. Batas ini bisa ditetapkan ketika semen itu
digunakan untuk
fondasi
dengan
jumlah-jumlah yang
mungkin memberi
reaksi yang
mengganggu. Tetapi dikarenakan sulitnya pemisahan
rendah
dan
tinggi-nya alkali pada semen,
ia
menjadi kebiasaan umum dibanyak
areal
di
Amerika
Serikat
untuk
semua
semen
untuk
menyesuaikan
diri
pada ketentuan alkali rendah.
|
|
22
2.1.4.5 Komposisi Potensial
Clinker
Analisa secara kimia memberi gambaran dari posisi oxida-oxida dalam
clinker
atau semen. Borgue
mengembangkan
metode
perhitungan,
rumus
bagi
kandungan
dari
mineral-mineral
clinker
(
C3S,
C2S,
C3
A
dan
C
4
AF )
dapat
diperoleh
dari
analisis
secara
kimia.
Seharusnya komposisi clinker
dikarkulasikan berdasarkan
metode
yang ditunjuk Borgue
sebagai kekuatan
komposisi. Kekuatan
berarti
mungkin
tetapi
tidak
aktual,
ia
juga
nantinya
dapat disebut bahwa kekuatan komposisi klinker yang ditetapkan oleh
metode
kalkulasi
Borgue
mungkin saja tidak sama dengan
komposisi
ilmu
mineral yang aktual.
Dikarenakan penyajian yang
jelas
dari
komposisi clinker dan
prediksi
yang
mungkin
dari
khasiat
semen,
metode
kalkulasi
Borgue
digunakan secara
umum.
Metode
perhitungan sudah
muncul
dalam
standar
semen
Amerika
Serikat,
USSR,
dan
di
negara-negara
lain.
Bagaimanapun, standar
semen
ASTM
dari
Amerika
Serikat
mengandung pembatasan
yang
mengatakan
bahwa pernyataan batas kimia dari perhitungan senyawa-senyawa tidak
berarti
penting bahwa oxida
tersebut sesungguhnya
atau sepenuhnya
dinyatakan sebagai senyawa-senyawa berikut
Jika oxida-oxida
CaO, SiO2
,
Al2
O3, Fe
2
O3
ditunjukkan oleh
a,
b,
c,
d
dan senyawa-senyawa
C3
S, C2S, C3A, C
4
AF
ditunjukkan oleh simbol
w,
x,
y,
z
|
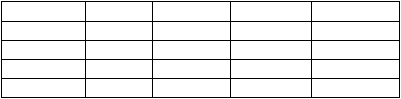 23
kemudian perhitungan berikutnya dapat ditampilkan: Dimulai dari, kita harus
menyadari bahwa C3
S
mengandung 73.69 % CaO, dan 26.31 % SiO2,
dan
C2
S
mengandung 65.12 % CaO, dan 34.88 % SiO2. Tabel dibawah ini juga
menunjukkan komposisi
dari
C3
A
dan
C
4
AF.
Sekarang
kita
dapat
memperlihatkan perbandingannya dalam tabel berikut:
Tabel 2.5 Komposisi clinker
C3
S
C2S ( x )
C3A ( y )
C
4
AF ( z )
a
CaO
0.7369
0.6512
0.6227
0.4616
b
SiO2
0.2631
0.3488
-
-
c
Al2
O3
-
-
0.3773
0.2098
d
Fe
2
O3
-
-
-
0.3286
Karena
itu,
dalam banyak
campuran
dari
keempat senyawa-senyawa,
CaO
dalam
C3S
sama
dengan
0.7369
kali
%
dari
C3S;
CaO
dalam
C2S
sama
dengan
0.6512
kali
%
dari C2S,
sebagai contoh.
Total
CaO
adalah
jumlah
dari nilai berikut, atau:
a
=
0.7569 w + 0.6512 x + 0.6227 y + 0.4616 z
b = 0.2631 w + 0.3488 x
c
=
0.3773 y + 0.2098 z
d = 0.3286 z
Solusi untuk w, x, y, dan z:
w = 4.071 a – 7.600 b – 6.718 c – 1.430 d
x = 8.602 b + 5.608 c – 3.071 a + 1.078 d
y = 2.650 c + 1.692 d
z
=
3.043 d
|
|
24
Menambahkan keempat senyawa diatas
C3
S
=
4.071 CaO – 7.600 SiO2 – 6.718 Al2
O3
–
1.430 Fe
2
O3
C2
S
=
8.602 SiO2 + 5.068 Al2O3
+
1.078 Fe2
O3 – 3.071 CaO
=
2.867 SiO2 – 0.7544 C3S
C3
A
=
2.650 Al2
O3 – 1.692 Fe
2
O3
C
4
AF = 3.043 Fe2
O3
2.1.4.6 Modul-modul
Semen
Telah lama sekali semen portland di produksi atas dasar praktik pengalaman
diambil
dari
proses
produksi.
Ketika
membandingkan analisa
kimia
pada
semen portland, ditemukan bahwa sering adanya hubungan antara persentase
dari lime disatu sisi dan kombinasi silica, alumina, dan iron oxida dan yang
lainnya. Kemudian,
ratio oxide
memberi peningkatan kepada
formula
yang
disebut
2.1.4.6.1
Hydraulic
modulus
Dimana memiliki rumus
HM
CaO
1.7
2.3 ( pers 1 )
SiO
2
Al
2
O
3
Fe
2
O
3
hydraulic modulus dengan kualitas semen yang bagus berkisar antara 2.
Semen dengan HM < 1.7 sering menunjukkan kekuatan yang tidak
cukup;
semen
dengan
HM
=
2.4
dan
lebih
memiliki
volume
stabilitas
yang rendah.
Jika
formula tersebut didemonstrasikan,
karakteristik
hydraulic
modulus
semen dari ratio CaO, ke total dari faktor hydraulic, sebagai contoh SiO2,
Al2O3, dan Fe2
O3
. HM umumnya dibatasi antara nilai 1.7 – 2.3. Ia
|
|
25
ditentukan dengan
HM
yang
meningkat, lebih
banyak panas dibutuhkan
untuk pembakaran
clinker; kekuatanya,
terutama
kekuatan
tingkat
pertama
bertambah dan juga
panas dari
hidrasi
meningkat; dan
secara
serentak daya tahan terhadap serangan kimia menurun. Saat ini hydraulic
modulus masih
digunakan.
Kemudian,
untuk
evaluasi
yang
lebih
baik
terhadap
semen,
silica
ratio
dan
alumina
ratio
di
perkenalkan; untuk
tingkatan khusus ratio ini sebagai penambah hydraulic modulus.
2.1.4.6.2
Silica ratio
Merepresentasikan perbandingan SiO2
dengan Al2O3 total
dan Fe2O3
:
SR
SiO
2
Al
2
O
3
Fe
2
O
3
( pers 2 )
umumnya, silica ratio
berkisar antara 1.9 dan 3.2. Jumlah istimewa dari
silica
ratio
antara 2.2
dan
2.6.
Sekarang
dan
kemudian juga
jumlah
tertinggi
untuk silica
ratio
dapat ditemukan
sebagai contoh 3
sampai
5
dan
kadang-kadang melebihinya,
khususnya
untuk
semen
yang
kandungan silicanya
tinggi
dan
untuk
semen
portland
putih.
Demikian
juga, jumlah sedikit untuk silica ratio dapat diterima paling rendah 2 dan
terendah
sampai
1.5.
Peningkatan
silica
ratio
merusak
kekuatan
bakar
dari
clinker,
dengan
mengurangi kandungan
tahap
cairan
dan
kecenderungan terhadap
pembentukan
lapisan
dalam
kiln.
Peningkatan
silica ratio juga
menyebabkan pembentukan dan pengerasan yang lambat
pada semen. Dengan penurunan silica
ratio
kandungan dari tahap cairan
meningkat;
ini
menigkatkan kekuatan
membakar
dari
clinker
dan
pembentukan lapisan dalam kiln.
|
 26
Silicic acid
ratio
Mussgnug menamai ratio
SiO
2
Al
2
O
3
silicic acid ratio.
Ketika
pembakaran clinker
dalam
rotary
kiln,
kondisi
pelapisan
baik
terbentuk dalam zona pembakaran ketika nilai dari hasil bagi ini dibatasi
sampai 2.5 – 3.5, secara bersamaan menjaga nilai alumina ratio antara 1.8
–
2.3. Silicic acid ratio
tidak seharusnya dibingunkan dengan silica ratio
yang dibahas sebelumnya.
2.1.4.6.3
Alumina
ratio
Alumina
ratio
mengkarakteristikkan semen
dengan
membandingkan
alumina dan iron oxide :
AR
Al
2
O
3
Fe
2
O
3
( pers 3 )
umumnya, nilai
dari
alumina
ratio
berkisar dari
1.5 sampai
2.5.
Semen
dengan kandungan alumina
yang
tinggi
menunjukkan alumina ratio
2.5
atau lebih. Alumina ratio
dari semen dengan kandungan alumnia
rendah
dibawah
1.5
(
disebut
ferro
cements
).
Alumnia ratio
menentukan
komposisi
cairan
dalam
clinker.
Dimana
alumina
ratio
adalah
0.637,
kedua oksida dikenalkan dalam ratio molekul, dan oleh karena itu hanya
tetracalcium
alumino
ferrite dapat
dibentuk
dalam
clinker
(
4
CaO
.
Al2O3
.
Fe2
O3
);
sebagai akibat,
clinker
tidak
dapat
secara
numerik
mengandung
tricalcium
aluminate
(
3
CaO
.
Al2O3 ).
Ini
adalah kasus
yang
kita
sebut
Ferrari-cement
dimana
dikarakteristikkan
oleh
hydrasi
panas
yang
rendah,
pembentukan
rendah, dan
penyusutan
rendah.
|
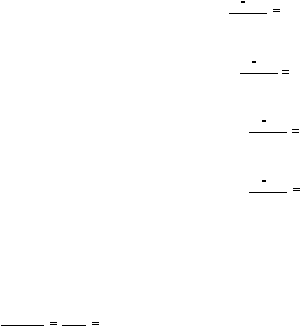 27
Alumina
ratio tinggi
bersamaan dengan
silica ratio rendah dihasilkan
antara benda-benda lain, dalam pembentukan yang cepat dari semen; ini
membutuhkan penambahan tingkat gypsum yang tinggi untuk mengontrol
waktu pembentukan.
2.1.4.7 Rumus-rumus
Lime
2.1.4.7.1
Faktor
saturasi
lime
Untuk
mencapai lime saturation
yang komplit dalam
clinker, total
silica
harus
dikombinasikan
menjadi
C3S,
semua
iron
oxide harus
dikombinasikan
dengan
jumlah
sama
dari
alumina
menjadi
C
4
AF,
dan
sisa
alumina
harus
dikombinasikan
menjadi
C3A.
Diekspresikan
dalam
bagian berdasarkan berat :
1 bagian SiO
2
dalam C3S mengikat
3
56
60
2.8 bagian CaO
1 bagian Al2O3 dalam C3A mengikat
3
56
100
1.65 bagian CaO
1 bagian Al2O3 dalam C
4
AF mengikat
2
56
102
1.1 bagian CaO
1 bagian Fe
2
O3 dalam C
4
AF mengikat
2
56
160
0.7 bagian CaO
Untuk
memasukkan total alumina dalam satu posisi satu
harus
di
asumsikan
bahwa
C
4
AF
mengandung
C3
A
+
CF.
Kemudian
CaO
56
0.35 , sebagai
contoh
1 bagian
Fe O3
mengikat
hanya
Fe
2
O
3
2 3
160
0.35 bagian CaO.
|
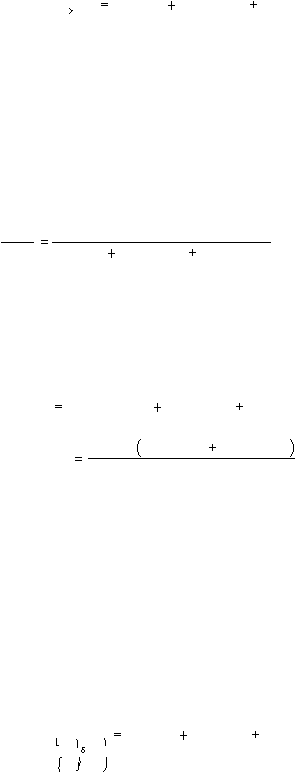 28
TM
Kemudian jumlah maksimum dari
lime adalah ( dalam alumina ratio >
0.64 )
CaO
max(TM
0.64)
2.8SiO
2
1.65 Al
2
O
3
0.35Fe
2
O
3
Hasil yang sama dapat didapat jika C2S dlaam Bogue-formula sama
dengan nol, atau, dalam Kind formula ( lihat bawah ) KS
K
=1
Kemudian level lime dalam clinker di karakteristikkan berdasarkan faktor
saturasi lime (LSF), sebagai contoh berdasarkan ratio effektif kandungan
lime sampai maksimum memungkinkan kandungan lime dalam clinker.
KSG
LSF
100CaO
2.8SiO
2
1.65 Al
2
O
3
0.35Fe
2
O
3
( pers 4 )
Kind’s formula, yang digunakan di Uni Soviet berdasarkan asumsi bahwa
hasil
saturasi
lime
yang
tidak
komplit
hanya
dari
derajat
rendah
dari
pengikatan antara lime dan silica.
CaO
KS
K
.2.8SiO
2
1.65 Al
2
O
3
0.35Fe
2
O
3
CaO
1.65 Al O
0.35Fe
O
dan membentuk
KSK
2 3
2 3
2.8SiO
2
( pers 5 )
Untuk tujuan teknis, tingkatan faktor saturasi lime, menurut rumus pers 5,
berfluktuasi antara 0.80 dan 0.95.
Dalam
clinker
memperlihatkan
kandungan
iron
oxide
yang
tinggi
(alumina
ratio,
AR
<
0.64),
alumina mengikat hanya pada tahapan
pencampuran
kristal
C2(A,F),
dan
kandungan
maksimum lime
seperti
halnya faktor saturasi lime adalah:
CaO
2.8SiO
2
1.1Al
2
O
3
0.7 Fe
2
O
3
max
0.64
AR
|
 29
TM
KSG
0.64
100CaO
LSF
AR
2.8SiO
2
1.1Al
2
O
3
0.7Fe
2
O
3
Jadi juga, faktor rumus kind merubah AR
0.64.
2.1.4.7.2 Standar
lime
Bagaimanapun juga,
ini
bukan kasus
dengan clinker yang
mengandung
C3A. Pada sintering
temperatur sekitar 1450
C, mineral silica C3
S
dan
C2S,
dan
kemungkinan tidak
mengubah
urutan
lime
dalam
tahap
yang
tetap,
dimana
seperti
C3A
dan
C3AF
berada
dalam tahap
perpaduan.
Bagaimanapun juga,
tahap
cairan
lebih
rendah dalam lime
kemudian
ia
akan dihasilkan dari partisipasi dalam C3A; untuk membuat komplit C3
A,
kekurangan lime
dapat
ditambah
dengan
menyuling
kekurangan lime
seteleh
proses
kristalisasi dari
lime
tetap, dinamai
lime
bebas
dan
C3S.
Bagaimanapun juga,
proses
ini
tidak
dapat
di
selesaikan
setelah
pendingingan cepat klinker secara teknis; secara praktek, cairan
aluminate tidak dapat mengikat lebih banyak lime ketika dia sudah
terlebih dahulu
diserap
pada
sintering
temperatur
(“frozen
equilibium”,
menurut
kühl).
Pengalaman
investigasi
menunjukkan bahwa
semakin
banyak lime jenuh cairan aluminate
mengikat
dua molekul CaO per
Al2O3. Oleh sebab itu, dibawah kondisi teknis, ini adalah batas lime yang
bisa diterima, yang disebut “standar lime”
CaO
S
tan d
2.8SiO
2
1.1Al
2
O
3
0.7Fe
2
O
3
|
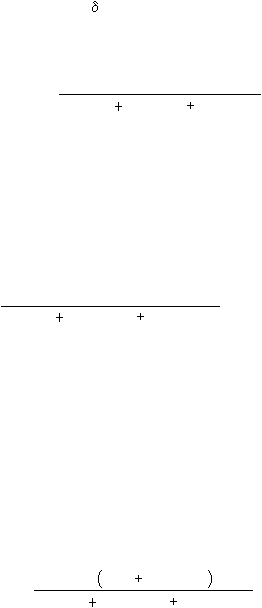 30
Rumus ini menunjukkan
koefisien
yang sama seperti lime saturation
factor dengan alumnina ratio AR
0.64. Dari sini kita dapat standar lime
seperti ratio dari kandungan lime yang sebenarnya sebagai standard lime :
KSt (Lime Standard) =
100CaO
2.8SiO
2
1.1Al
2
O
3
0.7 Fe
2
O
3
( pers 6 )
Kemudian standar
ini
dikenal sebagai
Lime
Standard I
(KSt I),
untuk
membedakan rumus ini dari investigasi seksama berdasarkan seperempat
system CaO – SiO
2
–
Al2O3
–
Fe2
O3
dan dikenal sebagai Lime Standard
II (KSt II)
KSt II =
100CaO
2.8SiO
2
1.18 Al
2
O
3
0.65Fe
2
O
3
( pers 7 )
Perbedaan
hasil
koefisien
dari
pemeriksaan yang
tepat
dimana
yang
menunjukkan dalam
bentuk
cair
molekul
CaO
mengikat per
Al2
O3
dan
berdasarkan perhitungan, untuk mengikat Fe2
O3
hanya membutuhkan 4 –
2.15 = 1.85 molekul CaO.
baru-baru
ini,
kemurnian lebih
lanjut
dari
rumus
standar
lime
kühl
dikemukakan, sebagai pertimbangan kandungan MgO
100
CaO
0.75MgO
KSt III =
2.8SiO
2
1.18 Al
2
O
3
0.65Fe
2
O
3
Untuk rumus penyaringan, Kandungan MgO hanya sekitar 2 % saja yang
dapat digunakan, sejak batasan ini, MgO muncul sebagai periclase.
Umumnya,
KSt
II
yang
biasa
digunakan. Nilai
ini
persis
mengikuti
“
Faktor
saturasi
lime
“
Inggris. Ia
sama
dengan
standar
lime
(
KSt )
|
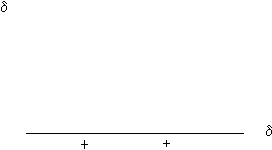 31
Jerman, tetapi tidak sama dengan faktor saturasai lime ( KSG ) Jerman.
Untuk TM
0.64, tidak ada perbedaan antara Kst dan KSG.
“Faktor saturasi
lime
“
juga
merupakan bagian standar
perincian,
dan
wadah untuk kandungan lime yang dapat diterima.
LSF =
CaO
0.7SO
3
2.8SiO
2
1.18 Al
2
O
3
0.65Fe
2
O
3
=
1.2 - = 0.66
Dalam rumus ini LSF mengarah ke pencampuran akhir semen. Faktor 0.7
SO3 dalam
perhitungan
berarti
kandungan
CaO
yang
sama
dengan
penafsiran analys kandungan SO3
,
harus dikurangi dari total kandungan
CaO. Dalam
hubungan dengan
ini diasumsikan bahwa
total SO3 berasal
dari tambahan gypsum dan bukan dari clinker.
Standar
lime
yang
tinggi biasanya
menyebabkan kekuatan
semen
yang
tinggi.
Nilai
standar
lime
yang
terkandung di
dalamnya
merupakan
karakteristik semen Portland:
Strandar Semen Portland
90 – 95
Kekuatan tinggi awal semen
95 – 98
Lime
yang
bebas
disebabkan oleh
standar
lime
diatas
100.
Bagaimanapun, standar
lime
yang
tinggi
memerlukan
komsumsi panas
yang tinggi untuk pembakaran clinker.
|
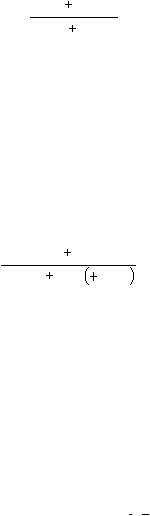 32
E
2.1.4.8 Modul-modul Lain
Di Perancis kandungan lime dirata-ratakan
berdasarkan index hydraulic;
dibaca ( dalam mol ):
SiO
2
Al
2
O
3
CaO
MgO
=
0.42 – 0.48
Bagaimanapun, standard Perancis yang diterima ( NFP 15-302,1964 ) tidak
lagi mengandung unsur ini.
Dibawah ini
lebih banyak rumus
yang dikutip: berikutnya
merupakan
percobaan
untuk
mengekspresikan silica
ratio
yang
dikenal
dalam
bentuk
lain:
C
3
S
C
2
S
( pers 8 )
SM =
C
4
AF
C
3
A
C
2
F
Peningkatan SM secara berkala meningkatkan daya tahan terhadap kimia dan
serangan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan atmosfir dan menyebabkan
terutama kekuatan semen yang lebih tinggi.
Ratio Pengerasan :
M =
C
3
S C
2
S
Dengan
peningkatan
M
E
ada
juga
peningkatan dalam
kekuatan
awal
dari
semen, peningkatan dalam suhu hydrasi dan penurunan daya tahan terhadap
serangan
kimia.
Standar
semen
M
E
diatas 0.5.
Kekuatan awal
semen
yang
tinggi
memiliki M
E
sekitar 8; Semen dengan M
E
<
0.5 adalah semen belitic
dan cenderung menghancurkan diri dalam clinker.
|
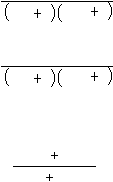 33
S
S
Kombinasi
dari kedua
modul,
contoh
M
S
dan
M
E
menunjukkan
hubungan
yang lebih dekat antara modul ini dan C3S dan C2
S
berturut-turut :
C3
S
=
M
M
S
.M
E
1
.
M
E
1
C2
S
=
M
M
S
1
.
M
E
1
Rumus Caloric :
C
S
C
A
M
K
=
3
3
C
2
S
C
4
AF
Peningkatan
M
K
menyebabkan
peningkatan suhu hydrasi
semen.
Kutipan
nilai untuk M
K
berada dalam batas 0.3 dan 1.8.
2.2
Kerangka
Berfikir
Dari
hasil
teori dan temuan yang dikemukakan pada sub baigan 2.1 diatas
maka pada sub bagian 2.2 ini akan membahas
teori-teori
yang berisi defenisi-
defenisi
yang
lebih
detail
yang
berhubungan dengn
pemodelan
dinamik
proses
pengumpanan material pada pabrik semen.
Diharapkan dengan membaca ini
maka
hubungan antar permasalahan, data
yang terkumpul dan teknik analisis serta hasil penelitian akan menjadi lebih jelas.
2.2.1
Motor
servo
Motor servo adalah motor dc yang secara spesifik dirancang untuk digunakan
pada system control simpal tertutup.
Dengan rangkaian motor servo :
|
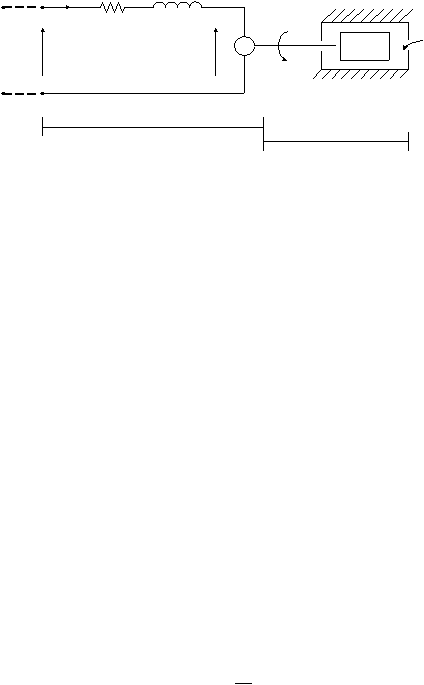 34
Rm
Lm
ea
em
J
B
?, t
Rangkaian arm atur
Beban mekanis
Gambar 2.1 Rangkaian motor servo
dimana : ea (t) = tegangan jangkar (masukan)
em (t) = back EMF
ia (t) = arus jangkar
t
(t) = torsa yang di bangkitkan
?
(t) = sudut poros motor
d? (t) / dt = ? (t) = kecepatan poros (keluaran)
Pada
gambar
ini
ea
(t)
adalah
tegangan armature, yang
dianggap sebagai
masukan
system. Resistansi
dan
induktansi
rangkaian armature
adalah
Rm
dan
Lm.
Tegangan
em
(t)
adalah
tegangan yang
timbul
pada
kumparan
armature karena
adanya
pergerakan
pada
kumparan
didalam
medan
magnetik
motor, dan biasanya disebut sebagai
EMF
balik. Sehingga dapat
ditulis :
em (t) = k F
d?
……………………….
( 1 )
dt
sehingga k adalah parameter motor, F adalah fluks medan dan ? adalah poros
motor.
Jadi
d?
/
dt
adalah
kecepatan
sudut
poros.
Diasumsikan fluks
F
konstan, maka :
|
 35
d?
em (t) = km
……………………….
( 2 )
dt
perlu dicatat bahwa asumsi ini sangat penting. Jika fluks merupakan variabel
system,
persamaan (
1
)
menjadi
persamaan nonlinear,
karena
adanya
perkalian
dan
2
variabel.
Kemudian analisa
akan
menjadi jauh
lebih
sulit,
khususnya
tranformasi laplace
tidak
dapat
digunakan. Diingatkan kembali
bahwa transformasi laplace dari perkalian untuk persamaan ( 2 )
tidak sama
dengan perkalian transformasi
Transformasi laplace untuk persamaan ( 2 ) menghasilkan :
Em (s) = km S T (s)
………………
( 3 )
Untuk rangkaian armature dapat dituliskan
Ea (s) = ( Lm S + Rm ) Ia (s) + Em (s)
……….…… ( 4 )
yang menyelesaikan Ia (s)
Ia (s) =
Ea(s)
Em(s)
LmS
Rm
…………………..…..
( 5 )
Persamaan untuk torsi adalah
t
(t) = k1
F
ia (t) = k
t
ia (t) ………………….….. ( 6 )
karena
fluks diasumsikan konstan.
Persamaan
dapat
menjadi
nonlinear
jika
fluks bervariasi dengan waktu.
Transformasi laplace dari persamaan ini menghasilkan
T
(s) = k
t
Ia (s)
…………………..….. ( 7 )
Persamaan akhir diturunkan dari penjumlahan torsi-torsi pada armature
motor. Pada
gambar
diatas,
momen
inersia
J
meliputi semua
inersia
yang
|
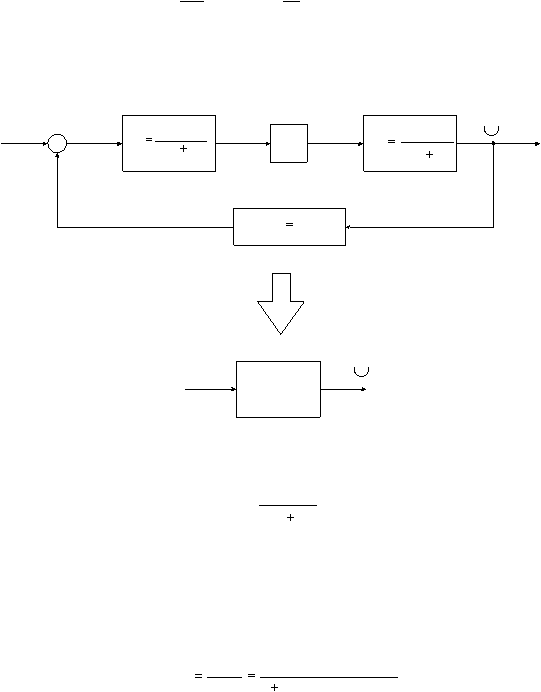 36
diasumsikan
ke
poros
motor,
dan
E
meliputi
gesekan
udara
dan
gesekan
k
bantalan poros. Maka persamaan torsi adalah :
d
2
?
J
dt
2
=
t
(t) – E
d?
dt
……………..……
( 8 )
Dan dapat ditulis
T
(s) = ( J S² + E S ) T (s)……………………….
(
9 )
Ea
+
G1
1
SLm
Rm
Ia
T
t
G
2
1
JS²
ES
Em
H(s)
k
m
S
Ea
G
(s)
Gambar
2.2
Diagram
blok
Motor Servo
T
(s) =
T(s)
JS²
ES
…………………………
( 10 )
Sekarang diagram blok dapat dibentuk dari keempat persamaan ( 3, 5, 7, 10 )
yang terlihat pada diagram blok diatas. Dari rumus Bati Mason dapat ditulis
fungsi alih motor:
G(s)
T(s)
Ea(s)
G
1
(s)k G
t
2
(s)
1
k G
t
1
(s)G
2
(s)H(s)
……………. ( 11 )
|
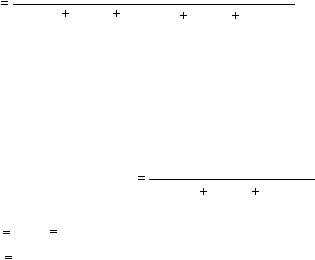 37
Evaluasi ekspresi ini menghasilkan
G(s)
JLmS³
k
t
(ELm
JRm)S²
(ERm
k
t
km)S
………
( 12 )
Pendekatan
yang biasa dilakukan
untuk
motor
servo
adalah
mengabaikan
induktansi armature Lm. Untuk Lm yang cukup kecil untuk diabaikan, fungsi
alih menjadi orde 2 yaitu
G(s)
JRmS²
k
t
(ERm
k
t
km)S
x
1
(t)
?(t)
x
2
(t)
ia(t)
d ?(t)/dt
2.2.2 Komposisi
Salah
satu
bagian
penting
dalam analisa
material feeder adalah disamping
analisa
cara
kerja
mesin
adalah
bahannya.
Bahan
pembuatannya cukup
banyak. Namun
yang akan dianalisa hanya 4
yaitu
Limestone, shale, Silica
dan Iron.
Hal
ini dikarenakan keempat bahan
ini
adalah
yang dominan dan
merupakan bahan utamanya. Sedangkan bahan yang lain persentasenya
sangat kecil sehingga dalam analisa ini dapat diabaikan.
Campuran-campuran
yang diperlukan
untuk membuat keempat bahan
tersebut
adalah
CaO,
SiO2,
Al2
O3
dan
Fe2
O3.
Untuk
persentase masing-
masing
keempat bahan
akan
dibahas
berikut
ini.
Ada
3
variabel yang
digunakan
untuk
menentukan sifat
suatu
semen,
yaitu
SM,
AM
dan
LSF.
Hubungan
ketiga
variabel
tersebut dengan
kandungan semen
dapat
dilihat
sebagai berikut:
|
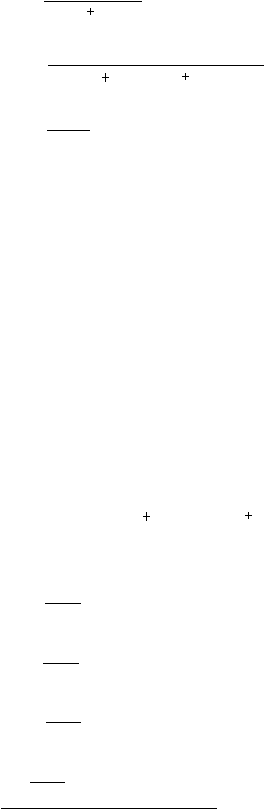 38
SM =
LSF =
SiO
2
Al
2
O
3
Fe
2
O
3
CaO
AM =
2,8SiO
2
1,65 Al
2
O
3
0,35Fe
2
O
3
Al
2
O
3
Fe
2
O
3
Pada databook, diperoleh
nilai
AM
berkisar
antara
1,5
s/d
2,5,
nilai
SM
berkisar antara 1,6 s/d 3,2, serta nilai LSF berkisar antara 0,8 s/d 0,95.
Maka nilai LSF, AM dan SM dapat diasumsikan sebagai berikut:
AM = 2
LSF = 0,8
SM = 2,5
Maka perbandingan persentase tiap campuran dapat dihitung sebagai berikut:
A = AM . F
S = SM AM + SM
C
=
2,8.SM .AM .LSF
1,65.AM .LSF
0,35.LSF
Total = C + S + A + F
%C =
%S =
%A =
C
Total
S
Total
A
Total
100%
100%
100%
F =
F
Total
100%
Total
= 100%
|
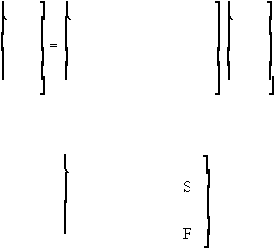 39
Maka kandungan Limestone, Shale, Silican dan Iron dapat dituliskan dalam
bentuk matriksnya sebagai berikut:
% C
C
LS
C
SH
C
Si
C
Fe
%
L
S
%
S
S
LS
S
SH
S
Si
S
Fe
.
%
S
H
%
A
A
LS
A
SH
A
Si
A
Fe
%
Si
%
F
F
LS
F
SH
F
Si
F
Fe
%
Fe
Nilai Limestone, shale, silica dan Iron tergantung pada
C
LS
S
LS
A
LS
F
LS
C
SH
S
SH
A
SH
F
SH
C
Si
S
Si
A
Si
F
Si
C
Fe
Fe
A
Fe
Fe
Nilai
masing-masingnya
tergantung
pada
standarisasi
pada
masing-masing
industri semen. Tentunya juga berdampak pada sifat semen yang dihasilkan.
Nilai kandungan Limestone, shale, silica dan Iron akan dimasukkan ke
persamaan state space putaran motor.
Persamaan baku state space motor adalah:
?
m
'
= A ?
m
+ B U
maka
nilai
kandungan
material
dimasukkan ke
U,
dalam
hal
ini
u
adalah
tegangan masukan (ea).
2.2.3 State
Space
Persamaan matriks dasar digunakan untuk menjelaskan konsep dari
keadaan dan metode penulisan untuk menyelesaikan
persamaan keadaan.
Keadaan
suatu sistem, dilihat
secara
struktur matematikanya berisi sejumlah
variabel x1
(t), x
2
(t),…,x
i
(t),…x
n
(t), yang dinamakan state variable. Nilai initial
|
|
40
x1(t
0
)
dan input sistem uj(t) memenuhi persyaratan untuk menjelaskan respons
sistem yang akan datang dari t = t
0
.
Sejumlah variabel keadaan x1(t) menjabarkan elemen-elemen atau
komponen pada n-dimensional vector keadaan x(t).
Nilai
orde
dari
suatu
persamaan
karakteristik
sistem adalah
n
dan
persamaan
keadaan
yang
menjabarkan
suatu
sistem meliputi
n
persamaan
diferensial orde pertama.
State space adalah n-dimensional space di mana setiap komponen dari
vector keadaan menjabarkan koordinat axis. Bentuk persamaan state space orde
pertama
untuk
multiple
input
multiple output sistem, dengan
m
input
dan
1
output, persamaan umumnya adalah :
X
AX
BU
Y = CX + DU
Dimana:
A adalah state matrix
B adalah kontrol matrix
C adalah output matrix
D adalah feed forward matrix
U adalah control vector
Y adalah output vector
|
 41
h
2.2.4 Runge
Kutta Orde
4
Metode
Runge
Kutta
orde
4
adalah
akurat untuk perhitungan orde 4 pada
pengembangan dari deret Taylor, dan arena itu, kesalahan pemotongan yang terjadi
adalah
0(h
5
). Metode
Runge
Kutta
orde
4
adalah
paling
sering digunakan.
Ada
beberapa versi metode dari Runge-Kutta dan di bawah ini adalah yang biasa
dipakai dalam perhitungan.
2.2.4.1 Persamaan definisi yang dipakai
Persamaan umumnya adalah sebagai berikut:
yi
1
yi
h
k1
2k 2
2k 3
k 4
6
dimana :
k1
f
xi, yi
k
2
k
3
f
xi
f
xi
1
h, yi
2
1
h, yi
2
1
1
2
1
hk 2
2
k
4
f
xi
h, yi
hk 3
Metode Runge Kutta dipakai
untuk
membuat variable set point dari
input
suatu sistem menjadi variable yang aktual dan dipakai sebagai redaman pada suatu
sistem.
|
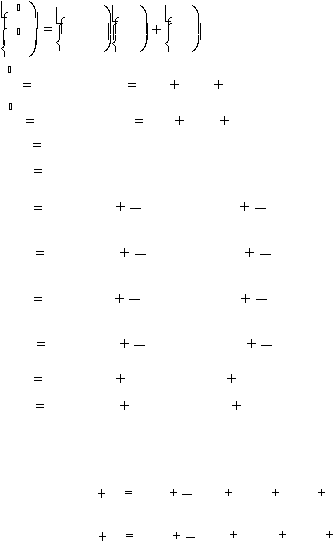 42
2.2.4.2 Persamaan antar
k11, k12, k21, k22, k31, k32, k41, k42
x1
a
b
x1
b1
u
x
2
c
d
x
2
b
2
x1
x
2
f
1( x1, x 2, u )
ax1
bx 2
b1u
f 2( x1, x 2, u )
cx1
dx 2
b 2u
k11
k12
k
21
f
1( x1(i), x 2(i), u )
f 2( x1(i), x 2(i), u )
f
1(( x1(i)
1
h.k11), ( x 2(i)
1
h.k12 ), u )
2
2
k
22
f 2(( x1(i)
1
h.k11), ( x 2(i)
1
h.k12 ), u )
2
2
k
31
f
1(( x1(i)
1
h.k 21), ( x
2(i)
1
h.k 22 ), u )
2
2
k
32
f 2(( x1(i)
1
h.k 21), ( x 2(i)
1
h.k 22 ), u )
2
2
k
41
k
42
f
1(( x1(i)
h.k 31), ( x 2(i)
h.k 32 ), u )
f 2(( x1(i)
h.k 31), ( x 2(i)
h.k 32 ), u )
…………………..(13)
2.2.4.3 Persamaan
Solusi
x
1
(i
1)
x
1
(i)
h
(k11
2k 21
2k 31
k 41)
6
………………(14)
x
2
(i
1)
x
2
(i)
h
(k12
2k 22
2k 32
k 42)
6
|