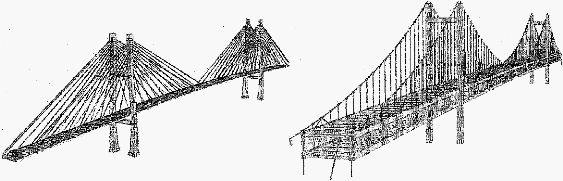 BAB2
TINJAUAN
KEPUSTA.KAAN
2.1
Jemllatan
Bentang Panjamg
Jembatan bentang panjang adalahjembatan
yang memiliki panjang bentang tengah
lebih
dari
100
meter. Jembatan
bentang
panjang
pada
umumnya
didesain
dengan
menggunakan
st:ruktur
kabel penggantung baik secant langsung maupun tidak langsung
untuk memenuhi kebutuhan bentang yang panjang. Salah satu tipe jembatan yang paling
efisien
untuk
jembatan bentang panjang
adalah tipe
sw:pended span bridges, yaitu tipe
cable stayed
dan
tipe
suspension.
(a) cable stayed
(b) suspension
Gll!mbar 2.1.Suspended span
bridges
Di
libat
dari
segi panjang bentang utamanya
ada perbedaan antarn jembatan tipe
cable stayed
dan
jembatan tipe
suspension.
Jembatan
tipe
cable stayed
banya
bisa
digunakan
untuk
bentang
utama
dengan
panjang
maksimal
1000
m.
Untuk
jernbatan
yang rnerniliki bentang utama lebih dari 1000 m
digunakan jembatan tipe suspension.
|
|
9
'-'
-'-
-'
'-''-'
....
....
-'
._
"'-
._
...,
._..
._,
J
-'
'-"
2.2
Jembatan Cable Stayed
Jembatan
cable
stayed
adalah
strulctur yang mempunyai sederetan kabellinear
dan
memilrnl
elemen
horisontal
kalrn
(misalnya balok atau
mngka
hatang).
Jemhatan
cable
stayed
terdiri
atas
sistem struktur
yang
meliputi
suatu dek
dan
balok
girder
menerus
yang
didulrnng oleh
penunjang, be:rupa
kebel yang dibentang miring
dan
dihubungkan
ke
menara sebagai tunjangan utamanya. Kabel-kabel tersebut umumnya menyebar dari
sam
atau !ebih tiam!tekan
renvanl!l!a. Keselurnhan
sistem
danru:
memnunvai
bentanl!
besar tanpa harus menggunakan kabellenglrnng yang rwnit. DeWliSa
ini, banyak
struktur
jembatan yang
dibangun dengan
cam
dem.ikian.
Untuk jembatan
dengan
berrtang yang
cukup
panjang
diperlukan
struktur
kabel
(cable
stayed)
yang berfungsi
sebagai
pilar-
nilar
ren!!hubunl!
dalam
memilrnl sebll.l!ian besar dari
beban iembatan van!! kemudian
dilimpahkan ke pondasi.
Dwi
fungsi
sistem
cable stayed
ialah sebagai perletakan antara
dari bentangan gelagar pengaku dan
sekaligus sebagai penahan untuk stabilitas menara.
Setiap 1:ahapan
konstruksi
dilihat
dari
besamya
gaya-gaya
dalam
tidak
boleh
melampaui
kapasitas
penampang
pada
tahap
akhir
pembebanan, perpindahan
titik
puncak
tower
dan
lendutan
lantai
jembatan
harus memenuhl
yang
disyaratkan dalam
perencanaan dalam pelaksanaan konstrnksi jembatan.
Pada kasus
jembatan
sistem
cable
stayed,
pada
tahap akhlr dari pembebanan
(heban
konstruksi),
displacement
dari
puneak
tower
hams
sekeeil
mungkin
dan
masih
dalam
toleransi. Demikian
pula
dengan
lendutan
pada
lantai jembatan.
Sebagai
syarat,
bahwa
displacement
dari
lantai pada posisi kabel
(stay support)
akibat beban konstruksi
bekelja
harus
sekecil
mungkin. Dengan
dicapainya
lendutan
pada
posisi
kabel yang
kecil, bidang momen
dari lantai
jemhatan
menjadi
optimum
dan
hahkan
dapm
dicapai
|
|
10
kondisi momen positif hampir sama
dengan momen negatif pada setiap peralihan antar
tumpl!all
stay.
Untllk
mendapatkan
kondisi
keseimbangan tersebut
dapat
dilalrukan dengan
mengaplikasikan gaya pratekan (gaya aksial) pada kabel. Dengan eara demikian, setiap
tahapan pelaksanaan konstruksi jembatan besarnya gaya pratekan dapat ditenrukan. Pada
analisa struktur
jembatan sistem cable
stayed, metode konstruksi al(an menenrukan
tahapan analisa.
Pada jembatan
cable stayed,
beban
ekstemal
dipilrul bersama oleh sistem kabel dan
elemen primer
yang
membentang
dan
berfungsi
sebagai balok atau rangka
batang.
Jumlah
kabel
yang
digunakan
tergantung
pada
ukuran
dan
kekakuan batang
yang
terbentang. Kabel
dapat
beljarak
dekat,
sehingga
balok
atau
rangka
batang
yang
digunakan dapat
berukman
relatif
kecil
atau
jarak
antara
kabel
tersebut
lebih
jauh
sehingga balok atau
rangka
batang yang lebih
besar
dan
lebih kaku harus
digunakan.
Umumnya, jembatan
cable
stayed
digunakan
apahila
bentang
yang
ada
melebihl yang
mU!lgkin Ulltuk
pemakaian balok atau rangka batang dalam memilrul berat sendiri.
Kabel selalu
mengalami tarik. Menentukan gaya kabel dapat sederhana atau rumit,
tergantung
pada banyak kabel
di
dalam sistem dan kekaknan relatif balok atau
rangka
batang. Pendekatan avval
yang
berglllla
1lllruk
mendesain
kabel
dan
sistem
penyangga
adalah dengan mengabaikan kekakuan balok atau rangka batang dan menganggap sistem
kabel yang memilrul seluruh
beban.
Sudut
yang dibentuk antara
kabel
dan
arah
beban
memegang peranan
penting.
Sudut
yang
kecil
perlu
dihiindari
karena
kabel
tidak
memberikan kekaknan yang yang eukup
dalam memilrul balok, dan
gaya
yang timbul
dalam kabel akan
menjadi sangat besar. Penggunaan kabel memberikan suatu gambaran
|
|
11
barn
kepada
telrnik konstruksi
jembatan
bentang
panjang. Aplikasi
yang
diperbarui
sistem
cable stayed
hanya
mungkin
mengilruti
kondisi sebagai berikut:
a. Perkembangan analisa dari sistem
struki:ur.
b.
Penggunaan
tegangan
batang
berdasarkan berat
sendiri dengan mempertimbangkan
derajat kekakuan dalam mencapai
pratekan tinggi,
dan di samping itu
dengan
kapasitas yang ada culrup untuk mengakomodasi beban hidup.
c_
Penggunaan
metode pendirian
yang
memastikan bahwa
asumsi desain direalisir
secara ekonomi.
Suatu
penelitian
antara
jembatan
gantung
(jembatan
tipe
suspension)
dan jembatan
cable stayed
menunjukkan bahwa kelebihan
jembatan
cable stayed
lebih ungglll
daripada jembatan
gantung. Kelebihan jembatan
cable stayed
antara lain
rasio panjang
bentang utama dan tinggi pilon yang lebih rendah. Defleksi akibat pembebanan simetris
dan
asimetris
pada lebih
dari
separuh bentang jembatan
gantung mempunyai defleksi
yang lebih besar di
tengal1bentang
daripada
cable stayed.
Keuntungan yang
menonjol
dari
cable
stayed
adalah
tidak
diperlukan
pengangkeran kabel
yang berat dan
besar seperti
jembatan gantung. Gaya-gaya angker
pada ujung kabel
bekelja secara vertikal
dan
biasanya diseimbangkan dengan berat dari
pilar
dan pondasi
tanpa
menambah
biaya konstruksi
lagi.
Komponen
horisontal
gaya
pada kabel dilimpahkan pada struktur atas gelagar berupa takanan dan tarik
2.3
Eh men Jembatan CO!ble Stayed
Elemen
jembatan
cable stayed
dibagi menjadi
dua
bagian
utama,
yaitu
elemen
struktur
atas
jembatan
dan
elemen
struktur
bawah
jembatan. Elemen
struktur
atas
jembatan terdiri dari struktur
tower
(mensra), struktur dek
I
gelagar, dan struktur kabel.
|
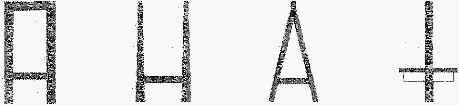 12
Sedangkan
elemen
struki:ur
bawah
jembatan adalah
pondasi
yang
menopang seluruh
beban struktur atas jembatan. Pondasi yang digunakan biasanya pondasi dari kelompok
tiang
berukuran besar untuk memilian gaya-gaya besar yang menumpu pada pilon dan
diteruskan ke pondasi dari elemen
struki:ur
atas jembatan.
1.3.1
StlrliLirtlllr
Tower
(ll;'ilenara) Jemllatan Cable Stayed
Pemilihan
bent1lk
tower
I
menarn
sangat
dipengaru.hi
oleh bentuk
kabel, estetika,
dan kebutuhan
perencanaan
serta
pertimbangan biaya.
Bentuk-bentuk
menara
dapat
berupa rangka portal trapezoidal, menara kembar, menara
A,
atau menara tunggal.
Selain
bentuk menara yang te!ah disebulkan, masili banyak
bentuk
menara
lain
namun jarang dipergunakan seperti mern1m
Y,
menara
V,
dan
lain sebagainya. Bentuk-
bentuk menara yang
umum
digunakan adalah seperti yang ditunjukan gambar 2.2.
(a}
menara portal
{b) menara kembar
(c) menaraA
(d)
menara tunggal
Gam bar
2.2.Tipe-i:ipe menrura
2.3.2 Struktur Dek Jemllatan
Cable Sttzyed
Bentuk dek
I
gelagar jembatan cable stayed sangat bervariasi. Namun, yang paling
sering
digunakan
ada
dua
yaitu
stiffening truss
dan solid
web (Podolny
dan Scalzi,
1976). Stiffening
truss
digunakan
untuk
struktur
baja
dan
solid
web
digunakan
untuk
struktur baja atau beton baik beton bertulang maupun beton prategang.
|
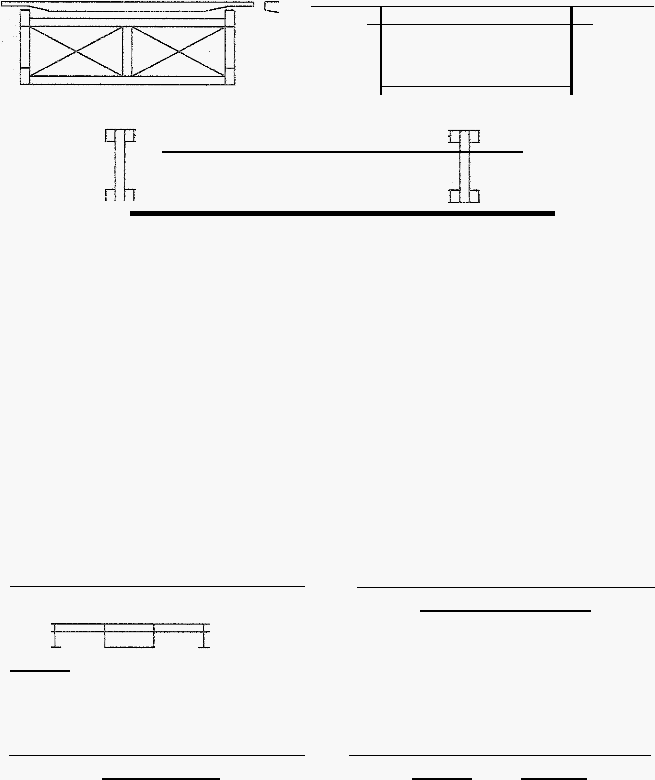 13
I
I
II
Beberapa bentuk dari stiffening truss dapat dilihat pada gambar 2.3.
(a)untukjalan
raya
(b)
untuk jalan
raya dan
jalan kereta api
liAS!I
(c)
untukjalan mya danjalan lrereta api
Grunlllar 2.3. Deli.
f
gelagar sdffmilllg truss
(Smnlller:Troitslky, 1977)
Gelagar yang tersusun dari solid web yang terbuat
dari
baja
atau beton cenderung
terbagi atas dua tipe seperti pada garnbar 2.4, yaitu:
a.
gelagar
pelat
(plate girder), dapat terdiri
dari
dua atau banyak gelagar.
b.
gelagar
box (box
girder),
dapat terdiri
dari
satu atau susunan
box
yang
dapat
berbentuk persegi panjang atau trspesium.
(a)
gelagar 1
kembar
(b)
gelagar horpersegi
(c) -kombinasi gelagar box
"
""""''
17
J
(d)
Kombinasi gelagar bax selu!ar
kembar individual dengan sloping stn-!ts
(e) geiagar box trapezoidal
(f)
ge!agar box persegi kembar
Gamlllar 2.<1.Gelagar
solid web
(Smnlller: Troitslky, 1977)
|
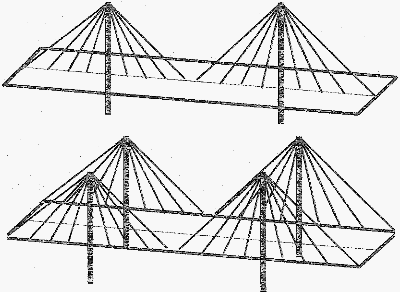 14
2.31.3 Strnldur Klltllel Jemi:Patan
Cable Stayed
Sistem
kabel
merupakan
salai:P sam hal yang
mendasar
dalam
perencanaan
jembatan
cable
stayed.
Kabel
digunakan
untuk
menopang
dek atau gelagar
diantara
dua
rumpuan
dan
memindahkan
beban
tersebut
ke
menara.
Secara
umum
sistem
kabel
dapat
dilihat
sebagai
tatauan
kabel
transversal
(tatanan
kabel
terhadap
aral1 sumbu
memanjang)
dan
tatanan
kabel
longitudinal
(tatanan
kabel pada
sumbu
memanjang)
pada
jembatan cable stayed.
a.
Tatanan Kabel
TrllnSllersal
Jembatan
Cable Stayed
Tatanan
kabel
transversal
dapat
dibuat sam
atau
dua
bidang
dan
sebaliknya
ditempatkan
secara
simetri.
Adapun
perencanaan
yang
menggunakan
sistem
tiga
bidang kabel, tetapi
sampai sekarang belum dapat
diterapkan di
lapangan.
(a}Sistem satu bidang
(b) Sistem dua bidang
Gamba!!' 2.5.Tamrum l!mbe
t
l
ronsvenal
pallia jembatim
cable stayed
|
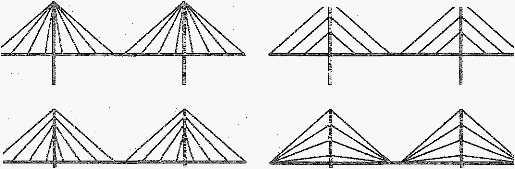 15
b. Tatanan
Kabel longitudimd Jembatlln Cable Stayed
Penataan
kabel
longitudinal
pada jembatan
sangat bervariasi
tergantung
dari
perencanaan dan
pengalarnan dalam menentukan
perbandingan
antara bentang
dengan tinggi menara. Pada jembatan dengan bentang yang pendek mungkin dengan
menggunakan kabel tunggal sudah cukup
untuk menahan beban rencana. Jembatan
dengan
bentang utama
yang panjang diperlukan tatanan kabel cukup banyak
sehingga menghasilkan dasar tatanan kabe! longitudinal sepeti pada gambar 2.6.
(a)
tipe
terpusat
(c) tipe kipas
(b)
tipe barpa
(d) ripe binumg
Gmnbar 2.6.Tatm:l.lm
kabellongitMdinal
pooa
jembamn
cable stayed
Pemilihan
tatanan
kabel
tersebut
didasarkan
atas berbagai
hal
karena
akan
memberikan pengaruh yang berlainan terhadap perilaku stuklur terutama pada
bentuk menara dan tampang dek
atau gelagar. Selain itu
akan berpengaruh pula pada
metode
pelaksanaan,
biaya dan arsitektur
jembatan. Sebagian
besar
strukrur
yang
sudah dibangun terdiri atas dua bidang kabel dan
diangkerkan pada sisi-sisi gelagar.
Namun ada beberapa yang hanya menggunakan satu bidang. Penggunaan riga bidang
atau lebih mungkin dapat dipikirkan untuk jembatan yang sangat Iebar agar dimensi
balok melintang dapat lebih kecil.
|
|
16
2.3.4 Pondasi Jembatan
Coble Stayed
Pondasi jemba1lm adalah bagian
dari
sub-struktur bangunan jembatan
yang
menghubungkan
jemba1lm ke
tanah.
Suatu
pondasi te:rillri
dari elemen
struktural
yang
illbuat manusia yang illbangun ill
atas atau tanpa lapisan tanah ada. Fungsi dari pondasi
adalah
untuk
menyeillakan
sarana
pendukung
untuk
jemba1lm
dan
untuk memindahkan
beban atau energi antara struktnr jembatan dan tanah /landasan.
Pondasi illbedakan
menjaill
pondasi
dangkal
dan pondasi dalam. Pondasi
dalam
adalah
suatu
jenis
pondasi ill
mana
bidang
lekat
lebili besar
dari
dimensi
bidang
maksimumnya. Pondasi tersebut didesain untuk menyangga pada material geologi
lapisan tanah yang lebih dalam, sebab baik tanah rnaupun batuan dekat permukaan tanah
tidaklah cukup mampu untuk menanggung beban desain.
Kelebihan
dari
pondasi dalam
atas
pondasi
dangkal
bermacam-macam. Dengan
disertai material lapisan 1lmah
yang lebib
dalam, pondasi dalam
menduduld suatu area
yang
secara
relatif
lebih
kecil
dari
permukaan
tanah.
Pondasi
dalam pada
umurunya
dapat menahan beban yang lebih besar dibanding pondasi dangkal yang menempati area
yang sama dari permukaan 1lmah.
Pondasi dalam mampu menjangkau lapisan 1lmah
yang
lebih
dalam dari tahanan
tanah
atau
batuan, sedangkan pondasi dangkal tidak mampu.
Pondasi dalam dapat juga menal1ru1
gaya uplift yang besar dan beban lateral, sedangkan
pondasi dangkal pada umumnya tidak bisa.
2.4
Pondasi Dalam pada Jembatan
Tipe-tipe pondasi dalam yang biasa digunakan, antara lain:
a.
Pile
(pondasi tiang), pada mnumnya menghadirkan suatu
unsur struktural langsing
yang
dipancang
ke
dalam
tanah. Bagaimanapun,
pondasi tiang
sering
digunakan
|
|
17
sebagai
suatu
istilah
yang
umum
untuk
menyatakan semua
jenis
pondasi
dalam,
tennasuk tiang pancang, tiang bor, pondasi kaison, atau
pondasi jangkar. Kelompok
tiang digunakan untuk menyatakan berbagai pondasi dalam yang berkelompok.
b.
Shaft (pondasi lubang)
adalah
jenis pondasi yang
dibangun
dengan beton cast-in
place
(tuang
ditempat)
setelah
lubang yang
pertama dibor
atau
digali
hlngga batas
tertentn.
Rock
Socket
adalah
pondasi yang
dipasang
pada
batnan.
Pondasi
lubang
disebut juga sebagai pondasi bor.
c.
Caisson (pondasi kaison) adalah
jenis pondasi besar
yang
dibangun dengan
penurunan elemen
pondasi prakonstruksi melalui penggalian dari tanah atau batuan
pada
dasar
pondasi.
Bagian
baw-ah
dari
pondasi
kaison
pada
umumnya
tertutnp
dengan beton setelah konstruksi diselesaikan.
d.
Anchor (pondasi jangkar) adalah
suatn jenis pondasi yang didesain untuk menahan
beban daya rentang. Pondasi jangkar biasanya langsing, elemen diameter yang kecil
terdiri dari suatn tiang penguat yang dipasangkan pada lubang yang dibor oleh beton
pengisi.
Kabel
mutn
tinggi
biasanya
digunakan
sebagai
penguat
pondasi
jangkar
berkapasitas
besar. Bagaimanapun,
pondasi
mendukung
beban
pellllrikan
yang
ditempatkan pada bagian
ak:h:ir dari
suatu jembata:n, pondasi bisa
merupakan
terowongan raksasa (massive),
atau suatu sistem pondasi gabungan yang mencakup
pondasi jangkar biasa, tiang pancang, dan
pondasi bor.
e.
Spread footing (pondasi telapak
menyebar) adalah suatn jenis
pondasi yang bidang
lekat biasanya lrurang dari Iebar sisi yang
paling
keci.l.
|
 18
Bedrock
Bedrock
Anchor
(a) Foolin!l Foundation
(c) Caisson
(b)
Drilled Shaft
(d)
Driven Piles
Bedrock
|
|
19
Untuk
jembatan
yang
kecil,
pondasi
skala
kecil
seperti
pondasi
telapak
individu
atau pondasi
tiang bor, atau kelompok
tiang
pancang
ska!a kecil dapat
mencukupi.
Untuk
jembatan
yang
lebih
besar,
pondasi
tiang
diameter
besar,
pondasi
kaison,
atau
kombinasi
pondasi
mnngkin
diperlukan.
Pondasi
kaison,
pondasi
tiang
pipa
baja
diameter
besar,
atau jenis lain
dari
pondasi
yang
dibangun
dengan
penggunaan
metoda
cofferdam
(ruangan
di air yang dikeringkan
nntuk
pembangunan dasar
jembatan)
mnngkin perlu
untuk pondasi yang dibangun
didalam
air.
Pondasi
jembatan
sering
dibangun
dalam
kondisi-kondisi
tanah
yang
sulit
seperti
area tanah
longsor, tanah
yang mudah
terkikis,
tanah
yang
mudah
runtuh,
tanah
lembut
yang
sangat
mudah
dimampatkan,
lahan
timbunan,
em:lapan
karang,
dan
gua
bawah
tanah. Desain
danjenis
pondasi k:husus
mungkin diperlukan
didalam
k:eadaan
ini.
Walaupun
suatu
pondasi kelompok
tiang
terdiri
dari
sejumlah
tiang
individu,
perilaku
dari
suaiu
kelompok
tiang
bukanlah
setara
dengan
penjumlahan
dati semua
tiang
seolah-olah
mereka
adalah
tiang
individu
yang terpisah.
Perilaku
dati
suatu
kelompok
tiang
lebih
kompleks
daripada
tiang
individu
kareua
efek dati
kombinasi
tiang,
interaksi
diantara
tiang
dalam
kelompok,
dan
efek
dari pile cap.
Contohnya,
tegangan
pada
tanah
dari pembebanan
tiang
individu
akan
tidak
signifikan
pada
kedalaman
tertentu
dibawah
ujung
tiang.
Bagaimanapnn,
tegangan
lapisan
dari
semua
bagian
tiang
disehelahnya
dapat
menambah
tingkat
tegangan
pada
keda!aman 1iang
dan
basil penurunan
yang ada atau kegagalan
kapasitas
tahanan,
khususnya
jika pada
bagian
tersebut
ada
dasar
lapisan
tanah
yang
lemah.
Interaksi
dan pengarnh
diantara
tiang
biasanya berkurang
untukjarak
tiang kira-kira 7 sampai 8
diameter.
|
|
20
2.4.1 Pondasi Tiang
Pondasi tiang adalah suatu konstruksi pondasi yang berfungsi meneruskan beban
yang
berasal dati
elemen
struktu:r
bangunan atas
kepada tanah, baik
beban dalam arah
vertikal
maupun
horisontal.
Namun
demikian
fungsi
pondasi
tiang
lebih dari itu, dan
penerapannya untuk masalah-masalah lain cukup banyak diantaranya:
a. Memikul beban struktur atas.
b.
Menahan gaya angkat
(uplift)
pacta
pondasi.
c. Mengurangi penurunan (sistem tiang rakit dan cerucuk).
d.
Mengurangi amplitudo getaran dan frekuensi alarniah dari
sistem (pondasi mesin).
e.
Memberikan tambahan fuk:tor
keamanan, khususnya pada kaki jembatan yang dapat
mengalami erosi.
f.
Menahan longsoran.
g.
Sebagai
soldier piles.
Suatu
faktor
keamanan
(FK)
biasanya digunakan
untuk
mengantisipasi
kemungkinan variasi daya dukung tiang akibat kondisi tanah maupun metode konstruksi
atau
untuk menghindari penurunan secara
berlebihan
yang dapat
membahayakan
struktu:r
diatasnya.
Pondasi tiang
memperoleh daya dukungnya dari gesekan
antara
selimut
tiang
dengan
tanah
dan
dari
tahanan
ujung tiang.
Kedua
komponen
tersebut
dapat
bekerja
bersama maupun terpisah. Namun demikian pada suatu pondasi tiang umunmya salah
satu dari
komponen tersebut dapat lebib dominan. Tiang yang memiliki tahanan ujung
lebih
tinggi
daripada tahanan
selimutnya
disebut
tiang
tahanan
ujung
sebaliknya
bila
tahanan selimutnya lebib tinggi maka disebut tiang gesekan.
|
|
21
a.
Klasi:fikasi Pondasi Tiang
Berdasarkan metoda instalasinya, pondasi tiang diklasifikasikan atas:
');>
Tiang pancang, adalah
sebuah
tiang yang dipancang kedalam tanah sampai
kedalaman yang culrup antuk
menimbulkan tahanan
selimut pacta
selimut tiang
atau
tahanan
pacta
ujang tiang.
Pemancangan tiang dapat dilakukan
dengan
memulru! kepa!a tiang dengan
palu
atau getaran atau dengan penekanan secara
hid:rolis. Pondasi tiang yang dipancang umanmya memberikan desakan kedalam
tanah
sehingga mencapai
tegangan kontak antara
selimut
tiang
dengan
tanah
yang relatif lebih besar.
');>
Tiang
bor,
adalah
sebuah
tiang
yang
dikonstruksikan
dengan
cara
pengga!ian
sebuah
lubang
bor
yang
kemudian
diisi
deng:
>'l material beton dengan
memberikan penulangan terlebib dahu!u.
Kedua jenis tiang diatas dibedakan karena mekanisme pemikulan beban yang relatif
tidak
sama, secara empirik menghasilkan daya dukang yang berbeda, pengendalian
mutu
yang
berbeda,
dan
cara
evaluasi yang
tersendiri
untuk
masing-masing
jenis
tiang tersebut.
Klasifikasi
tiang berdasarkan jenis
bahan
tiang dan
pembuatarmya terdiri
atas
5
(lima) kategori, yaitu:
:.- Pondasi tiang kayu, adalah jenis pondasi tiang yang paling primitif. Pondasi jenis
ini
mudah diperoleh, siap dipotong sesuai dengan panjang yang diingiukan, dan
pada kondisi lingkungan tertentu dapat bertahan lama. Tiang kayu diperoleh dari
pohon dan mempunyai diameter 150 - 400
mm, dengan panjang 6 - 15 m.
Beban
yang
dapat
dipikul
berkisar
5 - 30
ton. Pondasi tiang
kayu sangat cocok
diganakan sebagai tiang tahanan selimut. Tiang ini umunmya
mengalami
|
|
22
kerusakan ringan saat dipancang. Oleh sebab
ita,
tidak
direkomendasikan untuk
digunakan sebagai tiang tahanan ujung pada tanah pasir padat atau tanah berbatu.
Untuk
mengatasi
kerusakan pada
pemancangan
pondasi tiang
kayu
clapat
ditempuh dengan
cara
menggunakan
palu
ringan,
dan
pada
ujoognya
diberi
gelang baja, sebelum pemancangan dilakukan pemboran
(pre-drilling).
Pondasi
tiang baja,
umumnya berbentuk
pipa atau
pmfil
H
clan
umlil1mya
tiang
jenis
ini
ringan,
kuat,
mampu
menahan
beban
yang
berat
dan
penyamboogan
tiang clapat
dilakukan dengan sangat
mudah. Tiang pipa
baja
clapat
dipancang
clengan bagian
ujoog
tertutup
Jnaupoo
terbuka.
Berdasarkan
pengalaman
bentuk
ujoog
terbuka
lebih
menguntoogkan
dari
segi
kedalaman
penetrasi dan
dapat
dikombinasi
dengan
pemboran
bila
diperlukan,
misalnya
penetrasi
tiang
pada
tanah
berbatu.
Selain
itu
tanah
yang
beracla pada
bagian
dal.am
pipa
clapat
dikeluarkan dengan mudah
dan
dapat diisi kembali dengan betonjika
diinginkan.
Untuk penetrasi
ke
dal.am
tanah
berbatu
disarankan
mengguuakan
tiang
baja
profil H. Jenis ini
tidak banyak mendesak volume tanah dan tidak menyebabkan
penyembulan.
Tiang
pipa memilild inersia lebih tinggi daripacla tiang
H,
sehingga
ootuk
memilrul
beban
lateral
yang besar
tiang
pipa
lebih
menguntungkan.
Tipe
tiang
baja
lain
yang
digunakan
untuk
mernikul
beban
ringan adalah
screw pile.
Instalasi
tiang
dilakukan
dengan
cam
memutar
tiang
tersebut
ke
clalam
tanah
tanpa
adanya
penggalian.
Tiang
ini
clapat
digunakan
ootuk semua
jerris
tanah
clan
paling
sering
digunalcan ootuk
menahan
tarik
(tension piles).
Kelemahan
dari tiang baja adal.ah
korosifterhadap
asam
maupoo
rur.
|
|
23
li> Pondasi
tiang
beton
pracetak.
Sesmri dengan namanya
tiang
jenis
ini
d:icetak,
dibiarkan
curing dan
disimpan
di lapangan
sebelum
dipancang.
Bentuk
penampang tiang ini
dapat
berbaga.i rupa. Namun umunmya berbentuk lingkaran,
persegi, segitiga dan
oktagonal. Pada bagian tengab dapat d:ibuat
berlubang untuk
menghemat beret tiang
itu
send:iri.
Pondasi
tiang
beton
pracetak
d:irancang
agar
mampu menaban gaya
dan
momen lentur yang timbul
pada
saat pengangkatan
dan
tegangan-tegangan
saat
pemancangan
d:isamping
beban
yang
hams
d:ipikul.
Tipe tiang ini
dapat bersifut sebaga.i tiang selimutan maupun tiang tabanan ujung.
li>
Pondasi
tiang
beton
pratekan,
memiliki kekuatan yang
lebih
tinggi
dan
memperkecil kemungkinan kerusakan saat pengangkatan
dan
pemancangan.
Tiang
jenis
ini
sangat cocok
untuk
kond:isi
d:imana
dibutuhkan tiang yang
panjang dan
merniliki daya dukung yang tinggi.
li> Pondasi tiang komposit, merupakan gabungan antara dua
material yang berbeda.
Misalnya material baja dengan beton, material kayu dengan beton. Kesulitannya
hanya
pada ikatan
antarn kedua
material tersebut
terutama
pada material
kayu-beton sehingga jenis ini ditinggalkan. Ik.atan
antara
bahan baja
dan
beton
culrup ba.ik
b.
Penyaratan
Pmu:lasi Tiang
Beberapa persyarntan yang hams d:ipenuhi oleh
suatu
pondasi
tiang,
ya.itu:
;:;.
Untuk
menjamin
keamanan
bangunan
maka
beban
yang
diterima
oleh
pondasi
tidak boleh melebihi daya dukung tanal1 maupun tegangan yang melebihi
kekuatan baban tiang.
|
|
24
:P
Pembatasan
penurunan yang
terjadi
pada
bangunan
dengan
nilai
penurunan
maksimum yang dapat diterima dan tidak merusak struktur.
:P
Pengend.alian
atau pencegahan efek
dari
pelaksanaan konstruksi
pondasi seperti
misalnya getaran saat pemancangan atau galian atau pekeljaan pondasi yang lain
untuk membatasi pergerakan bangunan atau struktur lain diseldtarnya.
c. Prosedur Perancangan Pondasi Tiang
Prosedur
perancangan pondasi tiang
pada
umumnya mengilruti 6
(enam)
langkah
sebagai berikut:
:P
Menentukan profil dan karakteristik teknis tanah.
:P
Penentuan
ked.alaman pondasi.
:P
Penentuan jenis dan dimensi pondasi tiang.
:P
Perancangan pondasi tiang.
:P
Penentuan komposisi tiang.
:P
Pengaruh konstruksi pada bangunan disekitar proyek.
2.4.2
Pondasi Tiang Bor
Pondasi tiang
bor mempunyai karalcteristik khusus
karena
cara pelaksanaannya
yang dapat mengaldbatkan perbedaan perilakunya di
bawah pembebanan dibandingkan
dengan tiang pancang. Hal-hal yang mengakibatkan perbedaan tersebut diantaranya:
a.
Tiang bor dilaksanakan dengan
menggali lubang
bor dan
mengisinya dengan
material
beton,
sedangkan
tiang
pancang
dimasukkan
ke
tanah
dengan
mendesak
tanah disekitanya (displacement pile).
b.
Beton dicor dalam keadaan basah dan
mengalami masa curing
di
bawah tanah.
|
|
25
c.
Kadang-kadang
digunakan
casing
untuk
kestabilan
dinding
lubang
bor
dan
dapat
pula
casing
tersebut tidak dicabut karena kesulitan di lapangan.
d.
Kadang-kadang
digunakan
slurry
untuk
kestabilan
lubang
hor yang
dapat
membentuk
lapisan
lumpur
pada
dinding
galian,
serta
mempengaruhi
mekanisme
gesekan tiang
dengan tanah.
e.
Cara penggalian !ubang
bor
disesuaikan dengan
kondisi tanah.
Beberapa
masalah pada
tiang bor,
diantaranya:
a.
Besarnya reduksi kuat geser tanah akibat cara pemboran
yang berbeda.
b.
Efek
migrasi
air
dari beton ke dalam tanah.
c.
Pengaruh dari
teknik
pelaksanaan. d.
Pemikulan
beban di dasar
tiang bor. Keuntungan
pemakaian pondasi tiang bor
adalah:
a.
Metode
desain
yang semakin
andal.
Berbagai
metode
desain
yang
rasional
telah
dikembangkan
untuk berbagai
macam
pembebanan dan
kondisi tanah.
b.
Kepastian
penentuan
kedalaman
elevasi
ujung
pondasi
I
lapisan
pendukung.
Peneniuan
lokasi
yang pasti dari penggalian
untuk
pondasi tiang
bor dapat
diinspeksi
atau diuk:ur,
sedangkan
pada
pondasi
tiang
pancang
!okasi
dapat
menyimpang
dari
lokasinya akibat
adanya
lapisan
batuan, dan
faktor-faktor !ainnya.
c.
Inspeksi
tanah
basil galian.
Keandalan
dari
desain
pondasi
hanya baik bila kondisi
tanah
diketahui.
Pada
pondasi
tiang bor,
saat penggalian dapat dilakukan
pemeriksaan
mengenai
jenis tanah
untuk
membandingkan
dengan
jenis
tanah
yang
diantisipasi.
|
|
26
d.
Dapat dilakukan pada berbagai jenis tanah. Pondasi tiang bor
pada umumnya dapat
dikonstruksi pada hampir
semua jenis
tanah. Penetrasi dapat dilakukan pada tanah
kerikil, juga dapat menembus batuan.
e.
Gangguan lingkungan
yang minimal. Suara, getaran dan
gerakan dati
tanah
sekitamya dapat dikatakan minimum.
f
Kemudalmn terlmdap perubalmn konstruksi.
Kontraktor dapat
dengan
mudah
mengikuti
pembalmn
diameter
atau
panjang
tiang
bor
untuk
mengkompensasikan
suatn kondisi yang tidak terduga.
g.
Umumnya
daya
dukung yang
amat
tinggi
memungkinkan
perancangan satu
kolom
dengan
dnkungan
satn
tiang
(one
column one
pile)
sehingga
dapat
menghemat
kebutnhan untuk
pile-cap.
h.
Mudah
memperbesar
kepala
tiang
bila
diperlnkan
misalnya
untnk
meningkatkan
inersia terhadap momen.
L
Tiang bor
dengan diameter 0.5 hingga 6.0 meter sudah dapat dibuat
J.
Tidak ada resiko penyembulan
(heaving).
Namun
demikian
terdapat
juga
beberapa
kelrurangan tiang bor, diantaranya:
a.
Pelaksanaan
konstruksi yang
sukses
sangat
bergantung
pada
ketrampilan
dan
kemampuan kontraktor, berbeda dengan tiang pancang atau pondasi dangkal, dimana
pelaksanaan yang
bu:ruk
dapat
menyebabkan penumnan daya dukung yang
cnkup
berarti.
b.
Kondisi tanah di kaki tiang seringkali msak oleh proses pemboran atau sedimentasi
lumpur sehingga seringkali daya dukung ujungnya tidak dapat diandalkan.
c.
Pengeconm beton bukan pada kondisi ideal dan tidak dapat segera diperiksa.
d.
Berbahaya bila ada tekanan artesis karena tekanan ini dapat menerobos keatas.
|
|
27
Sebagai
konsekuensi dari
keandalan
yang
ditawarkan
oleh
pondasi
tiang
bor,
perhatian
yang
lebih
besar
juga
hams
dicurahkan
pada
detail
pelaksanaannya
dan
pengaruh yang potensial
terhadap per:ilaku serta biaya
konstruksinya.
Hal
ini
dapat
menuntut
investasi !anjut
Misa!nya
dibutuhkan
untuk
memperoleh
data
penyelidikan
tanah yang lebih akurat dan engineer yang berpengalarnan untuk pekeljaan inspeksi.
Karena
kedalarnan
dan
diameter
dari
tiang
bor
dapat
divariasi
dengan
mudah,
maka jenis
pondasi
ini
dipakai
baik
untuk
beban
r:ingan
maupun
untuk
struktur
berat
seperti bangunan bertingkat tinggi danjembatan.
2.4.3 Perrumerumgan
Pondasi Tiang Bmr
Daya dukung pondasi
tiang bor
mengikuti
runms
umum
yang
diperoleh
dari
penjumlahan
tahanan ujung
dan
tahanan
selimut tiang. Formula umum
daya
dukung
dapat dinyatakan dalam bentuk:
Qu=Qp+Qs
dimana :
Q.
=
daya dukung ultimit tiang (ton)
Qp
=
daya dukung ultimit ujung tiang (ton)
Q.
=
daya dukung ultimit selimut tiang (ton)
(2.1)
Metooe untuk memprediksi besamya daya dukung selimut maupun daya dukung
ujung
dapat dilakukan dengan
menggunakan metode
Reese &
Wright dan
metode
Kulhawy
a.
Daya Dukung Ujnng
Daya dukung ultimit pada ujung tiang bor dinyatakan sebagai berikut
Qp=qp.A
(2.2)
|
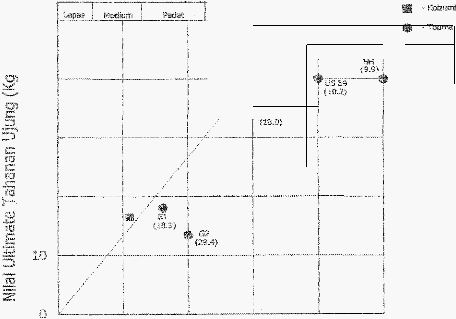 28
D
dimana :
Qp = daya dukung ultimit tiang (ton)
qp
=
tahanan ujung per
satuan luas (ton/m
2
)
A
=
luas penampang tiang bor ( )
Pada tanah kohesif besamya tahanan ujung per satuan luas,
qp
dapat diambil sebesar
9
kali
kuat geser tanah. Sedangkan
untllk tanah tidak kohesif, Reese mengusulkao
korelasi antara
qp,
dengan
NsPT
digambarkan pada gambar 2.8.
Perkiraan sudut
geser dalam
sn
r4'"''·-
r-::
·--
40
3G
2G
30
35
40
45
BB
0
20
40
60
80
100
Gambar 2.8.
Tarumom ujWJtg rutimit pada tomah
ndak
lrob.esif
(Smnber: Reese & Wright,
1977)
|
 29
;
.,.,.
V, ./:··
-
i:'.
f
/(
Bidangget
<at Aplikasi Tiang Bor
untuk Kestabilan Lereitg.
Klttusu:snya pada
l.ereng.
yang
telah
Iongs.or·. metode
ini
cu:kt11l._) baik. Tian.g
baik. Tian.g
bot
hams
masuk
iebih
daia.m
dati bidang iongsor.
El
8
<d. Arl'fkas.i Tiiang JBor untuk PlrOteksV: G&ian
Poooa..i tianr..,r J.npat dimanfaatkan
111lnmk mernahan
_gcr.!k>m
t
••
Jt,do
aki.b tt gaiian.
(e).
Apiikasi
Tiang
Bor
lllZltuk
Knnstruksi
Dok
Kava!
Pada
l><onstruksi
.dok,
pondas.i
liang
OOr d:apat
dig:una'kan untuk
rncnahan
gaya uplift.
(b\.
Apiikasi TnaVg Bor untuk Menahan Beban
Horisoptal
Contoh
di
atas
menggiimbadrnn bebart
lateral yan-g
betasal
dari
bebart angin pada papan
iktan.
MD. Aplibsi Twtg
Bw umtuk Jemhatru:r
Pada
jembatan di mana
gay2
tateml .cuku:p
besar.
penggunaan
tiang -bot-
menguntutngkan.
Lawen-a
memp-.1nyai inersia yang tin.ggi.
-rD. Aplnka.si Tianl! Bor
untuk
Pon:dasi
Gcdung
Tine:Jri
Ketompok
tiang
bor
.dapat dig:unaka.n u.ntuk
pondasi
hangtm.an-
tinggi
ba.ik untuk
m.en
han
uplift p-ada
podium
maupum_ rtlle!nahan
beban. aksial
t-ekan di
bav.cah tower.
b.
Daya Duknng Selimnt
Perhirungan daya dukung selimut tiang pada tanah homogen dapat ditnliskan dalam
bentuk:
Qs=f.L.p
(2.3)
dimana:
Qs
=
daya dukung ultimit selimut tiang (ton)
|
|
30
f
=
gesekan selimut tiang (ton/m²)
L
=
panjangtiang(m)
p
=
keliling penampang tiang (m)
);>
Metode Reese & Wright (1977)
Gesekan se!imut tiang per
satuan luas dipengarulri oleh jenis tanah dan parameter
kuat geser
tanah. Untuk tanah kohesif dan
tanah tidak kohesif
dapat
menggunakan formula sebagai berikut:
Pada tanah kohesif:
f= a.
c.
dimana:
a=
faktor koreksi
Cu
=
kohesi tanah (ton!
)
(2.4)
Berdasarkan hasil penelitian Reese faktor koreksi (a) dapat diambil sebesar 0.55.
Pada tanah
tidak kohesif, nilai
f
dapat diperoleh
dari korelasi langsung dengan
NsPT
ditampilkan pada gambar 2.10.
);>
Metode Kulhawy
Kulhawy
menyatakan bahwa faktor
adhesi pada tanah
kohesif tergantung
pada
besamya kuat geser tanah digambarkan pada gambar 2.11.
Pada tanah kohesif:
f=a.
c.
dimana:
a=
faktor adhesi
Cu
=
kohesi tanah (ton!m²
)
(2.5)
|
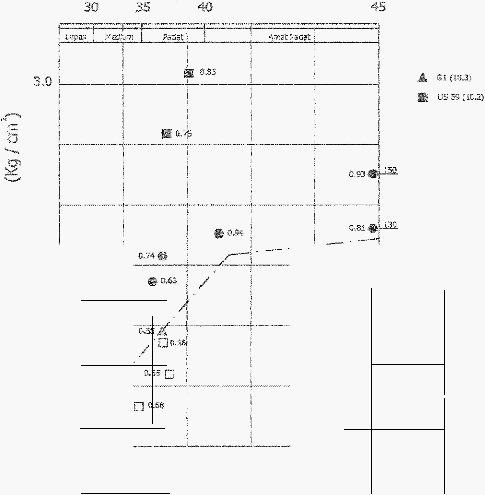 "
Pada tanah tidak kohesif gesekan selimut dihiicung
dengan formula:
f=K•.
el•.
tim
t;
dimana :
K.
Koefisien
tekanan
tanah
at rest1
-sin
¢
CTv
·
tekanan vertikal efektiftanah
(tonlm²)
¢
sudut geser da!am tanah
(2.6)
Perkiraan Sudut
Geser Da!am
-rrumbx
;:,s\:1pc!ni: ;.,. A;'(J
P.atio
-ffurn:w m ( ; <n
Kf0'1
:s
D/S R:
t:c
[J GT {46-J)
•
G2C29A)
tf.
f>Gi)RO}
""'
-
L
'!
.r
<
c
11')
cu
<I)
fJ
2J)
1.0
O.Mifl
(f:lS
A
/
/'
i)
20
40
60
80
100
Gambar 2.1II. T!lfum.an selimnt
mtimit vs
N
SPT
(Sumber:Wright, 1977)
|
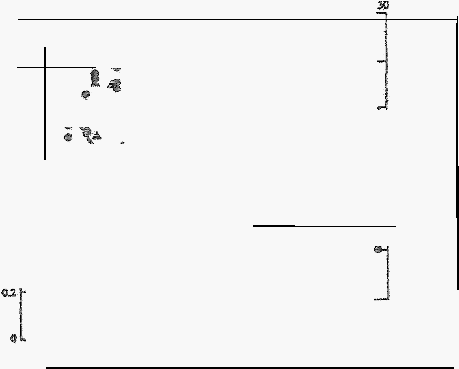 I
"'
-i
A
)
.
32
KW!1 ·C.('il'll'i)
0
5'
10
xs
;'II)
2S
1.2
!i,q-t
Ul
•!¥ill<{' '$
"i'-)
A. Coalyt
!"s(41
'1'-)
1:1
llJI
•
•if
A
ls
1' -
ll.i
·'·
A;
I.
s--·
l·
0.4
:
...
.
•
,
"
•
•
•
•
Gmnbar 2.U. Fakror adhesi
(Sumber: Kulhawy, 1991)
Bila tiang bor
pada
tanah
berlapis
maka fonnula
tersebut
dapat
dimodifikasi
menjadi:
n
Q,
="f.!;
.l,
.p
i=1
dimana:
Qs
=
daya dukung ultimit selimut tiang
(ton)
fi
=
gesekan selimut tiang per
satwm luas
(ton!m²
(2.7)
!1 = panjang tiang (m)
p
=
keliling penampang tiang (m)
2.4.4 Kelompok Tiang
Meskipun
pada tiang yang berdiameter
besar atau
untuk
beban
yang ringan sering
digunakan
pondasi
tiang
tunggal
untuk
memikul
beban
kolom
atau beban
struktur,
|